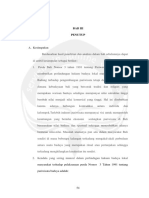Tri Purna Gumelar - 2281011031 - Kapita Selekta
Diunggah oleh
Choi PurnaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Tri Purna Gumelar - 2281011031 - Kapita Selekta
Diunggah oleh
Choi PurnaHak Cipta:
Format Tersedia
KAPITA SELEKTA
PARADIGMA KOMODIFIKASI BUDAYA PADA PERKEMBANGAN PARIWISATA
KONTEMPORER DI BALI TERHADAP TATANAN MORAL ETIS SOSIO-
EKONOMI-BUDAYA
Oleh
Tri Purna Gumelar
2281011031
PROGRAM STUDI MAGISTER PARIWISATA
FAKULTAS PARIWISATA
UNIVERSITAS UDAYANA
DENPASAR
2023
Setelah melihat video tersebut, penulis melihat pariwisata Bali sejak diperkenalkan sebagai
daya tarik wisata budaya, Bali selalu diimajinasikan, dikemas, dan disajikan sebagai daya tarik wisata
yang memiliki kekayaan dan keunikan seni budaya sebagai esensi dari pariwisata budaya. Selain daya
tarik seni budaya, keramahtamahan penduduk sebagai kebiasaan hidup masyarakat ikut mendukung
keunikan pariwisata budaya Bali. Dalam pariwisata kontemporer, penulis mencoba melihat kasus
wisatawan nomade dengan durasi tinggal yang cukup lama, secara masif dan konsisten sukses
memenuhi wilayah yang dulunya desa menjadi daya tarik wisata alternatif, seperti yang ada pada
video yaitu Canggu dan Ubud. Wisatawan kerap membawa cara hidup mereka yang kemudian
dipraktekkan di daerah tersebut, tentunya hal tersebut dalam tatanan sosio-budaya cukup memberikan
dampak. Indikasi dimulai dari kurs mata uang Indonesia yang lebih lemah dibanding negara
wisatawan, membuat wisatawan dengan mudah mendapatkan hal yang lebih “baik” dan “murah”
negara mereka sebelumnya, walaupun sebenarnya hal tersebut sangatlah legal. Dalam beberapa
pandangan bahwa seni budaya di tekan lebih “murah” untuk bisa menarik minat wisatawan, padahal
hal tersebut syarat akan historis, filosofis dan estetika. Kemudian cara hidup wisatawan juga
mempengaruhi permintaan dari pasar, yang kemudian penyedia internal, seperti masyarakat,
pengusaha dan pemerintah mencoba untuk “berinovasi”. Dalam hal ini biasa disebut dengan
komodifikasi.
Menurut The Oxford English Dictionary (1989) Komodifikasi didefinisikan sebagai
‘tindakan’ mengubah sesuatu menjadi, atau menjadikan sesuatu sebagai, (sekadar) komoditas;
komersialisasi suatu kegiatan, dan sebagainya, yang tidak bersifat komersial’ (Kitiarsa, 2007:6).
Bentuk komersialisasi inilah yang kemudian menjadi kontradiktif dari berbagai kalangan. Dalam
ekonomi global baru, komodifikasi budaya telah menjadi isu sentral bagi pengembangan pariwisata,
menurut Greenwood (1989) pertunjukan tersebut tidak lagi menjadi milik para pelaku saja, melainkan
menjadi tontonan bagi pihak luar. Ditambahkannya, pertunjukan tersebut dikomodifikasi dan dianggap
sebagai objek yang diminiaturkan dengan membuat pertunjukan menjadi lebih singkat dan variatif
untuk menarik wisatawan. Hal tersebut sejalan dengan landasan kekhawatiran akan terjadinya
komersialisasi berlebihan atas seni dan budaya, sesuatu yang sudah dikhawatirkan Spies dan Bonnet
tahun 1920-an/1930-an dengan berusaha menyelamatkan seni budaya Bali agar jangan sampai merosot
mutunya atau diabadikan sepenuhnya untuk komersial atau komoditisasi.
Komodifikasi tidak hanya berlaku sebatas seni dan budaya yang kemudian diproduksi dan
dikonsumsi saja, tetapi jasa penyedia termasuk amenitas dan aksesibilitas juga termasuk ke dalam
komodifikasi. Dapat dilihat Canggu dan Ubud sebagai pariwisata alternatif yang kemudian mendorong
secara distorsi untuk mengubah desanya menjadi daya Tarik wisata yang sesuai dengan gaya hidup
wisatawan mancanegara, semakin banyaknya wisatawan yang memenuhi daerah ini, tetapi tidak
dibarengi dengan penguatan tata Kelola daerah yang disesuaikan dengan masifnya kegiatan
kepariwisataan ini. Tentu yang terjadi adalah kemacetan, kebisingan, lahan tanah yang diakuisisi bule,
kekurangan air bersih dan masalah lingkungan lainnya. Hal tersebut perlu ditindaklanjuti dan
dimaknai sebagai “alarm” untuk stakeholder bisa bekerja sama untuk menyeimbangkan efek negatif
dari datangnya wisatawan yang menuju ke daerah tersebut. Satu sisi tentu saja bukan suatu yang keliru
melakukan komodifikasi, karena seni seperti juga produk kehidupan lainnya, seni atau kesenian selalu
memiliki dua dimensi, yaitu nilai guna (use values) dan nilai tukar (exchange values). Seni budaya
adalah hasil budi daya manusia yang sudah sewajarnya tidak sebatas untuk dinikmati secara imajinatif,
tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi.
perspektif sosio-ekonomi (Granovetter & Swedberg, 2019) disebut keterlekatan bahwa
kegiatan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari hubungan sosial dan kelembagaan yang ada dapat
digunakan bisa menyeimbangkan dampak negatif dari datangnya wisatawan. Komodifikasi budaya
tersebut membuka relasi baru antar aktor, seperti hubungan antar personal dan hubungan antar
lembaga pemerintah, sektor swasta, Pokdarwis, dan masyarakat Osing. Dengan hubungan yang kuat
ditemukan bahwa hubungan yang mengalami komodifikasi budaya adalah yang didorong oleh
kepentingan tertentu seperti keuntungan ekonomi, sehingga perluasan jejaring sosial bermanfaat bagi
masyarakat Bali untuk mendapatkan identitas budaya yang lebih kuat. Berkaitan dengan etika moral,
menggunakan utilitarianisme Bentham (1781). Konsep utilitarianisme menunjukkan kebahagiaan
sebagai konsekuensi dari aturan dalam masyarakat. Karena kebaikan menjadi sarana, maka secara
moral, ia setuju sebagai tujuan akhir. Namun, tujuan akhir dapat dikategorikan baik jika memiliki
kesenangan intrinsik dan tidak ada konsekuensi lebih lanjut. Suatu tujuan dianggap baik sejauh
keputusan itu dibuat berdasarkan pertimbangan kebahagiaan maksimum yang dapat diperoleh oleh
sebagian besar anggota masyarakat. Dengan masyarakat mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi
dengan berbagai pertimbangan dari keputusan umum, maka hal tersebut dianggap benar, demikian
pula dengan komodifikasi budaya terhadap tatanan sosio-budaya di Bali.
Dengan demikian dari kedua teori ini, dapat dimaknai sebagai batu loncatan sebagai kausalitas
dari komodifikasi budaya, untuk bisa menyeimbangi konsumsi dari wisatawan mancanegara yang
semakin radikal. Merujuk pada UU Pemajuan Kebudayaan 5/2017 dan Perda 4/2020 tentang
Pemajuan Kebudayaan Bali di mana pemanfaatan budaya bukanlah sesuatu yang tabu, sepanjang tiga
aspek lainnya, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pembinaan terhadapnya sudah dilaksanakan
mendahului atau berjalan serentak dan seimbang dengan pemanfaatannya. Bagaimana pun juga di Bali
budaya dan pariwisata tidak lagi bisa dipisahkan karena keduanya saling membentuk. Seperti kata
Picard dalam buku Bali: Cultural tourism and touristic culture bahwa promosi pariwisata budaya telah
membuat orang Bali sadar akan memiliki kebudayaan (1996:198). Tindakan dan regulasi yang tepat
dari antar aktor seperti pergelaran PKB contohnya, menjadi cara untuk bisa mewadahi masifnya
perkembangan pariwisata di Bali. Jauh lebih dalam pariwisata budaya yang berlandas pada sosio-
ekonomi-budaya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan secara kontemporer, tetapi didorong untuk
terus berkelanjutan yang tidak hanya bermanfaat secara sosial-ekonomi bagi masyarakat, tetapi atensi
penting terhadap tatanan ekologis lingkungan dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.
Anda mungkin juga menyukai
- Kesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikDari EverandKesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikBelum ada peringkat
- Simbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaDari EverandSimbol-Simbol Artefak Budaya Sunda: Tafsir-Tafsir Pantun SundaPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (16)
- Gde Deny Larasdiputra - Topik 1 File - Tugas Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.Dokumen8 halamanGde Deny Larasdiputra - Topik 1 File - Tugas Dr. Gede Rasben Dantes, S.T., M.T.I.I Dewa Agung Gede Mahardhika marthaBelum ada peringkat
- Antara Tradisi Dan PertunjukanDokumen15 halamanAntara Tradisi Dan PertunjukanDicky Yudha AnandaBelum ada peringkat
- Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Peme 0bc4c4d6Dokumen13 halamanAnalisis Partisipasi Masyarakat Dan Peme 0bc4c4d6yogaBelum ada peringkat
- Awaludin DAMPAK POSITIF DAN NEGATUF PARIWISATA SOSIAL BUDAYADokumen7 halamanAwaludin DAMPAK POSITIF DAN NEGATUF PARIWISATA SOSIAL BUDAYAPerhotelan Unmaha100% (1)
- Dampak Positif Dan Negatif PariwisataDokumen5 halamanDampak Positif Dan Negatif PariwisataSetsuna F. Yudha100% (1)
- c2 Pengkomersialan Budaya Orang SungaiDokumen14 halamanc2 Pengkomersialan Budaya Orang SungaiJosh MirezBelum ada peringkat
- Perayaan Seba BaduyDokumen17 halamanPerayaan Seba BaduyDinda Khansa A.RBelum ada peringkat
- Tugas 1Dokumen2 halamanTugas 1emelya noor fathonyBelum ada peringkat
- Resensi Miche Picard (Pariwisata Budaya Dan Budaya Pariwisata)Dokumen9 halamanResensi Miche Picard (Pariwisata Budaya Dan Budaya Pariwisata)Devi RosalinaBelum ada peringkat
- Template Artikel IlmiahDokumen18 halamanTemplate Artikel IlmiahSonnya Ayu Cindy Saputri100% (1)
- 10 +IJSSB+VOL +7+NO +1+Lis+Julianti+96-104Dokumen9 halaman10 +IJSSB+VOL +7+NO +1+Lis+Julianti+96-104marlinayosephaBelum ada peringkat
- Laporan Pariwisata BaliDokumen5 halamanLaporan Pariwisata BaliDewiBelum ada peringkat
- 1241-Article Text-2774-1-10-20201201Dokumen12 halaman1241-Article Text-2774-1-10-20201201asengBelum ada peringkat
- Kelompok 1 - Kelas B - Teori KritisDokumen5 halamanKelompok 1 - Kelas B - Teori KritisAnita AlviyaniBelum ada peringkat
- Pariwisata Berbasis BudayaDokumen2 halamanPariwisata Berbasis BudayaXhaqxaXhalzixqaBelum ada peringkat
- 3HK09565Dokumen6 halaman3HK09565Mala MamontoBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah Pesta Kesenian Bali (PKB)Dokumen14 halamanMakalah Sejarah Pesta Kesenian Bali (PKB)abu rasyidBelum ada peringkat
- 21 - I Wayan Robi Saputra - UAS Seni BudayaDokumen16 halaman21 - I Wayan Robi Saputra - UAS Seni BudayaPutu LianasariBelum ada peringkat
- Membangun BangsaDokumen680 halamanMembangun BangsaAudy Muhamad KaryadaraBelum ada peringkat
- Ekowisata - Bali TengahDokumen10 halamanEkowisata - Bali TengahDabii SefianizBelum ada peringkat
- REVIEWDokumen16 halamanREVIEWwenaysiyuuuu251Belum ada peringkat
- ID3 19780914200012100115081410830pariwisata Sebagai Wahana Pelestarian Subak Draft 2209Dokumen18 halamanID3 19780914200012100115081410830pariwisata Sebagai Wahana Pelestarian Subak Draft 2209Bunga UlulBelum ada peringkat
- Makalah Pariwisata Dan PerhotelanDokumen20 halamanMakalah Pariwisata Dan PerhotelanShofia Nur KhasanahBelum ada peringkat
- Antropologi PariwisataDokumen7 halamanAntropologi PariwisataPutu Wahyu100% (1)
- Laporan Penelitian Antropologi BudayaDokumen19 halamanLaporan Penelitian Antropologi BudayaZlatan IbrahimovicBelum ada peringkat
- Pengembangan CBTDokumen6 halamanPengembangan CBTintan maulydaBelum ada peringkat
- Franciskateori Pariwisata Dan Sosial Budaya ResumeDokumen5 halamanFranciskateori Pariwisata Dan Sosial Budaya Resumetugas franciskaBelum ada peringkat
- 95-Research Results-311-2-10-20191123Dokumen10 halaman95-Research Results-311-2-10-20191123ajieBelum ada peringkat
- Laporan EsdalDokumen19 halamanLaporan EsdalasnurBelum ada peringkat
- Hukum Dan Kebijakan PublikDokumen5 halamanHukum Dan Kebijakan PublikLia Siti SawaliahBelum ada peringkat
- Pengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui EkowisataDokumen12 halamanPengembangan Pariwisata Yang Berkelanjutan Melalui Ekowisatakeisha naulyBelum ada peringkat
- Override Parade: Isu-Isu Pariwisata Berkelanjutan Pada Destinasi Kepulauan Di IndonesiaDokumen20 halamanOverride Parade: Isu-Isu Pariwisata Berkelanjutan Pada Destinasi Kepulauan Di IndonesiaRinto YunarioBelum ada peringkat
- Kritik Review Jurnal CampDokumen18 halamanKritik Review Jurnal CampRika FajriyaniBelum ada peringkat
- Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten PekalonganDokumen85 halamanPeran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Ekowisata Di Kabupaten PekalonganMuhammad AssyafikriBelum ada peringkat
- Penanganan Dampak Perkembangan Pariwisata Dalam Aspek Lingkungan Fisik, Sosial, Ekonomi Dan Budaya Bali (Suatu Tinjauan Pustaka)Dokumen4 halamanPenanganan Dampak Perkembangan Pariwisata Dalam Aspek Lingkungan Fisik, Sosial, Ekonomi Dan Budaya Bali (Suatu Tinjauan Pustaka)Cantika KumaraBelum ada peringkat
- Laporan KuliahanDokumen4 halamanLaporan KuliahanBayaww tvBelum ada peringkat
- ID Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi PeDokumen10 halamanID Hukum Adat Bali Di Tengah Modernisasi PePuspita NariswariBelum ada peringkat
- Dampak Pariwisata Terhadap Sosial BudayaDokumen13 halamanDampak Pariwisata Terhadap Sosial BudayaGede Wahyu KurniasaBelum ada peringkat
- Pariwisata Sosiologi - PurnaDokumen19 halamanPariwisata Sosiologi - PurnaChoi PurnaBelum ada peringkat
- Pengaruh Perkembangan Budaya Terhadap Perkembangan Arsitektur Di DaerahDokumen15 halamanPengaruh Perkembangan Budaya Terhadap Perkembangan Arsitektur Di DaerahDila FadilhBelum ada peringkat
- Hukum KepariwisataanDokumen11 halamanHukum KepariwisataanLia Siti SawaliahBelum ada peringkat
- Marsya Simbolon - Tugas Review Perencanaan Destinasi PariwisataDokumen4 halamanMarsya Simbolon - Tugas Review Perencanaan Destinasi PariwisataMarsya SimbolonBelum ada peringkat
- Kolaborasi Masyarakat Ekonomi, Politik, Dan Sipil Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Untuk Pengentasan Kemiskinan Pesisir Di BaliDokumen24 halamanKolaborasi Masyarakat Ekonomi, Politik, Dan Sipil Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Untuk Pengentasan Kemiskinan Pesisir Di BaliNasanda AuliaBelum ada peringkat
- Febriandhika (Literature Pariwisata Berkelanjutan Melalui CBT)Dokumen8 halamanFebriandhika (Literature Pariwisata Berkelanjutan Melalui CBT)ppg.dwioktavani88Belum ada peringkat
- Dasar Pelancongan BudayaDokumen2 halamanDasar Pelancongan Budayanur aiman0% (1)
- Bab Ii IiiDokumen25 halamanBab Ii IiiMirah DitaBelum ada peringkat
- Makalah ParawisataDokumen10 halamanMakalah Parawisatanuel ludjiBelum ada peringkat
- ModalsosialekowisataDokumen31 halamanModalsosialekowisataAndi OctyelianBelum ada peringkat
- 780 784+Fadillah+AlmuzakirDokumen5 halaman780 784+Fadillah+AlmuzakirAyu PurnamaBelum ada peringkat
- Makalah Pariwisata Dampak PositifDokumen13 halamanMakalah Pariwisata Dampak PositifMifthahul JannahBelum ada peringkat
- PariwisataDokumen14 halamanPariwisatamade adeBelum ada peringkat
- Makalah Ekowisata Kel 2Dokumen15 halamanMakalah Ekowisata Kel 2M.alfiqron FiqronBelum ada peringkat
- 1187 2424 1 PBDokumen11 halaman1187 2424 1 PBKomang alit ParwataBelum ada peringkat
- BAB114122210930Dokumen22 halamanBAB114122210930Widiat MikoBelum ada peringkat
- Makalah Kel.12 Ekonomi Pariwisata Dan CBTDokumen12 halamanMakalah Kel.12 Ekonomi Pariwisata Dan CBTNur Amelia FitriBelum ada peringkat
- 94-Article Text-264-1-10-20200418Dokumen12 halaman94-Article Text-264-1-10-20200418Baihaqi FiazinBelum ada peringkat
- PariwisataDokumen11 halamanPariwisataSuyonoBelum ada peringkat
- 86 239 1 PB PDFDokumen14 halaman86 239 1 PB PDFHadie Mulyana IIBelum ada peringkat
- Entrepreneurship Tourism - Group 9 - Business PlanDokumen20 halamanEntrepreneurship Tourism - Group 9 - Business PlanChoi PurnaBelum ada peringkat
- Tri Purna Gumelar - Draft Tugas Perencanaan Prof SamsulDokumen7 halamanTri Purna Gumelar - Draft Tugas Perencanaan Prof SamsulChoi PurnaBelum ada peringkat
- Tri Purna Gumelar - 2281011031 - Perencanaan PariwisataDokumen7 halamanTri Purna Gumelar - 2281011031 - Perencanaan PariwisataChoi PurnaBelum ada peringkat
- Tri Purna Gumelar - 2281011031 - Analisis Metode KuantitatifDokumen5 halamanTri Purna Gumelar - 2281011031 - Analisis Metode KuantitatifChoi PurnaBelum ada peringkat
- Pariwisata Sosiologi - PurnaDokumen19 halamanPariwisata Sosiologi - PurnaChoi PurnaBelum ada peringkat
- Draft PPT Kapita SelektaDokumen5 halamanDraft PPT Kapita SelektaChoi PurnaBelum ada peringkat