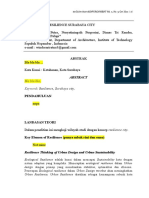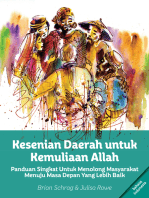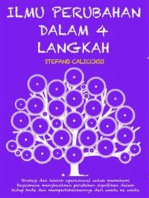Revisi UTS Arsitektur Perilaku
Revisi UTS Arsitektur Perilaku
Diunggah oleh
Adit taufik rJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Revisi UTS Arsitektur Perilaku
Revisi UTS Arsitektur Perilaku
Diunggah oleh
Adit taufik rHak Cipta:
Format Tersedia
UJIAN TENGAH SEMESTER
ARSITEKTUR PERILAKU
ADITYA TAUFIK R
ARSITEKTUR B
MENGUBAH PERILAKU DAN LINGKUNGAN DALAM PROGRAM BERBASIS KOMUNITAS DARI
KOMUNITAS RIVERSIDE
Joyce Marcella Laurens
Masyarakat tepi sungai menyusun program berbasis masyarakat untuk bernegosiasi
dengan pemerintah setempat agar mereka tidak digusur. Sebagai paket intervensi, -yang
bertujuan untuk memperbaiki lingkungan hidup dan meningkatkan perilaku warga yang
pro-lingkungan-, program ini terdiri dari organisasi dan informasi, dikombinasikan dengan
interaksi sosial, kinerja komitmen dan umpan balik. Pengamatan intensif digunakan untuk
menguji efektivitas program terhadap perubahan perilaku lingkungan dan perbaikan
permukiman. Temuan menunjukkan bahwa kesamaan tujuan renovasi merupakan
variabel yang paling berpengaruh dalam memotivasi individu untuk meningkatkan
perilaku ramah lingkungan pada penataan lingkungan.
© 2011 Diterbitkan oleh Elsevier Ltd. Seleksi dan peer-review di bawah tanggung jawab
Pusat Lingkungan- © 2012 Diterbitkan oleh Elsevier B.V. Seleksi dan/atau peer-review di
bawah tanggung jawab Centre for Environment-Behaviour Studi Perilaku (CE-Bs), Fakultas
Arsitektur, Perencanaan & Survei, Universiti Teknologi MARA, Malaysia Studi (CE-Bs),
Fakultas Arsitektur, Perencanaan & Survei, Universiti Teknologi MARA, Malaysia Akses
terbuka di bawah lisensi CC BY-NC-ND. Kata kunci: Perubahan perilaku; berdasarkan
komunitas; interaksi sosial
1. Perkenalan
Ada sekitar lima ribu keluarga di pemukiman bantaran kali sepanjang Kanal
Wonokromo dan Surabaya di Surabaya. Sebagai kota terbesar kedua di Indonesia,
Surabaya mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat dan perjuangan
pembangunan ekonomi. Pemkot berencana melakukan beautifikasi di sepanjang
kanal sesuai dengan gagasan menjadikan Surabaya sebagai kota perdagangan
internasional. Pada tahun 2002,
* Penulis yang sesuai. Tel.: +62-31-2983382; faks: +62-31-8436418. Alamat email:
joyce@peter.petra.ac.id
. 1877-0428 © 2012 Diterbitkan oleh Elsevier B.V. Seleksi dan/atau peer-review di
bawah tanggung jawab Centre for Environment-Behaviour Studies(cE-Bs), Fakultas
Arsitektur, Perencanaan & Survei, Universiti Teknologi MARA, Malaysia Akses
terbuka di bawah CC BY- Lisensi NC-ND. doi:10.1016/j.sbspro.2012.03.041
lebih dari 400 rumah di tepi sungai dihancurkan; rumah dan mata pencaharian
masyarakat terancam penggusuran selama bertahun-tahun. Orang tidak tahu di
mana dan bagaimana melanjutkan hidup mereka; karena apartemen walk-up yang
disediakan oleh pemerintah tidak terjangkau bagi mereka. Tampaknya dominasi
ranah ekonomi menggeser biaya lingkungan dan sosial ke komunitas miskin yang
tidak memiliki kekuatan politik atau ekonomi. Kebijakan, legislasi, dan regulasi tidak
berpihak pada mereka. Setiap kali kanal mendapat masalah serius, seperti
pencemaran sungai atau banjir yang sering terjadi di Surabaya, seluruh kota akan
menyalahkan masyarakat tepi sungai untuk bertanggung jawab, dan kembali ditekan
untuk direlokasi. Menanggapi kondisi ini, warga permukiman bantaran kali di
sepanjang kanal Surabaya mengorganisir diri, dan membentuk paguyuban Warga
Strenkali Surabaya - PWSS pada tahun 2004. Mereka mengembangkan proposal
berbasis komunitas untuk bernegosiasi dengan pemerintah, dan menunjukkan
bagaimana banjir dapat dihindari dan pembangunan kota tetap dapat digalakkan,
sementara mereka dapat tetap tinggal di sana tanpa merusak lingkungan. Didukung
oleh Urban Poor Consortium (UPC) dan Uplink, -organisasi non pemerintah-, dan
para ahli dari universitas, studi teknis telah dilakukan; Hasil penelitian menunjukkan
bahwa sebenarnya pemukiman masyarakat pinggiran sungai yang miskin tidak
bertanggung jawab atas sebagian besar degradasi integritas ekologi sungai, tetapi
cepatnya penurunan hutan di atas bukit, dan keberadaan industri dan pabrik di
sepanjang sungai. kontributor utama. Namun, penting untuk menyadarkan
masyarakat bahwa permukiman tepi sungai itu sendiri tidak dapat dipertahankan
sebagaimana adanya; mereka perlu ditingkatkan, dari daerah kumuh menjadi
pemukiman yang sehat dan berkelanjutan. Kebiasaan dan keputusan warga dalam
memanfaatkan sungai pada akhirnya berpengaruh besar terhadap kelestariannya
sungai dan lingkungan hidupnya. Mereka tidak menunjukkan perilaku lingkungan
bertanggung jawab yang diinginkan. Disebutkan dalam negosiasi mereka dengan
pemerintah bahwa, mereka perlu mengubah perilaku mereka sendiri dalam
berinteraksi dengan lingkungan bantaran sungai, agar berperilaku lebih ramah
lingkungan. Setelah berjuang selama 4 tahun mengusulkan konsep renovasi bukan
relokasi; pada tahun 2007 pemerintah menerbitkan peraturan daerah (Perda 2007)
yang memperbolehkan keberadaan permukiman terbatas di sepanjang bantaran
sungai dan memberi masyarakat waktu lima tahun untuk memperbaiki permukiman
mereka alih-alih merelokasinya. Peraturan ini bukanlah tujuan akhir dari masyarakat,
melainkan langkah awal yang harus diikuti dengan merealisasikan usulan mereka.
Mengingat banyak perilaku yang perlu diubah untuk mencapai masyarakat yang
berkelanjutan, maka prioritas dan fokus program berbasis masyarakat menjadi
sangat penting. Studi intervensi umumnya hanya menargetkan satu atau beberapa
jenis perilaku dalam waktu singkat, dan dengan demikian memiliki cakupan yang
terbatas. Selain itu, jika hanya mengubah satu jenis perilaku tertentu selama
intervensi, maka nilai praktisnya akan terbatas. Program berbasis komunitas
komunitas bantaran sungai bukanlah program intervensi jangka pendek. Sudah lebih
dari tujuh tahun dilakukan, dan masih berjalan untuk mencapai impian mereka
memiliki kehidupan yang damai dan bebas dari ancaman penggusuran. Mengingat
kondisi ini, sangat menarik untuk ditelitiprogram berbasis komunitas masyarakat tepi
sungai. Dalam tulisan ini, deskripsi diberikan untuk melihat lebih dalam dan lebih
menghargai efektivitas program ini dalam cara kerjanya. Masalah utama adalah
untuk memahami apa yang terjadi pada masyarakat sebelum dan sesudah peraturan
pemerintah diterbitkan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi orang
untuk mengubah perilaku pro-lingkungan mereka dan untuk memeriksa perilaku
pro-lingkungan yang substansial dan tahan lama yang berubah dalam kaitannya
dengan penyelesaian peningkatan. Perilaku individu terhadap lingkungan harus ada
hubungannya dengan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan
sehubungan dengan lingkungan dan tindakan pro-lingkungan. Studi perilaku
biasanya berfokus pada faktor determinan variabel pribadi, bukan variabel
situasional yang berhubungan dengan lingkungan fisik (Black, et.al. 1985). Dalam
penyelidikan mereka, Joze AC & Jaime B (2000) menunjukkan bahwa perilaku
lingkungan tergantung pada pribadi (nilai dan keyakinan) dan situasional (fisik
lingkungan) dengan cara yang interaktif. Interaksi antara variabel pribadi dan
situasional dapat didefinisikan dalam hal tingkat konflik atau konsistensi di antara
mereka. Konflik ini akan tinggi ketika variabel pribadi dan situasional memiliki tanda
yang berbeda. Ini adalah saat disposisi tinggi/positif untuk bertindak tetapi situasi
membuatnya sulit, atau ketika disposisi pribadi untuk bertindak rendah/negatif dan
situasi memfasilitasinya. Konsistensi terjadi ketika disposisi pribadi dan variabel
situasional memiliki tanda yang sama. Inilah saat disposisi pribadi terhadap perilaku
rendah dan situasi membuatnya sulit; atau ketika disposisi pribadi terhadap tindakan
itu tinggi dan situasi memfasilitasinya. Ketika tingkat konflik yang tinggi dihasilkan
antara disposisi pribadi dan kondisi situasional, kekuatan prediktif sikap cenderung
minimal. Sedangkan in cenderung maksimal jika ada konsistensi diantara keduanya.
Tingkat konflik antara variabel pribadi dan situasional akan memengaruhi perilaku
lingkungan orang, sedangkan pengaruh variabel situasional ditemukan bergantung
pada tindakan lingkungan yang dipertimbangkan. Pemahaman tentang proses
interaktif ini akan memfasilitasi peningkatan tingkat rata-rata perilaku pro-
lingkungan, dan mengajukan penjelasan tentatif tentang perbedaan perilaku
lingkungan. Faktor-faktor yang memotivasi individu untuk mengambil tindakan pro-
lingkungan dapat diindikasikan dalam penelitian Hines et.al. (1986) dan Aytul
Kasapoglu & Mehmet Ecevit (2002) yang mengidentifikasi variabel-variabel yang
berpengaruh dalam memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan pro-
lingkungan. Itu adalah variabel kognitif, -berurusan dengan pemahaman tentang
lingkungan-; variabel psikososial,-faktor yang berhubungan dengan karakteristik
pribadi, yaitu kemampuan untuk mengubah lingkungan, tanggung jawab pribadi
terhadap lingkungannya, komitmen verbal, dan orientasi ekonomi-, dan variabel
demografis.
2. Tinjauan Pustaka
Selama beberapa dekade terakhir, penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan
perilaku ramah lingkungan atau untuk mengurangi degradasi lingkungan telah
mendapat perhatian yang signifikan dalam berbagai skala dari tingkat individu
sukarela hingga skala nasional. Banyak penelitian telah dilakukan untuk menemukan
atau mengevaluasi teknik intervensi tertentu untuk mengubah perilaku dengan
konsekuensi lingkungan. Namun, penelitian semacam itu masih kurang di negara-
negara berkembang, terutama di daerah masyarakat miskin dengan masalah
lingkungan yang besar. Tulisan ini berkaitan dengan upaya masyarakat miskin untuk
mengubah perilaku lingkungan di lingkungannya. Program berbasis masyarakat yang
diinisiasi oleh masyarakat miskin di Surabaya tampaknya berperan sebagai program
intervensi
. 2.1. Perilaku lingkungan
Perilaku individu terhadap lingkungan harus ada hubungannya dengan apa yang
mereka rasakan dan apa yang mereka pikirkan sehubungan dengan lingkungan dan
tindakan pro-lingkungan. Studi perilaku biasanya berfokus pada faktor determinan
variabel pribadi, bukan variabel situasional yang berhubungan dengan lingkungan
fisik (Black, et.al. 1985). Dalam penyelidikan mereka, Joze AC & Jaime B (2000)
menunjukkan bahwa perilaku lingkungan bergantung pada variabel pribadi (nilai dan
keyakinan) dan situasional (lingkungan fisik) secara interaktif. Interaksi antara
variabel pribadi dan situasional dapat didefinisikan dalam hal tingkat konflik atau
konsistensi di antara mereka. Konflik ini akan tinggi ketika variabel pribadi dan
situasional memiliki tanda yang berbeda. Ini adalah saat disposisi tinggi/positif untuk
bertindak tetapi situasi membuatnya sulit, atau ketika disposisi pribadi untuk
bertindak rendah/negatif dan situasi memfasilitasinya. Konsistensi terjadi ketika
disposisi pribadi dan variabel situasional memiliki tanda yang sama. Inilah saat
disposisi pribadi terhadap perilaku rendah dan situasi membuatnya sulit; atau ketika
disposisi pribadi terhadap tindakan itu tinggi dan situasi memfasilitasinya. Ketika
tingkat konflik yang tinggi dihasilkan antara disposisi pribadi dan kondisi situasional,
kekuatan prediksi sikap cenderung minim. Sedangkan in cenderung maksimal jika
ada konsistensi diantara mereka. Tingkat konflik antara variabel pribadi dan
situasional akan mempengaruhi lingkungan orang perilaku, sedangkan pengaruh
variabel situasional ditemukan tergantung pada tindakan lingkungan
dipertimbangkan. Pemahaman tentang proses interaktif ini akan memfasilitasi
peningkatan rata-rata perilaku pro-lingkungan, dan mengusulkan penjelasan tentatif
perbedaan dalam lingkungan perilaku. Faktor-faktor yang memotivasi individu untuk
mengambil tindakan pro-lingkungan, dapat diindikasikan dalam studi Hines et.al.
(1986) dan Aytul Kasapoglu & Mehmet Ecevit (2002) yang mengidentifikasi pengaruh
variabel dalam memotivasi orang untuk mengambil tindakan pro-lingkungan. Itu
adalah variabel kognitif, -berurusan dengan pemahaman tentang lingkungan-;
variabel ps ychosocial,-faktor yang berhubungan dengan pribadi karakteristik, yaitu
kemampuan untuk mengubah lingkungan, tanggung jawab pribadi terhadap
lingkungannya, verbal komitmen, dan orientasi ekonomi-, dan variabel demografissi
2.2. Teknik intervensi
Dwyer, et.al. (1993) mengulas efektivitas beberapa teknik intervensi; mereka
menemukan itu sebagian besar teknik mengalami kesulitan dalam mencapai
perubahan perilaku yang tahan lama, karena ada yang terbatas durasi
perubahan perilaku dan umumnya mereka hanya memiliki sejumlah perilaku
yang terbatas target. Efektivitas program untuk mengubah perilaku yang ada
menjadi bertarget pro-lingkungan perilaku dipertahankan hanya kurang dari 12
minggu setelah program intervensi selesai. Tentang kegigihan perubahan
perilaku pro-lingkungan, De Young (1993) mendesak peneliti untuk fokus
mengembangkan teknik intervensi yang menciptakan perubahan mandiri. Dia
berpendapat bahwa produk yang tahan lama perubahan perilaku lingkungan
dapat difasilitasi dengan merancang teknik yang menggabungkan detail
informasi prosedural, umpan balik dari kinerja seseorang, dan lingkungan sosial
yang mendukung. Geller (1990) juga mengusulkan kombinasi elemen ini untuk
meningkatkan efektivitas intervensi teknik. Informasi adalah salah satu cara
yang paling banyak digunakan untuk mempromosikan perubahan perilaku pro-
lingkungan. Informasi dapat berfungsi untuk meningkatkan kesadaran masalah,
yang pada gilirannya dapat mempengaruhi perilaku atau menginformasikan
orang dari usaha orang lain yang dapat meningkatkan kerjasama. Umpan balik
kinerja dapat meningkatkan rasa kemanjuran individu dan kolektif. Umpan balik
mungkin juga memicu perubahan melalui daya tarik norma-norma sosial dan
pribadi. Secara umum, umpan balik sangat membantu dalam mengubah
perilaku; namun, tanpa penerapan umpan balik dan informasi berkala,
efektivitas pada tingkat individu berkurang. Lingkungan sosial yang mendukung
adalah kondisi yang menggunakan dukungan sosial. Lewin (dikutip dalam Staats,
2004) menyatakan bahwa salah satu faktor yang bertanggung jawab atas
keberhasilan perubahan perilaku dalam kelompok kecil adalah interaksi sosial
dengan mampu mengalami standar kelompok sebelum keputusan eksplisit
dibuat. Hopper dan Nielsen (1991) mempelajari dampak interaksi sosial
terhadap perubahan standar kelompok, atau sosial norma tentang perilaku daur
ulang, dengan mengidentifikasi seseorang di lingkungan yang secara pribadi
memberi tahu masyarakat sekitar tentang program tersebut dan mendorong
mereka untuk mendaur ulang
. 3. Metodologi
Penelitian ini didasarkan pada pendekatan fenomenologi, yang bertujuan untuk
melihat lebih dalam dan mengungkap sifat dasar dari program berbasis
masyarakat. Data dikumpulkan melalui empati melihat dan melihat,
pengamatan lingkungan yang cermat dan komprehensif, wawancara mendalam
dengan komunitas. Semuanya diperoleh melalui kunjungan dan partisipasi
dalam agenda masyarakat sejak itu 2003. Bahan sejarah dokumenter dan hasil
survei teknis yang dilakukan di tepi sungai masyarakat merupakan bagian dari
data yang diamati. Deskripsi kualitatif pemeriksaan telah dibuat berdasarkan
tinjauan pustaka di atas, dengan penekanan pada menemukan apa dan
bagaimana hal-hal yang kongkrit, peristiwa, dan pengalaman yang terjadi di
masyarakat. Pandangan holistik berusaha untuk mempertahankan keunikan
program berbasis masyarakat.
4. Hasil dan Pembahasan
Pembahasan dilakukan berdasarkan data yang terkumpul dari tahun 2003
hingga 2010. Inisiatif masyarakat untuk mendirikan PWSS dimulai pada tahun
2002, namun secara resmi diumumkan ke publik sebagai organisasi masyarakat
pada tahun 2004. Dalam rentang waktu tersebut, banyak agenda yang dilakukan
secara individual oleh kelompok. warga di kampung tertentu di sepanjang
bantaran sungai untuk memprotes penggusuran pemerintah. Mereka memang
belum terorganisasi dengan baik sebagai komunitas besar, tapi memang
merekalah pelopor PWSS. Dengan dukungan dan advokasi beberapa LSM, pada
tahun 2004 PWSS didirikan dengan anggota 1033 keluarga yang berasal dari 9
kampung yang terletak di bantaran sungai. Rata-rata mereka telah tinggal di
bantaran sungai selama 30 tahun (51,4% dari mereka telah tinggal di bantaran
sungai lebih dari 21 tahun; 4,3% lebih dari 50 tahun). Ketika ditanya tentang
alasan tinggal di bantaran sungai; 42,1% masyarakat menjawab nilai ekonomis
lokasi sebagai alasan utama (56,1% masyarakat memiliki tempat kerja kurang
dari 1 km dari rumahnya, 15,0% berjarak 1-3 km); hanya 5,3% dari mereka
menyebutkan sungai sebagai faktor penarik. Sumber informasi yang
memungkinkan mereka datang ke bantaran sungai adalah keluarga (37,5%) dan
teman (17,1%) yang berasal dari kampung yang sama. Semua kampung adalah
pemukiman yang sangat padat; sebagian besar merupakan kawasan kumuh.
Luas pemukiman bantaran sungai di sepanjang kanal Surabaya adalah 6,76 ha;
terdapat 926 bangunan (59,3% permanen, 30,9% semi permanen, 9,8%
bangunan tidak permanen). Sebagian besar bangunan difungsikan sebagai
rumah tinggal (57,8%) dan sebagian (33,6%) digunakan sebagai rumah kerja atau
tempat usaha. Kondisi lingkungan sekitar sangat memprihatinkan. Beberapa
bangunan bukanlah bangunan yang layak untuk ditinggali; Di sepanjang aliran
sungai banyak dibangun rumah atau MCK umum di areal reklamasi sungai.
Dalam waktu negosiasi dengan pemerintah, mereka mulai menghancurkan
bangunan tersebut; menunjukkan kesediaan mereka untuk mengubah perilaku
mereka dalam interaksi mereka dengan lingkungan (gambar 1).
4.1. Intervensi dan advokasi
Pada tahun 2010, PWSS direorganisasi. Manajemen dan kepemimpinan
organisasi dialihkan ke generasi muda. Situasi yang mereka hadapi berbeda;
generasi pertama harus meyakinkan dengan proposal mereka melawan konsep
relokasi pemerintah dan menunjukkan bahwa mereka dapat memperbaiki
lingkungan hidup mereka dan meningkatkan perilaku pro-lingkungan mereka,
sedangkan generasi kedua harus memberikan bukti tentang apa yang mereka
usulkan setelah peraturan pemerintah ( Perda 2007) diterbitkan. Pengelolaan
generasi pertama PWSS didukung penuh oleh LSM (UPC dan Jerit; kemudian
UPC dan Uplink). Sebagai organisasi yang baru berdiri, masyarakat harus banyak
belajar, bagaimana mengelola dan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi
rencana pemerintah menggusur pemukiman mereka. Ada dua kelompok papan.
NGO berperan sebagai Advocacy Organizers (AO) yang mengelola organisasi dan
berperan sebagai think tank PWSS; dan orang-orang dari masyarakat menjadi
koordinator wilayah. AO sedang melakukan beberapa program intervensi yang
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak
mereka dan lingkungan yang berkelanjutan, membangun dan memperkuat
hubungan sosial antara warga, kepercayaan diri mereka, melakukan jejaring
dengan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan lembaga, dan mengadvokasi
masyarakat. dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Koordinator wilayah harus
bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi kepada dan di antara warga
di wilayahnya masing-masing. Rapat internal diadakan secara rutin, namun
sebagian besar diselenggarakan oleh AO. Intervensi dan advokasi LSM (UPC dan
Uplink) selama generasi pertama PWSS dikelola tidak hanya dalam
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka atau mendidik
masyarakat tentang beberapa masalah teknis dan sosial yang berkaitan dengan
lingkungan mereka, tetapi juga secara tidak langsung menjadi kepemimpinan
pelatihan. Melalui semua program intervensi yang dilakukan oleh AO,
masyarakat mengalami bagaimana mengatur anggota masyarakat. Pemimpin
berbakat muncul dalam jumlah. Setelah tujuh tahun melakukan advokasi,
mereka memutuskan bahwa organisasi harus berdiri sendiri, tidak bergantung
pada AO lagi, dan diperlukan regenerasi.
5. Kesimpulan
Program berbasis komunitas Riverside Community berperan sebagai paket
intervensi dalam meningkatkan perilaku pro-lingkungan di lingkungan tempat
tinggal mereka. Generasi kedua PWSS, mengelola organisasi secara lebih
otonom dibandingkan dengan generasi pertama, yang sangat didukung oleh
Penyelenggara Advokasi dari LSM. Menerapkan pendekatan pemimpin
kelompok dalam program mereka memungkinkan masyarakat untuk mengalami
kelompok standar sebelum keputusan eksplisit individu dibuat. Ini adalah faktor
yang bertanggung jawab atas keberhasilan perubahan perilaku dalam
pengaturan kelompok kecil, unit K-10, dibandingkan dengan organisasi besar.
Pengaruh diskusi kelompok juga menguntungkan dibandingkan dengan instruksi
individu, mengesampingkan bahwa itu adalah jumlah perhatian yang diberikan
kepada setiap orang secara individu yang bertanggung jawab atas perubahan
perilaku. Efek bersama dari interaksi kelompok dan keputusan eksplisit yang
dibuat di depan umum oleh anggota kelompok ini tampaknya cukup berhasil
dalam mengubah perilaku. Ini menunjukkan efektivitas lingkungan sosial yang
mendukung dalam meningkatkan perilaku pro-lingkungan. Efek berpartisipasi
dalam kelompok diskusi tidak berkurang seiring berjalannya waktu, karena
kemungkinan untuk berdiskusi secara bebas tentang keuntungan dan kerugian
membuat keputusan yang jelas. Ini menunjukkan sisi positif dari interaksi tatap
muka mengenai perubahan perilaku. Karena programnya diprakarsai oleh
anggota masyarakat, intervensi datang dari dalam dan menyangkut masalah
mereka sendiri. Memiliki tujuan bersama, -yaitu menolak konsep relokasi
pemerintah, dan mempromosikan konsep renovasi mereka sendiri-, adalah agen
yang kuat dalam memotivasi mereka untuk terus meningkatkan perilaku pro-
lingkungan mereka dalam perbaikan lingkungan. Umpan balik kinerja diperlukan
untuk diterapkan secara teratur. Kondisi yang mempengaruhi beberapa perilaku
pro lingkungan akan membuat perilaku lain juga rentan berubah karena
kesamaan unsur kondisi pendukungnya masing-masing. Dikatakan bahwa
intervensi saja tidak menyebabkan efek tetapi perubahan lingkungan dan
interaksinya dengan lingkungan bertanggung jawab atas perubahan tersebut.
Paket intervensi PWSS berbasis komunitas telah membuktikan bahwa
perubahan, tidak hanya pada satu jenis perilaku tertentu, tetapi menciptakan
perubahan yang berkelanjutan dalam komunitas. Dengan rasa komunitas dan
tempat, ada keinginan untuk mengambil tanggung jawab lebih dari sekedar
rumah langsung mereka. Studi ini memiliki nilai praktis karena program
mengidentifikasi organisasi dan pembuat kebijakan tindakan mana yang harus
diambil untuk meningkatkan tingkat perilaku pro-lingkungan dan akibatnya
memperbaiki lingkungan.
Referensi
Aytulkasapoglu, M. & Ecevit Mehmet C. (2002). Sikap dan perilaku terhadap
lingkungan. Jurnal Lingkungan dan Perilaku 34, 363,
http://eab.sagepub.com/cgi.content/abstract1/34/3/363 Black, J.S., Stern, P.C.,
& Elworth, J.T. (1985). Pengaruh pribadi dan kontekstual terhadap adaptasi
energi rumah tangga. Jurnal Psikologi Terapan 70, 3 - 21 Corraliza, Joze A., &
Berenguer, Jaime (2000). Nilai lingkungan, keyakinan dan tindakan: pendekatan
situasional. Jurnal Lingkungan dan Perilaku 32, 832 De Young R (1993).
Mengubah perilaku dan membuatnya melekat. Konseptualisasi dan manajemen
motivasi konservasi dan kompetensi. Jurnal Lingkungan dan Perilaku 28, 358 382
Joyce Marcella Laurens / Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku 36 (2012) 372 – 382
Dolnicar, Sara & Grun, Bettina (2009). Perilaku ramah lingkungan: Bisakah
heterogenitas di antara individu dan konteks/lingkungan dimanfaatkan untuk
pengelolaan berkelanjutan yang lebih baik?. Jurnal Lingkungan dan Perilaku 41,
693, http://eab.sagepub.com/cgi.content/abstract41/5/693
Dwyer, W., Leeming, F.C., Cobern, M.K., Porter, B.E. & Jackson, J.M. (1993).
Tinjauan kritis intervensi perilaku untuk melestarikan lingkungan: Penelitian
sejak 1980. Jurnal Lingkungan dan Perilaku 25, 275 Geller, ES (1990). Analisis
perilaku dan perlindungan lingkungan: Kemana perginya semua bunga? Jurnal
Analisis Perilaku Terapan, 23, 269 Groot, Judith I.M. & Steg, Linda (2008).
Orientasi nilai untuk menjelaskan keyakinan terkait dengan perilaku penting
lingkungan. Bagaimana mengukur orientasi nilai egoistik, altruistik, dan biosfer.
Jurnal Lingkungan dan Perilaku 10, 330,
http://eab.sagepub.com/cgi.content/abstract10/3/330 Hines, J.M., Hungerford,
H.R., & Tomera, A.N. (1986). Analisis dan sintesis penelitian tentang perilaku
lingkungan yang bertanggung jawab: Sebuah meta-analisis. Jurnal Pendidikan
Lingkungan18, 1 - 8. Hopper J.R & Nielsen J.M (1991). Mendaur ulang sebagai
perilaku altruistik. Strategi normatif dan perilaku untuk memperluas partisipasi
dalam program daur ulang masyarakat. Jurnal Lingkungan dan Perilaku 23, 195
Oskamp S et.al (1991). Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku daur ulang
rumah tangga. Jurnal Lingkungan dan Perilaku 23, 494 Paguyuban Warga
Strenkali Surabaya (2004). Data-data Kampung Strenkali Surabaya (unpublished
research) Pollet, Fabien. (2005). Keterjangkauan dan desain. Pikiran, Bahasa dan
Ilmu Kognitif
Anda mungkin juga menyukai
- Canadian Geographies G Ographies Canadiennes - 2014 - Vodden - Governing Sustainable Coastal Development The Promise and - En.idDokumen14 halamanCanadian Geographies G Ographies Canadiennes - 2014 - Vodden - Governing Sustainable Coastal Development The Promise and - En.idNeva AdriBelum ada peringkat
- Template of Article IJPDDokumen5 halamanTemplate of Article IJPDwaridzulilmiBelum ada peringkat
- en IdDokumen6 halamanen IdOphelia muntheBelum ada peringkat
- Review Jurnal Kelompok 2Dokumen16 halamanReview Jurnal Kelompok 2Siva LarasathiBelum ada peringkat
- Pengelolaan Berbasis MasyarakatDokumen18 halamanPengelolaan Berbasis MasyarakatAlphaBelum ada peringkat
- P5 PpraDokumen5 halamanP5 PpraanwarBelum ada peringkat
- Jurnal STB DimasDokumen6 halamanJurnal STB DimasShion MoonBelum ada peringkat
- Arbuthnott2011 IdDokumen5 halamanArbuthnott2011 IdbyzgrowupBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian: Hubungan Fenomenologi Antara Keikutsertaan Muda-Mudi Pada Program December Beach Clean Up Oleh Bye Bye Plastic Bags SurabayaDokumen11 halamanProposal Penelitian: Hubungan Fenomenologi Antara Keikutsertaan Muda-Mudi Pada Program December Beach Clean Up Oleh Bye Bye Plastic Bags Surabayayucke auliaBelum ada peringkat
- Ekologi SosialDokumen3 halamanEkologi SosialIvan Salahadin0% (1)
- Soal pdgk4405 tmk1 3Dokumen4 halamanSoal pdgk4405 tmk1 3Pro AfkBelum ada peringkat
- Program Pemberdayaan Masyarakat "Cinta Citarum" Di Daerah Baleendah, Kabupaten BandungDokumen10 halamanProgram Pemberdayaan Masyarakat "Cinta Citarum" Di Daerah Baleendah, Kabupaten BandungRiko PurbowoBelum ada peringkat
- Makalah Masyarakat Kota Dan Desa Idar GunawanDokumen9 halamanMakalah Masyarakat Kota Dan Desa Idar GunawanKhaerani RamadhaniBelum ada peringkat
- Irmina Adi Ringrih - K012202012 Tugas Final Isip BaruDokumen13 halamanIrmina Adi Ringrih - K012202012 Tugas Final Isip BaruCantika IrminaBelum ada peringkat
- Makalah Komunikasi LingkunganDokumen10 halamanMakalah Komunikasi LingkunganYADI SUPYANDIBelum ada peringkat
- Peningkatan Pengetahuan Dan Sikap Kepala Keluarga Tentang Pengelolaan Sampah Melalui Pemberdayaan Keluarga Di Kelurahan Tamansari Kota BandungDokumen7 halamanPeningkatan Pengetahuan Dan Sikap Kepala Keluarga Tentang Pengelolaan Sampah Melalui Pemberdayaan Keluarga Di Kelurahan Tamansari Kota BandungtinaBelum ada peringkat
- 26A Goldia Erando Ginting HK Lingkungan UASDokumen7 halaman26A Goldia Erando Ginting HK Lingkungan UASkaijeBelum ada peringkat
- LK 10 - Eksplorasi Alternatif Solusi Masalah (Modul P5 Dan PPRA) OkDokumen6 halamanLK 10 - Eksplorasi Alternatif Solusi Masalah (Modul P5 Dan PPRA) OkHusaini CoolBelum ada peringkat
- rmsl,+482-492+EKA+B +Z +PAMEKAS+ (14021105035)Dokumen11 halamanrmsl,+482-492+EKA+B +Z +PAMEKAS+ (14021105035)dimasprastiiaBelum ada peringkat
- 127949-T 00974 Faktor-Faktor Yang - Kesimpulan PDFDokumen13 halaman127949-T 00974 Faktor-Faktor Yang - Kesimpulan PDFinne wahyuniBelum ada peringkat
- Makalah MAN 2 Malang SOSHUM - 3Dokumen8 halamanMakalah MAN 2 Malang SOSHUM - 3gamers IndonesiaBelum ada peringkat
- 33198-Article Text-40580-1-10-20200508Dokumen9 halaman33198-Article Text-40580-1-10-20200508nurulBelum ada peringkat
- Makalah Pai UAS Mitigasi Bencana BanjirDokumen12 halamanMakalah Pai UAS Mitigasi Bencana BanjirChika SheilaBelum ada peringkat
- Tugas LK 10 IFAHDokumen5 halamanTugas LK 10 IFAHNana MulyanaBelum ada peringkat
- Fullpapers Jpm9230107744fullDokumen20 halamanFullpapers Jpm9230107744fullTaufik HidayatBelum ada peringkat
- MODUL AJAR - IPAS - Bambang Hariyadi - SMKN 9 SKA 23-24 - Bams HariyadiDokumen177 halamanMODUL AJAR - IPAS - Bambang Hariyadi - SMKN 9 SKA 23-24 - Bams HariyadiSiti Ridha HidayatiBelum ada peringkat
- Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan LingkungDokumen9 halamanPartisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan LingkungsummeraprilyaBelum ada peringkat
- Pemb Yang BerkelanjutanDokumen14 halamanPemb Yang BerkelanjutanRirin LestariBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen16 halaman1 PBJanuarko AdiBelum ada peringkat
- Pengelolaan Pembuangan Sampah Melalui Aspek SosialDokumen8 halamanPengelolaan Pembuangan Sampah Melalui Aspek Sosialwika dhoraBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen5 halamanBab 1alfatianimambiBelum ada peringkat
- Sifa Salsabila - JurnallokalDokumen2 halamanSifa Salsabila - JurnallokalSifa SalsabilaBelum ada peringkat
- Jurnal Tentang Pengelolaan SampahDokumen12 halamanJurnal Tentang Pengelolaan SampahFaizal AriantoBelum ada peringkat
- Kelembagaan AirDokumen180 halamanKelembagaan AirDicky AditamaBelum ada peringkat
- Rati Alpita SariDokumen176 halamanRati Alpita SariAlya Mahastra PutriBelum ada peringkat
- Au Ah Gjls 5Dokumen21 halamanAu Ah Gjls 5INDAH PERMATASARI HUTAGALUNGBelum ada peringkat
- Mapel Project Ipas (Pendahuluan)Dokumen18 halamanMapel Project Ipas (Pendahuluan)lastriBelum ada peringkat
- Materi Mata Kuliah PKLHDokumen5 halamanMateri Mata Kuliah PKLHAnonymous Kgpoh02pBelum ada peringkat
- Review JurnalDokumen21 halamanReview JurnalYuniar WidyaBelum ada peringkat
- Laporan Geografi PermukimanDokumen18 halamanLaporan Geografi PermukimanwildaBelum ada peringkat
- Report 1 CTUDokumen9 halamanReport 1 CTUgsm_gurl91Belum ada peringkat
- Rencana Gerakan Peduli Dan Perbudya Lingkungan Hidup2021Dokumen27 halamanRencana Gerakan Peduli Dan Perbudya Lingkungan Hidup2021dwi purwaningsihBelum ada peringkat
- Loka 10Dokumen6 halamanLoka 10Joe DaveBelum ada peringkat
- Analisis Jurnal Perilaku Kesehatan MasyarakatDokumen55 halamanAnalisis Jurnal Perilaku Kesehatan Masyarakatimroatul faizahBelum ada peringkat
- DL 15 (7.00 WITA) - Revisi ProposalDokumen29 halamanDL 15 (7.00 WITA) - Revisi ProposalIrfan sosantroBelum ada peringkat
- Tugas.1 Materi Dan Pembelajaran Ips SDDokumen4 halamanTugas.1 Materi Dan Pembelajaran Ips SDswandewipradnyaBelum ada peringkat
- Tujuan, Alur, Target ProjekDokumen4 halamanTujuan, Alur, Target Projekfhyan hadiatBelum ada peringkat
- LAPORAN Praktek Lapangan PLH Ririn Octaviani 1812140006Dokumen14 halamanLAPORAN Praktek Lapangan PLH Ririn Octaviani 1812140006Aimer RainBelum ada peringkat
- Swedish Eco-Villages Edit Kuisioner - En.idDokumen23 halamanSwedish Eco-Villages Edit Kuisioner - En.idRizal 83Belum ada peringkat
- 2 PBDokumen11 halaman2 PBNeng raniBelum ada peringkat
- PKLHDokumen27 halamanPKLHAhmad MaksumiBelum ada peringkat
- ID Peran Serta Masyarakat Dalam MeningkatkaDokumen10 halamanID Peran Serta Masyarakat Dalam MeningkatkaAisah Cory PrasonoBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen4 halaman1 SMSimamora Darsib CmraBelum ada peringkat
- Pengantar Geo - Muhamad Rizkan - 2310416310022 - 4 Pendekatan EkologiDokumen4 halamanPengantar Geo - Muhamad Rizkan - 2310416310022 - 4 Pendekatan Ekologi2310416310022Belum ada peringkat
- Das Air BengkuluDokumen58 halamanDas Air BengkuluDenny Boy MochranBelum ada peringkat
- Resume Studium Generale Program Studi Perencanaan Wilayah Dan KotaDokumen5 halamanResume Studium Generale Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kotatari bertaBelum ada peringkat
- Kesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikDari EverandKesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikBelum ada peringkat
- ILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuDari EverandILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (6)
- Langkah-Langkah menuju Pengetahuan (AH1-Indonesian Edition)Dari EverandLangkah-Langkah menuju Pengetahuan (AH1-Indonesian Edition)Belum ada peringkat