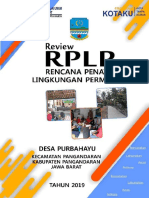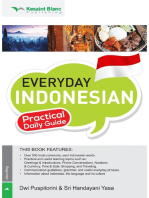Laporan Akhir Kajian Kontur Tanah
Laporan Akhir Kajian Kontur Tanah
Diunggah oleh
HavelJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Laporan Akhir Kajian Kontur Tanah
Laporan Akhir Kajian Kontur Tanah
Diunggah oleh
HavelHak Cipta:
Format Tersedia
KATA PENGANTAR
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
1
Kabupaten Karawang
KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Kami mengucapkan puji dan syukur setinggi-tingginya pada Tuhan Yang
Maha Esa atas kesempatan, kesehatan, dan waktu yang berharga telah diberikan
pada kami sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan tepat waktu. Kami juga
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang untuk
menjalankan amanat dalam kegiatan “Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik
Bencana Kabupaten Karawang”.
Kami menyadari pentingnya kajian penyusunan kontur tanah dan
karakteristik bencana Kabupaten Karawang terutama di Desa Karangligar,
Kecamatan Telukjambe Barat. Kajian ini dilakukan dalam rangka mengidentifikasi
ancaman bencana khususnya banjir serta fenomena penurunan tanah di Desa
Karangligar. Dari kajian ini nantinya akan teridentifikasi karakteristik bencana dan
permasalahan mengenai penurunan kontur tanah di Desa Karangligar. Selain itu
kajian ini juga akan menghasilkan arahan berupa alternatif dan solusi untuk
mengantisipasi fenomena penurunan kontur tanah di Desa Karangligar.
Kami menyadari dalam penyusunan laporan akhir ini tentunya terdapat
kelemahan dan kelebihan. Untuk itu, kami selalu terbuka untuk masukan yang
membangun dari berbagai pihak yang terkait. Sekali lagi kami mengucapkan
terima kasih pada BPBD Kabupaten Karawang serta semua pihak yang telah
membantu hingga selesainya laporan ini.
Hormat Kami,
Tim Penyusun
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
ii
Kabupaten Karawang
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
Latar Belakang .................................................................................................................. 1
Maksud dan Tujuan ........................................................................................................ 2
Ruang Lingkup Kegiatan .............................................................................................. 2
Ruang Lingkup Pekerjaan................................................................................... 2
Ruang Lingkup Wilayah ...................................................................................... 3
Kerangka Pemikiran ....................................................................................................... 4
Sistematika Penulisan .................................................................................................... 6
Geologi Regional ............................................................................................................. 8
Fisiografi Regional................................................................................................. 8
Stratigrafi Regional ............................................................................................. 10
Kondisi Geologi Daerah Penelitian ............................................................... 12
Daerah Aliran Sungai Citarum .................................................................................. 13
Gambaran Umum Wilayah Sungai Citarum .............................................. 13
Pola Curah Hujan ................................................................................................. 17
Kinerja DAS Citarum Hulu ................................................................................ 17
Permasalahan di Wilayah Sungai Citarum ................................................. 23
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
iii
Kabupaten Karawang
DAFTAR ISI
Rencana Pembangunan Waduk Cibeet ...................................................... 26
Perkembangan Kawasan Industri dan Kawasan Perkotaan Karawang ..... 27
Kebencanaan .................................................................................................................. 30
Guna Lahan...................................................................................................................... 33
Sosial Ekonomi ............................................................................................................... 36
Prasarana, Sarana dan Utilitas .................................................................................. 43
Aktivitas Eksplorasi dan Eksploitasi Migas........................................................... 46
Geologi .............................................................................................................................. 49
Geomorfologi........................................................................................................ 49
Satuan Geologi Teknik....................................................................................... 56
Kondisi Hidrogeologi Umum .......................................................................... 62
Penataan Pemanfaatan Ruang ................................................................................. 64
Peningkatan Kapasitas Terhadap Bencana .......................................................... 66
Peningkatan Koordinasi Para Pemangku Kepentingan .................................. 67
Pembangunan Sistem Peringatan Dini ................................................................. 68
Pembangunan Kolam Retensi .................................................................................. 68
Peralihan Kegiatan Perekonomian.......................................................................... 71
Upaya Mitigasi Terhadap Bencana Desa Karangligar...................................... 73
Kesimpulan ...................................................................................................................... 80
Rekomendasi .................................................................................................................. 82
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
iv
Kabupaten Karawang
DAFTAR TABEL
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Deskripsi Satuan Batuan di Sekitar Kecamatan Telukjambe Barat ....... 13
Tabel 2.2 Tabel Koefisien Aliran Permukaan DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014
............................................................................................... 19
Tabel 2.3 KRS DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014 ...................................... 20
Tabel 2.4 Tabel Qs DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014 ............................... 21
Tabel 2.5 Tabel Tutupan Lahan DAS Ciatarum Hulu Tahun 2013...................... 23
Tabel 2.6 Permasalahan di Wilayah Sungai Citarum....................................... 23
Tabel 2.7 Perubahan Penggunaan Lahan DAS Citarum Hulu Tahun 2001-2011 .. 25
Tabel 2.8 Data Perkembangan Industri di Kabupaten Karawang Tahun 2011-2015
(unit) ....................................................................................... 27
Tabel 3.1 Kejadian Bencana di Desa Karangligar Januari 2016-April 2017 ......... 31
Tabel 3.2 Peta Fungsi Lahan Desa Karangligar Tahun 2014 ............................. 33
Tabel 3.3 Penggunaan Lahan Pertanian Karangligar Tahun 2014 ..................... 33
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan Penduduk
Desa Karangligar ....................................................................... 36
Tabel 3.5 Jumlah Menurut Jenis Kelamin ..................................................... 37
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kampung Pangasinan dan Kampung Kampek
Terdampak Bencana Banjir .......................................................... 37
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
v
Kabupaten Karawang
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1 Peta Delineasi Wilayah Desa Karangligar .................................... 3
Gambar 2.1 Peta Kondisi Geologi Lokasi Penelitian ....................................... 9
Gambar 2.2 Penampang Stratigrafi Utara-Selatan Jawa Barat ........................ 11
Gambar 2.3 Penampang Utara-Selatan Di Sekitar Kecamatan Telukjambe ...... 12
Gambar 2.4 Peta Wilayah Sungai Citarum .................................................. 14
Gambar 2.5 Skema Sungai Citarum ........................................................... 16
Gambar 2.6 Skema DAS Citarum Hilir ........................................................ 16
Gambar 2.7 Analisis Hidrologi Wilayah DAS Cibeet ..................................... 17
Gambar 2.8 Koefisien Aliran Permukaan DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014 . 19
Gambar 2.9 Koefisien Regim Sungai DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014 ...... 21
Gambar 2.10 Koefisien Regim Sungai DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014 ...... 22
Gambar 2.11 Data Perkembangan Industri di Kabupaten Karawang Tahun 2011-
2015 (unit)............................................................................ 28
Gambar 2.12 Perkembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Industri Kabupaten
Karawang ............................................................................. 29
Gambar 3.1 Peta Fungsi Lahan Karangligar Tahun 2014 ............................... 34
Gambar 3.2 Peta Penggunaan Lahan Pertanian Karangligar Tahun 2014 ......... 35
Gambar 3.3 Peta Titik Observasi Lahan Pertanian Di Desa Karangligar ............ 38
Gambar 3.4 Peta Titik Observasi Genangan Di Desa Karangligar .................... 42
Gambar 3.5 Kondisi Pemancingan Ikan di Area Genangan ............................ 43
Gambar 3.6 Peta Titik Observasi Kondisi Jalan Di Desa Karangligar ..... 44
Gambar 3.7 Kondisi Irigasi di Desa Karangligar ........................................... 44
Gambar 3.8 Peta Lokasi Fasilitas Sosial dan Kantor Desa Karangligar ............. 45
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
vi
Kabupaten Karawang
DAFTAR GAMBAR
Gambar 3.9 Kondisi Banjir di SMPN 1 Telukjambe Barat ............................... 45
Gambar 3.10 Penanda Jalur Evakuasi di Kantor Desa Karangligar .................... 46
Gambar 3.11 Peta Lokasi Sumur eksplorasi PT Pertamina EP dan SP Cicauh ...... 48
Gambar 3.12 Perahu Karet Milik dan Layout layout APAR, Hydrant, Fire Hose, dan
Jalur Evakuasi di SP Cicauh ..................................................... 48
Gambar 3.13 Peta Pola Aliran Sungai Daerah Penelitian ................................. 50
Gambar 3.14 Citra Satelit yang Diambil Dari Tahun 2000 Hingga 2016 ............. 51
Gambar 3.15 Peta Kontur di Desa Karangligar dan Sekitarnya pada tahun 2007
(kiri) dan 2015 (kanan)............................................................ 52
Gambar 3.16 Peta Pola Aliran Sungai Daerah Penelitian ................................. 53
Gambar 3.17 Morfologi Perbukitan Barisan Yang Memanjang Barat-Timur Di
Sebelah Selatan Desa Karangligar ............................................ 55
Gambar 3.18 Morfologi Dataran Rendah Karangligar Yang Relatif Memanjang
Dari Barat-Timur.................................................................... 56
Gambar 3.19 Peta Geologi Teknik Desa Karangligar dan Sekitarnya ................. 57
Gambar 3.20 Singkapan Satuan Tanah Residual Batupasir .............................. 58
Gambar 3.21 Singkapan Satuan Endapan Dataran Banjir ................................ 60
Gambar 3.22 Singkapan Satuan Endapan Sungai .......................................... 61
Gambar 3.23 Rembesan Yang Terjadi Di Sungai Di Sebelah Barat Desa Karangligar
(Kiri) Dan Kenampakan Sungai Cabang Dari Sungai Cibeet (Kanan)
........................................................................................... 63
Gambar 4.1 Sketsa Kolam Retensi ............................................................. 69
Gambar 4.2 Skema Pengendalian Banjir Untuk Desa Karangligar ................... 70
Gambar 4.3 Jarak Dari Genangan Eksting ke Sungai Citarum dan Cibeet ........ 71
Gambar 5.1 Alternatif Rekomendasi Pertama ............................................. 86
Gambar 5.2 Alternatif Rekomendasi Kedua ................................................ 88
Gambar 5.3 Geodetik GPS ....................................................................... 82
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
vii
Kabupaten Karawang
DAFTAR GAMBAR
Gambar 5.4 Total Station ......................................................................... 83
Gambar 5.5 Piezocone ............................................................................ 83
Gambar 5.6 Bor...................................................................................... 83
Gambar 5.7 Grafik Piezocone ................................................................... 84
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
viii
Kabupaten Karawang
PENDAHULUAN
PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai bagian pendahuluan Kajian Kontur Tanah dan
Karakteristik Bencana Kabupaten Karawang meliputi latar belakang kajian,
maksud dan tujuan kajian, ruang lingkup kajian, kerangka pemikiran, serta
sistematika penulisan.
Latar Belakang
Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan pesat yang tidak
mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan karakteristik bencana
mengakibatkan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah penurunan kontur
tanah. Kabupaten Karawang merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang
mengalami permasalahan penurunan kontur tanah dikarenakan pembangunan
dan investasi yang masuk tidak mempertimbangkan daya dukung lingkungan.
Dampak dari pembangunan yang tinggi di Kabupaten Karawang, banyak
lahan pertanian yang mengalami alih fungsi. Padahal pada tahun 2010 disebutkan
bahwa Kabupaten Karawang merupakan salah satu penyumbang produksi beras
tertinggi di Jawa Barat dimana Jawa Barat merupakan sentra produksi nasional
(Wulandari dkk, 2012).
Seringkali alih fungsi lahan dianggap sebagai salah satu jawaban atas
permintaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas dan lokasi
aktivitas. Namun, hal ini mengakibatkan berkurangnya lahan terbuka seperti
lahan pertanian yang juga dapat berfungsi sebagai daerah untuk resapan air.
Kurangnya lahan resapan air (water catchment area) mengakibatkan tingginya
laju limpasan air (run off) yang menggenangi daerah dengan kontur tanah yang
mengalami penurunan signifikan. Adapun penurunan kontur tanah juga dapat
diakibatkan adanya eksploitasi atau pemanfaatan berlebih pada air bawah tanah.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
1
Kabupaten Karawang
PENDAHULUAN
Kecamatan Telukjambe Barat, khususnya Desa Karangligar merupakan
daerah dengan kerentanan tertinggi akan bencana banjir dan penurunan kontur
tanah di wilayah Karawang Barat. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi
permasalahan penurunan kontur tanah dan bencana banjir yang kerap kali
melanda Kabupaten Karawang, terutama pada Kecamatan Telukjambe Barat,
dilakukanlah kajian ini sebagai upaya untuk mengendalikan pembangunan dan
pemanfaatan lahan. Labih lanjut, kajian ini dimaksudkan pula agar pemanfaatan
lahan Kabupaten Karawang ke depannya berada pada koridor pembangunan
yang tetap memperhatikan karakteristik bencana.
Maksud dan Tujuan
Maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan penyusunan kajian
kontur tanah dan karakteristik bencana Kabupaten Karawang dengan mengambil
fokus pada Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang. Sejalan dengan
maksud tersebut, tujuan dari kegiatan ini adalah menyusun alternatif solusi dan
rekomendasi terkait dengan antisipasi terhadap fenomena penurunan kontur
tanah di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.
Ruang Lingkup Kegiatan
Ruang lingkup pembahasan pekerjaan ini terdiri dari lingkup pekerjaan
dan lingkup wilayah.
Ruang Lingkup Pekerjaan
Kegiatan Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana Kabupaten
Karawang ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:
1) Melakukan penelusuran terhadap kebijakan pemerintah dalam RPJP,
RPJM, RTRW, RDTR, dan dokumen perencanaan lainnya.
2) Mengidentifikasi karakteristik bencana di Desa Karangligar, Kecamatan
Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.
3) Mengidentifikasi permasalahan mengenai penurunan kontur tanah di
Kecamatan Telukjambe Barat.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
2
Kabupaten Karawang
PENDAHULUAN
4) Melakukan kajian ketidaksesuaian pemanfaatan lahan dengan daya
dukung lingkungan di Kabupaten Karawang serta karakteristik dan
susunan tanah dan batuan Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe
Barat.
5) Menyusun arahan sebagai alternatif dan solusi untuk antisipasi terhadap
fenomena penurunan kontur tanah di Desa Karangligar, Kecamatan
Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang.
Ruang Lingkup Wilayah
Lingkup wilayah Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang dilakukan di Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat
sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.1 berikut ini.
Gambar 1.1 Peta Delineasi Wilayah Desa Karangligar
Sumber: Hasil Analisis, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
3
Kabupaten Karawang
PENDAHULUAN
Kerangka Pemikiran
Pelaksanaan kajian ini akan diurutkan dari latar belakang hingga
kesimpulan dan rekomendasi melalui kerangka pemikiran pada Gambar 1.2
berikut ini.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
4
Kabupaten Karawang
PENDAHULUAN
Pada tahun 2007, Kecamatan Sejak tahun 2009-2017, Desa
Telukjambe Barat dilanda Karangligar dilanda banjir Ancaman banjir yang
banjir besar salah satunya paling parah dibandingkan semakin parah diduga akibat
Desa Karangligar desa-desa sekitarnya terjadinya penurunan tanah
Adanya genangan yang
terbentuk sepanjang tahun di
lahan pertanian Desa
Perlu dilakukan kajian
Karangligar
mengenai fenomena
penurunan tanah dan
karakteristik bencana Desa
Karangligar
Kajian Kontur Tanah dan
Karakteristik Bencana
Menyusun alternatif solusi dan rekomendasi terkait dengan
antisipasi terhadap fenomena penurunan kontur tanah di Desa
Karangligar
Penelusuran Identifikasi
Identifikasi
terhadap kebijakan permasalahan
karakteristik bencana
pemerintah di dalam penurunan kontur
di Desa Karangligar
dokumen tanah di Desa
perencanaan Karangligar
Analisis
Analisis karakteristik
ketidaksesuaian
dan susunan tanah
pemanfaatan lahan
dan batuan Desa
dengan daya dukung
Karangligar
lingkungan
Arahan alternatif dan solusi untuk antisipasi terhadap
fenomena penurunan kontur tanah di Desa Karangligar
Gambar 1.2 Kerangka Pemikiran Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik
Bencana Desa Karangligar
Sumber: Hasil Analisis, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
5
Kabupaten Karawang
PENDAHULUAN
Sistematika Penulisan
Dalam penyusunan laporan antara Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik
Bencana Kabupaten Karawang, sistematika penulisannya adalah sebagai berikut
ini.
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menjelaskan mengenai bagian pendahuluan Kajian Kontur Tanah Dan
Karakteristik Bencana Kabupaten Karawang meliputi latar belakang kajian,
maksud dan tujuan kajian, ruang lingkup kajian, kerangka pemikiran, serta
sistematika penulisan.
BAB 2 KAJIAN KEWILAYAHAN
Bab ini menjelaskan mengenai kajian kewilayahan Desa Karangligar meliputi
geologi regional, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, dan perkembangan
pembangunan di Kabupaten Karawang. Kajian mengenai geologi regional
membahas terkait fisiografi dan stratigrafi regional serta kondisi geologi di
daerah penelitian dan sekitarnya. Selanjutnya kajian mengenai DAS Citarum
membahas mengenai gambaran umum Wilayah Sungai Citarum, pola curah
hujan, kinerja DAS Citarum, permasalahan di Wilayah Sungai Citarum, dan
rencana pembangunan Waduk Cibeet.
BAB 3 KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Bab ini menjelaskan mengenai kajian lapangan Desa Karangligar meliputi kondisi
wilayah dan kondisi geologi berdasarkan hasil pengumpulan data. Penjelasan
mengenai kondisi wilayah Desa Karangligar berupa kondisi kebencanaan; guna
lahan; sosial ekonomi; prasarana, sarana, dan utilitas; aktivitas eksplorasi dan
eksploitasi migas; dan kondisi geologi.
BAB 4 MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA PENURUNAN MUKA
TANAH
Bab ini menjabarkan mengenai upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu dilakukan
dalam menghadapi fenomena penurunan tanah di Desa Karangligar.
BAB 5 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
6
Kabupaten Karawang
PENDAHULUAN
Bab ini menjabarkan mengenai kesimpulan dan alternatif rekomendasi
berdasarkan hasil kajian laporan akhir ini.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
7
Kabupaten Karawang
KAJIAN KEWILAYAHAN
KAJIAN KEWILAYAHAN
Bab ini menjelaskan mengenai kajian kewilayahan Desa Karangligar meliputi
geologi regional, Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, dan perkembangan
pembangunan di Kabupaten Karawang. Kajian mengenai geologi regional
membahas terkait fisiografi dan stratigrafi regional serta kondisi geologi di
daerah penelitian dan sekitarnya. Selanjutnya kajian mengenai DAS Citarum
membahas mengenai gambaran umum Wilayah Sungai Citarum, pola curah
hujan, kinerja DAS Citarum, permasalahan di Wilayah Sungai Citarum, dan
rencana pembangunan Waduk Cibeet.
Geologi Regional
Pembahasan mengenai geologi regional terdiri dari fisiografi dan
stratigrafi regional serta kondisi geologi di daerah penelitian dan sekitarnya.
Fisiografi Regional
Penelitian gerakan tanah ini dilakukan di daerah Karawang, Jawa Barat,
untuk peta lokasi daerah penelitiannya dapat dilihat pada Gambar 2.1. Van
Bemmelen (1949) membagi fisiografi Jawa Barat menjadi 4 bagian besar zona
fisiografi, yaitu: Zona Bogor, Zona Bandung, Dataran Pantai Jakarta, dan Zona
Pegunungan Selatan Jawa Barat. Berdasarkan pembagian zona fisiografi tersebut,
daerah penelitian termasuk di Zona Dataran Pantai Jakarta yang menempati
bagian utara Jawa membentang barat-timur mulai dari Serang, Jakarta, Subang,
Indramayu, hingga Cirebon. Daerah ini bermorfologi dataran dengan batuan
penyusun terdiri atas aluvium sungai/pantai dan endapan gunung api muda.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 8
KAJIAN KEWILAYAHAN
Gambar 2.1 Peta Kondisi Geologi Lokasi Penelitian
Sumber: Achdan dan Sudana, 1992
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 9
KAJIAN KEWILAYAHAN
Stratigrafi Regional
Martodjojo (2003) dalam tesis doktornya membagi daerah Jawa Barat
menjadi 3 mandala sedimentasi yaitu Mandala Paparan Kontinen, Mandala
Cekungan Bogor, dan Mandala Banten. Dasar pembagian mandala ini umumnya
berdasarkan ciri dan penyebaran sedimen Tersier dari stratigrafi regional di Jawa
bagian barat. Pada Tersier Awal pengembangan sedimentasi Mandala Banten
menyerupai Mandala Cekungan Bogor. Namun, pada Tersier Akhir lebih
menyerupai dengan Mandala Paparan Kontinen Utara (Martodjojo, 1984).
Berdasarkan pembagian mandala sedimentasi, daerah penelitian terletak pada
Mandala Cekungan Bogor. Mandala sedimentasi Cekungan Bogor meliputi zona
fisiografi van Bemmelen (1949) yaitu Zona Bogor, Zona Bandung dan
Pegunungan Selatan. Mandala ini dicirikan oleh endapan aliran gravitasi yang
umumnya berupa fragmen batuan beku dan sedimen, seperti andesit, basalt, tufa,
dan gamping.
Mandala Cekungan Bogor menurut Martodjojo (2003) mengalami
perubahan dari waktu ke waktu sepanjang zaman Tersier-Kuarter. Mandala ini
terdiri dari tiga siklus pengendapan, diawali dengan diendapkannya sedimen laut
dalam hasil mekanisme aliran gravitasi dari arah selatan menuju utara. Kemudian
pada Miosen Awal diendapkannya endapan gunung api yang berasal dari selatan
Pulau Jawa yang bersifat basalt-andesit. Diakhiri dengan pendangkalan Cekungan
Bogor kearah utara dimulai pada Miosen Tengah menghasilkan Formasi Subang
dan Formasi Kaliwangu yang menunjukkan lingkungan pengendapan paparan
sampai transisi.
Pada Miosen Akhir terendapkan suatu fasies turbidit lokal akibat adanya
lereng terjal di sebelah selatan cekungan. Fasies tersebut dinamakan dengan
Anggota Cikandung (Martodjojo, 1984), yang terbentuk pada tahap akhir dari
proses pendangkalan Cekungan Bogor. Pada kala Pliosen Cekungan Bogor telah
berubah menjadi darat yang kemudian diendapkan Formasi Citalang. Lebih lanjut,
Martodjojo (2003) telah membuat penampang stratigrafi terpulihkan utara-
selatan di Jawa Barat (Gambar 2.2).
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 10
KAJIAN KEWILAYAHAN
Gambar 2.2 Penampang Stratigrafi Utara-Selatan Jawa Barat
Sumber: Martodjojo, 2003
Di sebelah utara cekungan, batuan tertua yang dapat diteliti adalah
batuan basalt andesit dan tufa berumur Kapur hingga Eosen yang merupakan
Formasi Jatibarang. Di atas formasi ini diendapkan secara tidak selaras Formasi
Cibulakan yang berumur Miosen Tengah. Ciri litologi formasi ini adalah berupa
serpih karbonat berwarna coklat keabu-abuan dengan sisipan lapisan batubara di
bagian bawah, batugamping berwarna putih kotor dengan sisipan serpih dan
pasir tipis di bagian tengah, dan pasir gampingan berselang-seling dengan napal
dan lempung di bagian atas. Lingkungan pengendapan dari formasi ini berupa
marin dangkal.
Di daerah Leuwiliang yang merupakan sebelah barat dari sebaran formasi
ini, formasi ini berubah fasies menjadi Formasi Bojongmanik dengan lingkungan
pengendapan berupa daerah transisi antara pantai sampai lagoon. Formasi
Bojongmanik ini memiliki kisaran umur yang hamper sama dengan Formasi
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 11
KAJIAN KEWILAYAHAN
Cibulakan, yakni Miosen Tengah (N9-N13) (Martodjojo, 2003). Di atas Formasi
Cibulakan diendapkan secara selaras Formasi Parigi yang berupa satuan
batugamping di Jawa Barat. Formasi Subang diendapkan secara selaras di atas
Formasi Parigi. Ciri litologi Formasi Subang berupa lempung berlapis yang
semakin ke atas berubah menjadi pejal dan tak berlapis dan lempung berwarna
coklat. Formasi Subang ditutupi secara selaras oleh Formasi Kaliwangu yang
umumnya terdiri dari batupasir dan batulempung (Martodjojo, 2003).
Kondisi Geologi Daerah Penelitian
Kecamatan Telukjambe Barat berada pada daerah aliran Sungai Citarum
(Gambar 2.3 dan Tabel 2.1) yang memperlihatkan adanya Satuan Endapan Sungai
Muda (Qa), Satuan Endapan Dataran Banjir (Qaf), dan Satuan Batupasir
Konglomeratan dan Batulanau. Penampang C-D memperlihatkan struktur bawah
permukaan khususnya di sekitar Kecamatan Telukjambe dengan keterangan pada
Tabel 2.1.
Gambar 2.3 Penampang Utara-Selatan Di Sekitar Kecamatan Telukjambe
Sumber: Achdan dan Sudana, 1992
Endapan Kuarter (Q) merupakan satuan tanah atau batuan yang berumur
paling muda dan belum terkonsolidasi. Ketebalan endapan kuarter di Desa
Karangligar dan sekitarnya sekitar 30 meter. Apabila endapan yang belum
terkonsolidasi tersebut terkena beban tambahan dari atas, maka lapisan tanah
atau batuan akan mengalami pemadatan yang akan mengganggu struktur
bangunan yang dibangun diatasnya. Sehingga apabila infrastruktur akan
dibangun diatas endapan tersebut harus mempertimbangkan upaya untuk
menstabilkan endapan tersebut.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 12
KAJIAN KEWILAYAHAN
Formasi Subang (Tms) sebagai formasi yang tersebar luas yang
mengandung lempung tersier memiliki karakteristik fisik dan keteknikan tertentu
yang berhubungan dengan permasalahan pekerjaan keteknikan pada tanah
lempung Subang. Terdapat sejumlah kerusakan infrastruktur bangunan fisik yang
didirikan di atas lempung Formasi Subang disebabkan oleh sifat keteknikan
lempung Formasi Subang yang khas. Sifat batuan Formasi Subang yang dapat
membahayakan antara lain: sifat mengembang (expansive), konsolidasi dan
derajat pelapukan.
Simbol Nama Keterangan
Endapan Sungai Terdiri dari pasir, kerikil dan kerakal
Muda
Satuan Endapan Terdiri dari pasir lempungan, lempung pasiran
Dataran Banjir dan lempung humusan/gambutan
Satuan Batupasir Terdiri dari batupasir konglomeratan,
Konglomeratan batulanau dan batupasir
dan Batulanau
Formasi Subang Terdiri dari batulempung, batupasir dan
batugamping pasiran
Tabel 2.1 Deskripsi Satuan Batuan di Sekitar Kecamatan Telukjambe Barat
Sumber: Achdan dan Sudana, 1992
Daerah Aliran Sungai Citarum
Pembahasan mengenai Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum meliputi
gambaran umum Wilayah Sungai (WS) Citarum, pola curah hujan, kinerja DAS
Citarum, permasalahan di WS Citarum, dan rencana pembangunan Waduk Cibeet.
Gambaran Umum Wilayah Sungai Citarum
Sungai Citarum merupakan Wilayah Sungai terbesar dan terpanjang di
Propinsi Jawa Barat Dengan panjang sungai 269 km dan total area DAS Citarum
sebesar 12.000 km2. Penduduk yang dilayani adalah sebanyak 25 juta jiwa (15 Juta
Jiwa di Jawa Barat, dan 10 juta jiwa di DKI Jakarta). Sungai Citarum merupakan
sumber air baku bagi 80% penduduk Jakarta. Tiga Bendungan di Citarum
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 13
KAJIAN KEWILAYAHAN
meliputi: Jatiluhur (1963), Saguling (1986), dan Cirata (1988). Daya listrik yang di
hasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Air yaitu 1.400 Megawatt.
DAS Sungai Citarum melalui 9 Kabupaten dan 3 Kota meliputi Kabupaten
Bandung Barat, Bandung, Subang, Purwakarta, Karawang, Sumedang, Cianjur,
Bekasi, Indramayu serta Kota Bandung, Bekasi dan Cimahi. Total potensi air di
Wilayah Sungai Citarum adalah sebesar 13 milyar m3/tahun. Potensi air yang
sudah dimanfaatkan sebanyak 7.5 milyar m3/tahun (57,9%) dan yang belum
dimanfaatkan 5,45 milyar m3/tahun (42,1%).
Gambar 2.4 Peta Wilayah Sungai Citarum
Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 14
KAJIAN KEWILAYAHAN
Wilayah Sungai ini meliputi 5 DAS yaitu DAS Citarum, DAS Cipunegara, DAS
Cilamaya, DAS Cilalanang dan DAS Ciasem. Wilayah Sungai Citarum dapat dilihat
secara jelas pada Gambar 2.4. Untuk memudahkan penanganan, WS Citarum
dibagi menjadi tiga bagian:
1) Citarum Hulu: wilayah hulu sungai di Gunung Wayang hingga ujung
Saguling
2) Citarum Tengah: wilayah diantara tiga waduk Saguling-Cirata-Jatiluhur
3) Citarum Hilir: wilayah Citarum Hilir hingga Muara Citarum di daerah
Muara Gembong, Laut Jawa
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 15
KAJIAN KEWILAYAHAN
Gambar 2.5 Skema Sungai Citarum
Sumber: Imansyah, 2012
Sungai Citarum sebagai sungai utama di WS Citarum memiliki panjang
269 km. Sungai ini bermula dari mata air di Gunung Wayang (Kabupaten
Bandung) melewati Kabupaten Bandung/Bandung Barat, Kabupaten Cianjur,
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang/Bekasi dan bermuara di Muara
Gembong, Laut Jawa. Skema Sungai Citarum digambarkan pada Gambar 2.5.
Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum Hilir dibagi menjadi 8 sub-DAS, yaitu:
Cikao, Cilangkap, Ciampel, Cibalukbuk, Cipatunjang, Cijambe, Cisubah, dan
Cibeet. Skematisasi sungai-sungai yang ada di Citarum Hilir terlihat pada Gambar
2.6.
Gambar 2.6 Skema DAS Citarum Hilir
Sumber: Sumber: Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum
Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab banjir di Desa
Karangligar adalah karena luapan dari Sungai Cibeet. Menurut data dari BBWS
Citarum Tahun 2013, Sungai Cibeet memiliki panjang sungai 60 km dengan luas
DAS sebesar 480 km2. Sumber Mata Air sungai ini berasal dari Gunung
Singgabuana dan bermuara di Sungai Citarum. Daerah yang dilewati Sungai
Cibeet adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang
dengan debit maksimal 212,46 m3/detik dan debit minimal 2,19 m3/detik. Selain
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 16
KAJIAN KEWILAYAHAN
itu, Sungai Cibeet memiliki 5 Anak Sungai dan 1 Bendungan. Pos Cibeet
merupakan satu-satunya Stasiun Hujan DAS Citarum di Kabupaten Karawang
yaitu di Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat.
Pola Curah Hujan
Curah hujan harian maksimum di Wilayah DAS Cibeet meningkat drastis
pada tahun 2010 dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun yang
sama juga terjadi banjir besar di Desa Karangligar dan mulai membentuk
genangan permanen.
Gambar 2.7 Analisis Hidrologi Wilayah DAS Cibeet
Sumber: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum
Tahun 2016
Kinerja DAS Citarum Hulu
Secara administrasi DAS Citarum Hulu terdapat dalam wilayah Kabupaten
Bandung (56,24%), Kabupaten Bandung Barat (29,26%), Kota Bandung (6,53%),
Kota Cimahi (1,76%), Kabupaten Sumedang (5,5%), dan Kabupaten Garut (0,71%).
Berdasarkan sistem percabangan sungainya DAS Citarum dibagi menjadi 8 sub
DAS. Sub DAS yang paling luas adalah Cirasea (16,51%) yang diikuti Cisangkuy
(14,80%), Ciminyak (14,11%), Cikapundung-Cipamokolan (13,20%), Cihaur
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 17
KAJIAN KEWILAYAHAN
(12,12%), Citarik (9,94%), Ciwidey (9,61%), dan Cikeruh (8,24%) (Hidayat et al.
2013).
Koefisien Aliran Permukaan
Koefisien Aliran Permukaan merupakan perbandigan tinggi limpasan
dengan tinggi curah hujan. Lalu untuk koefisien Aliran Permukaan DAS Citarum
Hulu Tahun 2009-2014 dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 18
KAJIAN KEWILAYAHAN
Tabel 2.2 Tabel Koefisien Aliran Permukaan DAS Citarum Hulu Tahun 2009-
2014
Tahun Koefisien Aliran Sungai
2009 0,41
2010 0,55
2011 0,43
2012 0,31
2013 0,52
2014 0,64
Rata-rata 0,48
Sumber: Tommi, 2016
Tabel 2.2 menunjukkan rata-rata nilai koefisien aliran permukaan DAS
Citarum Hulu dari tahun 2009 sampai tahun 2014 adalah 0,48. Nilai tersebut
menunjukkan kriteria Koefisien Aliran Permukaan di DAS Citarum Hulu berada
pada kriteria sedang. Nilai tersebut juga menunjukkan bahwa curah hujan rata-
rata di DAS Citarum Hulu dari tahun 2009-2014 yang menjadi aliran permukaan
kurang dari 50%. Kondisi ini juga menunjukkan curah hujan yang masuk ke dalam
tanah masih lebih banyak. Menurut Peraturan Ditjen Rehabilitasi Lahan Desa
Sosial Tahun 2009 kriteria kinerja DAS masih pada tingkat sedang.
0.7 0.64
0.6 0.55
Koefisien Aliran Sungai (C)
0.52
0.5 0.43
0.41
0.4
0.31
0.3
0.2
0.1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahun
Gambar 2.8 Koefisien Aliran Permukaan DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014
Sumber: Tommi, 2016
Apabila dilihat dari pola perubahan koefisien aliran permukaan tiap
tahunnya. Tahun 2010 dan 2013-2014 termasuk dalam kinerja yang buruk.
Sedangkan untuk Tahun 2009 dan 2011-2012 berada dalam kinerja yang sedang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 19
KAJIAN KEWILAYAHAN
Koefisien Regim Sungai
Koefisien Regim Sungai adalah perbandingan debit (Q) maksimum
dengan debit aliran minimum dalam suatu DAS/Sub DAS. Selanjutnya, pada Tabel
2.3 ditunjukkan koefisien regim sungai DAS Citarum Hulu selama rentang tahun
2009 sampai dengan tahun 2014.
Tabel 2.3 KRS DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014
Tahun QMaks QMin KRS
2009 326,10 7,89 41,30
2010 544,90 57,10 9,50
2011 287,20 6,79 42,30
2012 281,10 10,10 27,80
2013 385,40 0,22 1751,80
2014 468,10 8,20 57,10
Rata-rata KRS 321,70
Sumber: Tommi, 2016
Nilai KRS yang cukup tinggi yaitu sebesar 321,7 yang mana nilai tersebut
termasuk ke dalam kriteria buruk. Nilai KRS yang tinggi menujukkan adanya
perbedaan debit yang tinggi antara musim hujan dan kemarau. KRS buruk
menunjukan tidak ada kontinuitas aliran air dan kemampuan lahan dalam
menyimpan air hujan dan mengeluarkan air rendah. Luas hutan yang berkurang
di daerah hulu menyebabkan ketika hujan air tidak tersimpan pada tegakan,
serasah dan tanah lebih lama dan ketika kemarau sungai mengalami kekurangan
air karena tidak ada tambahan aliran (Mahmud et al. 2009).
Koefisien KRS dari tahun 2009-2012 masuk dalam kriteria baik dan tahun
2014 dalam riteria sedang. Namun pada tahun 2013 dengan nilai KRS 1751,8
menunjukkan adanya perbandingan yang sangat jauh antara debit maksimum
dengan minimum, sehingga nilai tersebut termasuk ke dalam kriteria buruk.
Kondisi ini membuat daerah hulu ketika musim hujan tidak mampu menahan air
dan mengalirkannya ke dalam tanah, sehingga air hujan jatuh melimpas menjadi
aliran permukaan dan dialirkan ke sungai. Jumlah hujan yang tinggi dalam waktu
yang sangat singkat menyebabkan daerah hilir sering terjadi banjir, sebaliknya
pada musim kemarau sering terjadi kekeringan karena debit sungai yang sangat
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 20
KAJIAN KEWILAYAHAN
rendah. Koefisien aliran permukaan dan nilai KRS yang tinggi sangat dipengaruhi
oleh perubahan penggunaan lahan yang terjadi di DAS Citarum Hulu.
2000
1751.8
1800
Koefisien Regim Sungai (KRS)
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200 41.3 42.3 27.8 57.1
9.5
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahun
Gambar 2.9 Koefisien Regim Sungai DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014
Sumber: Tommi, 2016
Laju Sedimentasi
Sedimentasi adalah jumlah material tanah berupa kadar lumpur dalam air
oleh aliran air sungai yang berasal dari hasil proses erosi di hulu yang diendapkan
pada suatu tempat di hilir. Selanjutnya, pada Tabel 2.4 ditunjukkan laju
sedimentasi DAS Citarum Hulu selama rentang tahun 2009 sampai dengan tahun
2014. Dari tahun 2009 hingga 2014, rata-rata laju sedimentasi DAS Citarum Hulu
sebesar 1,28 mm/tahun yang dapat dikatakan masuk dalam kriteria baik.
Tabel 2.4 Tabel Qs DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014
Tahun Qs (mm/tahun)
2009 1,31
2010 2,57
2011 1,30
2012 2,32
2013 0,10
2014 0,10
Rata- 1,28
rata
Sumber: Tommi, 2016
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 21
KAJIAN KEWILAYAHAN
3
2.57
2.5 2.32
Laju Sedimentasi (mm/tahun)
1.5 1.31 1.3
0.5
0.1 0.1
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Tahun
Gambar 2.10 Koefisien Regim Sungai DAS Citarum Hulu Tahun 2009-2014
Sumber: Tommi, 2016
Laju sedimentasi tertinggi ada pada tahun 2010 dengan nilai 2,57 yang
termasuk dalam kriteria sedang. Lalu pada tahun 2012, laju sedimentasi termasuk
dalam kriteria sedang. Sedangkan untuk tahun 2009, 2011, dan 2013-2014
termasuk dalam kriteria baik. Kondisi tersebut menunjukkan laju sedimentasi
mulai ada peningkatan yang lebih baik.
Indeks Erosi
Erosi adalah peristiwa terangkutnya tanah atau bagian-bagian tanah dari
suatu tempat ke tempat lain oleh media alami. Pengikisan dan pengangkutan
tanah tersebut terjadi oleh media alami, yaitu air dan angin. (Arsyad, 2006)
DAS Citarum Hulu dengan luas 232.986 ha berada pada kisaran 50000-
260000 ha sehingga nilai SDR harus diinterpolasi. Hasil dari interpolasi
didapatkan bahwa SDR untuk DAS Citarum Hulu sebesar 0,0824 atau 8,24 %. Nilai
erosi aktual DAS Citarum Hulu rata–rata yang didapat dari tahun 2009 hingga
2014 adalah 15,54 ton/ha/tahun. Kondisi tanah di DAS Citarum Hulu sebagian
besar kondisinya lapisan bawahnya padat dan telah mengalami pelapukan maka
berdasarkan Tabel erosi yang diperbolehkan adalah 4,48 ton/ha/tahun.
Berdasarkan perhitungan nilai IE, maka nilai IE untuk DAS Citarum Hulu sebesar
3,47. Nilai IE DAS Citarum Hulu berdasarkan kriteria termasuk dalam kriteria
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 22
KAJIAN KEWILAYAHAN
buruk. Nilai tersebut menunjukkan erosi yang terjadi di DAS Citarum Hulu sangat
berat karena jauh melebihi erosi yang diperbolehkan. (Tommi, 2016)
Indeks Penutupan Lahan
Selanjutnya, pada Tabel 2.5 ditunjukkan indeks penutupan lahan DAS
Citarum Hulu selama rentang tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Luas
vegetasi permanen yang terdapat di DAS Citarum Hulu yaitu luas hutan hanya
18% dari luas DAS Citarum Hulu maka nilai tersebut berdasarkan kriteria
monitoring dan evaluasi kinerja DAS maka termasuk dalam kriteria buruk karena
nilainya <30%. Luas hutan <30 % menyebabkan erosi di daerah hulu terus
meningkat sehingga menyebabkan sering menyebabkan banjir di daerah hulu.
Tabel 2.5 Tabel Tutupan Lahan DAS Ciatarum Hulu Tahun 2013
Tutupan Lahan Luas (Ha) Persentase (%)
Hutan 40939,44 18
Permukiman 41620,92 18
Perkebunan 4717,33 2
Pertanian Lahan Kering 75560,00 32
Sawah 64938,96 28
Semak/Belukar 1684,33 1
Tanah Terbuka 1268,66 1
Tubuh Air 2256,38 1
Total 232986,00 100
Sumber: BPDAS tahun 2013
Permasalahan di Wilayah Sungai Citarum
Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di wilayah sungai Citarum
diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali yang berakibat
pada meningkatnya eksploitasi ruang dan sumber daya air. Tekanan penduduk
yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya peningkatan lahan kritis akibat
perubahan tata guna.
Tabel 2.6 Permasalahan di Wilayah Sungai Citarum
Zona Permasalahan
Berkurangnya fungsi kawasan lindung (hutan dan non hutan)
Zona
Berkembangnya permukiman tanpa perencanaan yang baik
Citarum
Budi daya pertanian yang tidak sesuai dengan kaidah konservasi
Hulu
yang menyebabkan banyaknya lahan kritis, kadar erosi yang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 23
KAJIAN KEWILAYAHAN
Zona Permasalahan
semakin tinggi yang mengakibatkan sedimentasi di palung
sungai, waduk, bahkan masuk ke jaringan prasarana air.
Degradasi fungsi konservasi sumber daya air yang
mengakibatkan peningkatan run off aliran permukaan
Tingkat pengambilan air tanah yang diluar kendali dimana
sebagian besar pengambilan air tanah tidak terregistrasi
Zona Pencemaran Waduk Saguling akibat sampah rumah tangga,
Citarum sampah padat, dan industri, serta adanya penambangan pasir
Tengah menyebabkan terjadinya pendangkalan waduk akibat sedimentasi.
Banyaknya alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi
permukiman akibat berkembangnya permukiman tanpa
perencanaan yang baik.
Terjadinya degradasi prasarana pengendali banjir
Menurunnya fungsi prasarana jaringan irigasi
Kurangnya prasarana pengendali banjir di muara
Banjir pada tahun 2010 yang terjadi disebabkan oleh curah
Zona hujan tinggi yang berlangsung terus menerus, Waduk Jatiluhur
Citarum tidak mampu menampung debit banjir sehingga limpas di
Hilir pelimpah dengan tinggi maksimum 141 cm. Akibatnya aliran
keluar dari waduk mengalir ke Sungai Citarum adalah sebesar
700 m3/detik. Bersamaan dengan meluapnya Sungai Cikao di
Purwakarta mengakibatkan banjir Sungai Cibeet di Karawang
yang mengalir ke Sungai Citarum, sehingga alur Sungai Citarum
di Karawang tidak mampu lagi menampung debit banjir dari
hulu, sehingga terjadi banjir di Telukjambe, Karawang Kulon,
Karawang Wetan Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bekasi.
Sumber: Rencana Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum 2010-2025
Tabel 2.6 menunjukkan selama tahun 2001-2011 di DAS Citarum hulu
terjadi pengurangan luas hutan seluas 1356,89 Ha; pertanian lahan kering seluas
1.903,65 Ha; sawah seluas 24,16 Ha; dan tanah terbuka seluas 1.241,10.
Pengurangan penggunaan lahan tersebut menyebabkan kurangnya daerah
resapan, teruma berkurangnya luas hutan menyebabkan kemampuan sungai
dalam menyimpan air berkurang dan juga meningkatkan volume sedimentasi
dikarenakan debit sungai yang makin tinggi banyak membawa material dari hulu
sehingga banyak terjadi pengendapan. Di sisi lain, terjadi peningkatan
penggunaan lahan permukiman juga semakin mengurangi derah resapan air.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 24
KAJIAN KEWILAYAHAN
Tabel 2.7 Perubahan Penggunaan Lahan DAS Citarum Hulu Tahun 2001-2011
Persentase Penggunaan
Luas Penggunaan Lahan (Ha)
Penggunaan Lahan Lahan (%)
2001 2011 Perubahan 2001 2011 Perubahan
Badan Air 2246,29 2246,29 0 0,97 0,97 0
Hutan 14191,59 12834,70 -1356,89 6,11 5,52 -0,59
Hutan Tanaman 25851,20 26512,32 661,12 11,13 11,41 0,28
Perkebunan 421558 4256,41 40,83 1,81 1,83 0,02
Pertanian Lahan
6597,94 44694,29 -1903,65 20,06 19,24 -0,82
Kering
Pertanian Lahan
31296,68 32350,83 1054,15 13,47 13,92 0,45
Kering Campuran
Permukiman 38899,15 41562,40 2663,25 16,74 17,89 1,15
Semak Belukar 1603,98 1710,43 106,45 0,69 0,74 0,05
Sawah 64689,00 64664,84 -24,16 27,84 27,83 -0,01
Tanah terbuka 2732,25 1491,15 -1241,10 1,18 0,64 -0,54
Sumber: Megandana, 2013
Penggunaan lahan DAS Citarum Hulu yang didominasi lahan pertanian
dan pemukiman banyak tidak sesuai dengan kapasitas daya dukung yang
menyebabkan air hujan sulit meresap ke dalam tanah sehingga aliran permukaan
meningkat lahan (Hidayat et al. 2013). Peningkatan aliran permukaan
menyebabkan debit sungai ketika musim hujan tinggi, namun dengan
kemampuan sungai dalam menyimpan air rendah menyebabkan debit ketika
musim kemarau sangat rendah. Curah hujan di DAS Citarum Hulu yang cukup
tinggi dan penggunaan lahan yang tidak sesuai kemampuan lahan menyebabkan
peningkatan erosi yang berakibat pada sedimentasi sungai meningkat.
Peningkatan aliran permukaan, debit sungai ketika musim hujan, dan sedimentasi
sungai sering menyebabkan banjir di daerah hilir.
Halim (2014) berpendapat bahwa daerah hulu dengan hilir DAS saling
berhubungan dan mempengaruhi dalam unit ekosistem DAS. Maka dari itu dalam
mengatasi bencana banjir di Kabupaten Karawang, penanganan tidak cukup
hanya dilakukan di Kabupaten Karawang saja namun juga perlu dilakukan di DAS
Citarum Hulu. Pendekatan bioregion (Bukhori, 2006) perlu dilakukan yakni
pengelolaan kawasan tanah dan air dalam kawasan aliran sungai secara terpadu.
DAS bagian hulu mempunyai arti penting terutama dari segi perlindungan fungsi
tata air dikarenakan mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 25
KAJIAN KEWILAYAHAN
(Amri 2008). Perubahan penggunaan lahan di DAS Citarum Hulu dari hutan
hingga menjadi lahan pertanian dan pemukiman menyebabkan limpasan air
hujan yang tinggi sehingga sering menyebabkan erosi dan banjir (Rohmat 2010).
Berdasarkan hasil analisis kerusakan DAS Citarum, KRS DAS Citarum masih
terlihat tinggi pada periode tahun 2009-2014. Selain itu nilai Indeks Erosi (IE) juga
masih tinggi. Tingginya nilai erosi dan KRS di DAS Citarum Hulu juga disebabkan
oleh masih sedikitnya tutupan lahan hutan di daaerah tersebut. Hal ini terlihat
dari nilai indeks penutupan lahan (IPL) masih 18%. Nilai IPL tersebut masih di
bawah kriteria baik yaitu 30%. Dari nilai-nilai tersebut perbaikan DAS Citarum
Hulu harus diarahkan pada perbaikan nilai KRS, erosi, dan juga penutupan lahan.
Makarim dan Ikwani (2011) berpendapat bahwa banjir di Jawa Barat
khususnya di Kabupaten Karawang, Subang, dan Indramayu disebabkan oleh
banyaknya saluran pembuangan air yang tidak berfungsi normal. Penyempitan
saluran pembuangan air karena banyak pengendapan tanah, sehingga kecepatan
air pembuangan lambat atau bahkan terhenti, daya tampung air berkurang
sehingga air mudah meluap atau banjir. Selain itu menurut Oktavianti et al. (2014)
di Kabupaten Karawang masih terdapat 30 daerah irigasi yang berada pada
kondisi kurang baik.
Rencana Pembangunan Waduk Cibeet
Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk mengakibatkan kondisi sosial
ekonomi dan tata ruang di Wilayah Sungai Citarum mengalami perubahan.
Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan banjir di daerah hilir dan kebutuhan
untuk pemenuhan irigasi dan air baku meningkat berbanding lurus dengan
pertumbuhan jumlah penduduk. Dengan adanya permasalahan tersebut diatas,
maka diperlukan pembangunan Waduk Cibeet. Hal ini menjadi perhatian
bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Sasaran dari terbangunnya waduk di DAS Cibeet adalah menanggulangi
permasalahan banjir yang terjadi di daerah hilir Sungai Citarum, peningkatan luas
areal irigasi teknis dan pemenuhan kebutuhan air baku. Berdasarkan Studi
Prakiraan Kelayakan Waduk Cibeet Tahun 2016, pembangunan waduk Cibeet
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 26
KAJIAN KEWILAYAHAN
dinyatakan layak untuk dilakukan konstruksi, karena sudah memenuhi
persyaratan kelayakan teknis dan ekonomi.
Pada akhir tahun 2016, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum
memastikan rencana pembangunan Waduk Cibeet sudah memasuki tahap studi
kelayakan (FS). Apabila Waduk Cibeet dinyatakan layak dibangun maka akan
dilanjut kepada proses perencanaan fisik (DED). Sementara pembangunan fisik
direncanakan akan dimulai pada tahun 2019 di Kecamatan Cariu, Kabupaten
Bogor. Kecamatan Cariu merupakan alternatif pertama karena lokasinya paling
hilir Waduk Cibeet diperkirakan akan mengurangi banjir di Karawang sebesar 9%.
Perkembangan Kawasan Industri dan Kawasan
Perkotaan Karawang
Dari seluruh industri yang berada di Kabupaten Karawang sekitar 5-7%
yang menggunakan pelayanan PDAM, mayoritas menggunakan air bor tanah.
Kegiatan industri yang relatif berkembang diantaranya di Kota Industri di bagian
timur yaitu Kota Bukit Indah City Kecamatan Cikampek; Kawasan Industri di
Kecamatan Telukjambe Timur dan Pangkalan; serta Zona Industri Kecamatan
Telukjambe Timur, Klari, Cikampek, dan Karawang. Untuk melihat pertumbuhan
industri dari tahun ke tahun mulai tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.8
dan Gambar 2.11 berikut ini.
Tabel 2.8 Data Perkembangan Industri di Kabupaten Karawang Tahun 2011-
2015 (unit)
Jenis Tahun
No
Industri 2011 2012 2013 2014 2015
A. Industri Besar
1. PMA 371 486 495 540 511
2. PMDN 213 213 226 237 226
3. Non
179 207 217 224 217
Fasilitas
Sub Total 763 906 938 1001 954
B. Industri Kecil 9014 9025 9025 9290 9290
Total 9764 9920 9963 10026 10224
Sumber: Dinas Perindagtamben dan BPMPT Kabupaten Karawang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 27
KAJIAN KEWILAYAHAN
10300 10224
10200
Jumlah Industri (Unit) 10100 10026
9963
10000 9920
9900
9764
9800
9700
9600
9500
2011 2012 2013 2014 2015
Tahun
Gambar 2.11 Data Perkembangan Industri di Kabupaten Karawang Tahun
2011-2015 (unit)
Sumber: Dinas Perindagtamen dan BPMPT Kabupaten Karawang
Pada tahun 1992 belum terdapat pengembangan kawasan industri
disebelah selatan Desa Karangligar dan pertumbuhan perkotaan pun belum
terlalu pesat. Selanjutnya pada tahun 1998 industri sudah mulai terbangun dan
mulai berkembang cukup pesat sampai dengan tahun 2011, sama halnya dengan
pertumbuhan perkotaan. Hingga pada tahun 2016, terlihat dengan jelas
perkembangan industri dan kawasan perkotaan yang sangat pesat.
Kondisi industri Kabupaten Karawang yang mayoritas menggunakan air
bor tanah menjadikan kuantitas air tanah di Kabupaten Karawang semakin lama
akan semakin berkurang, ditambah dengan perkembangan wilayah yang semakin
pesat bisa mengurangi kawasan resapan air juga. Kekosongan cadangan air yang
berada di bawah tanah tersebut dapat berdampak pada penurunan muka tanah
di atasnya.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
Kabupaten Karawang 28
KAJIAN KEWILAYAHAN
2016 2010 2004
Kawasan
Perkotaan
Desa
Karangli
gar
Kawasan
Industri
1998 1992
Gambar 2.12 Perkembangan Kawasan Perkotaan dan Kawasan Industri Kabupaten Karawang
Sumber: Google Earth, 1992-2016
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
29
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
KAJIAN LAPANGAN DESA
KARANGLIGAR
Bab ini menjelaskan mengenai kajian lapangan Desa Karangligar meliputi kondisi
wilayah dan kondisi geologi berdasarkan hasil pengumpulan data. Penjelasan
mengenai kondisi wilayah Desa Karangligar berupa kondisi kebencanaan; guna
lahan; sosial ekonomi; prasarana, sarana dan utilitas; aktivitas eksplorasi dan
eksploitasi migas; dan kondisi geologi.
Kebencanaan
Menurut data yang ada di BPBD Kabupaten Karawang, selama periode
Januari 2016-April 2017, Desa Karangligar telah mengalami 14 kali bencana
banjir. Wilayah yang sering tergenang air adalah di Dusun Kampek dan Dusun
Pengasinan. Sumber banjir berasal dari Sungai Cibeet di Desa Parungsari melalui
Kali Cidawolong. Sungai Cibeet tersebut merupakan sumber pengairan lahan
petani di Dusun Pangasinan untuk mengairi lahan pertanian mereka. Jika Sungai
Cibeet meluap maka Dusun Pangasinan akan banjir karena lokasi yang berbentuk
cekung dan berada dibawah Sungai Cibeet. Banjir yang terjadi tidak hanya lahan
sawah namun sampai menggenangi permukiman masyarakat hingga mencapai 2
meter. Dampak lahan sawah yang tergenang adalah petani mengalami gagal
panen dan rumah penduduk pun mengalami kerusakan.
Dalam periode periode Januari 2016-April 2017, bencana yang paling
sering terjadi adalah bencana banjir. Dari 14 kali kejadian bencana yang terjadi
selama periode tersebut, bencana banjir terlama terjadi pada November 2016,
dimana bencana terjadi selama kurang lebih 10 hari. Sedangkan dilihat dari
jumlah jiwa terdampak, bencana banjir pada akhir Februari dan awal Maret 2017
menjadi yang terparah dengan 1.702 jiwa terdampak banjir.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
30
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Tabel 3.1 Kejadian Bencana di Desa Karangligar Januari 2016-April 2017
Dampak
Tanggal Jenis Manusia Sarana Lain
Tahun Bulan Kerugian
Kejadian Bencana Rumah
Menderita Mengungsi
Hilang MD Luka Masjid Sekolah Sawah
KK Jiwa KK Jiwa
Januari - - - - - - - - - - - - - -
3 Banjir 65 222 - - - - - 63 - - - -
Februari
26 Banjir 271 799 - - - 271 799 224 - - - -
Maret - - - - - - - - - - - - - -
10 Banjir 90 267 - - - 90 267 61 - - 30
April 21 Banjir 357 1072 - - - 357 1072 300 - - 100
28 Banjir 34 122 - - - 34 122 25 - - -
Mei 25 Banjir 500 1525 420 180
2016 Juni - - - - - - - - - - - - - -
Juli - - - - - - - - - - - - - -
Agustus - - - - - - - - - - - - - -
September - - - - - - - - - - - - - -
10 Banjir 12 41 12 41 10
Oktober
30 Banjir 124 372 108
November 13-23 Banjir 527 1666 104 417
2 Puting Beliung 42 168 2 9 42 24.062.000
Desember
11 Puting Beliung 1 2 1 2 1 30.000.000
Januari - - - - - - - - - - - - - -
12-13 Banjir 225 672 225 672 194 4 2
Februari 16-17 Banjir 230 702 230 702 200 4 3 60
2017
26-28 Banjir 539 1702 539 1702 460
Maret 8-9 Banjir 539 1702 460 4 2 50
April 19-20 Banjir 62 186 51
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
31
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Sumber: BPBD Kabupaten Karawang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
32
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Guna Lahan
Jika dilihat dari fungsi lahan Desa Karangligar, penggunaan lahan untuk
kegiatan pertanian cukup dominan dengan 77,23% dari total luas wilayah Desa
Karangligar. Fungsi lahan untuk permukiman hanya 20,50%. Sedangkan sisanya
memiliki fungsi untuk jalan lokal, ruang terbuka hijau, dan badan sungai. Sebaran
penggunan lahan di Desa Karangligar dapat dilihat pada Tabel 3.5 dan Gambar
3.1.
Tabel 3.2 Peta Fungsi Lahan Desa Karangligar Tahun 2014
No Fungsi Lahan Luas (ha) Persentase
1 Pertanian 318,46 77,23%
2 Permukiman 84,54 20,50%
3 Jalan Lokal 4,49 1,09%
4 RTH 4,35 1,05%
5 Badan Sungai 0,49 0,12%
Total 412,33 100%
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
Jika dilihat dari penggunaan lahan pertanian Desa Karangligar,
penggunaan lahan untuk sawah cukup dominan. Penggunaan lahan untuk sawah
yang 2 kali ditanami padi paling besar dengan persentase 57,99% dari total
318,46 ha lahan pertanian. Sedangkan untuk Penggunaan lahan untuk sawah
yang 3 kali ditanami padi sebesar 39,26%. Sisanya merupakan kawasan pertanian
semusim lahan basah sebesar 1,45% dan kawasan pertanian semusim lahan
kering sebesar 1,30%. Pada Tabel 3.3 berikut ditunkukkan mengenai penggunaan
Lahan Pertanian Karangligar Tahun 2014.
Tabel 3.3 Penggunaan Lahan Pertanian Karangligar Tahun 2014
No Penggunaan Lahan Luas (ha) Persentase
1 Sawah 2 kali Ditanami Padi 184,68 57,99%
2 Sawah 3 kali Ditanami Padi 125,02 39,26%
3 Kawasan Pertanian Semusim Lahan Basah 4,61 1,45%
4 Kawasan Pertanian Semusim Lahan Kering 4,15 1,30%
Total 318,46 100%
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
33
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.1 Peta Fungsi Lahan Karangligar Tahun 2014
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
34
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.2 Peta Penggunaan Lahan Pertanian Karangligar Tahun 2014
Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karawang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
35
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Sosial Ekonomi
Desa Karangligar terdiri dari 2 Dusun, 5 Rukun Warga, dan 15 Rukun
Tetangga. Jumlah penduduk Desa Karangligar adalah sebanyak 5.625 jiwa pada
tahun 2015. Sedangkan pada tahun yang sama, jumlah rumah tangga di desa ini
berjumlah 1.562. Kepadatan penduduk Desa Karangligar adalah 1.406,25 per Km2.
Laju pertumbuhan penduduk Desa Karangligar mengalami fluktuatif per tahunnya
dalam rentang 4 tahun terakhir dimana pada dari tahun 2011 ke tahun 2015
terjadi laju pertumbuhan sebesar 0,37%. Pada rentang tahun yang sama, jika
dilihat berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Desa Karangligar
lebih banyak dari penduduk perempuan dengan sex ratio berkirar pada rentang
1,03-1,04. Sedangkan jika dilihat berdasarkan wilayah terdampak banjir di
Kampung Pangasinan dan Kampung Kampek maka jumlah penduduknya
mencapai 46,9% dari jumlah keseluruhan penduduk di Desa Karangligar.
Tabel 3.4 Jumlah Penduduk, Jumlah Rumah Tangga, dan Kepadatan
Penduduk Desa Karangligar
Jumlah Jumlah Kepadatan Laju
No Tahun Penduduk Rumah Penduduk Pertumbuhan
(jiwa) Tangga per Km2 Penduduk
1 2015 5.625 1.562 1.406,25 0,37%
2 2014 5.604 1.561 1.401,00 -0,21%
3 2013 5.616 1.494 1.404,00 0,21%
4 2011 5.604 1.466 1.401,00 -
Sumber: Kecamatan Telukjambe Barat Dalam Angka, 2012-2016
Berdasarkan Tabel 3.4 di atas dapat dilihat laju pertumbuhan di Desa
Karangligar mengalami kenaikan dari tahun 2011 ke tahun 2013 namun pada
tahun selanjutnya di tahun 2014 mengalami penurunan dan pada tahun 2015
kembali mengalami kenaikan. Namun secara keseluruhan dari tahun 2011
ketahun 2015 jumlah penduduk Desa Karangligar mengakami kenaikan.
Selanjutnya pada Tabel 3.5 ditunjukkan jumlah penduduk berdasarkan
jenis kelamin. Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk berjenis
kelamin laki-laki lebih banyak dibandingkan berjenis kelamin perempuan.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
36
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Tabel 3.5 Jumlah Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk (jiwa) Sex
No Tahun
Laki-laki Perempuan Ratio
1 2015 2.865 2.760 1,04
2 2014 2.850 2.754 1,03
3 2013 2.850 2.766 1,03
4 2011 2.840 2.764 1,03
Sumber: Kecamatan Telukjambe Barat Dalam Angka, 2012-2016
Selanjutnya pada Tabel 3.6 ditunjukkan jumlah penduduk kampung
pangasinan dan kampung kampek terdampak bencana banjir. Terdapat 4 RT yang
terdampak bencana banjir di Dusun Pengasinan Desa Karangligar dan 3 RT di
Dusun Kampek Desa Karangligar. Dilihat dari jumlah penduduk yang terdampak
bencana banjir Dusun Kampek lebih tinggi dibandingkan Dusun Pengasinan.
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Kampung Pangasinan dan Kampung Kampek
Terdampak Bencana Banjir
Nama Dusun RT/RW Jumlah Penduduk
001/001 421
002/001 201
Pangasinan
003/001 375
004/001 301
Jumlah 1.298
005/002 546
Kampek 006/002 392
007/002 402
Jumlah 1.340
Jumlah Keseluruhan 2.638
Sumber: Paparan Kronologis Desa Karangligar oleh BPBD Kabupaten Karawang, 2017
Pada saat banjir November 2016, petani di Desa Karangligar, bersusah
payah menyelamatkan tanaman padi dari rendaman banjir. Sambil membawa arit
para petani saling bergantian menyelam di sawah yang terkena genangan
setinggi 1,5 meter. Kemudian mereka memotong tanaman padi siap panen dan
mengumpulkannya pada sebuah rakit kecil. Tanaman padi selanjutnya
dikumpulkan di jalan setapak yang kondisinya tidak terendam banjir. Para petani
yang areal sawahnya terendam banjir pesimistis hasil panen mereka di tengah
kondisi banjir tersebut bisa terjual ke tengkulak atau Bulog (Badan Urusan
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
37
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Logistik). Alasannya adalah karena gabah akan menghitam dan membusuk
sehingga akan sulit untuk dijual. Salah seorang petani menuturkan bahwa seluas
80 hektare lahan sawah di desa tersebut terendam saat masa panen
(pasundanekspres.com)
Gambar 3.3 Peta Titik Observasi Lahan Pertanian Di Desa Karangligar
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Selanjutnya terkait dengan kerentanan ekonomi di bidang pertanian,
menurut Ellis (2000) dalam Tommi (2015), nafkah (livelihood) adalah mata
pencaharian terdiri dari aset (alam, manusia, finansial, dan modal sosial), kegiatan
dan akses masuk (dimediasi oleh lembaga dan hubungan sosial) yang bersama-
sama menentukan hidup yang diperoleh oleh individu atau rumah tangga. Berikut
meruapakan penjabaran dan pengertiannya:
1) Modal manusia merujuk pada tingkat pendidikan dan status kesehatan
individu dan populasi.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
38
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
2) Modal alam merujuk pada sumber daya alam dasar (tanah, air, pohon)
yang menghasilkan produk yang digunakan oleh populasi manusia untuk
kelangsungan hidup mereka.
3) Modal fisik merujuk pada aset-aset yang dibawa ke dalam eksistensi
proses produksi ekonomi, sebagai contoh, alat-alat, mesin, dan perbaikan
tanah seperti teras atau saluran irigasi.
4) Modal sosial merujuk pada jaringan sosial dan asosiasi di mana orang
berpartisipasi, dan dari mana mereka dapat memperoleh dukungan yang
memberikan kontribusi terhadap penghidupan mereka.
5) Modal finansial merujuk pada persediaan uang tunai yang dapat diakses
untuk membeli barang-barang konsumsi atau produksi, dan akses pada
kredit dapat dimasukkan ke dalam kategori ini.
Nilai kerentanan ekonomi Dusun Pangasinan lebih tinggi dari pada Dusun
Kampek. Namun untuk Dusun Pengasinan paling rentan adalah modal fisik yaitu
dampak banyak petani yang tidak memiliki traktor dan mesin pompa disebabkan
oleh lemahnya modal finansial (masih banyaknya petani yang pendapatannya
rendah) dan modal manusia (masih banyaknya petani yang hanya memiliki
penghasilan dari hasil pertanian saja).
Kondisi ini agak berbeda dengan Dusun Kampek walaupun secara modal
fisik dan modal alam kerentanannya cukup tinggi namun karena modal manusia
yang lebih tinggi dari Dusun Pengasinan membuat modal finansialnya cukup
kuat. Hal ini terjadi karena banyak yang memiliki sumber penghasilan lain selain
dari bertani sehingga pendapatan petani di Dusun Kampek sedikit lebih tinggi
dibandingkan dengan Dusun Pengasinan. Modal sosial petani Dusun Kampek
juga ikut membuat modal finansial petani yang terlihat dari jumlah petani yang
aktif dalam organisasi lebih banyak sehingga banyak petani yang mendapatkan
bantuan bibit ketika terkena banjir sehingga petani sedikit terbantu dalam biaya
produksi ulang.
Dampak dari adanya bencana banjir membuat penguasaan modal petani
menjadi lemah. Sebelum sering terjadi banjir banyak petani yang memiliki lahan
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
39
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
sawah, hewan ternak, dan lahan garapan yang luas. Namun sejak banjir sering
terjadi banyak petani yang mulai kehilangan lahan sawah pribadinya, lahan
garapannya, hewan ternak, dan juga perabotan rumah. Banjir juga membuat
modal finansial petani menjadi lemah hal ini dikarenakan banjir membuat
penghasilan petani menjadi berkurang dan juga pengeluaran petani semakin
bertambah.
Menurut Ellis (2000) dalam Giovanny (2016), terdapat tiga aspek
pembentuk strategi nafkah, yakni dari onfarm, off-farm, dan non farm. Onfarm
merupakan sumber nafkah yang diperoleh dari hasil pertanian dalam arti luas,
mencakup pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan
sebagainya. Off farm merupakan aktifitas ekonomi yang diperoleh dalam bentuk
upah tenaga kerja pertanian, sistem bagi hasil (harvest share system), dan lain-
lain. Non farm adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari luar kegiatan
pertanian seperti bekerja sebagai buruh pabrik, buruh panggul, buruh bangunan
dan lain-lain.
Dalam Giovanny (2016), Rumah tangga di wilayah banjir Dusun
Pengasinan Desa Karangligar mempunyai persamaan dalam hal kondisi ekonomi
yaitu rumah tangga yang terkena banjir akan bergantung terhadap anggota
rumah tangga lainnnya yang bekerja dalam bidang non farm serta kepala rumah
tangga akan mencari pekerjaan lain diluar bidang pertanian yang digunakan
untuk menafkahi rumah tangga selama periode tidak ada hasil tanam. Lapisan
rumah tangga yang ada lebih banyak berada di wilayah sedang hal ini
menunjukan bahwa rumah tangga di wilayah banjir Dusun Pengasinan lebih
banyak berada di daerah menengah (40%), selanjutnya lapisan bawah (33,33%),
dan lapisan atas (26,67%). Lapisan bawah lebih banyak dari pada lapisan atas
karena lapisan bawah cenderung tidak memiliki pekerjaan lain ketika musim
hujan dan pada saat tidak bisa tanam setelah banjir. Sedangkan pada lapisan atas
warga memiliki pekerjaan lainnya diluar bertani, dimana lapisan atas memiliki
pekerjaan di luar pertanian atapun memiliki lebih dari satu anggota rumah
tangga yang ikut bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Pada lapisan
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
40
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
menengah rumah tangga sebagian besar bekerja sebagai petani dan memilki
penghasilan dari anggota rumah tangga serta membuka warung kecil-kecilan
lainnya walaupun tidak sebanyak penghasilan lapisan atas. Pada lapisan bawah
pekerjaan yang dimiliki lebih sedikit dalam menghasilkan pendapatan, biasanya
bekerja sebagai kuli bangunan atau buruh tani pada daerah non banjir.
Rumah tangga lapisan bawah di wilayah banjir memiliki struktur ekonomi
yang didominasi oleh kegiatan non farm dan anggota rumah tangga lainya.
Kontribusi paling besar pada pendapatan rumah tangga lapisan bawah di wilayah
banjir adalah sektor non farm. Hal tersebut dilakukan karena sektor on farm dan
off farm sudah tidak dapat memberikan penghasilan akibat sawah tidak bisa
ditanami. Rumah tangga lapisan menengah di wilayah banjir sudah mulai
didominasi oleh sektor non farm, tidak ada rumah tangga yang masih
bergantung pada sektor on farm dan off farm. Pendapatan dari sektor non farm
lebih sedikit daripada pendapatan anggota rumah tangga lainnya. Hal ini
anggota rumah tangga lapisan menengah sudah memiliki pekerjaan tetap
dibandingkan rumah tangga lapisan bawah. Rumah tangga lapisan atas
didominasi oleh struktur ekonomi non farm dan pendapatan dari anggota rumah
tangga lainnya.
Nilai indeks kerentanan Desa Karangligar tergolong tinggi. Hal ini berarti
petani di Desa Karangligar sangat rentan sekali terhadap bahaya banjir dan masih
belum mampu dalam menghadapi banjir. Hal itu terlihat dari kerugian yang
dialami petani sangat besar sekali. Kerentanan petani yang tinggi di Desa
Karangligar banyak disebabkan oleh faktor sensitivitas ekonomi. Hal itu terlihat
dari kepemilikan lahan yang sedikit dan juga tingkat pendapatan yang masih
rendah. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak sangat besar ketika terjadi
banjir. Banjir di desa ini sangat sering menyebabkan gagal panen pada saat
menjelang panen. Petani di desa ini yang masih banyak tidak memiliki pekerjaan
sampingan tentunya akan kehilangan pendapatan. Selain itu, dengan modal yang
sedikit petani tidak langsung mampu menanam padi lagi. Petani butuh waktu
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
41
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
yang agak lama hingga tersedianya modal. Kondisi ini tentu saja membuat petani
tidak bisa mengatur waktu tanam yang baik.
Genangan yang terbentuk di Desa Karangligar terbentuk akibat banjir
dimulai pada tahun 2009, dimana Desa Karangligar dilanda banjir namun pada
saat itu jika dibandingkan desa-desa sekitar Desa Karangligar paling parah.
Genangan tersebut terbentuk di area pesawahan. Luasan genangan tersebut
mencapai seluas 60 hektar. Sedangkan kedalaman genangan kurang lebih
setinggi dada orang dewasa.
Area persawahan yang sudah tergenangi air tersebut saat ini tidak bisa
dimanfaatkan untuk kegiatan bertani. Hal yang menarik di lapangan adalah
genangan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan memancing. Kondisi
tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.5.
Gambar 3.4 Peta Titik Observasi Genangan Di Desa Karangligar
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
42
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.5 Kondisi Pemancingan Ikan di Area Genangan
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Prasarana, Sarana dan Utilitas
Kondisi jalan yang diamati pada kegiatan observasi tertera pada Gambar
3.6. Beberapa ruas jalan rusak cukup parah dengan kondisi berlubang di
sepanjang ruasnya. Hal ini diakibatkan oleh banjir yang sering menggenangi jalan
tersebut. Selain itu juga terdapat jalan yang berada dalam kondisi baik. Jalan
tersebut umumnya merupakan perkerasan beton.
Selain itu, dampak dari banjir di Desa Karangligar ini seringkali membuat
jalan penghubung antar desa tergerus air. Sehingga, jalan tersebut tak bisa dilalui
kendaraan. Jalan yang tergerus diperkirakan bisa mencapai satu kilometer
sehingga sulit dilalui kendaraan.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
43
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.6 Peta Titik Observasi Kondisi Jalan Di Desa Karangligar
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Sedangkan untuk irigasi yang diamati di lapangan kondisinya
mengkhawatirkan. Hal ini karena permukaan air irigasi lebih tinggi dari
permukaan lantai rumah di sampingnya. Apabila terjadi hujan dengan intensitas
tinggi maka irigasi akan meluap dan membanjiri rumah warga.
Gambar 3.7 Kondisi Irigasi di Desa Karangligar
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Dari hasil observasi lapangan, terdapat beberapa fasilitas sosial seperti
sarana pendidikan dan sarana peribadatan di Karangligar. Sarana pendidikan
tersebut antara lain SMPN 1 Telukjambe Barat, SDN Karangligar II, dan SMK
Jayabeka 02.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
44
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.8 Peta Lokasi Fasilitas Sosial dan Kantor Desa Karangligar
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
SMPN 1 Telukjambe Barat merupakan sekolah yang sering terendam
akibat bencana banjir. Adapun SDN Karangligar 2 merupakan lokasi yang sering
digunakan untuk pengungsian korban bencana banjir. Sedangkan SMK Jayabeka
02 juga bisa dijadikan alternatif sebagai lokasi pengungsian. Secara keseluruhan,
jumlah sarana pendidikan di Desa Karangligar terdiri dari 3 PAUD, 2 TKI/TPA/TQA,
3 SD, 1 SMP, 1 SMA/SMK, dan 1 Pesantren.
Gambar 3.9 Kondisi Banjir di SMPN 1 Telukjambe Barat
Sumber: BPBD Kabupaten Karawang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
45
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Selain itu pengamatan juga dilakukan terhadap Kantor Desa Karangligar.
Di kantor desa ini sudah pernah dilakukan kegiatan simulasi bencana.
Selanjutnya, terdapat signage (tanda) jalur evakuasi di jalan di depan kantor desa.
Kantor Desa Karangligar ini memang sering digunakan para warga desa yang
terdampak bencana untuk mengungsi. Akan tetapi karena luas genangan banjir
yang semakin meluas di Karangligar ikut merendam Kantor Desa. Oleh karena itu
perlu dicari lokasi alternatif lain ketika terjadi banjir dan perbaikan jalur evakuasi.
Gambar 3.10 Penanda Jalur Evakuasi di Kantor Desa Karangligar
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Aktivitas Eksplorasi dan Eksploitasi Migas
Desa Karangligar terdapat terdapat 8 sumur eksplorasi dan produksi gas
bumi. Hingga saat ini, sumur yang masih aktif sebanyak 4 sumur. Kegiatan
produksi terjadi mulai tahun 1990 dan hingga tahun 2017 sudah mencapai ± 27
tahun. Semua sumur ini bermuara ke Stasiun Pengumpul Cicauh. Selama kegiatan
observasi lapangan, sumur ekplorasi yang dilakukan pengamatan hanya 3 (tiga)
titik. Ketiga titik tersebut berdekatan dengan wilayah genangan di Desa
Karangligar. SP (Stasiun Pengumpul) Cicauh yang berada di Desa Karangligar
merupakan bagian dari PT Pertamina EP. PT Pertamina EP adalah perusahaan
yang menyelenggarakan kegiatan usaha di sektor hulu bidang minyak dan gas
bumi, meliputi eksplorasi dan eksploitasi. Di samping itu, Pertamina EP juga
melaksanakan kegiatan usaha penunjang lain yang secara langsung maupun
tidak langsung mendukung bidang kegiatan usaha utama. Wilayah Kerja
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
46
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Pertamina EP terbagi ke dalam lima asset dan operasinya terbagi menjadi 21 field.
SP Cicauh termasuk ke dalam wilayah kerja Asset 3 dan operasi Subang Field.
Berkaitan dengan bencana banjir yang sering melanda Desa Karangligar,
Pertamina EP Asset Subang Field bekerja sama CARE LPPM IPB dan pemerintah
Desa Karangligar menyelenggarakan kegiatan gerakan “Biopori for Karangligar”
pada tahun 2016. Biopori merupakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
yang berguna untuk mempercepat peresapan air hujan. Kegiatan ini sebagai
langkah awal gerakan pembuatan 5.000 lubang biopori di Desa Karangligar.
Kegiatan ini juga bertujuan untuk mengunggah kesadaran dan partisipasi masya-
rakat, bahwa ada teknologi sederhana, yakni biopori untuk mencegah banjir.
Akibat banjir yang terjadi Pertamina EP turut juga menjadi korban.
Beberapa fasilitas produksi Pertamina EP seperti yang menimpa SP Cicauh
terendam air cukup dalam. Meskipun beberapa fasilitas produksi milik Pertamina
EP terendam air, aktifitas produksi di SP Cicauh tetap berjalan seperti biasa.
Operator SP Cicauh menggunakan perahu karet untuk dapat masuk ke area
fasilitas produksi yang terendam untuk mengontrol dan memonitor produksi
minyak dan gas, demi kelangsungan pasokan energi untuk kebutuhan nasional.
Selain itu SP Cicauh juga dilengkapi dengan layout APAR, Hydrant, Fire Hose, dan
Jalur Evakuasi sebagai antisipasi terhadap hal-hal yang membahayakan.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
47
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.11 Peta Lokasi Sumur eksplorasi PT Pertamina EP dan SP Cicauh
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Gambar 3.12 Perahu Karet Milik dan Layout layout APAR, Hydrant, Fire
Hose, dan Jalur Evakuasi di SP Cicauh
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
48
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Geologi
Pembahasan mengenai kondisi geologi Desa Karangligar terdiri dari
geomorfologi, satuan geologi teknik, dan kondisi hidrogeologi umum.
Geomorfologi
Bentukan bentang alam mencerminkan proses-proses geologi yang telah
terjadi. Interaksi antara proses endogen dan eksogen berperan dalam
pembentukan bentang alam suatu daerah (Thornbury, 1989). Proses endogen
merupakan proses yang bersifat konstruktif seperti adanya pengangkatan,
perlipatan, intrusi, dan pensesaran. Sedangkan proses eksogen cenderung
bersifat destruktif seperti erosi, pelapukan, longsoran dan sedimentasi.
Analisis geomorfologi digunakan untuk mengetahui bagaimana proses-
proses geologi yang terjadi dan membentuk bentang alam pada masa kini.
Parameter utama dalam menganalisis dan mendeskripsi bentuk bentang alam
ada tiga, yaitu struktur, proses, dan tahapan (Lobeck, 1939). Struktur memberikan
informasi mengenai geologi bentukan bentang alam seperti punggungan,
pegunungan lipatan, pegunungan sesar, dan lain sebagainya. Proses merupakan
parameter yang sedang berlangsung pada bentang alam tersebut dan
memodifikasi bentukan asli dari bentang alam tersebut. Proses yang membentuk
bentang alam saat ini dikontrol oleh litologi dan struktur geologi. Litologi yang
resisten akan memberikan bentukan yang terjal, sedangkan litologi yang lunak
lebih membentuk morfologi dataran. Begitupun dengan kontrol struktur yang
berkembang akan membentuk pola aliran sungai tertentu. Tahapan merupakan
parameter yang menjelaskan seberapa jauh proses telah berlangsung pada
bentang alam untuk membuat bentukan yang terlihat pada saat ini. Tahapan
geomorfik diurutkan menjadi 3 tahap, yaitu tahap muda, tahap dewasa, dan
tahap tua.
Metode yang digunakan dalam melakukan analisis ini yaitu dengan
analisis peta topografi, analisis citra Shuttle Radar Topography Mission (SRTM),
dan pengamatan di lapangan. Data yang didapatkan berupa pola kerapatan
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
49
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
kontur, pola aliran sungai, bentuk lembah sungai, litologi, dan struktur geologi.
Kemudian data yang telah didapatkan dianalisis untuk menentukan satuan
geomorfologinya berdasarkan kondisi bentuk muka bumi (landform).
Geomorfologi Daerah Penelitian
Daerah penelitian tersusun atas morfologi perbukitan dan lembah yang
berada pada interval 12-37 mdpl. Titik terendah permukaan tanah berada pada
dataran tengah bentukan genangan. Sebagian besar bentang alam di daerah
penelititan terdiri dari lembahan dengan relief yang sangat landai (Gambar 3.13).
Hanya di daerah selatan saja yang memiliki ketinggian 37 mdpl. Lembahan yang
mendominasi daerah penelitian memanjang dari barat ke timur. Di tengah
lembahan tersebut terdapat suatu bentukan cekungan yang telah diisi oleh air
membentuk genangan dan rawa. Luas genangan dan rawa diperkirakan mencapai
60 hektar. Bentukan bentang alam yang terdapat di daerah penelitian ini
dikontrol oleh perbedaan tingkat resistensi dari tanah terhadap proses eksogen
yang terjadi.
Gambar 3.13 Peta Pola Aliran Sungai Daerah Penelitian
Sumber: Data PUPR Kabupaten Karawang
Dalam kurun waktu tertentu kondisi permukaan Desa Karangligar selalu
berubah-ubah, hal tersebut terlihat dari Citra satelit yang diambil tahun 2000
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
50
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
hingga 2016 (Gambar 3.14) dan peta kontur pada tahun 2007 dan 2015 (Gambar
3.15). Citra satelit tersebut memperlihatkan gambaran bagaimana perubahan
lahan pertanian yang tergenang pada tahun 2014. Daerah yang tergenan diberi
simbol area berwarna biru muda, sedangkan wilayah Desa Karangligar diberi
simbol area berwarna hijau muda. Berdasarkan peta kontur tahun 2007 dan 2015
terlihat adanya perubahan luasan area kontur 12,5 m. Hal tersebut dapat
mengindikasikan kecendurungan penurunan muka tanah sekitar 2 meter.
Gambar 3.14 Citra Satelit yang Diambil Dari Tahun 2000 Hingga 2016
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
51
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Sumber: Google Satellite
Gambar 3.15 Peta Kontur di Desa Karangligar dan Sekitarnya pada
tahun 2007 (kiri) dan 2015 (kanan)
Sumber: Google Sattelite Map (Kiri) dan Badan Informasi Geospatial (kanan)
Pola Aliran Sungai
Pola aliran sungai daerah penelitian dikontrol oleh litologi dan kemiringan
lereng. Berdasarkan pengamatan secara langsung di lapangan maupun tidak
langsung melalui peta topografi pola aliran sungai di daerah penelitian berupa
pola aliran sungai meander (Gambar 3,16). Sungai berpola meander hadir secara
dominan seperti yang terlihat di Sungai Citarum dan Cibeet. Sungai dengan pola
ini sangat umum dijumpai pada daerah dataran rendah dan lembahan yang
relatif datar.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
52
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.16 Peta Pola Aliran Sungai Daerah Penelitian
Sumber: Hasil Analisis, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
53
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Satuan Geomorfologi
Tahapan geomorfik suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor.
Adanya variasi litologi dan struktur yang berkembang memberikan pengaruh
terhadap tahap geomorfik daerah penelitian. Selain itu, hal yang harus
diperhatikan dalam menganalisis tahapan geomorfik suatu daerah adalah
morfologi sungai yang berkembang.
Pada umumnya tanah tertranspor yang lunak memberikan dampak pada
bentukan bentang alam berupa dataran rendah. Hal ini diakibatkan oleh sifat
ketahanan tanah tertranspor yang kurang resisten terhadap proses pelapukan
dan erosi. Morfologi lembahan pada daerah penelitian dijumpai di bagian tengah
Desa Karangligar. Sedangkan tanah yang lebih keras memiliki sifat ketahanan
yang lebih resisten terhadap proses pelapukan dan erosi. Oleh karena itu,
umumnya morfologi yang terbentuk berupa perbukitan. Hal tersebut dijumpai di
daerah penelitian yaitu di bagian ujung selatan. Proses erosi yang berkembang di
daerah penelitian didominasi oleh erosi horizontal yang terlihat dari bentukan
lembah sungai yang umumnya lebar dan sungai bermeander. Proses sedimentasi
yang berlangsung dapat dilihat pada dasar genangan yang umumnya terdiri dari
endapan dataran banjir.
Berdasarkan kondisi bentuk muka bumi (landform), daerah penelitian
dibagi menjadi 2 satuan geomorfologi, yaitu:
1) Satuan Punggungan Barisan.
Satuan ini menempati 11% luas daerah penelitian yang terdapat dibagian
selatan daerah penelitian. Satuan ini dicirikan dengan relief kasar yang
memiliki elevasi berkisar antara 28-47 mdpl. Pola kontur satuan ini cukup
rapat dengan kemiringan lereng 15° -28°.
Morfologi pada satuan ini berupa punggungan yang memanjang dengan
arah relatif barat-timur (Gambar 3.17). Morfologi tersebut menandakan
bahwa satuan ini terdiri dari endapan yang cukup resisten terhadap erosi.
Pengamatan di lapangan membuktikan bahwa satuan ini terdiri dari tanah
residual. Sungai-sungai yang berkembang pada satuan ini berupa sungai
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
54
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
kecil yang mengalir ke kaki lereng dan menyatu dengan sungai besar di
bawahnya. Proses eksogen yang terjadi yaitu pelapukan dan erosi di
beberapa titik pengamatan.
Gambar 3.17 Morfologi Perbukitan Barisan Yang Memanjang Barat-Timur Di
Sebelah Selatan Desa Karangligar
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
2) Satuan Dataran Rendah Karangligar
Satuan ini menempati 89% luas daerah penelitian yang terdapat di bagian
utara daerah penelitian. Satuan ini dicirikan dengan relief yang sangat
datar dan memiliki elevasi berkisar antara 12-18 mdpl. Pola kontur satuan
ini sangat renggang dengan kemiringan lereng 3°-15°.
Morfologi pada satuan ini berupa lembahan dengan arah relatif barat-
timur, Morfologi tersebut menandakan bahwa satuan ini terdiri dari
endapan yang berasal dari hasil transportasi dan terendapkan di tengah
lembahan (Gambar 3.18). Sehingga, morfologi tersebut kurang resisten
terhadap pelapukan dan erosi. Pengamatan di lapangan membuktikan
bahwa satuan ini terdiri dari tanah hasil pengendapan suatu dataran
banjir. Sungai-sungai yang berkembang pada satuan ini berupa sungai
dengan pola aliran menader. Sungai-sungai tersebut merupakan
percabangan dari Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Proses eksogen yang
terjadi yaitu pelapukan dan erosi di beberapa titik pengamatan.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
55
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.18 Morfologi Dataran Rendah Karangligar Yang Relatif
Memanjang Dari Barat-Timur
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Satuan Geologi Teknik
Sangat susah untuk menemukan suatu singkapan batuan yang utuh di
daerah penelitian. Tetapi dapat dibuat suatu satuan geologi teknik berdasarkan
data observasi lapangan dan acuan dari penelitian sebelumnya. Penentuan satuan
didasarkan pada intepretasi dan kolerasi bawah permukaan dari data observasi
lapangan dan penelitian sebelumnya. Dari hal tersebut, maka satuan geologi
teknik daerah penelitian dapat dibagi menjadi 3 satuan, yaitu Satuan Tanah
Residual Batupasir, Satuan Endapan Dataran Banjir, Satuan Endapan Sungai
(Gambar 3.19).
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
56
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.19 Peta Geologi Teknik Desa Karangligar dan Sekitarnya
Sumber: Hasil Analisis, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
57
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Satuan Tanah Residual Batupasir
Satuan ini menempati 11% dari luas daerah penelitian. Satuan ini
tersingkap baik di lereng sebelah selatan daerah penelitian. Persebarannya
dibatasi oleh sebuah sungai yang mengalir dari timur ke barat.
Satuan ini terdiri dari tanah residual batupasir yang berasal dari pelapukan
batupasir konglomeratan (Gambar 3.20). Pada satuan ini dijumpai adanya erosi-
erosi ke hulu tahap erosi parit. Satuan ini memiliki ciri berwarna coklat tua
dengan tebal diperkirakan 5 meter. Dibagian kaki lereng masih ditemui fragmen-
fragmen batupasir konglomeratan Satuan ini merupakan tanah hasil pelapukan
dari batuan kuarter. Sehingga umur dari satuan ini resen.
Hasil laboratorium dari sampel tanah yang diambil pada kedalaman 0,5 m
memberikan hasil kadar air (Wn): 28,7%, berat jenis (ϒn): 1,7 g/cm3, jenis tanah:
clayey SILT, warna: dark BROWN, plastisitas indeks (IP): 16,6%, batas cair (LL):
45,14% (high plastic), Kelas: ML, sudut geser dalam (θ): 32,3°, kohesi (c): 0,05
kg/cm2, koefisien permeabilitas (k): 0,000119 cm/detik, specify gravity (Gs): 2,41,
koefisien pemampatan (Cv): 0,000747 cm2/detik, indeks komprebilitas (Cc): 0,544.
Gambar 3.20 Singkapan Satuan Tanah Residual Batupasir
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
58
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Tanah yang ada di satuan ini didominasi oleh lanau lempungan yang
memiliki tingkat plastisitas yang tinggi dan sudut geser dalam yang cukup tinggi.
Dari hasil pengujian laboratorium terlihat bahwa satuan ini memiliki nilai
permeabilitas yang kecil yang menyebabkan air sukar masuk kedalam tanah.
Berdasarkan nilai koefisien pemampatan yang didapat, satuan ini masih
mengalami konsolidasi alami. Apabila koefisien pemampatan tersebut selalu
konstan, diperkirakan tanah permukaan akan mampat setebal sekitar 2,3 m.
Satuan Endapan Dataran Banjir
Satuan ini menempati 69% dari luas daerah penelitian menyebar dari
batas dengan Satuan Tanah Residual Batupasir hingga ke utara. Satuan ini
tersingkap baik di tengah Desa Karangligar, yaitu di sekitar bentukan genangan.
Satuan ini kebanyakan digunakan untuk area pertanian dan perikanan. Selain itu,
di bagian barat Desa Karangligar terbentuk area rawa dan umumnya tergenang
oleh air pada elevasi 12 mdpl.
Satuan ini berasal dari tanah tertranspor oleh medium air. Satuan ini
memiliki ciri berwarna coklat tua dan lunak (Gambar 3.21). Karena satuan ini
merupakan tanah hasil transpor suatu tanah dari tempat lain dan diendakan di
sekitar Desa Karangligar, maka umur dari satuan ini resen.
Hasil laboratorium dari sampel tanah yang diambil pada kedalaman
sekitar 0,5 m memberikan hasil kadar air (Wn): 42,4%, berat jenis (ϒn): 2,4 g/cm3,
jenis tanah: silty CLAY, warna: dark BROWN, plastisitas indeks (IP): 36,4%, batas
cair (LL): 64,25% (high plastic), Kelas: CH, sudut geser dalam (θ): 20,5°, kohesi (c):
0,06 kg/cm2, koefisien permeabilitas (k): 0,000038 cm/detik, specify gravity (Gs):
2,39, koefisien pemampatan (Cv): 0,00081 cm2/detik, indeks komprebilitas (Cc):
0,007.
Tanah yang ada di satuan ini didominasi oleh lempung lanauan yang
memiliki tingkat plastisitas yang tinggi dan sudut geser dalam yang rendah. Dari
hasil pengujian laboratorium terlihat bahwa satuan ini memiliki nilai permeabilitas
yang sangat kecil yang menyebabkan air sangat sukar masuk kedalam tanah.
Berdasarkan penelitian terdahulu, nilai permeabilitas di satuan ini mencapai
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
59
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
0.0095 cm/detik. Perubahan nilai permeabilitas menunjukkan adanya suatu
pengurangan laju aliran air melewati satuan ini.
Berdasarkan nilai koefisien pemampatan yang didapat, satuan ini masih
mengalami konsolidasi alami. Apabila koefisien pemampatan tersebut selalu
konstan, diperkirakan tanah permukaan akan mampat setebal sekitar 2,5 m.
Satuan ini memiliki ketebalan sekitar 30 m dengan batas bawahnya bertemu
dengan produk volkanik dari Formasi Cisubuh. Produk volkanik dari Formasi
Cisubuh memiliki ketebalan sekitar 60 m.
Gambar 3.21 Singkapan Satuan Endapan Dataran Banjir
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Satuan Endapan Sungai
Satuan ini menempati 20% dari luas daerah penelitian menyebar di sekitar
DAS sungai kecil maupun besar seperti Sungai Citarum dan Cibeet. Satuan ini
tersingkap jalur sungai yang merupakan cabang dari Sungai Cibeet. Ditemukan
banyak erosi di lereng-lereng yang tersusun oleh satuan ini. Sehingga dibeberapa
tempat, dijumpai adanya perkuatan yang telah dibangun.
Satuan ini berasal dari tanah tertranspor oleh medium air. Satuan ini
memiliki ciri berwarna abu-abu tua dan lunak (Gambar 3.22). Karena satuan ini
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
60
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
merupakan tanah hasil transpor suatu tanah dari tempat lain dan diendakan di
sekitar Desa Karangligar, maka umur dari satuan ini resen.
Hasil laboratorium dari sampel tanah dari satuan ini memberikan hasil
kadar air (Wn): 32,2%, berat jenis (ϒn): 2,5 g/cm3, jenis tanah: silty CLAY, warna:
dark BROWN, plastisitas indeks (IP): 37,1%, batas cair (LL): 65,04% (high plastic),
Kelas: CH, sudut geser dalam (θ): 21°, kohesi (c): 0,06 kg/cm2, koefisien
permeabilitas (k): 0,00012 cm/detik, specify gravity (Gs): 2,23, koefisien
pemampatan (Cv): 0.00147 cm2/detik, indeks komprebilitas (Cc): 0,171.
Tanah yang ada di satuan ini didominasi oleh lempung lanauan yang
memiliki tingkat plastisitas yang tinggi dan sudut geser dalam yang rendah. Dari
hasil pengujian laboratorium terlihat bahwa satuan ini memiliki nilai permeabilitas
yang sangat kecil yang menyebabkan air sangat sukar masuk kedalam tanah.
Berdasarkan nilai koefisien pemampatan yang didapat, satuan ini masih
mengalami konsolidasi alami. Apabila koefisien pemampatan tersebut selalu
konstan, diperkirakan tanah permukaan akan mampat setebal sekitar 4,6 meter.
Pemampatan yang terjadi sangat besar karena satuan ini merupakan tanah hasil
endapan sungai yang memiliki material lepas-lepas yang mudah tertranspor oleh
jalur sungai.
Gambar 3.22 Singkapan Satuan Endapan Sungai
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
61
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Kondisi Hidrogeologi Umum
Air yang meresap ke dalam tanah akan membentuk suatu sistem aliran air
bawah permukaan (airtanah), yang akan berbeda pada masing-masing daerah,
tergantung dari litologi dan bentang alamnya. Airtanah umumnya mengalir dari
daerah yang lebih tinggi ke daerah yang lebih rendah.
Terdapat aliran sungai di sebelah barat Desa Karangligar yang memiliki
elevasi muka airnya lebih tinggi dari muka tanah pada umumnya, sehingga di
beberapa tempat yang terjadi rembesan pada tanggul sungai membentuk rawa
di sekitarnya (Gambar 3.19). Hal tersebut harus segera ditanggulangi agar area
yang lebih rendah dari muka air sungai tidak tergenang.
Di tengah Desa Karangligar terbentuk suatu genangan dan rawa yang
luasnya diperkirakan mencapai 60 hektar. Berdasarkan hasil pengamatan
lapangan, genangan tersebut memiliki ketinggian muka air 12 mdpl. Ketinggian
tersebut merupakan titik terendah di Desa Karangligar, sehingga akan membuat
suatu anggapan bahwa terdapat suatu bentukan cekungan di area genangan
tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu, daerah Karangligar termasuk dalam
akuifer dengan tingkat keterusan rendah sampai sedang.
Air yang mensuplai genangan di Desa Karangligar berasal dari sungai hasil
percabangan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Air yang berasal dari sungai
percabangan Sungai Citarum mengalir mengikuti kemiringan lereng yang hanya
±3°. Air yang berasal dari Sungai Cibeet berasal dari Sungai Cidawolong yang
mengalirkan air menuju batas Desa Karangligar (Gambar 3.23). Sungai
Cidawolong seharusnya mengalirkan air dari Desa Karangligar keluar menuju
Sungai Cibeet. Suplai air juga ditambahkan dari sungai irigasi yang dibuat, baik
yang mengalir di area persawahan maupun sungai di barat desa.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
62
Kabupaten Karawang
KAJIAN LAPANGAN DESA KARANGLIGAR
Gambar 3.23 Rembesan Yang Terjadi Di Sungai Di Sebelah Barat Desa
Karangligar (Kiri) Dan Kenampakan Sungai Cabang Dari Sungai Cibeet
(Kanan)
Sumber: Hasil Observasi Lapangan, 2017
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
63
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP
BENCANA
Bab ini menjabarkan mengenai upaya mitigasi dan adaptasi yang perlu dilakukan
dalam menghadapi fenomena penurunan tanah di Desa Karangligar. Genangan
yang terjadi di Desa Karangligar bisa disebabkan oleh berbagai faktor, salah
satunya dapat berupa penurunan muka tanah, volume air permukaan yang terlalu
melimpah, ataupun gabungan keduanya. Penurunan muka tanah sendiri dapat
terjadi karena faktor alami dan faktor manusia. Kondisi penurunan muka tanah
alami akan berasosiasi dengan kejadian konsolidasi tanah penyusunnya.
Konsolidasi adalah suatu proses berkurangnya volume secara perlahan-lahan
pada lapisan tanah jenuh. Ketika suatu lapisan tanah jenuh mengalami kenaikan
tekanan, nilai tekanan air pori akan meningkat secara tiba-tiba. Kenaikan tekanan
air pori akan diikuti oleh berkurangnya volume dari massa tanah. Karena aliran
yang cepat dari air pori akan menyebabkan terjadinya settlement dan konsolidasi.
Kondisi ini akan terlihat di permukaan dengan terjadinya penurunan muka tanah
(land subsidence).
Penataan Pemanfaatan Ruang
Pendekatan yang diperlukan dalam penataan ruang didasarkan pada
perlindungan terhadap keseimbangan ekosistem dan jaminan terhadap
kesejahteraan masyarakat yang dilakukan secara harmonis, yaitu:
1) Penilaian pada struktur ruang dan pola ruang pada kawasan/wilayah
perencanaan; dan
2) Menjaga kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan pemanfaatan ruang
dengan fungsi dan daya dukung kawasan.
Pembangunan oleh manusia dapat menimbulkan atau membangkitkan
risiko bencana Keberadaan ancaman bencana alam menempatkan sehingga
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
64
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
perencanaan pembangunan menghindari dan mengurangi ancaman bencana
yang ada dengan mempertimbangkan keselamatan terhadap masyarakat,
bangunan dan lingkungannya (Henita, 2014).
Ketersediaan ruang untuk jalur evakuasi ketika terjadi bencana baik
berupa jalur penyelamatan atau ruang untuk mengungsian harus terpisah dari
pusat-pusat kegiatan sehingga tidak terjadi konsentrasi kegiatan yang
menyebabkan terjadinya konsentrasi penduduk pada satu ruang. Secara umum
yang harus diperhatikan adalah jalur tersebut dapat dilalui dengan baik dan
cepat, menjauhi sumber ancaman dan efek dari ancaman untuk jalur evakuasi di
luar bangunan hendaknya bisa memuat dua kendaraan jika saling berpapasan
tidak menghalangi proses evakuasi. Kemudian ada tempat pengungsian
sementara yang merupakan tempat aman dan tempat pengungsian akhir,
pengaturannya harus disepakati bersama oleh masyarakat, aman dan teratur.
(Henita, 2014)
Untuk wilayah yang dinyatakan rawan bencana harus dilakukan penataan
ulang dengan mempertimbang jaringan jalan yang mengarah ke upaya mitigasi
massal yaitu pola menyebar ke arah daerah yang ditetapkan sebagai area
evakuasi dengan jalan raya radial yang dilengkapi dengan jalan lingkar (ring road)
secukupnya (Soehartono, 2005).
Selain itu terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan pasca bencana seperti
penyediaan infrastruktur maupun penyediaan dan pengalokasian ruang-ruang
yang memiliki fungsi vital harus sudah memperhatikan perencanaannya ketika
dalam kondisi darurat. (Henita, 2014:45)
Penambahan ruang terbuka perlu dilakukan untuk memfasilitasi
terbentuknya fungsi-fungsi intergrasi sosial masyarakat sekaligus sebagai tempat
evakuasi bila terjadi bencana.
Selanjutnya, pembatasan terhadap perkembangan lahan terbangun yang
dapat mengurangi beban tanah. Penampungan sementara (retention pond) perlu
dilakukan agar air dari sungai tidak langsung masuk ke pemukiman penduduk
atau lahan pertanian tetapi ke daerah retensi terlebih dahulu.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
65
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Peningkatan Kapasitas Terhadap Bencana
Penguatan aturan yang memuat prosedur operasi perlu dioptimakan oleh
lembaga terkait penanggulangan bencana. Aturan terkait perlu dilaksanakan dan
diuji coba saat operasi darurat dan pemulihan bencana. Adanya Pusdalops
Penanggulangan Bencana di tingkat Kabupaten perlu didukung oleh mekanisme
dan prosedur yang jelas serta efektif. Dukungan tersebut juga dari kemampuan
dan kapasitas relawan dan personil yang memiliki kemampuan teknis dan siaga
selama 24 jam setiap harinya. Hal ini dilakukan untuk melihat efektivitas operasi
darurat bencana dan pemulihan bencana yang telah dilakukan.
Melalui riset-riset kebencanaan secara terstruktur untuk meningkatkan
rasio biaya investasi pra bencana dan biaya pemulihan perlu dibangun kerjasama
dengan mekanisme yang jelas dan efektif antara pemerintah, akademisi dan
masyarakat. Pelibatan peran seluruh sektor terkait penanggulangan bencana
menjadikan produktivitas riset dapat menjadi daya guna bagi upaya meredam
jatuhnya korban jiwa dan harta benda.
Perlu adanya forum pengurangan risiko bencana di tingkat Kabupaten
yang terdiri dari pemangku kepentingan lintas institusi untuk mempercepat
kemajuan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Salah satu fokus
kemitraan dalam forum yang dibentuk adalah optimalisasi peran dunia usaha
dalam pengurangan risiko bencana ditingkat lokal yang mampu mengurangi
kerentanan sektor ekonomi masyarakat rentan. Disamping itu Peningkatan
Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui upaya-upaya membangun desa-desa
percontohan untuk Kesiapsiagaan Bencana. Diharapkan Desa-desa percontohan
ini akan menjadi stimulan bagi masyarakat untuk membudayakan kesiapsiagaan
bencana dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut Sarwono (2006) faktor paling dasar dan paling awal yang
menyebabkan orang merasa perlu atau tidak perlu melakukan adjustment adalah
kesadaran (awareness).
Beberapa prinsip pembangunan berkelanjutan dari Deklarasi Rio pada
tahun 1992 (Miller, 2004), sebagai berikut:
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
66
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
1. Penduduk asli dan setempat mempunyai peran penting dalam pengelolaan
dan pembangunan lingkungan karena pemahaman dan pengetahuan
tradisional mereka
2. Penanganan terbaik isu-isu lingkungan adalah dengan partisipasi seluruh
masyarakat
Pemberian pengetahuan terkait bencana kepada masyarakat menjadi
penting untuk dilakukan seperti gejala munculnya bencana, gejala awal bencana,
pengembangan dan pengujian secara teratur terhadap sistem peringatan dini,
rencana evakuasi atau tindakan lain yang harus diambil selama periode waspada.
Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui brosur, informasi media cetak dan
elektronik dan lain-lain. Media membantu dengan menayangkan program yang
memberi informasi upaya penyelamatan terhadap bencana gempa, dilakukan
dengan program peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan,
diklat maupun sosialisasi. (Henita, 2014:45)
Peningkatan Koordinasi Para Pemangku
Kepentingan
Dalam upaya mengurangi kerugian akibat bencana banjir, aspek
pengendalian banjir adalah sangat penting. Secara umum, pengendalian banjir
dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu upaya struktur dan non struktur. Upaya
struktur antara lain seperti waduk, floodway, perbaikan alur sungai, danau retensi
(embung). Upaya struktur pengendalian banjir seringkali tidak berjalan dengan
optimal, karena penyelesaian banjir bersifat sektoral dan tidak terpadu.
Sedangkan upaya pengembangan non struktur antara lain Flood Planning
Zooning dan Flood Forecasting and Warning System (FFWS) atau sistem prediksi
dan peringatan dini banjir yang meliputi kegiatan prediksi (prakiraan) besar dan
kapan akan terjadi banjir sekaligus pemberitahuan kepada masyarakat yang
kemungkinan akan terjadinya.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
67
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Pembangunan Sistem Peringatan Dini
Pembangunan sistem peringatan dini memadukan kemajuan teknologi
dan kearifan lokal. Pembangunan sistem kesiapsiagaan lainnya adalah
penyusunan rencana kontijensi bencana yang diharapkan dapat menjamin
ketersediaan anggaran penanganan darurat bencana dari berbagai alternatif
sumber anggaran dan dapat memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh seluruh
institusi dan masyarakat untuk penanganan darurat bencana. Mobilisasi sumber
daya ini perlu diperkuat dalam sebuah mekanisme yang disepakati bersama.
Pembangunan Kolam Retensi
Sebagian besar dari upaya pengendalian banjir yang dilakukan umumnya
masih secara konvensional, yaitu memperbesar dan memperbaiki saluran
drainase yang ada sehingga air hujan dapat segera tersalurkan. Padahal konsep
drainase konvensional memiliki kekurangan yaitu tidak memberikan kesempatan
untuk air meresap ke dalam tanah. Selama ini konsep drainase konvensional
menimbulkan masalah lain yaitu berkurangnya pasokan air tanah karena air tidak
diresapkan ke tanah. Oleh karena itu diperlukan sistem pengendalian banjir yang
berwawasan lingkungan untuk mengoptimalkan resapan sekaligus sebagai
langkah mitigasi penurunan tanah di Desa Karangligar. Salah satu upaya yang
dapat dilakukan adalah dengan pembuatan kolam retensi.
Menurut Kementrian PUPR, kolam retensi (retention ponds) adalah
kolam/waduk penampungan air hujan dalam jangka waktu tertentu. Fungsinya
untuk memotong puncak banjir yang terjadi dalam badan air/sungai. Fungsi lain
dari kolam retensi adalah untuk menggantikan peran lahan resapan yang
dijadikan lahan tertutup/perumahan/perkantoran maka fungsi resapan dapat
digantikan dengan kolam retensi. Fungsi kolam ini adalah menampung air hujan
langsung dan aliran dari sistem untuk diresapkan ke dalam tanah. Sehingga
kolam retensi ini perlu ditempatkan pada bagian yang terendah dari lahan
(Florince dkk, 2015)
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
68
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Konsep dasar dari kolam retensi adalah menampung volume air ketika
debit maksimum di sungai datang, kemudian secara perlahan-lahan
mengalirkannya ketika debit di sungai sudah kembali normal. Secara spesifik
kolam retensi akan memangkas besarnya puncak banjir yang ada di sungai,
sehingga potensi over topping yang mengakibatkan kegagalan tanggul dan
luapan sungai tereduksi (Kunaifi, 2017).
Gambar 4.1 Sketsa Kolam Retensi
Sumber: Diolah dari Situs Foresite Group
Secara umum, skema pengendalian banjir di Desa Karangligar melibatkan
pembangunan tanggul untuk memisahkan bagian desa yang berada di bawah
badan/saluran air seperti jaringan irigasi atau sungai dan bagian desa yang
mengalami penurunan tanah untuk mencegah limpasan eksternal memasuki
desa. Kemudian dibangun sebuah kolam penyimpanan banjir (kolam retensi)
untuk penyimpanan sementara air hujan atau luapan dari Sungai Cibeet maupun
Sungai Citarum di dalam area yang sekarang telah menjadi genangan permanen.
Selain itu dibangun stasiun pemompaan air untuk memompa air dari kolam
retensi ke saluran pembuangan untuk dibuang ke sungai ketika debit di sungai
sudah kembali normal.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
69
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Gambar 4.2 Skema Pengendalian Banjir Untuk Desa Karangligar
Sumber: Diolah dari Situs Drainage Services Department
The Government of the Hong Kong
Apabila melihat kondisi eksisting jalur dari kolam retensi ke Sungai Cibeet
dan Sungai Citarum akan akan melewati bagian jalan atau bangunan. Oleh karena
itu, saluran air dari kolam retensi ke sungai maupun sebaliknya dapat berbentuk
sipon. Sipon adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengalirkan air dengan
menggunakan gravitasi yang melewati bagian bawah jalan, jalan kereta api dan
bangunan lainnya. Pada sipon air mengalir karena tekanan. Perencanaan hidrolis
sipon harus mempertimbangkan kecepatan aliran, kehilangan kecepatan aliran
pada peralihan masuk, kehilangan akibat gesekan, kehilangan pada bagian siku
sipon serta kehilangan pada peralihan keluar. Jarak dari genangan eksisting di
Desa Karangligar ke Sungai Cibeet kurang lebih 2 km. Sedangkan jaraknya ke
Sungai Citarum kurang lebih 1,2 km.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
70
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Gambar 4.3 Jarak Dari Genangan Eksting ke Sungai Citarum dan Cibeet
Sumber: Hasil Analisis, 2017
Peralihan Kegiatan Perekonomian
Kegiatan perekonomian utama adalah pertanian, namun setelah terjadi
banjir dan tergenang maka kegiatan pertanian tersebut tidak dapat lagi
dilakukan. Maka dari itu untuk adaptasi kegiatan ekonomi yang sesuai dengan
kondisi saat ini, daerah genangan yang ada dapat dipergunakan untuk kegiatan
perikanan seperti budidaya perikanan air tawar. Lalu untuk
mengimplementasikannya maka aspek penting yang perlu dipertimbangkan
dalam evaluasi lahan untuk budidaya budidaya perikanan air tawar meliputi
Chanrantchakool et al. (1995): sumber air, kualitas tanah, dan ketersediaan
infrastruktur. Selain itu Poernomo (1979) menyatakan bahwa aspek penting yang
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
71
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
harus memenuhi persyaratan dalam evaluasi lahan untuk budidaya budidaya
perikanan air tawar adalah aspek ekologi dan topografi, tanah, dan biologi. Aspek
rekayasa, kualitas tanah, kualitas air, dan fasilitas infrastruktur adalah aspek yang
dipertimbangkan oleh Karthik et al. (2005) dalam evaluasi lahan untuk budidaya
budidaya perikanan air tawar.
Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi budidaya perikanan air tawar
dapat mengembalikan lahan menjadi produktif kembali. Contohnya seperti yang
terjadi pada lahan sawah di Kota Pekalongan yang terlantar akibat terendam rob
menjadikan aktivitas perekonomian lumpuh khususnya sektor pertanian lumpuh
total. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen Perikanan
Budidaya telah berhasil memanfaatkan lahan sawah yang terendam air laut
tersebut menjadi budidaya perikanan ikan dengan teknik pen culture atau jaring
tancap. Terjadi perkembangan yang baik dalam budidaya perikanan tersebut,
sehingga banyak petani yang beralih ke budidaya perikanan . Kelebihan dari
bidaya tersebut adalah para petani dapat melakukan panen 4 kali dalam setahun.
Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari binaan pemerintah dalam rangka
meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan budidaya perikanan.
Untuk menyukseskan keberhasilan program budidaya tersebut, Pemerintah
Kabupaten Pekalongan juga memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada
bantuan bibit dan pompa pada beberapa budidaya perikanan percontohan pada
para pembudidaya ikan . Selain itu, Pemerintah daerah mengalokasikan APBD
untuk mendukung budidaya udang melalui pembangunan jalan produksi bekerja
sama dengan Kementrian PU maupun mengalirkan listrik ke lokasi budidaya
udang
Usaha budidaya udang di Pekalongan dinilai bisa menjadi tumpuan
ekonomi bagi masyarakat setempat sehingga bisa mengurangi tingkat
kemiskinan. Akibat bencana tersebut jumlah warga miskin di sana meningkat
hingga lebih dari 800 kepala keluarga (KK), namun dengan mulai dilakukannya
budidaya udang, jumlah warga miskin di wilayah tersebut berkurang menjadi 160
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
72
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
KK saja dikarenakan banyak warga setempat yang tadinya menganggur kini
menjadi pembudidaya udang.
Untuk menjaga keberlangsungan usaha di bidang budidaya perikanan
perlu mempertimbangkan daya dukung kawasan budidaya agar tingkat
produktivitas tetap baik sekaligus meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan
pembudidaya ikan di sekitarnya. Salah satu upaya menjaga daya dukung
kawasan adalah dengan melakukan revitalisasi tambak. Kementerian Kelautan
dan Perikanan mendapat dukungan Kementerian Pekerjaan Umum untuk
melakukan perbaikan infrastruktur berupa saluran primer dan sekunder sebagai
upaya memberi jaminan pasokan air dengan baik kepetakan tambak.
Permasalahan yang dialami dalam budidaya tersebut adalah limbah pabrik
batik dikarenakan limbah yang dibuang langsung ke sungai tanpa pengolahan
terlebih dulu. Kondisi tersebut serupa dengan di Kabupaten Karawang yang
berkembang pesat dalam industri.
Upaya Mitigasi Terhadap Bencana Desa
Karangligar
Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka upaya mitigasi baik
yang bersifat struktural maupun non struktural di Desa Karangligar dirangkum
dalam Tabel 4.1 berikut ini.
A. Mitigasi Struktural
1. Membangun dan Mengembangkan Jaringan Drainase Wilayah
2. Menjaga Pasokan Air untuk Pertanian/Budidaya Perikanan Air Tawar
Dengan Mengembalikan Fungsi Irigasi
3. Pengembalian Fungsi Sempadan Sungai
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 28 /PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis
Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau
Kriteria penetapan garis sempadan sungai me meliputi ruang di kiri
dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
73
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
sungai untuk sungai tidak bertanggul, atau di antara garis sempadan
dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggul.
Sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan terdiri atas
sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar dari 500
km2 dan sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari
atausama dengan 500 km2.Garis sempadan sungai besar tidak
bertanggul di luar kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit
berjarak 100 meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang
alur sungai. Garis sempadan sungai kecil tidak bertanggul di luar
kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit 50 meter dari tepi kiri
dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai
Garis sempadan sungai bertanggul di luar kawasan perkotaan
ditentukan paling sedikit berjarak 5 meter dari tepi luar kaki tanggul
sepanjang alur sungai.
4. Pengembalian Fungsi Sempadan Irigasi Bertanggul
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 08 /PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis
Sempadan Jaringan Irigasi
Jarak garis sempadan paling sedikit sama dengan ketinggian
tanggul saluran irigasi yaitu mempunyai ketinggian kurang dari 1
meter, jarak garis sempadan saluran irigasi bertanggul paling sedikit
1 meter;
Penetapan garis sempadan jaringan irigasi dilakukan dengan
pemasangan patok Dinas, Balai Besar Wilayah Sungai/Balai
Wilayah Sungai, badan usaha dan/atau badan sosial
menyelenggarakan pemetaan batas kepemilikan tanah sepanjang
saluran irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya;
Dalam hal terdapat kepemilikan tanah melebihi batas garis
sempadan jaringan irigasi yang diperlukan, pemetaan patok batas
sempadan jaringan irigasi dapat melebihi batas garis sempadan
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
74
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
jaringan irigasi guna mentolerir keperluan pemilik tanah atas tanah
yang tersisa paling sedikit harus memenuhi kriteria seperti tidak
layak secara ekonomis, luasan maksimum 200 meter2 dan lebar
maksimum 2 meter;
Pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi hanya dapat
dimanfaatkan untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi. Namun
dalam keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan
fungsi jaringan irigasi, ruang sempadan jaringan irigasi dapat
dimanfaatkan untuk keperluan lain. Keperluan lain tersebut dapat
berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan
rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas,
mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan
umum; dan
Dilakukan pengamanan ruang sempadan jaringan irigasi meliputi
kegiatan pencegahan dan penertiban dalam bentuk fisik dan
nonfisik beserta pengawasan dalam rangka memantau tindakan-
tindakan yang terjadi di ruang sempadan jaringan irigasi.
5. Ruang dan Jalur Evakuasi
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 7
Tahun 2015 tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana
a. Rambu petunjuk bencana terdiri atas:
Rambu tempat berkumpul sementara
Rambu tempat lokasi pengungsian
Rambu lokasi posko
Rambu tempat untuk membuat api
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
75
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Rambu arah jalur evakuasi
Rambu arah tempat pengungsian
Rambu petunjuk dengan kata
b. Papan informasi bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan
bencana atau bahayanya, informasi kejadian bencana yang pernah
terjadi dan/atau berpotensi akan terjadi serta lokasi tempat kumpul
sementara atau tempat pengungsian, terdiri atas:
Papan informasi jenis bahaya
Papan informasi kejadian bencana
Papan informasi memasuki kawasan rawan bencana
Papan informasi jalur evakuasi bencana
Papan informasi penanda tempat
c. Penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana
Selain itu dari segi kewilayahannya sebagai berikut.
a. Jalur penyelamatan atau ruang untuk mengungsian harus terpisah
dari pusat-pusat kegiatan sehingga tidak terjadi konsentrasi
kegiatan yang menyebabkan terjadinya konsentrasi penduduk pada
satu ruang.
b. Jalur evakuasi dapat dilalui dengan baik dan cepat, menjauhi sumber
ancaman dan efek dari ancaman untuk jalur evakuasi di luar
bangunan hendaknya bisa memuat dua kendaraan jika saling
berpapasan tidak menghalangi proses evakuasi.
c. Terdapat tempat pengungsian sementara yang merupakan tempat
aman dan tempat pengungsian akhir, pengaturannya harus
disepakati bersama oleh masyarakat, aman dan teratur.
Untuk wilayah yang dinyatakan rawan bencana harus dilakukan penataan
ulang dengan mempertimbang jaringan jalan yang mengarah ke upaya
mitigasi massal yaitu pola menyebar ke arah daerah yang ditetapkan
sebagai area evakuasi dengan jalan raya radial yang dilengkapi dengan
jalan lingkar (ring road) secukupnya.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
76
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
6. Penambahan Kawasan Resapan Air
Dilakukan dengan penambahan Ruang Terbuka perlu dilakukan untuk
memfasilitasi terbentuknya fungsi-fungsi intergrasi sosial masyarakat
sekaligus sebagai tempat evakuasi bila terjadi bencana. Serta adanya
pemanfaatan air hujan dilakukan dengan cara membuat kolam
pengumpul air hujan, sumur resapan, dan/atau lubang resapan biopori.
Kewajiban pemanfaatan air hujan dikecualikan pada kawasan karst, rawa,
dan/atau gambut. (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor
12 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Air Hujan
B. Mitigasi Non Struktural
1. Adaptasi Perubahan Kegiatan Ekonomi Pertanian ke Budidaya Perikanan
Air Tawar
2. Penyusunan Rencana Kontijensi Bencana Penurunan Tanah F
3. Peningkatan Kapasitas Masyarakat
1) Membangun desa-desa percontohan untuk Kesiapsiagaan Bencana.
Diharapkan Desa-desa percontohan ini akan menjadi stimulan bagi
masyarakat untuk membudayakan kesiapsiagaan bencana dalam
kehidupan bermasyarakat.
2) Pengelolaan dan pembangunan lingkungan berdasarkan
pemahaman dan pengetahuan tradisional mereka
3) Partisipasi aktif seluruh masyarakat
4. Penghematan Penggunaan Air Tanah
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penghematan
Penggunaan Air Tanah, cara-cara penghematan yang dapat dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai
macam kebutuhan
Menggunakan air sesuai kebutuhan
Menghindari pemborosan penggunan air
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
77
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Pemanfaatan peralatan yang dapat menghemat penggunaan air
Menggunakan water meter untuk memantau pengambilan air
tanah
Merawat peralatan instalasi air secara berkala serta mengganti
peralatan yang tidak bekerja dengan baik
b. Mengurangi penggunaan air tanah
Air bersih dari air tanah hanya digunakan untuk memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari
Membuka keran setangah dari bukaan total dalam penggunaan
Menutup keran segera ketika air tidak digunakan
Membuat bak penampungan air hujan sebagai air cadangan
untuk berbagai kebutuhan
c. Menggunakan kembali air tanah
Menggunakan air bekas untuk menyiram tanaman
Menggunakan air bekas cucian untuk mencuci mobil, kemudian
dibilas dengan air bersih
Menggunakan air bekas untuk flushing
d. Mendaur ulang air tanah
Air kotor didaur ulang pada instalasi pengolah air sesuai standar
baku selanjutnya diresapkan ke dalam tanah atau digunakan
kembali untuk kebutuhan lainnya
Membuat bak penampungan air bekas pemakaian yang masih
mempunyai kualitas cukup baik untuk dapat dipergunakan
kembali
Membuat sumur resapan hujan ke dalam tanah
e. Mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan
Menggunakan sistem penampungan air
Menggunakan sistem otomatis untuk pengambilan air tanah
berdasarkan kapasitas penampungan air
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
78
Kabupaten Karawang
MITIGASI DAN ADAPTASI TERHADAP BENCANA
Untuk pertanian, air tanah digunakan terutama untuk tanaman
yang hemat air
f. Menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir
Mengutamakan penggunaan air permukaan
Memanfaatkan air hujan
Mengutamakan penggunaan perusahaan air
minum/perusahaan daera h air minum bagi daerah yang
terjangkau layanan perusahaan air minum/perusahaan daerah
air minum
g. Mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air
Menggunakan shower untuk mandi
Menggunakan penggelontor otomatis
Menggunakan teknologi lain yang terbukti lebih hemat air
h. Memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah
Memberikan disinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah
5. Peningkatan Pemahaman terhadap kondisi Bencana di Karawang dengan
melakukan riset-riset kebencanaan lanjutan
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
79
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Bab ini akan menjabarkan mengenai kesimpulan dan alternatif rekomendasi
berdasarkan hasil kajian laporan akhir ini.
Kesimpulan
Berdasarkan hasil kajian hingga laporan akhir ini maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut ini. Pertama, dari hasil kajian eksternal kewilayahan
Desa Karangligar terhadap DAS Citarum menunjukkan bahwa kondisi DAS yang
mengalami erosi dan sudah tidak bisa menampung air menyebabkan daerah hilir
sering terjadi banjir, sebaliknya pada musim kemarau sering terjadi kekeringan.
Hal ini diperparah dengan luas vegetasi permanen yang terdapat di DAS Citarum
Hulu yaitu luas hutan hanya 18%. Permasalahan banjir terjadi tidak hanya
diakibatkan permasalahan yang ada di lokasi yang terkena banjir saja namun
terkait juga dengan masalah yang terjadi di daerah hulu sampai dengan hilirnya.
Adanya rencana pembangunan Waduk Cibeet diharapkan dapat mengurangi
dampak dari bahaya banjir di Desa Karangligar. Selain itu kajian eksternal
terhadap perkembangan kegiatan industri di Kabupaten Karawang ditemukan
fakta bahwa sari seluruh industri yang berada di Kabupaten Karawang sekitar 5-
7% yang menggunakan pelayanan PDAM, mayoritas menggunakan air bor tanah.
Hal ini memungkinkan adanya pengaruh terhadap fenomena penurunan tanah di
Karangligar.
Kedua, dari hasil kajian lapangan Desa Karangligar menunjukkan bahwa
kegiatan pertanian yang ada tersebut terganggu bencana di Desa Karangligar
mengakibatkan terjadinya kerentanan ekonomi di masyarakat. Kondisi sarana
prasarana seperti irigasi sudah tidak dapat menampung air yang berdampak pada
kerusakan jalan karena tergenang banjir. Selain itu juga terdapat aktivitas
eksplorasi dan produksi migas oleh Pertamina EP yang juga turut menjadi korban
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
80
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
banjir. Beberapa fasilitas produksi Pertamina EP seperti yang menimpa SP Cicauh
terendam air cukup dalam. Terdapat 8 sumur eksplorasi dan produksi gas bumi
dan yang masih aktif sebanyak 4 sumur, yang bermuara ke Stasiun Pengumpul
Cicauh. Kegiatan produksi terjadi mulai tahun 1990 dan hingga tahun 2017 sudah
mencapai ± 27 tahun. Selain itu terdapat kegiatan “Biopori for Karangligar” untuk
mengurangi resiko bencana.
Lebih lanjut, dari sisi geologi di Desa Karangligar, daerah penelitian
tersusun atas morfologi perbukitan dan lembah yang berada pada interval 12-37
mdpl. Sungai berpola meander yang ditunjukan oleh kenampakan sungai besar
yang berkelak-kelok dan pola lembah sungai yang lebar dan panjang. Di tengah
Desa Karangligar terbentuk suatu genangan dan rawa yang luasnya diperkirakan
mencapai 60 hektar dengan ketinggian muka air pada kontur 12 mdpl.
Berdasarkan kondisi bentuk muka bumi (landform), daerah penelitian dibagi
menjadi 2 satuan geomorfologi, yaitu Satuan Punggungan Memanjang dan
Satuan Dataran Rendah Karangligar Satuan Dataran Rendah Karangligar menjadi
satuan yang mendominasi di daerah penelitian. Berdasarkan data kontur tahun
2007 dan 2015 didapatkan penurunan muka tanah di Desa Karangligar sekitar 2
meter.
Satuan geologi teknik daerah penelitian dapat dibagi menjadi 3 satuan,
yaitu Satuan Tanah Residual Batupasir, Satuan Endapan Dataran Banjir, Satuan
Endapan Sungai. Satuan Endapan Dataran Banjir menjadi satuan yang
mendominasi di daerah penelitian dan pada satuan ini masih berlangsung
konsolidasi alami. Endapan Kuarter yang berada di Desa Karangligar umumnya
memiliki daya dukung yang rendah dengan ketebalan sekitar 30 meter.
Berdasarkan sampel yang diambil di permukaan, Satuan Tanah Residual Batupasir
akan termampatkan ±2,3 meter, Satuan Endapan Dataran Banjir akan
termampatkan ±2,5 meter, dan Satuan Endapan Sungai akan termampatkan ±4,6
meter. Adanya perubahan nilai permeabilitas dari peneltian terdahulu yang
menunjukkan suatu pengurangan laju aliran air melewati satuan ini.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
81
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Rekomendasi
Dari hasil kajian terhadap bentuk mitigasi terhadap bencana di Desa
Karangligar, upaya mitigasi struktural dapat dilakukan dengan, normalisasi
sungai, menghilangkan daerah genangan, menjaga pasokan air untuk
pertanian/budidaya perikanan , pengembalian fungsi sempadan sungai,
pengembalian fungsi sempadan irigasi bertanggul, pembangunan ruang dan jalur
evakuasi, penambahan kawasan resapan air, dan adaptasi perubahan kegiatan
ekonomi pertanian ke perikanan air tawar. Sedangkan dari sisi mitigasi non
struktural, maka dapat dilakukan upaya penyusunan rencana penanggulangan
bencana, peningkatan kapasitas masyarakat, penghematan penggunaan air
tanah, dan pemahaman terhadap kondisi bencana di karawang.
Studi lanjutan untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi mengenai
penurunan kontur tanah dapat dilakukan dengan:
• Pengukuran topografi dengan Total Station dan Geodetic GPS untuk
mengetahui kecepatan penurunan tanah dalam kurun waktu tertentu.
• Pengujian Piezocone (CPTu) untuk mengetahui tekanan air di bawah
permukaan, sehingga dapat diketahui lapisan-lapisan yang kemungkinan
masih mengalami konsolidasi/ pemampatan.
• Pengeboran untuk mengetahui karakteristik dari endapan Kuarter yang
berada di bawah permukaan
Gambar 5.1 Geodetik GPS
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
82
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Gambar 5.2 Total Station444
Gambar 5.3 Piezocone
Gambar 5.4 Bor
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
83
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Gambar 5.5 Grafik Piezocone
Selanjutnya berdasarkan hasil studi lanjutan untuk mendapatkan hasil
yang lebih presisi mengenai penurunan kontur tanah nantinya, maka dapat
diusulkan dua alternatif rekomendasi sebagai upaya penanganan fenomena
penurunan kontur tanah di Desa Karangligar terutama pada area genangan
banjir. Alternatif rekomendasi yang pertama adalah mempertahankan genangan
supaya tidak bertambah dan lahan pertanian yang tersisa saat ini tetap produktif
serta ditetapkan menjadi LP2B. Hal ini sesuai jika masyarakat memiliki keinginan
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
84
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
bertahan pada sektor pertanian. Penyebabnya adalah karena terdapat
ketidakpastian nafkah jika masyarakat yang sekarang bekerja sebagai petani
bekerja di luar sektor pertanian. Upaya mengembalikan area genangan menjadi
lahan pertanian dapat dilakukan dengan perbaikan total jaringan irigasi dan
drainase, pembatasan pengambilan air tanah, pembatasan penambahan beban
bangunan, pengembalian fungsi sempadan sungai dan jaringan irigasi serta
penetapan Perda LP2B.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan Insentif perlindungan Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan kepada Petani dengan jenis berupa:
1. Bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan
2. Pengembangan infrastruktur pertanian
a. Pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
b. Pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
c. Pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
d. Perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
e. Konservasi tanah dan air.
3. Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul
a. Penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul,
hibrida, dan lokal; dan
b. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih
4. Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi berbentuk
penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi
5. Penyediaan sarana produksi pertanian
a. Penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk
organik dan anorganik, serta pestisida; dan
b. Sarana produksi pertanian sesuai dengan kebutuhan dan
rekomendasi dari tim penilai yang dibentuk oleh bupati.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
85
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
6. Bantuan dana penerbitan sertipikat hak atas tanah pada Lahan Pertanian
Pangan Berkelanjutan; dan/atau
Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi.
Perbaikan total jaringan
irigasi dan drainase
Mempertahankan
genangan supaya
Pembatasan
Keinginan tidak bertambah dan
pengambilan air tanah
masyarakat lahan pertanian yang
bertahan pada tersisa saat ini tetap
Pembatasan
sektor pertanian produktif serta
penambahan beban
ditetapkan menjadi
bangunan
LP2B
Pengembalian fungsi
Penyebab: sempadan sungai dan
Ketidakpastian jaringan irigasi
nafkah di luar
sektor pertanian Penetapan Peraturan
Daerah tentang LP2B
Gambar 5.6 Alternatif Rekomendasi Pertama
Menurut BBPBAP (2007) manajemen yang baik akan berpengaruh positif
terhadap keberhasilan usaha budidaya perikanan , pengertian sistem budidaya
perikanan dan fungsinya berdasarkan pengelolaan budidaya perikanan yang
baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Mendapatkan air pasok yang bebas hama penular dan logam berat yang
berbahaya;
b. Kolam dapat menampung air dan mempertahankan kedalaman sesuai
yang diinginkan (tidak rembes);
c. Mengeluarkan limbah dengan tingkat sedimen dan bahan organik terlarut
yang rendah;
d. Dapat menjaga keseimbangan proses mikrobiologis;
e. Menggunakan bahan kimiawi/obat-obatan yang aman bagi manusia dan
lingkungan dan
f. Menebar benih yang sehat.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
86
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pasokan kualitas air yang baik merupakan faktor yang penting bagi
budidaya perairan karena berpengaruh terhadap reproduksi, pertumbuhan dan
kelangsungan hidup organisme aquatik (Chien, 1992). Apabila sumber air untuk
budidaya perikanan udang mengalami penurunan kualitas karena polusi maka
kualitas air pada kolam akan terganggu dan kerentanan terhadap penyakit lebih
besar dan tingkat kematian lebih tinggi.
Sedangkan untuk alternatif rekomendasi yang kedua adalah menjadikan
genangan sebagai kolam retensi atau embung (retention ponds). Hal ini adalah
sebagai bentuk adaptasi masyarakat dengan fenomena alam yang terjadi.
Penyebabnya adalah penurunan tanah secara alami yang masih berlangsung.
Upaya yang harus dilakukan untuk menjadikan genangan sebagai embung adalah
dengan pembuatan tanggul untuk menahan perkembangan genangan,
penyediaan akses khusus ke salah satu sumur milik Pertamina yang terganggu,
pembebasan lahan untuk pembangunan embung, pembangunan dan Perbaikan
jaringan drainase, pengembalian fungsi sempadan sungai dan jaringan irigasi,
serta pengalihan fungsi kegiatan pertanian menjadi perikanan air tawar dan
pengembangan masyarakatnya.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
87
Kabupaten Karawang
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Pembuatan tanggul untuk
menahan perkembangan
genangan
Penyediaan akses khusus ke
salah satu sumur milik
Pertamina yang terganggu
Pembebasan lahan untuk
pembangunan embung
Menjadikan
Adaptasi masyarakat
genangan sebagai
dengan fenomena alam
embung (retention Pembangunan dan Perbaikan
yang terjadi
ponds) jaringan drainase
Pengembalian fungsi
sempadan sungai dan jaringan
Penyebab:
irigasi
Penurunan tanah secara
alami yang masih
berlangsung Pengalihan fungsi kegiatan
pertanian menjadi perikanan air
tawar beserta pengembangan
masyarakat
Gambar 5.7 Alternatif Rekomendasi Kedua
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
88
Kabupaten Karawang
DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR PUSTAKA
Achdan, A. dan Sudana, D. 1992. Peta Geologi Lembar Karawang, Jawa, Skala
1:100.000. Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi. Bandung.
Brahmantyo, B., dan Bandono, 2006. Klasifikasi Bentuk Muka Bumi (landform)
untuk Pemetaan Geomorfologi pada Skala 1:25.000 dan Aplikasinya untuk
Penataan Ruang. Jurnal Geoaplika 1(2):71-78.
Das, B. M.. 2007. Fundamentals of Geotechnical Engineering 3rd edition. Parainfo:
Madrid.
Fillah, Azmi Sahid, Ishartono Ishartono, and Muhammad Fedryansyah. 2016.
Program Penanggulangan Bencana Oleh Disaster Management Center
(DMC) Dompet Dhuafa. Prosiding KS 3, No. 2 ().
Firmansyah, Iman, and Hanny Rasni. 2014. Hubungan Pengetahuan dengan
Perilaku Kesiapsiagaan dalam Menghadapi Bencana Banjir dan Longsor
pada Remaja Usia 15-18 tahun di SMA Al-Hasan Kemiri Kecamatan Panti
Kabupaten Jember (The Correlation Between Knowledge and behavior
preparedness in Facing of Floods And Landslides disaster in adolescents
aged 15-18 in SMA Al-Hasan Kemiri Sub district Panti of Jember Regency).
Flanagan, Barry E., Edward W. Gregory, Elaine J. Hallisey, Janet L. Heitgerd, and
Brian Lewis. 2011. A Social Vulnerability Index For Disaster Management."
Journal Of Homeland Security And Emergency Management 8, No. 1.
Florince, dkk. 2015. Studi Kolam Retensi sebagai Upaya Pengendalian Banjir
Sungai Way Simpur Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat.
JRSDD, Edisi September 2015, Vol. 3, No. 3, Hal:507-520 (ISSN:2303-0011).
Giovanny, Abednego. Kelentingan Nafkah Masyarakat Desa di Kawasan Banjir
(Kasus: Daerah Aliran Sungai Cibeet, Desa Karangligar, Kecamatan
Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang). Departemen Sains Komunikasi
Dan Pengembangan Masyarakat-Fakultas Ekologi Manusia IPB 2016.
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
89
Kabupaten Karawang
DAFTAR PUSTAKA
Imansyah, Muhammad Fadhil. Studi Umum Permasalahan dan Solusi DAS Citarum
Serta Analisis Kebijakan Pemerintah. Jurnal Sosioteknologi Edisi 25 Tahun
11, April 2012. Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan
Lingkungan ITB.
Kaku, Kazuya, and Alexander Held. 2013. Sentinel Asia: A space-based disaster
management support system in the Asia-Pacific region. International
Journal of Disaster Risk Reduction 6: 1-17.
Kunaifi, Azwar Annas. 2017. Kolam Retensi (Retarding Basin) Sebagai Alternatif
Pengendali Banjir Dan Rob. Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah.
Lobeck, A. K.. 1939. Geomorphology: An Introduction to the Study of Landscapes.
Mc.Graw-Hill Book Company, New York.
Martodjoyo, S.. 1984. Evolusi Cekungan Bogor, Jawa Barat. Disertasi Doktor.
Penerbit ITB: Bandung.
MasterPlan Penanganan Terpadu Wilayah Sungai Citarum 2010-2025.
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang 2005-2025
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang 2011-2031
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 2009-2029
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum
Mitigasi Bencana
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana
Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
90
Kabupaten Karawang
DAFTAR PUSTAKA
Potensi Desa Jawa Barat, 2014
Prawiradisastra, Suryana. 2013. Analisis Kerawanan Dan Kerentanan Bencana
Gempabumi Dan Tsunami Untuk Perencanaan Wilayah Di Kabupaten
Maluku Tenggara Barat. Jurnal Sains dan Teknologi Indonesia 13, No. 2.
Ren, G., B. N. Whittaker, and D. J. Reddish. 1989.Mining Subsidence And
Displacement Prediction Using Influence Function Methods For Steep
Seams. Mining Science and Technology 8, No. 3: 235-251.
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Citarum Tahun 2016. Balai
Besar Wilayah Sungai Citarum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
Rahmayanti, Henita. 2014. Adaptasi Masyarakat Kota Rawan Bencana “Tinjauan
Konsep Pemahaman,Persepsi dan Kesiapan Mitigasi Dalam Perubahan
Tata Ruang”. UniversitasI Indonesia: Jakarta
Sagala, Saut, Dodon Yamin, Alpian A. Pratama, and Elisabeth Rianawati. 2016. 13
Social Protection, Disaster Risk Reduction And Community Resilience.
Social Development and Social Work Perspectives on Social Protection:
260.
Sudibyakto, Sudibyakto Sudibyakto. 2016.Anomali Iklim Dan Mitigasi Kebakaran
Hutan Di Indonesia. Majalah Geografi Indonesia 17, No. 1: 71-80.
Thornbury, W. D. 1989. Principles of Geomorphology. John Willey & Sons, inc
Tommi dkk. 2015. Analisis Kerentanan Petani Terhadap Bahaya Banjir di
Kabupaten Karawang. Jurnal Geografi UNNES 2015Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
Van Bemmelen, R. W.. 1949. The Geology of Indonesia. Govt. Printing Office: The
Haque
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
91
Kabupaten Karawang
DAFTAR PUSTAKA
Laporan Akhir-Kajian Kontur Tanah dan Karakteristik Bencana
92
Kabupaten Karawang
Anda mungkin juga menyukai
- Executive Summary RIP Kobisadar Rev PDFDokumen58 halamanExecutive Summary RIP Kobisadar Rev PDFPepo SupalaBelum ada peringkat
- 01 Lapdul DAS PengabuanDokumen170 halaman01 Lapdul DAS PengabuanAnonymous z8fFrbp2Belum ada peringkat
- Rencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi PerubahanDokumen71 halamanRencana Aksi Mitigasi Dan Adaptasi PerubahanharyantoBelum ada peringkat
- Analisis Dan Pemetaan Daerah Rawan Banjir Untuk Menentukam Titik Kumpul Dan Rute Evakuasi Bencana Di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten TakalarDokumen97 halamanAnalisis Dan Pemetaan Daerah Rawan Banjir Untuk Menentukam Titik Kumpul Dan Rute Evakuasi Bencana Di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalargalang rimbawanBelum ada peringkat
- RIP Rembang Exum A3 (Maret 2017) PDFDokumen69 halamanRIP Rembang Exum A3 (Maret 2017) PDFsigit l.prabowoBelum ada peringkat
- Laporan InterimDokumen147 halamanLaporan InterimRona Aria NugrahawanBelum ada peringkat
- Laporan RSKP PrafiDokumen276 halamanLaporan RSKP PrafidoglasBelum ada peringkat
- Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Environmental EngineeringDokumen64 halamanDiajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Environmental EngineeringTiara NoviriBelum ada peringkat
- Dokumen RP2KPKPK Kab. Bangka Selatan - FullDokumen350 halamanDokumen RP2KPKPK Kab. Bangka Selatan - FullReza AlkautsaryBelum ada peringkat
- Laporan Akhir LikuefaksiDokumen42 halamanLaporan Akhir LikuefaksiArif KomaraBelum ada peringkat
- Bab 0 Lapan RDTR Ketapang 2018 FixDokumen7 halamanBab 0 Lapan RDTR Ketapang 2018 FixMuh Ardiasta KadirBelum ada peringkat
- Laporan AntaraDokumen192 halamanLaporan Antarafarasyifa100% (3)
- Laporan Akhir - Draft 4 AKHIRDokumen26 halamanLaporan Akhir - Draft 4 AKHIRLukmanul HakimBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Cabang Karanganyar Dan KarangawenDokumen67 halamanLaporan Akhir Cabang Karanganyar Dan KarangawendrikaBelum ada peringkat
- Laporan Karst Lengkap1 PDFDokumen127 halamanLaporan Karst Lengkap1 PDFBocah_eLLekBelum ada peringkat
- Review Design DED Pembangun Jaringan Irigasi WungkoloDokumen109 halamanReview Design DED Pembangun Jaringan Irigasi WungkoloIkhsan IkhsanBelum ada peringkat
- Pengukuran Penampang Melintang Dan Survei Untuk OP SungaiDokumen61 halamanPengukuran Penampang Melintang Dan Survei Untuk OP SungaiTia AdestyBelum ada peringkat
- Laporan Akhir NgotokDokumen218 halamanLaporan Akhir NgotokAgung R Ramadhani100% (1)
- RPL Danau Rawa PeningDokumen107 halamanRPL Danau Rawa PeningDhestiana Sulistyaningsih67% (3)
- Laporan PendahuluanDokumen38 halamanLaporan PendahuluanrifaiBelum ada peringkat
- Daftar Isi 2Dokumen10 halamanDaftar Isi 2Hilma QonianaBelum ada peringkat
- 01 Laporan Survey Bathimetry Sungai SentiongDokumen37 halaman01 Laporan Survey Bathimetry Sungai SentiongNayziLa DocgirlsBelum ada peringkat
- Laporan Bulan Ke-Vi - Profil Kegiatan Dan Kesiapan RCDokumen118 halamanLaporan Bulan Ke-Vi - Profil Kegiatan Dan Kesiapan RCUllye Grace AriestaBelum ada peringkat
- Inventarisasi Daya Dukung Daya TampungDokumen75 halamanInventarisasi Daya Dukung Daya Tampunghermawan100% (1)
- Laporan - Survei - BatimetriDokumen223 halamanLaporan - Survei - BatimetriRudiBelum ada peringkat
- Buku AnalisaDokumen245 halamanBuku AnalisaLewi Meichal100% (1)
- Laporan Akhir - Blok ViiiDokumen153 halamanLaporan Akhir - Blok Viiianissa100% (2)
- Laporan PendahuluanDokumen81 halamanLaporan PendahuluanRona Aria Nugrahawan100% (1)
- Laporan Akhir Peta Kawasan Banjir 2021Dokumen159 halamanLaporan Akhir Peta Kawasan Banjir 2021opikBelum ada peringkat
- ANDAL RPL RKL Kakap NatunaDokumen157 halamanANDAL RPL RKL Kakap NatunaBudi PrasetyoBelum ada peringkat
- Tatralok Kabupaten GresikDokumen327 halamanTatralok Kabupaten Gresikpras huda100% (9)
- Daftar Isi Lap. AntaraDokumen4 halamanDaftar Isi Lap. Antaratim08alitBelum ada peringkat
- Studi Potensi Logam Tanah Jarang Di Kalimantan Timur 2014 EKOBANGDokumen145 halamanStudi Potensi Logam Tanah Jarang Di Kalimantan Timur 2014 EKOBANGKhoirul AnamBelum ada peringkat
- Pelabuhan Torik FINALDokumen55 halamanPelabuhan Torik FINALHirasawa YuiBelum ada peringkat
- Laporan Kerja Praktek DLHDokumen38 halamanLaporan Kerja Praktek DLHmelanieBelum ada peringkat
- Kajian Pengembangan Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Kapuas HuluDokumen87 halamanKajian Pengembangan Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Kapuas HuluWanxND'RastafaraBelum ada peringkat
- Kelompok 11 (Review RZWP3K Dan RTRWP Sumatera Utara)Dokumen26 halamanKelompok 11 (Review RZWP3K Dan RTRWP Sumatera Utara)Cindie Suparyati MuarsarsarBelum ada peringkat
- Skrip SiDokumen78 halamanSkrip SiYolanda Octa TiurmaBelum ada peringkat
- LAPORAN KKN Raja4Dokumen171 halamanLAPORAN KKN Raja4Rico PanjaitanBelum ada peringkat
- Buku Sda 2019Dokumen160 halamanBuku Sda 2019Yayan FernandaBelum ada peringkat
- TugasDokumen309 halamanTugasZizil Luph PapiBelum ada peringkat
- Perencanaan Sabo Dam Di Sungai Sapta KubDokumen155 halamanPerencanaan Sabo Dam Di Sungai Sapta KubWahyubiBelum ada peringkat
- Laporan Perencanaan Desa Punggur KapuasDokumen76 halamanLaporan Perencanaan Desa Punggur KapuasRIZKY ANGGORO PUTRABelum ada peringkat
- RPLP 2019 Desa PurbahayuDokumen125 halamanRPLP 2019 Desa PurbahayuSIM TasikmalayaBelum ada peringkat
- Identifikasi Kondisi Fisik Dan Lingkungan Permukiman Pesisir RW 05 Kelurahan TalloDokumen38 halamanIdentifikasi Kondisi Fisik Dan Lingkungan Permukiman Pesisir RW 05 Kelurahan TallonasriBelum ada peringkat
- LAPORAN Exsum 12012016Dokumen47 halamanLAPORAN Exsum 12012016Dadang destari PutraBelum ada peringkat
- Lap Eksplorasi ARG 2015Dokumen46 halamanLap Eksplorasi ARG 2015naila2020Belum ada peringkat
- UKL-UPL Reservoir 1000 M3 Lambaro PDFDokumen48 halamanUKL-UPL Reservoir 1000 M3 Lambaro PDFHavidBelum ada peringkat
- LAPORAN Pendahuluan FS Pembangunan Drag BikeDokumen55 halamanLAPORAN Pendahuluan FS Pembangunan Drag Bikezainimusthofa80% (5)
- Buku II Buku Data SLH 20131 PDFDokumen98 halamanBuku II Buku Data SLH 20131 PDFDiniersetianiBelum ada peringkat
- Kemang Manis (Kelas A Indralaya)Dokumen43 halamanKemang Manis (Kelas A Indralaya)Citra TricesyaniaBelum ada peringkat
- Laporan Kairatu 2015 - 7dayDokumen70 halamanLaporan Kairatu 2015 - 7dayghanyBelum ada peringkat
- Executive Summary Batang F4 PDFDokumen98 halamanExecutive Summary Batang F4 PDFDede HermawanBelum ada peringkat
- Kajian Pengembangan Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Kapuas HuluDokumen85 halamanKajian Pengembangan Angkutan Sungai Dan Danau Di Kabupaten Kapuas HuluAnang Widhi Nirwansyah50% (2)
- Laporan Hidrologi NgotokDokumen72 halamanLaporan Hidrologi NgotokAgung R Ramadhani100% (1)
- Kata PengantarDokumen52 halamanKata PengantarNasrun SibelaBelum ada peringkat
- Laporan Magang Pemetaan MangroveDokumen52 halamanLaporan Magang Pemetaan MangroveHangga PradanaBelum ada peringkat
- Tugas Perencanaan & Permodelan TransportasiDokumen46 halamanTugas Perencanaan & Permodelan Transportasidecky94Belum ada peringkat
- Everyday IndonesianDari EverandEveryday IndonesianPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (2)