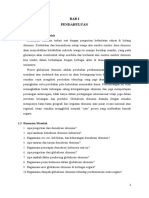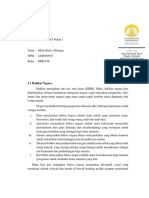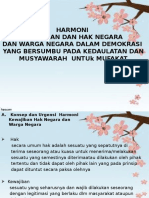Document
Document
Diunggah oleh
wietboyz0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
14 tayangan5 halamanJudul Asli
Document (1)
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
14 tayangan5 halamanDocument
Document
Diunggah oleh
wietboyzHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
Dengan mencontoh negara-negara tetangga yang
mendahulukan kepentingan pembangunan ekonomi kerakyatan
dari tingkat terbawah seperti Jepang, Korea, China, Singapura,
dan Malaysia, Indonesia sudah sepatutnya melakukan hal yang
sama sejak semula.
Namun, kenyataannya tidak demikian. Sistem ekonomi
Indonesia sejak kemerdekaan, yang sudah 72 tahun umurnya,
praktis sama saja dengan kita selama sekian abad berada di
bawah penjajahan asing. Sistem ekonomi yang berkembang
sampai saat ini masih bersifat liberal-kapitalistik-pasar bebas,
sekaligus dualistik.
Padahal, UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”
(Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai
oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan
alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal
33 Ayat 3); dan ”Perekonomian nasional diselenggarakan
berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip
kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
(Pasal 33 Ayat 4).
Lalu disambung lagi dengan Pasal 34 Ayat 1: ”Fakir miskin dan
anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara”; Ayat 2:
”Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”; dan Ayat 3:
”Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak”.
Ekonomi dualistik
Semua itu hanya angin surga yang diimpikan para penggagas
dan pendiri republik ini. Sementara yang berjalan dan
dipraktikkan selama ini justru sebaliknya. Selain karena terlalu
lama dijajah, juga karena sistem sosial-budaya yang dimiliki
oleh bangsa ini yang dominan adalah feodalistik, hierarkis-
vertikal, sentripetal, etatik, nepotik, dan bahkan despotik.
Alhasil, itulah yang berlanjut sampai hari ini, yaitu sistem
ekonomi yang dualistik. Terbentuklah jurang menganga antara
95 persen penduduk yang merupakan rakyat asli, pribumi—
yang sejak semula hidup dalam kemiskinan, kebodohan, dan
terbelakang—dan penyertaan sekitar 5 persen dari ekonomi
nasional yang ”bergedumpuk” di sektor nonformal. Sementara
5 persen lainnya—umumnya nonpribumi—menguasai 95 persen
kekayaan ekonomi negeri ini: dari hulu sampai ke muara, di
darat, laut, dan bahkan udara di negara kepulauan terbesar di
dunia ini.
Antara harapan seperti dituangkan dalam Pasal 33 dan 34 UUD
1945 dan kenyataan yang dihadapi bagaikan siang dengan
malam. Orang Jepang, Korea, China, Singapura, dan Malaysia
bangga dengan negeri dan tanah airnya karena mereka sendiri
yang punya dan menguasai bumi, air, dan segala isinya yang
dinikmati oleh rakyatnya sendiri. Kalaupun ada orang luar yang
ikut serta, mereka adalah tamu dan tunduk kepada ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Di kita, Indonesia, sebaliknya. Kita
malah bagaikan tamu atau orang asing di rumah sendiri.
Tanah, air, dan bahkan udara yang kita jawat secara turun-
temurun dari nenek moyang kita hanya namanya kita yang
punya, tetapi praktis seluruhnya mereka yang kuasai.
Padahal, alangkah luas, kaya, dan indah negara ini sehingga
menempati empat terbesar di dunia. Akan tetapi, kita hanya
menguasai secara de jure di atas kertas, de facto dikuasai
kapitalis mancanegara dan konglomerat nonpribumi yang
sudah mencengkamkan kukunya sejak dulu. Lihatlah, hampir
semua warga Indonesia terkaya ukuran dunia adalah mereka,
diselingi satu-dua elite pribumi yang hidup sengaja mendekat
dan/atau bagian dari api unggun kekuasaan itu.
Untuk mengembangkan usaha makro di bidang perkebunan,
kehutanan, galian alam, misalnya, pemerintah bahkan
mengambil alih tanah ulayat milik rakyat yang dipusakai turun-
temurun. Tanah itu lalu diserahkan berupa hak guna usaha,
yang bisa diperpanjang setelah 30 tahun, ke kapitalis
mancanegara dan konglomerat.
Sekali tanah ulayat menjadi tanah negara, kendati sudah habis
masa pakai ataupun tak lagi dipakai, tak juga bisa
dikembalikan ke pemiliknya: rakyat! Hal itu hanya karena
penafsiran Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 yang sangat negara-
sentris, harfiah, bahwa ”bumi, air, dan kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
Kata ”dikuasai” secara harfiah tentu saja tidak sama dengan
”dimiliki”. Pemiliknya tetap adalah rakyat yang mengulayati
tanah itu secara turun-temurun.
Jelas sekali bahwa negara sama sekali tak berpihak kepada
rakyat, tetapi kepada para kapitalis multinasional dan
konglomerat nonpribumi yang sekarang menguasai bagian
terbesar dari tanah rakyat itu. Sekarang, yang namanya tanah
ulayat di mana-mana habis. Tandas sudah!
Alangkah tragis, mengingat semua ini terjadi justru di alam
kemerdekaan. Ukuran keberhasilan pembangunan bagi
penguasa negara jadinya bukan ”siapa” dan seberapa besar
hasilnya dinikmati oleh rakyat, melainkan ”berapa” dari target
yang diinginkan tercapai dalam angka-angka statistik.
Pencapaian target itu, dalam kenyataannya, nyaris diborong
habis oleh para kapitalis yang sesungguhnya menggerakkan
roda ekonomi nasional.
Penduduk asli-pribumi? Kelompok ini hidupnya masih seperti
itu juga dari waktu ke waktu, rezim berganti rezim. Sementara
rakyat pribumi rata-rata memiliki tanah kurang dari setengah
hektar per keluarga, jutaan hektar tanah ulayat diserahkan
oleh negara kepada para pengusaha kapitalis multinasional
dan konglomerat.
Kerja sama triumvirat kapitalis multinasional dan konglomerat
nonpribumi di bawah lindungan elite penguasa negara yang
pribumi inilah yang menggelindingkan ekonomi Indonesia
selama ini. Sementara rakyat pribumi yang merupakan ahli
waris sah republik ini tetap saja hidup melarat dalam
kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
Walau janji-janji dilontarkan oleh penguasa Reformasi yang
sudah jilid dua pula sekarang ini, masih ada saja yang tertulis
di atas kertas yang tak segera terlihat ada implementasinya,
seperti program kredit usaha rakyat dan entah apa lagi
namanya itu. Jangan-jangan itu pun hanya janji gombal karena
sebentar lagi pemilu akan datang pula.
Akibat salah urus
Bagaimana ke depan? Akan seperti ini juga tanpa perubahan
struktural yang berarti, yang sifatnya harus fundamental,
mendasar; atau seperti selama ini juga, sekadar tambal sulam
di permukaan, yang esensinya itu ke itu juga.
Kuncinya ada pada diri kita sendiri, terutama pada kelompok
elite pribumi yang secara politis mengendalikan negeri dan
negara ini. Seperti kita lihat, selama ini mereka (para elite
pribumi) sekadar menumpang di biduk ke hilir. Mereka lebih
suka menerima daripada memberi, lebih suka dilayani daripada
melayani sesuai tugas mereka sebagai abdi negara.
Tanpa bersusah-susah mereka menerima upeti berbagai
macam, yang jumlahnya bisa tak termakan di akal sehat kita.
Mereka datang dari semua lapisan birokrasi: dari eksekutif,
legislatif, yudikatif, polisi maupun militer; dari orang pertama
di tingkat atas sampai ke tingkat bawah; di pusat maupun di
daerah.
Dengan kebebasan pers yang kita nikmati sekarang, semua
borok ini jadi terbuka. Tahulah kita betapa sakit negara ini
sehingga dunia menjulukinya sebagai salah satu dari negara
terkorup di dunia.
Kita sesungguhnya sedang berada di tepi jurang kehancuran
sebagai negara akibat salah urus dan akibat dari sistem sosial
dan budaya politik yang kita anut selama ini, yang berbeda
antara yang diucapkan dan yang dilakukan. Pilihannya tinggal
satu: kembali ke pangkal jalan dengan mempraktikkan UUD
1945, khususnya Pasal 33 dan 34, secara jujur dan konsekuen;
atau kaput, habis kita!
Anda mungkin juga menyukai
- Booklet Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945Dokumen28 halamanBooklet Gerakan Nasional Pasal 33 UUD 1945Partai Rakyat Demokratik (PRD)100% (2)
- Tugas 1 ADPU4337Dokumen4 halamanTugas 1 ADPU4337PutriBelum ada peringkat
- Negara Kaya Namun Miskin Negarawan (Beni Pramula)Dokumen5 halamanNegara Kaya Namun Miskin Negarawan (Beni Pramula)salmanBelum ada peringkat
- Tugas Pendidikan Kewarganegaraan: Harmoni Dan Problematika Kewajiban Dan Hak Negara Dan WarganegaraanDokumen17 halamanTugas Pendidikan Kewarganegaraan: Harmoni Dan Problematika Kewajiban Dan Hak Negara Dan WarganegaraanLa Ode MuliadiBelum ada peringkat
- Resume4 - Meliza S-WPS OfficeDokumen6 halamanResume4 - Meliza S-WPS OfficeGinaa BudiartiBelum ada peringkat
- Resume PKN BAB 5 - Muhamad As'ad Almu'tashimDokumen7 halamanResume PKN BAB 5 - Muhamad As'ad Almu'tashimMuhamad Asad AlmutashimBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan: 1.1 Latar Belakang MasalahDokumen28 halamanBab I Pendahuluan: 1.1 Latar Belakang MasalahEka PermanaBelum ada peringkat
- Tugas 1 Sistem Ekonomi IndonesiaDokumen1 halamanTugas 1 Sistem Ekonomi IndonesiaMuhamad Dazka PratamaBelum ada peringkat
- Tugas Kewarganegaraan Muhammad Rabbil Gazali 23342036Dokumen15 halamanTugas Kewarganegaraan Muhammad Rabbil Gazali 23342036yufri yantiBelum ada peringkat
- Resume Harmonasasi Kewajiban Dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi - Mariyah Putri 22042247Dokumen4 halamanResume Harmonasasi Kewajiban Dan Hak Negara Dengan Warga Negara Dalam Demokrasi - Mariyah Putri 22042247Mariyah PutriRBelum ada peringkat
- Adpu4337 Tugas1Dokumen3 halamanAdpu4337 Tugas1Roqez MarquesBelum ada peringkat
- Hijau Imut Sederhana Laporan Kelompok PresentasiDokumen14 halamanHijau Imut Sederhana Laporan Kelompok PresentasiAgnes SaputriBelum ada peringkat
- Sifat NegaraDokumen4 halamanSifat NegaraYong JinBelum ada peringkat
- Sistem Ekonomi Yang Cocok Diterapkan Di Indonesia Adalah Sistem Ekonomi CampuranDokumen5 halamanSistem Ekonomi Yang Cocok Diterapkan Di Indonesia Adalah Sistem Ekonomi CampuranMuhammad YusufBelum ada peringkat
- Demokrasi Di Bidang EkonomiDokumen8 halamanDemokrasi Di Bidang EkonomiNicolas StevenBelum ada peringkat
- Analisis Demokrasi Permuafakatan PENULISANDokumen33 halamanAnalisis Demokrasi Permuafakatan PENULISANHafidz DerusBelum ada peringkat
- Makalah Nkri Harga Mati1Dokumen3 halamanMakalah Nkri Harga Mati1M Lica100% (1)
- Dampak Ekonomi Dan Politik Neolib Terhadap IndonesiaDokumen11 halamanDampak Ekonomi Dan Politik Neolib Terhadap IndonesiaArif SolehBelum ada peringkat
- Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga NegaraDokumen18 halamanHarmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga NegaraDhian NovitaBelum ada peringkat
- Makna Pasal 33 UUD 45Dokumen2 halamanMakna Pasal 33 UUD 45deka100% (1)
- Hubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945Dokumen60 halamanHubungan Antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945addiwisudawanBelum ada peringkat
- NKRI IndonesiaDokumen15 halamanNKRI IndonesiaSurya RightofsayBelum ada peringkat
- Sistem Ekonomi Indonesia Dan SingapuraDokumen6 halamanSistem Ekonomi Indonesia Dan SingapuraSilvi DianaBelum ada peringkat
- Trigger Question #1Dokumen5 halamanTrigger Question #1Silvy PermatasariBelum ada peringkat
- TUGAS PKN Minggu 7-8 MIFTAHUL QAIRA 18133057Dokumen6 halamanTUGAS PKN Minggu 7-8 MIFTAHUL QAIRA 18133057DesyBelum ada peringkat
- Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Pertemuan 5 6Dokumen23 halamanHarmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Pertemuan 5 6aditya prasetyaBelum ada peringkat
- Esensi Dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa Dan KarakterDokumen54 halamanEsensi Dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa Dan KarakterYusuf Abdur RazaqBelum ada peringkat
- Tugas KWN HudaDokumen17 halamanTugas KWN HudaOkta VasandaniBelum ada peringkat
- Mohammad Gerry Oxa - 051711133149Dokumen6 halamanMohammad Gerry Oxa - 051711133149Gerry OxaBelum ada peringkat
- Hak & Kewajiban Warga NegaraDokumen20 halamanHak & Kewajiban Warga NegaraMela WidiawatiBelum ada peringkat
- Konsep Kebijakan PublikDokumen7 halamanKonsep Kebijakan PublikGina Sonia Fy EffendiBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Agraria Natasya Salsabila Khairun 04020200354Dokumen8 halamanMakalah Hukum Agraria Natasya Salsabila Khairun 04020200354PuputriBelum ada peringkat
- Dinamika Hubungan InternasionalDokumen8 halamanDinamika Hubungan Internasionalindah widianiBelum ada peringkat
- JawabDokumen10 halamanJawabAstriBelum ada peringkat
- PancasilaDokumen5 halamanPancasilaNathanBelum ada peringkat
- DINAMIKA Dan TANTANGAN Harmoni Hak Dan Kewajiban Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia - JamilaDokumen4 halamanDINAMIKA Dan TANTANGAN Harmoni Hak Dan Kewajiban Kehidupan Berbangsa-Negara Indonesia - JamilaMhilaaBelum ada peringkat
- PPKN - Kelompok - 3-Xi - Ips - 3-Kedaulatan - Ekonomi IndonesiaDokumen13 halamanPPKN - Kelompok - 3-Xi - Ips - 3-Kedaulatan - Ekonomi IndonesiaAni Sri WahyuniBelum ada peringkat
- PENDEKATAN TEORi KekuasaanDokumen7 halamanPENDEKATAN TEORi KekuasaanZafia AzzahraBelum ada peringkat
- Tugas LTM MPKT Pekan 3 - Milan SilitongaDokumen5 halamanTugas LTM MPKT Pekan 3 - Milan SilitongaGhana JewelleryBelum ada peringkat
- Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk MufakatDokumen27 halamanHarmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara Dalam Demokrasi Yang Bersumbu Pada Kedaulatan Rakyat Dan Musyawarah Untuk MufakatRachmawatiBelum ada peringkat
- Masyarakat Dan Hukum Internasiona1Dokumen3 halamanMasyarakat Dan Hukum Internasiona1Khofifa NiarniBelum ada peringkat
- 2TB04.Bintang Nalendra Dinata.T2Dokumen47 halaman2TB04.Bintang Nalendra Dinata.T2BintangBelum ada peringkat
- Hak Dan Kewajiban NegaraDokumen2 halamanHak Dan Kewajiban NegaraDeva Nupita SariBelum ada peringkat
- Harmoni Hak Dan Kewajiban Dan Warga Negara Dalam DemokrasiDokumen13 halamanHarmoni Hak Dan Kewajiban Dan Warga Negara Dalam DemokrasiAsri Samrotul HilmiahBelum ada peringkat
- Kewarganegaraan Bab 5Dokumen20 halamanKewarganegaraan Bab 5Silvana RorimpandeyBelum ada peringkat
- Berhala Globalisme Dan Kapitalisme GlobalDokumen4 halamanBerhala Globalisme Dan Kapitalisme Globaladi sulhardiBelum ada peringkat
- Pamflet Solidaritas: Agenda Rakyat Menegakkan KeadilanDokumen38 halamanPamflet Solidaritas: Agenda Rakyat Menegakkan KeadilanInstitut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)Belum ada peringkat
- Bagaimana Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan WargaDokumen26 halamanBagaimana Harmoni Kewajiban Dan Hak Negara Dan Wargawardalina tri putriBelum ada peringkat
- Resume PT 9&10 Fira Ayuni SalsabillaDokumen12 halamanResume PT 9&10 Fira Ayuni SalsabillaIntan Mesriany PutriBelum ada peringkat
- HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA Pertemuan 5 & 6Dokumen23 halamanHARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA DAN WARGA NEGARA Pertemuan 5 & 6Dini Ayu ARCHBelum ada peringkat
- Kewarganegaraan 5Dokumen19 halamanKewarganegaraan 5Bintang Adha PerdanaBelum ada peringkat
- Diskusi 8 HAMDokumen3 halamanDiskusi 8 HAMMuhammad PramadaniBelum ada peringkat
- Lembaga Alternatif PijamanDokumen50 halamanLembaga Alternatif Pijamankapri yaniBelum ada peringkat
- Sejarah Pemungutan PajakDokumen33 halamanSejarah Pemungutan PajakSamara ApriliaBelum ada peringkat
- Konstitusionalisme Hak Menguasai Atas TaDokumen30 halamanKonstitusionalisme Hak Menguasai Atas TaSalfius SekoBelum ada peringkat
- PENGARUH KEMAJUAN IPTEK TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KLPK 5Dokumen13 halamanPENGARUH KEMAJUAN IPTEK TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA KLPK 5zahratulkhairatBelum ada peringkat
- 5a. Hubungan Negara Dan Warga Negara Nop 2017Dokumen19 halaman5a. Hubungan Negara Dan Warga Negara Nop 2017Michael GionandaBelum ada peringkat
- HARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA....... OkDokumen23 halamanHARMONI KEWAJIBAN DAN HAK NEGARA....... OkSarah mclBelum ada peringkat
- PancasilaDokumen6 halamanPancasilachastellia50% (2)