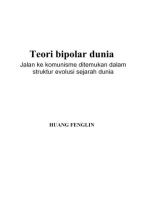Prosiding ICONIC2021 Terbit
Prosiding ICONIC2021 Terbit
Diunggah oleh
Gema AripraharaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Prosiding ICONIC2021 Terbit
Prosiding ICONIC2021 Terbit
Diunggah oleh
Gema AripraharaHak Cipta:
Format Tersedia
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.
net/publication/358467518
RESILIENSI BUDAYA DAN HUBUNGAN PATRON-KLIEN: KEBIJAKAN SIMA
MAKUDUR OLEH RAJA AIRLANGGA
Conference Paper · December 2021
CITATIONS READS
0 331
1 author:
Muhamad Alnoza
Universitas Gadjah Mada
35 PUBLICATIONS 17 CITATIONS
SEE PROFILE
All content following this page was uploaded by Muhamad Alnoza on 09 February 2022.
The user has requested enhancement of the downloaded file.
RESILIENSI BUDAYA DAN HUBUNGAN PATRON-KLIEN: KEBIJAKAN SIMA
MAKUDUR OLEH RAJA AIRLANGGA
Muhamad Alnoza
Mahasiswa Progam Master Antropologi, Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosiohumaniora, No.1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta
Abstrak:
Tulisan ini secara umum membahas mengenai upaya resiliensi kebudayaan yang dilakukan oleh
Airlangga pasca peristiwa pralaya atau perang saudara. Kajian ini mengangkat permasalahan kebijakan
sima makudur yang berlaku pada masa itu melalui paradigma ekologi kebudayaan, terutama dalam
lingkup resiliensi budaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
perubahan struktur sosial di masa Raja Airlangga telah mempengaruhi pembagian kuasa atas lahan
garap dengan media hubungan patron klien. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah
dalam penelitian ini menerapkan metode kualitatif, yang terdiri atas pengumpulan data, analisis, dan
interpretasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa Airlangga di masa itu telah
menggunakan hubungan patron-kliennya dalam memulihkan keadaan pasca pralaya.
Kata Kunci: Airlangga, hubungan patron-klien, resiliensi budaya, sima makudur.
PENDAHULUAN
Pemerintahan Airlangga secara umum telah menjadi bahan perhatian para peneliti terdahulu.
Ninie Susanti (2010) dalam disertasinya misalnya, menetapkan Airlangga sebagai yang membawa
pembaruan bagi sistem pemerintahan monarki di Jawa. Pernyataan tersebut didapatkan Susanti dengan
membandingkan gaya pemerintahan raja-raja sebelum, sezaman, dan sesudah Airlangga. Dari kajian
itu Susanti menemukan bahwa Airlangga menempatkan dirinya sebagai raja purohita dan memiliki
misi vijigishu. Airlangga dianggap sebagai raja perwujudan dewa (dewaraja) yang turun ke dunia
untuk membasmi kejahatan dan menjadi penguasa dunia. Seorang sejarawan sekaligus sosiolog,
B.J.O. Schrieke (2016) berpendapat bahwa kemunculan Airlangga di panggung sejarah Hindu-Buddha
di Jawa sendiri, diawali dengan adanya peristiwa pralaya atau “kiamat” dalam kepercayaan Hindu
Jawa. Peristiwa tersebut di masa awal kekuasaan Airlangga adalah adanya konflik perebutan wilayah
penguasa-penguasa vazal di Jawa Timur. Airlangga dalam hal ini dianggap sebagai cakravartin atau
juru selamat rakyat Jawa kala itu, sehingga ia mentadbirkan diri sebagai Wisnu.
Di samping peristiwa sekitar pemerintahan Raja Airlangga, keunikan pemerintahan Airlangga
terletak pada banyaknya ia memberikan anugerah sima makudur. Adapun dari 15 prasasti Airlangga yang
berangka tahun, 9 di antaranya yang menyebut soal kebijakan semacam ini. Sima makudur dalam hal
ini berakar dari konsep sima bagi masyarakat Jawa Kuno. Menurut Boechari (2012) sima adalah bentuk
pemberian hak yang diberikan oleh raja kepada suatu desa atau wilayah tertentu agar mereka terbebas
dari pembebanan pajak. Singkat kata penetapan sima berarti penatapan suatu daerah menjadi suatu
daerah otonom. Sima makudur di lain pihak adalah salah satu bentuk kebijakan sima yang dikeluarkan
oleh raja, yang mana raja memberikan hak tersebut sebagai bentuk balas budi kepada sang penerima
kebijakan. Bahwa setiap tanah garapan yang diberi anugerah ini dibebaskan dari pajak, dan biasanya
disebabkan akan adanya tindakan balas budi dari sang raja terhadap seorang pendeta. Perlu diperjelas
bahwa pada dasarnya sima makudur bukan satu-satunya jenis sima yang dimuati kepentingan balas
budi, mengingat sima makudur hanya diperuntukan bagi golongan agamawan yang berjasa. Kebijakan
2 ICONIC 2021 | Prosiding
balas budi tersebut bisa juga diberikan kepada golongan pimpinan desa (sima karaman) atau golongan
ksatria (sima kapatihan) (Darmosoetopo, 2003; Haryono, 1999). Namun atas pertimbangan bahwa
konteks dari eksistensi dari Airlangga adalah raja purohita, maka tulisan ini menggunakan istilah sima
makudur dalam menjelaskan kebijakan sima balas budi.
. Berkenaan dengan fenomena sima makudur dalam pemerintahan Airlangga, tulisan ini melihat
fenomena tersebut dari perspektif dari ekologi budaya. Perspektif ini menekankan bahwa lingkungan
mempengaruhi sebagian unsur dari kebudayaan. Menurut P.E. Little (2007), paradigma ekologi budaya
berfokus kepada hubungan antara unsur alam, sosial, dan lingkungan sosial. Konsep-konsep yang
diaplikasikan pada paradigma ini, yang terdiri dari wilayah konflik, arus energi, dan perselisihan akan
nilai, dilihat sebagai satu kesatuan yang relasional. Manusia dalam hal ini dipandang memanfaatkan
interaksinya terhadap lingkungan untuk melestarikan dan memperbaharui eksistensinya. Teori ini yang
kemudian dikenal sebagai resiliensi budaya (Holling, 1973).
Berkaitan dengan sudut pandang yang dipaparkan di atas, dapat dihipotesiskan bahwa fenomena
sima makudur sebagai upaya pemulihan stabilitas pembagian hak penggunaan lahan setelah sebelumnya
dikacaukan oleh perang perebutan kekuasaan (pralaya). Adapun kaitannya dengan hal ini, hubungan
patron klien antara raja dan rakyatnya menjadi aspek yang tak terlepaskan dari fenomena tersebut.
Mengenai definisi hubungan patron-klien, James C. Scott dalam penelitiannya mengenai hubungan
patron-klien di Asia Tenggara mendefinisikan patron-klien dalam uraian sebagai berikut:
“suatu hubungan antar dua pihak yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, di
mana pihak yang lebih tinggi kedudukan sosial-ekonominya (patron), menggunakan pengaruh
dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau
kedua-duanya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya (klien), yang pada gilirannya
membalas pemberian tersebut dengan memberikan dukungan umum dan bantuan, termasuk
jasa-jasa pribadi, kepada patron” (1972, p. 92)
Menurut Heddy Shri Ahimsa-Putra (2018), hubungan patron-klien memiliki ciri-ciri yang
membedakannya dengan bentuk-bentuk hubungan lain yang sekilas mirip dengan hubungan ini, seperti
koersi atau wewenang politis, yang di antaranya 1) adanya unsur ketidaksetaraan, 2) bersifat yang face
to face, 3) bersifat fleksibel dan memiliki cakupan negosiasi yang luas, dan 4) adanya kecenderungan
hubungan persahabatan instrumentalis. Ahimsa-Putra menjelaskan bahwa dalam hubungan patron-
klien terdapat tiga unsur yang membuat hubungan tersebut tetap langgeng. Unsur-unsur tersebut di
antaranya, a) adanya sesuatu objek yang bernilai bagi suatu pihak, b) adanya hubungan timbal balik
yang berkelanjutan, dan c) adanya kesempatan bagi kedua belah pihak (terutama klien) untuk melakukan
tawar menawar.
Kajian ini pada akhirnya berusaha untuk menjawab permasalahan yang berkenaan dengan
menjelaskan kebijakan sima makudur yang berlaku pada masa itu melalui paradigma ekologi
kebudayaan, terutama dalam lingkup resiliensi budaya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana perubahan struktur sosial di masa Raja Airlangga telah mempengaruhi
pembagian kuasa atas lahan garap dengan media hubungan patron klien.
METODE PENELITIAN
Untuk menjawab masalah dalam penelitian ini, dilakukan tahapan metode penelitian kualitatif yang
terdiri dari pengumpulan data, analisis dan interpretasi (Somantri, 2005). Pengumpulan data dalam
ICONIC 2021 | Prosiding 3
kajian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan terhadap referensi yang memuat hasil pembacaan
prasasti-prasasti masa Airlangga yang berkenaan dengan kebijakan sima makudur. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, dengan mengurai hak-hak yang didapatkan rakyat
dalam kebijakan sima makudur. Interpretasi dilakukan dengan menafsirkan hak-hak yang didapatkan
rakyat dengan memposisikan hak tersebut sebagai pertukaran yang dilakukan oleh raja sebagai patron
terhadap rakyat sebagai klien.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Prasasti berisi Kebijakan Sima Makudur masa Airlangga (1010-1043 M)
Data dari masa paling awal yang menyebutkan penetapan kebijakan sima makudur oleh
Airlangga adalah Prasasti Cane (943 Ś/ 1021 M). Prasasti tersebut dikeluarkan oleh Raja Airlangga
dengan memberikan titah kepada Rakai Mahamantri Sanggramawijaya untuk kemudian dilaksanakan
oleh Rakai Padan Pu Dwija dan Rakai Jasun Mapapan. Adapun perintah yang dimaksud adalah
penetapan desa Cane sebagai sima, karena warga desa tersebut telah membantu sang raja selama tapa
persiapannya menjadi raja. Oleh karena itu kebijakan yang dikeluarkan dalam Prasasti Cane bisa
disebut sebagai prasasti sima karaman. Perintah balas budi Airlangga terhadap seluruh warga desa
muncul pula dalam Prasasti Baru yang berangka tahun 952 Ś atau 1030 M. Prasasti ini menetapkan desa
Baru sebagai sima karena warga desanya yang telah menyediakan pengungsian bagi Airlangga selama
perang (Poesponegoro & Notosusanto, 2010).
Kebijakan sima karaman juga muncul dalam Prasasti Munggut yang berangka tahun 944 Ś
atau 1022 M. Airlangga menetapkan bahwasannya desa Munggut menjadi sima. Kebijakan ini diberikan
karena pertolongan yang diberikan tokoh bernama Gamala ketika Airlangga lari kota Wwuatan Mas.
Peristiwa pelaraian Airlangga dari kota Wwuatan Mas agaknya begitu membekas bagi Airlangga,
terbukti dari dikeluarkannya lagi kebijakan balas budi yang kali ini berbentuk sima makudur pada
Prasasti Terep I. Prasasti yang berangka tahun 954 Ś atau 1032 M ini menetapkan agar pertapaan
di Terep dijadikan wilayah sima. Penetapan pertapaan tersebut sebagai sima berhubungan dengan
giatnya seorang agamawan bernama Rake Pangkaja Dyah Tumambong dalam mendoakan Airlangga
yang kalah perang di Wwuatan Mas. Dikisahkan bahwa sang agamawan begitu giat memohon kepada
Bhatari Durga (istri/sakti Dewa Siwa) agar selamat dalam peperangan. Di dalam doanya tersebut,
Dyah Tumambong bernazar apabila Airlangga dapat selamat dan memenangkan peperangan, maka ia
sendiri yang akan meminta anugrah sima kepada Airlangga. Perintah balas budi melalui penetapan sima
pasca peristiwa Wwuatan Mas bahkan hadir kembali pada masa akhir pemerintahan Airlangga, yaitu
pada Prasasti Pasar Legi (965 Ś/ 1043 M). Prasasti itu diperkirakan berisi anugrah sima terhadap Desa
Patakan, karena budi warga desa tersebut yang berkehendak agar sang raja mengungsi di desa mereka
ketika kalah di Wwuatan Mas (Susanti, 2010).
Kebijakan sima makudur semacam ini juga terdapat Prasasti Kakurugan I (945 Ś/ 1023 M).
Prasasti ini menyebutkan adanya seorang pendeta bernama Dyah Kaki Ngadulengen yang baktinya
terhadap raja teramat luar biasa. Namun uniknya tanah sima di sini sifatnya diberikan kepenguasaannya
pada satu pihak dan bukan ditetapkan. Artinya tanah sima yang dianugerahkan belum tentu merupakan
daerah asal dari Dyah Kaki Ngadulengen. Tokoh ini nampaknya juga begitu diistimewakan, karena
Airlangga turut pula memberikan hak-hak istimewa terhadap Dyah Kaki Ngadulengen. Adapun
hak istimewa yang dimaksud di sini beraneka ragam rupanya, seperti diperbolehkan menggunakan
tandu dengan tirai, diperbolehkan membangun pendopo, diperbolehkan membuat dipan bertingkat,
4 ICONIC 2021 | Prosiding
diperbolehkan memiliki budak berkulit hitam, dan lain sebagainya (Susanti, 2010).
Airlangga dalam beberapa kesempatan juga menganugerahkan tanah sima sebagai bagian
dari pemenuhan sumpahnya, yang umumnya kemudian dihadiahkan kepada beberapa pihak tertentu.
Prasasti Turunhyang A yang berangka tahun 958 Ś atau 1036 M misalnya, memuat soal penetapan tanah
sima di Desa Turunhyang. Penetapan desa tersebut sima dikarenakan Airlangga telah berhasil seluruh
musuh-musuhnya di berbagai penjuru, yang karenanya Airlangga kemudian digelari sebagai cakravartin
(Munandar et al., 2012). Kasus yang serupa juga ditemukan pada Prasasti Pucangan berbahasa Jawa
Kuno (963 Ś/ 1041 M). Prasasti ini menyebutkan adanya perintah Raja Airlangga untuk menetapkan
tiga desa sekaligus (terdiri dari Desa Brahem, Pucangan dan Cepuri) untuk ditetapkan sebagai daerah
sima. Alasan ditetapkannya ketiga desa ini kurang lebih serupa dengan yang disampaikan pada Prasasti
Turunhyang A, yaitu sebagai bentuk pemenuhan sumpah Airlangga yang akan menghadiahi rakyatnya
setelah seluruh musuhnya berhasil diberantas (Kern, 1913).
Prasasti yang cukup unik untuk dikaji lebih lanjut berkenaan dengan kebijakan balas budi
Airlangga adalah Prasasti Kamalagyan (959 Ś/ 1037 M). Prasasti ini secara umum berisi perintah
penetapan desa sima bagi Desa Kamalagyan, yang mana Airlangga memutuskan untuk membangun suatu
bendungan bernama Waringin Pitu di desa tersebut. Uniknya Airlangga menyebut bahwa pembangunan
waduk tersebut diperuntukan bagi kemaslahatan rakyatnya (warga desa setempat) dan bukan untuk
kepentingannya sendiri. Selain daripada bendungan dibuat pula saluran air yang digunakan untuk
memecah arus sungai. Penetapan Desa Kamalagyan sebagai daerah sima dilakukan tepat sehari setelah
para raja bawahan yang ditaklukan Airlangga menghaturkan hormat kepadanya (sowan) (Siswanto,
2018).
Penetapan daerah sima oleh Airlangga bukan serta merta terjadi tanpa konsekuensi lain.
Beberapa penerima anugrah sima dari Airlangga juga dimendapatkan beberapa hal tertentu. Salah
satu yang utama dari konsekuensi ditetapkannya suatu daerah sebagai sima adalah seluruh denda dari
sukhaduhka diserahkan kepada penduduk dari daerah sima itu. Sukhaduhka dalam hal ini adalah biaya
yang dikeluarkan oleh seseorang apabila melakukan tindak pidana. Sukhaduhka dalam hal penetapan
sima berhubungan dengan dana denda yang kemudian didapatkan oleh para penghuni desa sima tersebut
(Susanti, 2010).
Keuntungan yang didapatkan Raja Airlangga melalui Hubungan Patron-Klien dalam Kebijakan
Sima Makudur
Sebagai seorang raja yang bertakhta di suatu kerajaan masa Hindu-Buddha, Airlangga baik secara
mandiri diakui atau memang disahkan oleh rakyatnya, ialah seorang dewaraja atau raja yang bertakhta
di dunia. Dewaraja di sini berarti raja yang lahir di dunia adalah perwujudan dari dewa yang lahir
ke dunia untuk membawa kemaslahatan di dunia (Kulke, 1978; Mabbet, 1969). J.G. (de Casparis,
1985) mengatakan bahwa raja masa Jawa Kuno menempati posisi kewenangan tertinggi, mengingat
keabsahannya sebagai perwujudan dewa di dunia. Secara tradisional hingga di masa sekarang, perintah
raja atau pemimpin bagi masyarakat Jawa dapat disamakan sebagai perintah tuhan. Melanggar perintah
raja sama saja dengan menolak perintah dewa. Mengingat sifatnya yang mewujudkan dewa di dunia ini
lah, seorang raja pada dasarnya secara tidak eksplisit juga diharapkan memiliki sifat-sifat para dewa.
Mengikut pada pendapat Ninie Susanti (2010), Airlangga telah mendaku diri sebagai Dewa
Wisnu. Kehadirannya seakan-akan menjadi juru selamat bagi rakyat Jawa dari peristiwa pralaya.
ICONIC 2021 | Prosiding 5
Kaitan klaim ini dengan hubungan patron-klien dengan masyarakat Jawa masa itu, dapat ditelusuri dari
bagaimana klaim tersebut telah dimanfaatkan Airlangga dalam meraup keuntungan. Keuntungan yang
dimaksud di sini di antaranya:
1) Tanah-tanah garapan dapat terawasi secara lebih efisien, karena dikelola oleh para pendukung
raja sejak awal
Melalui kebijakan sima balas budi yang berazaskan hubungan patron-klien, pada dasarnya raja
Airlangga telah menyerahkan kewenangannya pada suatu daerah terhadap penghuni desa tertentu.
Dengan kata lain Airlangga sebenarnya telah memberikan hak otonomi kepada beberapa pihak
tertentu. Pemberian hak otonomi ini bukanlah pemberian “gratis” dari Airlangga, melainkan pada
hakikatnya Airlangga telah menyerahi para penerima anugrah sima ini beban untuk mengawasi
suatu daerah tertentu secara implisit. Pemberian anugrah ini pun dilakukan secara sistematis oleh
Airlangga, dimana dirinya hanya menyerahkan anugrah tersebut terhadap pihak-pihak yang dari
awal (ketika dirinya masih berjuang menuju takhta) mendukungnya. Oleh karena itu Airlangga
juga telah mendapatkan jaminan bahwa pemberian anugrah tersebut di masa depan tidak akan
berbalik padanya, karena orang-orang yang diberi hak tersebut memang setia terhadap dirinya.
2) Fasilitas-fasilitas publik dapat diurus secara otomatis oleh rakyat, tanpa membebani negara
sumber daya yang dimiliki pemerintahan.
Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemberian anugrah sima juga seringkali disertai dengan
kewajiban pemeliharaan suatu fasilitas, baik berupa bangunan suci atau fasilitas profan lain.
Dengan diserahkannya anugrah sima, otomatis pemeliharaan bangunan suci tidak lagi mebebankan
pemerintahan pusat yang diampu oleh Airlangga. Peran pemerintah pusat di sini hanya cukup
mendirikan fasilitas, sedangkan untuk kepengurusannya diserahkan kepada daerah sima terkait.
Tentu dengan demikian Airlangga tidak perlu bersusah payah untuk membangun citra bahwa
dirinya adalah “raja pembangun”.
3) Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya pertanian dan maritim didukung pula oleh
partisipasi dari rakyat
Penyerahan hak otonomi melalui kebijakan sima juga berkonsekuensi terhadap didukungnya
kebijakan perekonomian Airlangga oleh rakyatnya. Penyerahan hak untuk penggarapan lahan
melalui kebijakan sima bisa ditafsirkan sebagai langkah Airlangga dalam mengikutsertakan
rakyatnya ke dalam strategi ketahanan pangan yang ia terapkan. Sima makudur sebagaimana
disampaikan sebelumnya, juga memuat perintah implisit agar rakyat dapat memenuhi kebutuhan
pangan secara mandiri (tanpa campur tangan raja). Dengan demikian pemenuhan kebutuhan pangan
rakyat tidak lagi menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, tetapi diserahkan sepenuhnya terhadap
warga desa sima terkait. Contoh yang lebih jelas lagi dapat ditemui pada Prasasti Kamalagyan,
yang mana di dalam prasasti itu rakyat telah didorong agar partisipatif dalam kegiatan dagang di
pelabuhan yang baru saja dibangun oleh Airlangga melalui kebijakan sima makudur.
Keuntungan yang didapatkan Rakyat melalui Hubungan Patron-Klien dalam Kebijakan Sima
Makudur
6 ICONIC 2021 | Prosiding
Tinjauan ini melihat bahwa kebijakan Airlangga melalui Sima Makudur telah menimbulkan
dua keuntungan bagi rakyat Jawa Kuno masa itu. Keuntungan pertama dan yang paling kentara dari
pengaplikasian kebijakan sima makudur bagi rakyat Jawa Kuno adalah terbebasnya rakyat dari pajak
yang membebaninya. Selama pemerintahan Jawa Kuno (abad ke-8-15 M), kedudukan rakyat terikat
dengan raja. Di masa itu dikenal suatu jabatan khusus yang disebut sebagai maṅilala drabya haji.
Boechari (2012b) menyebut bahwa orang yang memangku jabatan ini memiliki kewajiban langsung
kepada raja dalam memungut pajak. Pajak dibebankan terhadap rakyat atas berbagai macam motif, ada
yang berkenaan dengan kewarganegaraannya (misalnya pajak terhadap orang asing) dan ada pula yang
berhubungan dengan kemampuan yang mereka miliki (misalnya pajak terhadap pandai besi, seniman
dan sebagainya).
Keuntungan yang lain yang didapat rakyat adalah didapatkannya penghasilan tambahan atas
pajak lokal daerah mereka. Status sima memungkinkan orang Jawa Kuno mendapatkan penghasilan
dari denda sukhaduhka yang mereka dapatkan dari para pelaku pidana. Hasil denda ini yang nantinya
dikumpulkan dan dimanfaatkan bagi pembangunan desa tersebut secara mandiri, tanpa harus menyetor
kepada raja.
Rakyat di sisi yang lain juga mendapat keuntungan berupa didirikannya fasilitas dengan
menggunakan dana negara. Seperti yang disebutkan di atas, bahwa raja Airlangga melalui kebijakan
sima juga terkadang memberi kebijakan sima beserta perintah untuk membangun suatu fasilitas, yang
bisa saja bentuknya berupa bangunan suci, pelabuhan dan bahkan waduk. Fasilitas-fasilitas ini kendati
pemeliharaannya diserahkan kepada rakyat, namun rakyat pula lah yang berhak atas manfaat dari
bangunan tersebut.
KESIMPULAN
Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa pembagian lahan pada masa Airlangga merupakan bentuk
demokratisasi pemanfaatan lahan, yang berarti raja telah membagi-bagi “kekuasaannya” pada rakyat
di suatu daerah tertentu. agar sistem pemanfaatan lahan yang sebelumnya terganggu oleh perebutan
kekuasaan menjadi lebih stabil dan dapat dengan mudah dikontrol oleh Airlangga sendiri. Secara
garis besar kebijakan sima makudur yang berkaitan dengan pembagian kuasa atas suatu bentang
lahan merupakan upaya yang dilakukan Airlangga dalam mempertahankan hubungan patron-klien
yang dijalinnya dengan rakyat di bawahnya. Airlangga telah menggunakan hubungan patron-kliennya
dengan rakyat, untuk menghadapi efek dari peristiwa pralaya negaranya. Sehingga pantas apabila ia
mengklaim diri sebagai juru selamat.
Airlangga pribadi melalui kebijakan ini mendapat legitimasi sebagai cakravartin di hadapan
rakyatnya. Pencitraan ini bisa menjadi lebih menguat, karena banyaknya anugerah yang ia berikan
pada rakyat. Oleh karena legitimasi tersebut, bisa diasumsikan bahwa kepercayaan rakyat terhadap raja
saat itu pun mengalami peningkatan. Peningkatan kepercayaan ini yang kemudian menjadi indikator
menguatnya posisi Airlangga sebagai raja dan terhindarnya pemerintahan Airlangga dari konflik dalam
negeri berupa pemberontakan.
ICONIC 2021 | Prosiding 7
Daftar Pustaka
Ahimsa-Putra, H. S. (2018). Patron Klien di Sulawesi Selatan: sebuah kajian Fungsional Struktural.
Kepel Press.
Boechari. (2012a). Manfaat Studi Bahasa dan Sastra Jawa Kuno ditinjau dari Segi Sejarah dan
Arkeologi. In Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat Prasasti (pp. 29–46). Kepustakaan
Populer Gramedia dan EFEO.
Boechari. (2012b). Ulah Para Pemungut Pajak di dalam Masyarakat Jawa Kuno. In Melacak Sejarah
Kuno Indonesia lewat Prasasti. Kepustakaan Populer Gramedia dan EFEO.
Darmosoetopo, R. (2003). Sima dan Bangunan keagamaan di Jawa abad IX-X TU. Universitas
Gadjah Mada.
de Casparis, J. G. (1985). Sedikit tentang Golongan-golongan di dalam Masyarakat Jawa Kuno.
Amerta, II, 52–59.
Haryono, T. (1999). Sang Hyang Watu Teas dan Sang Hyang Watu Kulumpang: Perlengkapan Ritual
Upacara Penetapan Sima pada Masa Kerajaan Mataram Kuna. Humaniora, 12, 14–21.
Holling, C. S. (1973). Resilience and stability of ecological systems. Annual Review of Ecology and
Systematics, 4.
Kern, H. C. (1913). Een Oud-Javaansche Steeninscriptie van Koning Er-langga. Bijdragen Tot de
Taal-, Land- En Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 67(4), 610–622.
Kulke, H. (1978). Devaraja Cult. Department of Asian Studies Cornell University.
Little, P. E. (2007). Political ecology as ethnography: a theoretical and methodological guide.
Antropol, 12(25), 85–103.
Mabbet, I. W. (1969). Devarāja. Journal of Southeast Asian History, 10(2), 202–223.
Munandar, A. A., Utomo, B. B., Wurjantoro, E., Astra, I. G. S., Ardika, I. W., Suhadi, M., Mustopo,
M. H., Nur, M., Julianto, N. S., Rahardjo, S., & Nastiti, T. S. (2012). Indonesia dalam Arus
Sejarah: Kerajaan Hindu-Buddha (E. Sedyawati & H. Djafar (eds.)). PT Ichtiar Baru van
Hoeve.
Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2010). Sejarah nasional indonesia jilid ii: zaman kuno.
Balai Pustaka.
Schrieke, B. J. O. (2016). Kajian Historis Sosiologis Masyarakat Indonesia: Penguasa dan Kerajaan
Jawa pada Masa Awal. Penerbit Ombak.
Scott, J. C. (1972). Patron-Client politics and political change in Southeast Asia. American Political
Science Review, 66(1), 91–113.
Siswanto. (2018). Identifikasi Penggunaan Lahan berdasarkan Sumber Prasasti abad ke-11 Masehi di
Jawa Timur. PURBAWIDYA: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Arkeologi, 7(1), 21–34.
Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Makara: Sosial Humaniora, 9(2), 57–65.
Susanti, N. (2010). Airlangga: Biografi Raja Pembaharu Jawa Abad XI. Komunitas Bambu.
8 ICONIC 2021 | Prosiding
View publication stats
Anda mungkin juga menyukai
- Laporan KKN ANG.56Dokumen47 halamanLaporan KKN ANG.56Muhammad ArdiBelum ada peringkat
- Resensi Buku Relasi Negara Dan Masyarakat AdatDokumen8 halamanResensi Buku Relasi Negara Dan Masyarakat AdatSergio AlvinBelum ada peringkat
- M Zain Wirasena - 18 - 430817 - SP - 28661Dokumen4 halamanM Zain Wirasena - 18 - 430817 - SP - 28661Zain WirasenaBelum ada peringkat
- 1324-Article Text-3599-1-10-20171108Dokumen10 halaman1324-Article Text-3599-1-10-20171108Ratna Aristiya Dewi AnggraeniBelum ada peringkat
- Patron Klien 1Dokumen10 halamanPatron Klien 1Raisya HodriaBelum ada peringkat
- Review Jurnal Kelompok 2Dokumen16 halamanReview Jurnal Kelompok 2Siva LarasathiBelum ada peringkat
- The Construction of An Islamic Capitalism Through Pagang Gadai Amongst The Minangkabau People IdDokumen22 halamanThe Construction of An Islamic Capitalism Through Pagang Gadai Amongst The Minangkabau People Idtirsaelpita98Belum ada peringkat
- Proposal Skripsi GadaiDokumen33 halamanProposal Skripsi GadaiYog's AlexanderBelum ada peringkat
- Tinjauan Buku Politik Ambivalensi: Nalar Elit Dibalik Pemenangan Pilkada Karya Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.Dokumen12 halamanTinjauan Buku Politik Ambivalensi: Nalar Elit Dibalik Pemenangan Pilkada Karya Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.Sebastianus G. DumingguBelum ada peringkat
- Miniriset Pancasila-Kelompok 3Dokumen9 halamanMiniriset Pancasila-Kelompok 3Ainnur FitriyaBelum ada peringkat
- Neng Annisa Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Retribusi Rekreasi Gunung Padang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan MasyarakatDokumen18 halamanNeng Annisa Peran Pemerintah Dalam Pengawasan Retribusi Rekreasi Gunung Padang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan MasyarakatAnisa.nfnBelum ada peringkat
- Kebijakan Hukum Pinana Terkait BudayaDokumen22 halamanKebijakan Hukum Pinana Terkait BudayarandarisgiantBelum ada peringkat
- 1661 3807 1 SPDokumen22 halaman1661 3807 1 SPSintia DerliaBelum ada peringkat
- Potret Hubungan Patron Klien Antara Buruh TaniDokumen16 halamanPotret Hubungan Patron Klien Antara Buruh TaniChristian BL DE RozariBelum ada peringkat
- UAS Agama Islam 2Dokumen34 halamanUAS Agama Islam 2Haura MahirahBelum ada peringkat
- (SC 15) Shohibuddin & Adiwibowo-2018-Meninjau Ulang PSDADokumen53 halaman(SC 15) Shohibuddin & Adiwibowo-2018-Meninjau Ulang PSDAwritermasagipediaBelum ada peringkat
- PROPOSAL IIN RevisiDokumen35 halamanPROPOSAL IIN Revisiogah mosesBelum ada peringkat
- Dian,+9 +yani+222-232Dokumen11 halamanDian,+9 +yani+222-232Astri IsnainiBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen7 halaman1 SMEdi NahakBelum ada peringkat
- Bab 2 PDFDokumen37 halamanBab 2 PDFBaiq PINA ELMAYANABelum ada peringkat
- CJR SdaDokumen13 halamanCJR SdaIlman AshariBelum ada peringkat
- Dinamika Tugasan 1 Left 3 N 5Dokumen10 halamanDinamika Tugasan 1 Left 3 N 5Yi Wen YapBelum ada peringkat
- Ketoprak Klasik Gaya Yogyakarta "Ki Ageng Mangir" Sebagai Media Pendidikan KarakterDokumen8 halamanKetoprak Klasik Gaya Yogyakarta "Ki Ageng Mangir" Sebagai Media Pendidikan KarakterPutri Regina AgustinBelum ada peringkat
- CJR Ilmu PolitikDokumen14 halamanCJR Ilmu PolitikSarahBelum ada peringkat
- Jurnal Mutiara CantikDokumen17 halamanJurnal Mutiara CantikMutiaraBelum ada peringkat
- Busana Adat MangkunegaranDokumen52 halamanBusana Adat Mangkunegaranilham robbani28Belum ada peringkat
- Politik Di KambojaDokumen13 halamanPolitik Di KambojaTatya Alifa Koeswanto100% (1)
- Buku Laporan KKN 56 Proses EditDokumen76 halamanBuku Laporan KKN 56 Proses EditMuhammad ArdiBelum ada peringkat
- 2376 6919 1 PBDokumen7 halaman2376 6919 1 PBchanBelum ada peringkat
- Adat Bali Dalam Diskursus Generasi Z Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa Dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Nur Putri HidayahDokumen70 halamanAdat Bali Dalam Diskursus Generasi Z Hasil Riset Studi Klinis Mahasiswa Dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Nur Putri Hidayahmoyraplokoon8c6100% (5)
- M Zain Wirasena - 18 - 430817 - SP - 28661Dokumen2 halamanM Zain Wirasena - 18 - 430817 - SP - 28661Zain WirasenaBelum ada peringkat
- MAKALAHDokumen14 halamanMAKALAHDoniBelum ada peringkat
- Persepsi Masyarakat Terhadap Gema AdzanDokumen36 halamanPersepsi Masyarakat Terhadap Gema AdzanYogaPratama100% (1)
- IDENTITASSOSIALABDIDALEMGARAP ELYKRISTANTIRevisiDokumen9 halamanIDENTITASSOSIALABDIDALEMGARAP ELYKRISTANTIRevisiDian SusiloBelum ada peringkat
- CJR Sosio AntropologiDokumen11 halamanCJR Sosio AntropologiPutrisyalwa lbs0% (1)
- Antropologi Dalam Budaya Lampung BegawiDokumen16 halamanAntropologi Dalam Budaya Lampung Begawileehamis65Belum ada peringkat
- Bab IDokumen26 halamanBab IAmanda WindiantikaBelum ada peringkat
- Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat LawangDokumen19 halamanTinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Dengan Sistem Indek Tahunan Di Desa Paduraksa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat LawangLuki AzumardikaBelum ada peringkat
- MAHADELTADokumen256 halamanMAHADELTAYessy YasmaraldaBelum ada peringkat
- 37-Article Text-323-1-10-20230210Dokumen11 halaman37-Article Text-323-1-10-20230210sisiiillBelum ada peringkat
- 0003-MUSTAKIM-BAB II - (Revisi-Ok)Dokumen45 halaman0003-MUSTAKIM-BAB II - (Revisi-Ok)Tio Marcelino ,29Belum ada peringkat
- KB 2 Analisis FiqihDokumen3 halamanKB 2 Analisis Fiqihwahyu ramanBelum ada peringkat
- Teori Pertukaran SosialDokumen7 halamanTeori Pertukaran SosialDicky Nur RahmanBelum ada peringkat
- Demokratisasi+Dan+Pembangunan Jurnal+Analisis+Sosial AkatigaDokumen165 halamanDemokratisasi+Dan+Pembangunan Jurnal+Analisis+Sosial AkatigaFathor RahmanBelum ada peringkat
- Sejarah Sosial Fix-3Dokumen16 halamanSejarah Sosial Fix-3Denada rahmadaniBelum ada peringkat
- 2 LilisDokumen8 halaman2 LilisAfiful AdrianBelum ada peringkat
- Subalternitas Pelajar Perempuan Minangkabau Dalam Kontroversi Pengaturan JilbabDokumen15 halamanSubalternitas Pelajar Perempuan Minangkabau Dalam Kontroversi Pengaturan JilbabAlfitaBelum ada peringkat
- Representasi Wacana Sultanah Di Media Masssa DaringDokumen22 halamanRepresentasi Wacana Sultanah Di Media Masssa Daringwempi gunartoBelum ada peringkat
- Proposal My ResDokumen8 halamanProposal My ResRika Budi LestariBelum ada peringkat
- Heldy Makalah EkopolDokumen16 halamanHeldy Makalah Ekopolandi suwandiBelum ada peringkat
- Konsep Resiprositas Dan Redistribusi Kel.3Dokumen12 halamanKonsep Resiprositas Dan Redistribusi Kel.3Indana SweetBelum ada peringkat
- Kumpulan Abstrak Jurnal ElektronikDokumen18 halamanKumpulan Abstrak Jurnal ElektronikS4lBelum ada peringkat
- Bab II Tinjauan KonseptualDokumen19 halamanBab II Tinjauan KonseptualUJIQ XXXBelum ada peringkat
- Jurnal Skripsi RakaDokumen14 halamanJurnal Skripsi RakaRaka AnugrahBelum ada peringkat
- Konsep MandalaDokumen10 halamanKonsep MandalaWanie Ameera100% (1)
- CH 9 Warren MC CarthyDokumen24 halamanCH 9 Warren MC Carthysastrowiyono52Belum ada peringkat
- Filsafat Kota Yogyakarta PDFDokumen42 halamanFilsafat Kota Yogyakarta PDFGladys C Anastasia50% (2)
- CBR Pendidikan Pancasila Violin PurbaDokumen23 halamanCBR Pendidikan Pancasila Violin Purbayolanda tuaBelum ada peringkat
- Agnes Hemas Aksata - Review Buku Perlawanan Kaum TaniDokumen15 halamanAgnes Hemas Aksata - Review Buku Perlawanan Kaum TaniAgnes Hemas AksataBelum ada peringkat
- Teori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaDari EverandTeori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)