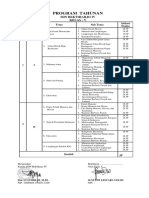Wali Songo
Wali Songo
Diunggah oleh
fajarnovita4030 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan25 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
12 tayangan25 halamanWali Songo
Wali Songo
Diunggah oleh
fajarnovita403Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 25
Semester 1
Pelajaran 1 Mengaji Surah al-Falaq
Pelajaran 2 Mengimani Allah dan Rasul-Nya
Pelajaran 3 Memahami Asmaul Husna
Pelajaran 4 Berakhlak Karimah 1
Pelajaran 5 Islam Mengajarkan Kesucian
Pelajaran 6 Mengidolakan Nabi dan Rasul
Semester 2
Pelajaran 7 Mengaji Surah al-Fil
Pelajaran 8 Mengimani Malaikat Allah
Pelajaran 9 Berakhlak Karimah 2
Pelajaran 10 Ayo Tertib Salat
Pelajaran 11 Kisah Keteladanan Wali Songo
Kisah Keteladanan Wali Songo
Pernahkah kamu mendengar kata wali?
Wali adalah sebutan untuk orang yang
dicintai Allah Swt. Mereka memiliki ilmu
agama yang tinggi. Di Indonesia ada Wali
Songo. Mereka adalah para penyebar
agama Islam di Indonesia. Banyak hal
yang bisa kita teladani dari mereka.
Jasa Wali Songo di Indonesia sangat besar dalam penyebaran dakwah
Islam, terutama di Pulau Jawa. Mereka memiliki ilmu agama yang tinggi dan
berakhlak mulia. Oleh karena itu, dakwah mereka pun dapat diterima oleh
masyarakat di mana mereka berada.
Isi Materi
A. Kisah Para Wali Songo
B. Keteladanan Para Wali Songo
A. Kisah Para Wali Songo
Wali Songo adalah sebutan yang diberikan kepada para
penyebar agama Islam di Indonesia. Mereka adalah para
ulama yang luar biasa. Ilmu pengetahuan agamanya sangat
tinggi. Ketaatannya kepada Allah Swt. juga sangat dalam.
Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan
Allah Swt. Oleh karena itu, Allah memberikan mereka
karamah. Karamah adalah kekuatan atau keajaiban yang
diberikan Allah Swt. kepada para wali.
Para ulama yang termasuk ke dalam Wali Songo adalah
1. Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik
2. Raden Rakhmat alias Sunan Ampel
3. Raden Paku alias Sunan Giri
4. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati
5. Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang
6. Raden Qosim alias Sunan Drajat
7. Ja’far Shadiq alias Sunan Kudus
8. Raden Syahid alias Sunan Kalijaga
9. Raden Umar Said alias Sunan Muria.
1. Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik
Sunan Gresik adalah tokoh tertua di kalangan Wali Songo.
Nama Syekh Maulana menunjukkan bahwa dia adalah
seorang ulama besar dan berpengaruh. Dia menjadi guru bagi
para wali dan penasihat bagi sultan.
Ketika dewasa, dia diperintahkan ayahnya untuk menyebar-kan
Islam ke wilayah selatan. Bersama dengan 40 orang rombongan,
mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 M. Pada masa itu,
Nusantara dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Maulana Malik
Ibrahim dan rombongan kemudian menetap di Desa Leran, arah
barat Kota Gresik.
Perlahan-lahan, Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran
Islam. Mula-mula membuka warung yang menjual keperluan
penduduk. Lama-kelamaan, warungnya ramai dikunjungi pembeli.
Setelah itu, dia menjadi tabib. Dia mengobati penyakit dengan
doadoa yang diambil dari Al-Qur’an. Masyarakat pun mulai
tertarik dan menjadi pengikutnya. Setelah pengikutnya banyak,
Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Banyak
murid yang datang ke pesantrennya untuk memperdalam ilmu
agama.
Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai
pribadi yang santun. Di samping itu, dia juga murah hati kepada
fakir miskin. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 M dan
dikenal dengan nama Sunan Gresik.
2. Raden Rakhmat alias Sunan Ampel
Nama aslinya adalah Ali Rahmatullah. Dia adalah putra
Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Candrawulan.
Ayahnya adalah seorang ulama dari Samarkand di Asia
Tengah. Dari silsilahnya, dia adalah keturunan Nabi
Muhammad saw. yang ke-23. Menurut catatan sejarah, dia
lahir pada tahun 1410 M.
Sunan Ampel datang pertama kali ke Nusantara pada tahun
1443 M. Bersama keluarganya, dia mendarat di Pantai
Tuban. Di Tuban, dia mengajarkan agama Islam kepada
masyarakat. Kepribadiannya yang santun membuat masya-
rakat tertarik dan mengikuti ajarannya. Akhirnya, dia
menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyi
Ageng Manila. Sejak menikah, dia dikenal dengan nama
Raden Rakhmat. Dari pernikahan ini, Raden Rakhmat
dikaruniai enam anak. Dua di antara putra-putrinya juga
menjadi wali, yaitu Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang dan
Raden Qosim alias Sunan Drajat.
Setelah menikah, Raden Rakhmat menyebarkan Islam ke
wilayah Ampel Denta, dekat Surabaya. Di sini, Raden
Rakhmat membangun masjid sebagai pusat dakwah. Selain
masjid, dia juga mendirikan pesantren untuk mendidik
masyarakat belajar agama Islam. Banyak masyarakat yang
datang dan tinggal di pesantren. Sejak itu, Kota Ampel
menjadi kota yang ramai dikunjungi.
Ajaran Raden Rakhmat yang terkenal adalah Moh Limo. Moh
artinya tidak mau, Limo artinya lima perkara. Artinya, tidak
mau melakukan lima hal yang tercela. Lima perbuatan tercela
tersebut adalah tidak mau berjudi (moh main), tidak mau
mabuk (moh ngombe), tidak mau mencuri (moh maling), tidak
mau mengonsumsi narkoba (moh madat), dan tidak mau
berzina (moh madon). Dengan ajaran Moh Limo ini, masya-
rakat terhindar dari perbuatan maksiat sehingga mereka
menjadi orang yang taat beribadah.
Di kalangan para wali, Raden Rakhmat dikenal sebagai orang
yang toleran. Dia menghormati perbedaan pendapat.
Meskipun tidak setuju dengan pendapat orang lain, Raden
Rakhmat tetap bersikap baik. Pada tahun 1478 M Raden
Rakhmat meninggal dunia. Dia dimakamkan di sebelah barat
Masjid Ampel Surabaya dan dikenal dengan nama Sunan
Ampel. Sampai sekarang, banyak umat Islam yang berziarah
ke makamnya.
3. Raden Paku alias Sunan Giri
Nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku atau Jaka
Samudra. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan
Dewi Sekardadu. Ayahnya adalah seorang ulama dari Gujarat
India. Ibunya adalah putri Bupati Blambangan, Jawa Timur.
Dia lahir sekitar tahun 1443 M di Blambangan. Karena ada
suatu urusan, Syekh Maulana Ishaq meninggal-kan Dewi
Sekardadu dan putranya pergi ke Pasai.
Raden Paku pertama kali mendapatkan pendidikan agama
dari Pesantren Ampel, pimpinan Sunan Ampel. Karena kecer-
dasannya, dia mendapatkan gelar Maulana Ainul Yaqin.
Setelah bertahun-tahun belajar kepada Sunan Ampel,
Maulana Ainul Yaqin dan Raden Maulana Makhdum Ibrahim
dipanggil menghadap Sunan Ampel. Mereka berdua diutus
oleh Sunan Ampel untuk menimba ilmu di Mekah. Akan
tetapi, sebelum menuju Mekah, mereka berdua diminta agar
singgah terlebih dulu di Pasai untuk menemui Syekh Maulana
Ishak.
Rupanya, Sunan Ampel ingin mempertemukan Maulana
Ainul Yaqin dengan ayah kandungnya. Lalu mereka berdua
pun berguru kepada Syekh Maulana Ishak. Setelah belajar
selama tujuh tahun di Pasai, mereka kembali ke Jawa. Pada
saat hendak pulang, Maulana Ishak membekali Raden Paku
dengan segenggam tanah. Beliau memintanya agar men-
dirikan pesantren di sebuah tempat yang warna dan bau
tanahnya sama dengan yang diberikannya.
Sepulangnya ke Jawa, Maulana Ainul Yaqin segera mencari
tanah yang dimaksud Ayahandanya. Ternyata tanah itu cocok
dengan tanah di daerah Giri, Gresik. Kemudian, dia mulai
berdakwah dengan mendirikan pesantren di daerah Giri
sehingga mendapat julukan Sunan Giri. Pesantrennya
menjadi pusat kajian ilmu tauhid dan fikih. Dalam menyebar-
kan Islam, Sunan Giri menjaga kemurnian akidah. Dia tidak
mau menerima adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran
Islam.
Di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai ahli
politik dan ketatanegaraan. Dia menyusun peraturan ketata-
prajaan dan pedoman tata cara di keraton. Karyanya inilah
yang kemudian digunakan di kerajaan Islam, seperti Demak,
Pajang, dan Mataram.
Sunan Giri wafat pada tahun 1506 M. Makamnya terletak di
Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa
Timur.
4. Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati
Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448. Ayahnya adalah
seorang Sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Ibunya adalah
putri Raja Siliwangi yang bernama Nyai Lara Santang. Pada saat
berusia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk
memperdalam ilmu agama. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad
untuk belajar tasawuf.
Pada tahun 1475 M, Syarif Hidayatullah dan ibunya tiba di
Nagari Caruban Larang atau Cirebon. Pada masa itu, penguasa
Nagari Caruban adalah pamannya sendiri, Prabu Cakrabuana.
Syarif Hidayatullah kemudian dinikahkan dengan putri paman-
nya, Ratu Pakungwati. Setelah Prabu Cakrabuana meninggal,
Syarif Hidayatullah diangkat menjadi raja di Nagari Caruban.
Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 M dan dimakamkan di
Pasir Jati, bagian tertinggi kompleks makam Gunung Sembung.
Salah satu putranya adalah Pangeran Sabang-kingking.
Pangeran Sabangkingking adalah penguasa kerajaan Banten
yang dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin.
5. Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang
Maulana Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel. Dia
lahir di Tuban pada tahun 1465 M. Sepulang dari Pasai,
Maulana Makdum Ibrahim diutus ayahnya untuk berdakwah di
Tuban. Selain itu, dia juga menyebarkan Islam di daerah Pati
dan Pulau Bawean.
Untuk memperlancar dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim
mendirikan pesantren di Tuban. Ketika berdakwah, dia meng-
gunakan gamelan, yaitu kesenian rakyat Bonang. Peng-
gunaan gamelan tersebut adalah untuk menarik masyarakat
agar datang ke masjid. Gamelan yang ditabuh itu lalu dinama-
kan Bonang.
Ketika Sunan Bonang menabuh gamelan, masyarakat
berbondong-bondong ke masjid. Setelah itu, Sunan Bonang
menjelaskan makna tembang yang dinyanyikannya.
Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang yang terkenal
adalah Tombo Ati, artinya obat penawar hati. Menurut
tembang atau lagu tersebut, obat hati ada lima, yaitu:
a. membaca Al-Qur’an dan memahami maknanya;
b. rajin melaksanakan salat malam atau salat tahajud;
c. berkumpul dengan orang-orang saleh untuk belajar kesa-
lehannya;
d. rajin berpuasa;
e. banyak berzikir di waktu malam.
Ajaran Sunan Bonang meliputi tasawuf, ushuluddin, dan fikih.
Dia mengajarkan masyarakat agar bersungguh-sungguh
dalam ibadah dan mencintai Allah Swt. Orang harus salat,
puasa, dan membayar zakat. Dalam hidup sehari-hari, orang
harus bersikap rendah hati, tidak putus asa, dan selalu
bersyukur atas nikmat Allah. Perbuatan yang harus dijauhi
adalah dengki, sombong, serakah, dan gila jabatan.
Demikianlah ajaran-ajaran penting dari Sunan Bonang. Sunan
Bonang wafat pada tahun 1525 M.
6. Raden Qosim alias Sunan Drajat
Raden Qosim adalah saudara Sunan Bonang. Dia diutus
ayahnya untuk berdakwah ke wilayah Gresik. Raden Qosim
kemudian menetap di Kampung Jelak, Banjarwati. Di tempat
ini, dia mendirikan surau yang kemudian menjadi pesantren.
Kampung ini kemudian berganti nama menjadi Banjaranyar.
Beberapa tahun kemudian, Raden Qosim pindah ke dataran
yang lebih tinggi. Bersama para muridnya, Raden Qosim
membangun perkampungan baru, dinamakan Desa Drajat.
Sejak itulah, Raden Qosim dikenal dengan panggilan Sunan
Drajat.
Salah satu nasihat Sunan Drajat kepada muridnya adalah
bapang den simpangi, ono catur mungkur. Artinya, jangan
mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekkan orang lain.
Sunan Drajat wafat pada tahun 1522 M. Untuk mengenang
jasanya, dibangunlah museum dekat makamnya. Di museum
tersebut kita dapat melihat barang-barang peninggalan Sunan
Drajat.
7. Ja’far Shadiq alias Sunan Kudus
Ayahnya bernama Sunan Ngudung dan ibunya bernama
Syarifah, cucu Sunan Ampel. Sunan Ngudung adalah
panglima kerajaan Demak yang terkenal. Ketika ayahnya
wafat, Ja’far Shadiq menggantikan posisinya sebagai pang-
lima perang.
Setelah tidak menjadi panglima perang, Ja’far Shadiq memu-
tuskan untuk berdakwah ke daerah Tajug, utara Demak. Di
Tajug, Ja’far Shadiq hidup bersama dengan santrinya yang
dibawa dari Demak. Dia kemudian mendirikan masjid dan
menara pada tahun 1549 M. Kota Tajug diubah namanya
menjadi Quds, yang artinya suci. Masyarakat kemudian
mengenalnya sebagai Kota Kudus. Ja’far Shadiq kemudian
dikenal dengan nama Sunan Kudus.
8. Raden Syahid alias Sunan Kalijaga
Nama aslinya adalah Raden Said atau Raden Syahid. Dia
adalah putra bupati Tuban, Arya Wilwatikta. Sunan Kalijaga
disebut juga dengan Syekh Malaya. Raden Said adalah murid
Sunan Bonang.
Setelah ilmunya cukup, Sunan Bonang mengutusnya untuk
mendakwahkan ajaran Islam. Pada mulanya, Sunan Kalijaga
pergi ke Cirebon. Setelah itu, dia berdakwah ke Kadilangu,
Demak dan sekitarnya. Di tempat inilah, Sunan Kalijaga
tinggal hingga akhir hayatnya.
Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga memadukan
dakwah dengan seni budaya masyarakat. Dia menciptakan
wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran, dan batik.
Di antara tembang yag diciptakannya adalah Ilir-ilir dan
Dandanggula Semarangan. Adapun gamelan yang dibuat oleh
Sunan Kalijaga adalah Kyai Nagawilaga dan Kyai Guntur
Madu. Kedua gamelan tersebut saat ini disimpan di Keraton
Yogyakarta dan Keraton Surakarta.
Kedua gamelan ini disebut dengan gamelan Sekaten. Karya
Sunan Kalijaga lainnya yang hingga kini masih digemari oleh
orang Jawa adalah wayang kulit. Setiap tokoh wayang dibuat
gambarnya, lalu diukir di atas kulit lembu.
9. Raden Umar Said alias Sunan Muria
Raden Umar said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dia
menyebarkan ajaran Islam di wilayah lereng Gunung Muria,
Jawa Tengah. Oleh karena itu, dia dikenal dengan nama
Sunan Muria. Selain di Muria, dia juga mengembangkan
dakwah ke pelosok Pati, Kudus, Juwana, hingga ke pesisir
utara Pulau Jawa.
Sunan Muria berusaha mengislamkan tradisi kebudayaan
masyarakat. Sedikit demi sedikit, tradisi tersebut diubah dan
disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam bidang kesenian,
Sunan Muria juga menciptakan tembang, yaitu Sinom dan
Kinanthi. Lewat tembang-tembang itulah, Sunan Muria
mengajak orang-orang mengamalkan ajaran Islam.
Sunan Muria dikenal lebih suka berdakwah pada rakyat jelata
di banding kaum bangsawan. Oleh karena itu, daerah
dakwahnya cukup luas dan tersebar, mulai lereng Gunung
Muria hingga daerah pesisir utara. Cara dakwah inilah yang
menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai sunan yang suka
berdakwah topo ngeli, yaitu dengan mengikuti kegemaran
masyarakat.
Setelah bertahun-tahun berdakwah, Sunan Muria wafat dan
dimakamkan di Desa Colo, sekitar 19 km dari pusat Kota
Kudus. Hingga sekarang, banyak umat Islam yang berziarah
ke makamnya untuk meneladani kealiman dan perjuangan-
nya dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam.
B. Keteladanan Para Wali Songo
1. Berdakwah dengan Cara Damai
Dalam menyebarkan ajaran Islam, para Wali Songo tidak
memaksakan Islam kepada masyarakat. Pada masa itu,
masyarakat Indonesia beragama Hindu. Dengan sabar,
mereka mengajarkan Islam. Sedikit demi sedikit, masyarakat
pun mampu menerimanya. Bagi masyarakat yang tidak
menerima Islam, mereka tidak dipaksa masuk Islam.
Wali Songo berdakwah dengan cara yang bijaksana. Peng-
ajaran Islam dilakukan dengan bahasa yang santun. Mereka
mengajarkan ketaatan kepada Allah Swt. sebagai satu-
satunya Tuhan yang wajib disembah. Mereka mengajak
masyarakat untuk rajin beribadah.
2. Toleransi terhadap Kebudayaan Masyarakat
Para wali sangat peduli dengan kebudayaan masyarakat.
Mereka mengislamkan tradisi-tradisi yang sudah ada.
Tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam tetap
dipelihara. Akan tetapi, tradisi yang bertentangan dengan
Islam diubah dan disesuaikan dengan Islam.
Masyarakat Jawa pada waktu itu sangat menyukai kese-
nian. Mereka biasa menonton wayang dan menabuh
gamelan. Mereka juga gemar menggubah tembang. Para
wali menjadikan kesenian sebagai sarana berdakwah.
Mereka menciptakan tembang-tembang yang berisi
ajaran Islam, seperti Tombo Ati, Lir Ilir, Sinom, dan
Kinanthi. Melalui tembang tersebut, para wali mengajar-
kan Islam kepada masyarakat.
3. Menyantuni Fakir Miskin
Sasaran dakwah Wali Songo adalah rakyat jelata. Mereka
kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Wali Songo mengajar-
kan orang-orang untuk menjadi dermawan. Mereka mendidik
masyarakat agar suka bersedekah kepada fakir miskin dan
anak-anak telantar. Masyarakat yang miskin mendapatkan
santunan. Mereka diberi tanah garapan untuk pertanian.
Anak-anak mereka dididik di pesantren yang didirikan para
wali. Mereka belajar tanpa dipungut bayaran. Para wali
menunjukkan bahwa Islam menyayangi fakir miskin.
Menyantuni fakir miskin adalah perintah Allah. Barang siapa
yang mencintai Allah harus mencintai fakir miskin. Harta
kekayaan adalah amanah dari Allah. Di dalamnya ada hak
yang dimiliki fakir miskin. Oleh karena itu, rajinlah berse-
dekah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah.
Terima Kasih ...
Semoga Ilmunya Bermanfaat,
Aamiin.
Editor : Bilal Inc.
Sumber Bahan Ajar :
Anda mungkin juga menyukai
- Kisah Wali SongoDokumen3 halamanKisah Wali SongoArif Muttaqin75% (4)
- Makalah Wali SongoDokumen12 halamanMakalah Wali SongoFahrul Syawal76% (17)
- Kisah Hikayat Sahabat Rasul Vol 1 Abu Hurairah Sang Bapak Kucing Kecil Edisi Bilingual Indonesia & MelayuDari EverandKisah Hikayat Sahabat Rasul Vol 1 Abu Hurairah Sang Bapak Kucing Kecil Edisi Bilingual Indonesia & MelayuPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (6)
- Sejarah Wali 9Dokumen7 halamanSejarah Wali 9Muhammad Nashiruddin ZarkasyiBelum ada peringkat
- Biografi WalisongoDokumen6 halamanBiografi WalisongoevilisBelum ada peringkat
- Sejarah Masuknya Islam Ke IndonesiaDokumen11 halamanSejarah Masuknya Islam Ke IndonesiaGandiihgrBelum ada peringkat
- Wali SongoDokumen17 halamanWali Songoforza milanBelum ada peringkat
- Wali SongoDokumen17 halamanWali SongonikenBelum ada peringkat
- Tugas SEJARAH INDONESIA 1Dokumen7 halamanTugas SEJARAH INDONESIA 1Joseph BryanBelum ada peringkat
- Wali SongoDokumen8 halamanWali SongoYossy RamadhantiBelum ada peringkat
- Wali Songo 3Dokumen12 halamanWali Songo 3Amanda net2ccBelum ada peringkat
- WalisongoDokumen6 halamanWalisongoDenny AlfhajriBelum ada peringkat
- Walisongo Dan Model Penyebaran IslamDokumen33 halamanWalisongo Dan Model Penyebaran IslamMaulana AsyariBelum ada peringkat
- Kisah Wali Songo 2Dokumen11 halamanKisah Wali Songo 2AhmadFadilahBelum ada peringkat
- Wali SongoDokumen10 halamanWali SongoDhani Purnama Sari, S.Pd.Belum ada peringkat
- Tugas Bahasa InggrisDokumen11 halamanTugas Bahasa InggrisNanda RizkiansyahBelum ada peringkat
- Tugas Pendidikan Agama IslamDokumen10 halamanTugas Pendidikan Agama IslamWahyöe MuhammadBelum ada peringkat
- Makalah Wali Songo OkDokumen11 halamanMakalah Wali Songo OkImri OfficialBelum ada peringkat
- Biografi Wali SangaDokumen4 halamanBiografi Wali SangaFirdaus AbbasBelum ada peringkat
- WALISONGODokumen6 halamanWALISONGOFAISAL100% (1)
- Biografi PaiDokumen15 halamanBiografi Paimaru komputerBelum ada peringkat
- Rangkuman Walisongo-1Dokumen20 halamanRangkuman Walisongo-1Nadhira SorayaBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah Kebudayaan Islam-1Dokumen7 halamanMakalah Sejarah Kebudayaan Islam-1Ivana TuguBelum ada peringkat
- Wali Sanga Tugas AbrorDokumen3 halamanWali Sanga Tugas AbrorMuhamad Sahid SaputraBelum ada peringkat
- ReviewJurnal Ryan SKIDokumen3 halamanReviewJurnal Ryan SKIBimaAnangBelum ada peringkat
- Kliping Sejarah Wali SongoDokumen12 halamanKliping Sejarah Wali SongoHauzan Ilham AqilBelum ada peringkat
- WALI SONGO-WPS OfficeDokumen14 halamanWALI SONGO-WPS OfficeNabila JuliantiBelum ada peringkat
- Biografi Wali SongoDokumen9 halamanBiografi Wali SongoZugaBelum ada peringkat
- Wali Songo-1Dokumen12 halamanWali Songo-1Javas RabniBelum ada peringkat
- Biografi Wali SongoDokumen10 halamanBiografi Wali SongoAndhika NugrahaBelum ada peringkat
- Sunan GresikDokumen22 halamanSunan GresikkevinjunivokevinBelum ada peringkat
- WALIDokumen11 halamanWALIbina jayaBelum ada peringkat
- Dokumen Wali Sanga AnjayDokumen13 halamanDokumen Wali Sanga AnjaynadaBelum ada peringkat
- Wali SongoDokumen7 halamanWali SongoJavas RabniBelum ada peringkat
- Tugas Pai KELOMPOK 4-RevisiDokumen13 halamanTugas Pai KELOMPOK 4-RevisiRisqi KnockBelum ada peringkat
- Peran Walisongo Dalam Menyebarkan Agama Islam Diindonesia NewDokumen8 halamanPeran Walisongo Dalam Menyebarkan Agama Islam Diindonesia Newutaminurul725Belum ada peringkat
- Tugas Kliping Wali SongoDokumen20 halamanTugas Kliping Wali SongoLeonard pratamaBelum ada peringkat
- WalisangaDokumen3 halamanWalisanga????Belum ada peringkat
- Peran Walisongo Dalam Penyebaran Islam Di IndonesiaDokumen7 halamanPeran Walisongo Dalam Penyebaran Islam Di IndonesiaAnonymous 4IaxCF100% (1)
- Peran Wali SongoDokumen16 halamanPeran Wali SongoTutik HandayaniBelum ada peringkat
- Sejarah Kebudayaan IslamDokumen18 halamanSejarah Kebudayaan Islamboxkoko77Belum ada peringkat
- Materi SKI IX Sesuai KMA 183 Tahun 2019Dokumen18 halamanMateri SKI IX Sesuai KMA 183 Tahun 2019Astin IstianaBelum ada peringkat
- Kisah 9 Tokoh WalisongoDokumen9 halamanKisah 9 Tokoh WalisongoPutri Yogi SelvianaBelum ada peringkat
- MAKALAH SKI WALISONGO-WPS Office-2Dokumen11 halamanMAKALAH SKI WALISONGO-WPS Office-2Indhah 1203Belum ada peringkat
- Biografi Dan Sejarah Wali Songo 1. Sunan GresikDokumen9 halamanBiografi Dan Sejarah Wali Songo 1. Sunan Gresikprima ega patriaBelum ada peringkat
- Dakwah Wali SangaDokumen4 halamanDakwah Wali SangaAminah AlaydrusBelum ada peringkat
- Wali SongoDokumen10 halamanWali SongoLala TiranyaBelum ada peringkat
- Sunan GresikDokumen7 halamanSunan GresikAndalas ComputerBelum ada peringkat
- KeteladananDokumen17 halamanKeteladananFah Reni ReniBelum ada peringkat
- Tugas Ski BilqisDokumen8 halamanTugas Ski BilqisBilqis DaudBelum ada peringkat
- Sejarah Wali Songo Dan Asal UsulnyaDokumen3 halamanSejarah Wali Songo Dan Asal UsulnyaSyah NapirahBelum ada peringkat
- 2 Nilai Perjuangan Wali SongoDokumen10 halaman2 Nilai Perjuangan Wali SongoWarnet CigadogBelum ada peringkat
- Biografi WalisongoDokumen10 halamanBiografi Walisongoabc50% (2)
- Wali SongoDokumen11 halamanWali SongoAbdul HaliemBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok Perkembangan IslamDokumen20 halamanTugas Kelompok Perkembangan IslamMuhamad RafliBelum ada peringkat
- Makalah Wali SongoDokumen12 halamanMakalah Wali Songoarya fotocopykbBelum ada peringkat
- Biografi Walisango Dan Perannya Dalam Mengembangkan Islam Di IndonesiaDokumen10 halamanBiografi Walisango Dan Perannya Dalam Mengembangkan Islam Di IndonesiaYasmin Mumtaz0% (1)
- WalisongoDokumen7 halamanWalisongoSiti Nur HalizaBelum ada peringkat
- Kel. 9Dokumen32 halamanKel. 9Laila TsaniBelum ada peringkat
- Wali Songo 1Dokumen17 halamanWali Songo 1Amanda net2ccBelum ada peringkat
- Nabi Ibrohim Dan Isma'IlDokumen25 halamanNabi Ibrohim Dan Isma'Ilfajarnovita403Belum ada peringkat
- Promes KLS 5 - SMT 2Dokumen10 halamanPromes KLS 5 - SMT 2fajarnovita403Belum ada peringkat
- Jurnal Kelas 5 Tema 7Dokumen26 halamanJurnal Kelas 5 Tema 7fajarnovita403Belum ada peringkat
- Program Tahunan Kelas 5Dokumen2 halamanProgram Tahunan Kelas 5fajarnovita403Belum ada peringkat
- CP Bahasa JawaDokumen3 halamanCP Bahasa Jawafajarnovita403Belum ada peringkat