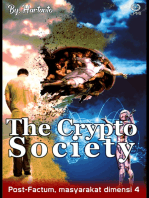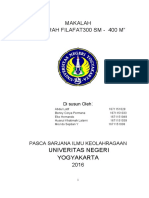Sejarah Etika
Diunggah oleh
Eido JpeHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Sejarah Etika
Diunggah oleh
Eido JpeHak Cipta:
Format Tersedia
Sejarah Etika
Manusia secara alami akan senatiasa membutuhkan pangan, kehangatan, papan dan reproduksi demikian juga hal-hal yang mampu memebrikan kepuasaan/kebutuhan dasar yang selalu memiliki nilai buat manusia. Manusia dalam hal ini tidak ubahnya seperti binatang pada umumnya. Namun, dalam beberapa hal sepanjang sejarah manusia, mereka memulai berfikir dengan memfungsikan akal bahwa hal-hal tertentu bernilai bagi mereka (dan hal tertentu tidak bernilai bagi mereka). Hal inilah yang membedakan manusia dengan binatang. [1] Kemudian melalui akal tersebut manusia dihadapkan dengan kondisi sosial masyarakat yang berbeda tergantung pada daerah tertentu. Interaksi masyarakat dalam kondisi akan senantiasa meniscayakan adanya peraturan-peraturan yang berupa kesepakatan-kesepakatan tertentu (social agreement). Hal inilah yang kemudian mendorong terlahirnya nilai-nilai moral dan etika. [2] Beberapa filosof menyatakan bahwa konsep-konsep moral adalah abadi, terbatas, tidak berubah, penentu dari sebuah konsep tertentu, tentu diantara beberapa pernyataan tersebut memiliki pola yang sama sepanjang sejarah mereka, sehingga ada bagian yang secara investigatif patut menjadi pertimbangan dari "bahasa moral ". Para ahli sejarawan sekaligus para filosof moral telah sepakat mengenai keberagaman praktek moral dan isi dari penilaian moral dari satu masyarakat ke masyarakat yang lain dan dari satu orang ke orang lain, tapi pada saat yang sama para sejarawan telah berasimilasi tentang adanya konsep moral yang berbeda-beda sehingga pada akhirnya menyatakan bahwa meskipun apa yang dianggap benar atau yang baik tidak selalu sama, namun bisa dipastikan bahwa keberadaan konsep tentang yang benar dan baik bersifat universal. [3] Alasdair mengatakan bahwa konsep moral berubah karena perubahan kehidupan sosial. Konsepkonsep moral yang ada pada perkembangannya terwujud dan telah menjadi acuan normatif dalam kehidupan sosial. Salah satu jalan untuk dapat mengidentifikasi adanya perbedaan bentuk kehidupan sosial yakni dengan mengidentifikasi perbedaan dalam konsep moral.[4] James C. Swindal dan Earl W. Spurgin mengatakan bahwa etika memiliki sejarah yang dapat membantu setiap orang untuk memahami pendekatan kontemporer. Karena itu, menurut Swindal dan Spurgin perlu kiranya memasukkan sebuah sketsa singkat tentang sejarah etika. Oleh mereka, sketsa tersebut membagi pemikiran etika menjadi tiga periode utama. Ancient: Socrates and plato, Aristotle, Epicureans and Stoics. Medieval: St Augustine, St Thomas Aquinas, Duns Scotus and William of Ockham. Modern: Hobbes, David Hume, Immanuel Kant and John Stuart Mill. Para pengkaji menggunakan istilah modern untuk menyebut periode pencerahan, yakni abad ketujuh belas dan kedelapan belas; yang merentang sampai abad kesembilan belas. Sebaliknya, istilah "kontemporer" merujuk pada periode seratus tahun terakhir yakni abad kedua puluh dan kedua puluh satu.[5] Pengamatan di dunia Barat terhadap kajian etika telah dimulai dengan representasi pemikiran Yunani kuno. Pakar etika Yunani bertanya bagaimana orang bisa menggunakan alasan untuk mencapai "hidup baik". Tetapi mereka memiliki perbedaan pendapat tentang dua hal yakni apa yang dinamakan dengan kehidupan yang baik itu dan apakah hakikat dari alasan praktis yang mengantarkan untuk mencapainya. Adapun sejarah munculnya etika tergambar dalam petikan dari tulisan Swindal dan Spurgin berikut ini: Life in Greece and Asia Minor in the fifth century BC was a time of relative peace. This enabled trade and commerce to increase among diverse people in the region. Such interaction brought increased awareness of social differences. This led philosophers both to question their own way of doing things and to notice positive features in social practices other than their own. In his Histories, Herodotus (485-430 BC) defended the view that what is good is relative to a specific culture. This respect for custom inspired the sophist Protagoras (480-410 BC) to claim, man is the measure of all things. The sophist stressed the difference between subjective val ues and objective facts, holding that decisions should be based not on stable natures (phusis) but on conventional rules (nomos). The Athenian Socrates (470-399 BC) was in fact considered a relativist by some, though his student Plato saw him in a different light. [6]
Kehidupan di Yunani dan Asia Kecil pada abad kelima SM adalah kehidupan yang relatif damai. Hal ini memungkinkan usaha perdagangan dan bisnis untuk berkembang di antara orang-orang yang beragam di wilayah tersebut. Interaksi tersebut menyebabkan timbulnya peningkatan kesadaran karena perbedaan (status) sosial. Ini mendorong para filosof mempertanyakan cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu dan melihat ciri/sifat positif dalam praktek-praktek sosial lain selain kehidupan mereka sendiri. Herodotus (485-430 SM), dalam sejarahnya, mempertahankan pandangan bahwa apa yang baik adalah relatif terhadap budaya tertentu. Perhatian terhadap adat ini telah mengilhami seorang sofis Protagoras (480-410 SM) untuk mengklaim, "manusia adalah ukuran dari segala sesuatu". Kaum Sofis menekankan akan adanya perbedaan antara nilai-nilai subjektif dan fakta-fakta obyektif, demikian juga beranggapan bahwa keputusan harus didasarkan bukan pada hakekat (alam) yang stabil (phusis) tapi pada aturan konvensional (nomos). Bagaimanapun seorang Athenian Socrates (470-399 SM) memang dianggap sebagai yang relativis, namun demikian muridnya Plato melihatnya dalam sudut pandang yang berbeda. Kemudian pada perkembangannya pemikiran etika menjadi perdebatan dialektis antara beberapa filosof Yunani yang terlihat dalam tulisan berikut: According to Plato (427-348 BC), Socrates believed in the existence of objective ethical standards while nothing how difficult it was for us to specify them. In the early dialogue the Euthyphro, Socrates inquires into the meaning of piety with Euthyphro, a young man who was going to report his father for having killed a slave. Socrates asks Euthyphro whether something is good because the god loves it, or whether the god loves it because it is good. The dialogue reaches the conclusion that human reasoning about what is good has a certain independence from the vagaries of the gods determination of the rightness of our actions and mores. Then in Gorgias, Socrates indicates that the pleasure and pain fail to furnish an objective standard for determining right from wrong since they never exist apart from one another, while good and evil do. Menurut Plato (427-348 SM), Socrates percaya akan adanya standar etika yang obyektif, sementara betapa sulitnya bagi kita untuk menentukan standar etika tersebut. Socrates bertanya tentang makna kesalehan dengan Euthyphrodalam dialog awal Euthyphro, kisahnya tentang seorang pemuda yang akan melaporkan ayahnya karena telah membunuh seorang budak. Sokrates bertanya Euthyphro apakah sesuatu itu baik karena dewa menyukainya, atau apakah dewa mencintai karena sesuatu itu baik. Dialog mencapai kesimpulan bahwa penalaran manusia tentang apa yang baik memiliki pengertian akan kebebasan tertentu dari campur tangan dewa terhadap kebenaran dari tindakan dan adat istiadat kita. Kemudian pada Gorgias, Socrates menunjukkan bahwa (ukuran) kesenangan dan penderitaan gagal untuk memberikan suatu standar objektif dalam menentukan benar dari yang salah karena mereka tidak pernah terpisah dari satu sama lain, sementara kebaikan dan kejahatan akan selalu menjadi dialektika yang akan terus terjadi tanpa terpisah. Plato menulis dalam karya Republik sebuah dialog, bahwa Socrates mempertimbangkan tentang apa itu hakikat dari sebuah kehidupan yang adil. Dia pertama menyerang konsepsi umum dari keadilan. Beberapa sophis mengklaim bahwa siapa pun orangnya yang hidup dengan caranya sendiri, maka tidak akan ada keadilan. [7] Selain itu, ketidak adilan (tanpa aturan) cenderung lebih bahagia daripada keadilan. Sokrates menjawab dengan analogi: sama seperti di masyarakat yang baik, setiap orang memiliki fungsi tertentu yang diperintahkan secara harmonis berinteraksi dengan fungsi semua, jadi hanya orang yang memiliki keseimbangan yang tepat antara, aspek rasional dan spriritual lah yang mampu menjadi penyokong keadilan. Seseorang dengan jiwa yang bersih dan terkontrol dengan baik akan bahagia. [8] Kemudian dialog tersebut memberikan fondasi yang sistematis mengenai pandangan tentang keadilan. Plato berpendapat bahwa semua hal yang terlihat dalam dunia akan mampu (secara potensial) untuk dimengerti, berpartisipasi dalam bentuk terpisah yang tidak terlihat, tidak berubah dan sempurna. [9] Jadi akan selalu ada bentuk yang berbeda mengenai moral bahkan mengenai keadilan dan kebahagiaan. Yang tertinggi dan sangat sulit untuk dipahami, adalah tentang apa itu yang baik (the good). Untuk mengetahui yang baik (the good) dibutuhkan sebuah perilaku asketis yang
ketat secara intelektual. Orang yang memahami baik akan selalu melakukan perbuatan baik. Perbuatan buruk dilakukan karena adanya pengabaian terhadap hal yang baik. Plato mengatakan bahwa tindakan praktis yang dipandu oleh aturan yang baik, lebih diutamakan daripada pemikiran teoretis tentang sesuatu. [10] _________________________________ [1] Robert L. Holmes, Basic Moral Philosophy, (New York: Wadsworth Publishing Company, 1998), hal 3-4 [2] Ibid., hal 2 [3] Ibid., hal 1 [4] Alasdair Mclntyre, A Short History of Ethics, (New York: Macmillan Publishing Company, 1966), hal 1 [5] James C. Swindal dan Earl W. Spurgin, The History of Ethics dalam Ethics: Contemporary Reading, (New York: Routledge, 2004), hal 25 [6] Ibid., hal 26 [7] Denise, Theodore C. (ed.), Great Traditions in Ethics, (New York: Wadsworth Publishing Company, 1999), hal 2 [8] Ibid., hal 3 [9] Ibid., hal 4 [10] James C. Swindal dan Earl W. Spurgin, Op.Cit., hal 27
Anda mungkin juga menyukai
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)
- Sejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniDari EverandSejarah psikologi ilmiah: Dari kelahiran psikologi hingga neuropsikologi dan bidang aplikasi terkiniBelum ada peringkat
- Sejarah FilsafatDokumen13 halamanSejarah FilsafatAditya Fauzan AhadianBelum ada peringkat
- Pemikiran SocratesDokumen5 halamanPemikiran SocratesInestya SnelliusBelum ada peringkat
- Sejarah Dan Perkembangan Teori Filsafat HukumDokumen25 halamanSejarah Dan Perkembangan Teori Filsafat HukumKanza Latunhi RayesBelum ada peringkat
- Sejarah Filsafat YunaniDokumen12 halamanSejarah Filsafat YunaniNovita AnugrahBelum ada peringkat
- Sejarah Etika NewDokumen13 halamanSejarah Etika Newhanbin 1022Belum ada peringkat
- Sokrates Dan DialektikaDokumen8 halamanSokrates Dan DialektikaJessel Bastian SupitBelum ada peringkat
- Aliran EtikaDokumen4 halamanAliran Etikaaji100% (1)
- Buku ETIKA Dan Budaya SUMUT24Dokumen131 halamanBuku ETIKA Dan Budaya SUMUT24Anak jenderalBelum ada peringkat
- Sejarah Filsafat EtikaDokumen46 halamanSejarah Filsafat EtikaEcha Annisa NizamuddinBelum ada peringkat
- Sejarah Etika1Dokumen5 halamanSejarah Etika1Eido JpeBelum ada peringkat
- Akhlak Tasawuf Kel 4Dokumen12 halamanAkhlak Tasawuf Kel 4Mrnda DimasirawanBelum ada peringkat
- Sejarah Pertumbuhan EtikaDokumen7 halamanSejarah Pertumbuhan EtikaSri Ayu NuraeniBelum ada peringkat
- Filsafat Ilmu - 1Dokumen31 halamanFilsafat Ilmu - 1Fatmawati Agustina100% (1)
- 4 Filsuf Periode Yunani Yang Menandai Eksistensi Pemikiran FilsafatDokumen2 halaman4 Filsuf Periode Yunani Yang Menandai Eksistensi Pemikiran FilsafatRumah PelitaBelum ada peringkat
- Etika ProfesiDokumen10 halamanEtika ProfesiWildani Deza FahmiBelum ada peringkat
- SocratesDokumen5 halamanSocratesFarid Mesbah0% (1)
- Kelahiran Dan Perkembangan FilsafatDokumen18 halamanKelahiran Dan Perkembangan FilsafatCalum MaBelum ada peringkat
- Sejarah EtikaDokumen2 halamanSejarah EtikaAgus SalimBelum ada peringkat
- KeilmuaaannDokumen19 halamanKeilmuaaannCHARNEST STARLYNT TUMANANBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Akhlak Pada Zaman YunaniDokumen3 halamanSejarah Perkembangan Akhlak Pada Zaman YunaniSaski Aulia Putri100% (1)
- Filsafat SpekulatifDokumen16 halamanFilsafat Spekulatifanti khoirifahBelum ada peringkat
- Masa SocratesDokumen9 halamanMasa SocratesMatias Dwi PamungkasBelum ada peringkat
- Pandangan Tentang Hukum Pada Zaman KlasikDokumen6 halamanPandangan Tentang Hukum Pada Zaman KlasikDr.Fitri WahyuniunisiBelum ada peringkat
- Moral Dalam Perspektif Barat Dan IslamDokumen9 halamanMoral Dalam Perspektif Barat Dan IslamFahrilBelum ada peringkat
- Filsafat TimurDokumen34 halamanFilsafat TimurIdo VerlyBelum ada peringkat
- BAB II EtikaDokumen7 halamanBAB II Etikawarda naurisBelum ada peringkat
- Tugas Filsafat HukumDokumen4 halamanTugas Filsafat Hukumjasman040802Belum ada peringkat
- FilsafatDokumen5 halamanFilsafatIzzaBelum ada peringkat
- Klasifikasi Ilmu Dan Hirarki IlmuDokumen9 halamanKlasifikasi Ilmu Dan Hirarki IlmuYenni Manurung100% (3)
- Sejarah Singkat Filsafat: Susane K. Langer Yang Membagi Sejarah Filsafat Ke Dalam EnamDokumen6 halamanSejarah Singkat Filsafat: Susane K. Langer Yang Membagi Sejarah Filsafat Ke Dalam EnamRahmatiah HasanBelum ada peringkat
- Refleksi Teologi Pedagogis Pemikiran Filosofis SokratesDokumen9 halamanRefleksi Teologi Pedagogis Pemikiran Filosofis Sokratesleonardus100% (1)
- Materi Kuliah OL FHDokumen4 halamanMateri Kuliah OL FHMuhammad MarioBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok Filsafat (Pertemuan 4)Dokumen6 halamanTugas Kelompok Filsafat (Pertemuan 4)louisa audyBelum ada peringkat
- BAB I FilsafatDokumen10 halamanBAB I FilsafatYoghyeBelum ada peringkat
- Tugas Filsafat Klasik Dan ModernDokumen15 halamanTugas Filsafat Klasik Dan ModernAddhia diaaBelum ada peringkat
- Etika & Filsafat KomunikasiDokumen12 halamanEtika & Filsafat Komunikasiara mulBelum ada peringkat
- Filsafat Umum - Etika Socrates, Palto Dan AristotelesDokumen6 halamanFilsafat Umum - Etika Socrates, Palto Dan AristotelesPutri shela damayanti100% (3)
- Pertemuan II Filsafat Agama YunaniDokumen52 halamanPertemuan II Filsafat Agama YunaniNikita RahelBelum ada peringkat
- Essay Perbandingan Filosofi Yunani Kuno (SPA) Dan MedievalDokumen3 halamanEssay Perbandingan Filosofi Yunani Kuno (SPA) Dan MedievalJericho IrawanBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Filsafat Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Masa KiniDokumen6 halamanSejarah Perkembangan Filsafat Dari Zaman Yunani Kuno Hingga Masa KiniSURYABelum ada peringkat
- Etika KeilmuanDokumen8 halamanEtika KeilmuanReza AditiaBelum ada peringkat
- ETIKA Administrasi NegaraDokumen15 halamanETIKA Administrasi Negarahamzah ansoriBelum ada peringkat
- Bantu Minbar FilsafatDokumen7 halamanBantu Minbar Filsafatal kimBelum ada peringkat
- BiografiDokumen19 halamanBiografiHar UnBelum ada peringkat
- Filsafat Plato Dan AristotelesDokumen10 halamanFilsafat Plato Dan AristotelesRiaBelum ada peringkat
- FILSAFAT MakalahDokumen12 halamanFILSAFAT MakalahAnggunBelum ada peringkat
- Makalah 300 SM-400MDokumen36 halamanMakalah 300 SM-400MlalarniBelum ada peringkat
- Resume Pak Bayu (Filsafat Ilmu)Dokumen10 halamanResume Pak Bayu (Filsafat Ilmu)Nopri PardiansonBelum ada peringkat
- Filsafat Umum Pada Zaman Socrates, Plato, & AristotelesDokumen12 halamanFilsafat Umum Pada Zaman Socrates, Plato, & AristotelesAchyar MunawarBelum ada peringkat
- Pengantar FilsafatDokumen17 halamanPengantar FilsafatBryanBelum ada peringkat
- Filsafat Pemikiran Socrates Mengenai Sains Dan AgamaDokumen5 halamanFilsafat Pemikiran Socrates Mengenai Sains Dan AgamaLundu HutabaratBelum ada peringkat
- Makalah Kode Etik AuditorDokumen19 halamanMakalah Kode Etik AuditorKhumairoh Dila JihadBelum ada peringkat
- Makalah PengantarDokumen10 halamanMakalah Pengantarnor ismahBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat Kel 2Dokumen9 halamanMakalah Filsafat Kel 2Adil RifahiBelum ada peringkat
- Kelompok 2Dokumen47 halamanKelompok 2silmi sofyanBelum ada peringkat
- Filsafar Socrates Dan Kaum Sofis - Sitti Sofiyah&Fatimatus ZahrohDokumen13 halamanFilsafar Socrates Dan Kaum Sofis - Sitti Sofiyah&Fatimatus ZahrohMuhis MuhiaBelum ada peringkat
- Sejarah Filsafat.2Dokumen14 halamanSejarah Filsafat.2nurdincahyadi90Belum ada peringkat