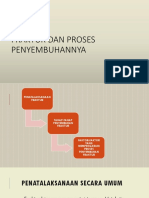Refer at
Refer at
Diunggah oleh
Raya KurniawanJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Refer at
Refer at
Diunggah oleh
Raya KurniawanHak Cipta:
Format Tersedia
BAB I PENDAHULUAN
Suara serak bukanlah suatu penyakit melainkan gejala dari suatu penyakit, umumnya berhubungan dengan gangguan pita suara. Gangguan pita suara dapat terjadi karena adanya infeksi pada tenggorokkan, pemakaian suara yang berlebihan, pertumbuhan tumor pada pita suara, gangguan saraf pita suara, trauma pada leher akibat benturan dan infeksi paru-paru. Penyebab paling sering umumnya adalah infeksi pada tenggorokkan, biasanya karena infeksi saluran nafas atas, lesi jinak pita suara dan gangguan suara fungsional. Perlu diwaspadai apabila suara serak lebih dari 2 minggu harus segera diperiksakan untuk menilai gangguan pada pita suara. Penyebab lain yang perlu diwaspadai adalah tumor laring.1 Tumor laring dapat ditemukan diberbagai belahan dunia dengan insiden yang bervariasi. The American Cancer Society melaporkan pada 2006 di Amerika tercatat ada 12.000 kasus baru dengan 4.740 kasus meninggal akibat tumor laring. Laporan dari WHO menyatakan 1,5 orang dari 100.000 penduduk meninggal karena tumor ganas ini.2 Di Indonesia angka kekerapan tumor laring belum dapat dipastikan, namun diperkirakan mencapai 1% dari semua keganasan di bidang THT. Artinya, menempati posisi ketiga tumor terbanyak di bidang THT, setalah tumor ganas nasofaring, dan tumor ganas hidung dan sinus paranasal. Data Departemen Patologi Anatomi FKUI/RSCM selama periode 2000-2005 ditemukan 3.344 kasus tumor ganas di daerah kepala-leher, terbanyak kasus kanker nasofaring 948 kasus (28,35 %) sedangkan tumor ganas laring sekitar 213 kasus (6,73%). Sekitar 60 % keganasan laring ditemukan didaerah glotis, ada 35 % di supraglotis, dan 5 % di subglotis.2
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Anatomi Laring Faring, laring, trakea dan paru-paru merupakan derivat foregut embrional yang terbentuk sekitar 18 hari setelah konsepsi. Kemudian terbentuk alur faring median yang berisi tanda pertama sistem pernafasan dan benih laring. Sulkus atau alur laringotrakea menjadi nyata pada sekitar hari ke-21 kehidupan embrio. Perluasan alur kearah kaudal merupakan primordial paru. Alur menjadi lebih dalam dan berbentuk kantung dan kemudian menjadi dua lobus pada hari ke-27 atau ke-28. Bagian proksimal dari tuba yang membesar ini akan menjadi laring. Pembesaran aritenoid dan lamina epitelial dapat dikenali menjelang 33 hari, sedangkan kartilago, otot, dan sebagian besar pita suara terbentuk dalam tiga atau empat minggu berikutnya. Hanya kartilago epiglotis yang tidak terbentuk hingga masa midfetal. Gangguan perkembangan dapat berakibat berbagai kelainan yang dapat didiagnosis melalui pemeriksaan laring secara langsung.3 Laring merupakan struktur kompleks yang telah berevolusi yang menyatukan trakea dan bronkus dengan faring sebagai jalur aerodigestif umum. Secara umum, laring dibagi menjadi tiga: supraglotis, glotis dan subglotis. Supraglotis terdiri dari epiglotis, plika ariepiglotis, kartilago aritenoid, plika vestibular (pita suara palsu) dan ventrikel laringeal. Glotis terdiri dari pita suara atau plika vokalis. Daerah subglotik memanjang dari permukaan bawah pita suara hingga kartilago krikoid. Ukuran, lokasi, konfigurasi, dan konsistensi struktur laringeal, unik pada neonatus.3
Gambar 1. Anatomi laring5
Laring adalah organ khusus yang mempunyai sphincter pelindung pada pintu masuk jalan nafas dan berfungsi dalam pembentukan suara. Diatas laring terbuka ke dalam laringopharing dan dibawah laring berlanjut sebagai trakea. Kerangka laring dibentuk oleh beberapa kartilago, dihubungkan oleh membran, ligamentum, dan digerakkan oleh otot. Laring dilapisi oleh membran mukosa.6 Batas laring adalah aditus laring, sedangkan batas bawahnya adalah batas kaudal kartilago krikoid. Bangunan kerangka laring tersusun dari satu tulang yaitu tulang hyoid dan beberapa buah tulang rawan. Tulang hyoid berbentuk seperti huruf U yang permukaan atasnya dihubungkan dengan lidah, mandibula dan tengkorak oleh tendo dan otot-otot. Sewaktu menelan, kontraksi otot-otot ini akan menyebabkan laring tertarik keatas sedangkan bila laring diam maka otot-otot ini bekerja untuk membuka mulut dan membantu menggerakkan lidah. Tulang rawan yang menyusun laring adalah kartilago epiglottis, kartilago krikoid, kartilago aritenoid, kartilago kornikulata, dan kartilago tiroid.6 Gerakan laring dilakukan oleh kelompok otot-otot ekstrinsik dan otot-otot intrinsik. Otot ekstrinsik laring ada yang terletak suprahioid dan infrahioid. Otot ekstrinsik terutama bekerja pada laring keseluruhan, sedangkan otot-otot intrinsik menyebabkan gerak bagian-bagian laring sendiri. Otot-otot ekstrinsik laring yang
suprahioid berfungsi menarik laring ke bawah sedangkan yang infrahioid menarik laring ke atas.3 Batas atas cavum laring ialah aditus laring, batas bawah ialah bidang yang melalui pinggir bawah kartilago krikoid. Batas depan ialah permukaan belakang epiglottis, tuberkulum epiglotik, ligamentum tiroepiglotik, sudut antara
keduabelah lamina kartilago tiroid dan arkus kartilago krikoid. Batas lateral ialah membrane kuadraangularis, kartilago aritenoid, konus elastikus, dan arkus kartilago krikoid sedangkan batas belakangnya ialah m. aritenoid transverses dan lamina kartilago krikoid. Adanya lipatan mukosa pada ligamentum vocal dan ligamentum ventrikulare maka terbentuk plika vokalis dan plika ventrikularis. Bidang antara plika vokalis kanan dan kiri disebut rima glottis sedangkan antara kedua plika ventrikularis disebut rima vestibule. Plika vokalis dan plika ventrikularis membagi rongga laring dalam tiga bagian, yaitu vestibulum laring, glotik dan subglotik.3 Laring dipersarafi oleh cabang-cabang n. vagus yaitu n. laringis superior dan n.laringis inferior. Perdarahan laring terdiri dari 2 cabang yaitu a. laringis superior dan a. laringis inferior.3
Gambar 2. Anatomi pita suara7
2.2 Fisiologi Laring Laring berfungsi untuk proteksi, batuk, respirasi, sirkulasi, menelan, emosi serta fonasi. Pembentukan suara merupakan fungsi laring yang paling kompleks. Pemantauan suara dilakukan melalui umpan balik yang terdiri dari telinga manusia dan suatu sistem dalam laring sendiri. Fungsi fonasi dengan membuat suara serta menentukan tinggi rendahnya nada. Tinggi rendahnya nada diatur oleh peregangan plika vokalis. Syarat suara nyaring yaitu anatomi korda vokalis normal dan rata, fisiologis harus normal dan harus ada aliran udara yang cukup kuat. 8,9,10 Terdapat 3 fase dalam berbicara: pulmonal (paru), laringeal (lariynx), dan supraglotis/oral. Fase pulmonal menghasilkan aliran energi dengan inflasi dan ekspulsi udara. Aktivitas ini memberikan kolom udara pada laring untuk fase laringeal. Pada fase laringeal, pita suara bervibrasi pada frekuensi tertentu untuk membentuk suara yang kemudian di modifikasi pada fase supraglotik/oral. Kata (word) terbentuk sebagai aktivitas faring (tenggorok), lidah, bibir, dan gigi. Disfungsi pada setiap stadium dapat menimbulkan perubahan suara, yang mungkin saja di interpretasikan sebagai hoarseness oleh seseorang/penderita.11 Adapun perbedaan frekuensi suara dihasilkan oleh kombinasi kekuatan ekspirasi paru dan perubahan panjang, lebar, elastisitas, dan ketegangan pita suara. Otot adduktor laringeal adalah otot yang bertanggung jawab dalam memodifikasi panjang pita suara. Akibat aktivitas otot ini, kedua pita suara akan merapat (aproksimasi), dan tekanan dari udara yang bergerak menyebabkan vibrasi dari pita suara yang elastik.11 Laring khususnya berperan sebagai penggetar (vibrator). Elemen yang bergetar adalah pita suara. Pita suara menonjol dari dinding lateral laring ke arah tengah dari glotis. pita suara ini diregangkan dan diatur posisinya oleh beberapa otot spesifik pada laring itu sendiri. 12
Gambar 3. Fisiologi suara12
Gambar 12 B, menggambarkan pita suara. Selama pernapasan normal, pita akan terbuka lebar agar aliran udara mudah lewat. Selama fonasi, pita menutup bersama-sama sehingga aliran udara diantara mereka akan menghasilkan getaran (vibrasi). Kuatnya getaran terutama ditentukan oleh derajat peregangan pita, juga oleh bagaimana kerapatan pita satu sama lain dan oleh massa pada tepinya.12 Gambar 12 A, memperlihatkan irisan pita suara setelah mengangkat tepi mukosanya. Tepat di sebelah dalam setiap pita terdapat ligamen elastik yang kuat dan disebut ligamen vokalis. Ligamen ini melekat pada anterior dari kartilago tiroid yang besar, yaitu kartilago yang menonjol dari permukaan anterior leher dan (Adams Apple). Di posterior,ligamen vokalis terlekat pada prosessus vokalis dari kedua kartilago aritenoid. Kartilago tiroid dan kartilago aritenoid ini kemudian berartikulasi pada bagian bawah dengan kartilago lain, yaitu kartilago krikoid. 12 Pita suara dapat diregangkan oleh rotasi kartilago tiroid ke depan atau oleh rotasi posterior dari kartilago aritenoid, yang diaktivasi oleh otot- otot dari kartilago tiroid dan kartilago aritenoid menuju kartilago krikoid. Otot-otot yang terletak di dalam pita suara di sebelah lateral ligament vokalis, yaitu otot tiroaritenoid, dapat mendorong kartilago aritenoid ke arah kartilago tiroid dan, oleh karena itu, melonggarkan pita suara. Pemisahan otot-otot ini juga dapat
mengubah bentuk dan massa pada tepi pita suara, menajamkannya untuk menghasilkan bunyi dengan nada tinggi dan menumpulkannya untuk suara yang lebih rendah (bass). Akhirnya, masih terdapat beberapa rangkaian lain dari otot laryngeal kecil yang terletak di antara kartilago aritenoid dan kartilago krikoid, yang dapat merotasikan kartilago ini ke arah dalam atau ke arah luar atau mendorong dasarnya bersama-sama atau memisahkannya, untuk menghasilkan berbagai konfigurasi pita suara.12
2.3 Suara serak (hoarseness) Kelainan yang berasal dari fase oral dan fase paru tidak dianggap sebagai hoarseness. True hoarseness atau suara serak yang sebenarnya, berasal dari abnormalitas pada laring dan umumnya menghasilkan suara yang kasar (raspy voice).11 Di bawah ini terdapat berbagai istilah untuk mengkarakteristikan hoarseness atau perubahan kualitas suara:11 1. Disfonia: digunakan untuk menggambaran perubahan umum kualitas suara 2. Diplofonia: Menggambarkan suara yang dibentuk oleh vibrasi pita suara menghasilkan 2 frekuensi yang berbeda 3. Afonia: Terjadi jika tidak ada suara di hasilkan oleh pita suara. Ini sering terjadi sekunder terhadap tidak adanya aliran udara melalui pita suara, atau defisiensi dalam aproksimasi pita suara. 4. Stridor: Mengindikasikan bising yang dihasilkan dari saluran penapasan atas selama inspirasi dan/atau ekspirasi karena adanya obstruksi. Stridor menandai keadaan emergensi, dan tidak dipertimbangkan sebagai hoarseness. Artinya mungkin saja muncul bersamaan dengan hoarseness jika obstruksi terjadi di level pita suara.
Suara serak dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu: onset akut dan onset kronis. Onset akut lebih sering terjadi dan biasanya karena peradangan lokal pada laring. Onset kronis (Laringitis kronis), dapat disebabkan refluks faringeal, polip
jinak, nodul pita suara, papilomatosis laring, tumor, defisit neurologis, ataupun peradangan kronis sekunder karena asap rokok atau voice abuse. 11 Penyebab suara parau dapat bermacam-macam yang prinsipnya menimpa laring dan sekitarnya. Penyebab suara serak dapat dibagi atas:10 1. Anatomi tidak normal 2. Fisiologi tidak normal, dibagi 2 yaitu: 2.1 Korda vokalis tidak dapat bergerak ke medial (paralise, fiksasi aritenoid) 2.2 Korda vokalis tidak dapat merapat ke median (korda vokalis konkaf, adanya halangan untuk merapat). Penyebab suara serak tersering, yaitu: 11 Laringitis akut viral Nodul pita suara, polip, kista, papiloma Paralisis pita suara Hipotiroidisme Rhinosinusitis Kanker laring Refluks laringofaringeal Tindakan Intubasi Alergi
Penyakit sistemik yang dapat mempengaruhi suara dan menyebabkan suara serak yaitu Hipotirodisme, Multiple sklerosis, Rematoid arthritis, Penyakit Parkinson, Lupus sistemik, Wagener's granulomatosis, Miasenia Gravis, Sarkoidosis, dan Amiloidosis.11 Radang laring dapat akut atau kronik. Radang akut biasanya disertai gejala lain seperti demam, malaise, nyeri menelan atau nyeri bicara, batuk, disamping suara parau. Kadang-kadang dapat terjadi sumbatan laring dengan gejala stridor serta cekungan di epigastrium, sela iga dan sekitar klavikula. Radang kronik tidak spesifik, dapat disebabkan oleh sinusitis kronik atau bronkitis kronik atau karena penggunaan suara sperti berteriakteriak atau biasa bicara keras. Radang kronik
spesifik misalnya tuberkulosa dan lues. Gejala selain suara parau, terdapat juga gejala penyakit penyebab lain atau penyakit yang menyertainya.11 Tumor laring dapat jinak atau ganas. Gejala tergantung dari lokasi tumor, misalnya tumor pita suara segera timbul suara parau dan bila tumor tumbuh menjadi besar menimbulkan sumbatan jalan nafas.8 Paralisis otot laring dapat disebabkan oleh gangguan persarafan baik sentral maupun perifer dan biasanya paralisis motorik bersama dengan paralisis sensorik. Kejadiannya dapat unilateral atau bilateral.8 Paralisis pita suara merupakan kelainan otot intrinsik laring yang sering ditemukan dalam klinik. Tingkat pembukaan rima glottis dibedakan dalam 5 posisi pita suara yaitu median, para median, intermedian, abduksi ringan, dan abduksi penuh. Menurut jenis otot yang terkena dikenal paralisis aduktor atau paralisis abduktor atau paralisis tensor. Sedangkan penggolongan menurut jumlah otot yang terkena dibagi atas paralisis sempurna atau tidak sempurna.8 Secara klinik paralisis otot laring dikenal unilateral midline paralisis, unilateral incomplete paralysis, bilateral midline paralisis, bilateral incomplete paralisis, adductor paralisis, thyroarythenoid muscle paralysis, dan cricotyroid muscle paralysis. 8
2.4 Diagnosis Setiap keadaan yang menimbulkan gangguan dalam getaran, gangguan dalam ketegangan serta gangguan dalam pendekatan kedua pita suarakiri dan kanan akan menimbulkan suara parau. Walaupun suara parau hanya merupakan gejala tetapi bila prosesnya berlangsung lama (kronik) keadaan ini dapat merupakan tanda awal dari penyakit yang serius di daerah tenggorok, khususnya laring. 8 Penentuan diagnosis dimulai dari anamnesa yang lengkap. Anamnesa meliputi keluhan saat ini, riwayat keluhan sebelumnya yang berkaitan dengan keluhan yang dialami sekarang. Pada disfonia dapat ditanyakan riwayat penggunaan suara berlebih, riwayat trauma, dan riwayat penyakit sistemik. 13 Pemeriksaan klinik meliputi pemeriksaan umum (status generalis), pemeriksaan THT termasuk pemeriksaan laring tak laingsung untuk melihat laring
melalui kaca laring, maupun pemeriksaan laring langsung dengan laringoskop (atau dengan mikroskop). 8 Pemeriksaan penunjang yang diperlukan meliputi pemeriksaan laboratorium klinik, radiologik, mikrobiologik dan patologi anatomi. Pemeriksaan darah, pemeriksaan leukositosis pada infeksi akut, BTA pada biakan laryngitis tuberculosis, histopatologi untuk kasus tumor, dan CT scan pada karsinoma laring. 8,13
2.5 Penatalaksanaan suara serak Penatalaksanaan suara serak dilakukan setelah penyakit terdiagnosis. Sehingga penatalaksaan dapat dilakukan secara tepat sesuai diagnosis. Penatalaksanaan suara serak, yaitu: 13 1. Secara khusus yaitu eradikasi infeksi dan inflamasi Pemberian obat antibiotika, antiinflamasi, anti TB pada laring TB dan antasida pada penyakit reflux gastro-esofagitis (GERD). 2. Koreksi bedah (phonosurgery) a. Mikrolaringoskopi pada tumor jinak laring (vocal thyroplasty, arytenoids adduction) b. Laringektomi pada karsinoma laring 3. Rehabilitasi Terapi suara / wicara (oleh unit rehabilitasi medic). Tujuan: Memperbaiki kualitas suara (para paresis pita suara) Dapat berkomunikasi secara verbal (pada pasien pasca laringektomi) nodul,
LARINGITIS Penatalaksanaan pada laringitis terbagi atas perawatan umum dan perawatan khusus. Perawatan umum, yaitu: 14 1. Istirahat bicara dan bersuara selama 2-3 hari 2. Dianjurkan menghirup udara lembab 3. Menghindari iritasi pada faring dan laring, misalnya merokok, makan pedas atau minum dingin
10
4. Penderita dapat berobat jalan. Bila ada sumbatan jalan nafas, penderita harus dirawat terutama anak-anak Perawatan khusus, yaitu: 14 1. Terapi medikamentosa o Antibiotika golongan penisilin o Anak 50 mg/kgBB dibagi dalam 3 dosis o Dewasa 3x500 mg /hari o Bila alergi terhadap penisilin dapat diberikan eritromisin atau bactrim o Kortikosteroid dapat diberikan untuk mengatasi edem laring 2. Terapi bedah Tergantung pada stadium sumbatan laring. Pada anak bila terjadi gejala sumbatan jalan nafas menurut klasifikasi Jackson, dilakukan terapi sebagai berikut:15 Stadium I : Rawat, observasi, pemberian oksigen dan terapi adekuat
Stadium II-III : Trakheostomi Stadium IV : Intubasi dan oksigenasi, kemudian dilanjutkan dengan
Trakeostomi Pada laringitis kronis penatalaksanaan yaitu menghindari dan mengobati faktor-faktor penyebab dengan: 15 1. Istirahat bersuara (vocal rest), tidak banyak bicara atau bersuara keras 2. Antibiotika, bila terdapat tanda infeksi 3. Ekspektoran Dapat pula dilakukan pengangkatan jaringan yang menebal dan polipoid serta pemeriksaan patologi anatomik untuk menyingkirkan kemungkinan proses spesifik dan keganasan. 14 Penatalaksanaan laringitis tuberkulosa, yaitu: 15 1. Anti-TB seperti streptomisin , asam paraamino salisilat dan rifampisin. Jika timbul keluhan tinnitus atau vertigo, waspada terhadapat
kemungkinan intoksikasi obat. 2. Istirahat suara 3. Trakeostomi bila timbul sumbatan jalan nafas
11
Penatalaksanaan laringitis sifilis yaitu dengan pemberian penisilin dosis tinggi dalam jangka waktu lama.
NODUL VOKAL Penanganan nodul vocal adalah istirahat suara dan tidak merokok. Pada kasus yang persisten dapat dilakukan pengangkatan nodul dengan
mikrolaringoskopi. Setelah pengangkatan nodul, pasien harus istirahat suara paling kurang 14 hari dan setelah itu terapi wicara untuk mencegah kekambuhan.
15
TUMOR LARING Secara umum ada 3 jenis penanggulangan karsinoma laring yaitu pembedahan, radiasi dan sitostatika, ataupun kombinasi. 16 1. Pembedahan Tindakan operasi untuk keganasan laring terdiri dari :
12
a. Laringektomi 1. Laringektomi parsial Laringektomi parsial diindikasikan untuk karsinoma laring stadium I yang tidak memungkinkan dilakukan radiasi, dan tumor stadium II. 2. Laringektomi total Tindakan pengangkatan seluruh struktur laring mulai dari batas atas (epiglotis dan os hioid) sampai batas bawah cincin trakea.
b. Diseksi leher radikal Tidak dilakukan pada tumor glotis stadium dini (T1 T2) karena kemungkinan metastase ke kelenjar limfe leher sangat rendah. Sedangkan tumor supraglotis, subglotis dan tumor glotis stadium lanjut sering kali mengadakan metastase ke kelenjar limfe leher sehingga perlu dilakukan tindakan diseksi leher. Pembedahan ini tidak disarankan bila telah terdapat metastase jauh. Perawatan pasca operatif, yaitu: 17 - Penderita makan melalui pipa hidung lambung selama 2 minggu, dilarang menelan ludah. - Pemberikan antibiotika o Garamycin 80 mg IV/2x perhari selama 7 hari atau kedacillin atau clafucillin o Metronidazol 3 x 500 mg - Perawatan luka operasi dengan disertai balut tekan
2. Radioterapi Radioterapi digunakan untuk mengobati tumor glotis dan supraglotis T1 dan T2 dengan hasil yang baik (angka kesembuhannya 90%). Keuntungan dengan cara ini adalah laring tidak cedera sehingga suara masih dapat dipertahankan. Dosis yang dianjurkan adalah 200 rad perhari sampai dosis total 6000 7000 rad. adioterapi dengan dosis menengah telah pula dilakukan oleh Ogura, Som, Wang, dkk, untuk tumor-tumor tertentu. Konsepnya adalah untuk memperoleh kerusakan maksimal dari tumor tanpa kerusakan yang tidak dapat disembuhkan pada
13
jaringan yang melapisinya. Wang dan Schulz memberikan 45005000 rad selama 46 minggu diikuti dengan laringektomi total.16
3. Kemoterapi Diberikan pada tumor stadium lanjut, sebagai terapi adjuvant ataupun paliativ. Obat yang diberikan adalah cisplatinum 80120 mg/m2 dan 5 FU 800 1000 mg/m2. 16
4. Rehabilitasi Rehabilitasi setelah operasi sangat penting karena telah diketahui bahwa tumor ganas laring yang diterapi dengan seksama memiliki prognosis yang baik. rehabilitasi mencakup Vocal Rehabilitation, Vocational Rehabilitation dan Social Rehabilitation. 16
PARALISIS KORDA VOKALIS Penatalaksanaan paralisis korda vokalis sensorik biasanya tidak ada. Penderita dapat diberikan obat neurotika atau methylcobalamin. 18 Penatalaksanaan paralisis korda vokalis motorik, terdiri dari pembedahan dan terapi suara. Pada beberapa kasus, suara dapat kembali normal dalam satu tahun tanpa pengobatan apapun. Oleh karena itu pada beberapa kasus, terapi pembedahan ditunda selama satu tahun untuk memastikan suara dapat kembali secara spontan atau tidak. Untuk sementara dilakukan terapi suara dengan tujuan
14
untuk memperkuat koda vokalis atau mengendalikan udara yang keluar saat bicara. 19 Penatalaksanaan paralisis unilateral korda vokalis dengan tujuan membuat korda yang paralisis ke tengah dan mengurangi jarak antara kedua korda sehingga suara dapat keluar. Terdapat 3 prosedur pembedahan yang sering digunakan, yaitu: 19,20,21 1. Medialisasi tiroplasty Biasa dilakukan dengan local anastesi dan sedasi sehingga saat pembedahan dapat mendapatkan suara pasien. Insisi dilakukan dileher dan diperdalam sampai kartilago tiroid. Prostesis yang sering digunakan menggunakan bahan silikon. Prostesis ini dimasukkan dan mendorong korda yang paralisis ke tengah sehingga mengurangi jarak antara kedua korda vokalis. 2. Aduksi arytenoids Aduksi aritenoid yaitu dengan reposisi korda vokalis dan kartilago. 3. Injeksi korda vokalis Dilakukan penyuntikan bahan pada korda vokalis. Bahan yang paling seing digunakan disuntikkan yaitu Teflon. Bahan lain yaitu kolagen, silikon, atau lemak tubuh. Penambahan materi ini dengan tujuan untuk mengurangi jarak antara korda vokalis sehingga korda yang normal dapat mendekati korda vokalis yang paralisis. Pada umumnya, bilateral midline paralisis terjadi setelah operasi tiroid akibat cedera nervus laringeus rekuren pada operasi tiroid dan bermanifestasi sebagai paralisis plika vokalis bilateral yang berada pada linea mediana. Awalnya, pita suara terletak pada posisi paramedian, sehingga terjadi gejala disfoni berat walaupun tanpa obstruksi saluran napas. Setelah beberapa lama, pita suara berpindah perlahan-lahan ke garis tengah dengan akibat perbaikan suara namun terjadi sesak napas. Pada laringoskopi tidak langsung dan langsung dapat terlihat kelumpuhan bilateral pita suara. Pada kasus yang bukan disebabkan oleh trauma, fungsi satu atau kedua pita suara mungkin dapat membaik secara spontan. Penyembuhan spontan lebih sulit jika kelumpuhan disebabkan oleh trauma bedah atau cedera leher berat. Waktu
15
yang diperlukan sampai terjadinya peralihan sesak napas berat bervariasi antara beberapa hari sampai 20 tahun. 20 Penanganan bervariasi tergantung pada gejala namun tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan sesak napas. Penatalaksanaan bilateral paralisis harus dilakukan trakeotomi untuk membantu pernafasan. 19,22
BAB III PENUTUP
Suara serak berasal dari abnormalitas pada laring dan umumnya menghasilkan suara yang kasar. Suara serak dapat dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu: onset akut dan onset kronis. Onset akut lebih sering terjadi dan biasanya karena peradangan lokal pada laring. Onset kronis, dapat disebabkan refluks faringeal, polip jinak, nodul pita suara, papilomatosis laring, tumor, defisit neurologis, ataupun peradangan kronis sekunder karena asap rokok. Untuk menegakan diagnosis suatu penyakit dengan gajala suara serak dapat diperoleh dari anamnesa, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Sehingga dapat diperoleh suatu diagnosis yang tepat. Beberapa penatalaksanaan suara serak adalah secara khusus yaitu eradikasi infeksi dan inflamasi, koreksi bedah (phonosurgery), atau rehabilitasi. Penatalaksanaan suara serak dilakukan setelah penyakit terdiagnosis. Sehingga penatalaksaan dapat dilakukan secara tepat sesuai diagnosis.
16
DAFTAR PUSTAKA
1. Diza, Miralza. Suara serak. [online] 2008. Available from: http://d132a.wordpress.com 2. Hermani, Bambang. Keganasan laring [online] Desember 2007. Available from: www.majalah- farmacia .com 3. Banvetz JD. Gangguan laring jinak Dalam BOIES buku ajar penyakit TH edisi 6. Jakarta: EGC, 1994. 4. Ryan,Matthew. Surgical Treatment of Laringomalacia. University of Texas Medical Branch. 2005. 5. Anonymous. Laryng (online) Available at www.academic kellog.cc.mi.us 6. Snell RS. Anatomi klinik untuk mahasiswa kedokteran edisi 6. Jakarta: EGC, 2006. 7. Anonymous. Normal laryng (online) Available at
www.voiceandswallowing.com 8. Hermani B, Kartosoediro S. Suara parau dalam buku ajar ilmu penyakit THT edisi ketiga. Jakarta: FKUI, 1997. 9. Cohen JI. Anatomi dan fisiologi laring dalam BOIES buku ajar penyakit THT edisi . Jakarta: EGC, 1994.
17
10. Hajati, NL. Bahan kuliah laring. Banjarmasin: Bagian THT FK UNLAM/RSUD Ulin. 11. Megantara, Imam. Suara serak [online] Agustus 2008. Available from: http://imammegantara.blogspot.com 12. Anonymous. Fisiologi pengunyahan, penelanan dan bicara [online]. Available from: http://www.scribd.com 13. Hermani, Bambang. Disfonia. Jakarta: Sub Divisi Laring Faring Departemen THT FKUI/RSCM. 14. Hermani, Bambang. Laringitis akut dalam penatalaksanaan penyakit dan kelainan THT edisi ketiga. Jakarta: FKUI. 15. Hadiwikarta, A. Laringitis kronis dalam penatalaksanaan penyakit dan kelainan THT edisi ketiga. Jakarta: FKUI. 16. Haryuna TSH. Tumor ganas laring. Sumatera Utara: Bagian PA FK USU. 17. Munir M, Abdurrachman H. Tumor ganas laring dalam penatalaksanaan penyakit dan kelainan THT edisi ketiga. Jakarta: FKUI. 18. Abdurrachman, Hartono. Paralisis laring dalam penatalaksanaan penyakit dan kelainan THT edisi ketiga. Jakarta: FKUI. 19. NIDCD. Vocal cord paralysis [online]. Available from:
http://www.nidcd.nih.gov 20. Anonymous. Vocal fold paralysis [online]. Available from:
http://www.ent.ufl.edu 21. Mayo clinic. Treatment of vocal cord paralysis www.mayoclinic.com 22. Perkasa, FM. The management of bilateral midline. Departement THT FK Universitas Hasanuddin Makassar [online]. Available from:
http://www.med.unhas.ac.id
18
ANATOMI7,8,9 Laring dibentuk oleh sebuah tulang di bagian atas dan beberapa tulang rawanyang saling berhubungan satu sama lain dan diikat oleh otot intrinsik dan ekstrinsik serta dilapisi oleh mukosa. Tulang dan tulang rawan laring yaitu : os Hioid: terletak paling atas, berbentuk huruf U, mudah
diraba pada leher bagian depan. Pada kedua sisi tulang ini terdapat prosesus longus dibagian belakang dan prosesus brevis bagian depan. Permukaan bagian atas tulang ini melekat pada otot-otot lidah, mandibula dan tengkorak.2. Kartilago tiroid : merupakan tulang rawan laring yang terbesar, terdiri dari dua lamina yang bersatu di bagian depan dan mengembang ke arah belakang. Kartilago Krikoid : terletak di belakang kartilago tiroid dan merupakan tulang rawan paling bawah dari laring. Di setiap sisi ligamentum dan di bagian krikoaritenoid, belakang otot melekat
tulang rawan krikoid melekat krikoaritenoid lateral
otot krikoaritenoid posterior. Otot-otot laring terdiri dari 2 golongan besar, yaitu : Otot-otot ekstrinsik : Otot elevator :M. Milohioid, M. Geniohioid, M. Digrastikus dan M. Stilohioid Otot depressor :-M. Omohioid, M. Sternohioid dan M. Tirohioid. Otot-otot Intrinsik : Otot Adduktor dan Abduktor
M. Krikoaritenoid, M. Aritenoid oblique dan transversum Otot yang mengatur tegangan ligamentum vokalis
:M. Tiroaritenoid, M. Vokalis, M. Krikotiroid Otot yang mengatur pintu masuk laring :M. Ariepiglotik, M. Tiroepiglotik.
19
Anda mungkin juga menyukai
- Ocd AinaDokumen28 halamanOcd AinaNurul AinaBelum ada peringkat
- Paresis Paralisis Plika VokalisDokumen13 halamanParesis Paralisis Plika VokalisEdelyn C. Iskandar100% (1)
- Referat - Paresis Plika VokalisDokumen21 halamanReferat - Paresis Plika VokalisDesiana AyuBelum ada peringkat
- Hoarseness. Revisi DR IvanDokumen14 halamanHoarseness. Revisi DR IvanMaulana Okta RhezaBelum ada peringkat
- Css Trauma Thorax - WordDokumen42 halamanCss Trauma Thorax - WordBilla NabillaBelum ada peringkat
- DisfoniaDokumen30 halamanDisfoniamirandadaBelum ada peringkat
- DisartriaDokumen50 halamanDisartriaMay MaghdalenaBelum ada peringkat
- Refrat RM Pbi WidaDokumen40 halamanRefrat RM Pbi WidaWidaRiniHarunoBelum ada peringkat
- Referat Fisologi MenelanDokumen15 halamanReferat Fisologi Menelanmuhammad sholihuddinBelum ada peringkat
- HemangioblastomaDokumen20 halamanHemangioblastomaPriskaApril100% (1)
- Referat OtotoksikDokumen14 halamanReferat OtotoksikWidodo SaputraBelum ada peringkat
- Catatan Neurologi Polri PDFDokumen22 halamanCatatan Neurologi Polri PDFNofilia Citra CandraBelum ada peringkat
- Lobus Temporal (Presentasi)Dokumen9 halamanLobus Temporal (Presentasi)zack zackBelum ada peringkat
- Refarat Gangguan Jiwa Pada AnakDokumen40 halamanRefarat Gangguan Jiwa Pada AnakputriBelum ada peringkat
- Referat DiensefalonDokumen15 halamanReferat DiensefalonMuhammad Azhary LazuardyBelum ada peringkat
- Sistem Saraf (Print File)Dokumen119 halamanSistem Saraf (Print File)Indah Permata SariBelum ada peringkat
- Ilmu PskiatriDokumen60 halamanIlmu PskiatrimeikisirmanBelum ada peringkat
- Jurnal Kranial ArteritisDokumen8 halamanJurnal Kranial ArteritisyosihariantiBelum ada peringkat
- Kelumpuhan Pita SuaraDokumen3 halamanKelumpuhan Pita SuaraRyanIndraSaputraBelum ada peringkat
- Kasus Tumor CPADokumen4 halamanKasus Tumor CPAAvisena AzisBelum ada peringkat
- Vocal Overuse and MisuseDokumen21 halamanVocal Overuse and Misusefrsiscaselvia100% (1)
- 7crirfcr 8yfitcrcuDokumen4 halaman7crirfcr 8yfitcrcuZahra Mardhaatillah100% (1)
- Pengayaan - Post Traumatic AmnesiaDokumen19 halamanPengayaan - Post Traumatic AmnesiaNabilah Hanifah MBelum ada peringkat
- Terapi Rehabilitasi KeseimbanganDokumen5 halamanTerapi Rehabilitasi KeseimbanganRani Tiyas BudiyantiBelum ada peringkat
- Cedera Medulla SpinalisDokumen9 halamanCedera Medulla SpinalisAnonimBelum ada peringkat
- Rehabilitasi Medik Pada Penderita ParkinsonDokumen8 halamanRehabilitasi Medik Pada Penderita ParkinsonDwi Wahyu Setyo IrawanBelum ada peringkat
- Reff ThalamusDokumen20 halamanReff ThalamusGde LeoBelum ada peringkat
- Referat Tic FasialisDokumen16 halamanReferat Tic FasialisAlwis AsidiqBelum ada peringkat
- Case Bipolar I - PsikiatriDokumen34 halamanCase Bipolar I - PsikiatriCharlos Yosua Christian MewengkangBelum ada peringkat
- Refarat ASSR 2Dokumen34 halamanRefarat ASSR 2Yunita HamdaniBelum ada peringkat
- Tugas Referat CraniosinostosisDokumen8 halamanTugas Referat CraniosinostosisYaasin R NBelum ada peringkat
- Sindrom Gradenigo Pada OMSK Tipe Bahaya - YurniDokumen9 halamanSindrom Gradenigo Pada OMSK Tipe Bahaya - YurniKabir MuhammadBelum ada peringkat
- Sari PustakaDokumen36 halamanSari PustakaAde IndrawanBelum ada peringkat
- Gangguan Psikiatri AnakDokumen27 halamanGangguan Psikiatri Anak-NurmayuImdaSimatupang-Belum ada peringkat
- Peran Cerebral Digital Subtraction Angiography (C-Dsa) Untuk Menegakkan Kelainan Di Bidang NeurologiDokumen8 halamanPeran Cerebral Digital Subtraction Angiography (C-Dsa) Untuk Menegakkan Kelainan Di Bidang NeurologiIgor HermandoBelum ada peringkat
- Referat Radiologi HNPDokumen103 halamanReferat Radiologi HNPbambang kentoletBelum ada peringkat
- Atelektasis IsiDokumen35 halamanAtelektasis IsiNi Made AyuNathasariBelum ada peringkat
- Radiologi NeoplasmaDokumen22 halamanRadiologi NeoplasmaLukluk RHbabyshopBelum ada peringkat
- Proses Penyembuhan FrakturDokumen21 halamanProses Penyembuhan FrakturTata Tamara Tam TamBelum ada peringkat
- Tumor SupratentorialDokumen40 halamanTumor SupratentorialEkacitra Galiz100% (1)
- Referat Neurobehavior Pada EpilepsiDokumen15 halamanReferat Neurobehavior Pada EpilepsiIndra SilaenBelum ada peringkat
- 3.Dr. Mirna - KELAINAN KONGENITAL SSP - Mirna Sobana Utk Panitia MABIDokumen32 halaman3.Dr. Mirna - KELAINAN KONGENITAL SSP - Mirna Sobana Utk Panitia MABIAdityaBelum ada peringkat
- CHOLEASTOMADokumen28 halamanCHOLEASTOMAmaya lubisBelum ada peringkat
- 13.neuroimaging Dan Musculoskeletal ImagingDokumen100 halaman13.neuroimaging Dan Musculoskeletal ImagingMuhammad HasanBelum ada peringkat
- Celah PalatumDokumen53 halamanCelah PalatumEndro Ri WibowoBelum ada peringkat
- Referat Sympathetic OphthalmiaDokumen25 halamanReferat Sympathetic OphthalmiaDevin AlexanderBelum ada peringkat
- Obstructive Sleep ApneaDokumen22 halamanObstructive Sleep ApneaIckha WulandaryBelum ada peringkat
- Karakteristik Gangguan Tidur Pada Penyakit Parkinson Berdasarkan Parkinson Disease SleepDokumen8 halamanKarakteristik Gangguan Tidur Pada Penyakit Parkinson Berdasarkan Parkinson Disease SleepAfifa NingrumBelum ada peringkat
- Papper RadiologiDokumen15 halamanPapper RadiologiFahmy zaeni dahlanBelum ada peringkat
- Referat GBM Abdul Hakam 1910017003Dokumen24 halamanReferat GBM Abdul Hakam 1910017003hakam asyafaqBelum ada peringkat
- Materi Dasar 4 - Etiologi Dan Tatalaksana Gangguan Pendengaran Dan KeseimbanganDokumen46 halamanMateri Dasar 4 - Etiologi Dan Tatalaksana Gangguan Pendengaran Dan KeseimbanganAsiatiBelum ada peringkat
- OTOTOKSIKDokumen23 halamanOTOTOKSIKsantri safiraBelum ada peringkat
- Korteks Motorik Dan Homonkulus MotorikDokumen2 halamanKorteks Motorik Dan Homonkulus MotorikPatricia VirginiaBelum ada peringkat
- Paper Trigeminal NeuralgiaDokumen16 halamanPaper Trigeminal NeuralgiaMuhammad Yamin LBelum ada peringkat
- KuesionerDokumen17 halamanKuesionerMohammad HayatBelum ada peringkat
- Penatalaksanaan Suara SerakDokumen23 halamanPenatalaksanaan Suara Serakdina aulia insaniBelum ada peringkat
- Nodul Pita SuaraDokumen9 halamanNodul Pita SuaraWiduri PratamaBelum ada peringkat
- LaringitisDokumen17 halamanLaringitisDovi Pratama100% (1)
- Anatomi Dan Fisiologi MuskuloskeletalDokumen48 halamanAnatomi Dan Fisiologi Muskuloskeletalemilia_khairaniBelum ada peringkat
- Referat Suara Serak THT RidwanDokumen26 halamanReferat Suara Serak THT Ridwanardiansandhi100% (1)
- Sindrom-Terowongan-Carpal (RAJA)Dokumen14 halamanSindrom-Terowongan-Carpal (RAJA)Raya KurniawanBelum ada peringkat
- Asma Akibat KerjaDokumen17 halamanAsma Akibat KerjaRaya KurniawanBelum ada peringkat
- Contoh VeRDokumen4 halamanContoh VeRRaya KurniawanBelum ada peringkat
- Pleura Adalah Membran Serosa Yang LicinDokumen2 halamanPleura Adalah Membran Serosa Yang LicinRaya KurniawanBelum ada peringkat
- Presentasi Prolaps RektumDokumen36 halamanPresentasi Prolaps RektumRaya KurniawanBelum ada peringkat
- Pneumothorax PenyuDokumen27 halamanPneumothorax PenyuRaya KurniawanBelum ada peringkat
- SUARA SERAK PresentasiDokumen41 halamanSUARA SERAK PresentasiRaya KurniawanBelum ada peringkat
- Presentasi Prolaps RektumDokumen36 halamanPresentasi Prolaps RektumRaya KurniawanBelum ada peringkat
- Laporan Kasus Heg Dr. YanDokumen13 halamanLaporan Kasus Heg Dr. YanRaya KurniawanBelum ada peringkat
- Referat Prolaps RektumDokumen18 halamanReferat Prolaps RektumRaya KurniawanBelum ada peringkat