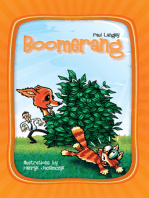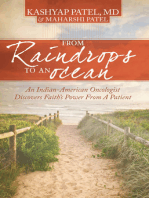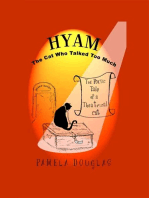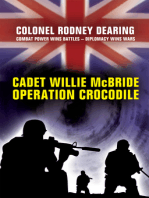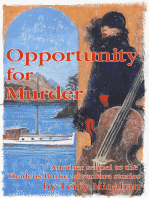Tokoh
Diunggah oleh
DwieVAdmadjaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Tokoh
Diunggah oleh
DwieVAdmadjaHak Cipta:
Format Tersedia
Tokoh-Tokoh Nasional Dan Daerah Dalam Perjuangan Menegakkan Negara Republik Indonesia
Pangeran Dipanegara, juga sering dieja Diponegoro (lahir di Yogyakarta, 11 November 1785
meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 Januari 1855pada umur 69 tahun) adalah salah seorang pahlawan
nasional Republik Indonesia. Pangeran Diponegoro terkenal karena memimpin Perang Diponegoro/Perang
Jawa (1825-1830) melawan pemerintah Hindia-Belanda. Perang tersebut tercatat sebagai perang dengan
korban paling besar dalam sejarah Indonesia.
Riwayat perjuangan
Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Dipanegara di desa
Tegalrejo. Saat itu, beliau memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat
setempat dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak.
Sikap Dipanegara yang menentang Belanda secara terbuka, mendapat simpati dan dukungan rakyat. Atas
saran Pangeran Mangkubumi, pamannya, Dipanegara menyingkir dari Tegalrejo, dan membuat markas di
sebuah goa yang bernama Goa Selarong. Saat itu, Dipanegara menyatakan bahwa perlawanannya adalah
perang sabil, perlawanan menghadapi kaum kafir. Semangat "perang sabil" yang dikobarkan Dipanegara
membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan danKedu. Salah seorang tokoh agama di Surakarta, Kyai
Maja, ikut bergabung dengan pasukan Dipanegara di Goa Selarong.Perjuangan Pangeran Dipanegara ini
didukung oleh S.I.S.K.S. Pakubuwono VI dan Raden Tumenggung Prawirodigdaya Bupati Gagatan.
Selama perang ini kerugian pihak Belanda tidak kurang dari 15.000 tentara dan 20 juta gulden.
Berbagai cara terus diupayakan Belanda untuk menangkap Dipanegara. Bahkan sayembara pun dipergunakan.
Hadiah 50.000 Gulden diberikan kepada siapa saja yang bisa menangkap Dipanegara. Sampai akhirnya
Dipanegara ditangkap pada 1830.
Nyi Ageng Serang bernama asli Raden Ajeng Kustiyah Wulaningsih Retno Edi (Serang, Purwodadi, Jawa
Tengah, 1752 - Yogyakarta, 1828) adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Ia adalah anak Pangeran
Natapraja yang menguasai wilayah terpencil dari kerajaan Mataram tepatnya di Serang yang sekarang wilayah
perbatasan Grobogan-Sragen. Setelah ayahnya wafat Nyi Ageng Serang menggantikan kedudukan ayahnya.
Nyi Ageng Serang adalah salah satu keturunan Sunan Kalijaga, ia juga mempunyai keturunan seorang
Pahlawan nasional yaitu Soewardi Soerjaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Ia dimakamkan di Kalibawang, Kulon
Progo. Ia pahlawan nasional yang hampir terlupakan,mungkin karena namanya tak sepopuler R.A. Kartini atau
Cut Nyak Dhien tapi beliau sangat berjasa bagi negeri ini.Warga Kulon Progo mengabadikan monumen beliau
di tengah kota Wates berupa patung beliau sedang menaiki kuda dengan gagah berani membawa tombak
Sisingamangaraja XII (lahir di Bakara, 18 Februari 1845 meninggal di Dairi,17 Juni 1907 pada umur 62
tahun) adalah seorang raja di negeri Toba,Sumatera Utara, pejuang yang berperang melawan Belanda,
kemudian diangkat oleh pemerintah Indonesia sebagai Pahlawan Nasional Indonesiasejak tanggal 9 November
1961 berdasarkan SK Presiden RI No 590/1961. Sebelumnya ia makamkan di Tarutung, lalu dipindahkan ke
Soposurung, Baligepada tahun 1953.[1]
Sisingamangaraja XII nama kecilnya adalah Patuan Bosar, yang kemudian digelari dengan Ompu Pulo Batu. Ia
juga dikenal dengan Patuan Bosar Ompu Pulo Batu, naik tahta pada tahun 1876 menggantikan ayahnya
Sisingamangaraja XI yang bernama Ompu Sohahuaon, selain itu ia juga disebut juga sebagai raja imam.
Penobatan Sisingamangaraja XII sebagai maharaja di negeri Toba bersamaan dengan dimulainya open door
policy (politik pintu terbuka) Belanda dalam mengamankan modal asing yang beroperasi di Hindia-Belanda,
dan yang tidak mau menandatangani Korte Verklaring (perjanjian pendek) di Sumatera terutama Kesultanan
Aceh dan Toba, di mana kerajaan ini membuka hubungan dagang dengan negara-negara Eropa lainya. Di sisi
lain Belanda sendiri berusaha untuk menanamkan monopolinya atas kerajaan tersebut. Politik yang berbeda
ini mendorong situasi selanjutnya untuk melahirkan Perang Tapanuli yang berkepanjangan hingga puluhan
tahun.
Perang melawan Belanda
Pada tahun 1877 para misionaris di Silindung dan Bahal Batu meminta bantuan kepada pemerintah kolonial
Belanda dari ancaman diusir oleh Singamangaraja XII. Kemudian pemerintah Belanda dan para penginjil
sepakat untuk tidak hanya menyerang markas Si Singamangaraja XII di Bakara tetapi sekaligus menaklukkan
seluruh Toba.
Pada tanggal 6 Februari 1878 pasukan Belanda sampai di Pearaja, tempat kediaman penginjil Ingwer Ludwig
Nommensen. Kemudian beserta penginjil Nommensen dan Simoneit sebagai penerjemah pasukan Belanda
terus menuju ke Bahal Batu untuk menyusun benteng pertahanan[butuh rujukan]. Namun kehadiran tentara
kolonial ini telah memprovokasi Sisingamangaraja XII, yang kemudian mengumumkan pulas (perang) pada
tanggal 16 Februari 1878 dan penyerangan ke pos Belanda di Bahal Batu mulai dilakukan.
Pada tanggal 14 Maret 1878 datang Residen Boyle bersama tambahan pasukan yang dipimpin oleh Kolonel
Engels sebanyak 250 orang tentara dariSibolga. Pada tanggal 1 Mei 1878, Bangkara pusat pemerintahan Si
Singamangaraja diserang pasukan kolonial dan pada 3 Mei 1878 seluruh Bangkara dapat ditaklukkan namun
Singamangaraja XII beserta pengikutnya dapat menyelamatkan diri dan terpaksa keluar mengungsi. Sementara
para raja yang tertinggal di Bakara dipaksa Belanda untuk bersumpah setia dan kawasan tersebut dinyatakan
berada dalam kedaulatan pemerintah Hindia-Belanda.
Walaupun Bakara telah ditaklukkan, Singamangaraja XII terus melakukan perlawanan secara gerilya, namun
sampai akhir Desember 1878 beberapa kawasan seperti Butar, Lobu Siregar, Naga Saribu, Huta Ginjang,
Gurgur juga dapat ditaklukkan oleh pasukan kolonial Belanda.
Antara tahun 1883-1884, Singamangaraja XII berhasil melakukan konsolidasi pasukannya[butuh rujukan].
Kemudian bersama pasukan bantuan dari Aceh, secara ofensif menyerang kedudukan Belanda antaranya
Uluan dan Balige pada Mei 1883serta Tangga Batu pada tahun 1884
Pattimura(atau Thomas Matulessy) (lahir di Haria, pulau Saparua,Maluku, 8 Juni 1783 meninggal di
Ambon, Maluku, 16 Desember 1817pada umur 34 tahun), juga dikenal dengan nama Kapitan Pattimuraadalah
pahlawan Maluku dan merupakan Pahlawan nasional Indonesia.
Menurut buku biografi Pattimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M Sapija menulis, "Bahwa
pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina (Seram). Ayah beliau yang
bernama Antoni Mattulessy adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Mattulessy. Yang terakhir ini adalah putra
raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan".
Namun berbeda dengan sejarawan Mansyur Suryanegara. Dia mengatakan dalam bukunya Api Sejarah bahwa
Ahmad Lussy atau dalam bahasa Maluku disebut Mat Lussy, lahir di Hualoy, Seram Selatan (bukan Saparua
seperti yang dikenal dalam sejarah versi pemerintah). Dia adalah bangsawan dari kerajaan Islam Sahulau, yang
saat itu diperintah Sultan Abdurrahman. Raja ini dikenal pula dengan sebutan Sultan Kasimillah (Kazim
Allah/Asisten Allah). Dalam bahasa Maluku disebut Kasimiliali.
Perjuangan
Sebelum melakukan perlawanan terhadap VOC ia pernah berkarier dalam militer sebagai mantan sersan
Militer Inggris.[3]Kata "Maluku" berasal dari bahasa Arab Al Mulk atau Al Malik yang berarti Tanah Raja-
Raja.[4] mengingat pada masa itu banyaknya kerajaan
Pada tahun 1816 pihak Inggris menyerahkan kekuasaannya kepada pihak Belanda dan kemudian Belanda
menetapkan kebijakan politik monopoli, pajak atas tanah (landrente), pemindahan penduduk serta pelayaran
Hongi (Hongi Tochten), serta mengabaikan Traktat London I antara lain dalam pasal 11 memuat ketentuan
bahwa Residen Inggris di Ambon harus merundingkan dahulu pemindahan koprs Ambon dengan Gubenur dan
dalam perjanjian tersebut juga dicantumkan dengan jelas bahwa jika pemerintahan Inggris berakhir di Maluku
maka para serdadu-serdadu Ambon harus dibebaskan dalam artian berhak untuk memilih untuk memasuki
dinas militer pemerintah baru atau keluar dari dinas militer, akan tetapi dalam pratiknya pemindahan dinas
militer ini dipaksakan [5] Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras
dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk
selama dua abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura
[4] Maka pada waktu pecah perang melawan penjajah Belanda tahun 1817, Raja-raja Patih, Para Kapitan, Tua-
tua Adat dan rakyat mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan
memiliki sifat-sfat kesatria (kabaressi). Sebagai panglima perang, Kapitan Pattimura mengatur strategi perang
bersama pembantunya. Sebagai pemimpin dia berhasil mengkoordinir Raja-raja Patih dalam melaksanakan
kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan dan membangun
benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para Raja Patih maupun
rakyat biasa. Dalam perjuangan menentang Belanda ia juga menggalang persatuan dengan kerajaan Ternate
dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi dan Jawa. Perang Pattimura yang berskala nasional itu dihadapi Belanda
dengan kekuatan militer yang besar dan kuat dengan mengirimkan sendiri Laksamana Buykes, salah seorang
Komisaris Jenderal untuk menghadapi Patimura.
Pertempuran-pertempuran yang hebat melawan angkatan perang Belanda di darat dan di laut dikoordinir
Kapitan Pattimura yang dibantu oleh para penglimanya antara lain Melchior Kesaulya, Anthoni Rebhok, Philip
Latumahina dan Ulupaha. Pertempuran yang menghancurkan pasukan Belanda tercatat seperti perebutan
benteng Belanda Duurstede, pertempuran di pantai Waisisil dan jasirah Hatawano, Ouw- Ullath, Jasirah Hitu di
Pulau Ambon dan Seram Selatan. Perang Pattimura hanya dapat dihentikan dengan politik adu domba, tipu
muslihat dan bumi hangus oleh Belanda. Para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan mengakhiri
pengabdiannya di tiang gantungan pada tanggal 16 Desember 1817 di kota Ambon. Untuk jasa dan
pengorbanannya itu, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai PAHLAWAN PERJUANGAN KEMERDEKAAN oleh
pemerintah Republik Indonesia.
Sampeyandalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana X(lahir di Surakarta, 29
November 1866 meninggal di Surakarta, 1 Februari1939 pada umur 72 tahun) adalah raja Kasunanan
Surakarta yang memerintah tahun 1893 1939.
Masa Pemerintahan
Sayiddin Malikul Kusno naik tahta sebagai Pakubuwana X pada tanggal 30 Maret 1893menggantikan ayahnya
yang meninggal dua minggu sebelumnya. Pakubuwana X menikah dengan GKR. Hemas (putri Sultan
Hamengkubuwana VII) dan dikaruniai seorang putri yang bernama GKR. Pembayun.
Masa pemerintahannya ditandai dengan kemegahan tradisi dan suasana politik kerajaan yang stabil. Pada
masa pemerintahannya yang cukup panjang, Kasunanan Surakarta mengalami transisi, dari kerajaan
tradisional menuju era modern, sejalan dengan perubahan politik di Hindia-Belanda.
Dalam bidang sosial-ekonomi, Pakubuwana X memberikan kredit untuk pembangunan rumah bagi warga
kurang mampu. Di bidang pendidikan, ia mendirikan sekolah Pamardi Putri dan Kasatriyan untuk kepentingan
kerabat keraton. Infrastruktur moderen kota Surakarta banyak dibangun pada masa pemerintahannya, seperti
bangunan Pasar Gede Harjonagoro, Stasiun Solo Jebres, Stasiun Solo-Kota (Sangkrah), Stadion Sriwedari,
Kebun Binatang Jurug, jembatan Jurug yang melintasi Bengawan Solo di timur kota, Taman Balekambang,
gapura-gapura di batas KotaSurakarta, rumah pemotongan hewan ternak di Jagalan, rumah singgah bagi
tunawisma, dan rumah perabuan (pembakaran jenazah) bagi warga Tionghoa.
Pada tanggal 21 Januari 1932, Pakubuwana X mendapatkan bintang kehormatan Sri Maharaja dari Ratu
Wilhelmina dariBelanda berupa Grutkreissi Ordhe Nederlanse Leyo dengan sebutan raja dalam Bahasa
Belanda, Zijne Vorstelijke Hoogheid.
Meskipun berada dalam tekanan politik pemerintah kolonial Hindia Belanda, Pakubuwana X memberikan
kebebasan berorganisasi dan penerbitan media massa. Ia mendukung pendirian organisasi Sarekat Dagang
Islam, salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia I di Surakarta
(1938) diadakan pada masa pemerintahannya.
Sultan Hasanuddin (lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, 12 Januari 1631 meninggal di Makassar,
Sulawesi Selatan, 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun) adalah Raja Gowa ke-16 dan pahlawan nasional Indonesia
yang terlahir dengan nama I Mallombasi Muhammad Bakir Daeng Mattawang Karaeng Bonto Mangepe.
Setelah memeluk agama Islam, ia mendapat tambahan gelar Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Balla Pangkana,
hanya saja lebih dikenal dengan Sultan Hasanuddin saja. Karena keberaniannya, ia dijuluki De Haantjes van
Het Oosten oleh Belanda yang artinya Ayam Jantan/Jago dari Benua Timur. Ia dimakamkan di Katangka,
Makassar.
Ia diangkat sebagai Pahlawan Nasional dengan Surat Keputusan Presiden No. 087/TK/1973, tanggal 6
November 1973.[1]
Sejarah
Sultan Hasanuddin lahir di Makassar, merupakan putera kedua dari Sultan Malikussaid, Raja Gowa ke-15.
Sultan Hasanuddin memerintah Kerajaan Gowa, ketika Belanda yang diwakili Kompeni sedang berusaha
menguasai perdagangan rempah-rempah. Gowa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang
menguasai jalur perdagangan.
Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Speelman, Kompeni berusaha menundukkan
kerajaan-kerajaan kecil, tetapi belum berhasil menundukkan Gowa. Di lain pihak, setelah Sultan Hasanuddin
naik takhta, ia berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagian timur untuk
melawan Kompeni.
Pertempuran terus berlangsung, Kompeni menambah kekuatan pasukannya hingga pada akhirnya Gowa
terdesak dan semakin lemah sehingga pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan Perdamaian
Bungaya di Bungaya. Gowa merasa dirugikan, karena itu Sultan Hasanuddin mengadakan perlawanan lagi.
Akhirnya pihak Kompeni minta bantuan tentara ke Batavia. Pertempuran kembali pecah di berbagai tempat.
Hasanuddin memberikan perlawanan sengit. Bantuan tentara dari luar menambah kekuatan pasukan
Kompeni, hingga akhirnya Kompeni berhasil menerobos benteng terkuat Gowa yaitu Benteng Sombaopu pada
tanggal 12 Juni 1669. Sultan Hasanuddin kemudian mengundurkan diri dari takhta kerajaan dan wafat pada
tanggal 12 Juni 1670.
Martha Christina Tiahahu (lahir di Nusa Laut, Maluku, 4 Januari 1800 meninggal di Laut Banda,
Maluku, 2 Januari 1818 pada umur 17 tahun) adalah seorang gadis dari Desa Abubu di Pulau Nusalaut. Lahir
sekitar tahun 1800 dan pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda berumur 17 tahun.
Ayahnya adalah Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas
Matulessy dalam perang Pattimura tahun 1817 melawan Belanda.
Martha Christina tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik yaitu seorang puteri remaja yang
langsung terjun dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda dalam perang Pattimura tahun
1817. Di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh, ia dikenal sebagai gadis
pemberani dan konsekwen terhadap cita-cita perjuangannya.
Sejak awal perjuangan, ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur. Dengan rambutnya yang
panjang terurai ke belakang serta berikat kepala sehelai kain berang (merah) ia tetap mendampingi ayahnya
dalam setiap pertempuran baik di Pulau Nusalaut maupun di Pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir
dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan. Ia bukan saja mengangkat senjata, tetapi juga memberi
semangat kepada kaum wanita di negeri-negeri agar ikut membantu kaum pria di setiap medan pertempuran
sehingga Belanda kewalahan menghadapi kaum wanita yang ikut berjuang.
Di dalam pertempuran yang sengit di Desa Ouw Ullath jasirah Tenggara Pulau Saparua yang nampak betapa
hebat srikandi ini menggempur musuh bersama para pejuang rakyat. Namun akhirnya karena tidak seimbang
dalam persenjataan, tipu daya musuh dan pengkhianatan, para tokoh pejuang dapat ditangkap dan menjalani
hukuman. Ada yang harus mati digantung dan ada yang dibuang ke Pulau Jawa. Kapitan Paulus Tiahahu divonis
hukum mati tembak. Martha Christina berjuang untuk melepaskan ayahnya dari hukuman mati, namun ia
tidak berdaya dan meneruskan bergerilyanya di hutan, tetapi akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Pulau
Jawa.
Di Kapal Perang Eversten, Martha Christina Tiahahu menemui ajalnya dan dengan penghormatan militer
jasadnya diluncurkan di Laut Banda menjelang tanggal 2 Januari 1818. Menghargai jasa dan pengorbanan,
Martha Christina dikukuhkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia.
I Gusti Ketut Jelantik (1849) adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Karangasem, Bali.
Ini merupakan patih Kerajaan Buleleng. Ia berperan dalam Perang Jagaraga yang terjadi di Bali pada tahun
1849. Pertandingan ini dimulai karena pemerintah kolonial Hindia Belanda ingin menghapuskan hak tawan
karang yang terjadi di Bali, yaitu hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di
perairannya beserta seluruh isinya. Ucapannya yang terkenal saat itu adalah "Apapun tidak akan terjadi.
Selama aku hidup aku tidak akan mangakui kekuasaan Belanda di negeri ini". Perang ini berakhir sebagai suatu
puputan, seluruh anggota kerajaan dan rakyatnya bertarung mempertahankan daerahnya sampai titik darah
penghabisan. Namun akhirnya ia harus mundur ke Gunung Batur, Kintamani. Pada saat inilah beliau gugur.
Sultan Iskandar Muda (Aceh, Banda Aceh, 1593 atau 1590 [1] - Banda Aceh, Aceh, 27 September 1636)
merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh, yang berkuasa dari tahun 1607 sampai
1636. [2] Aceh mencapai kejayaannya pada masa kepemimpinan Iskandar Muda, dimana daerah
kekuasaannya yang semakin besar dan reputasi internasional sebagai pusat dari perdagangan dan
pembelajaran tentang Islam. [1]
Keluarga dan masa kecil
Asal usul
Dari pihak leluhur ibu, Iskandar Muda adalah keturunan dari Raja Darul-Kamal, dan dari pihak leluhur ayah
adalah keturunan dari keluarga Raja makota Alam. Darul-Kamal dan makota Alam dikatakan sebelumnya
adalah dua tempat pemukiman bertetangga (yang terpisah oleh sungai) dan yang afiliasinya merupakan asal
mula Aceh Darussalam. Iskandar Muda seorang diri mewakili kedua cabang itu, yang berhak sepenuhnya
menuntut takhta. [2]
Ibunya, bernama Putri Raja Indra Bangsa, yang juga dinamai Paduka Syah Alam, adalah anak dari Sultan
Alauddin Riayat Syah, Sultan Aceh ke-10; dimana sultan ini adalah putra dari Sultan Firman Syah, dan Sultan
Firman Syah adalah anak atau cucu (menurut Djajadiningrat) Sultan Inayat Syah, Raja Darul-Kamal.
Putri Raja Indra Bangsa menikah dengan upacara besar-besaran dengan Sultan Mansur Syah, putra dari Sultan
Abdul-Jalil, dimana Abdul-Jalil adalah putra dari Sultan Alauddin Riayat Syah al-kahhar, Sultan Aceh ke-3. [2]
Pernikahan
Sri Sultan Iskandar Muda kemudian menikah dengan seorang Putri dari Kesultanan Pahang. Putri ini dikenal
dengan nama Putroe Phang. Konon, karena terlalu cintanya sang Sultan dengan istrinya, Sultan
memerintahkan pembangunan Gunongan di tengah Medan khayali (Taman Istana) sebagai tanda cintanya.
Kabarnya, sang puteri selalu sedih karena memendam rindu yang amat sangat terhadap kampung halamannya
yang berbukit-bukit. Oleh karena itu Sultan membangun Gunongan untuk mengobati rindu sang putri. Hingga
saat ini Gunongan masih dapat disaksikan dan dikunjungi.
Masa kekuasaan
Masa kekuasaan Sultan Iskandar Muda yang dimulai pada tahun 1607 sampai 1636, merupakan masa paling
gemilang bagi Kesultanan Aceh, walaupun di sisi lain kontrol ketat yang dilakukan oleh Iskandar Muda,
menyebabkan banyak pemberontakan di kemudian hari setelah mangkatnya Sultan.
Aceh adalah negeri yang sangat kaya dan makmur pada masa kejayaannya. Menurut seorang penjelajah asal
Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam,
kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi sampai Perak.
Ketika Iskandar Muda mulai berkuasa pada tahun 1607, ia segera melakukan ekspedisi angkatan laut yang
menyebabkan ia mendapatkan kontrol yang efektif di daerah barat laut Indonesia. [1] Kendali pemerintah
terlaksana dengan lancar di semua pelabuhan penting di pantai barat Sumatra dan di pantai timur, sampai ke
Asahan di selatan. Pelayaran penaklukannya diluncurkan sampai jauh ke Penang, di pantai timur Semenanjung
Melayu, dan pedagang asing dipaksa untuk tunduk kepadanya. Kerajaannya kaya raya, dan menjadi pusat ilmu
pengetahuan.
Cut Nyak Dhien
Lahir 1848
Lampadang, Kesultanan Aceh
Meninggal 6 November 1908
Sumedang, Hindia Belanda
Dikenal karena Pahlawan Nasional Indonesia
Agama Islam
Pasangan Ibrahim Lamnga, Teuku Umar
Kehidupan awal
Cut Nyak Dhien dilahirkan dari keluarga bangsawan yang taat beragama di Aceh Besar, wilayah VI Mukim pada
tahun 1848. Ayahnya bernama Teuku Nanta Setia, seorang uleebalang VI Mukim, yang juga merupakan
keturunan Machmoed Sati, perantau dari Sumatera Barat. Machmoed Sati mungkin datang ke Aceh pada abad
ke 18 ketika kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Jamalul Badrul Munir. Oleh sebab itu, Ayah dari Cut Nyak
Dhien merupakan keturunan Minangkabau[2][4]. Ibu Cut Nyak Dhien adalah putri uleebalang Lampagar.
Pada masa kecilnya, Cut Nyak Dhien adalah anak yang cantik.[2] Ia memperoleh pendidikan pada bidang
agama (yang dididik oleh orang tua ataupun guru agama) dan rumah tangga (memasak, melayani suami, dan
yang menyangkut kehidupan sehari-hari yang dididik baik oleh orang tuanya). Banyak laki-laki yang suka pada
Cut Nyak Dhien dan berusaha melamarnya. Pada usia 12 tahun, ia sudah dinikahkan oleh orangtuanya pada
tahun 1862 dengan Teuku Cek Ibrahim Lamnga[2][4], putra dari uleebalang Lamnga XIII. Mereka memiliki satu
anak laki-laki.
Perlawanan saat Perang Aceh
Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh, dan mulai melepaskan tembakan
meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Perang Aceh pun meletus. Pada perang
pertama (1873-1874), Aceh yang dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Machmud Syah bertempur
melawan Belanda yang dipimpin Johan Harmen Rudolf Khler. Saat itu, Belanda mengirim 3.198 prajurit. Lalu,
pada tanggal 8 April 1873, Belanda mendarat di Pantai Ceureumen di bawah pimpinan Khler, dan langsung
bisa menguasai Masjid Raya Baiturrahman dan membakarnya. Cut Nyak Dhien yang melihat hal ini berteriak:
Lihatlah wahai orang-orang Aceh!! Tempat ibadat kita dirusak!! Mereka telah mencorengkan nama Allah!
Sampai kapan kita begini? Sampai kapan kita akan menjadi budak Belanda?[2]
Kesultanan Aceh dapat memenangkan perang pertama. Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan
kembali dengan sorak kemenangan, sementara Khler tewas tertembak pada April 1873.
Pada tahun 1874-1880, di bawah pimpinan Jenderal Jan van Swieten, daerah VI Mukim dapat diduduki
Belanda pada tahun 1873, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. Cut Nyak Dhien dan bayinya
akhirnya mengungsi bersama ibu-ibu dan rombongan lainnya pada tanggal 24 Desember 1875. Suaminya
selanjutnya bertempur untuk merebut kembali daerah VI Mukim..
Anda mungkin juga menyukai
- 4C Resume Sib ZidanariyanshahsanjayaDokumen8 halaman4C Resume Sib ZidanariyanshahsanjayaZIDAN ARIYANSHAH SANJAYA 2019Belum ada peringkat
- Biografi Sisingamangaraja XIIDokumen6 halamanBiografi Sisingamangaraja XIIAlfazzastoreBelum ada peringkat
- Pahlawan DaerahDokumen9 halamanPahlawan Daerahlucya kurnialinBelum ada peringkat
- PDokumen9 halamanPNurma LiaBelum ada peringkat
- 6 Pahlawan Nasional Perjuangan Bangsa Tahun 1908Dokumen6 halaman6 Pahlawan Nasional Perjuangan Bangsa Tahun 1908Vivo BiruBelum ada peringkat
- Sejarah Kelas 11Dokumen6 halamanSejarah Kelas 11Salwa AnnisaBelum ada peringkat
- Cut Nyak DhienDokumen8 halamanCut Nyak DhienMastersBestHackersBelum ada peringkat
- Cokelat Sejarah Pendidikan PresentasiDokumen9 halamanCokelat Sejarah Pendidikan PresentasiMeyra Laretha PasaribuBelum ada peringkat
- PAHLAWAN 34 ProvDokumen31 halamanPAHLAWAN 34 Provheri.accBelum ada peringkat
- Biografi Sisingamangaraja XIIDokumen3 halamanBiografi Sisingamangaraja XIIIDA100% (3)
- Biodata Pangeran PattimuraDokumen13 halamanBiodata Pangeran PattimuraFirman ArixTraBelum ada peringkat
- ArdannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnDokumen8 halamanArdannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnichaaaBelum ada peringkat
- Biografi Sisingamangaraja XIIDokumen3 halamanBiografi Sisingamangaraja XIIFebricho SianturiBelum ada peringkat
- Tokoh Pejuang Pada Penjajahan Belanda Dan JepangDokumen25 halamanTokoh Pejuang Pada Penjajahan Belanda Dan Jepangrandy mykenBelum ada peringkat
- Tugas Kliping PKNDokumen7 halamanTugas Kliping PKNNevia orvalaBelum ada peringkat
- Tokoh Tokoh Perjuangan KemerdekaanDokumen10 halamanTokoh Tokoh Perjuangan KemerdekaanchelseadevinaaaBelum ada peringkat
- Strategi Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadappenjajahan Bangsa EropaDokumen4 halamanStrategi Perlawanan Bangsa Indonesia Terhadappenjajahan Bangsa Eropamedia pembelajaran100% (1)
- Kapiten PattimuraDokumen9 halamanKapiten Pattimuramonogatari sisBelum ada peringkat
- Pangeran DiponegoroDokumen5 halamanPangeran Diponegorodanielfrans25Belum ada peringkat
- Cerita PahlawanDokumen18 halamanCerita PahlawanAYI JUMAD100% (4)
- Biografi Pangeran DiponegoroDokumen9 halamanBiografi Pangeran DiponegoroMadhan Bla100% (1)
- Sisingamangaraja XIIDokumen13 halamanSisingamangaraja XIINoel Agung100% (1)
- Tugas Projek PKNDokumen7 halamanTugas Projek PKNTheresia AmandaBelum ada peringkat
- 8 Pahlawan Yang Menentang BelandaDokumen10 halaman8 Pahlawan Yang Menentang BelandadiannBelum ada peringkat
- Raja BatakDokumen13 halamanRaja Batakberak diaerBelum ada peringkat
- Tokoh Tokoh Pahlawan Terhadap Penjajahan Bangsa Bangsa EropaDokumen16 halamanTokoh Tokoh Pahlawan Terhadap Penjajahan Bangsa Bangsa Eropa6mfnddnrrbBelum ada peringkat
- Propil Imam Bonjol DLLDokumen9 halamanPropil Imam Bonjol DLLBcex PesantrenBelum ada peringkat
- 5 Tokoh Nasional Dan DaerahDokumen5 halaman5 Tokoh Nasional Dan DaerahFreddy ThenBelum ada peringkat
- Sisingamangaraja XIIDokumen4 halamanSisingamangaraja XIIdandiBelum ada peringkat
- Tugas PPKNDokumen10 halamanTugas PPKNCelle LyysaBelum ada peringkat
- PANGERAN DIPONEGORO Dan Cut Nyak DienDokumen6 halamanPANGERAN DIPONEGORO Dan Cut Nyak DienOyeh SomantriBelum ada peringkat
- Biografi Pahlawan Daerah Dari Sumatera UtaraDokumen3 halamanBiografi Pahlawan Daerah Dari Sumatera UtarahanBelum ada peringkat
- Perlawanan SisingamangarajaDokumen4 halamanPerlawanan SisingamangarajaNona KimtaeBelum ada peringkat
- Perlawanan Rakyat BatakDokumen11 halamanPerlawanan Rakyat BatakSabrinaseptiani84100% (1)
- 7 Pahlawan Yang Menentang BelandaDokumen6 halaman7 Pahlawan Yang Menentang BelandaIka Serfiani PratiwiBelum ada peringkat
- 1201 Peran Umat Islam Pada Masa Penjajahan Dan Kemerdekaan.Dokumen8 halaman1201 Peran Umat Islam Pada Masa Penjajahan Dan Kemerdekaan.Safira Aulia100% (9)
- PPKN Perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Pattimura Dan I Gusti Ketut JelantikDokumen4 halamanPPKN Perjuangan Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Pattimura Dan I Gusti Ketut JelantikNur FitrianiBelum ada peringkat
- Pahlawan Nasional IndonesiaDokumen11 halamanPahlawan Nasional IndonesiaLeny Marisha SitorusBelum ada peringkat
- Cut Nyak DienDokumen10 halamanCut Nyak DienKamali HutaBelum ada peringkat
- Biografi Pangeran DiponegoroDokumen13 halamanBiografi Pangeran DiponegoroNur Fadilla Akram100% (2)
- Sultan Mahmud Badaruddin IIDokumen17 halamanSultan Mahmud Badaruddin IIS yendra100% (1)
- Pahlawan NasionalDokumen25 halamanPahlawan NasionalMuhammad GabrielBelum ada peringkat
- Sejarah Peminatan KLS Xi Ips PDFDokumen17 halamanSejarah Peminatan KLS Xi Ips PDFleoBelum ada peringkat
- Pahlawan NasionalDokumen11 halamanPahlawan NasionalMachbub SobariBelum ada peringkat
- Sisingamangaraja XiiDokumen5 halamanSisingamangaraja XiiMitha Siahaan IIBelum ada peringkat
- Sultan HasanudinDokumen13 halamanSultan HasanudinPUSKRIPBelum ada peringkat
- Peristiwa Perlawanan Terhadap BelandaDokumen9 halamanPeristiwa Perlawanan Terhadap BelandaHasbariah HasbariahBelum ada peringkat
- Biografi SEJARAHDokumen4 halamanBiografi SEJARAHmuloko dmn93Belum ada peringkat
- 7 Tokoh Pahlawan Dan Kisah PerjuangannyaDokumen8 halaman7 Tokoh Pahlawan Dan Kisah PerjuangannyaKholis WahyudynBelum ada peringkat
- Sejarah Perang BatakDokumen6 halamanSejarah Perang BatakAndi Arta YuliantoBelum ada peringkat
- Pahlawan KemerdekaanDokumen15 halamanPahlawan KemerdekaanelviraBelum ada peringkat
- Kapitan PattimuraDokumen3 halamanKapitan PattimuraHendry BayuBelum ada peringkat
- Pahlawan IndonesiaDokumen14 halamanPahlawan IndonesiahazaziBelum ada peringkat
- Sejarah Perang BatakDokumen5 halamanSejarah Perang BatakAhmad AdipBelum ada peringkat
- Pahlawan NasionalDokumen10 halamanPahlawan Nasionalroni4512Belum ada peringkat
- Pangeran DiponegoroDokumen9 halamanPangeran DiponegoroSiti Fatimah Noviyanti100% (1)
- Pangeran DiponegoroDokumen2 halamanPangeran Diponegorodede jojoBelum ada peringkat
- Sejarah Perang Batak SisingamangarajaDokumen4 halamanSejarah Perang Batak SisingamangarajaVira ZataBelum ada peringkat
- Perang BatakDokumen6 halamanPerang BatakMuhammad Fajar Maulana IhsanBelum ada peringkat
- RPP Standar Proses 3Dokumen5 halamanRPP Standar Proses 3DwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Pesawat SederhanaDokumen6 halamanPesawat SederhanaDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Sebelum Kita Mempelajari Makna Pembukaan UUD 1945Dokumen22 halamanSebelum Kita Mempelajari Makna Pembukaan UUD 1945DwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Hiwalah Dan SharfDokumen2 halamanHiwalah Dan SharfDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Pentingnya PendidikanDokumen9 halamanPentingnya PendidikanDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Kliping Bahasa ArabDokumen1 halamanKliping Bahasa ArabDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- MoluskaDokumen15 halamanMoluskaDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Berbagai Macam Ideologi Yang Ada Di DuniDokumen24 halamanBerbagai Macam Ideologi Yang Ada Di DuniRendy Hardienka Bilogical ChildrenBelum ada peringkat
- Model - Model Pendidikan Non FormalDokumen15 halamanModel - Model Pendidikan Non FormalDwieVAdmadja100% (1)
- Hukum ProustDokumen4 halamanHukum ProustDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Sophie GermainDokumen1 halamanSophie GermainDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Pidato Perpisahan SekolahDokumen1 halamanPidato Perpisahan SekolahDwieVAdmadja100% (2)
- MatahariDokumen2 halamanMatahariDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan Pada Pre OperasiDokumen1 halamanAsuhan Keperawatan Pada Pre OperasiDwieVAdmadjaBelum ada peringkat
- The Voice of God: Experience A Life Changing Relationship with the LordDari EverandThe Voice of God: Experience A Life Changing Relationship with the LordBelum ada peringkat
- From Raindrops to an Ocean: An Indian-American Oncologist Discovers Faith's Power From A PatientDari EverandFrom Raindrops to an Ocean: An Indian-American Oncologist Discovers Faith's Power From A PatientPenilaian: 1 dari 5 bintang1/5 (1)