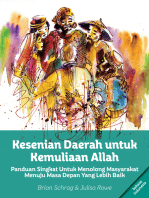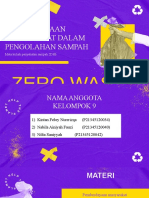Sampah Komunitas
Sampah Komunitas
Diunggah oleh
suyantokitHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Sampah Komunitas
Sampah Komunitas
Diunggah oleh
suyantokitHak Cipta:
Format Tersedia
STUDI PENGELOLAAN SAMPAH
BERBASIS KOMUNITAS DI PEKANBARU
Dr. Suyanto, MPH
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS RIAU
PEKANBARU
2015
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar belakang
Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat
perhatian yang serius. Data dari Dinas Kebersihan Kota Semarang menunjukan
bahwa sampah perkotaan dari tahun ke tahun terus meningkat seiring dengan laju
pertumbuhan jumlah penduduk. Permasalahan yang dialami oleh pemerintah Kota
Semarang dalam pengelolaan sampah dari penerimaan retribusi kebersihan belum
mampu membiayai teknis operasional dan pemeliharannya. besaran distribusi
sekitar 46.53 % dari pengelolaan sampah bulanan. Hal ini berarti untuk mencapai
break even point penerimaan retribusi masih harus mencapai 53.48 % lagi dari
biaya pengelolaan sampah.3
Peningkatan jumlah sampah yang tidak diikuti oleh perbaikan dan
peningkatan
sarana
dan
prasarana
pengelolaan
sampah
mengakibatkan
permasalahan sampah menjadi komplek, antara lain sampah tidak terangkut dan
terjadi pembuangan sampah liar, sehingga dapat menimbulkan berbagai penyakit,
kota kotor, bau tidak sedap, mengurangi daya tampung sungai dan lain-lain. 3 Pada
dasarnya mengelola sampah secara baik adalah merupakan tanggung jawab setiap
individu manusia yang memproduksi sampah, dalam hal ini sampah padat, yang
dihasilkan rumah tangga, industri perusahaan, perkantoran, pabrik, pasar, dan
sebagainya.4
Adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah menjadi sangat
penting. Penelitian oleh Syamsurial (2009) menunjukkan data bahwa tanggung
jawab masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri sebanyak 46% dari jumlah
sampah, hampir sebanding daripada tanggung jawab pemerintah, yakni hanya
54% saja dari total sampah yang dapat ditangan. Persepsi masyarakat bahwa
pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah harus diubah. Demikian
pula adanya persepsi masyarakat mengenai lingkungan haruslah meningkat tidak
sekedar memperhatikan kebersihan sekitar rumahnya saja, tetapi juga harus ada
kesadaran bahwa kebersihan lingkungan sekitar juga mendukung terciptanya
kebersihan rumah sendiri.4
Masalah sampah mutlak harus ditangani secara bersama-sama antara
pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena
itu dibutuhkan kesadaran dan komitmen bersama menuju perubahan sikap,
perilaku dan etika yang berbudaya lingkungan. Sebagai upaya menggugah
kepedulian dalam penanganan permasalahan lingkungan, khususnya persampahan
serta untuk menciptakan kualitas lingkungan pemukiman yang bersih dan ramah
lingkungan maka, harus dilakukan perubahan paradigma pengelolaan sampah
dengan cara pengurangan volume sampah dari sumbernya dengan pemilihan, atau
pemrosesan dengan teknologi yang sederhana seperti komposting dengan skala
rumah tangga atau skala lingkungan dan peran serta masyarakat dalam
pengelolaan sampah di koordinir oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM),
kelompok ini bertugas mengkoordinir pengelolaan kebersihan lingkungan.3
1.2 Tujuan penelitian
1.3.1
Tujuan umum
Diketahuinya gambaran Pengelolaan Sampah Berbasis Komunits di Kota
Pekanbaru
Tujuan khusus.
1. Diketahuinya pengelolaan Sampah di FK UNR
2. Diketahuinya
Pengelolaan
Sampah
AnOrganik
di
Masayarakt Peduli Sampah
3. Diketahuinya Persepsi Pemulung terhadap Pengelolaan
Sampah di TPS
4. Diketahuinya Persepsi Pemulung terhadap Pengelolaan
Sampah di TPA
5. Diketahuinya Persepsi Mahasiswa FK terhadap Pengelolaan
Sampah
6. Diketahuinya Gambaran K3 pada pekerja Penglola sampah
di Dalang Collection
1.4
1.4.1
Manfaat penelitian
Bagi peneliti
Penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti tentang pengelolaan
sampah berbasis komunitas dan memahami cara melakukan penelitian kedokteran
khususnya penelitian deskriptif, mengaplikasikan ilmu kesehatan masyarakat pada
komunitas tertentu
1.4.2
Bagi Instansi Terkaiy
Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi gambaran peneglolan sampah
berbasiis komunitas sehingga dapat dijadikan masukan untuk membuat kebijakan
dan program pengelolaan sampah73
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Budaya Pemberdayaan
Pertama-tama perlu terlebih dahulu dipahami arti dan makna keberdayaan
dan pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah
kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun
keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian
besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif,
tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi.
Namun, selain nilai fisik di atas, ada pula nilai-nilai intrinsik dalam
masyarakat yang juga menjadi sumber keberdayaan, seperti nilai kekeluargaan,
kegotong-royongan, kejuangan, dan yang khas pada masyarakat kita, kebinekaan.
Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu
masyarakat
bertahan
(survive),
dan
dalam
pengertian
yang
dinamis
mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Keberdayaan masyarakat ini
menjadi sumber dari apa yang di dalam wawasan politik pada tingkat nasional kita
sebut ketahanan nasional.
Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan
martabat lapisan masyarakat kita yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk
melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata
lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat secara implisit mengandung arti menegakkan
demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi secara harafiah berarti kedaulatan rakyat
di bidang ekonomi, di mana kegiatan ekonomi yang berlangsung adalah dari
rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep ini menyangkut masalah penguasaan
teknologi, pemilikan modal, akses ke pasar dan ke dalam sumber-sumber
informasi, serta keterampilan manajemen. Agar demokrasi ekonomi dapat
berjalan, maka aspirasi masyarakat yang tertampung harus diterjemahkan menjadi
rumusan-rumusan kegiatan yang nyata. Untuk menerjemahkan rumusan menjadi
kegiatan nyata tersebut, negara mempunyai birokrasi. Birokrasi ini harus dapat
berjalan efektif, artinya mampu menjabarkan dan melaksanakan rumusanrumusan kebijaksanaan publik (public policies) dengan baik, untuk mencapai
tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Dalam paham bangsa Indonesia, masyarakat
adalah
pelaku
utama
pembangunan,
sedangkan
pemerintah
(birokrasi)
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan iklim yang
menunjang.
B. Pendekatan Pemberdayaan
Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat
tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan
subjek
dari
upaya
pembangunannya
sendiri.
Pendekatan
pemberdayaan
masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya
masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri
mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya
diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi
sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.
Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti
pendekatan sebagai berikut:
1. Upaya itu harus terarah (targetted). Ini yang secara populer disebut
pemihakan. Ia ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan
program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai
kebutuhannya.
2. Program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan
oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat
yang akan dibantumempunyai beberapa tujuan, yakni supaya bantuan
tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan kemampuan serta
kebutuhan mereka. Selain itu sekaligus meningkatkan keberdayaan
(empowering)
melaksanakan,
masyarakat
mengelola,
dengan
dan
pengalaman
dalam
merancang,
mempertanggungjawabkan
upaya
peningkatan diri dan ekonominya.
3. Menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri
masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang
dihadapinya.
Juga
lingkup
bantuan
menjadi
terlalu
luas
kalau
penanganannya dilakukan secara individu. Karena itu seperti telah
disinggung di muka, pendekatan kelompok adalah yang paling efektif, dan
dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Di samping itu
kemitraan usaha antara kelompok tersebut dengan kelompok yang lebih
maju harus terus-menerus di bina dan dipelihara secara sating
menguntungkan dan memajukan.
Selanjutnya untuk kepentingan analisis, pemberdayaan masyarakat harus
dapat dilihat baik dengan pendekatan komprehensif rasional maupun inkremental.
Dalam pengertian pertama (komprehensif rasional), dalam upaya ini diperlukan
perencanaan berjangka, serta pengerahan sumber daya yang tersedia dan
pengembangan potensi yang ada secara nasional, yang mencakup seluruh
masyarakat. Dalam upaya ini perlu dilibatkan semua lapisan masyarakat, baik
pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga sosial dan kemasyarakatan, serta
tokoh-tokoh dan individu-individu yang mempunyai
kemampuan untuk
membantu. Dengan demikian, programnya harus bersifat nasional, dengan
curahan sumber daya yang cukup besar untuk menghasilkan dampak yang berarti.
Dengan pendekatan yang kedua (incremental), perubahan yang diharapkan tidak
selalu harus terjadi secara cepat dan bersamaan dalam derap yang sama.
Kemajuan dapat dicapai secara bertahap, langkah demi langkah, mungkin
kemajuan-kemajuan kecil, juga tidak selalu merata. Pada satu sektor dengan
sektor lainnya dapat berbeda percepatannya, demikian pula antara satu wilayah
dengan wilayah lain, atau suatu kondisi dengan kondisi lainnya. Dalam
pendekatan ini, maka desentralisasi dalam pengambilan keputusan dan
pelaksanaan teramat penting. Tingkat pengambilan keputusan haruslah didekatkan
sedekat mungkin kepada masyarakat.
Salah satu pendekatan yang mulai banyak digunakan terutama oleh LSM
adalah advokasi. Pendekatan advokasi pertama kali diperkenalkan pada
pertengahan tahun 1960-an di Amerika Serikat (Davidoff, 1965). Model
pendekatan ini mencoba meminjam pola yang diterapkan dalam system hukum, di
mana penasehat hukum berhubungan langsung dengan klien. Dengan demikian,
pendekatan advokasi menekankan pada pendamping dan kelompok masyarakat
dan
membantu
mereka
untuk
membuka
akses
kepada
pelaku-pelaku
pembangunan lainnya, membantu mereka mengorganisasikan diri, menggalang
dan memobilisasi sumber daya yang dapat dikuasai agar dapat meningkatkan
posisi tawar (bargaining position) dari kelompok masyarakat tersebut.
Pendekatan advokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada
hakekatnya masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang masing-masing
mempunyai kepentingan dan sistem nilai sendiri-sendiri. Masyarakat pada
dasarnya bersifat majemuk, di mana kekuasaan tidak terdistribusi secara merata
dan akses keberbagai sumber daya tidak sama (Catanese and Snyder, 1986).
Kemajemukan atau pluralisme inilah yang perlu dipahami. Menurut paham ini
kegagalan pemerintah sering terjadi karena memaksakan pemecahan masalah
yang seragam kepada masyarakat yang realitanya terdiri dari kelompok-kelompok
yang
beragam.
Ketidakpedulian
terhadap
heterogenitas
masyarakat,
mengakibatkan individu-individu tidak memiliki kemauan politik dan hanya
segelintir elit yang terlibat dalam proses pembangunan.
Dalam jangka panjang diharapkan dengan pendekatan advokasi masyarakat
mampu secara sadar terlibat dalam setiap tahapan dari proses pembangunan, baik
dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
Seringkali pendekatan advokasi diartikan pula sebagai salah satu bentuk
penyadaran secara langsung kepada masyarakat tentang hak dan kewajibannya
dalam proses pembangunan.
C. Model Pemberdayaan
Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi
yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru
pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering,
and sustainable" (Chambers, 1995).
Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari
tiga model.
Pertama, Model Pemberdayaan untuk menciptakan suasana atau iklim
yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik
tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki
potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama
sekali tanpa daya, karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan
10
adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk
mengembangkannya.
Kedua, Model Pemberdayaan untuk memperkuat potensi atau daya yang
dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkahlangkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan
ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai
masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang
(opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.
Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan
taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber
kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan
sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah
dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada
lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan,
dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang
keberdayaannya amat kurang.
Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya,
karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat
menyentuh lapisan masyarakat ini.
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat,
tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti
kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok
dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi
sosial dan pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan
masyarakat di dalamnya. Sungguh penting di sini adalah peningkatan partisipasi
rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan
masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya
dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan demokrasi. Friedman (1992)
menyatakan The empowerment approach, which is fundamental to an alternative
development, places the emphasis on autonomy in the decision-marking of
11
territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct
(participatory) democracy, and experiential social learning.
Ketiga, Model Pemberdayaan untuk memberdayakan mengandung pula
arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi
bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.
Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar
sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti
mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan
yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya
untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang
kuat atas yang lemah.Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat
menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena,
pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang
hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan
akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun
kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara
sinambung.
D. Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Pembentukan komunitas
peduli sampah)9
Pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan pengelolaan sampah
yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dilibatkan pada
pengelolaan
sampah
dengan
tujuan
agar
mayarakat
menyadari
bahwa
permasalahan sampah merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk merintis pengelolaan sampah
mandiri berbasis masyarakat yaitu:
1. Sosialisasikan Gagasan Kepada Masyarakat dan Tokoh Masyarakat
Sosialisai ini dilakukan oleh penggagas terbentuknya pengelolaan berbasis
masyarakat kepada sebagian kcil masyarakat yang bersedia untuk ikut andil
dalam pengelolaan sampah dan tokoh masyarakat misalnya kepala dusun,
ketua RT maupun ketua RW.
2. Bentuk Tim Pengelola Sampah
Tim pengelola sampah ini dapat terdiri dari pelindung biasanya oleh
kepala dusun, ketua RT atau ketua RW. Ketua pelaksana biasanya dipegang
12
oleh penggagas, sekretaris, bendahara, seksi penerimaan sampah, seksi
pemilahan, seksi humas dan seksi-seksi lain yang diperlukan sesuai
kesepakatan bersama.
3. Mencari pihak yang bersedia membeli sampah (Pengepul sampah)
Pihak-pihak yang bersedia membeli sampah adalah orang-orang yang
mengumpulkan barang-barang rongsokan berupa sampah-sampah yang dapat
didaur ulang.
4. Sosialisasi dengan seluruh masyarakat
Jika tim telah terbentuk dan terdapat kesepakatan bersama bahwa akan
dilaksanakan program pengelolaan sampah mandiri maka dilakukan
sosialisasi dengan seluruh masyarakat. Masyarakat diberi informasi tentang
keuntungan ikut serta dalam pengelolaan sampah mandiri, peranan
masyarakat dan manfaatnya terhadap lingkungan.
5. Menyiapkan fasilitias yang diperlukan bersama-sama
Fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah mandiri
ini adalah tempat sebagai pengepul sampah sebelum diambil oleh pembeli
sampah. Tempat ini dilengkapi dengan timbangan, buku administrasi,
kantong-kantong untuk pemilahan sampah.
6. Lakukan monitoring dan eveluasi
Monitoring dan evaluasi dapat dilakukan sebulan sekali melalui rapat
anggota pemasok sampah meliputi jenis sampah yang dipasok, sistem bagi
hasil antara pengelola dan pemasok sampah dan lain-lain. Monitoring dan
evaluasi dilakukan oleh penanggung jawab pelaksana.
7. Laporkan hasil-hasil program kepada komunitas
Hasil-hasil pelaksanaan program pengelolaan sampah mandiri berbasis
masyarakat dilakukan sebulan sekali kepada seluruh warga yang terlibat
dalam program ini. Pelaporan hasil dilakukan dengan transparan tanpa ada
pihak-pihak yang dirugikan.
8. Kerjasama dan minta dukungan dengan pihak lain
Kerjasama yang dilakukan dalam program pengelolaan sampah mandiri ini
antara lain pengepul sampah skala besar, toko-toko yang bersedia untuk
konsinyasi barang-barang yang dibuat dari daur ulang sampah, toko-toko
pertanian yang bersedia menjualkan kompos hasil pengelolaan sampah
mandiri tersebut. Dukungan yang dapat diperoleh pada pelaksanaan program
ini adalah dukungan dari pemerinyah setemoat misalnya tingkat kabupaten
13
yang turut serta menggalakkan program ini dan menyediakan dana untuk
pengembangan program ini.
E. Partisipasi kelompok peduli sampah di indonesia
Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak
keempat di dunia dengan total penduduk mencapai 237 juta. Diperkirakan, jumlah
penduduk Indonesia akan bertambah menjadi 270 juta pada 2025. Dengan jumlah
penduduk sebanyak itu, diperkirakan akan dihasilkan sampah sebanyak 130.000
ton/hari. Ini merupakan potensi yang besar sebagai sumberdaya (bahan yang dapat
didaur ulang, sumber energi, dll). Tetapi saat ini sebagian besar masih menjadi
sumber penyebab polusi. Pengurangan sampah yang bertujuan untuk membatasi
volume sampah yang dihasilkan harus segera dilakukan. Salah satu upaya
mengurangi sampah adalah melalui pembudayaan kegiatan reduce, reuse dan
recycle (3R) sampah.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum telah
mengembangkan berbagai proyek percontohan 3R di beberapa provinsi. Bahkan
selama periode 2010-2014, Kementerian Pekerjaan Umum telah membangun
kurang lebih 336 fasilitas pengolahan sampah 3R. Berbagai kebijakan dan
program yang dikembangkan Pemerintah Indonesia terkait pengelolaan sampah
dan 3R hanya akan berhasil jika mendapat dukungan dari masyarakat dan
kemitraan dengan berbagai pihak.
Komunitas Peduli Sampah adalah komunitas yang peduli memberikan
solusi bagaimana mengelola sampah ini lebih bermanfaat. Komunitas peduli
sampah
merupakan
bentuk
salah
satu
partisipasi
masyarakat
terhadap
kepeduliannya pada sampah. dengan adanya komunitas peduli sampah maka akan
mendorong semua elemen pemerintah dan masyarakat lebih peduli terhadap
14
sampah melalui pengembangan kegiatan 3R. Dengan gerakan ini diharapkan tidak
hanya mengurangi sampah yang dihasilkan, tapi juga dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. dan diharapkan dari gerakan ini adalah mewujudkan
Indonesia peduli sampah melalui pelaksanaan 3R, mendorong seluruh masyarakat
membudayakan 3R dengan mengelola sampah dimulai dari diri sendiri, mengubah
cara pandang masyarakat bahwa sampah adalah sumberdaya yang berguna dan
bermanfaat. Selain itu juga menurunkan timbulan sampah dengan target sampah
terolah 3R.
15
16
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis dan desain penelitian
Jenis dan desain penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif
Kualitatif
3.2.
Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian akan dilakukan di Pekanbaru pada pertengahaPern Juli 2015- Oktober
2015.
Penelitian akan melibatkan Mahasiswa sebagai berikut:
Dewi Latifah: Pengelolaan Sampah di FK UNRI
Heni Haryani: Pengelolaan Sampah AnOrganik di Masayarakt Peduli Sampah
Saskia Novianti : Persepsi Pemulung terhadap Pengelolaan Sampah di TPS
Ridha Faisal: Persepsi Pemulung terhadap Pengelolaan Sampah di TPA
Regina Putri Riandes: Persepsi Mahasiswa FK terhadap Pengelolaan Sampah
Hafiza Azhar: Gambaran K3 pada pekerja Penglola sampah di Dalang Collection
3.3.
Populasi dan sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masayarakat Pekanbaru yang terlibat
dalam pengelolaan sampah
3.4.
Besar sample dan teknik pengambilan sampel
Besar sampel menggunakan prinsip kecukupan data
17
Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara:
1. Pengisian lembar observasi
2. Wawancara mendalam
3. Focus Grup Discussion
3.6
Pengolahan dan analisis data
Pengolahan data hasil penelitian dilakukan secara analisa konten dan
dilakukan triangulasi pada masing masing isu penelitian
18
DAFTAR PUSTAKA
1. Mubarak Z. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat ditinjau dari Proses
Pengembangan Kapasitas pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa
Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Universitas Diponegoro. 2010.
2. Cholisin. Pemberdayaan Masyarakat : Manajemen Pemertintahan Desa. Staf
Pengajar
FIS
UNY:
2010.
[Avaliable
on
http://staff.uny.ac.id/
sites/default/files/tmp/PEMBERDAYAAN%20MASYARAKAT.pdf]
3. Artiningsih A. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga. Universitas Diponegoro. 2008.
4. Syamsurial. Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
Padat. Universitas Andalas. 2009
5. Jamasy,
Owin.2004
Keadilan,
Pemberdayaan
dan
Penanggulangan
Kemiskinan. Bumi Putera:Jakarta.
6. Payne .1997.Empowerment seeks.London.
7. Moelyarto.1999.Pendekatan pengelolaan sumber daya lokal yang berbasis
masyarakat.Erlangga:Jakarta.
8. Pranarka dan Vidhyandika.1996. Proses pemberdayaan
9. Marwati S. Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat. Universitas
Negeri Yogyakarta. 2010.
Anda mungkin juga menyukai
- ILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuDari EverandILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (6)
- Kesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikDari EverandKesenian Daerah untuk Kemuliaan Allah: Panduan Singkat Untuk Menolong Masyarakat Menuju Masa Depan Yang Lebih BaikBelum ada peringkat
- Strategi Pelayanan Kebidanan KomunitasDokumen12 halamanStrategi Pelayanan Kebidanan Komunitasroullion100% (4)
- Jurnal Tentang SampahDokumen18 halamanJurnal Tentang SampahMachmud Suhaemi Fathiyah73% (11)
- Sanitasi Berbasis MasyarakatDokumen13 halamanSanitasi Berbasis MasyarakatAdhi WighunaBelum ada peringkat
- Studi Kelayakan RS Do'a BundaDokumen18 halamanStudi Kelayakan RS Do'a BundasuyantokitBelum ada peringkat
- Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis MasyarakatDokumen7 halamanPengelolaan Sampah Terpadu Berbasis MasyarakatbangunismansyahBelum ada peringkat
- Konsultasi Pendirian Rumah Sakit Dan Langkah Operasional Dan Penjaminan Mutu LayananDokumen9 halamanKonsultasi Pendirian Rumah Sakit Dan Langkah Operasional Dan Penjaminan Mutu LayanansuyantokitBelum ada peringkat
- Dissemination Strategy 7Dokumen16 halamanDissemination Strategy 7Putu Fina100% (1)
- ANALISIS Program Pemberdayaan MasyarakatDokumen26 halamanANALISIS Program Pemberdayaan MasyarakatYanuar Dicky Pradana100% (1)
- Tim 2 - Kel 15 - Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank SampahDokumen8 halamanTim 2 - Kel 15 - Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Bank SampahDesi Tri RahmawatiBelum ada peringkat
- 2d3b - Kel.9 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan SampahDokumen17 halaman2d3b - Kel.9 - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengolahan SampahKintan FebryBelum ada peringkat
- MAKALAH PENGELOLAAN SAMPAH - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah - 2D3A - Kelompok 5Dokumen12 halamanMAKALAH PENGELOLAAN SAMPAH - Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah - 2D3A - Kelompok 5helmalia abidahBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa IndonesiaDokumen18 halamanMakalah Bahasa Indonesiasamsuljihad582Belum ada peringkat
- Uts PKN Kemasyarakatan Nanda Aulia NursidkyahDokumen13 halamanUts PKN Kemasyarakatan Nanda Aulia NursidkyahNanda AuliaBelum ada peringkat
- SKRIPSI IDRUS BISMILLAH ACC AMIN ProffDokumen73 halamanSKRIPSI IDRUS BISMILLAH ACC AMIN ProffrskyanandacntikaBelum ada peringkat
- Risma Widiyawati, Ika RusdianaDokumen17 halamanRisma Widiyawati, Ika Rusdianapaklek joBelum ada peringkat
- Proposal Program Kreativitas MahasiswaDokumen8 halamanProposal Program Kreativitas MahasiswaRadhophan SevenfoldBelum ada peringkat
- Laporan LampuaraDokumen102 halamanLaporan LampuaraNiyaBelum ada peringkat
- Proposal 1Dokumen18 halamanProposal 134Ria FatmawatiBelum ada peringkat
- Tugas Akhir Pengembangan MasyarakatDokumen15 halamanTugas Akhir Pengembangan Masyarakatmurni ratnasariBelum ada peringkat
- Study KasusDokumen20 halamanStudy Kasuselda.sulistiawati1Belum ada peringkat
- Pengorganisasian Masyarakat-1Dokumen11 halamanPengorganisasian Masyarakat-1Jamal LBelum ada peringkat
- PPM Materi 5Dokumen21 halamanPPM Materi 5selviaBelum ada peringkat
- Konsep Pemberdayaan MasyarakatDokumen22 halamanKonsep Pemberdayaan Masyarakat035 I Gusti Ayu Dita Adinda PutriBelum ada peringkat
- Tugas Individu Pengembangan Dan Pengorganisasian MasyarakatDokumen8 halamanTugas Individu Pengembangan Dan Pengorganisasian MasyarakatFetry HusnayatyBelum ada peringkat
- ASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS Strategi Pelayanan Kebidanan Di KomunitasDokumen7 halamanASUHAN KEBIDANAN KOMUNITAS Strategi Pelayanan Kebidanan Di KomunitasUpi Krisdayanti LahaguBelum ada peringkat
- LktiDokumen9 halamanLktiaini denadaBelum ada peringkat
- KKN JatirokeDokumen4 halamanKKN JatirokeWildaniBelum ada peringkat
- JURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH (AutoRecovered)Dokumen13 halamanJURNAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI BANK SAMPAH (AutoRecovered)Iman SoedirmanBelum ada peringkat
- Pemberdayaan Masyarakat Perumahan - Dki Jakarta - 090 - Muhammad Akmal Abdillah - PKM-PMDokumen16 halamanPemberdayaan Masyarakat Perumahan - Dki Jakarta - 090 - Muhammad Akmal Abdillah - PKM-PMakmalabdillah1203Belum ada peringkat
- Wa0031.Dokumen2 halamanWa0031.Amalina Husna RosyidBelum ada peringkat
- Proposal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Air BersihDokumen16 halamanProposal Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Air BersihIbi Yulia Setyani100% (1)
- Pemberdayaan Masyarakat DesaDokumen11 halamanPemberdayaan Masyarakat DesaArisSekti100% (5)
- Kesadaran Mengelola Sampah Untuk Mendukung Program "Makassar Tidak Rantasa"Dokumen34 halamanKesadaran Mengelola Sampah Untuk Mendukung Program "Makassar Tidak Rantasa"Anggrek HitamBelum ada peringkat
- Laporan KKN ParDokumen11 halamanLaporan KKN ParYusuf Haidar AliBelum ada peringkat
- Pengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran MasyarakatDokumen10 halamanPengelolaan Sampah Secara Bersama: Peran Pemerintah Dan Kesadaran MasyarakatYudha KristantoBelum ada peringkat
- Makalah Pemberdayaan Masyarakat PetaniDokumen3 halamanMakalah Pemberdayaan Masyarakat PetaniM Afdal ZikriBelum ada peringkat
- Jurnal WbiDokumen14 halamanJurnal WbiIman SoedirmanBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membuat Kerajinan Dari KoranDokumen9 halamanTugas Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Membuat Kerajinan Dari KoranElvi AzzizahBelum ada peringkat
- ID Penanganan Sampah Sederhana Sebagai PrakDokumen20 halamanID Penanganan Sampah Sederhana Sebagai PrakFirda Arista KisriBelum ada peringkat
- Pemberdayaan Manusia Dan KesetaraanDokumen11 halamanPemberdayaan Manusia Dan KesetaraanNi Nyoman BinarBelum ada peringkat
- Buku Saku GNRM Rev 1Dokumen104 halamanBuku Saku GNRM Rev 1Rizqi SameraBelum ada peringkat
- Proposal Magang AANDI IHRAM ACTDokumen64 halamanProposal Magang AANDI IHRAM ACTAyu Wulan Sari100% (1)
- Konsep Pengorganisasian Masyarakat Dalam KeperawatanDokumen11 halamanKonsep Pengorganisasian Masyarakat Dalam KeperawatanWendy GoxilBelum ada peringkat
- Karya IlmiahDokumen6 halamanKarya Ilmiahimel sandrinaBelum ada peringkat
- Bab I PBLDokumen19 halamanBab I PBLfafa jin bao kucaiBelum ada peringkat
- Penyusunan Rencana Penyuluhan Ahli PDFDokumen53 halamanPenyusunan Rencana Penyuluhan Ahli PDFSyamsul RizalBelum ada peringkat
- Teknik Pendampingan Dan Manajemen Konflik1Dokumen26 halamanTeknik Pendampingan Dan Manajemen Konflik1scribdkuadiBelum ada peringkat
- Pengorganisasian KomunitasDokumen5 halamanPengorganisasian KomunitasClrnd SintyaBelum ada peringkat
- Laporan KKNDokumen18 halamanLaporan KKNAl Waqiah Al WaqiahBelum ada peringkat
- HANDOUT Rahayu MacroDokumen9 halamanHANDOUT Rahayu MacroSriRahayuBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan A. Latar BelakangDokumen26 halamanBab I Pendahuluan A. Latar BelakangUse inBelum ada peringkat
- $ Bab 1-5 MPKuantitatif (Bab - 2)Dokumen40 halaman$ Bab 1-5 MPKuantitatif (Bab - 2)Nofy HadiBelum ada peringkat
- Isi Makalah PPM Kel 5Dokumen14 halamanIsi Makalah PPM Kel 5El FinaBelum ada peringkat
- (Poin 4 Revisi) Kepala Swadaya Masyarakat Pengelola SampahDokumen12 halaman(Poin 4 Revisi) Kepala Swadaya Masyarakat Pengelola SampahMalik VoxBelum ada peringkat
- General Content Objektif Approach2Dokumen12 halamanGeneral Content Objektif Approach2Rulianto MaraullaBelum ada peringkat
- Managemen Dan Peraturan Perundangan Dalam Pengelolaan SampahDokumen10 halamanManagemen Dan Peraturan Perundangan Dalam Pengelolaan SampahFitria RahayuBelum ada peringkat
- Tugas UAS Pengmas - Khoirunnisa Dyah 25000219410017Dokumen6 halamanTugas UAS Pengmas - Khoirunnisa Dyah 25000219410017Khoirunnisa DyahBelum ada peringkat
- Uas Social Enterpreneurship - Siti Kusrini - 1901010038Dokumen4 halamanUas Social Enterpreneurship - Siti Kusrini - 1901010038PKBM Ki Hadjar DewantaraBelum ada peringkat
- Pemberdayaan Ma-WPS Office (Autosaved)Dokumen23 halamanPemberdayaan Ma-WPS Office (Autosaved)RahmawatiBelum ada peringkat
- Jurnal TalasemiaDokumen6 halamanJurnal TalasemiaDavid SilalahiBelum ada peringkat
- Daftar Hadir Tutorial & Nama KLPK Blok VDokumen37 halamanDaftar Hadir Tutorial & Nama KLPK Blok VsuyantokitBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian FK 2015mepenDokumen15 halamanProposal Penelitian FK 2015mepensuyantokitBelum ada peringkat
- Kurikulum Kader TBDokumen70 halamanKurikulum Kader TBsuyantokit100% (1)
- Fast Start Presentasi 5 JariDokumen1 halamanFast Start Presentasi 5 JarisuyantokitBelum ada peringkat
- Masalah Gizi Di Masa DatangDokumen16 halamanMasalah Gizi Di Masa DatangsuyantokitBelum ada peringkat
- Istilah Kesper (Mega Purnama Sari)Dokumen1 halamanIstilah Kesper (Mega Purnama Sari)suyantokitBelum ada peringkat
- Sanitasi PesawatDokumen14 halamanSanitasi Pesawatsuyantokit100% (2)
- Rumah SehatDokumen23 halamanRumah Sehatchaif100% (3)