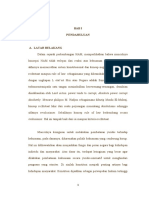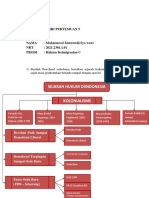PERS MASA PENJAJAHAN
Diunggah oleh
Prilly NathalyaDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
PERS MASA PENJAJAHAN
Diunggah oleh
Prilly NathalyaHak Cipta:
Format Tersedia
http://farelbae.wordpress.
com/catatan-kuliah-ku/pers-masa-penjajahan/ Peraturan pertama mengenai pers di jaman Negara Hindia Belanda dituangkan pada 1856, dalam Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie, yang bersifat pengawasan preventif. Aturan ini pada 1906 diperbaiki menjadi bersifat represif, yang menuntut setiap penerbit mengirim karya cetak ke pemerintah sebelum dicetak. Dua puluh lima tahun kemudian, pada 1931, pemerintah kolonial melahirkan Persbreidel Ordonnantie. Aturan ini memberikan hak kepada Gubernur Jenderal untuk melarang penerbitan yang dinilai bisa mengganggu ketertiban umum Selain itu pemerintah kolonial Belanda juga memiliki pasal-pasal terkenal, Haatzaai Artikelen, yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia Belanda berlaku sejak 1918.
http://yoanfa18.blogspot.com/2008/05/pers-nasional-di-masa-belanda.html Diantaranya sekelumit peraturan terdapat undang-undang sebagai berikut: 1. Drukpers reglement tahun 1856 tentang aturan sensor preventif. 2. Pers ordonantie tahun 1931 tentang pembredelan surat kabar. Kedua undang-undang tersebut menyulitkan keberadaan media-media pribumi saat itu. Mana yang dianggap oleh Belanda berseberangan maka tidak akan segan-segan dibreidel. Tokoh yagn menyuarakan tentang Indonesia mereka di media massa, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir, dibuang ke Boven Digul oleh dua penguasa tertinggi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yaitu Gubernur Jenderal De Jonge (1931-1936) dan Gubernur Jenderal Tjarda van Star. Alasan dari De Jonge adalah artikel-artikel tokoh pergerakan (memberi labelling) gezagsvijandige artikelen atau tulisan-tulisan yang memusuhi pemerintah. Selain undang-undang tersebut, tercatat masih ada beberapa peraturan lain. Dalam buku berjudul Maters tercatat ada lima periode pers dari tahun 1906-1942. Penjelasannya adalah sebagai berikut: 1.Periode I (1856-1913)
-coret lai apa yang dibatnya di dalam peraturan undang-undang preventif pada tahn 1906.
2. Periode II (1913-1918)
aan hukum pidana bagi yan melanar peraturan pers. -Belanda. 3. Periode III (1918-1927) sme dan nasionalisme radikal. 4.Periode IV (1927-1931) bit media cetak dinilai membelenggu pers. 5.Periode V (1931-1942)
Berbagai peraturan-peraturan buatan Belanda ini berakhir pada tahun 1942 , yakni saat masuknya Jepang ke Indonesia.
http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=3993&coid=3&caid=21&gid=2 http://arifusun.blogspot.com/2008/05/makalah-sejarah-pers-nasional.html http://catatancalonwartawan.wordpress.com/tag/undang-undang-pers/ http://gudangilmu-blooddy.blogspot.com/2010/04/sejarah-media-dan-sejarah-hukum-media.html http://kranten.kb.nl/themes/Perscensuur
SEJARAH pers dan hukum pers di Tanah Air sebenarnya sudah cukup panjang. Seperti diketahui, sejak awal peraturan pers dibuat adalah untuk m penjajah kolonial. Oleh sebab itu dibuatlah peraturan-peraturan oleh Pemerintah Belanda yang mengekang pers dan menindas para pejuang kemer ketentuan tentang delik pers dibuat sangat ketat dan karenanya banyak dikaitkan dengan ketentuan hatzaai-artikelen atau pasal-pasal penyebar keb Ketentuan tentang delik pers ini kemudian dirumuskan oleh dua ilmuwan hukum Belanda, yakni oleh WFC Van Hattum yang menyebut delik per middle van de drukpers gepleegd atau kejahatan yang dilakukan dengan pers. Yang kedua adalah Hazewingkel Suringa yang mengatakan bahwa d penghasutan, penghinaan, atau pencemaran nama baik yang dilakukan dengan barang cetak.
Telah banyak para pendiri republik ini yang dijerat oleh ketentuan hukum pers kolonial ini. Ambil contoh Ki Hajar Dewantoro. Karena tulisannya yang berjudul Als Ik, een Nederlander Was (Seandainya Saya Orang Belanda) tanggal 20 Juli 1913 ia harus dikucilkan dan dipenjara. Ki Hajar m yang merayakan kemerdekaannya di Indonesia. Ki Hajar mengatakan, kaum kolonial Belanda itu tidak pantas berpesta pora justru di negeri jajaha
Beberapa tahun kemudian dibuatlah Pressbreidel Ordonantie 1931 (yang kemudian dicabut pada zaman Soekarno tahun 1954). Ketentuan ini sebe British Indian Penal Code yang di negeri Belanda sendiri ditolak untuk diterapkan karena dianggap berasal dari hukum penjajah, Inggris. Akan te ordonansi 1931 ini dibawa ke Indonesia dan diterapkan di sini. Tujuannya? Sebagai alat politik untuk menekan kaum inlanders dan untuk menyel kaum kolonial. Celakanya, hukum kolonial tersebut dipertahankan dan diterapkan setelah kita merdeka. Makanya banyak terjadi pembredelan per Erdward C Smith (1983). Baik di zaman orde baru maupun orde lama, sudah banyak terjadi pemberangusan terhadap pers. Sejarah mencatat bahw pencabutan surat izin usaha penerbitan pers (SIUPP) ditiadakan dan pers dibebaskan baru terjadi sejak zaman reformasi.
SEJAK dicabutnya ketentuan tentang SIUPP dan pers dibebaskan, maka pers benar-benar menikmati kemerdekaannya. Namun, belakang ini kebe pers mulai agak terganggu. Mekanisme yang tersedia seperti hak jawab (right to hit back) tak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baikn Sebenarnya orang yang nama dan reputasinya sudah jelek di mata masyarakat, lalu diberitakan oleh media massa, ini namanya bukan "pencemara "penginformasian perilaku tercela". Kini pers banyak digugat. Selama kampanye ataupun Pemilu 2004 ini boleh jadi juga akan banyak gugatan te pencemaran nama baik misalnya. Kecenderungan seperti ini dapat menimbulkan ketakutan di kalangan wartawan untuk merdeka menulis. Jika ha maka yang rugi adalah masyarakat sendiri, sebab pers kata E Lloyd Sommerland adalah a spokesman for the public at large (1966:156) dan karen ditunggu oleh publik. http://gudangilmu-blooddy.blogspot.com/2010/04/sejarah-media-dan-sejarah-hukum-media.html C. Sejarah Media di Indonesia Sejarah pers di Nusantara dimulai sejak abad ke-8 ketika Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Bataviasche Nouwells tahun 1744, tiga abad setelah mesin cetak ditemukan oleh Gutenberg. Bila sejarah pers Indonesia dimulai sejak berdirinya Koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indietahun 1856. Bila sejarah Pers Indonesia dimulai sejak berdirinya Koran pertama tahun 1744, maka sejarah hukum media di Indonesia dimulai sejak keluarnya peraturan hukum tentang media yang pertama di Indonesia, yaitu tatkala Pemerintah Hindia Belanda memberlakukan Reglement po de Drukwerken in Nederlandsch-indie tahun 1856. Secara umum, sejarah hukum media di Indonesia dalam kurun waktu sekitar 1,5 abad sejak zaman Hindia Belanda hingga era reformasi di abad ke-21 diwarnao dengan ketentuan hukum yang mengekang kebebasan media, khususnya kebebasan pers. Meskipun terdapat pasang surut, namun secara umum pengekangan lebih menonjol daripada kebebasannya. Isi atau materi hukum media yang pernah berlaku di Indonesia bisa dibedakan dalam beberapa materi sebagai berikut : 1. Hukum yang member kewenangan penguasa untuk melakukan sensor preventif. Sensor preventif adalah sensor yang dilakukan sebelum sebuah media diterbitkan.
2. Hukum media yang memberi kewenangan kepada penguasa untuk menutup dan membredel sebuah media. 3. Hukum media yang member kewenangan kepada penguasa untuk mengeluarkan dan mencabut izin dan sebaliknya juga mewajibkan media untuk mendapatkan izin sebelum menerbitakan medianya. 4. Hukum media yang berisi jaminan kebebasan pers atau kebebasan media. Dilihat dari sifat peraturannya, sejarah hukum media dapat dibagi dalam tiga periode. 1. Pertama, periode sensor preventif. Periode ini dimulai sejak keluar peraturan pertama tentang pers yang mengatur sensor preventif sampai dicabutnya peraturan itu (1856-1906) dan dilanjutkan pada zaman Jepang (1942-1945). 2. Kedua, periode perizinan/pemberedelan. Periode ini berlangsung sejak kedatangan Jepang (1940-1942) dan kemudian berlanjut ketika terjadi pemberedelan 13 penerbit pada masa akhir Demokrasi Liberal sampai berakhirnya Orde Baru (1957-1998). 3. Ketiga, periode kebebasan pers. Periode ini dimulai sejak Republik Indonesia diproklamasikan hingga menjelang berakhirnya Demokrasi Liberal (1945-1957) dan dilanjutkan dengan pada masa reformasi (1998-sekarang). ketiga periode tersebut tidak dalam suatu pembatasan waktu yang ketat, karena pada masa yang disebut sebagai masa kebebasan pers terdapat upaya-upaya untuk mengekang pers. Pada masa sensor preventif juga terdapat pemberedelan. Pembagian periode ini juga tidak dibatasi oleh periodisasi kekuasaan politik. Sebab pergantian penguasa politik baik masa penjajahan (Belanda/Jepang) maupun masa kemerdekaan (Orde Baru/Orde Lama) masing-masng memiliki kesamaan dalam melihat kebebasan pers, perbedaannya terdapat pada gradasi bukan pada substansi. http://kranten.kb.nl/themes/Perscensuur Perscensuur in Nederlands-Indi Persvrijheid is er in Indi nooit geweest. In 1857 werd het 'Reglement op de drukwerken in Nederlandsch-Indi', kortweg 'Drukpersreglement', vastgesteld, het 'gewrocht der duisternis' volgens de liberaal Thorbecke. Het bevatte niet minder dan negen artikelen die waren gewijd aan de overtredingen die konden worden gepleegd en de daaraan verbonden straffen. Een redacteur kon bijvoorbeeld vervolgd worden, wanneer hij zich schuldig maakte aan 'smaad, hoon en laster' jegens de gouverneur-generaal (art. 23) of wanneer hij had 'opgezet tot haat of minachting tegen de regering van de kolonin' (art. 24). Vooral deze twee artikelen vormden de grond van spraakmakende persdelicten in de decennia na 1857. De geschiedenis van de negentiende-eeuwse Indische pers is er een geweest van steeds weer oplaaiende conflicten tussen kranten die streefden naar vrije meningsuiting en de koloniale overheid die dat streven dwarsboomde. Het leidde regelmatig tot vervolgingen. Een aantal rechtszaken is zeer geruchtmakend geweest, zoals die tegen H.J. Lion (in 1860), J. Nosse en S.E.W. Roorda van Eysinga (in 1864) beiden werden verbannen uit de kolonie - en P.A. Daum (in 1885), wiens krant niet meer mocht verschijnen. Onder invloed van politieke ontwikkelingen kwam er in het begin van de twintigste eeuw meer openheid in Indi met meer ruimte voor vrije nieuwsgaring. Het belang van de pers als alerte observator van misstanden in de kolonie werd erkend en gewaardeerd door de overheid. Dat verhoogde haar status en prestige. De 'haatzaai-artikelen' De ontwikkeling had betrekking op de Nederlandstalige kranten. Tot omstreeks 1900 was de Maleistalige pers nog van weinig betekenis. Dat werd anders toen de 'inlandse beweging' opkwam, die zich bij het uitdragen van haar idealen vanzelfsprekend bediende van kranten. Deze verwierven zich in korte tijd een plaats in het politieke krachtveld van de kolonie. Voor een groeiend aantal Europeanen was dat een doorn in het oog. Hun spreekbuis was de rechtse pers met Het nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indi en het Soerabaiasch Handelsblad als haar belangrijkste exponenten. Haar racistisch-krenkende bejegening van Indonesirs en hun leefwereld leidde tot steeds scherpere reacties van nationalistische kranten. Het uiten van minachting over en weer werd in korte tijd schering en inslag. Het is om die reden dat de koloniale pers - de Nederlandse en inheemse tezamen - een van de voornaamste bronnen is voor onze kennis over de dramatische wijze waarop de verhoudingen tussen het bestuur en de inlandse beweging, wat algemener gezegd tussen heersers en overheersten, zich ontwikkelden. Sterker nog: Nederlandse en nationalistische kranten hebben door de heftige manier waarop zij op elkaar reageerden die ontwikkeling in belangrijke mate benvloed. Om de toenemende agitatie te beteugelen kwamen in 1914 de zogenaamde 'haatzaai-artikelen' in het Indisch Wetboek voor Strafrecht terecht. Het uiten van vijandschap, haat of minachting jegens andere bevolkingsgroepen werd strafbaar gesteld. Door de willekeur echter waarmee de haatzaai-artikelen werden gehanteerd, schoten zij hun doel voorbij. Vanaf het moment dat journalisten terechtstonden vanwege de overtreding ervan, werd er met twee maten gemeten: verreweg de meeste aanklachten betroffen Indonesirs die steevast zwaar werden gestraft, terwijl hun Nederlandse collega's vaak werden vrijgesproken of er met een lichte straf vanaf kwamen. Alle ethische bedoelingen ten
spijt ging macht boven recht. Er was sprake van klasse- en rassenjustitie. De bitterheid in nationalistische kring groeide. Nederlanders en Indonesirs dreven steeds verder weg van elkaar. Persbreidelordonnantie De jaren twintig kenmerkten zich door grote maatschappelijke onrust. De oplopende spanningen culmineerden in de communistische opstand van eind 1926 en begin 1927. Alle inspanningen van A.C.D. de Graeff, de laatste 'ethische' gouverneur-generaal, om het vertrouwen terug te winnen van de gematigde nationalisten, waren vergeefs geweest. Het ging van kwaad tot erger. De rechtse kranten, onder leiding van Wybrands en Zentgraaff, attaqueerden De Graeff en zijn intenties op ongehoord grove wijze. Daarnaast eisten zij een meedogenloos optreden tegen alle toekomstige nationalistische uitingen. Zonder ophouden speelden zij in op de door de rebellie gewekte angstgevoelens van het Europese publiek. De toepassing door justitie van de haatzaai-artikelen, waar door critici om werd gevraagd, bleef achterwege, onder andere uit angst de publieke opinie over zich heen te krijgen. Het was onder die omstandigheden dat het gouvernement besloot een preventieve censuur in te stellen door het opleggen van schorsingen aan bladen die zich schuldig maakten aan een persdelict. In september 1931 trad de zogenaamde Persbreidelordonnantie in werking. Maar ook de toepassing van die ordonnantie was uiterst partijdig: tegen het fel antinationalistische sentiment in Nederlandse kranten werd vrijwel niet opgetreden, terwijl Indonesische bladen veelvuldig werden getroffen door een persbreidel. Na de muiterij op het oorlogschip 'De Zeven Provincin' in 1933 overspoelde een reactionaire vloedgolf de kolonie. Voor alternatieve geluiden was nu geheel geen plaats meer. De nationalistische pers werd de adem afgeknepen. Ook de weinige nog overgebleven linkprogressieve Nederlandse (week)bladen, de WestJava Courant, De Stuw en Het Indische Volk, verdwenen van het toneel. Indi had de karaktertrekken van een politiestaat gekregen. Literatuur Ahmad B. Adam, The vernacular press and the emergence of Modern Indonesian consciousness (1855-1913). Ithaca/New York 1995: Cornell University, Southeast Asia Program. [Studies on Southeast Asia 17.] Mirjam Maters, Van zachte wenk tot harde hand; Persvrijheid en persbreidel in Nederlands-Indi 1906-1942. Hilversum 1998: Verloren. Gerard Termorshuizen, Journalisten en heethoofden; Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van Anneke Scholte. Amsterdam/Leiden 2001: Nijgh & Van Ditmar en KITLV Uitgeverij. (het afsluitende deel, periode 1905-1942, verschijnt in mei 2011) Haatzaai Artikelen Pasal-pasal tentang penyebaran kebencian (haatzaai artikelen) terhadap Martabat Kerajaan diatur dalam Pasal 134 tentang opzettelijke belediging den Koning of der Koningin (penghinaan yang disengaja terhadap Raja atau Ratu); Pasal 135 opzettelijke belediging den gemaal der regerende Koningin, den troonopvolger, een lid van het Koninklijk Huis of den Regent (penghinaan yang disengaja terhadap suami Ratu yang memerintah, ahli waris tahta, anggota Keluarga Kerajaan atau Wali Raja); dan Pasal 136 opzettelijke belediging den Gouverneur-Generaal of den waarnemende Gouverneur-Generaal (penghinaan yang disengaja terhadap Gubernur Jenderal atau Gubernur Jenderal ad-interim). Penghinaan dapat dilakukan secara lisan, tulisan, gambar, terbuka ataupun tertutup, di hadapan yang dihina ataupun tidak di hadapan yang dihina adalah tindak pidana terhadap Martabat Kerajaan. http://www.suaramerdeka.com/harian/0505/19/opi03.htm haatzaai artikelen (pasal-pasal penyebarluasan perasaan permusuhan dan kebencian dalam masyarakat terhadap pemerintah yang sah). Kedua, seperti diketahui haatzaai artikelen ini diimpor pemerintah Belanda dari India sewaktu masih dijajah Inggris. Berasal dari Pasal 125a British Indian Penal Code. Tadinya pasal ini mau dimasukkan ke dalam KUHPidana Belanda (Wetboek van Strafrecht), tapi ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda waktu itu dan menyatakan bahwa pasal-pasal itu hanya cocok diberlakukan bagi penduduk di negeri jajahan. Kemudian pada tahun 1915, pasal-pasal mematikan itu dimasukkan ke dalam KUHPidana Hindia Belanda dan berlaku sampai sekarang. http://www.tempo.co/read/caping/1991/07/06/121/Sejarah Sabtu, 06 Juli 1991
HARI ini, hampir 60 tahun yang lalu. Pada tanggal 23 Juni 1933, Gubernur Jenderal De Jonge menurunkan satu perintah: koran Soeara Oemoem di Surabaya dibredel. Seorang wartawan bernama Tjindar Boemi lima bulan sebelumnya menerbitkan sebuah tulisan tentang pemberontakan di atas kapal De Zeven Provincien. Isinya dianggap "menghasut". Yang menarik ialah bahwa tindakan itu tidak terjadi mendadak. Dalam buku Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia yang diterbitkan oleh Proyek Penelitian Pengembangan Penerangan Deppen pada tahun 1980, disebutkan bagaimana titah Gubernur Jenderal itu bermula dari laporan Procureur Generaal pada tanggal 10 Februari 1933. Dalam laporan itu disebut adanya perintah kepada yang berwajib di Surabaya untuk menahan Tjindar Boemi. Juga untuk "mendengar keterangan" dari pimpinan Soeara Oemoem, dr. Soetomo, dan menyuruhnya "menandatangani pernyataan setia". Ternyata, di zaman kolonial itu, perintah macam itu tak bisa dengan serta-merta efektif. Pada tanggal 3 Maret, Raad van Indie, semacam dewan perwakilan masa itu, menyatakan tak setuju bila dr. Soetomo harus menandatangani pernyataan setia. Raad van Indie menyarankan tindakan terhadap dr. Soetomo "ditunggu saja" sampai pemeriksaan terhadap Tjindar Boemi selesai. Menghadapi reaksi ini, pihak Procureur Generaal meminta Gubernur Jenderal, penguasa tertinggi di Hindia Belanda waktu itu, menerapkan peraturan pembredelan pers atau Persbreidel Ordonnantie. Tak lupa, di dalam saran itu disertakan kutipan dari sebuah tulisan di Soeara Oemoem yang dinilai "bisa mengganggu ketertiban umum". Empat hari kemudian, Raad van Indie akhirnya juga menyarankan agar peraturan pembredelan pers itu dikenakan terhadap koran yang dipimpin dr. Soetomo. Maka, dibredellah Soeara Oemoem. Penting rasanya untuk disebut bahwa pembredelan hanya bisa berlangsung selama delapan hari. Pasal 2 dari Persbreidel Ordonnantie menyebutkan bahwa Gubernur Jenderal berhak melarang pencetakan, penerbitan, dan penyebaran sebuah surat kabar paling lama delapan hari. Jika sesudah terbit koran itu masih dinilai mengganggu "ketertiban umum", larangan terbit bisa jadi lebih lama, tapi tidak lebih lama dari 30 hari berturut-turut. Zaman itu tampaknya memang zaman yang keras bagi pers, tetapi bukan suatu masa yang kacau kepastian. Buku sejarah yang diterbitkan oleh proyek penelitian dan pengembangan Deppen itu menegaskan hal itu, "Dengan adanya ketentuan itu, maka pihak surat kabar yang terkena tidak menunggu-nunggu tak menentu ...." Larangan terbit yang mendadak-sontak juga tak ada. "Paling tidak," tulis buku yang redakturnya adalah Sejarawan Abdurrachman Surjomihardjo itu pula, "tidak dilakukan begitu saja ... seperti geledek di siang bolong."
Dengan jelas buku itu bahkan menyebutkan bahwa prosedur di zaman De Jonge lebih "rapi" daripada "yang terjadi sekarang" -- meskipun penilaian bahwa tulisan-tulisan tertentu "mengganggu ketertiban umum" sangat sepihak sifatnya. Semuanya, tulis buku sejarah itu, "hanya dilakukan oleh pihak penguasa dan tidak adanya kesempatan membela diri". Hari ini, sekitar 60 tahun yang lampau, mungkin bukan hari yang baik untuk belajar dari sejarah. Atau mungkin setiap generasi mempunyai pukulan-pukulannya sendiri. September 1957, ada 10 surat kabar dan tiga kantor berita serentak ditutup. Tetapi pembredelan yang luas yang pertama kalinya terjadi dalam sejarah pers Indonesia itu -- dilakukan oleh penguasa militer Jakarta Raya -- hanya berlangsung selama 23 jam. Betapapun, suatu babak baru tampaknya telah mulai: ada yang mencicipi enaknya dan ada yang mencicipi pahitnya. Pada 1 Oktober 1958 apa yang pernah berlaku di zaman penjajahan fasisme Jepang diberlakukan lagi di zaman kemerdekaan: setiap penerbitan harus mempunyai Surat Izin Terbit (SIT). Sebuah buku, Garis Perkembangan Pers Indonesia, yang diterbitkan oleh Serikat Penerbit Suratkabar pada tahun 1971 menyebut hal itu dengan muram, "Sejak 1 Oktober 1958, Sejarah Pers Indonesia memasuki periode hitam." "Tanggal 1 Oktober 1958," tulis buku itu, "dapat dikatakan sebagai tanggal matinya kebebasan pers di Indonesia. Surat kabar yang masih terbit sesudah itu harus mengikuti kehendak penguasa. Setiap waktu SIT dapat dicabut oleh Penguasa .... Sejak itu pers Indonesia bukan lagi sebagai salah satu lembaga demokrasi ...." Agaknya begitulah. Tanggal 24 Februari 1965, Menteri Penerangan membredel serentak 21 surat kabar. Alasan: mereka dituduh bersimpati kepada sesuatu yang terlarang, yakni "Badan Pendukung Sukarnoisme", sebuah organisasi yang menentang PKI. Dengan kata lain: mereka tidak sejalan dengan kehendak yang berkuasa. Mereka telah bersikap (untuk memakai tuduhan yang secara sepihak sering dilontarkan waktu itu) "kontrarevolusioner". Mereka harus "dibabat". Tidak ada lagi kepastian. Tidak ada lagi hak, bahkan untuk membeli diri. Sekian puluh tahun yang lalu, sekian puluh tahun kemudian .... Goenawan Mohamad
Kamus Gestok Hersri Setiawan, Galangpress Group, 2003
http://www.mail-archive.com/indonews@indo-news.com/msg07768.html Negara Koloni: Represi Silih Berganti Awal mula tradisi represi terhadap Pers Indonesia adalah warisan pemerintahan kolonial. Peraturan pertama mengenai pers di jaman Negara Hindia Belanda dituangkan pada 1856, dalam Reglement op de Drukwerken in Nederlandsch-Indie, yang bersifat pengawasan preventif. Aturan ini pada 1906 diperbaiki menjadi bersifat represif, yang menuntut setiap penerbit mengirim karya cetak ke pemerintah sebelum dicetak. Dua puluh lima tahun kemudian, pada 1931, pemerintah kolonial melahirkan Persbreidel Ordonnantie. Aturan ini memberikan hak kepada Gubernur Jenderal untuk melarang penerbitan yang dinilai bisa mengganggu ketertiban umum[3] Selain itu pemerintah kolonial Belanda juga memiliki pasal-pasal terkenal, Haatzaai Artikelen, yang mengancam hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Nederland atau Hindia Belandaberlaku sejak 1918.
International book publishing: an encyclopedia
Anda mungkin juga menyukai
- SEJARAHPERSDokumen18 halamanSEJARAHPERSNovia FaradilaBelum ada peringkat
- SEJARAH KEBEBASAN PERS DI INDONESIADokumen18 halamanSEJARAH KEBEBASAN PERS DI INDONESIAAnnisa Sofia Noviantina100% (1)
- Sejarah Kebebasan Berpendapat Dan Kemerdekaan Pers Di IndonesiaDokumen7 halamanSejarah Kebebasan Berpendapat Dan Kemerdekaan Pers Di IndonesiaFaiz IndriansyahBelum ada peringkat
- Tugas MakalahDokumen8 halamanTugas MakalahRereBelum ada peringkat
- Jurnalistik - BelandaDokumen4 halamanJurnalistik - BelandaSALSABIL NAJWA AZHARIBelum ada peringkat
- Teknik Mencari Dan Menulis Berita Diskusi 1Dokumen1 halamanTeknik Mencari Dan Menulis Berita Diskusi 1femtarBelum ada peringkat
- Hukum Media MassaDokumen12 halamanHukum Media MassaBajelizzerBelum ada peringkat
- Hukum Media MassaDokumen4 halamanHukum Media MassaRicoBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan: 1.1 Latar BelakangDokumen17 halamanBab I Pendahuluan: 1.1 Latar BelakangcawBelum ada peringkat
- Hukum Pers Dari Masa Ke MasaDokumen27 halamanHukum Pers Dari Masa Ke MasasalsabilnurazizahhBelum ada peringkat
- Powerpoint Peranan Pers Di IndonesiaDokumen36 halamanPowerpoint Peranan Pers Di IndonesiaRivaldi Pojan Mas60% (5)
- Perkembangan PersDokumen6 halamanPerkembangan PersRiki100% (1)
- Perkembangan Pers Di IndonesiaDokumen6 halamanPerkembangan Pers Di IndonesiaNur AsiaBelum ada peringkat
- HUKUM MEDIA MASSADokumen15 halamanHUKUM MEDIA MASSAFina Adithya RachmayantiBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Surat Kabar Di IndonesiaDokumen13 halamanSejarah Perkembangan Surat Kabar Di IndonesiaMuti AngelinaBelum ada peringkat
- A. Pengertian Pers: Tirtohadisorejo Atau Raden Djokomono, Pendiri Surat Kabar Mingguan Medan PriyayiDokumen15 halamanA. Pengertian Pers: Tirtohadisorejo Atau Raden Djokomono, Pendiri Surat Kabar Mingguan Medan PriyayiSamsul SyamsiBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Pers Di Indonesia Tidak Terlepas Dari Sejarah Politik IndonesiaDokumen2 halamanSejarah Perkembangan Pers Di Indonesia Tidak Terlepas Dari Sejarah Politik IndonesiaSolihin IhinBelum ada peringkat
- Perkembangan HAM di IndonesiaDokumen24 halamanPerkembangan HAM di IndonesiasdedisaputraBelum ada peringkat
- Peran Pers Koran Era ReformasiDokumen4 halamanPeran Pers Koran Era ReformasiRizky Achmad HidayatullohBelum ada peringkat
- Pers Indonesia: Sejarah dan PerkembangannyaDokumen36 halamanPers Indonesia: Sejarah dan PerkembangannyaWahyuu uuuBelum ada peringkat
- Aryanto-SISTEM PERS INDONESIADokumen10 halamanAryanto-SISTEM PERS INDONESIASupriadiBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Media - WPS OfficeDokumen6 halamanSejarah Perkembangan Media - WPS OfficeAgus AlfarisiBelum ada peringkat
- Bab III Peranan Pers (PKN SMK Kelas XII Semester 1)Dokumen14 halamanBab III Peranan Pers (PKN SMK Kelas XII Semester 1)Dicky Mardiansyah50% (8)
- PERAN PERSDokumen13 halamanPERAN PERSMuhammad RafyBelum ada peringkat
- Makalah Sejarah Hukum IndonesiaDokumen11 halamanMakalah Sejarah Hukum Indonesiasiti rohmahBelum ada peringkat
- Fungsi Pers Secara UmumDokumen3 halamanFungsi Pers Secara UmumAnisa CarinaBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan PersDokumen7 halamanSejarah Perkembangan Perslini1969_n10tangselBelum ada peringkat
- Tugas PPKNDokumen16 halamanTugas PPKNTMR ChannelBelum ada peringkat
- Teori Pers Di Indonesia - Idris AbqoryDokumen7 halamanTeori Pers Di Indonesia - Idris Abqorybunda gardeniaBelum ada peringkat
- Tugas PKN PersDokumen8 halamanTugas PKN PersHasmira ZiniaBelum ada peringkat
- Pwerpoint Peranan Pers Di Indonesia-1Dokumen29 halamanPwerpoint Peranan Pers Di Indonesia-1nikmahsuryandariBelum ada peringkat
- 03-Muhammad Mutawalli Sya'rawi-Hukum C-PHI 2022Dokumen8 halaman03-Muhammad Mutawalli Sya'rawi-Hukum C-PHI 2022Annisa PraditaBelum ada peringkat
- Diskusi 1 Teknik Mencari Dan Menulis BeritaDokumen3 halamanDiskusi 1 Teknik Mencari Dan Menulis Beritaemelia sipahutarBelum ada peringkat
- 10 Politik Media Di IndonesiaDokumen34 halaman10 Politik Media Di IndonesiaNajwa NabillaBelum ada peringkat
- SEJARAH HAM DUNIADokumen17 halamanSEJARAH HAM DUNIAIna Aina IrliandiBelum ada peringkat
- Perkembangan Pers Pada Masa Orde LamaDokumen23 halamanPerkembangan Pers Pada Masa Orde LamaDandi PerdanaBelum ada peringkat
- Pengertian Pers Menurut para AhliDokumen17 halamanPengertian Pers Menurut para Ahlim. arif budi setiawanBelum ada peringkat
- Tugas MK - Sistem Hukum Resume Bab Iii Ilham Shafrudin H.Dokumen4 halamanTugas MK - Sistem Hukum Resume Bab Iii Ilham Shafrudin H.ilham.shafrudin39Belum ada peringkat
- Regulasi Media Jaman Orde Baru dan ReformasiDokumen43 halamanRegulasi Media Jaman Orde Baru dan ReformasiIntan Imarmas Nababan578Belum ada peringkat
- Sejarah Pengantar Hukum IndonesiaDokumen4 halamanSejarah Pengantar Hukum IndonesiaMohammadTaufan100% (5)
- Kilas Sejarah Pers IndonesiaDokumen7 halamanKilas Sejarah Pers IndonesiaZakki AlbantaniBelum ada peringkat
- Jurnalis Sejarah Hari PersDokumen16 halamanJurnalis Sejarah Hari PersAsdar Waris To KappungBelum ada peringkat
- MAKALAH Hukum Dan Etika Media MasaaDokumen13 halamanMAKALAH Hukum Dan Etika Media MasaaTomatsu HarukaBelum ada peringkat
- PERKEMBANGAN PERS DI INDONESIADokumen14 halamanPERKEMBANGAN PERS DI INDONESIAsiskaBelum ada peringkat
- Tugas Sejarah Perkembangan H.hamDokumen2 halamanTugas Sejarah Perkembangan H.hamSiti ZubaidahBelum ada peringkat
- Makalah Pembreidelan TempoDokumen16 halamanMakalah Pembreidelan TempoShei LatiefahBelum ada peringkat
- Kel 2 - Perkembangan Pers Di IndonesiaDokumen13 halamanKel 2 - Perkembangan Pers Di IndonesiaNur LailaBelum ada peringkat
- Makalah Pers (PPKN Bab 3)Dokumen19 halamanMakalah Pers (PPKN Bab 3)Nur Laila IIBelum ada peringkat
- Makalah Peran Pers Di Indonesia (Tugas SMAN 3 Bandung)Dokumen11 halamanMakalah Peran Pers Di Indonesia (Tugas SMAN 3 Bandung)Denss100% (1)
- Peranan Pers di IndonesiaDokumen3 halamanPeranan Pers di Indonesianadia indah putriBelum ada peringkat
- PersDokumen9 halamanPersMuhammad Alinur SBelum ada peringkat
- Regulasi Kebebasan PersDokumen4 halamanRegulasi Kebebasan PersCandra KusumaBelum ada peringkat
- PERS SEBAGAI BAGIANDokumen10 halamanPERS SEBAGAI BAGIANAndri AgustianBelum ada peringkat
- Hukum Media MassaDokumen4 halamanHukum Media MassaBPKP Maluku UtaraBelum ada peringkat
- Alif Ferdiansyah Pengantar Hukum IndonesiaDokumen6 halamanAlif Ferdiansyah Pengantar Hukum IndonesiaALIF FERDIANSYAHBelum ada peringkat
- Teori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaDari EverandTeori bipolar dunia:Jalan ke komunisme ditemukan dalam struktur evolusi sejarah duniaPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Ebook Ubuntu IndonesiaDokumen215 halamanEbook Ubuntu IndonesiaIskandarBelum ada peringkat
- Dear Dylan PDFDokumen165 halamanDear Dylan PDFmochi90100% (2)
- Jawaban Ujian PIHDokumen7 halamanJawaban Ujian PIHPrilly NathalyaBelum ada peringkat
- Contoh PenelitianDokumen1 halamanContoh PenelitianPrilly NathalyaBelum ada peringkat
- Ebook Ubuntu IndonesiaDokumen215 halamanEbook Ubuntu IndonesiaIskandarBelum ada peringkat
- Pepes JamurDokumen2 halamanPepes JamurPrilly NathalyaBelum ada peringkat