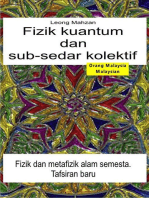Bab III Positivisme Dalam Teori Dan Ajaran1
Bab III Positivisme Dalam Teori Dan Ajaran1
Diunggah oleh
Yunita PuspitasariHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bab III Positivisme Dalam Teori Dan Ajaran1
Bab III Positivisme Dalam Teori Dan Ajaran1
Diunggah oleh
Yunita PuspitasariHak Cipta:
Format Tersedia
Handout 'Teori-Teori Sosial Untuk Kajian Hukum' Prof.
Soetandyo Wignjosoebroto
03
POSITIVISME :
PARADIGMA KE ARAH LAHIRNYA TEORI-TEORI SOSIAL
Positivisme itu adalah suatu paham falsafati dalam alur tradisi pemikiran saintisme yang mengedepan sejak abad-abad 16-17. Apa yang kemudian disebut saintisme (<science<scire= pengetahuan) ini pertama-tama marak di kalangan para ahli astronomi dan fisika, yang kemudian juga di berbagai cabang ilmu pengetahuan yang lain, bahkan juga yang berkonsentrasi di bidang persoalan kemasyarakatan dan hukum. Sebagaimana tradisi pemikiran yang berparadigma Galilean, yang menjadi cikal-bakal scientism, positivisme juga bertolak dari anggapan aksionatik bahwa alam semesta ini pada hakikatnya adalah suatu himpunan fenomen yang berhubung-hubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang sekalipun dinamik namun juga deterministik dan mekanistik. Di sini fenomen yang satu akan selalu dapat dijelaskan sebagai penyebab atau akibat dari fenomen yang lain. Hubungan sebab-akibat seperti ini dikatakan berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah suatu alam objektif yang indrawi, tersimak sebagai kejadian-kejadian yang faktual dan actual, lepas dari kehendak subjektif sesiapapun. Dikatakanlah bahwa hubungan kausalitas antar-fenomen itu dikuasai oleh suatu imperativa alami yang berlaku universal, dan yang oleh sebab itu dapat saja berulang atau diulang, di manapun dan kapanpun asal saja syarat atau kondisinya tak berbeda atau tak berubah (ceteris paribus!). Asal saja fenomen peneyebabnya diketahui, dan kondisi tak berubah, maka terulangnya kasus akan selalu dapat saja diprakirakan atau bahkan diramalkan.
Positivism: Suatu Metodologi Scientism Yang Dipakai Untuk Menjelaskan Liku-Liku Kehidupan Manusia dalam Masyarakat Positivisme -- sekalipun dengan nama dan dalam bentuk lain telah lama dikenal dalam kehidupan intelektual manusia di Barat tertengarai berkembang sebagai hasil pemikiran falsafati seseorang yang bernama Auguste Comte (1798-1857) dari Perancis. Comte, yang melanjutkan ide Madame de Stael dan Henry Saint-Simon ke tahap pemikiran yang lebih bermakna, menuliskan bagaimana metode sains dapat juga didayagunakan untuk mengkaji fenomen sosial. Comte yang berlatarbelakangkan kesarjanaan matematika dan fisika menyatakan keyakinannya bahwa konsep dan metode ilmu pengetahuan alam (yang dipakai untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat antarbenda anorganik yang mati) dapat juga dipakai untuk menjelaskan alam kehidupan kolektif manusia (yang, seabad kemudian, oleh Kroeber dikatakan berada pada tataran supraorganik). Untuk keyakinannya itulah maka, dalam dunia sains, Comte secara tepat atau tidak acap digelari Bapak Sosiologi. Menurut Comte, kehidupan manusia itu -- sebagaimana peristiwa-peristiwa yang berlangsung seperti apa adanya di kancah alam benda-benda anorganik pun terjadi di bawah imperativa hukum sebab-akibat yang berlaku universal. Dikatakan bahwa kehidupan manusia itu yang individual maupun (lebih-lebih lagi!) yang kolektif adalah selalu terlepas dari kehendak dan/atau rencana sesiapapun yang subjektif. Imperativa hukum sebab-akibat yang berlaku universal
dan yang tak akan mungkin terbantah ini benar-benar telah dikonsepkan oleh Comte (dan penerusnya yang berpaham positivisme) sebagai paradigma rule of law. Adapun law yang dimaksud di sini (harap diperhatikan dengan sungguh-sungguh) adalah law yang berdayalaku universal serta berkedudukan tertinggi (having supremacy state of law), lepas dari kehendak sesiapapun yang subjektif. Berpikir positivistik adalah berpikir nonteleologis (<teleos=berarah ke suatu tujuan yang final), sehingga terjadinya setiap akibat mestilah secara logis dan lugas diterima sebagai konsekuensi terjadinya suatu sebab. Dari paradigmanya yang nonteleologik seperti itu, kaum positivis tak mengenal istilah rule of man atau rule of human being atau rule of other beings (yang supranatural sekalipun). Dalam kehidupan alam yang dikaji oleh IPA ataupun dalam kehidupan manusia yang dikaji oleh IPS, paradigma seperti itulah yang berlaku. Sebagaimana halnya dengan kejadian-kejadian di alam semesta yang tunduk pada suatu hukum yang sifatnya universal dan objektif, kehidupan manusiapun selalu saja dapat dijelaskan dalam wujudnya sebagai proses-proses aktualisasi hukum sebab-akibat yang berlaku universal itu pula. Maka . Maka, ini berarti bahwa setiap kejadian dan/atau perbuatan dalam kehidupan manusia pada tatarannya yang individual sekalipun -- selalu saja dapat dan secara ontologik dan epistimologik mestilah dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional dan alami, dan yang karena itu bersifat ilmiah/scientific. Setiap kejadian alam dan perbuatan manusia adalah sama-sama tidak dapat dijelas-jelaskan dari substansinya yang berupa niat dan tujuannya itu sendiri (yang moral-altruistik dan bahkan sering metafisikal atau metayuridis!) melainkan dari apa yang tertampakkan dalam wujud-wujudnya yang tersimak itu saja. Mencoba menjelas-jelaskan kehadiran suatu peristiwa dari esensinya, dan tidak dari fenomen penyebabnya, adalah suatu usaha yang harus dianggap tidak ilmiah/unscientific. Metodologi Monisme Kaum Positivis, Yang Juga Dikembangkan Orang di Ranah Jurisprudence Berpenjelasan seperti itu, kaum positivis ini sesungguhnya menganut paham monisme dalam ihwal metodologi keilmuan. Artinya, bahwa dalam kajian sains itu hanya ada satu metode saja yang dapat dipakai untuk menghasilkan simpulan yang berkepastian dan lugas. Itulah scientific method yang secara objektif benar untuk didayagunakan dalam kajian ilmu pengetahuan, baik yang alam dan hayat (natural and life sciences) maupun yang social-kultural (social sciences). Menurut kaum positivis ini, mempelajari perilaku benda-benda mati dalam fisika dan mempelajari perilaku manusia (yang konon mempunyai jiwa dan ruh) tidaklah perlu dibedakan. Dua macam perilaku dalam ranah yang berbeda ini dikatakan sama-sama dikontrol oleh hukum sebab-akibat yang hanya dapat dijelaskan sebagai imperativa-imperativa yang berlaku secara universal. Syahdan, memasuki abad 20, sebagaimana dibuktikan dengan diselenggarakannya pertemuan ilmuwan dari berbagai kalangan disiplin sedunia di Wina pada tahun 1928, positivisme kian tampil untuk meneguhkan keyakinannya akan kebenaran monisme dalam metodologi ilmu pengetahuan. Ditegaskan dalam pertemuan itu bahwa hanya ada satu metode untuk menemukan pengetahuan yang akan dapat diakui berkebenaran menurut tolok ilmu pengetahuan (scientific truth). Semua upaya manusia untuk memperoleh pengetahuan yang terakui kesahihan (validity) dan keterandalannya (reliabililty) baik itu pengetahuan tentang fenomen anorganik dan organik maupun yang tentang fenomen supraorganik (=social-kultural) mestilah mengikuti metodologi yang sama. Ialah mengikuti aturan-aturan prosedural untuk memperoleh pengetahuan tentang suatu fenomen yang bersih dari sembarang unsur yang bersifat evaluatif dan yang karena tak berada di ranah indrawi yang kasatmata lalu menjadi sulit diukur-ukur sebagai variabel. Fenomen adalah fenomen, dan sebagai objek sains, fenomen secara nominal adalah realitas indrawi yang objektif. Maka dalam sains yang lugas dan buta-nilai itu tidak perlulah orang mencoba-coba mempersoalkan isi kandungannya yang substantif, ialah yang normatif, etis ataupun estetis (yang mungkin saja ada
pada fenomen-fenomen itu). Dari situlah bermulanya kerisauan puak pemikir dan pengkaji sosial yang tak habis pikir bagaimana mungkin fenomen manusia bisa direduksi secara konseptual cuma merupakan perilakuperilaku jasmaniah yang kasatmata semata? Memang mungkin saja betul apa yang dikatakan kaum positivis, ialah bahwa metodologi yang memungkinkan eksperimentasi -- berdasarkan hasil pengamatan dan pengukuran yang akurat, berketerandalan dan sahih dapat menjelaskan banayak hal mengenai objek-objek alam mati dan alam hidup yang nonmanusia. Akan tetapi, metodologi semacam ini dapatkah menjelaskan (explaining, erklaerung), apalagi untuk lebih lanjut memahami (understanding, verstehen) secara total dan utuh perilaku manusia yang kompleks ini? Bukankah apa yang menampak dalam perilaku dan tindakan manusia itu sebenarnya tak cuma bergatra fisikalbehavioral saja, melainkan juga berhakikat sebagai manifestasi-manifestasi itikat dan semangat, niat dan tekad? Dari sinilah pulalah awal cabaran terhadap pemikiran kaum positivis yang selama ini menggerakkan pemikirannya dari pangkalan bertolak Galilean yang berparadigma deterministik itu. Bermula dari Max Weber, atau barangkali juga sebelumnya dari Karl Marx, datanglah pemikiran antitetik bahwa unsur intensi atau kehendak manusia kalaupun bukan kehendak suatu dzat kekuatan supranatural yang metafisikal haruslah ikut diperhitungkan dalam kajian-kajian yang bersangkutanm dengan kehidupan manusia yang riil. Hukum sebab-akibat yang dicoba diungkap untuk memperoleh kejelasan lewat kajian-kajian sains, dengan atau tanpa eksperimentasi, dalam alam kehidupan manusia tidaklah akan berlangsung sepenuhnya di alam yang objektif, terlepas dari kontrol subjek-subjek yang manusia itu. Pada kasus-kasusnya yang kongkrit, yang dikualifikasi sebagai kasus-kasus yang down to earth atau grounded, unsur kehendak subjektif manusia akan selalu tersimak mengintervensi dan mencabar kebenaran hukum sebab-akibat (yang semula diklaim bersifat universal itu). Pada kajian-kajian yang lebih menggrondid dan menjurus ke paradigma barunya yang lebih mengarah ke seni hermeunetika seperti ini kehidupan manusia menjadi lebih tertampak secara riil dalam diskripsi-diskripsi yang lebih partikularistik (kalaupun tak singularistik), serta pula mengesankan hadir dan bekerjanya kekuatan-kekuatan manusiawi yang rasional dan indeterministik. Dari sini pulalah datangnya kesadaran para pengkaji ilmu pengetahuan sosial bahwa ilmu yang satu ini seperti yang ditulis oleh George Ritzer sesungguhnya berparadigma ganda dan oleh sebab itu pula juga bermetodologi ganda. Pada tataran makro-struktural yang berobjekkan pola perilaku manusia yang terinstitusionalisasi metodologi sains yang klasik dan yang memungkinkan kerja-kerja (quasi)- eksperimental tidaklah menimbulkan keberatan apapun apabila digunakan. Akan tetapi pada tataran yang mikro-interaksional, suatu metodologi baru yang dapat didayagunakan untuk mengajuk lebih dalam ke dalam alam imaji manusia yang kaya dengan simbol dan makna-makna yang tak pernah dikenal dalam kajian-kajian fisika atas benda-benda mati amat lebih diperlukan Apa yang diupayakan oleh Anselm Strauss dan Barney, dengan hasil yang ditulis dalam publikasi mereka berdua The Discovery of Grounded Theory Research adalah contoh usaha menanggapi kebutuhan metodologi yang baru ini.
Positivisme/Legisme Dalam Alam Pemikiran Para Pengkaji Ilmu Hukum (Jurisprudence) Introduksi positivisme untuk menjelaskan liku-liku kehidupan bermasyarakat manusia, yang pada waktu itu tengah berkembang menuju ke kehidupan beruang lingkup nasional, memang setidak-tidaknya pada masa-masa awalnya cukup memenuhi harapan. Tertib masyarakat baru yang telah kehilangan karakter agraris-feodalistiknya, untuk segera beranjak ke modelnya yang kapitalistik-industrial, sudah sulit bisa dijelaskan atas dasar paradigmanya yang lama. Ialah paradigma yang acapkali tak cuma teleologik tapi juga teologik, seperti yang misalnya dikemukakan oleh Gottfried`Wilhelm Leibniz (1646-1716) tentang asumsi adanya pre-estabvlished harmonious order yang final dalam seluruh tatanan di alam semesta ini.
Maka transisi ke model kehidupan baru -- dari yang lokal-parokhial ke yang translokalnasional dengan berbagai krisis dan suasana chaosnya terasa benar kian memerlukan model kontrol-kontrol baru yang sentral. Inilah kontrol yang diyakini akan dapat diefektifkan lewat asumsi-asumsi paradigmatik yang baru namun juga lebih saintifik, ialah kontrol atas suatu akibat dengan mengontrol fenomen penyebabnya. Inilah kontrol yang tak lagi bisa diserahkan kepada bekerjanya Leibnizian ius yang menjamin keselarasan secara alami, melainkan yang harus diupayakan dengan paradigma baru yang Galilean, yang secara lebih positif tak hanya mampu menjelaskan hubungan kausalitas antara fenomen kontrol dengan tertib perilaku dalam masyarakat, melainkan bisa pula mengupayakan terwujudnya suatu ketertiban pada tataran yang lebih bertaraf nasional. Maka dari sinilah datangnya penjelasan mengapa Leibnizian ius serta merta ditinggalkan untuk digantikan Comtian ius constitutum guna memenuhi kebutuhan bangsa untuk membangun tertib hukum nasional. Paradigma epistomologik Galilean yang berlanjut sebagai model dalam pemikiran positivisme seperti itu secara nyata dan serta merta segera saja teraplikasikan di dalam alam pemikiran hukum, untuk mempositifkan ius dalam bentuknya yang constitutum menjadi lege atau lex (aturan yang tertulis dengan jelas dan tegas, ialah aturan undang-undang). Mengklaim diri bahwa ilmu hukum adalah sekaligus juga ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang sudah semestinya tertib mengikuti norma-norma kausalitas, maka para penganut positivisme dalam perkara berhukum-hukum ini mengklaim juga bahwasanya kajian ilmiah mereka tidak lagi sebatas kajian dalam bilangan jurisprudence (yang berarti kearifan yuris). Sekalipun di Eropa pada abad 19 kajian-kajian hukum nasional secara positivistik ini sudah dipopulerkan dengan sebutan sebagai positive jurisprudence di Amerika Serikat, pada akhir abad 19 itu, di tangan Langdell yang gurubesar hukum di Universitas Harvard kajian hukum yang posiotivistik seperti itu lebih tegas lagi disebut legal science atau mechanistic jurisprudence. Positive jurisprudence yang,di tangan Hans Kelsen diklaim sebagai eine reine Rechtslehre, atau setepatnya (seperti yang harus dikatakan berkenaan dengan mechanistic jurisprudence tersebut di muka) harus disebut legalisme atau legisme*) telah benar-benar mereduksi eksistensi manusia di dalam seluruh proses kehidupan yang dikuasai oleh keniscayaan hukum kausalitas. Bertolak dari paham seperti ini, manusia tidak terpikir untuk dikonsepkan sebagai subjek-subjek yang mempunyai kehendak bebas. Meminjam kata-kata Rousseau, positivisme sepertuinya hendak menyatakan bahwa manusia-manusia itu memang dilahirkan sebagai makhluk bebas, akan tetapi di dalam kehidupan yang nyata di masyarakat ini mereka itu akan menemukan dirinya terikat di mana-mana. Kehidupan manusia dikuasai dan dikontrol oleh seperangkat hukum positif yang lengkap dan tuntas serta bersanksi, demikian rupa sehingga diyakinilah bahwa law is society. Hukum dipositifkan dengan statusnya yang tertinggi di antara berbagai norma (the supreme state of law), terdiri dari suatu rangkaian panjang pernyataanpernyataan tentang berbagai perbuatan yang didefinisikan sebagai fakta hukum dengan konsekuensinya yang disebut akibat hukum.
Keteraturan Dalam Kehidupan Manusia Yang Disebut Hukum:
* )
Secara salah kaprah, paham Kelsenian dan semua derivatnya yang mengetengahkan ajaran hukum murni ini disebut dengan aliran positivisme. Sesungguhnya, semua aliran teori dan/atau ajaran dalam kajian-kajian hukum itu, selama bermetodologi lanjutan dari keyakinan adanya kausalitas dalam ihwal perilaku hukum manusia (yang nomotetik maupoun dalam modelnya yang normatif), selama itu pula ajaran atau aliran paham dalam ilmu hukum itu harus dibilangkan ke dalam kategori positivisme. Lebih tepat kiranya apabila paham-paham aliran tersebut -yang mempositifkan hukum (ius) dengan cara membentuknya ke dalam wujud statemen-statemen normatif yang disebut aturan undang-undang itu -- disebut saja legisme atau legalisme (< lege = undang-undang).
Tidak Lagi Dihakikatkan Sebagai Bagian Dari Gods Moral Order, Melainkan Diteorikan Sebagai Hasil Akhir Suatu ProsesTransakasi Yang Acak Pengaruh model berpikir saintifik yang juga dikenali sebagai model berpikir positivistik seperti ini ternyata merasuk ke dan marak pula di dalam alam pemikiran berhukum-hukum untuk menata kehidupan manusia yang pada abad-abad 18-19 memasuki skala dan formatnya yang baru. Industrialisasi dan sekularisasi kehidupan telah kian menggiring kehidupan dari satuan-satuan lokal yang tradisional ke bentuknya yang baru sebagai negara bangsa. Berseiring dengan kebutuhan untuk membangun hukum baru sebagai sarana control tertib kehidupan pada skala nasional ini, pemikiran yang berlangsung menurut alur positivisme Galillean itu segera saja didayagunakan untuk melandasi paradigma pembentukan hukum nasional yang modern. Perkembangan hukum yang diperlukan untuk mengontrol kehidupan negara bangsa yang modern ini mencita-citakan terwujudnya jaminan akan kepastian dalam hal pelaksanaan hukum sebagai sarana piata tertib itu. Hukum menurut modelnya yang baru ini diperlukan para reformis untuk mengatasi kesemena-menaan para penguasa otokrat di masa lalu dalam ihwal penciptaan dan pelaksanaan hukum. Sejak awal mula, para penguasa otokrat ini mengklaim dirinya secara sepihak sebagai penegak hukum yang bersumber dari kekuasaan Illahi yang Maha Sempurna. Tiadanya rujukan normatif yang dapat didayagunakan untuk mencheck menjadikan hukum raja (kings order) ini terkesan amat semena-mena dan represif. Tiadanya rujukan normatif juga menyebabkan tiadanya kepastian mengenai apa yang harus digolongkan sebagai rujukan normatif yang berlaku guna menjamin keteraturan dalam kehidupan nasional, dan mana pula yang tidak atau belum. Di sinilah awal pemikiran yang hendak mengetengahkan dan memperjuangkan ide bahwa apa yang dimaklumatkan sebagai hukum haruslah mempunyai statusnya yang positif, dalam arti telah disahkan tegas-tegas (positif!) sebagai hukum, dengan membentuknya dalam wujud produk perundang-undangan. Inilah pemikiran positivisme yang amat marak pada masa pasca revolusi Perancis, yang serta merta menolak segala pemikiran yang serba metafisik, dan menolak pula prakltik-praktik penyelenggaraan tertib kehidupan atas dasar rujukan yang metayuridis. Inilah era tatkala, baik dalam teori maupun dalam praktik hukum, orang tidak lagi mau bicara tentang hukum yang belum berbentuk, (disebut ius). Akan gantinya, pada era ini, apabila orang bicara tentang hukum, yang mereka maksudkan tak lain daripada ius yang telah dibentuk (ius constitutum). yang juga disebut lex (kalau satu) atau lege (apabila berjumlah lebih dari satu), . Inilah tipe hukum yang di dalam Bahasa Indonesia diistilahi hukum undang-undang. . Setiap undang-undang berikut unsur-unsur yang ada di dalamnya (yang disebut pasal atau ayat), ditandai secara resmi dengan penomoran. Setiap unsur ini terbaca sebagai aturan, berupa kalimat yang menyatakan ada-tidaknya suatu peristiwa atau perbuatan tertentu (disebut fakta hukum, iudex facti), yang disusul dengan pernyataan tentang apa yang akan menjadi akibatnya (akibat hukum). Setiap kalimat pernyataan yang berfungsi sebagai aturan bersanksi ini memang acapkali dipersepsi dan dikonsepsi sebagai perintah-perintah untuk berbuat atau tak berbuat dengan segala konsekuensinya. Terbaca seperti itu, kalimat-kalimat tersebut tak salah kalau dipahami sebagai norma-norma; namun demikian, didasari oleh paham positivisme yang bernalar atas dasar hubungan sebab-akibat, setiap kalimat yang terumus itu dapat pula dipersepsi dan dikonsepsi sebagai nomos. Maka, dalam khazanah peristilahan hukum nasional modern, setiap baris aturan dalam setiap undang-undang disebut norma-norma positif, dan keseluruhannya disebut hukum positif (sebagai kataganti istilah hukum perundang-undangan). Difungsikan sebagai apa yang disebut Robert Redfield dan Donald Black sebagai governments social control, norma-norma positif ditata secara sistematis ke dalam suatu corpus juris yang berkoherensi tinggi, sebagaimana dirasionalisasikan lewat pengembangan teori-teori dan doktrin-doktrin. Dalam upaya sistematisasi ini pulalah terwujudnya organisasi hukum perundangundangan itu dalam tatanan yang hierarkik, berdasarkan hierarki posisi badan-badan pembentuknya. Selanjutnya, mengalami positivisasi dan sistematisasi, hukum perundang-undangan nasional yang modern inipun serta merta menuntut pengelolaan dan perawatannya untuk kepentingan adjudikasi
dalam proses-proses yudisial yang tidak asal-asalan, melainkan yang professional. Para pengelola ini adalah ahli-ahli yang terdidik sampai ke tingkat universiter,disebut jurists di Eropa Kontinental atau lawyers di Amerika. Jaminan akan berlakunya kepastian hukum, demi terwujudnya keteraturan dalam kehidupan nasional, yang diupayakan lewat langkah-langkah positivisasi dan sistemastisasi sebagaimana diutarakan di muka itu, pada akhirnya memerlukan pengukuhan dan penegakannya pada ranahnya yang politik. Upaya itu tidaklah cukup manakala cuma disokong oleh legitimasi-legitimasinya dari dunia akademi dan atau profesi. . Dari sinilah awal pembentukan institusi-institusi yang berfungsi sebagai badan-badan pemerintahan, dengan segala konfigurasi politiknya, yang berwenang untuk membentuk dan/atau membuat norma-norma positif dalam wujudnya sebagai undang-undang (ialah badan legislatif), untuk merealisasikan norma-norma positif itu benar-benar bermakna dalam kancah kehidupan nasional (ialah badan eksekutif), dan juga untuk mendayagunakannya dalam setiap penyelesaian perkara-perkara yang relevan dalam kehidupan hukum (ialah badan yudisial). Hukum Nasional Yang Modern: Tentang Doktrinnya Yang Disusun Atas Dasar Logika Positivisme Yang Lugas Berbeda dari hukum yang berparadigma Aristotelian dan yang mendasarkan diri pada paradigma Aristotelian, yang lebih bernuansa falsafati dan lebih mengekspresikan nilai-nilai moralitas, hukum nasional dibangun atas dasar paham aliran falsafah positivisme yang menghendaki penegasan (demi kepastian!) mana yang harus didefinisikan dan dikategorikan sebagai hukum, dan mana pula yang harus didefinisikan dan dikategorikan sebagai norma-norma sosial biasa, yang moral ataupun yang bukan moral, yang kepatuhan kepadanya atau pelanggaran terhadapnya tidak akan menimbulkan akibat hukum macam apapun. Walhasil, hukum nasional yang menganut ajaran positivisme -- yang marak di Barat dan mengalami puncak keberhasilannya pada akhir abad 18 ini -- kemudian daripada itu akan dikenali sebagai hukum positif, dan tampil dalam rupa hukum perundang-undangan (lege, lex, atau ius constitutum yang berarti 'hukum yang sudah terbentuk'). Walhasil, hukum yang sudah dipositifkan sebagai hukum nasional ini tidaklah lagi akan cuma berupa asas-asas umum yang tidak eksplisit (melainkan implisit-implisit saja!) mengenai apa yang harus dan boleh dilakukan dan mana pula yang terlarang (disebut ius) untuk dilakukan. Maka, di sini, dalam kajian-kajian yang semula terbilang filsafat moral, dan yang kemudian dikenali sebagai ilmu hukum (jurisprudence), konsep hukum sebagai norma yang mencerminkan moral kesempurnaan Tuhan menjadi kian tak berfungsi dalam perannya sebagai faktor pengintegrasi kehidupan bernegara bangsa. Kemajemukan masyarakat bangsa, dengan keragaman moral atau keragaman interpretasi atas moral sentral yang ko-eksis dalam kehidupan berbangsa itu, telah mendorong dengan pesat proses sekularisasi moral -- yang semula berlaku dalam ujudnya yang partikularistik di berbagai segmen warga bangsa -- ke bentuknya yang baru sebagai hukum nasional. Moral tak lagi disadari dari dalam sebagai norma, atau ajaran, yang harus dipatuhi sebagai perintah suatu sumber kepenguasaan tertentu. Alih-alih demikian, moral dilihat dari luar sebagai nomos, atau fakta keteraturan, as it is, yang berhakikat sebagai sarana kelompok-kelompok manusia yang tengah mencoba mempertahankan kelestarian kehidupan duniawinya. Dari sinilah awal bermulanya hukum nasional -- yang dituliskan atas dasar konsep-konsep kaum positivis -- akan dikelola dan dirawat oleh sebarisan ahli yang professional. Dari sinilah awal mula hukum sebagai norma-norma penata tertib tidak lagi menjadi objek rawatan para filosof dan/atau kaum moralis, melainkan kian berlanjut jatuh ke tangan pengelolaan dan rawatan para ahli penggunanya (ahli hukum, the lawyers) dan/atau para pengkajinya yang ilmuwan (sarjana hukum, jurist). Di sinilah awal perkembangan suatu cabang kajian ilmu baru yang disebut ilmu hukum (jurisprudence, Rechtslehre), yang bahkan kian lanjut mempromosikan diri ilmu pengetahuan tentang kehidupan dan perilaku warga masyarakat yang semestinya tertib mengikuti norma-norma
kausalitas (legal science, Rechtswissenschaft). Sekalipun di Eropa pada abad 19, kajian-kajian hukum nasional secara positivistik ini tetap dipopulerkan dengan sebutan (analytic atau positive) jurisprudence , di Amerika Serikat, pada akhir abad 19 itu, di tangan Langdell yang gurubesar hukum di Universitas Harvard kajian hukum yang positivistik seperti itu lebih tegas lagi disebut legal science atau mechanistic jurisprudence. Di tangan keahlian profesional para jurists, sejumlah prinsip dikembangkan -- dengan mengingati dalil-dalil logika -- untuk menata norma-norma (yang dibentuk dari asas-asas moral yang berlaku dalam masyarakat, yang oleh karena itu disebut ius constitutum alias norma-norma positif) ke dalam suatu sistem yang koheren. Keseluruhan norma positif yang telah terorganisasi ke dalam satuan sistem yang koheren inilah yang disebut sistem hukum perundang-undangan, suatu corpus juris, dengan komponen-komponennya yang disebut undang-undang (lex atau lege kalau jamak), yang, pada gilirannya, undang-undang ini terdiri dari pasal-pasal berikut rinciannya yang disebut ayat-ayat. Pasal-pasal dan ayat-ayat inilah yang dalam pembicaraan sehari-hari disebut aturan-aturan, berupa kalimat-kalimat deklaratur (as it is), yang tak bermaksud membuat judgment atas dasar penilaian buruk-baik (as ought to be), yang menetapkan secara positif dan resmi di situ tentang apa faktanya (bisa berupa perbuatan manusia, bisa berupa peristiwa) yang relevan dengan persoalan hukum, dan apa pula akibat hukumnya, ialah akibat yang juga relevan dengan kehidupan hukum. Karena rumusan-rumusan deklaratur ini menyatakan apa saja fakta yang dikualifikasi sebagai yang dibangun atas dasar hubungan sebab-akibat ke dalam wujud suatu corpus juris inipun lazim pula disebut sistem hukum positif. Penataan dan pengelolaan hukum positif ke dalam sistem yang logis dan koheren inilah yang disebut ilmu hukum positif (the positive jurisprudence). Patut diingatkan di sini bahwa pekerjaan para yuris yang mengembangkan prinsip-prinsip penataan seluruh norma-norma positif ke dalam suatu corpus yang koheren itu tidaklah harus diartikan bahwa para yuris inilah yang membuat hukum. Hukum undang-undang dibuat -- atau tepatnya, setidak-tidaknya dulu pada awalnya, dibentuk -- oleh badan-badan pemerintahan, langsung atau tidak lewat proses-proses politik. Tak ayal lagi, kerja yuris boleh dikatakan akan lebih berupa pelaksanaan seni manajemen atas dasar asas-asas tertentu, bagaikan ahli bahasa yang menyusun suatu tatabahasa, dan semuapun tahu bahwa bukan para ahli inilah yang menciptakan bahasa. Akan tetapi, sekalipun pada mulanya bekerja dengan batasan-batasan seperti itu, dengan pengembangan pemikiran dan tafsir-tafsir yang dibuatnya atas hukum nasional yang resmi itu, pada akhirnya kerja-kerja para ahli itu amat berpengaruh juga. Karena pada akhirnya hasil pemikiran dan tafsir-tafsir tersebut dalam praktik hukum tak jarang diakui berotoritas juga sebagai sumber hukum, yang dalam teori disebut sumber hukum yang materiil (yang dibedakan dari hukum perundang-undangan yang disebut sumber hukum yang formil), tak pelak lagi kegiatan para ahli professional itu baik yang dikemukakan dalam bentuk opini-opini lisan maupun (terlebih-lebih lagi!) yang tertulis tidaklah sekali-kali dapat diabaikan.[**]
Anda mungkin juga menyukai
- Filsafat Historisisme Lengkap PenjelasanDokumen8 halamanFilsafat Historisisme Lengkap PenjelasanSekkeeBelum ada peringkat
- Apa Itu Dialektika MaterialismeDokumen11 halamanApa Itu Dialektika MaterialismeAzharuddin Al AyubiBelum ada peringkat
- Konstruksi TeoriDokumen47 halamanKonstruksi TeoriBudi Armansyah100% (1)
- Positivisme Auguste ComteDokumen20 halamanPositivisme Auguste ComteNur SyaFaBelum ada peringkat
- Hubungan Perubahan Sosial Dan Perkembangan Ilmu PengetahuanDokumen13 halamanHubungan Perubahan Sosial Dan Perkembangan Ilmu Pengetahuandewi aulianiBelum ada peringkat
- Tugas rmk4Dokumen5 halamanTugas rmk4rahmi_hijriatiBelum ada peringkat
- Aliran Positivisme Dalam FilsafatDokumen2 halamanAliran Positivisme Dalam FilsafatDwy LestariBelum ada peringkat
- 2020112063-Muhamad Ilham Azizul Haq (Ringksan Catatan Filsafat Hukum-II)Dokumen12 halaman2020112063-Muhamad Ilham Azizul Haq (Ringksan Catatan Filsafat Hukum-II)jsp.pa.painanBelum ada peringkat
- Laporan Baca Positivisme Dan PragmatismeDokumen4 halamanLaporan Baca Positivisme Dan Pragmatismerickysitinjak9Belum ada peringkat
- Pandangan Habermas Tentang Pengetahuan Dan Kepentingan ManusDokumen10 halamanPandangan Habermas Tentang Pengetahuan Dan Kepentingan Manusaufar machine50% (2)
- Filsafat Positivisme ErwinDokumen18 halamanFilsafat Positivisme Erwinerwinwibowo100% (1)
- Soal Sospen 2021Dokumen4 halamanSoal Sospen 2021iputputra0Belum ada peringkat
- Disiplin Ilmu Pada Bidang SainsDokumen4 halamanDisiplin Ilmu Pada Bidang Sainsrada armiBelum ada peringkat
- Positivisme (Penemuan Huhukum)Dokumen15 halamanPositivisme (Penemuan Huhukum)gabepangestuBelum ada peringkat
- ALIRAN POSITIVISME AUGUST COMTE ScribdDokumen6 halamanALIRAN POSITIVISME AUGUST COMTE ScribdDwi KurniaBelum ada peringkat
- Kriminologi Dengan Hukum PidanaDokumen8 halamanKriminologi Dengan Hukum PidanaVirlanBelum ada peringkat
- Analisis Eksistensial IIDokumen18 halamanAnalisis Eksistensial IIJaprax Lailyas0% (1)
- Positivisme Logika Sains Dalam Kajian HukumDokumen9 halamanPositivisme Logika Sains Dalam Kajian HukumKuntoBelum ada peringkat
- Pembelajaran Filsafat Tapi BoongDokumen10 halamanPembelajaran Filsafat Tapi BoongAKBAR PELAYATIBelum ada peringkat
- Paradigma Ilmu 04Dokumen3 halamanParadigma Ilmu 04fifi musfiraBelum ada peringkat
- Pandangan Positivisme Tentang Ilmu 9Dokumen4 halamanPandangan Positivisme Tentang Ilmu 9tapedie1Belum ada peringkat
- Postivism Dan PostpositivismDokumen15 halamanPostivism Dan PostpositivismS'Salt Leng100% (1)
- Tugas 1 Filsafat IlmuDokumen9 halamanTugas 1 Filsafat IlmuEfraim El-Roi PasilaBelum ada peringkat
- Perkembangan Akal Budi ManusiaDokumen17 halamanPerkembangan Akal Budi ManusiaDevi TrianurBelum ada peringkat
- Bab I MetodeDokumen43 halamanBab I MetodeginulBelum ada peringkat
- Positivisme Auguste Comte by Zainal AbidinDokumen8 halamanPositivisme Auguste Comte by Zainal Abidinchinen oudettaBelum ada peringkat
- Teori Kebenaran Dalam Ilmu Pengetahuan IADDokumen16 halamanTeori Kebenaran Dalam Ilmu Pengetahuan IADSumadiyasaBelum ada peringkat
- Paradigma Positivisme Bagi Ilmu Pengetahuan ModernDokumen10 halamanParadigma Positivisme Bagi Ilmu Pengetahuan ModernHanief MitsukhaBelum ada peringkat
- Pancas SBG PengetahuanDokumen8 halamanPancas SBG PengetahuanFasya Ega NabillaBelum ada peringkat
- 2pppaliran Positivisme Dalam TeoriDokumen22 halaman2pppaliran Positivisme Dalam TeorikaklahBelum ada peringkat
- Mashab Positifisme HukumDokumen53 halamanMashab Positifisme HukumIsnawan Dwi PBelum ada peringkat
- Paradigma IsoshumDokumen5 halamanParadigma Isoshumwafanurf368Belum ada peringkat
- AKSIOLOGIDokumen4 halamanAKSIOLOGIirfann25Belum ada peringkat
- Positivisme Dan FenomenologiDokumen4 halamanPositivisme Dan FenomenologilordbendBelum ada peringkat
- Teori Alam Semesta StatisDokumen11 halamanTeori Alam Semesta StatisAl-Qudsi LViinaBelum ada peringkat
- Positivisme MerDokumen2 halamanPositivisme MerVianka Meisya AzzahraBelum ada peringkat
- Makalah FilsafatDokumen12 halamanMakalah Filsafatzulfa khasanahBelum ada peringkat
- Sesi 1 - Rasionalitas ModernDokumen23 halamanSesi 1 - Rasionalitas ModernDidit SuryoBelum ada peringkat
- Hukum Dalam Konteks Aliran PositivismeDokumen16 halamanHukum Dalam Konteks Aliran Positivismesahnaz kartikaBelum ada peringkat
- Dato Pentafsiran Dalam Pensejarahan Barat Di Antara Aspirasi Positivis Dan Rritikan RelativisDokumen23 halamanDato Pentafsiran Dalam Pensejarahan Barat Di Antara Aspirasi Positivis Dan Rritikan RelativisMuhaimin Abdu AzizBelum ada peringkat
- Hermeneutik N Ilmu SosDokumen3 halamanHermeneutik N Ilmu SosTommy A NaimBelum ada peringkat
- Teori KebenaranDokumen5 halamanTeori KebenaranNoor- CahayaBelum ada peringkat
- Pengertian OntologiDokumen5 halamanPengertian OntologiIGusti Ayu PratiwiBelum ada peringkat
- Hegemoni PositivismeDokumen8 halamanHegemoni PositivismeEdwinBelum ada peringkat
- Positivisme Auguste Comte - 20 SlideDokumen20 halamanPositivisme Auguste Comte - 20 SlideMaria UlfaBelum ada peringkat
- Filsej - Filsafat Naturalisme PDFDokumen17 halamanFilsej - Filsafat Naturalisme PDFLussy Midani RizkiBelum ada peringkat
- Tugas 5 - Filia Cintami Madao E041211029Dokumen5 halamanTugas 5 - Filia Cintami Madao E041211029Filia Cintami MadaoBelum ada peringkat
- Twelve Tenets PDFDokumen2 halamanTwelve Tenets PDFajarBelum ada peringkat
- Makalah Filsafat Ilmu (Positivisme)Dokumen15 halamanMakalah Filsafat Ilmu (Positivisme)Nurrahmah Cindy100% (7)
- Pendekatan Kultural Dan Struktural Dalam SosiologiDokumen38 halamanPendekatan Kultural Dan Struktural Dalam SosiologiAri SaputraBelum ada peringkat
- Dunia Posmo Dan HiperealitasDokumen6 halamanDunia Posmo Dan HiperealitasDimas Panji PangestuBelum ada peringkat
- Teori Kebenaran IlmiahDokumen5 halamanTeori Kebenaran IlmiahDhea HurisfaBelum ada peringkat
- Bahasa Artifisial Atau Bahasa Buatan Atau Bahasa TerkonstruksiDokumen7 halamanBahasa Artifisial Atau Bahasa Buatan Atau Bahasa Terkonstruksimuhammad rizkyBelum ada peringkat
- MKLH FilsafatDokumen19 halamanMKLH Filsafatprabu_gra007Belum ada peringkat
- 2.objektivitas Pengetahuan Ilmiah-Prof SudarmintaDokumen46 halaman2.objektivitas Pengetahuan Ilmiah-Prof SudarmintadanurlambangBelum ada peringkat
- BAHAN AJAR 9 Nilai-NIilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan IlmuDokumen17 halamanBAHAN AJAR 9 Nilai-NIilai Pancasila Sebagai Dasar Pengembangan IlmuAlbian HavizaBelum ada peringkat
- Keterlibatan kuantum dan semua warnanya. Dari mitos gua Plato, ke sinkronisasi Carl Jung, ke alam semesta holografik David Bohm.Dari EverandKeterlibatan kuantum dan semua warnanya. Dari mitos gua Plato, ke sinkronisasi Carl Jung, ke alam semesta holografik David Bohm.Belum ada peringkat
- Fizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baruDari EverandFizik kuantum dan sub-sedar kolektif. Fizik dan metafizik alam semesta. Tafsiran baruPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Keterikatan kuantum dan ketidaksadaran kolektif. Fisika dan metafisika alam semesta. Interpretasi baruDari EverandKeterikatan kuantum dan ketidaksadaran kolektif. Fisika dan metafisika alam semesta. Interpretasi baruPenilaian: 3 dari 5 bintang3/5 (5)