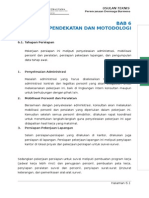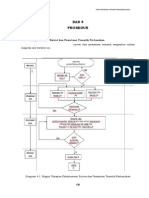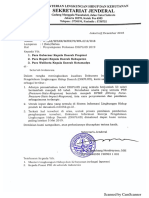Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Diunggah oleh
Halili KendariJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Bab Iv Pengumpulan Dan Pengolahan Data
Diunggah oleh
Halili KendariHak Cipta:
Format Tersedia
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
BAB IV
PENGUMPULAN DATA DAN PENGOLAHAN DATA
Pengumpulan data merupakan salah satu bagian terpenting dalam
penyusunan rencana zonasi WP-3-K. Data yang dikumpulkan berupa data
sekunder yang berasal dari instansi terkait, terutama data yang berupa
data spasial dan hasil-hasil pemetaan yang telah dilakukan oleh instansi
tersebut. Data sekunder yang dikumpulkan dari instansi terkait memiliki
berbagai macam bentuk dan format, diantaranya berupa peta analog
(hardcopy), peta digital (data digital), dan data tabular/numerik.
Tabel 4.1. Jenis dan bentuk data sekunder yang dikumpulkan
dalam penyusunan rencana zonasi WP-3-K
N
o
Jenis
Data
Tipe Data
Format
Data
Contoh Data/Peta
Peta
Analog
Peta Cetakan
Hardcopy
Peta Hardcopy Rupabumi, Peta
Hardcopy Geologi
Data/Pet
a Digital
Data hasil digitasi
peta analog
Shapefile
Data vektor penggunaan lahan,
Data vektor garis pantai
Data hasil konversi
data
Shapefile
Peta kontur ketinggian lahan hasil
konversi dari Data Digital
Elevation Model (DEM)
Data Hasil Plotting
GPS/Pengukuran
Lapangan
Shapefile
Data titik lokasi sampel
pengukuran fisika perairan
Data Hasil
Interpretasi Citra
Satelit
Shapefile
Peta penggunaan lahan, peta batas
ekosistem mangrove
Data Hasil Analisis
GIS dan Pemodelan
Matematis
Shapefile
Peta Sebaran Terumbu Karang
hasil Pemodelan Lyzenga, Peta
risiko bencana, Peta arah dan
kecepatan arus
Data numerik
(Angka) yang
memiliki informasi
Lokasi
.xls, .dbf
Data Jumlah Penduduk Kecamatan
X, Data perubahan luas
penggunaan lahan di kawasan
Pesisir X, Data Numerik Hasil
Pengukuran Fisika Perairan di Laut
X, Lokasi Infrastruktur
Data
Tabular/
Numerik
Dengan adanya keragaman format data dari berbagai instansi
tersebut, maka data sekunder tersebut perlu diseragamkan formatnya
menjadi format peta digital, sehingga dapat dilakukan penilaian kualitas
dan kuantitas data sekunder yang ada diperoleh. Penilaian kualitas data
17
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
sekunder terkait dengan beberapa kriteria diantaranya skala, akurasi
spasial, dan akurasi atribut.
4.1. Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder dilakukan sesuai dengan
kebutuhan penyusunan Rencana Zonasi WP-3-K. Data yang
dikumpulkan dari instansi terkait berupa data spasial dan hasil-hasil
pemetaan yang telah dilakukan oleh instansi tersebut. Untuk
mendapatkan data sekunder tersebut, langkah-langkah yang perlu
dilakukan adalah sebagai berikut:
1) Menyiapkan daftar data yang dibutuhkan di setiap instansi
2) Mendatangi instansi terkait untuk mendapatkan data sesuai
dengan tema
3) Melakukan kompilasi data dan mengklasifikasikan data sesuai
tema dan skala
4) Melakukan analisis data untuk menyamakan format data yang
berbeda-beda menjadi format data/peta digital
5) Menyusun peta-peta tematik
6) Melakukan penilaian kualitas dan kuantitas data
Data yang dikumpulkan dari dari berbagai instansi dapat
dikategorikan menjadi peta dasar dan citra satelit, dataset dasar dan
dataset tematik. Penjelasan pengumpulan data untuk penyusunan
RZWP-3-K dijabarkan sebagai berikut:
18
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
4.1.1.
Peta Dasar dan Citra Satelit
Peta dasar dan citra satelit dibutuhkan untuk membuat peta wilayah perencanaan dalam penyusunan
RZWP-3-K.
Tabel 4.2. Pengumpulan Peta Dasar dan Citra Satelit dari Berbagai Instansi untuk RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGO
RI DATA
Peta
Dasar
JENIS
DATA/PETA
SKALA/RESOLUSI
BENTUK/FORMA
T DATA/PETA
SUMBER DATA &
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
Peta
Rupabumi
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Rupabumi Indonesia
skala 1 : 250.000, dan 1
: 50.000
BIG
Lingkungan
Pantai
Indonesia
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Lingkungan Pantai
Indonesia
skala 1 : 250.000, dan 1
: 50.000
BIG
Citra Satelit
Resolusi 30 x 30 m, 10
x 10 m
Softcopy
Citra satelit
LAPAN
4.1.2.
Dataset Dasar
Data spasial dasar merupakan data spasial yang menjadi dasar dalam pemetaan tematik suatu wilayah.
Data spasial dasar terbagi menjadi data terestrial dan bathimetri.
Tabel 4.3. Pengumpulan Dataset Dasar dari Berbagai Instansi untuk RZWP-3-K
19
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGORI
DATA
Garis Pantai
Garis pantai
1:
250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Lingkungan Pantai
Indonesia
skala 1 : 250.000, dan 1 :
50.000
BIG
Bathimetri
Bathimetri
1:
250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Lingkungan Pantai
Indonesia skala 1 : 250.000,
dan 1 : 50.000
Peta Laut skala 1 : 250.000,
dan 1 : 50.000
BIG
1:
250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Data Dasar yang dikeluarkan
oleh BIG
BIG
Batas
Wilayah Laut
Provinsi
JENIS
DATA/PETA
Wilayah
Administrasi
SKALA/R
ESOLUSI
BENTUK/FORMA
T
DATA/PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
DISHIDROS
TNI AL
4.1.3.
Dataset Tematik
Data spasial tematik merupakan data spasial yang memiliki tema tertentu yang dibutuhkan sebagai
bahan penyusunan peta tematik. Data tematik yang dibutuhkan dalam penyusunan rencana zonasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terbagi menjadi data geologi dan geomorfologi, oseanografi;
penggunaan lahan, status lahan, rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan wilayah laut, sumberdaya
air, ekosistem pesisir dan sumberdaya ikan, infrastruktur, demografi dan sosial, ekonomi wilayah, dan
risiko bencana dan pencemaran.
Tabel 4.4. Pengumpulan Dataset Tematik dari Berbagai Instansi
20
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
Oseanogr
af
Geologi
dan
Geomorfo
logi Laut
JENIS
DATA/PETA
Oseanografi
Fisik:
a. Arus
b. Gelombang
c. Pasang Surut
d. Suhu
Permukaan
e. Kecerahan
SKALA/
RESOLUSI
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta oseanografi fisik
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000
Dishidros, KKP,
LIPI, Instansi
terkait,
Perguruan
Tinggi
Oseanografi
Kimia
a. pH
b. salinitas
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta oseanografi kimia skala 1
: 250.000, 1 : 50.000
Dishidros, KKP,
LIPI, Instansi
terkait,
Perguruan
Tinggi
Oseanografi
Biologi
Klorofil
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta oseanografi biologi skala
1 : 250.000, 1 : 50.000
Dishidros, KKP,
LIPI, Instansi
terkait,
Perguruan
Tinggi
Geologi Laut
1 : 250.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Geologi laut
skala 1 : 250.000
Pusat Survei
Geologi, Kemen
ESDM
(Walidata)
P3GL
Kementerian
ESDM
21
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
JENIS
DATA/PETA
SKALA/
RESOLUSI
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
Dit. Vulkanologi
Kementerian
ESDM
Ekosiste
m Pesisir
dan
Pulaupulau
kecil
Sumberd
Substrat Dasar
Laut
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Geologi & geomorfologi
dasar laut skala 1 : 250.000,
dan 1 : 50.000
- Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Geologi Laut
Kemen ESDM
(Walidata)
Deposit pasir
laut
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Geologi & geomorfologi
dasar laut skala 1 : 250.000,
dan 1 : 50.000
Mangrove
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta Mangrove skala 1 :
250.000, 1 : 50.000
Dit. Konservasi
Tanah dan Air
KLHK
(Walidata), BIG,
LIPI, KKP
Terumbu
Karang
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta Terumbu Karang
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
Pusat Penelitian
Oseanografi LIPI
(Wali
data),
BIG , KKP
Lamun
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta Lamun
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
Pusat Penelitian
Oseanografi LIPI
(Wali data), BIG,
KKP
Pelagis
1 : 250.000
Softcopy
Peta Daerah Penangkapan Ikan
(Fishing Ground) Pelagis &
- Pusat
Penelitian dan
22
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
JENIS
DATA/PETA
pemanfaa
tan ruang
laut yang
telah ada
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
1 : 50.000
aya Ikan
(Jenis
dan
Kelimpah
an Ikan)
SKALA/
RESOLUSI
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
Jenis dan Kelimpahan Ikan
Pelagis
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000
Pengembangan
Perikanan KKP
(Walidata
Sumberdaya)
KKP, Instansi
terkait
Demersal
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta Daerah Penangkapan Ikan
(Fishing Ground) Demersal &
Jenis dan Kelimpahan Ikan
Demersal
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
- Pusat
Penelitian dan
Pengembangan
Perikanan KKP
(Walidata
Sumberdaya)
KKP, Instansi
terkait
Kawasan
Pemanfaatan
Umum
(bangunan
laut,
transportasi
atau utilitas
laut,
infrastruktur
laut, KJA,
Bagan, Fishing
Ground,
Pendaratan
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy
Peta Pemanfaatan Wilayah
Perairan/Laut
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
KKP, Instansi
terkait
23
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
JENIS
DATA/PETA
SKALA/
RESOLUSI
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
Pesawat,
pariwisata,
pertambangan,
pemanfaatan
masyarakat
hukum adat,
tempat suci,
dan lain-lain)
Dokumen
Perencan
aan
Pemanfaa
tan
Kawasan
Konservasi
atau Kawasan
Lindung Laut
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Kawasan Konservasi
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000
KKP, KLHK
Alur Laut
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta
laut skala 1 : 250.000, 1 :
50.000,
Kemenhub,
Kementerian
ESDM, KKP,
LIPI, Instansi
terkait
Kawasan
Strategis
Nasional
Tertentu
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta KSNT skala 1 : 250.000,
1 : 50.000,
KKP, TNI,
Kemenhub,
Kemenparekraf
Rencana Induk
Pariwisata,
Rencana Induk
Pelabuhan, dan
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Dokumen perencanaan atau
peta skala 1 : 250.000, 1 :
50.000,
Kementerian/
Lembaga
terkait, SKPD
24
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
JENIS
DATA/PETA
Perairan
Pesisir
lain-lain
Sosial,
Ekonomi
dan
Budaya
Data
Kependudukan
dan Sosial:
Populasi:jumla
h, kepadatan
dan distribusi
umur (time
series 10
tahun)
Trend
pertumbuhan
populasi :
tingkat
kelahiran dan
kematian (time
series 10
tahun)
Pendidikan
umum
Mata
Pencaharian
Agama
Budaya
Tingkat akses
dan
keterlayanan
SKALA/
RESOLUSI
1 : 250.000
1 : 50.000
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
Softcopy &
hardcopy
SUMBER DATA
Peta Kependudukan dan
Sosial
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
- Direktorat
Diseminasi
Statistik, BPS
(Walidata
Demografi)
Peta RTRW,
Data BPS (time
series)
25
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
JENIS
DATA/PETA
SKALA/
RESOLUSI
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
fasilitas
publik: listrik,
air bersih,
sanitasi,
kesehatan,
pendidikan
Lembaga
Masyarakat,
LSM
Masyarakat
Hukum adat
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta Kependudukan dan
Sosial
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
- Dit. Survei dan
Pemetaan
Tematik, Kemen
ATR (Walidata
Wilayah Adat)
Peta RTRW,
Wilayah
tangkapan
tradisional
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta tangkapan nelayan
tradisional
KKP, DKP,
Bappeda,
Instansi terkait
Tingkat
perekonomian
wilayah:
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta perekonomian wilayah
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000, 1
: 25.000
Peta RTRW, Data
statistik BPS,
Disnaker, Dinas
pariwisata,
Dinas Perikanan
(time series)
o Pendapatan
perkapita
provinsi
o Pertumbuhan
26
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
JENIS
DATA/PETA
SKALA/
RESOLUSI
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
Pendapatan
perkapita
provinsi
o Angkatan kerja
dan tingkat
penganggura
n per
kabupaten
o Tenaga kerja di
bidang
perikanan,
pertanian,
kehutanan,
dll
o Populasi dan
kepadatan
nelayan
o Pendapatan di
sektor
perikanan
o Produksi
perikanan
dan sektor
-sektor lain
o Potensi
pengembang
an
sumberdaya
perikanan
27
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
PENGUMPULAN DATA SEKUNDER UNTUK PENYUSUNAN RZWP-3-K
NO
KATEGOR
I DATA
JENIS
DATA/PETA
SKALA/
RESOLUSI
BENTUK/
FORMAT
DATA/ PETA
SUMBER DATA
INSTANSI
PENYEDIA
DATA
dan kelautan
o Jumlah
wisatawan
o Pendapatan
rata-rata dan
pengeluaran
per sektor
8
Risiko
Bencana
Peta sebaran
daerah rawan
dan risiko
bencana
1 : 250.000
1 : 50.000
Softcopy &
hardcopy
Peta sebaran daerah rawan
dan risiko bencana
skala 1 : 250.000, 1 : 50.000,
PPIT
BIG
(Walidata Multi
Rawan Bencana)
Dit.
Pengurangan
Risiko Bencana
BNPB (Walidata
Risiko Bencana)
Pusat
Vulkanologi dan
Mitigasi
Bencana Geologi
Kemen
ESDM
(Walidata
Rencana
Bencana
Geologis)
28
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
4.2. Pengolahan Data Sekunder
Data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait
dapat berupa peta analog (hardcopy), peta digital (data digital), dan
data tabular/numerik. Sebagai contoh, rincian data sekunder dari
instansi terkait seperti yang terlihat pada tabel dibawah. Format
yang beragam tersebut perlu dikonversi terlebih dahulu menjadi
data spasial atau peta yang memiliki informasi keruangan. Apabila
tidak memenuhi persyaratan secara kualitas dan tidak sesuai
dengan kebutuhan penyusunan RZWP-3-K, maka perlu dilakukan
pengumpulan data melalui survei lapangan.
Pengolahan yang dilakukan terhadap hasil pengumpulan data
sekunder merupakan upaya mengolah data menjadi data yang
memiliki informasi keruangan, tetapi tidak mengubah substansi
data. Pengolahan yang dilakukan berbeda-beda, tergantung jenis
data yang dikumpulkan dari berbagai instansi terkait, misalnya peta
analog, data/peta digital, atau data tabular/numerik.
Tabe 4.5. Metode Pengolahan Data Sekunder
N
o
Jenis
Data
Tipe Data
Peta
Analog
Peta
Cetakan
Data/Pet Data hasil
a Digital digitasi
peta analog
Forma
t Data
Contoh
Data/Peta
Hardc
opy
Peta Hardcopy
Rupabumi, Peta
Hardcopy Geologi
Shape
file
Data vektor
penggunaan
lahan, Data vektor
garis pantai
Peta kontur
ketinggian lahan
hasil konversi dari
Data Digital
Elevation Model
(DEM)
Data titik lokasi
sampel
pengukuran fisika
perairan
Data hasil
konversi
data
Shape
file
Data Hasil
Plotting
GPS/Pengu
kur-an
Lapangan
Shape
file
Data Hasil
Interpretasi
Citra
Satelit
Shape
file
Peta batas
ekosistem
mangrove
Data Hasil
Shape
Peta Sebaran
Metode
Pengolahan
Data/Peta
Konversi data
analog ke digital
(scanning),
digitasi, dan
plotting ke peta
dasar
Digitasi dan
plotting ke peta
dasar
Konversi dari data
raster ke data
vektor
(Vectorization) dan
plotting ke peta
dasar
Standardisasi
format dan
kelengkapan data,
Interpolasi dan
plotting ke peta
dasar
Standardisasi
format dan
kelengkapan data
dan plotting ke
peta dasar
Standardisasi
29
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Analisis GIS file
dan
Pemodelan
Matematis
3
Data
Tabular/
Numeri
k
Data
numerik
(Angka)
yang
memiliki
informasi
Lokasi
Xls,
Dbf
Terumbu Karang
hasil Pemodelan
Lyzenga, Peta
risiko bencana,
Peta arah dan
kecepatan arus
Data Jumlah
Penduduk
Kecamatan X,
Data perubahan
luas penggunaan
lahan di kawasan
Pesisir X, Data
Numerik Hasil
Pengukuran Fisika
Perairan di Laut X,
Lokasi
Infrastruktur
format
dan
kelengkapan data
dan plotting ke
peta dasar
Analisis Data dan
Plotting ke peta
dasar
Rincian metode dan langkah-langkah pengolahan terhadap
data-data sekunder adalah sebagai berikut:
1) Peta Analog
Peta analog merupakan peta-peta tematik dari instansi terkait
yang berupa peta cetakan dalam ukuran tertentu sesuai
dengan skala petanya. Pengolahan dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
Pemeriksaan Kual
Skala
Akurasi Spasial
Akurasi Atribut
2) Data/Peta Digital
Data atau peta digital merupakan data yang berbentuk
softfile yang diperoleh dari berbagai sumber data. Rincian
pengolahan data atau peta digital adalah sebagai berikut:
a. Data Digital Hasil Plotting/Pengukuran Lapangan
30
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Pemeriksaan Kualitas
Data
Skala
Akurasi Spasial
Akurasi Atribut
b. Data Hasil pengolahan GIS dan Pemodelan Matematis
Pemeriksaan Kualitas
Data
Skala
Akurasi Spasial
Akurasi Atribut
c. Data Hasil Digitasi
31
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Peta Tematik
d. Data Hasil Konversi Data
Peta Tematik
3) Data Tabular/Numerik
Data numerik (angka) merupakan data yang berbentuk
angka-angka atau deskripsi dari obyek atau fenomena
tertentu. Data numerik yang memiliki informasi lokasi (lokasi
relative dan lokasi absolut) dapat dikonversi menjadi data
spasial melalui plotting ke dalam peta dasar. Sebagai contoh
lokasi relative adalah : data wilayah administrasi dan data
Jumlah Penduduk Kecamatan X. Contoh lokasi absolut
adalah : Data Numerik Hasil Pengukuran Fisika Perairan di
Laut X pada koordinat x,y dan Data Lokasi Infrastruktur
pada koordinat x,y.
32
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Pemeriksaan Kualitas
Data
Skala
Akurasi Spasial
Akurasi Atribut
4.3. Survei Lapangan (Pengumpulan Data Primer)
Survei lapangan wajib dilakukan oleh Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan apabila
data sekunder yang dikumpulkan belum memenuhi standar kualitas
dan kuantitas. Standar kualitas data meliputi (1) skala, (2) akurasi
spasial dan (3) akurasi atribut. Standar kuantitas data meliputi
dataset (1) garis pantai, (2) bathimetri, (3) batas wilayah laut, (4)
oseanografi, (5) geomorfologi dan geologi laut, (6) ekosistem pesisir
dan pulau-pulau kecil, (7) sumber daya ikan pelagis dan demersal,
(8) pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang
telah ada, (9) dokumen perencanaan pemanfaatan ruang di wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil, (10) sosial, ekonomi, dan budaya, dan
(11) resiko bencana dan pencemaran.
4.3.1.
Pengolahan Data Pra Survei
Sebelum pelaksanaan survei
lapangan, terlebih dahulu
dilakukan pengolahan data citra satelit sebagai bahan acuan
survei lapangan. Pengolahan data citra satelit dilakukan untuk
peta-peta tematik tertentu, antara lain oseanografi (suhu,
klorofil), ekosistem pesisir (terumbu karang, lamun, mangrove),
dan sumberdaya ikan pelagis.
A. Pengolahan Citra Satelit
Tahap pengolahan awal citra satelit (image preprocessing)
dilakukan untuk memperoleh peta tematik tentatif.
Pengolahan dilakukan dengan cara memperbaiki data citra
asli (raw data) menjadi citra satelit yang siap untuk
diinterpretasi. Pekerjaan yang dilakukan meliputi perbaikan
kesalahan akibat hamburan partikel di atmosfer yang
terekam oleh citra satelit (radiometric correction), perbaikan
kesalahan posisi perekaman citra satelit terhadap referensi
bumi (geometric correction) dan penajaman obyek pada citra
melalui perentangan nilai spektral citra.
Koreksi Radiometrik
33
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Koreksi
radiometrik
dilakukan
untuk
menghilangkan
kesalahan radiometrik, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh
adanya pantulan balik dari partikel-partikel di atmosfer yang
ikut terekam oleh detektor satelit, yang mengakibatkan
terjadinya penambahan nilai piksel obyek tertentu. Koreksi
radiometrik dilakukan dengan cara memperbaiki nilai
spektral citra, yang pada prinsipnya adalah menghilangkan
penambahan tingkat kecerahan piksel akibat hamburan
atmosfer.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
penyesuaian histogram. Cara yang dilakukan dalam metode
ini adalah dengan cara mengurangi seluruh nilai piksel citra
dengan nilai kecerahan dari hamburan atmosfer. Nilai piksel
citra dan besarnya nilai kecerahan akibat hamburan atmosfer
dapat diketahui melalui histogram citra atau melalui
perhitungan statistik citra.
Koreksi Geometrik
Koreksi geometrik yang paling mendasar adalah penempatan
kembali posisi piksel sedemikian rupa sehingga dihasilkan
gambaran obyek yang sesuai dengan kondisi sebenarnya di
lapangan atau pada peta topografi. Pada koreksi geometrik
terjadi pengalihan posisi (relokasi) seluruh piksel pada citra
sehingga
membentuk
konfigurasi
piksel
baru
yang
dipersepsikan sebagai citra.
Koreksi geometrik ini dilakukan dengan menggunakan
rujukan titik-titik tertentu pada peta (peta topografi) yang
mempunyai posisi kenampakan yang sama dengan titik-titik
yang ada pada citra. Pasangan titik-titik tersebut kemudian
digunakan untuk membangun fungsi matematis yang
menyatakan hubungan posisi sembarang titik pada citra
dengan titik yang sama pada peta. Hasilnya adalah citra
digital yang memiliki koordinat baru dan konfigurasi piksel
yang baru. Perubahan posisi piksel ini secara otomatis
menyebabkan perubahan nilai spektral dan menyebabkan
citra digital memiliki kesalahan radiometrik kembali,
sehingga perlu dilakukan penataan ulang piksel-piksel yang
berubah
tersebut.
Metode
yang
diterapkan
untuk
mengembalikan posisi piksel-piksel citra digital adalah
interpolasi nilai piksel citra atau disebut resampling atau
penempatan kembali posisi piksel-piksel yang berubah
tersebut. Resampling yang diterapkan adalah interpolasi
tetangga terdekat atau nearest neighbour.
Disamping jumlah titik-titik ikat, ketelitian koreksi geometrik
juga dipengaruhi oleh besarnya nilai kesalahan akibat
pergeseran letak pada waktu pengambilan titik-titik ikat
tersebut . Kesalahan ini dinyatakan dalam sigma () atau
RMS (Root Mean Square Error). Nilai RMS harus sekecil
34
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
mungkin untuk
akurat.
mendapatkan ketelitian geometrik yang
Penajaman Citra
Penajaman citra yang lazim digunakan ada dua, yakni
ekualisasi histogram dan perentangan linear. Teknik
ekualisasi histogram akan memberikan efek kontras yang
tajam (kontras maksimum) pada citra, sehingga perbedaan
antara obyek yang satu dengan obyek lainnya akan lebih
jelas. Teknik ini lebih rumit dari perentangan linear karena
menggunakan hitungan statistik.
Perentangan linear baik untuk mempertajam kenampakan
obyek tertentu yang terwakili oleh histogram. Teknik ini
dapat dilakukan secara interaktif dengan melihat distribusi
nilai citra asli (nilai maksimum dan minimum), kemudian nilai
minimum ditarik ke titik nol dan nilai maksimum ditarik ke
titik 255 (untuk citra dengan resolusi radiometric 8-bit).
Untuk citra multispektral, perentangan dilakukan terhadap
band merah, hijau dan biru dalam komposisi warna RGB.
Metode perentangan ini sangat bermanfaat untuk kajian
terumbu karang, pengenalan obyek secara visual maupun
penentuan titik referensi lapangan pada citra resolusi tinggi.
Secara teknis penajaman kontras ini dapat dilakukan dengan
software GIS.
B. Interpretasi Citra
Interpretasi citra dilakukan untuk memperoleh peta tematik
tentatif yang dilakukan melalui analisis citra satelit dengan
metode
klasifikasi
tak
terbimbing
(unsupervised
classification)
dan
klasifikasi
terbimbing
(supervised
classification). Klasifikasi tak terbimbing dilakukan dengan
cara mengklasifikasikan piksel ke dalam sejumlah kelas yang
memiliki pola atau ciri yang sama. Untuk klasfikasi
terbimbing dilakukan dengan cara Digitasi on screen dengan
menginterpretasi pada citra penginderaan jauh secara
manual pada layar monitor dengan pendekatan unsur
rona/warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, bayangan, situs,
asosiasi, dan konvergensi bukti.
4.3.2.
Metode Survei Lapangan
Metode survei lapangan dilakukan pada data-data yang
memerlukan validasi ataupun data yang tidak dapat diperoleh
dari data sekunder. Metode survei yang digunakan berbedabeda disesuaikan dengan jenis data yang dihasilkan dengan
menggunakan standar yang telah ditentukan.
A. Bathimetri
Metode Pengukuran Bathimetri
35
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Pengumpulan data bathimetri dimaksudkan sebagai data
dasar dalam menganalisis kedalaman perairan laut. Untuk
mendapatkan informasi bathimetri digunakan metode
pemeruman, dengan menggunakan alat echosounder yang
terintegrasi dengan GPS. Alat tersebut memancarkan
gelombang suara secara vertikal ke dasar perairan dan
dipantulkan kembali ke echosounder melalui jalur-jalur yang
telah direncanakan pada peta pre plot digital, yang dapat
terbaca di dalam komputer. Pengukuran kedalaman muka air
laut dengan alat echosounder dilakukan dari atas perahu
motor, dengan kecepatan kapal maksimum 5 (lima) knot (2,5
m/detik) dan kondisi kapal stabil.
Koordinat titik-titik
pengukuran didapat dengan menggunakan alat GPS (Global
Positioning System) yang telah terintegrasi dengan
echosounder.
Pada pemetaan skala 1: 250.000, lokasi ditentukan dengan
menggunakan metode grid pengukuran 2.500 meter yaitu
dengan perekaman data bathimetri setiap satu detik. Misal:
lebar tegak lurus ke arah laut (ke selatan) 12 mil dan sejajar
pantai sepanjang garis pantai (lihat gambar 2.3). Pada
pemetaan skala 1:50.000, lokasi ditentukan dengan
menggunakan metode grid pengukuran 500 meter yaitu
dengan perekaman data bathimetri setiap satu detik. Misal:
lebar tegak lurus ke arah laut (ke selatan) 4 mil/kedalaman
maksimum 100 m dan sejajar pantai sepanjang garis pantai
Data kedalaman yang dihasilkan dari hasil survei bathimetri
dikoreksi dengan titik referensi Mean Sea Level (MSL) yang
diperoleh dari analisis data elevasi muka air saat
pengukuran. Jadwal pengukuran/pencatatan elevasi pasang
surut
(pasut)
dilakukan
bersamaan
dengan
jadwal
pengukuran bathimetri. Pengukuran Kedalaman perairan
yang sebenarnya dan garis kontur dasar laut diperoleh
dengan
superposisi
(memadukan)
data
pengukuran
bathimetri dengan selisih antara elevasi muka air laut saat
pengukuran bathimetri dengan MSL yang telah diikat dengan
referensi muka bumi.
Pengukuran bathimetri mengacu pada Standard IHO 44, LPI
SNI 19-6727-2002 skala 1 : 250.000, IHO S-57. Prinsip kerja
dari pemeruman dengan menggunakan echo-sounder
diterangkan oleh gambar-gambar berikut ini:
36
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.1. Ilustrasi Proses Survei Bathimetri
Keterangan :
GPS Satellites
Known Station (BM)
Sounding Boat + Mobile DGPS + Echosounder
Tide Observation/Tide Pole
Gambar 4.2 Prinsip Pengukuran Kedalaman Laut
37
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
38
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
12 mil
Daratan
Gambar 4.3. Contoh Rencana Jalur Pengukuran Kedalaman
Laut
Pengolahan Data Hasil Survei Bathimetri
Pengolahan data hasil survei bathimetri dilakukan terhadap
titik-titik kedalaman yang telah diukur di lapangan. Titik-titik
yang memiliki informasi kedalaman dan koordinat tersebut
kemudian diinterpolasi dengan metode Inverse Distance
Weighted (IDW). Interpolasi dapat dilakukan dengan bantuan
software GIS sehingga menghasilkan garis kontur kedalaman
untuk wilayah perairan yang disurvei.
Garis kontur
39
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
kedalaman menunjukkan lokasi-lokasi yang memiliki nilai
kedalaman yang sama (isobath). Garis kontur kedalaman
diolah lebih lanjut melalui GIS dan diklasifikasikan sesuai
kelas kedalaman untuk skala 1 : 250.000 dan skala 1 : 50.000.
Gambar 4.4. Contoh Ilustrasi Hasil Pengolahan Data
Bathimetri di procinsi Sulawesi Utara
B. Dataset Geomorfologi dan Geologi Laut
1. Substrat Dasar Laut
Metode Pengambilan Sampel Substrat Dasar Laut
Dataset geologi dan geomorfologi laut yang memungkinkan
untuk disurvei adalah jenis substrat dasar laut. Jenis
substrat dasar laut yang mungkin ditemukan misalnya
pecahan karang, pasir, lumpur, lumpur berpasir dan
sebagainya.
Untuk mendeteksi substrat dasar laut, dapat dilakukan
dengan metode penginderaan jauh dan survei lapangan.
Melalui pendekatan penginderaan jauh untuk wilayah
40
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
tertentu yang memiliki perairan dengan tingkat kecerahan
tinggi,
substrat
dasar
laut
dapat
diidentifikasi
menggunakan citra satelit yang memiliki kemampuan
menembus air sampai kedalaman tertentu (<20 m).
Identifikasi dilakukan menggunakan pendekatan kunci
interpretasi, diantaranya rona, warna, pola, bentuk,
tekstur, situs dan asosiasi. Hasil interpretasi citra
penginderaan jauh berupa poligon substrat dasar laut
tentatif. Berdasarkan poligon substrat dasar laut, dapat
ditentukan lokasi pengambilan sampel di lapangan. Untuk
perairan dengan kedalaman di atas 20 meter perlu
dilakukan survei lapangan secara langsung karena
umumnya citra satelit tidak mampu mendeteksi obyek
perairan dasar laut pada kedalaman lebih dari 20 meter.
Pada pemetaan skala 1:250.000 dan 1:50.000, jumlah
sampel substrat dasar laut yang diambil di lapangan
minimal 10 titik sampai dengan 4 mil atau sampai
kedalaman 100 m apabila sebelum jarak 4 mil telah
dijumpai kedalaman lebih dari 100 m. Peralatan yang
digunakan berupa peralatan sedimen dasar laut (Grab
sampler). Grab sampler diturunkan ke dasar laut dalam
keadaan terbuka menggunakan tali. Setelah sampai dasar
laut, alat tersebut akan menutup sambil menggaruk
sedimen ketika ditarik ke atas. Pada saat pengambilan
sampel substrat dasar laut dilakukan pengukuran posisi
menggunakan GPS.
Gambar 4.5. Proses pengambilan sampel substrat dasar
laut
Pengolahan Data Substrat Dasar Laut
Sampel substrat dasar laut dianalisis di laboratorium dan
besar butirnya diukur menggunakan metode Buchanan
(1984, dalam Holme and Mc Intyre (1984)). Analisis ukuran
butir dilakukan menggunakan kurva distribusi frekuensi
ukuran butir, sehingga dapat diketahui ukuran butir ratarata maupun persentase yang lain.
41
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.6. Sistem Grafik Trianguler Untuk Proses
Penamaan Sampel Substrat (Sumber: Buchanan, 1984
Dalam Holme Dan Mc Intyre, 1984)
Tabel 4.6. Skala ASTM (kisaran ukuran butir)
Jenis
Kisaran Ukuran Butir
Partikel (mm)
Bongkah
Berangkal
Kerakal
Kerikil
Pasir sangat kasar
Pasir kasar
Pasir sedang
Pasir halus
Pasir sangat halus
Lanau
Lempung
> 256
64 256
4 64
2 4
1 2
0,5 1,0
0,25 0,50
0,125 0,250
0,063 0,125
0,0039 0,0630
< 0,0039
Sumber : Dacombe dan Gardiner, 1983
Hasil analisis laboratorium dan perhitungan ukuran butir
tersebut kemudian dikonversi menjadi data GIS sehingga
menghasilkan data titik dalam format shapefile yang
memiliki informasi jenis bongkah dan koordinat geografis.
Data titik shapefile kemudian dianalisis dengan cara
interpolasi dengan software GIS untuk mengetahui lokasilokasi yang memiliki sebaran substrat yang sama di seluruh
dasar perairan. Hasilnya berupa data sebaran substrat
dasar laut.
42
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
2. Deposit Pasir Laut
Deposit pasir laut merupakan dataset tematik pada
penyusunan RWP-3-K yang berisi tentang informasi
sebaran, volume dan besar butir pasir laut. Informasi
tersebut digunakan untuk menentukan alokasi ruang,
khususnya untuk pertambangan dan reklamasi. Peruntukan
yang tidak sesuai, khususnya peruntukan pertambangan
pasir laut, dapat menyebabkan dampak negatif untuk
perairan.
Metode Perolehan Data Deposit Pasir Laut
Metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi
deposit pasir laut adalah melalui pengeboran langsung
dengan bagan sebagai tumpuan pengeboran (untuk
kedalaman kurang dari 10 meter), uji seismik pantul
dangkal (untuk kedalaman lebih dari 10 meter),
interpretasi lapisan batuan hasil survei, masstube.
Metode Pengolahan Data Deposit Pasir Laut
Analisis sampel substrat menghasilkan informasi jenis
substrat beserta besar butir hingga informasi ketebalan
lapisan. Ketebalan lapisan dan luasan tersebut digunakan
untuk pengukuran volume pasir laut.
43
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.7. Contoh Peta Pasir Laut Provinsi Kepulauan
Riau
C. Dataset Oseanograf
1. Data Pasang Surut
Metode Pengukuran Pasang Surut
Pengukuran pasang surut dilakukan untuk mengetahui
karakteristik pasang surut, sehingga dapat diketahui
elevasi muka air laut, tipe pasang surut dan komponen
pasang surutnya. Data pasang surut yang dikumpulkan
diharapkan dapat menjelaskan: tipe pasang surut, Mean
Sea level (MSL), Mean High Water Level (MHWL), Mean
Low Water Level (MLWL), Mean Lowest Low Water Level
(MLLWL) dan tunggang air (maksimum, minimum dan rata
rata). Metode yang digunakan dalam pengukuran pasang
surut meliputi:
1) Metode langsung
Merupakan metode pengukuran pasut pada lokasi
secara langsung (misalnya menggunakan papan
berskala, meteran, serta tide gauge outomatic).
2) Metode tidak langsung
Merupakan metode pengukuran gelombang laut
melalui informasi atau perekaman dari citra satelit
(satelit altimetry)
Pada pengukuran pasut dengan metode langsung, bila
belum ada stasiun pengamatan, maka penentuan lokasi
pengukuran pasut stabil dan terlindung dari ombak besar,
angin, lalu lintas kapal/perahu, arus kuat, serta titik pasut
diikatkan pada Bench Mark (BM) yang permanen yang
stabil, dengan kedalaman minimum air laut pada station
pasut minimum satu meter di bawah permukaan air laut
terendah. Kriteria lokasi pengamatan pasut adalah:
1)
2)
3)
4)
Tersedianya informasi awal tentang kondisi lokasi,
diutamakan pada lokasi yang sudah ada station
pengamatan pasang - surut dari Dishidros TNI - AL
atau BIG, jika tidak ada informasi tersebut maka
ditentukan
pada
lokasi
yang
aman,
mudah
pemantauan, serta tidak terganggu
Lokasi stasiun pasut stabil dan terlindung dari ombak
besar, angin, lalu lintas kapal/perahu, serta arus kuat
Kedalaman minimum air laut pada station pasut
minimum satu meter di bawah permukaan air laut
terendah
Stasiun pasut tidak terganggu selama pengamatan
berlangsung
44
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
5)
Titik pasut diikatkan pada BM yang permanen yang
stabil
Pasang surut diukur dengan menggunakan peralatan papan
berskala atau tide recorder selama 7 hari 7 malam pada 2
stasiun pengamatan. Papan berskala atau tide recorder
harus dipasang dengan posisi terendam air dan tegak tidak
bergerak, serta kedudukan tide recorder yang tidak
menghalangi alur nelayan. Setelah dilakukan pengukuran
harus diikat dengan Bench Mark terdekat (kalau ada). Jika
tidak ada maka harus dibuatkan Bench Mark.
Gambar 4.8. Ilustrasi Pengukuran Pasang Surut
Menggunakan Papan Berskala (Palem Pasut)
Gambar 4.9. Ilustrasi Pengukuran Pasang Surut
Menggunakan Tide Gauge Automatic
45
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.10. Ilustrasi Pengikatan Alat Pengukur Pasut
Pada Titik Ikat Bench Mark (BM)
Metode Analisis Data Pasang Surut
Setelah memperoleh data dari pengukuran di lapangan,
dilakukan analisis sebagai berikut:
a) Grafik Plot
Tujuan dari penyajian data dengan ini adalah untuk
mengetahui tinggi elevasi muka air (pasut) terhadap
waktu (selama waktu) pengukuran.
Neap tide
Neap tide
Spring tide
Neap tide
Gambar 4.11. Contoh Grafik Pengamatan Pasang Surut
Selama 30 Hari
b) Analisis Harmonik Pasut
Pengolahan data pasang surut dilakukan dengan
menggunakan metode admiralty. Metode ini bertujuan
untuk mengetahui komponen pasang surut, sehingga
dapat diketahui tipe pasut dan elevasi muka air acuan,
serta elevasi penting lainnya.
Tipe pasang surut dapat dihitung menggunakan formula
sebagai berikut:
F=
AK 1+ AO 1
AM 2 + AS 2
dimana :
F
= Konstanta pasut
AK1
= Amplitudo dari anak gelombang pasut
harian rata-rata yang dipengaruhi oleh
deklinasi bulan dan matahari
AO1 = Amplitudo dari anak gelombang pasut harian
tunggal yang dipengaruhi oleh deklinasi
matahari
AM2 = Amplitudo dari anak gelombang pasut harian
ganda rata-rata yang dipengaruhi oleh bulan
46
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
AS2 = Amplitudo dari anak gelombang pasut harian
ganda rata-rata yang dipengaruhi oleh matahari
Apabila F memiliki nilai :
0 < F < 0,25 : Sifat Pasut Harian Ganda Murni
0,25 < F < 1,50 : Sifat Pasut Campuran Condong
Harian Ganda
1,50 < F < 3,0 : Sifat Pasut Campuran Condong
Harian Tunggal
3,0 < F
: Sifat Pasut Harian Tunggal Murni
Gambar 4.12. Tipe pasut (Triatmojo, 1998)
Guna memastikan bahwa hasil pengolahan data pasang
surut dengan metode admiralty mempunyai tingkat
akurasi yang cukup baik, maka komponen-komponen
hasil dari pengolahan data pasut digunakan untuk
memprediksikan lagi kejadian pasang surut pada waktu
pengamatan dengan menggunakan metode least square.
Jika hasil prediksi dan pengamatan data lapangan
dengan model metode least square mempunyai pola yang
berimpit (hampir sama), maka hasil peramalan tersebut
mendekati kondisi sebenarnya dilapangan, seperti
gambar berikut:
47
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.13. Contoh verifikasi data pasang surut
lapangan dan hasil peramalan dengan model Least
Square
2. Data Gelombang
Metode Pengukuran Gelombang
Pengukuran gelombang dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui karakteristik dan parameter gelombang yang
meliputi tinggi dan periode. Periode gelombang (T) diukur
berdasarkan waktu tempuh antara satu puncak gelombang
dan puncak gelombang berikutnya, sedangkan tinggi
gelombang (H) merupakan jarak antara puncak gelombang
dan lembah gelombang yang terbentuk.
Metode pengukuran gelombang dapat dilakukan dengan
metode langsung dan atau tidak langsung. Metode
pengukuran secara langsung adalah menggunakan papan
berskala, meteran dan wave rider /wave recorder),
sedangkan metode tidak langsung dapat dilakukan melalui
informasi atau perekaman dari citra satelit.
Penentuan lokasi pengukuran gelombang dapat dilakukan
menggunakan metode non random sampling dengan teknik
area sampel, yaitu penentuan lokasi dengan pertimbangan
dapat mewakili karakteristik wilayah perairan setempat.
Karakteristik wilayah dalam penentuan lokasi pengukuran
gelombang sebagai berikut:
a) Karakteristik Wilayah Pantai dan Lepas Pantai
Pertimbangan yang digunakan untuk pengukuran
gelombang di pantai adalah untuk mengetahui
karakteristik gelombang di dekat pantai (near shore).
Pada lokasi di dekat pantai, karakteristik gelombang
sangat dipengaruhi oleh proses deformasi gelombang
48
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
akibat refraksi dan difraksi gelombang yang dipengaruhi
oleh perubahan kedalaman (pendangkalan), adanya
bangunan pantai, pulau-pulau kecil, maupun pengaruh
lainnya. Sedangkan pengukuran gelombang di lepas
pantai (off shore) bertujuan untuk mengetahui
karakteristik gelombang di lepas pantai.
b) Karakteristik Wilayah Teluk dan Tanjung
Pertimbangan
yang
digunakan
untuk
mengukur
gelombang di dalam teluk adalah untuk mengetahui
karakteristik gelombang di dalam teluk, sedangkan
lokasi di luar teluk untuk karakteristik gelombang di luar
teluk. Fenomena yang terjadi di daerah teluk didominasi
oleh proses refraksi gelombang (divergensi gelombang)
dan cenderung mempunyai tinggi ge-lombang yang
relatif lebih tenang. Oleh karena itu, karakteristik
gelombang di dalam teluk berbeda dengan gelombang di
daerah di luar teluk. Sedangkan untuk daerah tanjung
juga mempunyai karakteristik gelombang berbeda yang
disebabkan oleh refraksi gelombang (konvergensi
gelombang).
Gambar 4.14. Contoh Penentuan Lokasi Survei
Gelombang
Pengukuran gelombang di perairan laut dilakukan
minimal selama 3 x 24 jam dengan interval waktu
pencatatan antara 10-60 menit. Pengukuran sebaiknya
dilakukan pada saat kondisi pasang surut pada fase
spring tide (pasang surut di saat bulan purnama atau
bulan mati), hal ini untuk memperoleh hasil pengukuran
gelombang dengan kondisi pasang surut dengan kisaran
yang besar.
49
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Keterangan Gambar :
Persiapan Pemasangan Wave Recorder di atas kapal
Instalasi Deploy Wave Recorder
Penyelam untuk membantu pemasangan wave recorder di dasar perairan
Gambar 4.15. Ilustrasi alat dan proses pengukuran
gelombang
Data tinggi dan periode gelombang hasil pengukuran
dapat dilihat pada gambar berikut:
Gambar 4.16. Data Tinggi dan Periode Gelombang hasil
pengukuran tanggal 8 September 2015 14 September
2015 di kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau
Metode Pengolahan Data Gelombang
Penentuan Gelombang Representatif
Data
hasil
pengamatan
gelombang
menggunakan
metode
penentuan
representatif sebagai berikut:
dianalisis
gelombang
50
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
dimana : n = 33,3% x Jumlah data
Nilai Hs dihitung dari 33,3% kejadian tinggi gelombang
tertinggi, sedangkan nilai Ts dihitung dari 33,3%
kejadian periode gelombang terbesar. Guna mengetahui
kondisi gelombang pada berbagai musim, gelombang
dapat diprediksi berdasarkan data angin dengan
mempertimbangkan panjang fetch, kecepatan dan arah
angin. Data angin dapat diperoleh dari stasiun Badan
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika terdekat.
Perhitungan Parameter Gelombang
Data parameter gelombang yang dianalisis, meliputi
frekuensi gelombang, panjang gelombang, bilangan
gelombang, kecepatan gelombang, tinggi dan kedalaman
gelombang pecah, koefisien refraksi, koefisien defraksi
dan koefisien pendangkalan. Data parameter gelombang
salah satunya dapat digunakan untuk menentukan
kedalaman relatif.
Kedalaman
relatif
adalah
perbandingan
antara
kedalaman air dan panjang gelombang (Yuwono, 1982).
Berdasarkan data kedalaman relatif (d/L) dapat
dilakukan perhitungan klasifikasi gelombang yaitu:
Gelombang di laut dangkal jika d/L < 0,05
Apabila nilai kedalaman dibanding panjang gelombang
suatu perairan kurang dari 0,05 maka disebut sebagai
gelombang perairan dangkal atau gelombang panjang.
Gelombang di laut transisi jika 0,05 < d/L < 0,5
Apabila nilai kedalaman dibanding panjang gelombang
suatu perairan berada diantara 0,05 sampai 0,5 maka
disebut sebagai gelombang perairan menengah.
Gelombang di laut dalam jika d/L > 0,5
Apabila nilai kedalaman dibanding panjang gelombang
suatu perairan lebih besar dari 0,5 maka disebut
gelombang perairan dalam.
Dimana d adalah kedalaman laut dan L adalah panjang
gelombang.
Penjalaran gelombang ke laut dangkal membentuk orbit
yang terdiri dari partikel-partikel. Perubahan orbital
tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar dibawah:
51
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.17. Gerak orbit partikel zat cair di laut
dangkal, transisi, dan dalam
Sebagai contoh, dari data pengukuran gelombang
diperoleh data perhitungan dimana, L = 55,14 meter
dan d = 21 meter, maka d/L = 0,38, artinya bahwa 1/20
< d/L < sehingga termasuk klasifikasi gelombang laut
transisi.
Pemodelan Matematis Penjalaran Gelombang
Tujuan dari pemodelan matematis adalah untuk
mengetahui tinggi dan arah penjalaran gelombang
menuju pantai. Hal ini penting untuk mengetahui proses
deformasi gelombang menuju pantai, seperti difraksi
ataupun refraksi gelombang.
Untuk mengetahui
distribusi spasial tinggi dan arah gelombang, di seluruh
perairan wilayah perencanaan disimulasikan dengan
model matematika refraksi gelombang.
Hasil pemodelan matematik refraksi gelombang berupa
nilai tinggi gelombang disetiap titik grid yang ada di
seluruh perairan di wilayah perencanaan. Nilai tinggi
gelombang disetiap titik grid yang diperoleh dari hasil
pemodelan
matematik
diinterpolasi
sehingga
menghasilkan kontur tinggi gelombang. Kontur tinggi
gelombang kemudian diklasifikasi dengan interval kontur
gelombang setiap 0,1 meter .
Gambar 4.18. Diagram Proses Pembuatan Kontur
Tinggi: Data Titik Hasil Pemodelan Matematik (1),
Interpolasi (2), Konversi ke Line (3a) dan Polygon (3b).
52
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Penyajian Data Gelombang (Grafk Tinggi dan
Periode Gelombang)
Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk mengetahui
pola dari tinggi (H) dan periode gelombang (T) terhadap
waktu (selama waktu) pengukuran.
Gambar 4.19. Contoh Grafik Tinggi gelombang harian
tanggal 8 September 2015 - 14 September 2015 di kab.
Natuna, prov. Kepulauan Riau
Gambar 4.20. Contoh Grafik Periode Gelombang harian
hasil pengukuran tanggal 8 September 2015 - 14
September 2015 di kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau
3. Data Arus
Metode Pengumpulan Data Arus
Pengukuran arus dimaksudkan untuk mengetahui pola arus
di lokasi pengukuran dan dominasi jenis arus di perairan
(arus pasut atau arus selain pasut). Peta arus adalah peta
yang menginformasikan pola arus di wilayah perencanaan.
Informasi ini sangat diperlukan sebagai data dasar untuk
menentukan pemanfaatan pada wilayah perencanaan.
53
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Metode yang digunakan dalam pengukuran arus meliputi
Metode Euler dan Metode Lagrange.
Metode Euler
merupakan metode pengukuran arus pada lokasi yang
tetap (misal: cur-rent meter).
Sensor yang digunakan
meliputi sensor mekanik dan sensor non-mekanik. Sensor
Mekanik meliputi Current Meters seri RCM, Current
Meters Vektor Rata-rata (VACM) dan Vector Measuring
Current Meter (VMCM), sedang sensor non mekanik
terbagi
menjadi
Acoustic
Current
Meter
(ACM),
Elektromagnetik Current Meter (ECM) dan Acoustic
Doppler Current Profiller (ADCP).
Metode Lagrange merupakan metode pengukuran arus
dengan mengikuti jejak suatu alat (misal: pelampung).
Teknis konvensional dilakukan dengan terjun langsung ke
lapangan sedangkan teknik modern atau Pencatat Arus
Quasi-Lagrange, yang meliputi pencatat arus permukaan
dan bawah permukaan.
Gambar 4.21. Berbagai Tipe Macam Parasut (a), dan
Skema Drifter (b).
Metode penentuan lokasi pengukuran arus biasanya
menggunakan metode teknik non random sampling dengan
teknik area sampel, yaitu penentuan lokasi ditentukan pada
lokasi tertentu dengan pertimbangan dapat mewakili
karakteristik wilayah perairan setempat. Umumnya
pengukuran arus dapat diwakili dengan tiga kedalaman
perairan (permukaan 0,2 d, tengah 0,6 d dan dasar 0,8 d)
untuk setiap kawasan tertentu.
54
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.22. Contoh Penentuan Lokasi Pengukuran Arus
Arah dan kecepatan arus dipengaruhi oleh kondisi pasut,
gelombang dan angin (self current). Pengukuran arus di
perairan laut dilakukan minimal selama 3 x 24 jam dengan
interval waktu pencatatan antara 10 -60 menit (umumnya
dilakukan setiap 60 menit) secara simultan. Pengukuran
arus sebaiknya dilakukan pada saat kondisi pasang surut
pada fase spring tide (pasang surut di saat bulan purnama
atau bulan mati), hal ini untuk memperoleh hasil
pengukuran arus yang optimal.
Permukaan Air
Sel Akhir
Kedalaman Perairan
Sel Awal
Noise Distance
Blank Distance
Ketinggian Alat
Dasar Perairan
Gambar 4.23. Ilustrasi Pengukuran (Perekaman Data)
Kecepatan dan Arah Arus Menggunakan Accoustic Doppler
Current Profiler (ADCP)
55
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.24. Ilustrasi Pengukuran (Perekaman Data)
Kecepatan dan Arah Arus Menggunakan Accoustic Doppler
Current Profiler (ADCP)
Metode Pengolahan Data Hasil Survei Arus
Setelah memperoleh data dari pengukuran di lapangan,
maka hal terpenting adalah bagaimana data tersebut dapat
diolah sehingga dapat dilakukan analisis sesuai tujuan yang
akan dicapai.
Data tersebut diolah dalam bentuk scatter diagram dan
scatter plot. Untuk mengetahui distribusi spasial pola arus
di wilayah perairan pesisir maka dilakukan pemodelan
matematik hidrodinamika pola arus. Pemodelan matematik
hidrodinamika pola arus dapat menggunakan perangkat
lunak (software), seperti SMS BOSS (Amerika), Mike 21
(Denmark), 3DD (New Zealand), Trisula (Belanda),
Telemarc (Perancis), dan lain-lain yang hasilnya dikalibrasi
dengan hasil pengukuran arus.
56
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.25. Contoh verifikasi data kecepatan arus
realtime di lapangan dengan data model di perairan Subi,
kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau.
Gambar 4.26. Contoh verifikasi data arah arus realtime di
lapangan dengan data model
57
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.27. Contoh Kalibrasi Kecepatan Arus Hasil
Simulasi Model Matematik dengan Data Pengamatan
Lapangan dengan Scatter Plot di perairan Subi, kab.
Natuna, prov. Kepulauan Riau tahun 2015.
Vector dan Scatter Plot Arus laut
Tujuan dari penyajian data dengan vektor arus adalah
untuk mengetahui pola arah dan besarnya kecepatan
arus terhadap waktu (selama waktu) pengukuran.
Adapun scatter plot arus ialah untuk mengetahui
distribusi kecepatan dan arah arus selama pengukuran.
Gambar 4.28. Contoh hasil pengolahan data arus
berupa grafik arus
58
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.29. Contoh Penyajian Data Arus Dengan
Menggunakan Vektor Arus Laut di kab. Sangihe, prov.
Sulawesi Utara tanggal 19-30 Agustus 2015
Gambar 4.30. Contoh Penyajian Data Arus Dengan
Menggunakan Scatter Plot Arus di perairan Subi, kab.
Natuna, prov. Kepulauan Riau tahun 2015
Grafk Elevasi (Pasut), Kecepatan dan Arah Arus
Tujuan dari penyajian data dengan grafik elevasi (pasut),
kecepatan dan arah arus adalah untuk mengetahui pola
arah dan besarnya kecepatan arus terhadap waktu
(selama waktu) pengukuran, yang dikaitkan dengan
kondisi pasang surut (elevasi muka air laut). Hal ini juga
merupakan salah satu cara untuk mengetahui hubungan
pasut dengan kondisi arus.
Apakah pola arusnya
mengikuti pola pasang surut atau tidak. Selain itu juga
59
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
untuk melihat bagaimana kondisi arus di kedalaman
permukaan, tengah maupun dasar.
Gambar 4.31. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan
Arus Kedalaman 18-20 Meter (Cell 1) di Perairan kab.
Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14 September
2015.
Gambar 4.32. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan
Arus Kedalaman 16-18 meter (Cell 2) di Perairan kab.
Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14
September 2015.
60
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.33. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan
Arus Kedalaman 14-16 meter (Cell 3) di Perairan kab.
Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14
September 2015.
Gambar 4.34. Contoh hasil Pengolahan Data Kecepatan
Arus Kedalaman 12-14 meter (Cell 4) di Perairan kab.
Natuna, prov. Kepulauan Riau Tanggal 8 - 14
September 2015.
Current Rose (Mawar Arus)
Selanjutnya untuk melihat frekuensi kejadian arus
selama pengukuran dilakukan analisis statistik dengan
menyajikan current rose dan tabelnya. Pada analisis
61
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
tersebut arah arus dikelompokkan 16 mata angin dimana
setiap 22,5 derajat terwakili oleh 1 arah mata angin.
Gambar 4.35. Contoh Current Rose Kedalaman Ratarata di Perairan kab. Natuna, prov. Kepulauan Riau
Tanggal 8 - 14 September 2015.
Gambar 4.36. Contoh Current Rose Kedalaman Cell 5
(10-12 meter) di Perairan kab. Natuna, prov. Kepulauan
Riau Tanggal 8 - 14 September 2015.
62
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.37. Contoh Current Rose Kedalaman Cell 10
(0-2 meter) di Perairan kab. Natuna, prov. Kepulauan
Riau Tanggal 8 - 14 September 2015.
Pada kedalaman rata-rata arah arus dominan menuju ke
arah 315o (Barat Laut). Frekuensi kejadian kecepatan
arus secara keseluruhan yang menuju ke arah 315o
sebesar 43,25 %. Frekuensi kejadian kecepatan arus
dengan kecepatan terbanyak terjadi pada kecepatan arus
>60 cm/det dengan frekuensi kejadian kecepatan arus
secara keseluruhan sebesar 30,43 %. Kecepatan arus
terbesar, yaitu >60 cm/det menuju ke arah 315 (Barat
Laut) dengan frekuensi 19,45 %.
Plot World Current Untuk Mengetahui Jenis Arus
(Pasut atau Selain Pasut)
Untuk membantu analisis arus digunakan Program World
Current Versi 1.03 (12 Desember 2006). Grafik 3-day plot
menunjukkan data arus yang diamati (warna merah),
prediksi (biru), sisa/pengurangan (hijau), sehingga
memberikan sebuah grafik yang fluktuaktif dalam bentuk
gelombang yang menunjukkan model harmonik pasut
sesuai dengan data tersebut. Gambar 23 menunjukkan
bahwa pola kecepatan arus di lokasi kajian dipengaruhi
oleh pasang surut dan selain pasut.
Fluktuasi kecepatan arus berdasarkan data lapangan
(arus total) mempunyai pola yang hampir sama dengan
data model astronomik (arus pasang surut). Namun nilai
residu (arus selain pasut) yang merupakan selisih dari
arus total dan arus pasut mempunyai nilai fluktuasi yang
cukup besar.
Berdasarkan analisis tersebut dapat
disimpulkan bahwa arus di perairan wilayah kajian
dipengaruhi oleh pasang surut dan selain pasut (seperti
angin, gelombang, dll.).
Hasil pengukuran digambarkan dalam scatter diagram,
vektor plot, current rose (mawar arus). Untuk distribusi
63
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
spasial pola arus untuk tiap 2500 m disimulasikan
dengan model hidrodinamika pola arus dengan grid
maksimal 2500 x 2500 m, dan dikalibrasi dengan hasil
pengukuran. Pengukuran dilakukan pada saat kondisi
pasang tinggi (fase spring tide). Peta arus skala
1:250.000, digambar dalam bentuk kontur isoline dengan
interval 0,05 m/detik.
Gambar 4.38. Contoh Analisis Scatter plot Kecepatan
Arus Kedalaman Rata-rata Perairan Kec. Bualemo, Kab.
Banggai.
Gambar 4.39. Scatter Plot Kecepatan Arus Kedalaman
Cell 5 (2-4 meter) (Gambar Kiri) dan Kedalaman Cell 6
(0-2 meter) (Gambar Kanan) Dari Perairan Kec. Bualemo,
Kab. Banggai
Model Matematika
Untuk mengetahui distribusi spasial pola arus skala
1:250.000 (setiap grid 2500 meter) dan distribusi spasial
pola arus (setiap grid 500 meter untuk RZBWP-3-K) di
64
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
seluruh
perairan
wilayah
perencanaan
provinsi,
disimulasikan dengan model matematika hidrodinamika
pola arus dan dikalibrasi dengan hasil pengukuran yang
dilakukan pada kondisi pasang (spring tide).
Pemodelan matematik hidrodinamika yang digunakan
merupakan persamaan aliran 2 dimensi pada rerata
kedalaman (depth average). Percepatan gravitasi lebih
dominan dibandingkan dengan percepatan aliran
vertikal. Sehingga persamaan aliran dapat didekati
dengan persamaan aliran dangkal (shallow water
equation). Komponen kecepatan rata-rata kedalaman
dalam koordinat horizontal x dan y didefinisikan sebagai
berikut :
dimana :
H
= kedalaman air
zb
= elevasi dasar sungai
zb+ H = elevasi muka air
u
= kecepatan horizontal arah x
v
=kecepatan horizontal arah y
Persamaan kontinuitas untuk aliran dua dimensi ratarata kedalaman (averaged continuity equation) dapat
dituliskan sebagai :
H
HU HV 0
t x
y
Persamaan momentum pada arah sumbu x dan y untuk
aliran dua dimensi rata-rata kedalaman dapat dituliskan
sebagai :
zb 1 H 2 1
( HU ) + ( xx HUU ) +
xy HUV )+ gH
+ g
+ bx sx ( H xx )
(
t
x
y
x 2 x
x
untuk aliran arah sumbu x, dan
z 1 H2 1
( HV )+
xy HUV ) +
yy HVV ) + gH b + g
+ by sy ( H yx )
(
(
t
x
y
y 2 y
x
untuk aliran pada sumbu y, dimana :
xx, xy, yx yy
= koefisien koreksi momentum
g
= percepatan gravitasi
65
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
bx by
sx sy
= rapat massa air
= tegangan geser dasar
= tegangan geser permukaan
xx, xy, yx yy
= tegangan geser akibat turbulensi
Misal xy adalah tegangan geser ke arah sumbu x yang
bekerja pada bidang tegak lurus sumbu y, maka
komponen tegangan geser pada dasar dalam arah sumbu
x dan y dihitung sebagai berikut :
dengan cf adalah koefisien gesek dasar yang dapat
dihitung sebagai :
cf
g
gn 2
1
C 2 2 H 3
dengan C = koefisien Chezy; n = koefisien kekasaran
Manning; dan = 1,486 bila menggunakan satuan
Inggris dan 1,0 bila menggunakan satuan internasional
(SI).
Tegangan geser turbulen rata-rata kedalaman dihitung
menggunakan konsep eddy viskositas dari Boussinesq,
yakni :
Untuk
penyederhanaan
perhitungan,
nilai
eddy
viskositas kinematik rata-rata kedalaman dianggap
isotropik (diasumsikan bahwa nilai xx = xy = yx =
yy), dan eddy viskositas isotropik dinotasikan dengan
yang nilainya (0,3 0,6 U*H).
Hasil pemodelan matematik hidrodinamika pola arus
berupa nilai kecepatan dan arah arus disetiap titik-titik
66
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
grid yang ada di seluruh perairan di wilayah
perencanaan. Nilai kecepatan arus disetiap titik-titik grid
diinterpolasi sehingga menghasilkan kontur isoline
kecepatan arus. Kontur isoline kecepatan arus kemudian
diklasifikasi dengan interval kontur setiap 0,05 meter per
detik.
4. Data Suhu Permukaan Laut
Metode Pengumpulan Data Suhu Permukaan Laut
Data parameter suhu permukaan laut, diperoleh dari
analisis citra penginderaan jauh thermal, contohnya adalah
Citra Modis atau citra lain yang memiliki saluran thermal.
Untuk mendapatkan sebaran nilai suhu permukaan laut
tiap grid 2500 m untuk skala 1:250.000 dan tiap grid 500 m
untuk skala 1:50.000 pada citra satelit, dilakukan
transformasi
matematis
menggunakan
software
pengolahan citra. Analisis suhu permukaan laut dilakukan
berdasarkan data rerata suhu permukaan laut bulanan
minimal selama lima tahun.
Hasil transformasi tersebut digunakan untuk menentukan
titik sampel pengukuran suhu permukaan laut di lapangan.
Jumlah dan lokasi sampel ditentukan berdasarkan
keragaman nilai suhu permukaan laut dan keterwakilan
wilayah.
Metode Pengolahan Data Suhu Permukaan Laut
Analisis suhu permukaan laut dilakukan dengan cara
mengkoreksi data suhu permukaan laut hasil pengolahan
citra satelit dengan menggunakan data hasil pengukuran di
lapangan. Koreksi dilakukan dengan cara transformasi
matematik
menggunakan
software
pengolah
citra,
sehingga dihasilkan data suhu permukaan laut yang
valid/sesuai kondisi di lapangan.
5. Data Kecerahan
Metode Pengumpulan Data Suhu Permukaan Laut
Kecerahan air laut diukur secara langsung di lapangan
menggunakan Seechi Disk. Penentuan lokasi dan jumlah
sampel ditentukan dengan melihat variabilitas rona/warna
perairan, sehingga setiap tingkat kecerahan perairan dapat
terwakili secara proporsional. Variabilitas rona/warna
perairan yang menunjukkan tingkat kecerahan perairan
dapat diidentifikasi menggunakan
Metode Pengolahan Data Suhu Permukaan Laut
Berdasarkan hasil pengukuran kecerahan di lapangan
diperoleh tingkat kecerahan perairan untuk setiap titik
sampel. Tingkat kecerahan perairan tersebut kemudian di
67
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
interpolasi
sehingga
menghasilkan
kontur
isoline
kecerahan untuk seluruh perairan di wilayah perencanaan.
6. Data Oseanograf Kimia (pH dan Salinitas)
Metode Pengumpulan Data Oseanograf Kimia
Parameter oseanografi kimia diantaranya pH dan salinitas.
Untuk menjaga akurasi data, pengukuran semua parameter
ini sebaiknya dilakukan di lokasi (in situ). pH diukur
menggunakan pH meter. Salinitas diukur menggunakan
salinometer atau refraktometer.
Penentuan Lokasi sampel untuk data oseanografi kimia
dilakukan dengan metode purposive sampling. Lokasi
sampel
ditentukan
dengan
mempertimbangkan
karakteristik wilayah perairan setempat (daerah pertemuan
arus, daerah muara sungai, daerah di sekitar selat yang
menghubungkan dua perairan, daerah teluk dan tanjung
dan daerah yang memiliki variabilitas kondisi ekosistem).
Metode Analisis Data Oceanograf Kimia
Berdasarkan hasil pengukuran data oseanografi kimia di
lapangan, diperolah nilai-nilai pH dan salinitas untuk setiap
titik sampel. Masing-masing nilai parameter tersebut
kemudian di interpolasi sehingga menghasilkan kontur
isoline pH dan salinitas untuk seluruh perairan di wilayah
perencanaan.
7. Oseanograf Biologi (Klorofl)
Metode Pengumpulan Data Oseanograf Biologi
Data klorofil dapat diidentifikasi dari citra penginderaan
jauh, contohnya adalah Citra Modis, NOAA-AVHRR, atau
citra lain yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi
klorofil. Untuk mendapatkan sebaran nilai klorofil tiap grid
pada citra satelit, dilakukan transformasi matematis
menggunakan software pengolahan citra. Analisis klorofil
dilakukan berdasarkan data rerata klorofil bulanan minimal
selama lima tahun.
Hasil transformasi tersebut digunakan untuk menentukan
titik sampel pengukuran klorofil di lapangan. Nilai klorofil
di lapangan diperoleh dari Jumlah sampel ditentukan
berdasarkan keragaman interval nilai klorofil pada citra
satelit.
Metode Pengolahan Data Oceanograf Biologi
Analisis klorofil dilakukan dengan cara mengkoreksi data
klorofil hasil pengolahan citra satelit dengan menggunakan
data hasil pengukuran di lapangan. Koreksi dilakukan
dengan cara transformasi matematik menggunakan
68
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
software pengolah citra, sehingga dihasilkan data klorofil
yang valid/sesuai kondisi di lapangan.
Berdasarkan data klorofil yang telah terkoreksi, dilakukan
penyusunan peta kontur isoline klorofil dengan cara
interpolasi nilai-nilai klorofil disetiap titik-titik grid yang
ada di seluruh perairan di wilayah perencanaan.
D. Dataset Pemanfaatan Ruang Laut Yang Sudah Ada
Metode Pengumpulan Data Pemanfaatan Ruang Laut
Yang Sudah Ada
Pemanfaatan ruang laut yang sudah ada adalah berbagai
kegiatan pemanfaatan bentang perairan yang dilakukan
secara permanen maupun temporer. kegiatan pemanfaatan
laut
eksisting
diantaranya
pertambangan,
kawasan
konservasi, pariwisata, BMKT, tambat labuh, rig, floating
unit, bangunan perikanan permanen (KJA, seabed, dll.), area
penangkapan ikan modern dan tradisional dan budidaya laut
(seperti rumput laut dan mutiara).
Infrastruktur kelautan dan perikanan diantaranya pelabuhan
umum, pasar ikan, KUD, BBI, Pelabuhan perikanan, TPI,
Gudang penyimpanan ikan, bangunan pelindung pesisir (jeti,
penahan gelombang).
Untuk memperoleh data lokasi pemanfaatan wilayah laut
yang telah ada, dilakukan identifikasi visual menggunakan
citra penginderaan jauh resolusi tinggi (resolusi minimal 1
meter.) Hasil identifikasi visual pada citra tersebut digunakan
untuk groundcheck di lapangan dengan cara tracking dan
plotting koordinat pada lokasi pemanfaatan laut yang
ditemukan dengan menggunakan GPS.
Metode Pengolahan Data Pemanfaatan Wilayah Laut
Eksisting
Metode pengolahan data pemanfaatan laut existing dilakukan
dengan cara ploting koordinat titik GPS hasil identifikasi
citra penginderaan jauh dan poligon (untuk data yang berupa
area) hasil groundcheck di lapangan ke dalam peta dasar.
Kondisi infrastruktur dapat diketahui berdasarkan data
sekunder yang telah ada dan juga melalui pengamatan
langsung di lapangan. Data sekunder terkait dengan kondisi
infrastruktur berupa peta analog atau data tabular sebaran
infrastruktur.
Melalui pengamatan langsung di lapangan
diperoleh
data
jenis
infrastruktur
dan
posisinya
(menggunakan GPS).
69
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
E. Dataset Ekosistem Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
1. Data Terumbu Karang
Metode Pengumpulan Data Terumbu Karang
Data terumbu karang dapat diperoleh melalui pendekatan
penginderaan jauh dan survei lapangan. Identifikasi
terumbu karang melalui citra penginderaan jauh dilakukan
dengan cara dengan metode visual (on screen digitizing)
maupun transformasi matematis, misalnya transformasi
Lyzenga. Secara visual, untuk membedakan terumbu
karang dan substrat dasar lainnya dilakukan dengan
pendekatan unsur-unsur interpretasi citra.
Hasil
interpretasi
citra
satelit
digunakan
untuk
menentukan sampel yang akan dibawa ke lapangan untuk
verifikasi kebenarannya. Metode penentuan sampel yang
digunakan adalah purposive dan proportional random
sampling.
Purposive
dengan
mempertimbangkan
keragaman atau variabilitas kelas terumbu karang.
Proportional
random
sampling
digunakan
dalam
menentukan
titik
sampel
pada
lokasi
dengan
mempertimbangkan jumlah sampel pada setiap kelas
terumbu karang. Jumlah titik sampel yang ditentukan harus
representatif berdasarkan luasan area yang dipetakan.
Survei lapangan dilakukan untuk mendapatkan data
sebaran dan kondisi terumbu karang. Informasi sebaran
terumbu karang dapat diperoleh dengan menggunakan
metode Manta Tow. Untuk melihat kondisi terumbu karang
beserta keanekaragaman jenisnya digunakan Point
Intercept Transect (PIT). Pada saat survei terumbu karang,
dilakukan
pula
identifikasi
kelimpahan
dan
keanekaragaman jenis ikan karang (demersal). Metodemetode tersebut di atas akan dijelaskan secara rinci pada
paparan di bawah ini.
Manta Tow
Metode ini bertujuan untuk mengetahui kondisi
ekosistem terumbu karang dalam waktu yang relatif
singkat dalam skala yang luas. Metode ini berguna untuk
mengetahui
kondisi
umum,
heterogenitas
suatu
komunitas karang sehingga data yang dihasilkan dapat
digunakan sebagai acuan dalam menentukan lokasilokasi yang mewakili area terumbu untuk pengamatan
ekosistem terumbu karang yang lebih detail.
Manta Tow dilakukan dengan cara mengamati tutupan
substrat dasar laut oleh penyelam snorkel yang ditarik
oleh perahu kecil untuk menentukan kondisi terumbu
karang pada skala luas. Kecepatan perahu dijaga tetap
dengan kecepatan kurang lebih 5 km/jam atau sama
70
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
dengan kecepatan orang berjalan. Metode Manta Tow
melibatkan minimal 3 orang, yang terdiri dari pengamat
1, pengamat 2 dan pengemudi perahu. Pengamat 1
bertugas memotret, mengamati dan mencatat kondisi
tutupan substrat di wilayah yang diamati, dengan cara
berpegangan dengan papan manta kemudian ditarik oleh
perahu dan melintas di atas puncak terumbu (reef crest).
Sementara pengamat 2 yang berada di atas perahu
bertugas mengatur waktu, menggunakan GPS dan
berkomunikasi dengan pengamat 1. Pengemudi perahu
bertugas mengemudikan perahu agar berada di jalur
yang sesuai dengan kecepatan yang sesuai juga. Waktu
setiap tarikan adalah 2 menit, kemudian setelah 15
tarikan berhenti sejenak untuk pergantian dimana
pengamat 2 akan menggantikan pengamat 1 dan begitu
sebaliknya. Hal ini terus berulang sampai seluruh area
yang direncanakan teramati.
Gambar 4.40. Ilustrasi Teknik Manta Tow (diadaptasi
dari Brainard dkk, 2014)
Gambar 4.41. Aktifitas tambahan selama pelaksanaan
metode Manta Tow
71
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Point Transect
Metode Point Transect adalah salah satu metode
penilaian kondisi terumbu karang dengan cara mencatat
jenis substrat dasar utamanya karang keras di bawah
transek garis di setiap interval 0,5 m. Pengamat hanya
mencatat jenis substrat pada meter ke-0, lalu titik 0,5 m
kemudian titik 1 m dan seterusnya hingga meter ke-100.
Transek garis dibuat dengan memasang roll meter
sepanjang 100 m sejajar dengan reef crest pada
kedalaman 7 m (Gambar 3). Penyelam SCUBA yang
melakukan pencatatan dengan cara membagi transect
menjadi empat segmen, setiap segmennya terdiri dari 20
m dengan batas antar segmen sepanjang 5 m, sehingga
akan diperoleh 40 data point setiap segmen.
Kedalaman survei 10 20 m
Survei dilakukan dalam 2-3 transek sepanjang 25 m
Unit sampling bervariasi sepanjang transek
Gambar 4.42. Ilustrasi Teknik Point Transect
(diadaptasi dari Brainard dkk, 2014)
72
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.43. Pengamatan substrat dasar
menggunakan transek garis metode Point Transect
Metode Analisis Data Terumbu Karang
Kondisi Ekosistem Terumbu Karang
Kondisi ekosistem terumbu karang ditentukan oleh
persentase tutupan karang, indeks keanekaragaman,
indeks keseragaman, dan indeks dominansi biota.
Tutupan karang diperoleh menggunakan metode Manta
Tow. Indeks keragaman, indeks keseragaman, dan indeks
dominansi biota diperoleh menggunakan metode Point
Transect.
Persentase tutupan karang hidup dapat dilihat dari
jumlah karang keras hidup (Scleractinia spp.), yang
merupakan unsur dominan di dalam ekosistem terumbu
karang (Sukarno, 1995).
Tabel 4.3 Kriteria Penilaian Kondisi Terumbu Karang
Berdasarkan Persentase Tutupan Karang Hidup (SK
Meneg LH No. 04/2001)
Persentase Tutupan
Karang (%)
0 24,9
25 49,9
50 74,9
75 100
Kondisi Terumbu Karang
Rusak
Baik
Buruk
Sedang
Baik
Baik sekali
Keanekaragaman jenis karang dihitung berdasarkan
rumus Indeks Keanekaragaman dari Legendre &
Legendre (1983) dengan rumus sebagai berikut :
dimana :
H
n
ni
= Indeks Keanekaragaman Legendre &
Legendre
= jumlah spesies dalam sampel
= jumlah panjang karang jenis ke-i
= jumlah panjang total seluruh jenis
73
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Analisa data tentang nilai Indeks Keanekaragaman
Legendre & Legendre adalah sebagai berikut:
H < 3,20
= keanekaragaman kecil dan tekanan
ekologi sangat kuat
3,20 < H < 9,97 = keanekaragaman sedang dan
tekanan ekologi sedang (moderat)
H > 9,97
= keanekaragaman tinggi, terjadi
keseimbangan ekosistem.
Sementara Keanekaragaman jenis ikan karang dihitung
berdasarkan rumus Indeks Keanekaragaman ShannonWienner (1981) dengan rumus sebagai berikut :
dimana :
H = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wienner
S = jumlah spesies dalam sampel
ni = jumlah individu ikan karang jenis ke-i
N = jumlah total individu seluruh jenis
Analisa data tentang nilai Indeks Keanekaragaman
Shannon-Wienner adalah :
H < 1 = berarti komunitas dalam kondisi tak
stabil
1<H<3
= berarti komunitas dalam kondisi
sedang (moderat)
H>3
= berarti komunitas dalam kondisi baik
Indeks Keseragaman (J) jenis bertujuan untuk
mengetahui keseimbangan individu dalam keseluruhan
populasi terumbu karang/ ikan karang, yang merupakan
perbandingan nilai keragaman dengan nilai keragaman
maksimum. Nilai Indeks Keseragaman jenis karang dan
ikan karang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut
:
dimana :
J = Indeks Keseragamanan
74
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
H = Indeks Keanekaragaman
S = jumlah spesies dalam sampel
Pengambilan keputusannya adalah, jika :
J < 0,3
= keseragaman populasi kecil
0,3 < J < 0,6 = keseragaman populasi sedang
J > 0,6
= keseragaman populasi tinggi
Bila J mendekati 0 (nol), spesies penyusun tidak banyak
ragamnya, ada dominasi dari spesies tertentu dan
menunjukkan adanya tekanan terhadap ekosistem. Bila J
mendekati 1 (satu), jumlah individu yang dimiliki antar
spesies tidak jauh berbeda, tidak ada dominasi dan tidak
ada tekanan terhadap ekosistem.
Indeks Dominansi jenis digunakan untuk mengetahui
sejauh mana kelompok biota mendominasi kelompok lain
(Ludwig, 1988). Nilai Indeks Dominansi jenis karang dan
ikan karang dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut
:
dimana:
C = Indeks Dominasi Jenis
ni = Jumlah individu jenis ke-i
N = Jumlah total individu seluruh jenis
2. Data Lamun
Lamun memegang peranan penting pada komunitas pesisir
karena merupakan pendukung bermacam-macam fauna
yang berasosiasi di dalamnya, sehingga keberadaannya
mempengaruhi produktivitas pesisir. Komunitas ini juga
berperan sebagai penstabil sedimen dan mengontrol
kualitas dan kejernihan air.
Padang lamun pada wilayah tropis hidup di perairan
dangkal dengan substrat halus disepanjang pantai dan
estuari. Coles et.al, (1993) menyatakan bahwa komposisi
spesies lamun terdapat pada: (1) perairan dangkal
kurang dari 6 meter merupakan daerah dengan kelimpahan
tinggi; (2) perairan
kedalaman
antara
6
sampai
kedalaman 11 meter, didominasi oleh Halodule spp dan
Halophila spp; dan (3) perairan dengan lebih dari 11
meter, hanya dihuni oleh Halophila spp.
Metode Pengumpulan Data Lamun
75
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Pengumpulan data padang lamun dapat dilakukan melalui
interpretasi citra penginderaan jauh dan survei lapangan.
Melalui metode penginderaan jauh, sebaran padang lamun
dapat diidentifikasi menggunakan metode visual (on screen
digitizing) maupun transformasi matematis, misalnya
transformasi Lyzenga. Hasil interpretasi citra satelit
berupa peta tentatif sebaran padang lamun yang
selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penentuan titik
lokasi survei lapangan.
Untuk survei lapangan, pengamatan padang lamun
dilakukan
menggunakan
metode
transek
kuadrat.
Pelaksanaan metode ini menggunakan petak berbentuk
bujursangkar yang dibentangkan secara tegak lurus
terhadap garis pantai. Pengukuran dilakukan dengan
menggunakan petak pengamatan seluas 10 m x 10 m. Di
dalam petak pengamatan diletakkan petak berbentuk
bujursangkar ukuran 1 m x 1 m secara sejajar luas areal
pengamatan. Pengamatan didukung dengan kamera bawah
air (underwater camera). Hasil yang diperoleh dari metode
ini adalah persentase tutupan relatif (English et al, 1997).
Penutupan lamun menyatakan luasan area yang tertutupi
oleh tumbuhan lamun.
Persentase penutupan lamun
ditentukan berdasarkan rumus:
n
C= M i x F i /f
i=1
Keterangan:
C = nilai persentae penutupan lamun (%)
Mi = nilai tengah kelas penutupan ke-i
Fi = frekuensi munculnya kelas penutupan ke-i
f = jumlah total frekuensi penutupan kelas
Tabel. 4.4 Persentase Luas Tutupan Padang Lamun
(Kepmen LH No. 200 Tahun 2004)
PARAMET
ER
Prosentas
e Luas
Tutupan
Padang
Lamun
KRITERIA BAKU KERUSAKAN PADANG
LAMUN
(dalam %)
Miskin
< 29,9
Rusak
Kurang
kaya/kurang sehat
30 59,9
Baik
Kaya/sehat
> 60
Metode Pengolahan Data Lamun
76
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Berdasarkan hasil pengukuran persentase pengukuran
relatif padang lamun, dilakukan pengolahan lebih lanjut
untuk memperoleh komposisi jenis lamun, kerapatan
spesies, dan penutupan spesies.
Komposisi Jenis Lamun
Komposisi jenis merupakan perbandingan antara jumlah
individu suatu jenis terhadap jumlah individu secara
keseluruhan. Komposisi jenis lamun dihitung dengan
menggunakan rumus:
K i=
ni
x 100
N
Keterangan:
Ki = komposisi jenis ke-i (%)
ni = jumlah individu jenis ke-i (ind)
N = jumlah total individu (ind)
Kerapatan Jenis Lamun
Kerapatan jenis lamun yaitu jumlah total individu suatu
jenis lamun dalam unit area yang diukur. Kerapatan
jenis lamun ditentukan berdasarkan rumus:
p
K i =
i=1
ni
A
Keterangan:
Ki = kerapatan jenis ke-i (ind/m2)
ni = jumlah individu atau tegakan dalam transek kei (ind)
A = luas total pengambilan sampel (m2)
Penutupan Spesies
Penutupan Spesies (PCi) adalah perbandingan antara
luas area penutupan jenis i (Ci) dan luas total area
penutupan untuk seluruh jenis (A), yang dijelaskan
melalui rumus:
PCi = (Ci / A) x 100
3. Data Mangrove
Hutan mangrove merupakan komunitas pantai tropis yang
didominasi oleh beberapa jenis mangrove yang mampu
tumbuh dan berkembang di daerah pasang surut baik
77
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
pantai berlumpur atau berpasir (Bengen, 1999). Saenger et
al. (1983) mendefinisikan mangrove sebagai karakteristik
formasi tanaman litoral tropis dan sub tropis di sekitar
garis pantai yang terlindung.
Metode Pengumpulan Data Mangrove
Data mangrove dapat diperoleh melalui pendekatan
penginderaan jauh dan survei lapangan. Identifikasi
mangrove melalui citra penginderaan jauh dilakukan
dengan metode visual (on screen digitizing) maupun
transformasi matematis. Interpretasi mangrove dengan
citra penginderaan jauh dilakukan dengan melihat
perbedaan rona/tingkat kecerahan, warna, bentuk, pola,
dan asosiasi/kedekatan terhadap obyek lain. Selain metode
visual, identifikasi mangrove dapat juga dilakukan dengan
metode transformasi matematis diantaranya, Ratio
Vegetation Index (RVI), Transformed RVI (TRVI), Difference
Vegetation Index (DVI), Normalized Difference Vegetation
Index (NDVI), dan Transformed NDVI (TNDVI).
Hasil interpretasi citra penginderaan jauh meliputi
perkiraan luas, kerapatan, dan distribusi vegetasi. Hasil ini
selanjutnya digunakan untuk menentukan lokasi sampling
untuk verifikasi lapangan.
Penentuan sampel menggunakan metode purposive
random sampling dan proportional random sampling.
Purposive
random
sampling
mempertimbangkan
keragaman atau variabilitas kelas mangrove. Proportional
random sampling digunakan dalam menentukan titik
sampel pada lokasi dengan mempertimbangkan jumlah
sampel pada setiap kelas mangrove. Jumlah titik sampel
yang ditentukan harus representatif berdasarkan luasan
area yang dipetakan.
Survei lapangan kondisi ekosistem mangrove meliputi
pengambilan data jumlah individu,
kerapatan dan
distribusi vegetasi. Metode ini menggunakan plot/petak
dengan ukuran 10 x 10 meter yang diletakkan secara acak
sesuai dengan jumlah sampel yang telah ditentukan. Pada
setiap petak yang telah ditentukan, dilakukan identifikasi
setiap tumbuhan mangrove yang ada, jumlah individu
setiap jenis, dan lingkaran batang setiap pohon mangrove.
Data mangrove yang dikumpulkan meliputi jenis, komposisi
jenis, kerapatan jenis, frekuensi jenis, luas area penutupan,
nilai penting jenis, dan biota yang berasosiasi. Data
tersebut diolah lebih lanjut untuk memperoleh kerapatan
jenis, frekuensi jenis, luas area penutupan, dan nilai
penting suatu spesies dan keanekaragaman spesies.
Metode pengumpulan data mangrove dapat dilihat pada
tabel berikut:
78
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Tabel 4.7. Metode Survei Mangrove
Skala
Sumber data
Kerja
laboratoriu
m
1:
250.00
0
Peta
dasar
dengan tingkat
kedetilan
peta
1: 250.000
1:
50.000
Peta
dasar Deliniasi
Survei
verifikasi
dengan tingkat mangrove:
tutupan
mangrove
kedetilan
peta
dan non-mangrove
Klasifikasi Transek/jalur
1: 50.000
yang
penutupan
diambil
secara
tajuk
sistematik
dengan
awal teracak:
Penutupan tajuk
Kerapatan pohon
Deliniasi
tutupan
vegetasi
mangrove
Survei verifkasi
lapangan
Survei
verifikasi
tutupan mengrove dan
non-mangrove
Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit dan survei
lapangan, mangrove dapat dikategorikan sebagai berikut:
Tabel 4.8. Klasifikasi tingkat kerapatan mangrove
Skala
Klasifkasi
1:
Mangrove
250.00 Non-mangrove
0
1:
50.000
Penutupan tajuk (%)
Kerapatan ( pohon/ha)
Mangrove lebat (70
100)
Mangrove sedang (50
69)
Mangrove
jarang(<50)
Non-mangrove
Mangrove rapat (660)
Mangrove sedang (330
KP < 660)
Mangrove jarang(<330)
Non-mangrove
Sumber : SNI Survei dan Pemetaan Mangrove, 2011
Metode Pengolahan Data Mangrove
Berdasarkan data-data mangrove yang telah diidentifikasi
di lapangan berupa spesies, jumlah individu dan diameter
pohon,
dilakukan
pengolahan
lebih
lanjut
untuk
memperoleh kerapatan jenis, frekuensi jenis, penutupan
jenis, indeks keanekaragaman, dan indeks kemerataan.
Rumus-rumus untuk analisis data adalah sebagai berikut:
79
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Kerapatan Jenis (Di) adalah jumlah tegakan jenis i
dalam suatu unit area:
Di = ni / A
dimana Di adalah kerapatan jenis i, ni adalah jumlah total
individu dari jenis i dan A adalah luas total area
pengambilan contoh (luas total petak contoh/plot)
Frekuensi Jenis (Fi) adalah peluang ditemukannya
jenis i dalam petak contoh/ plot yang diamati:
Fi= pi/p
dimana, Fi adalah frekuensi jenis i, pi adalah jumlah
petak contoh/ plot dimana ditemukan jenis i, dan p
adalah jumlah total petak contoh/plot yang diamati.
Penutupan jenis (Ci) adalah jenis luas penutupan jenis
i dalam suatu unit area:
Ci=BA/A
dimana BA= DBH2/4 (dalam cm2), (3,1416) adalah
suatu konstanta dan DBH adalah diameter batang pohon
dari jenis i,A adalah luas area pengambilan contoh (luas
total petak contoh/ plot). DBH= CBH adalah lingkaran
pohon setinggi dada.
Indeks Keanekaragaman (H)
Keanekaragaman jenis (species diversity) vegetasi
mangrove ditentukan dengan indeks Keanekaragaman
Shanon-Wiener (H) (Odum, 1971) dengan formula
sebegai berikut :
H = - Pi ln Pi
dimana :
H
Pi
ni
= Indeks Keanekaragaman
= (ni / N)
= jumlah individu dari jenis ke-i
= jumlah total seluruh individu
Kisaran nilai indeks keanekaragaman Shannon Wienner
diklasifikasikan sebagai berikut:
H < 1 =
Keanekaragaman
jenis
kecil
dan
komunitas rendah
H < 1 < 3
= Keanekaragaman jenis sedang dan
komunitas sedang
80
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
H > 3 = Keanekaragaman
komunitas tinggi
jenis
tinggi
dan
Indeks Kemerataan (E)
Keseragaman
jenis vegetasi mangrove ditentukan
dengan indeks kemerataan (Brower and Zar, 1977),
dengan formula sebagai berikut :
E = H / Hmaks
; dan
Hmaks = l n S
dimana:
H
= Indeks Keanekaragaman
= Jumlah Jenis
Nilai keseragaman berkisar antara 0 1. Apabila nilai E
mendekati 0, maka sebaran individu antara jenis tidak
merata dan apabila nilai E mendekati 1, maka sebaran
individu antara jenis merata.
F. Dataset Sumberdaya Ikan Pelagis dan Demersal
1. Daerah Penangkapan Ikan Pelagis
Ikan pelagis merupakan ikan yang memiliki kebiasaan
berenang dekat permukaan perairan, berenang secara
terus menerus dan cenderung beruaya atau tidak menetap
di suatu area. Ikan pelagis dibagi menjadi ikan pelagis
besar dan ikan pelagis kecil. Contoh ikan pelagis besar
antara lain : ikan tuna besar (madidihang, tuna mata besar,
albakor, tuna sirip biru, tuna ekor kuning; ikan
pedang/setuhuk (ikan pedang, setuhuk, setuhuk biru,
setuhuk hitam, setuhuk loreng, ikan layaran); ikan tuna
kecil (cakalang, tongkol); dan jenis-jenis ikan cucut. Contoh
ikan pelagis kecil antara lain: ikan selar, kembung, teri,
layang, tembang, lemuru, dan ikan terbang.
Metode Pengumpulan Data Sumberdaya Ikan Pelagis
Delineasi/pemetaan daerah penangkapan ikan (DPI)
pelagis dilakukan dengan metode penginderaan jauh
multitemporal dan survei lapangan. Metode penginderaan
jauh
menggunakan
beberapa
parameter
sebagai
pendekatan, yaitu suhu permukaan laut (SPL)/Sea Surface
Temperature (SST), klorofil, Sea Surface Height Anomaly
(SSHA) dan Total Suspended Solid (TSS). Citra Satelit yang
digunakan diantaranya NOAA-AVHRR (Advance Very High
Resolution Radiometer), Aqua/Terra Modis dan SeaWiffs
untuk periode lima tahun (multitemporal). Penggunaan
parameter untuk DPI Pelagis pada skala pemetaan provinsi
(1 : 250.000 ):
81
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Tabel 4.9. Parameter Oseanografi Dalam Penentuan DPI
Pelagis Sesuai Skala Pemetaan
Skala
Pemetaa
n
Parameter yang
digunakan
1
: 1. Suhu permukaan laut
250.000
(SPL atau SST)
2. Klorofil
3. Sea Surface height
Anomaly (SSHA) Arus
Keterangan
Data diperoleh dari citra
penginderaan
jauh
oseanografi dan altimetri
multitemporal (5 tahunan)
Metode Analisis Daerah Penangkapan Ikan (DPI)
Pelagis
Untuk menentukan lokasi DPI ikan pelagis berbasis data
penginderaan jauh dapat menggunakan data citra. Data
citra tersebut berasal dari satelit SEAWIFT, Aqua MODIS,
dan SeaSAT, Landsat 8, AVHRR, dan RADARSAT, JASON2,
TOPEX/POSEIDON.
Langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan DPI
adalah:
Gambar 4.44. Tahapan Pengolahan Data Penginderaan
Jauh untuk Menghasilkan Daerah Penangkapan Ikan
(dimodifikasi dari Hendiarti, Suwarso, Aldrian, Amri,
Andiastuti, Sachoemar & Wahyono - 2005)
82
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
-
Analisis dan interpretasi data penginderaan jauh untuk
menghasilkan sebaran klorofil-a, suhu permukaan laut
dan arus geostropik (Tahap 1, 1A, 2, 2A, 3 dan 3A pada
Gambar 4.51)
Penetapan Daerah Potensi Ikan Pelagis Potensial
menggunakan analisis ontologi daerah penangkapan
ikan(Tahapan 4 pada Gambar 4.51)
Verifikasi dan validasi daerah potensi ikan pelagis
potensial dengan hasil pengukuran di lapangan seperti
data hasil tangkapan (in situ atau data sekunder) dan
data kualitas air (Tahap 5 pada Gambar 4.51).
Analisis non-spasial terkait dengan pengembangan
wilayah,
merujuk
pada
hal-hal
yang
perlu
dipertimbangan seperti yang telah dijabarkan di atas.
Analisi ini harapannya dapat menghasilkan zona-zona
yang ideal yang akan disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan (Tahap 6 pada Gambar 4.51)
Penetapan zona perikanan tangkap pelagis untuk
selanjutnya dapat disepakati oleh seluruh pemangku
kepentingan di daerah (Tahap 7 pada Gambar 4.51).
Analisis citra oseanografi
langkah sebagai berikut:
dilakukan
melalui
langkah-
Analisis Suhu Permukaan Laut
Identifikasi
suhu
permukaan
laut
menggunakan
pendekatan citra penginderaan jauh dilakukan melalui
penerapan algoritma untuk menonjolkan informasi suhu
permukaan pada citra satelit. Langkah-langkah analisis
citra sebagai berikut:
Gambar 4.45. Diagram Alir Pengolahan Citra Satelit
untuk analisis Suhu Permukaan Laut
83
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.46. Contoh Hasil Analisis SST Multitemporal
Dari Citra Satelit Untuk Wilayah Teluk Tomini
Analisis Klorofl
Dalam pendeteksian klorofil perairan, citra penginderaan
jauh Ocean Color (Misal SeaWIFS) dapat memberikan
data dan informasi tentang adanya variasi warna
perairan
sebagai
implementasi
dari
perbedaan
konsentrasi fitoplankton dalam perairan.
Langkahlangkah pengolahan data ocean color sebagai berikut:
Gambar 4.47. Pengolahan Data Ocean Color untuk
Identifikasi Klorofil Perairan
84
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.48. Contoh Hasil Analisis Klorofil
Menggunakan Citra Satelit Multitemporal Analisis Sea
Surface Height Anomaly (SSHA)
Data SSHA diperoleh melalui analisis citra penginderaan
jauh
altimetri,
yaitu
citra
satelit
yang
dapat
menunjukkan pola-pola perubahan permukaan laut
secara
kontinu, misalnya
perputaran arus dan
gelombang.
Analisis selanjutnya dilakukan melalui
tumpangsusun peta suhu permukaan laut, klorofil dan
arus sebagaimana gambar berikut:
Untuk mendapatkan informasi DPI pelagis yang valid
dilakukan identifikasi suhu permukaan laut, klorofil dan
SSHA pada tiga musim, yaitu musim barat, musim timur
dan musim peralihan. Dari hasil analisis didapatkan Peta
DPI Pelagis Musim Barat, Peta DPI Pelagis Musim Timur,
dan Peta DPI Pelagis Musim Peralihan. Peta-peta tersebut
kemudian divalidasi dengan cara membandingkan dengan
hasil pengukuran jenis dan kelimpahan ikan pelagis di
lapangan. Pengukuran di lapangan dilakukan pada waktu
dan musim yang sama dengan tanggal perekaman citra
penginderaan jauh.
Metode pengukuran jenis dan kelimpahan ikan pelagis di
lapangan sebagai berikut:
1. Pencatatan Data Hasil Tangkapan
85
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Data hasil tangkapan meliputi : komposisi jumlah dan
jenis serta total hasil tangkapan setiap hauling.
Pengambilan data dilakukan dengan cara menimbang
hasil tangkapan ikan dengan menggunakan timbangan
pada setiap kegiatan hauling selesai dilaksanakan.
Penghitungan jumlah tangkapan ikan berasal dari kapal
ikan (jumlah lebih dari satu kapal ikan sejenis dengan
ukuran dan jumlah trip yang sama). Untuk mendapatkan
data yang memiliki waktu yang sama dengan data dari
hasil analisis citra penginderaan jauh dan GIS, maka
data penangkapan ikan dari kapal ikan diambil pada
periode waktu yang sama dengan data penginderaan
jauh/citra satelit dan data GIS. Apabila analisis citra
satelit menggunakan data citra satelit multitemporal 5
tahun, maka data hasil tangkapan ikan menggunakan
data pada pariode yang sama. Data dapat diperoleh dari
fishing log book selama 5 tahun.
2. Identifikasi
Hidroakustik
densitas
ikan
menggunakan
Metode
Metode hidroakustik dilakukan untuk memperoleh
informasi tentang obyek di bawah air dengan cara
pemancaran gelombang suara dan mempelajari pantulan
gelombang suara yang dihasilkan. Perangkat akustik
yang digunakan antara lain: echosounder, fish finder,
sonar, dan Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP).
Berdasarkan metode ini, dapat diketahui tingkat densitas
ikan per meter kubik dan dapat diketahui sebarannya
untuk wilayah perairan yang disurvei.
Berdasarkan hasil identifikasi DPI Pelagis menggunakan
pendekatan penginderaan jauh dan hasil pengumpulan
densitas ikan di lapangan, dilakukan validasi dengan
metode sebagai berikut:
86
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.49. Alur Validasi DPI Pelagis berdasarkan
data densitas Ikan di lapangan
Berdasarkan hasil validasi diperoleh Peta Sebaran DPI
Pelagis Musim Barat, Peta Sebaran DPI Pelagis Musim
Timur, dan Peta Sebaran DPI Pelagis Musim Peralihan.
Selanjutnya, untuk mendapatkan titik lokasi fishing
ground pilihan dari berbagai lokasi tersebut perlu
dilakukan analisis:
Jarak titik/area
terdekat
Tumpang susun dengan batas wilayah perencanaan
kabupaten (4 mil)
fishing
ground
ke
pelabuhan
Contoh analisis dapat dilihat pada gambar berikut ini:
87
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Gambar 4.50. Contoh Hasil Analisis Lokasi Fishing
Ground Pilihan
2. Daerah Penangkapan Ikan Demersal
Ikan demersal adalah ikan yang mempunyai kebiasaan
hidup di dasar atau dekat dasar perairan. Contoh ikan
demersal diantaranya: kerapu, baronang, kakap putih,
kakap merah/bambangan, manyung, gerot-gerot, kurisi,
beloso, kuniran, bawal putih, bawal hitam, peperek, layur,
dll.
Delineasi/pemetaan DPI demersal dilakukan dengan
metode analisis GIS dengan pendekatan ekosistem
perairan.
Beberapa parameter yang digunakan yaitu
sebaran dan kualitas terumbu karang, padang lamun,
mangrove, kedalaman perairan, topografi perairan,
kecerahan, perubahan cuaca dan pencemaran.
Analisis kesesuaian untuk daerah penangkapan (fishing
ground) ikan demersal menggunakan 2 pendekatan, yaitu
pendekatan kesesuaian parameter biofisik dan pendekatan
konvensional.
Metode Identifkasi DPI Demersal
Identifkasi Sebaran DPI Demersal
Identifikasi Sebaran DPI Demersal dilakukan dengan
menggunakan kriteria kesesuaian berdasarkan habitat
sumberdaya ikan demersal. Habitat ikan demersal
umumnya berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan keberadaan ekosistem pesisir, antara lain:
ekosistem mangrove (habitat menetap dan habitat
temporer/ruaya pasang surut), ekosistem padang lamun
88
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
(habitat menetap dan habitat temporer/ruaya pasang
surut), dan ekosistem terumbu karang.
Data-data yang dibutuhkan dalam penentuan Identifikasi
Sebaran DPI Demersal dapat dilihat pada tabel di bawah
ini.
Tabel 4.10. Kebutuhan Data Dalam Penentuan
Kesesuaian Parameter Biofisik
N
o
1
Data
Sumber Data
Keterangan
Ekosistem pesisir (terumbu karang, mangrove, padang
lamun)
-
Kondisi
ekosistem Survei
(buruk, sedang, baik lapangan
sangat baik)
Kelimpahan ikan
Keanekaragaman/ke Survei
kayaan jenis ikan lapangan
(ikan target)
Kondisi ekosistem
mempengaruhi
kelimpahan ikan
Survei
lapangan
Kedalaman perairan
Peta bathimetri
Distribusi
ikan
demersal sangat
dibatasi
oleh
kedalaman
karena jenis ikan
demersal hanya
mampu
bertoleransi
terhadap
kedalaman
tertentu sebagai
akibat perbedaan
tekanan air.
Morfologi dasar laut
Peta morfologi
dasar perairan
dan bathimetri
(analisis garis
isodepth)
Persebaran
habitat
ikan
demersal
di
sekitar ekosistem
dengan morfologi
dasar laut landai
lebih
jauh
jangkauannya
dibandingkan
89
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
morfologi dasar
laut
curam
karena
faktor
kedalaman
4
Kecerahan air
Citra satelit
atau survei
lapangan
Mempengaruhi
feeding activity
Pencemaran
Pengukuran
lapangan
Mempengaruhi
distribusi/kehidu
pan ikan
Tabel 4.11. Kriteria Penentuan Daerah Potensi
Perikanan Tangkap Demersal
No
Parameter
Skor
1
Kondisi ekosistem
terumbu karang/ tutupan
karang hidup
Buruk
(<25%
)
Sedang
(2549,9%)
Baik &
sangat
baik
(50%)
Kondisi ekosistem
padang lamun/
penutupan lamun
Miskin
(<29,9
%)
Kurang
Kaya
(30
59,9%)
Kaya
(50%)
Kondisi ekosistem
mangrove/ penutupan
mangrove
Jarang
(<50%
)
Sedang
(5069,9%)
lebat
(70%)
Kelimpahan ikan
Renda
h
Sedang
Tinggi
Kekayaan Jenis
<10
jenis
10 30
jenis
> 30 jenis
Kedalaman perairan (m)
<3
dan
>100
3-5 dan
50-100
5-50
Morfologi dasar perairan
landai
Landai curam
curam
Kecerahan
<5
5-10
> 10
Pencemaran
Ada
Sedikit
Tidak Ada
90
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Sebagai
unit
analisis,
delineasi
DPI
demersal
menggunakan pendekatan ekosistem terumbu karang,
padang lamun dan mangrove. Asumsi yang digunakan
ialah ketiga ekosistem ini merupakan tempat spawning
ground, nursery ground dan feeding ground bagi
berbagai jenis ikan.
Identifkasi Kondisi Sumberdaya Ikan Demersal
Langkah ini ditujukan untuk mengetahui secara lebih
lebih detail kondisi sumberdaya ikan demersal yang
berasosiasi dengan ekosistem yang diamati. Lokasi
survei lapangan ditentukan berdasarkan hasil identifikasi
sebaran DPI demersal. Kondisi sumberdaya ikan
demersal yang diteliti melalui pendekatan ini adalah
jenis, kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dan
dominasi sumberdaya ikan demersal.
Identifikasi kondisi sumberdaya ikan demersal dilakukan
dengan pengamatan langsung oleh penyelam SCUBA
yang mencatat jenis dan jumlah ikan yang berada di
kolom air. Ikan karang yang berada di area terumbu
karang diidentifikasi dan dihitung dengan mengikuti
transek garis sepanjang 30 m. Pencatat berenang di atas
garis transek dan populasi ikan yang disensus adalah
pada luasan 7,5 m samping kiri-kanan dan atas bawah
sepanjang garis transek (Gambar 5.65). Selain
pencatatan data komunitas ikan karang (demersal) untuk
mendukung deskripsi kondisi ekosistem terumbu karang
juga dilakukan perekaman kondisi bawah air dengan
memotret dan mengambil gambar video menggunakan
kamera underwater.
survei pada kolom air di kedalaman 0-30 m
diameter transek sepanjang 15 m
pengambilan gambar benthos sepanjang alur transek
pencatatan data survei ikan
Gambar 4.51. Ilustrasi pengambilan data ikan karang
(diadaptasi dari Brainard dkk, 2014)
Jumlah ikan karang yang disensus disajikan sebagai
kelimpahan ikan karang sedangkan data ikan karang
dianalisa untuk menghitung keanekaragaman (H),
keseragaman (E) dan dominasi (C).
91
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Metode Pengolahan Data Sumberdaya Ikan Demersal
Untuk mendapatkan Peta DPI Demersal dengan identifikasi
sebaran DPI Demersal, dilakukan analisis dengan cara
overlay seluruh parameter sehingga menghasilkan Peta
DPI Demersal.
Untuk mengetahui kondisi sumberdaya ikan demersal,
dilakukan analisis komunitas ikan karang dengan
menggunakan
analisis
kelimpahan
ikan,
indeks
keanekaragaman (H), indeks keseragaman (E), dan indeks
dominansi. Berikut penjelasan masing-masing indeks
komunitas yang dipakai:
Kelimpahan Ikan
Kelimpahan komunitas ikan karang adalah jumlah ikan
karang yang dijumpai pada suatu lokasi pengamatan
persatuan luas transek pengamatan. Kelimpahan ikan
karang dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:
Xi= x 100
A
dimana:
Xi = Kelimpahan ikan ke-i (ind/ha)
ni = Jumlah total ikan pd stasiun pengamatan ke-i
A = Luas transek pengamatan
Indeks Keanekaragaman (H)
Indeks keanekaragaman atau keragaman (H)
menyatakan keadaan populasi organisme secara
matematis agar mempermudah dalam menganalisis
informasi jumlah individu masing-masing bentuk
pertumbuhan/genus ikan dalam suatu komunitas habitat
dasar/ikan. Indeks keragaman yang paling umum
digunakan adalah rumus:
dimana :
H = Indeks keanekaragaman
Pi = Perbandingan proporsi ikan ke i
S = Jumlah ikan karang yang ditemukan
Indeks keanekaragaman digolongkan dalam kriteria
sebagai berikut :
H 2
: Keanekaragaman kecil
2 < H 3 : Keanekaragaman sedang
92
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
H > 3
: Keanekaragaman tinggi
Indeks keseragaman (E)
Indeks keseragaman (E) menggambarkan ukuran jumlah
individu antar spesies dalam suatu komunitas ikan.
Semakin merata penyebaran individu antar spesies maka
keseimbangan ekosistem akan makin meningkat. Rumus
yang digunakan adalah:
dimana :
E
H maks
S
= Indeks keseragaman
= Ln S
= Jumlah ikan karang yang ditemukan
Nilai indeks keseragaman berkisar antara 0 1.
Selanjutnya
nilai indeks keseragaman dikategorikan
sebagai berikut :
0 < E 0.5 : Komunitas tertekan
0.5 < E 0.75
: Komunitas labil
0.75 < E 1 : Komunitas stabil
Semakin kecil indeks keseragaman, semakin kecil pula
keseragaman populasi, hal ini menunjukkan penyebaran
jumlah individu setiap jenis tidak sama sehingga ada
kecenderungan satu jenis biota mendominasi. Semakin
besar nilai keseragaman, menggambarkan jumlah biota
pada masing-masing jenis sama atau tidak jauh beda.
Indeks dominansi (C)
Indeks dominansi berdasarkan jumlah individu jenis ikan
karang digunakan untuk melihat tingkat dominansi
kelompok biota tertentu. Persamaan yang digunakan
adalah indeks dominansi yaitu :
dimana :
C = Indeks dominansi
Pi = Perbandingan proporsi ikan ke i
S = Jumlah ikan karang yang ditemukan
Nilai indeks dominansi berkisar antara 1 0. Semakin
tinggi nilai indeks tersebut, maka akan terlihat suatu
biota mendominasi substrat dasar perairan. Jika nilai
93
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
indeks dominansi (C) mendekati nol, maka hal ini
menunjukkan pada perairan tersebut tidak ada biota
yang mendominasi dan biasanya diikuti oleh nilai
keseragaman (E) yang tinggi. Sebaliknya, jika nilai
indeks dominansi (C) mendekati satu, maka hal ini
menggambarkan pada perairan tersebut ada salah satu
biota yang mendominasi dan biasanya diikuti oleh nilai
keseragaman yang rendah.
Nilai indeks dominansi
dikelompokkan dalam 3 kriteria, yaitu:
0 < C 0.5 : Dominansi rendah
0.5 < C 0.75
: Dominansi sedang
0.75 < C 1
: Dominansi tinggi
G. Dataset Sosial, Ekonomi, dan Budaya
1. Demograf Sosial
Pemetaan demografi dan sosial dimaksudkan untuk
mengetahui kondisi dan komposisi masyarakat di suatu
wilayah secara struktural dan kultural. Data terkait
demografi dan sosial yang dikumpulkan meliputi Populasi
(jumlah,
kepadatan
dan
distribusi
umur),
Trend
pertumbuhan populasi (tingkat kelahiran dan kematian),
Pendidikan, Mata Pencaharian, Agama, Budaya, Lembaga
kemasyarakatan dan hukum adat serta masyarakat
tradisional
Metode Pengumpulan Dataset Demograf dan Sosial
Metode pengumpulan data demografi dan sosial dapat
dilakukan
secara
primer
dan
sekunder.
Pengumpulan/survei data primer dilakukan dengan cara
wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) terhadap
kelompok masyarakat yang dianggap mengetahui informasi
yang diperlukan dan perwakilan masyarakat dari lembaga
lokal, pemuka masyarakat, pemuka agama, dan lainnya.
Pengamatan secara langsung terhadap lingkungan sosial,
hubungan sosial dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat
setempat, juga merupakan upaya yang dapat dilakukan
untuk memperoleh data primer serta memverifikasi (cross
check) informasi dari hasil wawancara dan Focus Group
Discussion (FGD) . Pengumpulan data sekunder dilakukan
dengan cara mengunjungi instansi penyedia data
kependudukan dan sosial seperti Badan Pusat Statistik
(BPS) dan Kantor Kepemerintahan lainnya.
2. Ekonomi Wilayah
Pemetaan ekonomi wilayah bertujuan untuk mengetahui
kondisi
perekonomian
suatu
wilayah.
Kondisi
perekonomian suatu wilayah dapat dilihat dari : 1)
Pendapatan perkapita; 2) Pertumbuhan Pendapatan
perkapita ; 3) Angkatan kerja dan tingkat pengangguran; 4)
94
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
Tenaga kerja di bidang perikanan, pertanian, kehutanan,
dll; 5) Populasi dan kepadatan nelayan; 6) Pendapatan di
sektor perikanan; 7) Produksi perikanan dan sektor-sektor
lain; 8) Potensi pengembangan sumberdaya perikanan dan
kelautan; 9) Jumlah wisatawan; 10) Pendapatan rata-rata
dan pengeluaran per sektor; dan data perekonomian
lainnya.
Metode Pengumpulan Data Ekonomi Wilayah
Metode pengumpulan data Ekonomi Wilayah dilakukan
melalui pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data
sekunder dilakukan dengan cara mengunjungi instansi
penyedia data ekonomi wilayah seperti Badan Pusat
Statistik (BPS) dan Kantor Kepemerintahan lainnya.
H. Dataset Risiko Bencana
Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan
akibat bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu
tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa
terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau
kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
Bencana Pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam atau
karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat
fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa,
harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau
kecil. Bencana yang diakibatkan karena peristiwa alam
seperti tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut
berbahaya, letusan gunung api bawah laut, kenaikan muka
air laut, dan erosi pantai.
Peta Risiko Bencana dan Kajian Risiko Bencana harus disusun
untuk setiap jenis ancaman bencana yang ada pada daerah
kajian. Rumus dasar umum untuk analisis risiko yang
diusulkan dalam 'Pedoman Perencanaan Mitigasi Risiko
Bencana' yang telah disusun oleh Badan Nasional
Penanggulangan Bencana Indonesia (Peraturan Kepala BNPB
Nomor 4 Tahun 2008) adalah sebagai berikut:
dimana:
R : Disaster Risk ; Risiko Bencana
H
: Hazard Threat : Frekuensi (kemungkinan)
bencana tertentu cenderung terjadi dengan
intensitas tertentu pada lokasi tertentu.
V : Vulnerability : Kerugian yang diharapkan (dampak)
di daerah tertentu dalam sebuah kasus bencana
tertentu terjadi dengan intensitas tertentu.
Perhitungan variabel ini biasanya didefinisikan
95
TATA CARA PENYUSUNAN PETA RZWP-3-K
sebagai pajanan (penduduk, aset, dll) dikalikan
sensitivitas untuk intensitas spesifik bencana
C : Adaptive Capacity : Kapasitas yang tersedia di
daerah itu untuk pulih dari bencana tertentu
Metode pengumpulan data, metode analisis data dan
simbolisasi peta mengacu pada Peraturan Kepala BNPB
Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian
Risiko Bencana. Sedangkan untuk penyajian peta risiko
bencana mengikuti Pedoman Pemetaan RZWP-3-K (Keputusan
Dirjen KP3K No 46 Tahun 2013).
96
Anda mungkin juga menyukai
- 6-Pendekatan Dan Metodologi DermagaDokumen10 halaman6-Pendekatan Dan Metodologi DermagaIndra Yuwono100% (2)
- Prosedur (IV) - Sesuai SOP Pemetaan TematikDokumen36 halamanProsedur (IV) - Sesuai SOP Pemetaan TematikRezha Maulana AzharBelum ada peringkat
- Juknis Penyusunan Lahan KritisDokumen23 halamanJuknis Penyusunan Lahan KritisMunajat NursaputraBelum ada peringkat
- Metodologi Air Baku PDFDokumen88 halamanMetodologi Air Baku PDFBenyBelum ada peringkat
- Metode Pemetaan Lahan Kritis Dari Dinas Kehutanan 2 PDFDokumen18 halamanMetode Pemetaan Lahan Kritis Dari Dinas Kehutanan 2 PDFburoco121Belum ada peringkat
- Pengelolaan Data Dan Informasi Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau KecilDokumen17 halamanPengelolaan Data Dan Informasi Untuk Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau KecilPUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)Belum ada peringkat
- Bab 4 Metode Pengambilan DataDokumen4 halamanBab 4 Metode Pengambilan DataMari BelajarBelum ada peringkat
- Pedum RZWP3K ProvinsiDokumen180 halamanPedum RZWP3K ProvinsiAndry Purnama Putra0% (1)
- Rangkuman Ronald D1D122021Dokumen35 halamanRangkuman Ronald D1D122021Fitrahayu FhyBelum ada peringkat
- Lampiran 4 (Outline Laporan RZWP3K) - KabKotaDokumen7 halamanLampiran 4 (Outline Laporan RZWP3K) - KabKotaNontonFilemBelum ada peringkat
- Tata Cara Penyusunan Peta HidrogeologiDokumen10 halamanTata Cara Penyusunan Peta HidrogeologiSaid AtomBelum ada peringkat
- Pemetaan Lahan KritisDokumen17 halamanPemetaan Lahan KritisTio Mahmudiarto100% (1)
- Metodologi Air Baku PDFDokumen88 halamanMetodologi Air Baku PDFWandy SupriadiBelum ada peringkat
- Kontur Muka Air Tanah Jakarta BekasiDokumen16 halamanKontur Muka Air Tanah Jakarta BekasiMartin DarmasetiawanBelum ada peringkat
- Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K ProvinsiDokumen153 halamanPedoman Teknis Penyusunan RZWP3K ProvinsiPUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)100% (1)
- Daftar Isi Prop. SkripsiDokumen9 halamanDaftar Isi Prop. SkripsiRudiny FarabyBelum ada peringkat
- Bab 4 Struktur Penyajian DataDokumen9 halamanBab 4 Struktur Penyajian Dataariefbudhy0% (1)
- Tugas Survei TanahDokumen20 halamanTugas Survei TanahramotnakbatakBelum ada peringkat
- Kerangka Acuan Kerja Disusun Oleh AaDokumen8 halamanKerangka Acuan Kerja Disusun Oleh AaFuad HasanBelum ada peringkat
- Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kab:KotaDokumen155 halamanPedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kab:KotaPUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)Belum ada peringkat
- Cara Buat DAS Pake QGIS Dan GRASSDokumen8 halamanCara Buat DAS Pake QGIS Dan GRASSLintang GalihsukmaBelum ada peringkat
- Uas Mp3kt-Jefrianus BriaDokumen7 halamanUas Mp3kt-Jefrianus Briananaklau06Belum ada peringkat
- Uas Mp3kt-Wilhelmina Terik KlauDokumen7 halamanUas Mp3kt-Wilhelmina Terik Klaunanaklau06Belum ada peringkat
- Edaran & Pedoman Dikplhd 2019Dokumen80 halamanEdaran & Pedoman Dikplhd 2019yuniaalfiantiBelum ada peringkat
- Uas Mp3kt-Yohanes Kenedi NahakDokumen7 halamanUas Mp3kt-Yohanes Kenedi Nahaknanaklau06Belum ada peringkat
- Tata Cara Rekomendasi BIG Pada Lampiran Peta RDTRDokumen33 halamanTata Cara Rekomendasi BIG Pada Lampiran Peta RDTRhendytamara50% (2)
- Pemetaan TambakDokumen9 halamanPemetaan TambakUpik Upiko Fitra SalehBelum ada peringkat
- SurveiDokumen8 halamanSurveiDio Alif UlamaBelum ada peringkat
- Metode Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah (NSASD) (Bagian I)Dokumen4 halamanMetode Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Spasial Daerah (NSASD) (Bagian I)YusrialdiBelum ada peringkat
- Direktur Jenderal Kelautan Pesisir Dan Pulau-Pulau KecilDokumen155 halamanDirektur Jenderal Kelautan Pesisir Dan Pulau-Pulau KecilGuido PareraBelum ada peringkat
- 6.mmbuat Laporan PekerjaanDokumen23 halaman6.mmbuat Laporan PekerjaanRahayu Rahayu MasqurotinBelum ada peringkat
- Kak Inventarisasi Potensi SdaDokumen19 halamanKak Inventarisasi Potensi Sdajherwindo895Belum ada peringkat
- Bab Iv Metodologi Pelaksanaan KegiatanDokumen19 halamanBab Iv Metodologi Pelaksanaan Kegiatanrickyjon1988Belum ada peringkat
- KAK Pemutakhiran Peta LPI 50k PDFDokumen12 halamanKAK Pemutakhiran Peta LPI 50k PDFDudin UngkulBelum ada peringkat
- Kerangka Acuan Kerja Survei Dan Pemetaan Topografi Daerah Jakarta-1Dokumen14 halamanKerangka Acuan Kerja Survei Dan Pemetaan Topografi Daerah Jakarta-1kangparjoBelum ada peringkat
- E. Pendekatan Dan MetodologiDokumen27 halamanE. Pendekatan Dan MetodologikinawonaBelum ada peringkat
- Pembuatan Peta HidrogeologiDokumen10 halamanPembuatan Peta HidrogeologiErnis LukmanBelum ada peringkat
- PERTEMUAN 02 - Kartografi Peta DigitalDokumen13 halamanPERTEMUAN 02 - Kartografi Peta DigitalgeodesiBelum ada peringkat
- Peta Tematik Rawan Banjir PDFDokumen8 halamanPeta Tematik Rawan Banjir PDFInsan PrasastiBelum ada peringkat
- GIS Pulau WetarDokumen49 halamanGIS Pulau WetarIrham FarhanBelum ada peringkat
- KarakteristikjragungtuntangDokumen40 halamanKarakteristikjragungtuntangononiha26100% (1)
- Kompilasi PetaDokumen25 halamanKompilasi PetaPambudiSusilaBelum ada peringkat
- Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi PDFDokumen153 halamanPedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Provinsi PDFDenny Karwur100% (1)
- Asistensi Peta Rencana RinciDokumen16 halamanAsistensi Peta Rencana RinciAde Irawan0% (1)
- 01 Proposal Peta-Dasar 1-5000Dokumen9 halaman01 Proposal Peta-Dasar 1-5000Satria KegelapanBelum ada peringkat
- Lampiran II. Juknis Perencanaan SPAM-212-253Dokumen42 halamanLampiran II. Juknis Perencanaan SPAM-212-253Way IndahBelum ada peringkat
- KAK Rancangan Teknis Satuan PermukimanDokumen45 halamanKAK Rancangan Teknis Satuan Permukimanyoesz75% (4)
- Format LaporanDokumen13 halamanFormat LaporanAbinya AlfatihBelum ada peringkat
- Modul Standar Teknis Peta RDTRDokumen42 halamanModul Standar Teknis Peta RDTREddie Syamsir67% (3)
- Format Laporan Galifu 2014Dokumen7 halamanFormat Laporan Galifu 2014Agung 'keluarga' KusumaBelum ada peringkat
- KAK Database DAS Di Kab. NiasDokumen9 halamanKAK Database DAS Di Kab. NiasArdiyanto Prawira AcehBelum ada peringkat
- Pedoman Penyusunan DIKPLHD Update..Dokumen10 halamanPedoman Penyusunan DIKPLHD Update..Mardiana Muhamad100% (1)
- Perencanaan Survei Tanah Dan Evaluasi LahanDokumen17 halamanPerencanaan Survei Tanah Dan Evaluasi LahanEko Gesang WahyudiBelum ada peringkat
- Sig Terhadap Pulau Pulau KecilDokumen10 halamanSig Terhadap Pulau Pulau Kecillindaapril939Belum ada peringkat
- Buku Pedoman Geoportal KSP v2Dokumen32 halamanBuku Pedoman Geoportal KSP v2Evan GunawanBelum ada peringkat
- Rencana Survey Dan Investigasi Design Talud PantaiDokumen66 halamanRencana Survey Dan Investigasi Design Talud PantaiAditya GunarsaBelum ada peringkat
- KAK Dan BOQ SID Pengembangan DIR Kab Tanjung Jabung Timur Berbasis KHR Tahap 1Dokumen46 halamanKAK Dan BOQ SID Pengembangan DIR Kab Tanjung Jabung Timur Berbasis KHR Tahap 1Heru GunawanBelum ada peringkat
- Ikan PasirDokumen9 halamanIkan PasirHalili KendariBelum ada peringkat
- Bab II Batasan IstilahDokumen4 halamanBab II Batasan IstilahHalili KendariBelum ada peringkat
- Buku Filsafat Ilmu 1 Ok PDFDokumen35 halamanBuku Filsafat Ilmu 1 Ok PDFSastri Dwisarini100% (2)
- LKS Asam BasaDokumen3 halamanLKS Asam BasaHalili KendariBelum ada peringkat
- Pedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kab KotaDokumen155 halamanPedoman Teknis Penyusunan RZWP3K Kab KotaikbalBelum ada peringkat
- Analisis Kelayakan Usaha Pengolahan Kerupuk Perusahaan Kerupuk Cap Dua Gajah PDFDokumen147 halamanAnalisis Kelayakan Usaha Pengolahan Kerupuk Perusahaan Kerupuk Cap Dua Gajah PDFHalili KendariBelum ada peringkat