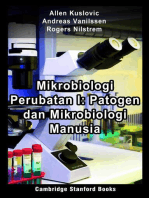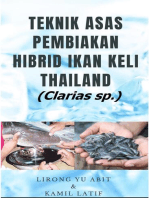Teori Dasar Percobaan 1
Teori Dasar Percobaan 1
Diunggah oleh
WatuJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Teori Dasar Percobaan 1
Teori Dasar Percobaan 1
Diunggah oleh
WatuHak Cipta:
Format Tersedia
TEORI DASAR
Penelitian farmakokinetik melibatkan penentuan kadar obat dalam sampel
biologis. Metode analisis yang digunakan untuk penentuan kuantitatif kadar obat dalam
suatu sampel biologis merupakan hal yang sangat penting dalam evaluasi dan interpretasi
data farmakokinetika. Berbagai sampel biologis dapat diambil untuk penentuan kadar
dalam tubuh untuk penelitian farmakokinetik, sebagai contoh darah, urine, feses, saliva,
jaringan tubuh, cairan blister, cairan spinal dan cairan synovial (Munson, 1991 : halaman
73).
Penentuan kadar suatu obat dalam sampel biologis merupakan hal yang
kompleks disebabkan sampel biologis pada umumnya merupakan suatu matriks yang
kompleks. Jika suatu obat atau metabolitnya dalam sampel biologis dapat dianalisa
langsung tanpa perlu dilakukan perlakuan awal terhadap sampel yang diperoleh maupun
pemisahan obat atau metabolit yang ditentukan maka hal ini merupakan suatu hal yang
menguntungkan. Akan tetapi perlakuan awal sampel maupun isolasi obat atau metabolit
yang akan ditentukan dari matriks biologis yang diperoleh harus dilakukan (Day &
Underwood, 2002 : halaman 223).
Hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan perlakuan awal sampel
maupun metode untuk memisahkan atau mengisolasi obat dan atau metabolitnya adalah
tahapan dari prosedur yang dipilih harus seminimal mungkin untuk menghindari
kehilangan obat dari obat atau metabolit yang akan ditentukan. Semakin panjang tahapan
prosedur untuk perlakuan awal maupun untuk memisahkan atau mengisolasi obat atau
metabolitnya makin besar kemungkinan hilangnya obat atau metabolit yang akan
ditentukan sepanjang prosedur yang dilakukan (Holford, 1998 : halaman 36).
Darah merupakan sampel biologis yang paling umum digunakan dan
mengandung berbagai komponen seluler seperti sel darah merah, sel darah putih, platelet,
dan berbagai protein seperti albumin dan globulin. Pada umumnya bukan darah utuh
(whole blood) tetapi plasma ataupun serum yang digunakan untuk penentuan kadar obat.
Serum diperoleh dengan membiarkan darah untuk menggumpal dan supernatant yang
dikumpulkan setelah sentrifugasi. Sedangkan plasma diperoleh dengan penambahan
antikoagulan pada darah yang diambil dan supernatant yang diperoleh setelah
sentrifugasi. Jadi, plasma dan serum dibedakan dari protein yang dikandungnya
(Katzung, B. 1998 : halaman 40)
Adapun kandungan protein dalam sampel biologis yang akan dianalisa
menyebabkan dibutuhkannya suatu tahap perlakuan awal dan atau penyiapan sampel
sebelum penentuan kadar obat dapat dilakukan. Hal ini untuk mengisolasi atau
memisahkan obat yang akan diteliti dari matriks sampel yang diperoleh. Protein, lemak,
garam dan senyawa endogen dalam sampel akan mengganggu penentuan kadar obat yang
bersangkutan dan selain itu dalam hal analisa menggunakan metode seperti HPLC adanya
zat-zat tersebut dapat merusak kolom HPLC sehingga usia kolom menjadi lebih singkat
(Neal, 2006 : halaman 70-71).
Berbagai prosedur untuk mendenaturasi protein dapat digunakan sebagai
perlakuan awal sampel biologis yang diperoleh dari suatu penelitian farmakokinetik,
meliputi penggunaan senyawa yang disebut sebagai zat pengendap protein (protein
precipitating agent) seperti asam tungstat, amonium sulfat, asam trikoroasetat (tricloro
acetic acid, TCA) asam perklorat, methanol dan asetonitril. Pengendapan protein
dilakukan dengan denaturasi protein. Denaturasi dapat dilakukan akibat adanya
perubahan pH, temperature, dan penambahan senyawa kimia. Cara denaturasi protein
yang umum digunakan adalah dengan penambahan precipitating agent. Protein dapat
diendapkan karena memiliki berbagai sifat diantaranya bersifat sebagai amfoter yakni
memiliki 2 muatan yang berlainan dalam 1 molekul, atau yang dikenal juga sebagai
zwitter ion. Sifat ini membuat potein memiliki muatan yang berbeda pada pH yang
berbeda pula. Akibatnya protein dapat larut pada rentang pH tertentu dimana protein
bermuatan. Suatu saat di pH tertentu protein akan mencapai titik isoelektrik, yakni pH
dimana jumlah total muatan protein sama dengan nol (muatan positif sebanding dengan
muatan negatif), hal ini akan mempengaruhi kelarutan protein. Pada titik isoelektrik,
kelarutan protein sangat rendah, sehingga potein dapat mengendap (Setiawati, 2005 :
halaman 811-812).
Selain itu, protein juga dapat membentuk ikatan dengan logam dimana
beberapa asam amino dapat terikat pada satu logam sehingga molekulnya menjadi besar,
beratnya juga menjadi besar sehingga potein mengendap. Selain itu terdapat juga
beberapa sifa lain yang berhubungan dengan presipitasi protein ini yang dijelaskan pada
mekanisme pengendapan oleh masing-masing reagen (Setiawati, 2005 : halaman 812).
Penggunaan pelarut organik seperti methanol dan asetonitril sebagai zat
pengendap protein sangat umum digunakan. Pengendapan ini berkaitan dengan pI
protein, dimana semakin jauh dari titik isoelektrik maka kelarutan akan semakin
meningkat dan semakin dekat dengan titik isoelektrik maka kelarutan akan semakin
menurun. Penambahan larutan organik seperti metanol ataupun asetonitril pada larutan
protein dalam air akan menurunkan Kd (Konstanta Dielektrik) pelarut/air yang
meningkatkan tarikan antara molekul-molekul bermuatan dan memfasilitasi interaksi
elektrostatik protein. Selain itu pelarut organik ini juga akan menggantikan beberapa
molekul air di sekitar daerah hidrofob dari permukaan protein yang berasosiasi dengan
protein sehingga menurunkan konsentrasi air dalam larutan dengan demikian kelarutan
protein akan menurun dan memungkinkan terjadinya pengendapan. Penggunaan
methanol dan asetonitril mempunyai suatu keuntungan karena kompabilitasnya dengan
berbagai eluen yang digunakan dalam metode HPLC (Putra, 2007 : halaman 81).
Metode isolasi atau pemisahan obat yang banyak digunakan dalam
penelitian farmakokinetik adalah ekstraksi padat-cair (solid-phase extraction) dan
ekstraksi cair-cair. Ekstraksi padat-cair menggunakan cartridge khusus untuk
memisahkan obat dari sampel dengan volume relatif lebih kecil (0.5-1mL) yang tersedia
secara komersial dengan harga yang cukup mahal. Ekstraksi cair-cair merupakan suatu
metode yang paling banyak digunakan karena relatif cepat,simpel, dan murah
dibandingkan dengan ekstraksi padat-cair. Baik metode ekstraksi cair-cair maupun padat-
cair pada umumnya diikuti dengan proses pemekatan obat yang akan dianalisa. Pemilihan
pelarut pengekstraksi dalam ekstraksi cair-cair harus didasarkan pada sifat fitokimia obat
maupun metabolit yang akan diisolasi. Berbagai faktor dapat menjadi pertimbangan
dalam seleksi pelarut yang akan digunakan antara lain:
Tidak bercampur dengan air
Mempunyai kemampuan melarutkan obat yang diinginkan dalam jumlah yang
besar sehingga memberikan nilai recovery yang besar.
Mempunyai titik didih yang relatif rendah sehingga waktu evaporasi pelarut dapat
lebih singkat.
Sedapat mungkin volume yang digunakan untuk ekstraksi adalah minimal
sehingga akan menekan biaya yang dikeluarkan.
Jika memungkinkan gunakan pelarut dengan berat jenis yang lebih kecil dari berat
jenis air sehingga proses pemisahan pelarut organik akan lebih mudah karena pelarut
organik akan berada pada lapisan atas.
(Botsoglou & Fletouris, 2001: halaman 582-583).
Keberhasilan suatu ekstraksi ditandai dengan nilai perolehan kembali yang
mendekati 100%. Berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mendapatkan perolehan
kembali yang sempurna, seperti penggunaan volume pelarut pengekstraksi dalam jumlah
yang besar, ekstraksi berulang (repeat extraction) atau ekstraksi bertahap (multistep
extraction). Pada ekstraksi berulang sampel yang sama diekstraksi beberapa kali
menggunakan pelarut baru sampai seluruh obat terekstraksi. Sedangkan pada ekstraksi
bertahap dilakukan beberapa tahap ekstraksi menggunakan pelarut dengan pH yang
berbeda. Akan tetapi 100% perolehan kembali pada umumnya tidak dapat diperoleh
sehingga perlu ditentukan perolehan kembali yang optimal dengan mempertimbangkan
jumlah obat telah cukup terekstraksi untuk memenuhi sensitifitas analisa, jumlah pelarut
yang digunakan berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan dan juga waktu untuk
melakukan keseluruhan proses ekstraksi termasuk evaporasi pelarut organik yang
diperoleh. Perolehan kembali obat dari matriks biologis sampai serendah 50% masih
dapat diterima dengan catatan parameter lain seperti sensitifitas, presisi, akurasi dan
selektifitas memenuhi standar umum yang berlaku (Shargel, L. 2005 : halaman 167).
DAFTAR PUSTAKA
Botsoglou, N.A. dan Fletouris, D.J. 2001. Drug Residues in Foods pharmacology,
Food Safety, and Analysis. New York: Marcel Dekker. Halaman 582-583
Day, R.A&Underwood, A.L. 2002. Analisis Kuantitatif Edisi Keenam. Jakarta :
Erlangga. Halaman 223
Holford, N.H. 1998. Farmakokinetik dan farmakodinamik : Pemilihan Dosis yang
Rasional dan waktu Kerja Obat. Farmakologi Dasar dan Klinik. Edisi VI. Jakarta.
Halaman 36
Katzung, B. 1998. Farmakologi dasar dan klinik. Edisi VI. Jakarta. Halaman 40
Munson, J.W. 1991. Analisis Farmasi. Surabaya: Universitas Air Langga. Halaman
73
Neal, M .J. 2006. Farmakologi Medis. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Erlangga
Halaman. 70-71.
Putra, E. 2007. Dasar-dasar Kromatografi Gas dan Kromatografi Cair Kinerja.
Tinggi. Medan : Fakultas Farmasi USU. Halaman 81
Setiawati, A. 2005. Farmakokinetik Klinik. Farmakologi dan Terapi. Edisi 4.
Jakarta : Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Halaman.
811-812.
Shargel, L. 2005. Biofarmasetika dan Farmakokinetika Terapan.Edisi Kedua.
Surabaya : Airlangga University Press. Halaman 167.
Anda mungkin juga menyukai
- Pengendapan Protein PlasmaDokumen9 halamanPengendapan Protein PlasmaRegita Ayu LestariBelum ada peringkat
- Farmakologi Eksperimental: Analisis Obat Dalam Cairan HayatiDokumen41 halamanFarmakologi Eksperimental: Analisis Obat Dalam Cairan HayatiNaisbitt Iman Hanif67% (3)
- Laporan Farmakokinetik PDFDokumen25 halamanLaporan Farmakokinetik PDFNaida RahmaBelum ada peringkat
- Modul IDokumen21 halamanModul IShifa FadillahBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Biofarmasetika Dan FarmakokinetikaDokumen26 halamanLaporan Praktikum Biofarmasetika Dan FarmakokinetikaDuta Nugraha Febrianto S1 - 2019Belum ada peringkat
- BIOANALISISDokumen16 halamanBIOANALISISfitri antiniBelum ada peringkat
- Farmakologi Eksperimental Analisis Obat Dalam Cairan HayatiDokumen34 halamanFarmakologi Eksperimental Analisis Obat Dalam Cairan HayatisisrinovritaBelum ada peringkat
- I. Tujuan PercobaanDokumen13 halamanI. Tujuan PercobaanhayyatBelum ada peringkat
- Arava Putri Fadhila-Mutiara Septiani-s1-Vb-Analisis Obat Dalam Matrik Biologi Bf-1801062Dokumen18 halamanArava Putri Fadhila-Mutiara Septiani-s1-Vb-Analisis Obat Dalam Matrik Biologi Bf-1801062Mutiara Septiani50% (2)
- MAI Modul 6Dokumen19 halamanMAI Modul 6Anisa Ashfahany100% (2)
- Analisis Parasetamol Dalam Cairan HayatiDokumen14 halamanAnalisis Parasetamol Dalam Cairan HayatifmansurohBelum ada peringkat
- Modul 1 Pengembangan Metode Analisis Obat Dalam Sampel Biologis (Limit of Detection, Limit of Quantification, Linieritas)Dokumen5 halamanModul 1 Pengembangan Metode Analisis Obat Dalam Sampel Biologis (Limit of Detection, Limit of Quantification, Linieritas)RasyidBelum ada peringkat
- Preparasi SampelDokumen25 halamanPreparasi SampelPharmChem Lab FFUHBelum ada peringkat
- PJ Kel9 BioanalisisDokumen19 halamanPJ Kel9 BioanalisisSyaharani SaraBelum ada peringkat
- WidiDokumen6 halamanWidiNabil DivapBelum ada peringkat
- Biologis A2Dokumen19 halamanBiologis A2Didit PrasetyaningsihBelum ada peringkat
- L Analisis Obat Dalam Cairan HayatiDokumen33 halamanL Analisis Obat Dalam Cairan Hayatiritha widyaBelum ada peringkat
- Dasar Teori BiotekDokumen4 halamanDasar Teori BiotekNisa AnnisaaBelum ada peringkat
- Analisis Obat Dalam Cairan HayatiDokumen5 halamanAnalisis Obat Dalam Cairan HayatiWiwik SetiawatiBelum ada peringkat
- CBR Kel9 BioanalisisDokumen11 halamanCBR Kel9 BioanalisisSyaharani SaraBelum ada peringkat
- Uji DisolusiDokumen6 halamanUji DisolusiAyyu Thrye SartheeqaaBelum ada peringkat
- Chenia Nandini T.metohanDokumen19 halamanChenia Nandini T.metohan2OO11O39 Chenia NandiniBelum ada peringkat
- Data UrinDokumen9 halamanData UrinDyah Putri Ayu DinastyarBelum ada peringkat
- Putriana Dewi - 11181171 - 4fa4 - Laporan Farmakokinetik Modul 1Dokumen21 halamanPutriana Dewi - 11181171 - 4fa4 - Laporan Farmakokinetik Modul 1Putriana DewiBelum ada peringkat
- Laporan BFFK Presipitasi Protein FIXDokumen10 halamanLaporan BFFK Presipitasi Protein FIXZakiya Kamila Muhamad100% (1)
- Analisis Obat Dalam Cairan HayatiDokumen2 halamanAnalisis Obat Dalam Cairan HayatiSyalzabila ImaningtyasBelum ada peringkat
- DASAR TEORI Laprak 34 - Blok FarkinDokumen6 halamanDASAR TEORI Laprak 34 - Blok FarkinReynand ThoriqBelum ada peringkat
- Praktikum Fareks P2Dokumen8 halamanPraktikum Fareks P2Hanifah NurrahmawatiBelum ada peringkat
- Analisis Paracetamol Dalam Urin IDokumen12 halamanAnalisis Paracetamol Dalam Urin IHikmah Setiawan75% (4)
- Tugas Paper BioanalisisDokumen10 halamanTugas Paper BioanalisisRakenityaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Biofarmasetika Dan Farmakokinetika Analisis Obat Dalam Matrik BiologiDokumen22 halamanLaporan Praktikum Biofarmasetika Dan Farmakokinetika Analisis Obat Dalam Matrik BiologiDuta Nugraha Febrianto S1 - 2019Belum ada peringkat
- FITO PARTISI JAGER FixxDokumen21 halamanFITO PARTISI JAGER Fixxdilla daniahBelum ada peringkat
- Laporan Analisis Parasetamol Dalam Cairan Hayati Kelompok 1ADokumen30 halamanLaporan Analisis Parasetamol Dalam Cairan Hayati Kelompok 1AAri DewiyantiBelum ada peringkat
- Prak Biofar 1Dokumen24 halamanPrak Biofar 1shulfa firlianiBelum ada peringkat
- Laporan Akhir p5 FarkindasDokumen19 halamanLaporan Akhir p5 FarkindasAlimWijaya75% (8)
- Analisis Dalam Matriks BiologisDokumen17 halamanAnalisis Dalam Matriks BiologisN0e 10Belum ada peringkat
- Laporan PraktikumDokumen24 halamanLaporan Praktikumahmad baharudinBelum ada peringkat
- PapaverineDokumen20 halamanPapaverineFiqrah LestariBelum ada peringkat
- Landasan TeoriDokumen18 halamanLandasan Teori12scorpi0% (1)
- Modul 4 Uji Disolusi (Teori Dasar)Dokumen5 halamanModul 4 Uji Disolusi (Teori Dasar)Eky SeptianBelum ada peringkat
- Acc Percobaan 1 Dan 3 Samaal Mallisa 18160 Kelas BDokumen31 halamanAcc Percobaan 1 Dan 3 Samaal Mallisa 18160 Kelas BSamal MallisaBelum ada peringkat
- DISOLUSIDokumen23 halamanDISOLUSIvia annisa gani nurfirdaBelum ada peringkat
- C Dan D - Tugas TatianaDokumen21 halamanC Dan D - Tugas TatianaTatiana Siska WardaniBelum ada peringkat
- Prak Biofar - IX - B - Dwi Melinia - 08061281823036 (Akhir)Dokumen29 halamanPrak Biofar - IX - B - Dwi Melinia - 08061281823036 (Akhir)Dwi MeliniaBelum ada peringkat
- Modul Praktikum Farmakokinetika-2019Dokumen43 halamanModul Praktikum Farmakokinetika-2019Dea Salsa NabilaBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 1 (Basic Concepts of Drug Action)Dokumen10 halamanMakalah Kelompok 1 (Basic Concepts of Drug Action)Desy Ratna Sari Nainggolan100% (1)
- Ts. Obat TradisionalDokumen34 halamanTs. Obat TradisionalmuhalaminBelum ada peringkat
- KLTDokumen22 halamanKLTSepel LongstickBelum ada peringkat
- EkstraksiDokumen16 halamanEkstraksiMarina FitrianiBelum ada peringkat
- Perjalanan Obat Dalam Tubuh - PENDAHULUANDokumen16 halamanPerjalanan Obat Dalam Tubuh - PENDAHULUANAyu Devi YantiBelum ada peringkat
- Soal Ujian Kimia Bahan AlamDokumen4 halamanSoal Ujian Kimia Bahan AlamAli Akbar AlayubiBelum ada peringkat
- KromatografiDokumen21 halamanKromatografiFajar SetiawanBelum ada peringkat
- Lapres Biofarmasi P1. Rafika Primadona.1041911117.KDokumen21 halamanLapres Biofarmasi P1. Rafika Primadona.1041911117.KRafika PrimadonaBelum ada peringkat
- Mikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaDari EverandMikrobiologi Medis I: Patogen dan Mikrobioma ManusiaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (11)
- Mikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaDari EverandMikrobiologi Perubatan I: Patogen dan Mikrobiologi ManusiaPenilaian: 2.5 dari 5 bintang2.5/5 (2)
- Teknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Dari EverandTeknik Asas Pembiakan Hibrid Ikan Keli Thailand (Clarias sp.)Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)