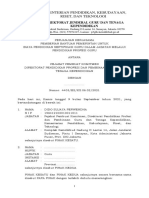Tugas Literasi Nadian Zulfa Divanissa
Diunggah oleh
eko rahardjo0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
13 tayangan10 halamanA
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniA
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
13 tayangan10 halamanTugas Literasi Nadian Zulfa Divanissa
Diunggah oleh
eko rahardjoA
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 10
Nama : Nadian Zulfa Divanissa
Kelas : X IPA 1
No. Absen : 28
MUKENA LUSUH SIMBOK
Riuh suara klakson bus antar kota antar provinsi yang sedang beradu kecepatan memaksaku
menepi. Memilih turun dari sepeda ontel dan menuntunnya melewati jalur berkerikil di
pinggir jalan raya.
Kesal sekali rasanya, melihat tingkah sopir yang ugal-ugalan. Seakan menganggap jalan raya
ini milik mbah buyutnya. Terkadang terlintas di benak, apa mereka itu tak memikirkan
keselamatannya? Bagaimana kalau tiba-tiba mereka mengalami kecelakaan. Apa tak kasihan
dengan keluarganya yang menanti di rumah.
Suara adzan Maghrib sayup-sayup mulai terdengar dari kejauhan. Di bawah sebatang pohon
waru doyong yang tumbuh di pinggir jalan, aku putuskan untuk beristirahat sebentar. Tadi
sebelum berangkat berkeliling, Simbok membekaliku sebotol teh tawar dan sebungkus nasi
aking bertabur kelapa parut.
Lumayan lah, walau tak mewah, kali ini aku bisa berbuka puasa dengan perut kenyang. Tak
seperti kemarin, karena tak ada yang dimakan, terpaksa aku hanya minum air putih. Ya …
beginilah kehidupan kami. Ketika di bulan Ramadhan orang lain bisa makan enak, bebas
memilih makanan yang mereka mau, kami ada yang bisa dimakan saja sudah bersyukur.
Jika mereka berpuasa setahun sekali, kami berpuasa hampir setiap hari. Hari ini bisa makan,
besok puasa, lusa bisa makan, lusanya lagi, puasa. Di satu sisi mereka para orang kaya
membuang-buang makanan, sementara di sini kami para kaum kere mau makan saja sulit.
Huff … kadang hidup ini memang embuh.
Harum aroma nasi aking yang dibungkus daun pisang menggodaku untuk segera
menghabiskan bekalku. Lapar sekali rasanya. Cuaca hari ini sangat terik, apalagi tadi aku
mulai berangkat keliling pas matahari sedang tepat berada di tengah kepala.
Hari mulai gelap, aku harus segera mencari masjid untuk menunaikan sholat Maghrib dan
segera pulang. Perih hati ini melihat tikar-tikar mendong yang teronggok di dalam keranjang.
Dari enam tikar yang kubawa, tak satu pun yang laku. Semakin kesini peminat tikar mendong
semakin berkurang. Zaman sekarang orang-orang lebih memilih menggunakan karpet atau
tikar plastik yang memang lebih awet.
Kembali kukayuh sepeda ontel peninggalan Mbah Kakung, menyusuri jalanan beraspal
dengan hati masygul. Membayangkan wajah sedih Simbok nanti yang melihatku pulang
tanpa membawa uang.
Kutarik nafas dalam-dalam dan membuangnya kasar, mengusir kabut yang mulai
menghalangi pandangan. Aku lelaki, pantang menangis.
Memasuki jalanan kampung, terlihat teman-teman sebayaku hendak berangkat ke masjid.
Sesekali tawa mereka pecah. Saling bercanda, berkejar-kejaran sambil mengibas-ngibaskan
sarung yang mereka bawa.
Kupacu sepeda lebih cepat. Agar bisa segera bergabung dengan mereka. Tak ingin
kulewatkan tarawih kali ini. Tadi, saat di sekolah, Joko temanku bercerita, katanya malam ini
ada seorang dermawan dari kota yang akan memberikan santunan Ramadhan buat kaum
dhuafa di kampung kami.
Semoga saja aku kebagian. Siapa tahu ada amplopnya, bisa kupakai buat membeli sepatu
yang sudah saatnya dimuseumkan saking antiknya. Bayangkan, sejak kapan sepatu ada
jendelanya?
Aku tersenyum sendiri, membayangkan bagaimana teman-temanku suka menggoda. “Ndri,
Sepatumu kui lho, ndang kon leren, melas masuk angin ngko jempolmu.”
Memasuki pelataran rumah, hatiku dirundung cemas. Pintu masih terbuka tapi mengapa gelap
gulita? Ke mana Simbok? Apa sedang pergi?
“Mboook! Simboook!”
“Iya.., apa Le. Sudah pulang kamu?”
Seraut wajah tua muncul dari balik pintu. Lega rasanya, tadi sempat terlintas fikiran-fikiran
buruk. Takut terjadi sesuatu sama Simbok.
Sudah beberapa hari kondisi Simbok kurang sehat. Terus menerus batuk. Kasihan sekali bila
malam, Simbok jadi tidak bisa tidur nyenyak. Sudah kuingatkan agar pergi berobat ke rumah
bidan Marni.
Toh bu bidan itu orang yang baik, beliau jarang mau menerima bayaran dari orang-orang
seperti kami. Tapi tetap Simbok tak mau, mungkin sungkan.
Akhirnya, Simbok hanya minum parutan kencur yang memang banyak tertanam di kebun
belakang rumah, atau sesekali beli obat di warungnya Mbah Mikem.
“Klasane hari ini gak ada yang laku, Mbok,” ujarku, sambil menuntun sepedaku dan
menyandarkannya ke tiang bambu penyangga emper. Tak berani kutatap wajahnya.
“Yo wes, Ndak apa-apa. Besok pasti laku. Sana cepat mandi, nanti telat sholat Tarawihnya.”
Segera kuberlari ke jeding (kamar mandi), mandi seperlunya dan berwudhu. Ketika di ruang
tamu langkahku sempat terhenti melihat apa yang sedang Simbok lakukan. Tapi mengingat
sebentar lagi Iqamat, kutepis tanya di benak. Takut ketinggalan.
Alhamdulillah, benar apa kata Joko, kali ini aku pulang dengan membawa sekantung plastik
bingkisan. Sempat kuintip tadi isinya, sekaleng roti, beras, sirup, gula, teh, minyak goreng
dan beberapa bungkus mie instan.
Ada juga sepucuk amplop yang di rekatkan di tutup kaleng roti. Semoga saja isinya cukup
untuk menambahi celenganku bakal beli sepatu.
Aku pulang dengan hati berbunga-bunga, terbayang besok aku dan simbok, sahur bisa makan
dengan kuah mie instan yang pasti sangat lezat. Esok aku akan langsung ke pasar beli sepatu
baru. Biar jempolku gak masuk angin lagi.
“Assalamualaikum.”
“Wa’alaikum salam. Apa yang kamu bawa itu, Le.”
“Bingkisan. Mbok. Tadi ada orang kaya dari kota yang mbagi-bagiin ini.” Tak sabar, kutaruh
plastik itu di atas meja kayu lalu mengeluarkan isi plastik satu persatu. Tentu saja karena
ingin melihat isi amplop.
“Alhamdulillah, mudah-mudahan rejeki mereka semakin bertambah dan berkah,” sahut
Simbok sambil ikut memegang-megang isi plastik.
“Kok lampune nggak dinyalain, Mbok.”
“Ya embuh, Le. Tadi siang Lik Pangat ke sini, minta setoran listrik. Kan, memang udah dua
bulan kita belum mbayar.”
Aku langsung tanggap, mungkin gara-gara itu maka sengaja Lik Pangat memutuskan aliran
listrik ke rumah kami. Ah tidak, bukan rumah sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya gubuk.
Mana ada rumah hanya berdinding anyaman gedek yang udah pada bolong, dan beratap rapak
(anyaman daun tebu).
Kok ya kebangeten banget Lik Pangat itu. Padahal lampu yang kami pakai hanya satu.
Bohlam kuning yang tergantung di tengah rumah. Itupun dinyalakannya jam enam sore dan
dipadamkan jam enam keesokan harinya, langsung dari rumah Lik Pangat.
“Lik Pangat itu jadi orang kaya kok pelit yo, Mbok.”
“Hush, gak boleh ngomong begitu.”
“Lha itu buktinya, Cuma lampu wae kok dipateni”.
Simbok tampak menarik nafas, sambil tersenyum dia membelai rambutku, “Ya mungkin
kondisinya lagi nggak bagus, Le. Jadi kalau kita nunggak ndak mbayar, dia jadi ngeluarin
uang lebih banyak buat setoran ke PLN”
“Tapi kan, Mbok ….”
“Sst, Wis. Gak usah ngomong wae. Ini bantu Simbok, masukin benang. Dari tadi Simbok
udah nyoba merucut terus.”
‘Ealah Mbok … Mbok, ya gimana mau masuk. Wong pas siang terang benderang saja,
Simbok pasti teriak-teriak kalau mau njahit. Apalagi sekarang malam, hanya ada nyala lampu
senthir.
Kulihat Simbok membentang-bentangkan mukena. Mencari posisi yang robek. Pantas saja,
tadi Simbok tidak ikut berangkat ke Masjid. Wong mukena satu-satunya suwek mbebrek
begitu (sobek parah).
“Suwek lagi ya, Mbok?” tanyaku, sambil mengangsurkan jarum dan benang yang barusan
kutelusupkan. Terlihat sobekan itu memanjang persis di bagian atas kepala.
Lucu sebenarnya, mukena Simbok putih lha kok benangnya berwarna hitam. Tapi mau
gimana lagi, wong adanya cuma itu.
“He eh, kecanthol kawat jemuran tadi, Le.”
Ah Simbok, biarpun aku anak lelaki, aku juga paham, penyebab sobeknya itu bukan karena
kecantol, tapi karena wis amoh (usang lapuk). Bagaimana tidak amoh, usia mukena itu lebih
tua dari umurku.
Sejak aku mudeng, itulah satu-satunya mukena yang Simbok punya. Warnanya menguning.
Di beberapa tempat terlihat tambalan, dan jahitan yang pating njekitut. Belum pernah
sekalipun diganti.
Perih hatiku melihat jemari tua Simbok gemetar saat menjahit. Tentu tidak mudah baginya
menjahit di tengah cahaya lampu yang temaram.
“Besok aja lagi, Mbok. Kalau hari terang.”
“Lha nanti Simbok sholat e piye?”
“Ya, gak usah sholat dulu. Prei. Allah juga maklum.”
“Heh, ra pareng ngomong begitu. Biar gimanapun kondisinya, harus terus menjaga sholat,
Le.”
“Lha kita sholat terus juga ndak sugih-sugih, Mbok. Mau makan aja susah. Kae artis-artis,
orang kaya, pada nggak pernah sholat tapi uripe pada enak.”
Mendengar omonganku yang terus ngeyel, akhirnya Simbok berhenti menjahit. Dengan sabar
mulai menasehati.
“Le.., apapun kondisinya, sesulit apapun hidup kita, sholat harus tetap dijaga. Allah paring
rejeki itu gak semata-mata hanya duit atau kekayaan. Kesehatan, kebahagiaan, ketenangan,
itu juga wujud rejeki. Nggak apa-apa sedikit yang penting berkah, halal, Allah Ridho.
Bayangin apa jadinya kita, udah miskin, gak mau sholat, terus sakit-sakitan. Udah di dunia
uripe rekasa (hidup susah) nanti di akherat plung langsung nyemplung neraka. Kamu mau?”
“Ya emoh, Mbok.”
“Makane, jangan lagi ngomong begitu, Mbok e ndak suka. Sana gek bobok. Besok awas aja
kalau susah dibangunin sahur. Simbok grujuk nanti pake air comberan,” sahutnya sambil
menjewer sayang telingaku.
Setelah salim Simbok, aku pun berlalu menuju bale-bale bambu satu-satunya milik kami di
sudut ruangan. Sebuah ide terlintas di benak. Seulas senyum tersungging di bibirku. Dalam
hati ikut menyenandungkan sholawat Nariyah yang Simbok lantunkan. Hingga perlahan aku
terlelap ke alam mimpi.
Terukir janji dalam hati, aku akan sekolah yang pintar dan setinggi mungkin, kelak harus jadi
orang sukses, akan kubahagiakan Simbok. Akan kutunjukkan pada dunia, jika Simbok tak
pernah salah sudah memungutku dari pinggir kalen (parit) deket sawah sebelas tahun yang
lalu.
Hari ini kujalani hariku dengan penuh semangat. Sepulang sekolah kubobol celengan
bagongku. Simbok tak terlihat. Mungkin sedang membantu Pak Supri, juragan gabah,
menjemur hasil panennya.
Alhamdulillah, uang pecahan dua ribuan dan logam seribuan serta lima ratusan terkumpul
tiga puluh delapan ribu rupiah. Ditambah uang amplop yang semalam kuterima, kira-kira
cukuplah untuk membeli barang yang aku mau.
Kembali kukayuh sepeda butut menyusuri jalanan. Menuju pasar di tengah kota. Semoga di
pasar banyak pembeli yang berminat dengan tikar mendong buatan Simbok. Dengan suara
lantang, kutawarkan barang daganganku.
Sepertinya ini hari keberuntunganku. Benar kata Simbok, Rejeki Allah yang mbagi. Sudah
ditakar sesuai kebutuhan masing-masing hamba-Nya. Daganganku ludes tak bersisa. Simbok
pasti nanti senang sekali. Apalagi akan ada kejutan lain buatnya.
Di depan sebuah toko yang memajang berbagai perlengkapan sholat, aku berhenti. Sepeda
terpaksa aku rubuhkan. Maklum sudah tak ada tiang standardnya. Kulepas sandal jepit usang
yang kukenakan. Sayang, bila lantai keramik yang putih mengkilat itu harus kotor karena
debu dari sendalku.
Di dalam toko aku celingak celinguk. Semua mukena yang digantung sangat indah. Aku tak
berani menyentuhnya.
Kuperhatikan satu persatu. Hingga akhirnya perhatianku tertuju pada mukena putih berbodir
bunga-bunga kecil. Kubayangkan, pasti Simbok akan sangat cantik mengenakan mukena itu.
“Cari apa, Dik?” teguran seorang lelaki berwajah khas timur tengah mengagetkanku.
Postur tubuhnya tinggi gede, dengan cambang lebat di dagu. Sorot matanya tajam. Tiba-tiba
saja rasa takut menyelusup di sudut hati.
“Em … sa … saya mau beli mukena buat Simbok, Pak.”
“O ya, silahkan dipilih, mau beli yang mana?”
“Kalau yang itu berapa, Pak?” tanyaku sambil menunjuk mukena berbodir yang sejak tadi
kuperhatikan.
“Seratus ribu rupiah saja.”
Hatiku mencelos. Seratus ribu? Lha uangku saja tak sampai segitu jumlahnya. Kukeluarkan
uang hasil dagangan. Menimbang-nimbang, tapi segera kumasukkan lagi ke kantong celana.
Ini uang Simbok, aku tak boleh menggunakan semauku tanpa izinnya.
“Yang harganya lebih murah ada nggak, Pak? uang saya Cuma lima puluh delapan ribu.”
Mendengar ucapan polosku, Bapak pemilik toko tersenyum.
“Kamu mau yang ini?”
Aku mengangguk, “Tapi uangnya tidak cukup, Pak. Ini ada uang, tapi uange Mboke. Wis gak
apa-apa yang lebih murah."
“Ayo, ikut Bapak.”
Digandengnya tanganku menuju dalam toko. Sesaat menghilang di balik Etalase lalu muncul
dengan sebuah plastik berisi mukena. Di hadapanku, dibukanya plastik itu dan
membentangkan isinya.
“Kamu mau yang ini kan?”
Mataku berbinar, reflek kusentuh mukena itu yang begitu lembut dan pasti adem bila dipakai
ketika sholat. Tak sadar aku mengangguk.
Si Bapak langsung melipat mukena itu kembali, memasukkannnya ke dalam plastik beserta
satu buah sajadah berwarna hijau bergambar ka’bah.
“Ini buat kamu. Kasihkan ke Simbok ya.”
"Tapi uange ndak cukup ki, Pak. Udah yang lain aja mboten napa-napa."
Tiba-tiba saja, si bapak pemilik toko duduk di depanku. Kini tinggi kami sejajar.
"Kalau mau ngasih orang tua, usahakan yang paling bagus. Biar Allah tambah ridho."
Aku menatapnya tak percaya, berulangkali pandanganku beralih antara plastik berisi mukena
yang dia pegang dan wajahnya.
Si Bapak mengangguk, “Iya, ini buat kamu. Ambillah.”
Bibirku tak sanggup berkata-kata. Rasa Bahagia membuncah di dada. Gemetar rasanya ketika
menerima plastik itu. Ini bukan mimpi kan?
Kuraih tangan kekar lelaki berhati malaikat yang sudah mengabulkan impianku dan
menciumnya takzim. Tak lupa menyerahkan uang receh lima puluh delapan ribu rupiah
milikku. Penuh kasih, dia mengelus rambutku.
“Tetaplah jadi anak yang sholeh. Allah menyertaimu.”
“Maturnuwun, Pak.”
Tanpa menunggu jawabannya aku segera berlalu. Meraih sepeda pancal dan mengayuhnya
secepat mungkin. Tak sabar rasanya untuk segera sampai di rumah.
“Mbok eeeeeeeee! Mukenamu anyaaaarr!”
“Mbok eeeeeeeeee! Mukenamu anyar Mboooook!”
Sepanjang jalan, kalimat itu yang terus kuteriakkan. Tak peduli dengan pandangan orang-
orang yang mungkin menganggapku kurang waras. Kali ini aku sangat bahagia. Lebaran kali
ini Simbok bisa memakai mukena baru untuk sholat Idul Fitri. Senyuman tak henti-hentinya
tersungging di bibirku yang kering.
Namun, ketika sampai di depan rumah. Mulutku tiba-tiba terkunci rapat. Tetangga kanan kiri
menyesaki gubukku yang sempit.
Kali ini Lik Pangat berbaik hati. Tidak hanya satu bohlam lampu yang dia beri, tapi beberapa
hingga rumahku yang biasanya temaram kini terang benderang.
Melihat kedatanganku, mereka menyingkir memberi jalan. Beberapa orang memeluk dan
mengelus kepalaku. Sebagian yang lain memintaku untuk bersabar. Ada apa ini?
Sepedaku kugeletakkan begitu saja. Dengan tentengan plastik yang kubawa, aku segera
masuk rumah. Bale-bale bambu yang biasa kutiduri bersama simbok, kini sudah berpindah ke
tengah ruangan. Di atasnya, membujur jasad Simbokku masih mengenakan mukena kumal
yang semalam dijahitnya.
Aku jatuh bersimpuh di samping bale-bale itu. Menatap wajah ayu simbok yang lebih mirip
orang yang sedang tidur. Tenang, damai, dengan seulas senyum yang tersungging di bibir.
Tak setitikpun air mata mengalir di pipiku. Hanya bibir yang terkunci dan tenggorokan yang
tercekat.
Bude RT maju menghampiri, ikut duduk di sampingku, sambil mengelus pundak, “Nangisa,
Le. Jangan ditahan.”
“Cah lanang ora pareng nangis, Budhe.”
Mendengar jawabanku, tangis Ibu-Ibu tetangga yang hadir di ruangan ini pecah.
Rangkaian prosesi pemakaman Simbok berjalan dengan lancar. Dari memandikan,
mengkafani, menyolatkan hingga mengantarnya ke pemakaman kuikuti tanpa setetes pun air
mata yang mengalir.
Perlahan jenazah Simbok diturunkan ke liang lahat. Sayang, tenagaku masih belum kuat
untuk menyambutnya. Namun ketika mengadzani Simbok, aku meminta pada Pak Ustadz
untuk mengadzaninya sendiri. Aroma harum menguar dari jenazah wanita terkasihku ini.
Semua yang hadir serentak mengucapkan tasbih.
Perlahan tanah merah diturunkan menutupi jasad Simbok hingga akhirnya tak terlihat lagi.
‘Selamat jalan, Mbok. Terimakasih untuk semua yang sudah Simbok berikan untukku.’
Usai sudah semuanya, kini aku, Andri, di usia sebelas tahun harus hidup sebatang kara.
Semampuku, sudah berusaha memenuhi bakti sebagai cucu, untuk mikul dhuwur lan mendem
jero derajate Mbah Kakung dan Simbok, orang tua yang kupunya.
Bagaimana masa depanku nanti? Entahlah. Terserah Allah mau mengarahkannya kemana.
Bukankah terkadang hidup ini memang EMBUH?
Analisis Unsur Intrinsik
a.Tema : Selalu bersyukur.
b. Penokohan :
Andri, memiliki sikap pekerja keras, pantang menyerah, berhati mulia, dan tegar.
1. Kembali kukayuh sepeda menyusuri jalanan. Menuju pasar di tengah kota.
2. Aku lelaki, pantang menangis.
3. Kali ini aku sangat bahagia. Lebaran kali ini simbok bisa memakai mukena
baru untuk sholat idul fitri.
4. “ Cah lanang ora pareng nangis, Budhe”.
Simbok, memliki watak penyabar, penasihat yang baik, dan berhati mulia.
1. “ Yo wes. Ndak apa-apa. Besok pasti laku. Sana cepat mandi, nanti telat sholat
Tarawehnya”.
2. “Le.., apapun kondisinya, sesulit apapun hidup kita, sholat harus tetap dijaga.
Allah paring rejeki itu gak semata-mata hanya duit atau kekayaan. Kesehatan,
kebahagiaan, ketenangan, itu juga wujud rejeki. Nggak apa-apa sedikit yang
penting berkah, halal, Allah Ridho. Bayangin apa jadinya kita, udah miskin,
gak mau sholat, terus sakit-sakitan. Udah di dunia uripe rekasa (hidup susah)
nanti di akherat plung langsung nyemplung neraka. Kamu mau?”
3. “Ya mungkin kondisinya lagi nggak bagus, Le. Jadi kalau kita nunggak ndak
mbayar, dia jadi ngeluarin uang lebih banyak buat setoran ke PLN”
Lik Pangat, mempunyai watak yang baik hati dan mengerti keadaan.
1. Aku langsung tanggap, mungkin gara-gara itu maka sengaja Lik Pangat
memutuskan aliran listrik ke rumah kami.
2. Kali ini Lik Pangat berbaik hati. Tidak hanya satu bohlam lampu yang dia
beri, tapi beberapa hingga rumahku yang biasanya temaram kini terang
benderang.
Penjual Mukena, memiliki sifat yang dermawan dan berhati mulia.
1. Si Bapak langsung melipat mukena itu kembali, memasukkannnya ke dalam
plastik beserta satu buah sajadah berwarna hijau bergambar ka’bah.
2. Si Bapak mengangguk, “Iya, ini buat kamu. Ambillah.”
Budhe RT, mempunyai empati yang tinggi.
1. Budhe RT maju menghampiri, ikut duduk di sampingku, sambil mengelus
pundak, “Nangisa, Le. Jangan ditahan.”
c. Alur : Alur maju.
d. Setting :
Latar tempat : pinggir jalan raya, rumah Simbok, pasar, toko perlengkapan sholat,
pemakaman.
1. Riuh suara klakson bus antar kota antar provinsi yang sedang beradu
kecepatan memaksaku menepi. Memilih turun dari sepeda ontel dan
menuntunnya melewati jalur berkerikil di pinggir jalan raya.
2. Memasuki pelataran rumah, hatiku dirundung cemas.
3. Semoga di pasar banyak pembeli yang berminat dengan tikar mendong buatan
Simbok.
4. Di depan sebuah toko yang memajang berbagai perlengkapan sholat, aku
berhenti.
5. Rangkaian prosesi pemakaman Simbok berjalan dengan lancar. Dari
memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga mengantarnya ke pemakaman
kuikuti tanpa setetes pun air mata yang mengalir.
Latar waktu : sore hari, malam hari.
1. Suara adzan Maghrib sayup-sayup mulai terdengar dari kejauhan.
2. Dalam hati ikut menyenandungkan sholawat Nariyah yang Simbok lantunkan.
Hingga perlahan aku terlelap ke alam mimpi.
Latar suasana : ceria, tegang, sedih.
1. Kali ini aku sangat bahagia. Lebaran kali ini Simbok bisa memakai mukena
baru untuk sholat Idul Fitri. Senyuman tak henti-hentinya tersungging di
bibirku yang kering.
2. Melihat kedatanganku, mereka menyingkir memberi jalan. Beberapa orang
memeluk dan mengelus kepalaku. Sebagian yang lain memintaku untuk
bersabar. Ada apa ini?
3. Mendengar jawabanku, tangis Ibu-Ibu tetangga yang hadir di ruangan ini
pecah.
e. Sudut pandang : Sudut pandang orang pertama.
f. Amanat : seperti apapun keadaan yang sedang kita alami, kita harus tetap bersyukur kepada
Allah. Dan ingat, Allah tidak akan memberi cobaan diluar batas kemampuan hambanya.
Anda mungkin juga menyukai
- Literasi - Cerpen 1Dokumen10 halamanLiterasi - Cerpen 1ARDIAN DWI SYAHPUTRA Hukum Tatanegara (Siyasah)Belum ada peringkat
- WowDokumen31 halamanWowMica Kallio41% (17)
- Mauliza Putri Cerpen Sia-SiaDokumen8 halamanMauliza Putri Cerpen Sia-SiaMauliza PutriBelum ada peringkat
- Kumpulan Cerpen DBPDokumen4 halamanKumpulan Cerpen DBPYusri Zainol AbidinBelum ada peringkat
- Cerpen Baru JadiDokumen5 halamanCerpen Baru JadiDias SofiaBelum ada peringkat
- Adoc - Pub Kupenuhi Janji Cerpen Hayatun ThayyibahDokumen7 halamanAdoc - Pub Kupenuhi Janji Cerpen Hayatun Thayyibahneni lufiasariBelum ada peringkat
- Revisi FelsiDokumen10 halamanRevisi Felsiseniwatiputri1976Belum ada peringkat
- Gsmb-Diara AyuDokumen3 halamanGsmb-Diara AyuZahra MustafidaBelum ada peringkat
- Cerpen YenniDokumen3 halamanCerpen YenniYenni MarsyandasyamBelum ada peringkat
- CERPENDokumen12 halamanCERPENmaheBelum ada peringkat
- Analisis Cerita PendekDokumen9 halamanAnalisis Cerita PendekShandy Ardian mahaputraBelum ada peringkat
- Lukisan Kota TuaDokumen15 halamanLukisan Kota TuaRifki RamadhanBelum ada peringkat
- BALKONDokumen12 halamanBALKONAri Ramadhan SetiawanBelum ada peringkat
- Pengalaman PribadiDokumen15 halamanPengalaman PribadiCalon MayitBelum ada peringkat
- Belanga KeramatDokumen3 halamanBelanga Keramatlitmatch instituteBelum ada peringkat
- Anak DesaDokumen4 halamanAnak DesaQurrotul Aien Fatah YasinBelum ada peringkat
- 2Dokumen4 halaman2khanifBelum ada peringkat
- Flash FictionDokumen5 halamanFlash FictionNajmi FirdaBelum ada peringkat
- NOVEL PERJUANGAN PEDIDIKANKU HafifahDokumen51 halamanNOVEL PERJUANGAN PEDIDIKANKU HafifahIwanSetiawanBelum ada peringkat
- Ketika Teduh Bertemu Terik - Khalda Athia ElzahraDokumen11 halamanKetika Teduh Bertemu Terik - Khalda Athia ElzahraecaBelum ada peringkat
- CerpenDokumen86 halamanCerpenthania luthfyahBelum ada peringkat
- Cerpen Surat Untuk Ayah Iskandar WasidDokumen8 halamanCerpen Surat Untuk Ayah Iskandar WasidMohammad Hasan Ma'arif100% (1)
- Untitled 2Dokumen24 halamanUntitled 2Mukhson AlbarBelum ada peringkat
- KESETIAANDokumen25 halamanKESETIAANLensa Om BibiBelum ada peringkat
- Della Bany Ruliana - CERNAK DAN PUISI UASDokumen8 halamanDella Bany Ruliana - CERNAK DAN PUISI UASDela BanirulianaBelum ada peringkat
- (Ceritaseru) Bibi LintikDokumen15 halaman(Ceritaseru) Bibi LintikDefri Rahman100% (1)
- Cerpen - Semburat Cahaya Gadis Nan Tunggal - Putri Alya Syakira - Smas Ibs Raudhatul Jannah - Kota Payakumbuh - Sumatera BaratDokumen9 halamanCerpen - Semburat Cahaya Gadis Nan Tunggal - Putri Alya Syakira - Smas Ibs Raudhatul Jannah - Kota Payakumbuh - Sumatera Baratseniwatiputri1976Belum ada peringkat
- 001 - Siswandi CeriteDokumen9 halaman001 - Siswandi CeriteSISWANDIBelum ada peringkat
- Cerpen BINDODokumen6 halamanCerpen BINDO22-Serene Widyawati Nissi S.Belum ada peringkat
- Cerpen - Sukacita Lentera Merah - Lolita Wiranda - Kabupaten Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-1Dokumen8 halamanCerpen - Sukacita Lentera Merah - Lolita Wiranda - Kabupaten Bangka - Provinsi Kepulauan Bangka Belitung-1Lolita WirandaBelum ada peringkat
- Seesaw by Sacha Chapter 1 & 2Dokumen54 halamanSeesaw by Sacha Chapter 1 & 2lia ghsnBelum ada peringkat
- Mutiara Air MataDokumen5 halamanMutiara Air MataabdussamadBelum ada peringkat
- P E N Y E S A L-WPS OfficeDokumen13 halamanP E N Y E S A L-WPS OfficeVeronica Samosir100% (1)
- CERPEN - Dia Yang TangguhDokumen6 halamanCERPEN - Dia Yang TangguhInfinite RoomBelum ada peringkat
- Jangan Paksa Aku Untuk MemilihDokumen4 halamanJangan Paksa Aku Untuk MemilihFitri UmmaBelum ada peringkat
- Safna Puspita Sari-Bidadari DuniaDokumen4 halamanSafna Puspita Sari-Bidadari DuniaSafna El lasemyBelum ada peringkat
- Asmaraloka Yang TernodaDokumen6 halamanAsmaraloka Yang TernodaLie SoraBelum ada peringkat
- Cerpen AlifDokumen9 halamanCerpen AlifSiti afifah siregarBelum ada peringkat
- Hubungan Dengan Cewek MisteriusDokumen14 halamanHubungan Dengan Cewek MisteriusCerita Sex Bergairah100% (3)
- Secercah CahayaDokumen5 halamanSecercah CahayaReza MuhtadinBelum ada peringkat
- Mudik Lahir Batin (Subro)Dokumen4 halamanMudik Lahir Batin (Subro)Chandra Ardilla PutraBelum ada peringkat
- CerpenDokumen5 halamanCerpenTeguh FirmansyahBelum ada peringkat
- Adoc - Pub Lentera Kelam Tiga Puluh Februari 20230913 112144Dokumen5 halamanAdoc - Pub Lentera Kelam Tiga Puluh Februari 20230913 112144Muh Rifky Awal Ramadhan [C8]Belum ada peringkat
- Gadis MalangDokumen6 halamanGadis Malangadhari_globalnetBelum ada peringkat
- Antara Hikayat Dan CerpenDokumen11 halamanAntara Hikayat Dan CerpenArizqa SalsabilaBelum ada peringkat
- EYANGDokumen10 halamanEYANGANDI RAHMIBelum ada peringkat
- Cerkak (Jawa)Dokumen17 halamanCerkak (Jawa)AfittBelum ada peringkat
- EYANG (Putu WijayaDokumen6 halamanEYANG (Putu WijayabursidBelum ada peringkat
- CECEPDokumen5 halamanCECEPWiji LestariBelum ada peringkat
- Cerpen LupaDokumen6 halamanCerpen Lupaefrahmaa watiBelum ada peringkat
- Novel ReinaDokumen96 halamanNovel ReinaIwanSetiawanBelum ada peringkat
- Cerpen Tukang Sol SepatuDokumen4 halamanCerpen Tukang Sol SepatuChinta TataBelum ada peringkat
- Amanah Yang Belum Tersampaikan Suci LestariDokumen5 halamanAmanah Yang Belum Tersampaikan Suci Lestariindah alfawardahBelum ada peringkat
- Akar Sebuah Hati CERPENDokumen7 halamanAkar Sebuah Hati CERPENminervagung2024Belum ada peringkat
- BerdikariDokumen4 halamanBerdikarimaulydia.widoBelum ada peringkat
- Sumatif Cerita PendekDokumen8 halamanSumatif Cerita Pendekaltjeliuw75Belum ada peringkat
- Book of Crime Chapter 1Dokumen5 halamanBook of Crime Chapter 1bluray bluray5001Belum ada peringkat
- Ibuku HebatDokumen7 halamanIbuku Hebativan_vanegaBelum ada peringkat
- KKC KK FV - SI 19-16 Wir SDokumen142 halamanKKC KK FV - SI 19-16 Wir SSATRIA WANBelum ada peringkat
- Laporan PKL CV MasterDokumen44 halamanLaporan PKL CV Mastereko rahardjoBelum ada peringkat
- Juknis Ktsp2021-2022 OkDokumen53 halamanJuknis Ktsp2021-2022 OkYenindrawBelum ada peringkat
- Jadwal Informatika Gasal 2021-2022 - 13 September 2021Dokumen3 halamanJadwal Informatika Gasal 2021-2022 - 13 September 2021eko rahardjoBelum ada peringkat
- Laporan Kuliah Kerja Media Desain Dalam Proses Produksi Media Promosi Di Cv. Papan Atas SoloDokumen34 halamanLaporan Kuliah Kerja Media Desain Dalam Proses Produksi Media Promosi Di Cv. Papan Atas SoloMuhammad Faza AdwitiyaBelum ada peringkat
- Daftar Guru Piket Sertifikasi Dan Pejabat Teras FixDokumen2 halamanDaftar Guru Piket Sertifikasi Dan Pejabat Teras Fixeko rahardjoBelum ada peringkat
- Format PKS Dengan Mahasiswa Angkatan 4 Yang Harus Diisi MahasiswaDokumen10 halamanFormat PKS Dengan Mahasiswa Angkatan 4 Yang Harus Diisi MahasiswaSMAN 10 Simbang MarosBelum ada peringkat
- DEVIDokumen1 halamanDEVIeko rahardjoBelum ada peringkat
- Engembang Erumahan & ErmukimanDokumen1 halamanEngembang Erumahan & Ermukimaneko rahardjoBelum ada peringkat
- DEVIDokumen1 halamanDEVIeko rahardjoBelum ada peringkat
- Skema MM Tahun KemarinDokumen1 halamanSkema MM Tahun Kemarineko rahardjoBelum ada peringkat
- Skema MM Tahun KemarinDokumen1 halamanSkema MM Tahun Kemarineko rahardjoBelum ada peringkat
- Engembang Erumahan & ErmukimanDokumen1 halamanEngembang Erumahan & Ermukimaneko rahardjoBelum ada peringkat