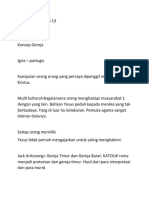Ke Solo Ke Njati
Diunggah oleh
Janri Zheiltor100%(1)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
218 tayangan4 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
100%(1)100% menganggap dokumen ini bermanfaat (1 suara)
218 tayangan4 halamanKe Solo Ke Njati
Diunggah oleh
Janri ZheiltorHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
Ke Solo Ke Njati
Karya : Umar Kayam
Bis jurusan Wonogiri mulai bergerak meninggalkan terminal. Habis sudah
harapannya untuk ikut terangkut. Orang begitu berjejal, berebut masuk. Tidak
mungkin dia akan dapat peluang, betapapun kecil itu, untuk dapat menyeruak
masuk di antara desakan berpuluh manusia yang mau naik. Bawaannya ber-
genteyong-an di pundak dan punggungnya, belum lagi tangannya yang mesti
menggandeng kedua anak-anaknya yang masih kecil.
Kemarin, pada hari Lebaran pertama, dia sudah hampir bisa masuk.
Tangannnya memegang erat-erat anak-anaknya, tangannya sebelah sudah
memegang pinggiran pintu. Tiba-tiba anaknya berteriak mainannya jatuh dan
sekelebat dilihatnya sebuah tangan ingin merenggut tasnya. Dengan sigap
dikibaskannya tangannya menangkis tangan yang ingin menggapai tasnya, dan
dengan kegesitan yang sama tangannya yang sebelah melepaskan pegangan anak-
anaknya untuk memungut mainan anaknya yang jatuh di tanah. Bersamaan
dengan itu orang-orang di belakangnya mendapat kesempatan untuk menyisihkan
dia dan anak-anaknya terlempar ke pinggir. Kalau kernet bis yang berdiri di
dekatnya tidak sigap menahan tubuhnya, pastilah dia dan anak-anaknya sudah
tercampak di tanah.
Anak-anaknya pada menangis dan ia pun segera minggir mencari tempat
yang agak sela. Anak-anaknya berhenti menangis sesudah dibelikan teh kotak dan
sebungkus kerupuk chiki. Ditariknya napas panjang di pinggir warung itu.
Dipandangnya bis yang masih berdiri dengan teguhnya diguncang-guncang orang
yang pada mau mudik.
“Bu, kita jadi mudik ke Njati, ya, Bu?” anaknya yang besar, yang berumur
enam tahun, bertanya.
“Wah, nampaknya susah, Ti. Lihat tuh penuhnya orang.”
“Kita nggak jadi mudik, ya, Bu.”
“Besok kita coba lagi,ya?”
Itulah keputusannya kemarin. Anak-anaknya pada menggerutu dan mau
menangis.
“Sekarang kita mau ke mana, Bu?”
“Ya, pulang, Ti.”
*
Pulang. Itu berarti pulang ke kamar sewaan yang terselip di tengah
kampung yang agak kumuh di bilangan Kali Malang. Anak-anaknya yang sudah
lelah menurut saja digandeng ibunya dan kemudian didorong masuk ke sebuah
bajaj yang pada sore hari itu memungut biaya entah beberapa kali lipat daripada
biasa. Anaknya yang kecil langsung tertidur begitu bajaj bergerak. Anaknya yang
besar diam, entah membayangkan atau memikirkan apa.
Pagi-pagi, sebelum mereka bersiap untuk pergi ke terminal pada sore hari,
dibawanya anak-anaknya ke makam suaminya, di kuburan yang terletak tidak jauh
dari kampung tempat dia tinggal. Suaminya, yang semasa hidup adalah buruh
bangunan pada sebuah perusahaan pemborong, meninggal kira-kira tiga tahun
yang lalu. Dia meninggal tertimpa dinding yang roboh. Untunglah perusahaan
cukup baik hati dan mau mengurus pemakamannya dan memberi santunan
sekadarnya.
Tetapi, sesudah itu, hidup terasa lebih berat dan getir. Pendapatannya
sebagai pembantu di rumah kompleks perumahan itu mepet sekali untuk
mengongkosi hidup mereka. Apalagi Ti, anak sulungnya itu, sudah harus sekolah.
Hari demi hari dijalaninya dengan kedatangan dan kebosanan, tetapi, entah
bagaimana, dia sanggup juga mengikutinya. Tahu-tahu, ajaib juga, tabungannya
yang dikumpulkannya dari sisa dan persenan dari sana-sini terkumpul agak
banyak juga selama tiga tahun itu. Kemudian terpikirlah untuk pulang mudik ke
Njati tahun ini. Anak-anaknya belum pernah kenal Njati dan embah-embahnya
serta sanak saudaranya yang lain. Sudah waktunya mereka kenal dengan mereka,
pikirnya. Juga desa mungkin akan memberikan suasana yang lebih
menyenangkan, pikirnya lagi. Setidaknya lain dengan tempat tinggalnya yang
sumpek di Jakarta. Maka diputuskannyalah untuk nekat pulang Lebaran tahun ini.
“Mbok kamu jangan pulang Lebaran. Tahun ini anak-anak saya pada
kumpul di sini. Banyak kerjaan.”
“Wah, nuwun sewu, Bu. Saya sudah terlanjur janji anak-anak.”
“Kalau kamu tidak mudik dan tetap masuk pasti dapat banyak persen dari
tamu-tamu. Ya, tidak usah pulang.”
“Wah, nuwun sewu, Bu. Saya sudah terlanjur janji anak-anak.”
Dengan kemantapan tekad begitulah dia memutuskan untuk mudik. Anak-
anaknya mulai diceriterai tentang Njati, sawah-sawahnya, kerbau dan sapinya,
bentuk-bentuk rumah di desa. Juga tentang embah-embahnya yang sudah pada
memutih rambutnya. Juga tentang kota-kota yang bakal mereka lewati, yang akan
dapat mereka lihat sekilas-sekilas dari jendela bis yang akan membawa mereka.
“Waduh, kota-kota mana saja itu, Bu?”
“Wah, banyak. Mungkin Cirebon, mungkin Purwokerto, mungkin lewat
Semarang, pasti Magelang, pasti Yogya, Solo, terus menuju Njati dan Wonogiri.”
“Waduh. Yang paling bagus kota mana, ya, Bu.”
“Wah, embuh. Mestinya, ya, Solo.”
“Waa, kita mau lihat Solo, Dik. Solo, Solo, Solo.”
“Solo, Solo, Solo…”
Dia berhenti termenung. Anaknya yang kecil sudah tidur dengan pulas di
tempat tidur. Kakaknya sudah bersiap juga untuk menyeruak menggeletak di
samping adiknya. Ditatapnya muka anak-anaknya sambil juga merebahkan
tubuhnya berdesakan dengan anak-anak mereka.
“Jangan terlalu kecewa, ya, Ti. Besok kita coba lagi. Kita pasti akan ke
Njati. Dan juga pasti lihat Kota Solo.” Dilihatnya anaknya mengangguk-
anggukkan kepalanya. Dengan setengah mengantuk dia mengucap, “Solo, Solo,
Solo…”
*
Itu kemarin, pada hari Lebaran pertama. Sekarang, pada hari Lebaran
kedua, mereka gagal lagi. Kemungkinan itu bahkan lebih tidak ada lagi. Karcis
yang dibelinya dari calo, seperti kemarin, memang sudah di tangan. Tetapi, orang-
orang itu kok malah jauh lebih banyak dari kemarin. Bahkan lebih beringas. Dia
dan anak-anaknya dengan genteyongan barang mereka seperti kemarin, ditarik,
didesak, digencet, sehingga akhirnya tersisih jauh ke pinggir lagi. Satu, dua bis
dicobanya. Gagal lagi. Orang masih sangat, sangat banyak dan kuat, untuk dapat
ditembus. Dan, akhirnya, dengan berdiri termangu di pinggir-pinggir warung,
dilindungi kain terpal, di bawah hujan, mereka melihat bis terakhir ke Wonogiri
berangkat.
“Yaa, kita nggak jadi betul ke Njati, ya, Bu.”
Ibunya melihat anak-anaknya dengan senyum yang dipaksakan.
“Iya, Nak. Nggak apa, ya? Tahun depan kita coba lagi.”
“Yaa.”
“Yaa.”
“Iya dong. Ibu harus kumpul uang lagi, kan?”
“Memangnya sekarang sudah habis, Bu?”
Ibunya menggigit bibirnya. Tersenyum lagi.
“Masih, masih. Tapi hanya bisa ke Kebon Binatang besok. Ke Njati tahun
depan saja, ya?”
Anak-anaknya diam. Hujan mulai agak reda. Dilihatnya hujan yang mereda itu
agak menggembirakan anaknya.
“Yuk, yuk, kita lari keluar cari bajaj, yuk.”
Anak-anak itu mengangguk, kemudian mengikuti ibunya digandeng sambil
berlari-lari kecil. Di dalam bajaj anak-anak mulai bernyanyi ciptaan mereka yang
terbaru.
“Solo, Solo, Solo. Solo, Solo, Solo.”
Mereka tertawa.
“Njati, Njati, Njati. Njati, Njati, Njati.”
Mereka tertawa lagi, mungkin senang bisa menciptakan lagu. Ibunya ikut
senang juga melihat anak-anaknya tidak menangis atau merengek-rengek. Dia
ingat akan janjinya kepada anak-anaknya untuk mengajak mereka ke Kebon
Binatang. Wah, dengan uang apa? Uangnya yang terbanyak sudah habis dimakan
calo karcis, ongkos bolak-balik bajaj, jajan, oleh-oleh yang sekarang sudah pada
peyot semua. Tinggal lagi sisa untuk beberapa hari. Wah. Tidak apa, pikirnya.
Uang itu cukup untuk ongkos ke Kebon Binatang. Saya akan ke gedong malam
ini, pikirnya. Pasti banyak kerjaan, pastinya. Siapa tahu tamu-tamu belum pada
pulang dan banyak persennya, harapnya. Di kamar sewaannya, anak-anaknya
segera ditidurkannya dan sekali lagi dibisikkannya janjinya untuk ke Kebon
Binatang besok.
“Lekas tidur. Besok kita ke Kebon Binatang.”
“Asyik, asyik, asyik.”
“Ibu pergi sebentar ke gedong, ya? Baik-baik di rumah, ya? Tidur.”
“Gajah, gajah, gajah. Jrapah, jrapah, jrapah.”
“Ssst, tidur.”
Ibunya dengan tersenyum menutup pintu. Tetapi, waktu di luar, dia dengar anak-
anaknya menyanyi yang lain lagi.
“Solo, Solo, Solo. Njati, Njati, Njati…..”
Ibunya menggigit lagi bibirnya sejenak. Kemudian dengan pasti melangkahkan
kakinya.
Di gedong, nyonya rumah berteriak waktu melihat dia masuk rumah lewat
pintu belakang.
“To, saya bilang apa. Saya bilang apa. Sokur tidak dapat bis kamu. Ayo
sini bantu kami sini. Tuh piring-piring kotor masih menumpuk di dapur.
Sana…….”
Anda mungkin juga menyukai
- 4 - Gerak MelingkarDokumen10 halaman4 - Gerak Melingkaraku katalistBelum ada peringkat
- Seni BudayaDokumen7 halamanSeni BudayaSri UrifahBelum ada peringkat
- Laporan Transport MembraneDokumen24 halamanLaporan Transport MembraneValeryBelum ada peringkat
- Rangkuman Bab 5 Peredaran DarahDokumen67 halamanRangkuman Bab 5 Peredaran DarahFalin NisriinaBelum ada peringkat
- Uraian 1Dokumen15 halamanUraian 1Hendri PermadiBelum ada peringkat
- RIMADokumen4 halamanRIMAkatarina claraBelum ada peringkat
- Jaringan HewanDokumen3 halamanJaringan HewanRohmi HidayahBelum ada peringkat
- PKWUDokumen3 halamanPKWUwindaaBelum ada peringkat
- Laras 1Dokumen22 halamanLaras 1sarahadzanyBelum ada peringkat
- Tugas Ukbm 4.7 Respirasi Tumbuhan & Kecepatan BernafasDokumen6 halamanTugas Ukbm 4.7 Respirasi Tumbuhan & Kecepatan Bernafasizzaturrachmi anwarBelum ada peringkat
- Remidi B.indDokumen5 halamanRemidi B.indShizu SeijuroBelum ada peringkat
- Ulangan HarianDokumen9 halamanUlangan HarianNadyatun KhasanahBelum ada peringkat
- Cerpen MAAFDokumen5 halamanCerpen MAAFchimonblack86Belum ada peringkat
- Tari Merak KreasiDokumen1 halamanTari Merak KreasiCitra Sintia RahmanBelum ada peringkat
- Paket 1 UTSGanjil 20182019Dokumen13 halamanPaket 1 UTSGanjil 20182019neni cortdiena77Belum ada peringkat
- KemarauDokumen3 halamanKemarauNur indriani SamiunBelum ada peringkat
- Proposal Persiapan Pergelaran Musik Barat (Traoble Is Friend)Dokumen9 halamanProposal Persiapan Pergelaran Musik Barat (Traoble Is Friend)Sur YatiBelum ada peringkat
- Lukman - Puisi Serenada HijauDokumen3 halamanLukman - Puisi Serenada HijauLukmanLatopas0% (2)
- Bahasa Indonesia Kelas XIDokumen11 halamanBahasa Indonesia Kelas XIWawan LuswandiBelum ada peringkat
- Naskah PembawaDokumen11 halamanNaskah PembawaGrace RaniBelum ada peringkat
- Bab 1 Tabel Periodik Unsur Dan Struktur AtomDokumen42 halamanBab 1 Tabel Periodik Unsur Dan Struktur AtomdesiratnasariBelum ada peringkat
- Bab 6 Kemagnetan Dan Induksi ElektromagnetikDokumen36 halamanBab 6 Kemagnetan Dan Induksi Elektromagnetikverlyn vanessaBelum ada peringkat
- Anak DesaDokumen4 halamanAnak DesaQurrotul Aien Fatah YasinBelum ada peringkat
- Lembar Kegiatan Peserta Didik: Animalia: Platyhelminthes Nematoda AnnelidaDokumen3 halamanLembar Kegiatan Peserta Didik: Animalia: Platyhelminthes Nematoda AnnelidaNurhidayahBelum ada peringkat
- Cerpen Basa SundaDokumen5 halamanCerpen Basa SundaAliffia Ardana PutriBelum ada peringkat
- CERPEN - 4 B.indoDokumen16 halamanCERPEN - 4 B.indoM Irsyad MaulanaBelum ada peringkat
- Ai MangkungDokumen3 halamanAi MangkungGillang MifttahBelum ada peringkat
- Bab Fluida StatisDokumen31 halamanBab Fluida StatisAsyrof AfifahBelum ada peringkat
- Resensi Novel Tesi Dwiyan Prilia Sastra Indonesia ADokumen8 halamanResensi Novel Tesi Dwiyan Prilia Sastra Indonesia ATesy PriliaBelum ada peringkat
- Ulangan Harian Biologi 1 Semester 2Dokumen4 halamanUlangan Harian Biologi 1 Semester 2mohamad fauziBelum ada peringkat
- Soal SenbudddddDokumen33 halamanSoal SenbudddddGevi Dwi Hermanto PutriBelum ada peringkat
- Pagelaran Seni TariDokumen16 halamanPagelaran Seni TariŘayñaldøBelum ada peringkat
- Sebutkan Dan Jelaskan Macam-Macam Cabang Ilmu Fisika Berdasarkan bida-WPS OfficeDokumen1 halamanSebutkan Dan Jelaskan Macam-Macam Cabang Ilmu Fisika Berdasarkan bida-WPS Officemrsy tprBelum ada peringkat
- Mengomentari Musikalisasi PuisiDokumen2 halamanMengomentari Musikalisasi PuisiRen AtaBelum ada peringkat
- Uji Kompetensi 3 Putri Delima Gultom Xi Ipa 3Dokumen5 halamanUji Kompetensi 3 Putri Delima Gultom Xi Ipa 3Johan NesBelum ada peringkat
- Tugas Teks EksplanasiDokumen7 halamanTugas Teks EksplanasiMarcelinus Nickey YuriadisBelum ada peringkat
- Bukti-Bukti Agama Kristen Sudah Masuk Ke Indonesia Pada Abad Ke-9Dokumen5 halamanBukti-Bukti Agama Kristen Sudah Masuk Ke Indonesia Pada Abad Ke-9anggraini DedeBelum ada peringkat
- Soal Dan Jawaban Sistem GerakDokumen9 halamanSoal Dan Jawaban Sistem GerakM. Rafif Azryan ZevaBelum ada peringkat
- Mind Map DramaDokumen1 halamanMind Map DramaAzzahra MadaniaBelum ada peringkat
- Laporan Jaringan Hewan 2Dokumen5 halamanLaporan Jaringan Hewan 2halim wisnuhadiBelum ada peringkat
- Bindo Teks Eksplanasi ReogDokumen2 halamanBindo Teks Eksplanasi ReogAdinda Arif0% (1)
- Sosiologi Ganjil XIDokumen11 halamanSosiologi Ganjil XIsri afrilyaniBelum ada peringkat
- Barisan Dan DeretDokumen15 halamanBarisan Dan Deretppk terasBelum ada peringkat
- Sistem Sirkulasi-2Dokumen13 halamanSistem Sirkulasi-2Nurul HanaBelum ada peringkat
- TrikDokumen10 halamanTrikFikri RozanBelum ada peringkat
- Latihan Un Sastra - PertamaDokumen9 halamanLatihan Un Sastra - Pertamasastra indonesia0% (1)
- Tugas B.indoDokumen6 halamanTugas B.indoPriska absen 21100% (1)
- Pengaruh Media Sosial Bagi Proses Belajar SiswaDokumen13 halamanPengaruh Media Sosial Bagi Proses Belajar Siswaaufar hanaBelum ada peringkat
- Pemandangan Senja KalaDokumen4 halamanPemandangan Senja KalaTrisna wulandariBelum ada peringkat
- Hati Yang LembutDokumen4 halamanHati Yang LembutRy Net CozioBelum ada peringkat
- Teknologi Untuk Membantu Kelainan Sistem PernapasanDokumen1 halamanTeknologi Untuk Membantu Kelainan Sistem PernapasanMuhammad Bintang prazegaBelum ada peringkat
- Wa0008.Dokumen6 halamanWa0008.auliawindinatasya6Belum ada peringkat
- Makalah SidalupaDokumen13 halamanMakalah SidalupaSiti WardinaBelum ada peringkat
- Cerpen IndieDokumen11 halamanCerpen IndieDhanyekaBelum ada peringkat
- Cinta Diatas Perahu CadikDokumen5 halamanCinta Diatas Perahu Cadikfitri solichahBelum ada peringkat
- Soal Kuis Bab 1Dokumen3 halamanSoal Kuis Bab 1Afwanilhuda NstBelum ada peringkat
- A Naufal Syaikhoni - BersyukurDokumen3 halamanA Naufal Syaikhoni - Bersyukurintan suryanaBelum ada peringkat
- Diary Masa LaluDokumen3 halamanDiary Masa LaluLaila HariniBelum ada peringkat
- Aku MenantimuDokumen7 halamanAku MenantimuOlimpianus SinurayaBelum ada peringkat
- Cerpen Lampu IbuDokumen4 halamanCerpen Lampu IbuPangsoed 2 BekasiBelum ada peringkat
- Masalah Sosial Pada FilmDokumen29 halamanMasalah Sosial Pada FilmJanri ZheiltorBelum ada peringkat
- Masalah Pemerataan PendidikanDokumen2 halamanMasalah Pemerataan PendidikanJanri ZheiltorBelum ada peringkat
- Tugas Pengantar PendidikanDokumen2 halamanTugas Pengantar PendidikanJanri ZheiltorBelum ada peringkat
- Agama Pertemuan 13Dokumen6 halamanAgama Pertemuan 13Janri ZheiltorBelum ada peringkat
- Evaluasi KWDokumen1 halamanEvaluasi KWJanri ZheiltorBelum ada peringkat
- Catatan Pengantar Ilmu Sastra Semester 1Dokumen32 halamanCatatan Pengantar Ilmu Sastra Semester 1Janri Zheiltor100% (1)
- Makalah Teori Dan Praktik Menyimak Komprehensif Berita Dan KuliahDokumen25 halamanMakalah Teori Dan Praktik Menyimak Komprehensif Berita Dan KuliahJanri ZheiltorBelum ada peringkat
- Makalah Membaca SastraDokumen12 halamanMakalah Membaca SastraJanri ZheiltorBelum ada peringkat
- Proposal Usaha MinumanDokumen11 halamanProposal Usaha MinumanJanri Zheiltor75% (4)
- Jalur Pendidikan SekolahDokumen2 halamanJalur Pendidikan SekolahJanri ZheiltorBelum ada peringkat
- Ronaldo SimangunsongDokumen6 halamanRonaldo SimangunsongJanri ZheiltorBelum ada peringkat