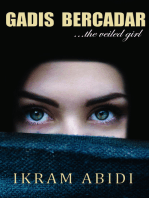Purnama Di Awal Senja
Diunggah oleh
el rosella0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
14 tayangan1 halamanJudul Asli
PURNAMA DI AWAL SENJA
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
14 tayangan1 halamanPurnama Di Awal Senja
Diunggah oleh
el rosellaHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 1
PURNAMA DI AWAL SENJA
“Sudahlah Bonang, mengapa kau menyerah sekarang?”
Kuperhatikan pria hampir senja ini berdiri didepanku. Dia mengenakan baju batik rapinya dengan model
penampilan yang sangat klimis. Rambutnya licin dan mengkilat, tertata rapi menyamping seperti sawah
padi yang tertanam di perbukitan terasiring. Kacamata tebal bertengger kuat di pangkal hidungnya. Pipi
dan dagunya licin meskipun samar-samar nampak tunas-tunas rambut ke-perak-kan yang beranjak
menembus pori-porinya. Bajunya rapi, jam tangan tua bermerk yang mungkin sudah berumur hampir
setengah hidupnya bergelayut di tangan kurusnya. Sepatunya hitam mengkilat. Penampilannya begitu
elegan, berbeda dengan outfit favoritku yang sering hanya menggunakan kain sarung dan kaos singlet
saja, ditambah sandal jepit yang seolah sudah melekat di epidermis kulit telapak kakiku.
Dia hanya membisu tanpa berucap sepatah kata pun.
Ku perhatikan pria ini hanya diam sambil mulutnya berkomat-kamit tanpa mengeluarkan suara. Gerak
bibirnya kelu, mukanya nampak tegang dan di seluruh kening dan sudut matanya sudah bergaris
bergambar retakan-retakan umur.
Aku sudah mengenalnya hampir seumur hidupku. Kami sudah sangat lama bersama sehingga setiap kali
kulemparkan pertanyaan untuknya, seolah-olah aku sudah mengetahui jawaban apa yang akan keluar dari
mulutnya. Seluruh pertanyaanku seakan-akan hanya menjadi retorika belaka yang renyah. Renyah
bagaikan tumpang tindih pikiranku yang seperti kerupuk jawa.
“Kita sudah berjalan sepanjang ini. Kita sudah bertahan selama ini. Kita pernah berhasil menerjang
gelombang. Kita sudah pernah berhasil menghadapi paceklik. Sekarang mengapa tiba-tiba menyerah
begitu saja, Bonang?” tanyaku menyakinkan.
Sekali lagi pertanyaanku hanya dijawab oleh komat-kamit kebisuan yang lelap. Mulutnya bergerak
bersamaku, tapi suaranya tenggelam dalam dimensinya sendiri.
Lama dia hanya tertegak menatapku. Menatap tajam retinaku, hingga nanar menyeruak dari balik
hitamnya jawaban yang aku tunggu.
“Aku ini sudah kering dan menguning! Hanya tinggal menunggu kurang dari tiga lebaran saja, maka
purna sudah pengabdianku. Sekarang purnama ini datang mendadak, memaksa mempersingkat senjaku.”
Suaranya bergetar. “Tidak gampang untuk berjalan di kelam malam sendirian. Dan aku belum terlalu
mengenal purnama ini untuk menerangi jalanku.” Keluhnya.
Jawabannya kemudian menghenyakkanku sesaat. Memaksa diam dan membekukan seluruh sisi lidahku,
pikiranku, bahkan emosi bathinku yang baru saja bergejolak seperti api besar yang melalap habis sebuah
rumah kemudian tenggelam dan memadam kehabisan oksigen.
“Tiga puluh lima tahun aku mengajar. Selama tiga puluh lima tahun itu pula aku melihat dan berkesan
dengan wajah baru setiap tahun. Tapi bukan wajah purnama ini yang bisa membekas di ingatanku.” Dia
melanjutkan, “Gairahku sudah tidak mampu lagi berpetualang menyelami cahaya purnama ini. Dan
hasratku sudah melunak tanpa energi meski purnama ini menjanjikanku cahaya yang menyilaukan
disepanjang jalan tapakku.”
Meski dia berbicara tanpa suara, kalimat ini begitu nyaring merobek selaput gendang bathinku hingga
menembus ke otak besarku. Seolah berteriak didalam ruang kontempelasi yang seumur hidupku hanya
kosong tanpa bunyi.
“Setidaknya bertahanlah sebentar, Bonang!” balasku lirih. “1 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau 3 tahun lagi
dan nikmatilah uzurmu dengan lapang.” Kali ini aku membalas dengan lemas. Memahami dengan sublim
tentang apa yang bergulat di pikirannya. Lebih dari simpati dan empati, tapi sublim, benar-benar dalam.
Tiba-tiba terdengar bunyi ketukan pintu dari luar oleh suara yang tak asing di telingaku; “Pak Bonang?!
Pak Bonang?!”.
“Ya wik?!” balasku, menjawab panggilan Dewi, asisten rumah tangga di sekolahku. “Tamu Pak Kepala
Sekolah sudah berpamit. Beliau sudah kosong. Beliau meminta saya memanggil bapak, jadi silahkan
menghadap ke beliau pak.” Kata Dewi.
“Baik wik.” Balasku. “Saya segera keruang Bapak!” kataku seraya keluar dari ruang toilet sambil
meninggalkan bayanganku di dalam kaca diatas wastafel. (tamat.Ilham2021)
Anda mungkin juga menyukai
- Petualang AsmaraDokumen744 halamanPetualang AsmaraErwin AnthonyBelum ada peringkat
- (Kaito Novel) Hello, Hello, and Hello Bahasa IndonesiaDokumen283 halaman(Kaito Novel) Hello, Hello, and Hello Bahasa IndonesiaAzazelBelum ada peringkat
- Cerpen Komang, LELAKI SENJA-WPS OfficeDokumen6 halamanCerpen Komang, LELAKI SENJA-WPS Officeputrichaaisyah535Belum ada peringkat
- BIANGLALADokumen6 halamanBIANGLALADiah Ayu Nuril AzizahBelum ada peringkat
- Tangis Di Ujung SenjaDokumen2 halamanTangis Di Ujung SenjaBuce SabilBelum ada peringkat
- Satu Hari Bersamamu (Cerpen)Dokumen15 halamanSatu Hari Bersamamu (Cerpen)Hijrianti Suharna100% (1)
- Cerpen SeramDokumen16 halamanCerpen SeramAlan melantinoBelum ada peringkat
- Kumpulan Cerpen AbsurdDokumen66 halamanKumpulan Cerpen AbsurdHendra Bangkit PramanaBelum ada peringkat
- Tugas Jyw 2Dokumen6 halamanTugas Jyw 2Em ShabirinBelum ada peringkat
- Bias Pelangi SenjaDokumen6 halamanBias Pelangi SenjaMuhammad IkhsanBelum ada peringkat
- Surat JiwaDokumen42 halamanSurat JiwakhairunnisakamaruddiBelum ada peringkat
- Cerpen 2Dokumen3 halamanCerpen 2Silvia NurBelum ada peringkat
- The Rain Has Change1Dokumen27 halamanThe Rain Has Change1Niken PalupiBelum ada peringkat
- CERPEN (Muhammad Abdi Fauzan)Dokumen8 halamanCERPEN (Muhammad Abdi Fauzan)fauzandwiky142Belum ada peringkat
- Cerpen KusutDokumen5 halamanCerpen KusutMustika RahmawatiBelum ada peringkat
- Cerpen PersahabatanDokumen9 halamanCerpen PersahabatanHelvia ViaBelum ada peringkat
- CerpenDokumen22 halamanCerpeniksan008_ndutBelum ada peringkat
- Joanna XIA1 - 17 - Tugas Keterampilan CerpenDokumen7 halamanJoanna XIA1 - 17 - Tugas Keterampilan Cerpendessythresyahutabarat03Belum ada peringkat
- Kumpulan PuisiDokumen11 halamanKumpulan PuisisaifullahBelum ada peringkat
- Cintaku Tertinggal Di Lombok TengahDokumen2 halamanCintaku Tertinggal Di Lombok TengahFerry AgusmansyahBelum ada peringkat
- SALMA NUR AMALINA - Tugas5 - IndividuDokumen7 halamanSALMA NUR AMALINA - Tugas5 - IndividuSalma AmalinaBelum ada peringkat
- Contoh CerpenDokumen4 halamanContoh CerpenshendyBelum ada peringkat
- Marry Me Senorita TeaserDokumen8 halamanMarry Me Senorita TeaserNUR KHAIRUNNISA FARHANA BINTI MOHD TAJARUDDIN MoeBelum ada peringkat
- Surga Yang DekatDokumen5 halamanSurga Yang DekatNatasha HadiwinataBelum ada peringkat
- Di Atas Bumi, Di Bawah Langit Finished)Dokumen159 halamanDi Atas Bumi, Di Bawah Langit Finished)Gilang FirmandaBelum ada peringkat
- DIA-WPS OfficeDokumen3 halamanDIA-WPS OfficeGenjiBelum ada peringkat
- Adoc - Pub - Di Interlude Aku Jatuh CintaDokumen7 halamanAdoc - Pub - Di Interlude Aku Jatuh Cintalingkar pena indonesiaBelum ada peringkat
- Tugas LonatgoDokumen16 halamanTugas LonatgoLosithaBelum ada peringkat
- Cerpen: Jalan Menuju KedewasaanDokumen10 halamanCerpen: Jalan Menuju KedewasaanonemahmudBelum ada peringkat
- Nuansa BeningDokumen39 halamanNuansa BeningimacatpersonBelum ada peringkat
- Cerpen Lentera PadamDokumen4 halamanCerpen Lentera PadamD. SyuryawanBelum ada peringkat
- Tangga Nada Violina - Siswa 1Dokumen9 halamanTangga Nada Violina - Siswa 1Herawati SunusiBelum ada peringkat
- BI CerpenDokumen9 halamanBI CerpenSely Oktaviolita AsriBelum ada peringkat
- Aruna & Setangkai Bunga Edelweiss - ReishaDokumen10 halamanAruna & Setangkai Bunga Edelweiss - ReishaReishadjati RenastaBelum ada peringkat
- Temaram #1Dokumen1 halamanTemaram #1lostmycultBelum ada peringkat
- Kata Khen Dak Men Jad Il EmbuDokumen83 halamanKata Khen Dak Men Jad Il EmbuCitra R. LestariBelum ada peringkat
- Apresiasi CerpenDokumen8 halamanApresiasi CerpenSurya N WijayaBelum ada peringkat
- CERPEN: "BANU" Karya: Davina A.SDokumen14 halamanCERPEN: "BANU" Karya: Davina A.SDavina yaaBelum ada peringkat
- Editan Antologi Kisah Chien PaoDokumen72 halamanEditan Antologi Kisah Chien PaoLandu KannaBelum ada peringkat
- DataDokumen17 halamanDataAbdi PrialamBelum ada peringkat
- The UnforgetableDokumen156 halamanThe UnforgetableLasmaBelum ada peringkat
- A Letter To CaesarDokumen241 halamanA Letter To CaesarSurya AnantaBelum ada peringkat
- Seragam - Aris Kurniawan BasukiDokumen3 halamanSeragam - Aris Kurniawan BasukikatrinaBelum ada peringkat
- Andira Eka PutriDokumen7 halamanAndira Eka PutriMuhammad FauziBelum ada peringkat
- Biseksual - Sebuah CerpenDokumen11 halamanBiseksual - Sebuah CerpenMuhamad FakhrusyBelum ada peringkat
- CemburuDokumen5 halamanCemburuaryBelum ada peringkat
- You Belong With MeDokumen64 halamanYou Belong With MeinayaverlyBelum ada peringkat
- Bahasa Jawa Kelas 10Dokumen2 halamanBahasa Jawa Kelas 10Depi Umar100% (1)
- AlienasiDokumen5 halamanAlienasi19. Marffel Andrian RBelum ada peringkat
- Bacaan CerpenDokumen4 halamanBacaan CerpenArinKharismaBelum ada peringkat
- Cerpen PersahabatanDokumen8 halamanCerpen Persahabatangladys thereceliaBelum ada peringkat
- Prita Istri KitaDokumen13 halamanPrita Istri Kitamaya setyawatiBelum ada peringkat
- Tri AbelDokumen8 halamanTri AbelputudesiirawanBelum ada peringkat
- Satu PermulaanDokumen107 halamanSatu Permulaankelissa2139Belum ada peringkat
- Senandung Rindu Bintang KecilkuDokumen10 halamanSenandung Rindu Bintang KecilkuIstin Nana Robi'ahBelum ada peringkat
- Badai Pasti BerlaluDokumen110 halamanBadai Pasti BerlaluAnis Najwa0% (1)
- Cerpen BellaDokumen15 halamanCerpen BellaAgustina SyaputriBelum ada peringkat
- Bab IDokumen3 halamanBab IdadarahahoBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Formulir Pendaftaran Lomba Pidato Tingkat SMPDokumen1 halamanFormulir Pendaftaran Lomba Pidato Tingkat SMPel rosellaBelum ada peringkat
- Cetakan Kode BillingDokumen1 halamanCetakan Kode Billingel rosellaBelum ada peringkat
- Purnama Di Awal SenjaDokumen1 halamanPurnama Di Awal Senjael rosellaBelum ada peringkat
- Formulir Pendaftaran Lomba Debat Tingkat SMPDokumen1 halamanFormulir Pendaftaran Lomba Debat Tingkat SMPel rosellaBelum ada peringkat
- Latihan Soal TeksamDokumen9 halamanLatihan Soal Teksammsyahidah100% (1)
- Latihan Statistik Deskriptif 664 Amik BSDokumen13 halamanLatihan Statistik Deskriptif 664 Amik BSDimas Barkah KaruniaBelum ada peringkat
- SK. Pan, Ngaws, Piket US 2021Dokumen4 halamanSK. Pan, Ngaws, Piket US 2021el rosellaBelum ada peringkat
- Kop SuratDokumen1 halamanKop Suratel rosellaBelum ada peringkat
- Formulir Pendaftaran Lomba Debat Tingkat SMPDokumen1 halamanFormulir Pendaftaran Lomba Debat Tingkat SMPel rosellaBelum ada peringkat
- Formulir Pendaftaran Lomba Pidato Tingkat SMPDokumen1 halamanFormulir Pendaftaran Lomba Pidato Tingkat SMPel rosellaBelum ada peringkat
- SKB StatistikDokumen17 halamanSKB StatistikDesiNurhasnawatiBelum ada peringkat