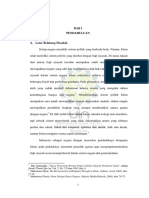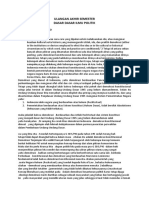Menguatnya Kartel Politik para ''BOS''
Diunggah oleh
Fanji Mangaraja0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
36 tayangan4 halamanJudul Asli
Menguatnya Kartel Politik Para ''BOS''
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
36 tayangan4 halamanMenguatnya Kartel Politik para ''BOS''
Diunggah oleh
Fanji MangarajaHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 4
Menguatnya Kartel Politik Para “Bos”
Banyak optimisme di ungkapkan setelah indonesia selesai menyelenggarakan pemilu
2009. Secara umum, pemilu dinilai sukses dan disebut sebagai langkah maju demokrasi.
Sekalipun demikian, muncul kritik bahwa pemilihan umum kali itu membosankan menngingat
tidak adanya perdebatan yang berarti di tingkat ideologi dan kebijakan. Di dalam negeri pun
hasil pemilu itu disambut sebagai kembalinya “zaman normal”. Indonesia dianggap telah
kembali ke lintasan yang benar sesudah mengalami periode-periode mengguncangkan usai
jatuhnya Soeharto. Tidak seperti tahun 1950 dan 1960, politik Indonesia saat ini sungguh
mengalami defisit dalam hal perdebatan ideologis. Hampir semua partai politik mengusung ide-
ide populis seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan gratis. Namun, tidak ada yang berani
mengakui secara terus terang bagaimana partai-partai akan membiayai pendidikan dan kesehatan
gratis itu. Kontras paling besar antara politik tahun 1950-an dan terkini adalah tidak adanya
kekuatan politik yang mau mengubah Negara. Jika dulu partai-partai nasionalis sekuler dan
partai-partai islam bersilang sengketa soal dasar negara, untuk saat ini perdebatan itu tampak
menghilang.
Secara garis besar ada beberapa hal yang patut dicatat dalam politik Indonesia
kontemporer, yang membedakannya dari periode-periode sebelumnya. Pertama, sistem
kepartaian Indonesia kontemporer jauh lebih stabil ketimbang masa-masa sebelumnya. Sebagai
mana ditulis Meitzner, sistem kompetisi antar partai masa kini bergerak sentripetal, sementara
kompetisi antar partai tahun 1950-an cenderung bergerak sentrifugal. Menurut Meitzner, partai-
partai pada tahun 1950-an cenderung bergerak ke ujung ekstrem, menuju ke basis ideologi
masing-masing, yang mengakibatkan polarisasi antar partai makin menajam. Tidak adanya partai
yang berhaluan “sentris” dan moderat menjadikan sistem kepartaian ini menghancurkan dirinya
sendiri, Hal sebaliknya terjadi dalam sistem kepartaian kontemporer. Sekalipun institusionalisasi
partai politik lemah, namun secara ideologis partai-partai tersebut bergerak ke tengah. Partai-
partai yang berada pada titik ideologis ekstrem (wing parties) menghadapi dilema; tetap kecil
atau bergerak ke tengah dan menjadi moderat. Dengan menjadi moderat, mereka mempermudah
koalisi dengan partai tengah dan memperlebar jangkauan pemilih. Kedua, yang juga patut dicatat
adalah tidak adanya persoalan terhadap ideologi negara. Kecuali beberapa kelompok kecil yang
menginginkan diberlakukannya syariat islam, hampir tidak ada kekuatan politik yang
mempertanyakan dasar negara. Setidaknnya begitulah yang ditampilkan di permukaan, namun
demikian, terlalu dini juga untuk menngatakan bahwa ideologi sudah lenyap sama sekali dari
politik Indonesia. Pilihan ideologis khususnya antara Islam dan Nasionalis masih terlihat dengan
jelas. Hal yang sering muncul dalam beberapa pemilihan umum di Indonesia adalah perpindahan
pemilih dari satu partai ke partai lain, namun dalam segmen ideologis yang sama. Kemerosotan
suara PDI-P pada pemilu 2009, misalnya, disebabkan oleh perpindahan pemilih PDI-P ke Partai
Demokrat yang masih dalam segmen ideologi yang sama dengan PDI-P dengan demikian, basis
sosial politik Indonesia terkenal dengan sebutan “politik aliran” tidak sepenuhnya terhapus.
Ketiga, politik Indonesia lebih terdesentralisasi dari pada masa-masa sebelumnya. Dinamika
politik nasional tidak sama dengan dinamika politik di daerah yang sangat plural.
Konsekuensinya, jalinan koalisi di tingkat nasional tidak sama dengan jalinan koalisi di tingkat
daerah. Dalam ruang lebih sempit, politikus di daerah memiliki kesempatan lebih luas untuk
menjalankan mobilisasi berdasarkan identitas kesukuan, agama, bahasa, dan bahkan clan. Kasus-
kasus pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) menunjukan bahwa kandidat dengan jejaring
personal (personal network) terkuat yang akan memenaangkan pemilihan. Kecendrungan ini,
selain mengubah peta hubungan pusat-daerah didalam partai, juga mengubah hubungan antara
elite lokal dan nasional. Keempat, dan menjadi fokus utama tulisan ini, adalah persoalan elite
politik. Berbeda dengan dugaan banyak orang yang berandai-andai bakal adanya pertarungan
antara elite pendukung otoritersime dengan pendukung demokratisasi, kalangan elite di
Indonesia menampakan stabilitas luar biasa dalam menghadapi kelompok-kelompok elite yang
mendukung faksi-faksi di dalam tentara. Pemerintahan Aquino menghadapi paling tidak tujuh
kali percobaan kudeta. Sementara di Indonesia situasinya relatif stabil dan hampir tanpa gejolak.
Apakah yang bisa menjelaskan stabilitas elite politik di negeri ini? Apakah ini akan berlangsung
dalam jangka waktu relatif lama dan akan menjadi pola perpolitikan Indonesia di masa depan?
Persoalan elite ini saling terkait dengan partai, sistem kepartaian, serta hubungan antara
kondisi lokal dan politik nasional. Namun sebelumnya kita akan melihat dua konstruksi teoretis
populer yang berkaitan dengan elite politik ini, yakni oligarki yang bersifat predator dan
bossism. Penulis sendiri akan keluar dengan konsep “kartel,” sebuah konsep ekonomi yang
diterapkan untuk menganalisis sistem kepartaian (politik). Dalam banyak hal, menurut penulis,
kartel lebih tepat untuk menganalisis stabilitas politik Indonesia.
Dua Konstruksi Teoretis: Oligarki atau Bossism?
Bannyak pengamat berusaha memberikan kerangka analisis terhadap politik Indonesia
pasca-Orde Baru. Salah satu yang paling berpengaruh adalah karya Richard Robinson dan Vedi
R Hadiz. Kedua sarjana terkemuka ini menyatakan bahwa sekalipun Indonesia lepas dari jerat
otoriterisme, dia tidak bisa lepas dari jerat oligarki yang memang sudah ditenun dalam struktur
politik Indonesia sejak lama. Oligarki yang hidup dalam pemerintahan otoriter dalam masa
demokrasi menjelma menjadi Oligarki politik uangg. Bahwa jaringan patronase dan
pengalokasian kekuasaan dan kekayaan publik mendapatkan ruang baru, yakni dalam partai
politik dan parlemen. Mereka yang awalnya masuk sebagai pembaru kemudian tengggelam
didalam perkawinan antara kapitalisme pemangsa (predatory capitalism) dan politik demokratik.
Jaringan Oligarki yang dahulu bekerja dalam sistem represi negara sekarang bekerja dalam
sistem pemilihan, partai-partai, dan parlemen. Oligarki lokal telah membajak lembaga-lembaga
demokrasi seperti partai politik, pemilihan umum, dan parlemen. Mereka mampu
mempertahankann kekusaan, karena mereka mampu menguasai sumber-sumber kekayaan
negara. Dengan kekayaan ini mereka membeli suara dalaam pemilihan. Selain itu, merekaa jugaa
memakai kekerasaan dengan kekuatan bersenjata semi-formal yang memungkinkan mereka
melakukan intimidasi fisik kepada lawan mereka. Kesinambungan diantara Oligarki pada zaman
pemerintahan otoriter bukan saja populer tetapi juga dominan dalam analisis politik pasca-Orde
Baru. Teori Oligarki menekankan daya tahan para oligarki dari zaman Orde Baru. Sementara,
Bossism memberi perspektif tentang bagaimana jejaring orang kuat itu menguasai, memperkuat,
dan memanfaatkan negara untuk kepentingan sendiri. Keduanya sama-samaa menekankan
karakter predatoris (pemangsa) dari negara. Pada bossism, karakter predatoris dinyatakan sebagai
konsekuensi untuk menciptakan negara kuat dari jaringan para bos. Sementara, untuk Oligarki
karakter ini berasal dari logika modal dalam sistem kapitalisme. Oligarki tidak terlalu percaya
bila kapitalisme akan membawa kemajuan, karena logika marxian yang mendasarinya.
Sebaliknya bossism bersikap agnostic terhadap massa-rakyat di wilayah masing-masing. Untuk
kasus indonesia, Sidel mengakui bahwa kekuatan politik, terutama di tingkat lokal, kurang (atau
belum) didominasi orang kuat atau dinasti-dinasti politik. Kemunculan orang kuat dihalangi oleh
struktur kelembagaan dari negara itu sendiri. Namun demikian, dia memprakirakan orang kuat
dan dinasti politik akan muncul bersamaan dengan pemilihan langsung. Ada beberapa kelemahan
mendasar dari dua konstruksi teoretis tersebut. Pertama daya tahan Oligarki yang berlangsung
sejak Orde Baru hingga kini mungkin tidak sekuat yang dihipotesiskan. Dengan kata lain, ruang
untuk perubahan mungkin terbuka lebar, dan sesungguhnya tidak terlalu sulit untuk memahami
bahwa politik Indonesia sedang mengalami perubahan mendasar. Kedua, perbincangan mengenai
Oligarki dan Bossism tidak masuk ke dalam wilayah persaingan kekuasaan diantara para Bos
atau Oligarki. Dengan demikian, cengkeraman, represi, dan kekuatan daya predator negara oleh
kedua teori diasumsikan sangat kuat kemungkinan melemah di beberapa bagian. Ketiga, kedua
konstruksi teoretis tersebut tidak membuka ruang bagi analisis tentang kemungkinan adanya
kekuatan oposisional. Keempat, teori-teori tersebut tidak menutup kemungkinan adanya
sejumlah variasi, baik spesial maupun temporal. Dengan demikian, pemisahan (disaggregation)
antara politik nasional dan politik lokal menjadi amat sangat penting.
Stabilitas Elite di Tingkat Nasional: Kartel dan
Segala Konsekuensinya
Satu hal yang menonjol dalam politik pasca Orde Baru adalah stabilitas elite. Tidak
seperti negara lain yang mengalami transisi demokrasi, dengan persaingan antar elite berjalan
sengit dan membawa instabilitas, di Indonesia kerja sama antar elite berlangsung dalam suasana
relatif damai. Ini membawa kita pada bentuk kartel yang dalam istilah ekonomi berarti
koordinasi untuk meminimalkan persaingan, mengontrol harga, dan memaksimalkan keuntungan
diantara anggota kartel. Pada awalnya, konsep itu dikembangkan untuk menganalisis
perkembangan baru dalam sistem kepartaian. Dengan menekan stabilitas elite, kita bisa
menganalisis sebuah sistem monopoli yang meminimalisasi persaingan, menoleransi korupsi dan
kolusi dan menjelaskan berbagai kegagalan fungsi institusi-institusi demokratis. Politik kartel
muncul dari sebuah koalisi besar diantara elite politik. Sistem ini diciptakan untuk
meminimalkan kerugian dari pihak yang kalah, entah dalam pemilu atau dalam koalisi. Ia
berbeda dengan sistem otoriterisme-birokratik yang memakai sistem “penyingkiran”
(Exclusionary), Kartel lebih mengutamakan mekanisme “perangkulan” (incoporation) dari elite
yang memiliki latar belakang ideologis berbeda. Kekuasaan menjadi tidak memiliki
pertanggungjawaban (unaccountable). Secara prosedural, sistem itu bisa dikatakan demokratis
karena pemilu dilakukan secara reguler. Akan tetapi, kompetisi antar partai akan berubah
menjadi kolusi antar elite begitu kotak pemilihan ditutup dan suara dihitung. Selain memberi
stabilitas elite Indonesia, kartel politik ini juga memberikan beberapa konsekuensi penting pada
politik Indonesia. Pertama, kartel sangat menekankan pragmatisme. Tidak terlalu mengherankan,
apa bila aktivis-aktivis radikal ingin masuk ke ranah politik, mereka dipaksa untuk
menyesuaikan diri dengan iklim pragmatis ini. Kedua, batas antara mereka yang memerintah dan
kalangan oposisi menjadi tidak jelas. Baik pemerintah maupun mereka yang beroposisi lebih
banyak menampilkan persetujuan ketimbang perbedaan. Para elite menjadi tidak responsif
terhadap suara rakyat. Ketiga, sistem kartel adalah sistem kolutif yang berakibat pada
pengebirian kekuatan massa rakyat. Kartel politik memang memberikan stabilisasi untuk para
elite. Keempat, politik kartel memberikan hasil sangat ironis bagi kekuatan politik masyarakat.
Ironi paling besar adalah apa yang dicapai dengan represi brutal oleh orde baru bisa dicapai
dengan persuasi dan manipulasi dalam iklim politik kartel.
Politik Kartel di Tingkat Lokal
Desentralisasi telah mengubah wajah politik Indonesia menjadi sangat berbeda dari yang
pernah ada dalam sejarah. Pada awalnya desentralisasi bermaksud menciptakan pemerintahan
yang baaik (good governance) di tingkat lokal. Bahkan world bank (IMF) sempat menyatakan
bahwa desentralisasi adalah “the big bang” (dentuman besar) dalam politik Indonesia. Apakah
politik kartel juga bekerja di tingkat lokal? Pertanyaan ini cukup sulit untuk dijawab mengingat
begitu besarnya variasi antar daerah di Indonesia. Namun, hampir semua pengamat dan
pemerhati sepakat bahwa desentralisasi telah melahirkan “orang-orang kuat” yang memiliki akar
di daerah.
Anda mungkin juga menyukai
- Pola Divergensi Dan KonvergensiDokumen15 halamanPola Divergensi Dan Konvergensiziyya_elhakimBelum ada peringkat
- Budaya Politik Yang Berkembang Di Indonesi1Dokumen4 halamanBudaya Politik Yang Berkembang Di Indonesi1Velvet CassieBelum ada peringkat
- Analisis Penyimpangan Demokrasi Di Indonesia - Alyaa RamadhaniaDokumen12 halamanAnalisis Penyimpangan Demokrasi Di Indonesia - Alyaa RamadhaniaAlyaa RamadhaniaBelum ada peringkat
- Sistem Politik Indonesia Era ReformasiDokumen14 halamanSistem Politik Indonesia Era ReformasiKholikBelum ada peringkat
- Tugas 3 (Sosiologi Politik 01)Dokumen6 halamanTugas 3 (Sosiologi Politik 01)Yuyun YunengsihBelum ada peringkat
- Desa Situs FixDokumen85 halamanDesa Situs FixFaisal HatamiBelum ada peringkat
- Demokrasi Dalam Tatanan KekacauanDokumen4 halamanDemokrasi Dalam Tatanan KekacauanBobsadinowikul AnonoBelum ada peringkat
- Refleksi Situasi Demokrasi Di IndonesiaDokumen11 halamanRefleksi Situasi Demokrasi Di IndonesiaTaufik PoliBelum ada peringkat
- Format PolitikDokumen22 halamanFormat PolitikAlimudin KhasanBelum ada peringkat
- Tugas Resume Demokrasi Ari SundariDokumen5 halamanTugas Resume Demokrasi Ari SundariAri SundariBelum ada peringkat
- Masyarakat Sipil Sebagai Kekuatan Politik TemanDokumen11 halamanMasyarakat Sipil Sebagai Kekuatan Politik TemanThesa KumayasBelum ada peringkat
- Artikel PolitikDokumen5 halamanArtikel PolitikArifBelum ada peringkat
- Bab 1 Affan GaffarDokumen5 halamanBab 1 Affan GaffarAlifahIreneMBelum ada peringkat
- Ringkasan Mata Kuliah Universitas Terbuka: Nama M. K: Sistem Kepartaian & Pemilu Kode M. K: IPEM 4318Dokumen15 halamanRingkasan Mata Kuliah Universitas Terbuka: Nama M. K: Sistem Kepartaian & Pemilu Kode M. K: IPEM 4318api-156790818100% (1)
- Tugas Review Buku Merancang Arah Baru DemokrasiDokumen5 halamanTugas Review Buku Merancang Arah Baru DemokrasiPemain 01Belum ada peringkat
- Tugas CRITICAL REVIEW UaiDokumen16 halamanTugas CRITICAL REVIEW UaiSeno Ones100% (2)
- Tantangan Demokrasi Di IndonesiaDokumen2 halamanTantangan Demokrasi Di Indonesiahalwa arkan safariBelum ada peringkat
- Review BukuDokumen9 halamanReview BukuAnonymous qkC3yrHVFBelum ada peringkat
- Tugas 2 Ilmu PolitikDokumen5 halamanTugas 2 Ilmu PolitikMULIA Almanisa100% (2)
- Makalah Politik 1Dokumen13 halamanMakalah Politik 1ROFHI SMARTBelum ada peringkat
- Critical Review Partai Politik Karya Ramlan Surbakti - Teddy Chrisprimanata Putra PDFDokumen9 halamanCritical Review Partai Politik Karya Ramlan Surbakti - Teddy Chrisprimanata Putra PDFTeddy Chrisprimanata PutraBelum ada peringkat
- Makalah DemokrasiDokumen21 halamanMakalah DemokrasiChristian Erikson SitioBelum ada peringkat
- Praditya Sukma Ramadhan - E-Learning PKN (Demokrasi)Dokumen5 halamanPraditya Sukma Ramadhan - E-Learning PKN (Demokrasi)PRADITYABelum ada peringkat
- Patologi PolitikDokumen3 halamanPatologi PolitikDewa RajaBelum ada peringkat
- Jerat OligarkiDokumen4 halamanJerat Oligarkiפרדו גולטוםBelum ada peringkat
- Resume Birokrasi Dan Dinamika KekuasaanDokumen12 halamanResume Birokrasi Dan Dinamika KekuasaanAlvita Kumara WasistiyanaBelum ada peringkat
- Birokrasi Sebagai Kekuatan Politik Di Indonesia Chapter IIIDokumen19 halamanBirokrasi Sebagai Kekuatan Politik Di Indonesia Chapter IIIWidyaIchaLestari67% (3)
- ID Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke MasaDokumen14 halamanID Demokrasi Indonesia Dari Masa Ke MasabrianBelum ada peringkat
- Reformasi ParpolDokumen5 halamanReformasi ParpolImam MuharrorBelum ada peringkat
- Budaya Politik Di IndonesiaDokumen6 halamanBudaya Politik Di IndonesiaLilik Sayank DyaBelum ada peringkat
- Jurnal Ilmu Pemerintahan Baru Koreksi Last 36 46Dokumen11 halamanJurnal Ilmu Pemerintahan Baru Koreksi Last 36 46Ardhiyanti HasibuanBelum ada peringkat
- PKNDokumen4 halamanPKNSarah Ummah MBelum ada peringkat
- Essay DemokrasiDokumen10 halamanEssay DemokrasiTriana Anggun SaputriBelum ada peringkat
- Tugas Revisi Demokrasi Sahda Sabilah LuhtansaDokumen9 halamanTugas Revisi Demokrasi Sahda Sabilah LuhtansaSahda Sabilah luhtansaBelum ada peringkat
- 4 Bab1Dokumen40 halaman4 Bab1Ulqia AkmamBelum ada peringkat
- Makalah Teori PolitikDokumen11 halamanMakalah Teori Politikjita olisa83% (6)
- PIPOLDokumen3 halamanPIPOLFarahBelum ada peringkat
- ZALFAVIOLINA UASIlpolDokumen6 halamanZALFAVIOLINA UASIlpolzalfaBelum ada peringkat
- Parti PolitikDokumen15 halamanParti PolitikHajjar AdenanBelum ada peringkat
- PolitikrabunayamwajahbarudemokrasiindonesiaDokumen18 halamanPolitikrabunayamwajahbarudemokrasiindonesiaMochammad Rizki FerdiansyahBelum ada peringkat
- Sistem Politik Indonesia Nama Kelompok: Nurul Atira Fajrin Daurin Putri MudiraDokumen7 halamanSistem Politik Indonesia Nama Kelompok: Nurul Atira Fajrin Daurin Putri MudiraDaurin mudiraBelum ada peringkat
- UntitledDokumen2 halamanUntitledAldi ImmanuelBelum ada peringkat
- Dasar-Dasar Politik Rafi IkrarDokumen4 halamanDasar-Dasar Politik Rafi IkrarRafa FadhilahBelum ada peringkat
- OLLE TORNQUIST - Kaum Demokrasi Versus ElitDokumen5 halamanOLLE TORNQUIST - Kaum Demokrasi Versus ElitRudi HartonoBelum ada peringkat
- Perspektif Orde BaruDokumen4 halamanPerspektif Orde BaruDyah Ayu WirantiBelum ada peringkat
- Resume Pak KisnoDokumen10 halamanResume Pak KisnoBerliana E GunturBelum ada peringkat
- MateriDokumen28 halamanMateriRika Graha FBelum ada peringkat
- Tugas 1 P.PKN DI SDDokumen5 halamanTugas 1 P.PKN DI SDnovitapuji lestaris1996Belum ada peringkat
- Pertanyaan Demokrasi PancasilaDokumen4 halamanPertanyaan Demokrasi PancasilaYaso SaputraBelum ada peringkat
- Demokrasi Di Bidang Ekonomi Dan BudayaDokumen5 halamanDemokrasi Di Bidang Ekonomi Dan BudayahitmeplissBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan: Kata PengantarDokumen5 halamanBab I Pendahuluan: Kata PengantarMoga JomangBelum ada peringkat
- Parpol PDFDokumen52 halamanParpol PDFBecka AjibBelum ada peringkat
- Gita AfwahDokumen13 halamanGita Afwahdestya renata ramadhiniBelum ada peringkat
- Partisipasi Politik Menurut Jurgen HabermasDokumen9 halamanPartisipasi Politik Menurut Jurgen Habermaslittle flowerBelum ada peringkat
- Ipem4437 3 M1Dokumen59 halamanIpem4437 3 M1kurniannBelum ada peringkat
- Sistem Politik Yang Berlaku Di IndonesiaDokumen11 halamanSistem Politik Yang Berlaku Di IndonesiaHusein NovalBelum ada peringkat
- Politik & Problematika DemokrasiDokumen7 halamanPolitik & Problematika Demokrasiokpay.infoBelum ada peringkat
- Tugas Pertemuan 8-Muhamad Qeisya Hanif-22338054Dokumen4 halamanTugas Pertemuan 8-Muhamad Qeisya Hanif-22338054Muhamad Qeisya HanifBelum ada peringkat
- Parpol 1Dokumen11 halamanParpol 1Perdianus DBelum ada peringkat
- Pemikiran Politik Negara BerkembangDokumen5 halamanPemikiran Politik Negara BerkembangFanji MangarajaBelum ada peringkat
- Makalah TPP Sistem Politik Gabriel AlmondDokumen14 halamanMakalah TPP Sistem Politik Gabriel AlmondFanji Mangaraja100% (1)
- Makalah Pemikiran Politik Di Negara BerkembangDokumen8 halamanMakalah Pemikiran Politik Di Negara BerkembangFanji MangarajaBelum ada peringkat
- Melawan Kapitalisasi KecantikanDokumen4 halamanMelawan Kapitalisasi KecantikanFanji MangarajaBelum ada peringkat
- Soal UAS - Pengantar Ilmu Hukum - Kelp A - Edi RoheidiDokumen1 halamanSoal UAS - Pengantar Ilmu Hukum - Kelp A - Edi RoheidiFanji MangarajaBelum ada peringkat
- Resume Partai Politik Dan Birokrasi Di Indonesia (Hirla Marsalino 2017210002)Dokumen7 halamanResume Partai Politik Dan Birokrasi Di Indonesia (Hirla Marsalino 2017210002)Fanji MangarajaBelum ada peringkat
- CV Format BaruDokumen39 halamanCV Format BaruAndini KartikasariBelum ada peringkat