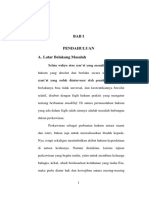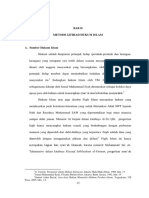8-Nafkah Batin
Diunggah oleh
Aant Asfihani0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
171 tayangan5 halamanArtikel ini membahas tentang nafkah batin yang didefinisikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri. Beberapa sumber fikih menyebutkan bahwa hubungan seksual merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi suami. Namun, istilah "nafkah batin" belum ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih.
Deskripsi Asli:
Judul Asli
8-nafkah batin
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniArtikel ini membahas tentang nafkah batin yang didefinisikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri. Beberapa sumber fikih menyebutkan bahwa hubungan seksual merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi suami. Namun, istilah "nafkah batin" belum ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
171 tayangan5 halaman8-Nafkah Batin
Diunggah oleh
Aant AsfihaniArtikel ini membahas tentang nafkah batin yang didefinisikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan seksual istri. Beberapa sumber fikih menyebutkan bahwa hubungan seksual merupakan salah satu hak istri yang harus dipenuhi suami. Namun, istilah "nafkah batin" belum ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih.
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 5
Menuntut Nafkah Batin, Mungkinkah?
Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Apabila kita mendengar kata “nafkah” biasanya selalu dikonotasikan dengan
salah satu kewajiban suami yang paling utama, yaitu memberi nafkah istri yang biasanya
juga terbatas pada kebutuhan istri untuk keperluan hidup sehari-hari, seperti makan
minum atau uang. Padahal, jika kita telusuri cakupan nafkah lebih dari itu. Kata nafkah
mempunyai cakupan yang lebih luas dari sekedar kewajiban suami. Sebagai tambahan
bahan informasi, berikut mari kita telusuri asal muasal istilah nafkah.
Penulis sengaja mengutip ulang sebuah wacana mengenai nafkah yang ditulis
oleh Dzulkifli Hadi Imawan, yang mengutip dari berbagai sumber mengenai definisi
nafkah ini dalam salah satu tulisan yang berjudul Fikih Nafkah. Dengan mengutip dari
berbagai referensi, secara bahasa, kata nafkah berasal dari bahasa arab ( ) نفقةyang berasal
dari kata nafaqa dan berimbuhan hamzah menjadi: anfaqa-yunfiqu-infak atau nafaqah.
Dalam Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, sebagaimana dikutip oleh Murtadla al-Zabidi
mendifinisikan nafkah adalah harta yang diberikan kepada diri sendiri atau keluarga. Kata
nafkah juga sering dilafalkan dengan infak yang diambil dari akar kata yang sama
“nafaqa”.
Dan dalam Lisanu al-‘Arab, Ibnu Manzhur menjelaskan bahwa kata nafkah atau infak
merupakan sinonim kata shadaqah dan ith’am (memberi makan). Infak dinamakan juga
sadaqah jika seseorang mengeluarkan hartanya dengan kejujuran (keikhlasan) dari
hatinya. Syaikh Muhammad Ali Ibnu Allan dalam kitab Dalil al-Falihin li Thuruqi
Riyadi al-Shahilin (penjelasan syarah kitab riyadu al-Shalihin karya Imam Nawawi dalam
bab al-Nafaqah), menjelaskan nafkah sebagai segala pemberian baik berupa pakaian,
harta, dan tempat tinggal kepada keluarga yang menjadi tanggungannya baik istri, anak,
dan juga pembantu.
Dengan mengacu kepada wacana di atas, dapat disimpulkan bahwa pembicaraan
mengenai nafkah ini pasti selalu terdapat 3 unsur, yaitu: 1. Yang mengeluarkan nafkah
(seperti suami, orang tua, atau anak), 2. Yang menerima nafkah (istri, orang tua, anak,
atau pembantu), dan 3. Benda yang dijadikan nafkah (barang, uang, makanan, dan setiap
yang diperlukan manusia dalam hal ini setidaknya yang dapat digunakan untuk
memenuhi kebutuhan dasar manusia).
Nafkah bathin
Sejauh hasil penulusuran kepustakaan yang sempat terjangkau, selama ini belum
ditemukan satu literatur (fikih) pun yang menyebut istilah “nafkah bathin” sebagai salah
satu lembaga hukum. Apalagi menjadi salah item kewajiban suami kepada istrinya. Akan
tetapi, istilah demikian memang sering kita dengar pada masyarakat Indonesia.
Penyebutannya sering dikaitkan dengan salah satu kewajiban suami kepada istri, yaitu
“kewajiban memberikan nafkah lahir dan nafkah batin”. Nafkah lahir dimaksudkan untuk
menyebut pemberian suami berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal serta
keperluan lain yang dibutuhkan oleh istri. Sedangkan nafkah batin lazim digunakan
menyebut kewajiban suami yang bisanya dikonotasikan dengan “hubungan seksual”.
Meskipun tidak secara spesifik disebut dalam kitab-kitab fikih akan tetapi tampaknya hal
tersebut memang dimungkinkan.
Sebagaimana kita ketahui, hubungan suami istri ialah ikatan suci yang di
dalamnya terdapat berbagai macam tuntunan dari syari’at. Aneka tuntutan syariat ini
bisanya terformulasi dalam bentuk “hak dan kewajiban”. Suami punya hak kepada
istrinya tetapi pada saat yang sama, istri pun punya hak dari suaminya. Hak dan
kewajiban suami istri ini oleh syariat sengaja dipatok secara seimbang. Apa yang
menjadi hak suami pada saat yang sama menjadi kewajiban istri dan sebaliknya. Apa
yang menjadi kewajiban istri, oleh karena menjadi hak suami , suami boleh menuntutnya.
Dan, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban suami, karena menjadi hak istri, istri pun
boleh menuntutnya.
Dalam konteks pembicaraan menganai hak istri, lantas meliputi apa saja hak istri
tersebut?
Seorang pakar fikih kontemporer dari Syiria, Syeikh Wahbah al-Zuhaily dalam
kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu Juz IX, halaman 6832 menulis sebagai berikut:
والعدل، وهي إحسان العشرة والمعاملة الطيبة: وحقوق غير مالية،للزوجة حقوق مالية وهي المهر والنفقة
Artinya: “Bagi istri terdapat beberapa hak yang bersifat materi berupa mahar dan
nafkah dan hak-hak yang bersifat non materi seperti memperbagus dalam menggauli dan
hubungan yang baik serta berlaku adil.”
Menurut pendapat tersebut jelas, bahwa secara garis besar istri memupunyai 2
macam hak dari suaminya, yaitu hak yang bersifat materi dan hak yang bersifat immateri.
Hak yang bersifat materi sebagaimana telah disinggung di atas, berupa benda-benda yang
berwujud fisik untuk menunjang kelangsungan hidup berkeluarga. Sedangkan hak
bersifat immateri pada pokoknya berupa perbuatan suami apa pun yang harus dilakukan
yang muaranya tertuju kepada perasaan-perasaan positif, seperti bahagia, ketenangan, dan
ketentaraman jiwa. Dalam fikih munakahat biasanya sikap demikian sering disebut
dengan istilah “al-mu’asyarah bi al-ma’ruf” yang penjabarannya dalam dunia nyata di
samping bisa bervariasi dan sesuai dengan perkembangan zaman juga bisa bersifat
sangat personal (individual).
Dengan pendekatan hak dan kewajiban ini, jelas hubungan seksual jika istri
memerlukan memang dapat menjadi salah satu hak istri yang juga harus ditunaikan oleh
suami. Pemikiran demikian jelas mendapatkan legitimasinya, ketika ada wacana fikih
mengenai kebolehan istri mengajukan fasakh dengan alasan suaminya tidak mampu lagi
memberikan kebutuhan seks kepada istrinya. Dalam konteks suami beristri lebih seorang
(poligini), kewajiban menggauli istri dengan porsi tertentu, menjadi salah satu item suami
dapat dikualifikasikan sebagai suami yang adil. Para pakar psikologi pada umumnya juga
berpendapat bahwa keharmonisan menjadi kunci utama keberhasilan hubungan rumah
tangga. Untuk mencapai itu, setiap pasangan hendaknya menjalin kemesraan satu sama
lain yang salah satunya dengan melakukan hubungan intim (seks).
Dalam literatur juga terdapat wacana tentang berapa lama seorang suami boleh tidak
menggauli istrinya. Ada yang berpendapat 1 bulan, ada yang berpendapat maksimal 4
bulan. Dalam sebuah riwayat, bahkan Khalifah Umar bin Khattab juga pernah melakukan
(semacam) ’riset’ mengenai hal ini.
Sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hafsh dari Zaid bin Aslam, bahwa suatu
malam ketika Khalifah Umar sedang ronda, ia lewat di depan rumah seseorang. Dari
rumah itu terdengar suara seorang perempuan terdengar lirih sedang bersenandung pilu
dengan untaian syair:
Malam ini terasa panjang
Sunyi senyap hitam kelam
Lama aku tiada kekasih
Yang kucumbu dan kurayu
Khalifah Umar pun lalu menanyakan kepada orang yang kebetulan berpapasan, siapa
gerangan perempuan itu. Darinya memperoleh informasi, bahwa perempuan tersebut
adalah “Fulanah”, istri seorang prajurit yang sedang berjuang di medan jihad. Keesokan
harinya, Khalifah Umar bersurat kepada komandan di lapangan agar suami “Fulanah”
segera pulang ke rumah.
Untuk meyakinkan dirinya, beliau pun mencari tahu tentang berapa lama sebenarnya
seorang perempuan (istri) dapat ‘menahan rindu’ kepada suaminya. Khalifah yang juga
bergelar al-Faruq itu pun lantas mengunjungi rumah putri kandungnya, Hafshah.
"Wahai, putriku, berapa lama seorang perempuan mampu menahan (sabar) ditinggal
pergi suaminya?", tanya sang khalifah setelah berbasa-basi. Awalnya, Hafshah terkejut
dan tersipu malu mendengar pertanyaan yang tak disangka itu. "Subhanallah. Orang
seperti Ayah bertanya kepada saya tentang soal-soal ini?" "Kalau misalnya bukan karena
kepentingan umat, tentu saya tidak akan menanyakan hal ini kepadamu," kata Umar,
melanjutkan. Setelah mendapatkan pengertian, sang putri pun menjawab, bahwa ada
rentang waktu sekitar lima atau enam bulan kesabaran seorang istri untuk menunggu
suaminya pulang. Sejak saat itu, Khalifah Umar menetapkan waktu tugas bagi seluruh
prajurit Muslim di medan perang tidak lebih dari enam bulan.
Dari peristiwa yang biasanya menjadi salah satu dalil hukum ila’ itu tampaknya
kehadiran suami di ranjang, menjadi salah satu kebetuhuhan (primer) istri. Oleh karena
menjadi kebutuhan, dalam konteks suami istri tampaknya hubungan seksual, juga dapat
dikategorikan sebagai “nafkah batin” yang dalam konteks pendapat al-Zuhaily tersebut
merupakan salah satu hak istri yang berkaitan dengan dengan “hak immateri”.
Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa sebagai hak, dalam konteks
peradilan (qadha’iy) jika tidak ditunaikan, memperoleh ‘jatah’ hubungan intim tentu bisa
saja dituntut istri kalau istri mau. Tetapi dalam kasus perceraian istri yang sudah dalam
pusaran perselisihan itu, jelas tidak mungkin menuntut hak tersebut dalam bentuk
perbuatan. Istri biasanya menuntut hak tersebut dalam bentuk “ganti rugi”. Dalam
konteks peradilan, sebagai orang yang terusik rasa keadilannya, sikap istri yang demikian
tentu tidak dilarang. Akan tetapi, yang jelas, mudahnya istri menulis tuntutan ‘ganti rugi’
nafkah batin itu, tentu tidak semudah hakim memberikan jawaban hukum dalam bentuk
putusan. Sebab, di dalamnya mengandung persoalan hukum materiil (kekinian) yang
pemecahannya tentu akan melibatkan pergulatan pemikiran hukum yang tidak ringan.
Selamat berijtihad.
BIO DATA PENULIS
Nama : Drs.H. ASMU’I SYARKOWI, M.H.
Tempat & Tgl Lahir : Banyuwangi, 15 Oktober 1962
NIP : 19621015 199103 1 001
Pangkat, gol./ruang : Pembina Utama Madya, IV/d
Pendidikan : S-1 Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 1988
S-2 Ilmu Hukum Fak Hukum UMI Makassar 2001
Hobby : Pemerhati masalah-masalah hukum, pendidikan, dan seni;
Pengalaman Tugas : - Hakim Pengadilan Agama Atambua 1997-2001
-Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2001-2004
- Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2004-2007
- Hakim Pengadilan Agama Jember Klas I A 2008-2011
- Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Klas IA 2011-2016
- Hakim Pengadilan Agama Lumajang Klas IA 2016-2021
- Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A 2021-2022.
Sekarang : Hakim Tinggi PTA Jayapura, 9 Desember 2022- sekarang
Alamat : Pandan, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi
Alamat e-Mail : asmui.15@gmail.com
Anda mungkin juga menyukai
- DziharkahDokumen10 halamanDziharkahdrs surosoBelum ada peringkat
- Uinsa,+journal+manager,+2 +salamun+ (17-34)Dokumen18 halamanUinsa,+journal+manager,+2 +salamun+ (17-34)Candra AzhariBelum ada peringkat
- Modul Hi TM-6Dokumen20 halamanModul Hi TM-6sofyanansorish11Belum ada peringkat
- Hukum Keluarga Islam Didunia IslamDokumen6 halamanHukum Keluarga Islam Didunia IslamSYAHRUL SHABRY50% (2)
- BAB I Satu Teisis B5Dokumen38 halamanBAB I Satu Teisis B5Ahmad abdul Halim shiddiqBelum ada peringkat
- Hak Dan Kewajiban Suami Istri 4Dokumen22 halamanHak Dan Kewajiban Suami Istri 4Erniyanti Puspita SariBelum ada peringkat
- Bab Ii - 2018451ihDokumen16 halamanBab Ii - 2018451ih44sntaBelum ada peringkat
- Nafkah Istri Karir Dalam IslamDokumen8 halamanNafkah Istri Karir Dalam IslamCuccon AyipinBelum ada peringkat
- Hak Nafkah Isteri Dalam Hadis Dan KhiDokumen18 halamanHak Nafkah Isteri Dalam Hadis Dan Khisurade kuaBelum ada peringkat
- Bil Dalil: Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami Aa SofyanDokumen28 halamanBil Dalil: Analisis Pemikiran Musdah Mulia Terhadap Keharaman Poligami Aa SofyanAiyna ZukhrufahBelum ada peringkat
- Nafkah Batin Dalam Pernikahan FixDokumen17 halamanNafkah Batin Dalam Pernikahan FixUsaid As-shidiqBelum ada peringkat
- 3751 8659 1 SMDokumen18 halaman3751 8659 1 SM6mad8Belum ada peringkat
- Uas Resume Hukum Kewarisan IslamDokumen8 halamanUas Resume Hukum Kewarisan IslamMnovals PrasetioBelum ada peringkat
- Wali Nikah PDFDokumen21 halamanWali Nikah PDFRusdi YantoBelum ada peringkat
- Bab IvDokumen48 halamanBab IvFilzah Anisa MayariBelum ada peringkat
- Sumber Hukum IslamDokumen8 halamanSumber Hukum IslamBella Ananda IslamiBelum ada peringkat
- Makalah Hukum PerdataDokumen7 halamanMakalah Hukum Perdatasuzela widya sariBelum ada peringkat
- Makala HDokumen20 halamanMakala HAyah Irsyad Al-HaqBelum ada peringkat
- Makalah Kaidah Ushuliya1Dokumen14 halamanMakalah Kaidah Ushuliya1AnggaPMBelum ada peringkat
- Fiqh Munakahat Perbandingan Tentang Pengertian MenikahDokumen12 halamanFiqh Munakahat Perbandingan Tentang Pengertian MenikahAnggia Juliana0% (1)
- 2187 5216 1 PBDokumen17 halaman2187 5216 1 PBYasmin IzdiharBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Kel 2Dokumen18 halamanMakalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia Kel 2sarah lisfizaBelum ada peringkat
- Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam DaDokumen25 halamanPoligami Dalam Perspektif Hukum Islam DaNUR AINAA NAJIHAH BINTI MOHD ZAWAWI MoeBelum ada peringkat
- Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Islam - FH UPHDokumen14 halamanPokok-Pokok Hukum Perkawinan Dan Kewarisan Islam - FH UPHbayu imantoroBelum ada peringkat
- Bab2 PDFDokumen36 halamanBab2 PDFNurul HasanahBelum ada peringkat
- Bab I, Iii, Iii, Pustaka PDFDokumen11 halamanBab I, Iii, Iii, Pustaka PDFqk2w72gp78Belum ada peringkat
- ID Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh Telaah HistorisDokumen11 halamanID Konsep Urf Dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh Telaah Historisall animeBelum ada peringkat
- Pandangan 4 Mazhab Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Dan HukumnyaDokumen13 halamanPandangan 4 Mazhab Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Serta Akibat Dan Hukumnyagian septianiBelum ada peringkat
- Tugas Prof AsfaDokumen7 halamanTugas Prof AsfaMuhammad Yusuf IsmailBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 6 Ushul FiqhDokumen15 halamanMakalah Kelompok 6 Ushul FiqhFajar SeptianBelum ada peringkat
- Bab 1 PendahuluanDokumen11 halamanBab 1 PendahuluanAsyari ZyBelum ada peringkat
- Jurnal Muhajir Dan FitrohDokumen8 halamanJurnal Muhajir Dan FitrohFitrotul HasanahBelum ada peringkat
- Bab I - 4Dokumen20 halamanBab I - 4dhanny projectBelum ada peringkat
- Pengertian Hukum Keluarga IslamDokumen4 halamanPengertian Hukum Keluarga Islam210202110133Belum ada peringkat
- KhuluDokumen12 halamanKhuluMilda SintiaBelum ada peringkat
- 469-Article Text-1408-4-10-20220101Dokumen26 halaman469-Article Text-1408-4-10-20220101Muhammad Ali Al AwshatBelum ada peringkat
- 1207 2703 4 PBDokumen12 halaman1207 2703 4 PBMuhammad RafiBelum ada peringkat
- Analisis JurnalDokumen3 halamanAnalisis JurnalZeze annisaBelum ada peringkat
- Isi Ushul FiqhDokumen22 halamanIsi Ushul FiqhSiti RahmahBelum ada peringkat
- Artikel Pernikahan AniDokumen5 halamanArtikel Pernikahan AniNur supri AniBelum ada peringkat
- Titik Temu Khilafiah Dalam Islam RevisiDokumen22 halamanTitik Temu Khilafiah Dalam Islam RevisiKevin FarrellBelum ada peringkat
- Hikmah PernikahanDokumen34 halamanHikmah PernikahanGantiara Assyfa FadilahBelum ada peringkat
- RANGKUMANDokumen5 halamanRANGKUMANWinaadwBelum ada peringkat
- Pembahasan Rujuk RevisiDokumen18 halamanPembahasan Rujuk RevisiUkhti FeeBelum ada peringkat
- Makalah Pergaulan Suami IstriDokumen17 halamanMakalah Pergaulan Suami IstriANDRIAN AKBARBelum ada peringkat
- Ringkasan Hukum Warisan Islam Salsabilla 2010117346Dokumen6 halamanRingkasan Hukum Warisan Islam Salsabilla 2010117346Salsa BilaBelum ada peringkat
- Ijma' Dan QiyasDokumen4 halamanIjma' Dan QiyasVivi yenni aryantiBelum ada peringkat
- Resume Materi IstihabDokumen5 halamanResume Materi IstihabRodziatun YulikhaBelum ada peringkat
- Istidlal PDFDokumen42 halamanIstidlal PDFHanifah Putri AksiomatikaBelum ada peringkat
- Agama Qiyas TaklifiDokumen26 halamanAgama Qiyas TaklifiKeysya Alya DinayaBelum ada peringkat
- Nufanbalafif,+journal+manager,+3 +Haris+HidayatullohDokumen23 halamanNufanbalafif,+journal+manager,+3 +Haris+HidayatullohAulia RahmiBelum ada peringkat
- Fiqih Keluarga - Ustad Muhsinin Fauzi, LC, MMDokumen45 halamanFiqih Keluarga - Ustad Muhsinin Fauzi, LC, MMMajelis Taklim TelkomselBelum ada peringkat
- Metode Ijtihad Hukum Islam PDFDokumen31 halamanMetode Ijtihad Hukum Islam PDFarniBelum ada peringkat
- Irhamullah - Uts AgamaDokumen6 halamanIrhamullah - Uts AgamaGood ByeeBelum ada peringkat
- Uts HK Waris Dela 2002010092Dokumen3 halamanUts HK Waris Dela 2002010092Dela WardahBelum ada peringkat
- Hpdki 2Dokumen10 halamanHpdki 20100 Putri SabrinaBelum ada peringkat
- Anitania M.A - TADokumen23 halamanAnitania M.A - TAsisca saniscaraBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok Vi-1Dokumen19 halamanMakalah Kelompok Vi-1ahmadzakifuadmahrusBelum ada peringkat
- Definisi UshulDokumen12 halamanDefinisi UshulAizuddin HamidBelum ada peringkat
- Https Unwiku - Ac.id Wp-Content Uploads 2017 07 Sertifikat-Akreditasi-Universitas-UNWIKU-Purwokerto PDFDokumen1 halamanHttps Unwiku - Ac.id Wp-Content Uploads 2017 07 Sertifikat-Akreditasi-Universitas-UNWIKU-Purwokerto PDFAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Uraian PekerjaanDokumen1 halamanUraian PekerjaanAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Brosur Hak-Hak Perempuan & Anak Pasca PerceraianDokumen2 halamanBrosur Hak-Hak Perempuan & Anak Pasca PerceraianAant Asfihani100% (1)
- MOOC - All QuestionsDokumen49 halamanMOOC - All QuestionsAant Asfihani100% (6)
- AnalisisisukontemporerDokumen79 halamanAnalisisisukontemporerAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Sertifikat Akreditasi TI UMP Jan 2022 Jan 2027 PDFDokumen1 halamanSertifikat Akreditasi TI UMP Jan 2022 Jan 2027 PDFAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Contoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.03Dokumen1 halamanContoh Soal Latihan Ujian Advokat PERADI - Ep.03Syukni Tumi Pengata71% (7)
- Soal-Try-Out-Ujian-Advokat 1Dokumen20 halamanSoal-Try-Out-Ujian-Advokat 1yudistya putra denisBelum ada peringkat
- Surat Pernyataan Tidak Klaim Ke Jasa RaharjaDokumen1 halamanSurat Pernyataan Tidak Klaim Ke Jasa RaharjaAant Asfihani67% (3)
- Surat Keterangan PascoDokumen1 halamanSurat Keterangan PascoAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Yang Diancam Sebagai Perbuatan Pidana Dalam UndangDokumen3 halamanYang Diancam Sebagai Perbuatan Pidana Dalam UndangAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Form PanwasluDokumen12 halamanForm PanwasluAant Asfihani67% (3)
- UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang KetenagalistrikanDokumen43 halamanUU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikanangin_majBelum ada peringkat
- PengosonganDokumen3 halamanPengosonganAant AsfihaniBelum ada peringkat
- SainsDokumen1 halamanSainsAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Lama RanDokumen1 halamanLama RanAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Proposal Penyuluhan KesehatanDokumen7 halamanProposal Penyuluhan KesehatanAant AsfihaniBelum ada peringkat
- LPJ KaDokumen2 halamanLPJ KaAant AsfihaniBelum ada peringkat
- I. Ditinjau Dari Sudut Hukum Privat DanDokumen5 halamanI. Ditinjau Dari Sudut Hukum Privat DanSugiarto_Mas_7766Belum ada peringkat
- Keamanan Nasional An Negara - Koesnanto AnggoroDokumen10 halamanKeamanan Nasional An Negara - Koesnanto AnggoroAant AsfihaniBelum ada peringkat
- Putusan Nomor 31-1Dokumen172 halamanPutusan Nomor 31-1Aant AsfihaniBelum ada peringkat