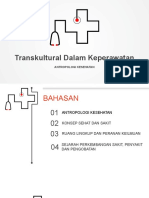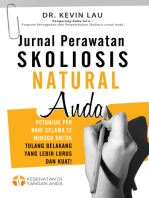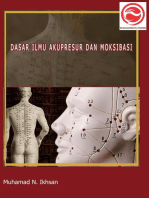LP KDM - PKK
LP KDM - PKK
Diunggah oleh
21102087Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
LP KDM - PKK
LP KDM - PKK
Diunggah oleh
21102087Hak Cipta:
Format Tersedia
LAPORAN PENDAHULUAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA
KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN PADA TN. A (59 tahun)
DENGAN DIAGNOSA MEDIS DIABETES MELITUS TIPE II
DI RUANG MELATI RS Tk. III BALADHIKA HUSADA
NAMA : Yuni Wardana
NIM : 21102119
PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS dr. SOEBANDI
JEMBER
2024
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Pengertian
Rasa aman didefinisikan oleh Maslow dalam Potter & Perry (2006)
sebagai sesuatu kebutuhan yang mendorong individu untuk memperoleh
ketentraman, kepastian dan keteraturan dari keadaan lingkungannya yang
mereka tempati. Keamanan adalah kondisi bebas dari cedera fisik dan
psikologis (Potter & Perry, 2006).
Kenyamanan rasa nyaman adalah suatu keadaan telah terpenuhinya
kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman (suatu kepuasan
yang meningkatkan penampilan sehari-hari), kelegaan (kebutuhan telah
terpenuhi), dan transenden (keadaan tentang sesuatu yang melebihi masalah
dan nyeri) (Kolcaba, 1992 dalam Potter & Perry,2006).
Berbagai teori keperawatan menyatakan kenyamanan sebagai kebutuhan
dasar klien yang merupakan tujuan pemberian asuhan keperawatan. Konsep
kenyamanan mempunyai subjektifitas yang sama dengan nyeri. Setiap
individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial, spiritual, psikologis, dan
kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka menginterpretasikan dan
merasakan nyeri. Setiap individu memiliki karakteristik fisiologis, sosial,
spiritual, psikologis, dan kebudayaan yang mempengaruhi cara mereka
menginterpretasikan dan merasakan nyeri.
1.2 Kebutuhan Fisiologis Kebutuhan Rasa Aman dan Nyaman
Fisiologi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman adalah bagian penting
dari fungsi tubuh manusia yang terkait erat dengan sistem saraf, hormonal,
dan psikologis. Rasa aman dan nyaman secara fisiologis dapat dipahami
melalui beberapa mekanisme dalam tubuh manusia, yaitu sebagai berikut.
1. Sistem Saraf: Sistem saraf otonom, yang terbagi menjadi sistem saraf
simpatis dan parasimpatik, memainkan peran kunci dalam regulasi
respons tubuh terhadap situasi yang mengancam atau menenangkan. Saat
merasa aman dan nyaman, sistem parasimpatik aktif, menyebabkan
penurunan denyut jantung, pernapasan yang dalam dan teratur, serta
relaksasi otot. Sebaliknya, dalam situasi stres atau ketegangan, sistem
saraf simpatis mengaktifkan respons "fight or flight", meningkatkan
denyut jantung, mempercepat pernapasan, dan mempersiapkan tubuh
untuk bertindak.
2. Hormon: Hormon-hormon seperti oksitosin, serotonin, dan endorfin
berperan dalam menciptakan perasaan aman dan nyaman dalam tubuh.
Oksitosin, misalnya, dikenal sebagai "hormon cinta" karena terlibat
dalam pembentukan ikatan sosial dan emosional antara individu.
Serotonin, yang berperan dalam regulasi suasana hati dan tidur, juga
memainkan peran dalam merasa nyaman dan puas. Endorfin, hormon
"kebahagiaan" yang dilepaskan dalam respons terhadap aktivitas fisik
atau situasi menyenangkan, membantu mengurangi rasa sakit dan
meningkatkan perasaan kesejahteraan.
3. Respon Fisiologis Terhadap Lingkungan: Lingkungan fisik juga dapat
mempengaruhi fisiologi kebutuhan akan rasa aman dan nyaman.
Lingkungan yang nyaman, seperti suhu yang sesuai, pencahayaan yang
cukup, dan kebersihan, dapat memicu respons relaksasi dalam tubuh.
Sebaliknya, lingkungan yang tidak nyaman atau tidak aman, seperti
kebisingan berlebihan atau ancaman fisik, dapat mengaktifkan respons
stres dan ketegangan.
4. Keterkaitan dengan Kesehatan Mental: Fisiologi kebutuhan akan rasa
aman dan nyaman juga berkaitan erat dengan kesehatan mental.
Ketidakamanan atau ketidaknyamanan kronis dapat menyebabkan
gangguan tidur, gangguan pencernaan, peningkatan risiko penyakit
jantung, dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi.
5. Oksigen: Bahaya umum yang ditemukan dirumah adalah sistem
pemanasan yang tidak berfungsi dengan baik dan pembakaran 4 yang
tidak mempunyai sistem pembuangan akan menyebabkan penumpukan
karbondioksida.
1.3 Faktor Yang Mempengaruhi
Potter & Perry, 2006 menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi
keamanan dan keselamatan meliputi:
1. Emosi
Kondisi psikis dengan kecemasan, depresi, dan marah akan mudah
mempengaruhi keamanan dan kenyamanan.
2. Status Mobilisasi
Status fisik dengan keterbatasan aktivitas, paralisis, kelemahan otot, dan
kesadaran menurun memudahkan terjadinya resiko cedera.
3. Gangguan Persepsi Sensori
Adanya gangguan persepsi sensori akan mempengaruhi adaptasi
terhadaprangsangan yang berbahaya seperti gangguan penciuman dan
penglihatan.
4. Keadaan Imunitas
Daya tahan tubuh kurang memudahkan terserang penyakit.
5. Tingkat Kesadaran
Tingkat kesadaran yang menurun, pasien koma menyebabkan respon
terhadap rangsangan, paralisis, disorientasi, dan kurang tidur.
6. Informasi atau Komunikasi
Gangguan komunikasi dapat menimbulkan informasi tidak diterima
dengan baik.
7. Gangguan Tingkat Pengetahuan
Kesadaran akan terjadi gangguan keselamatan dan keamanan dapat
diprediksi sebelumnya.
8. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional
Antibiotik dapat menimbulkan resisten dan anafilaktik syok.
9. Status nutrisi
Keadaan kurang nutrisi dapat menimbulkan kelemahan dan mudah
menimbulkan penyakit, demikian sebaliknya dapat beresiko terhadap
penyakit tertentu.
10. Usia
Pembedaan perkembangan yang ditemukan diantara kelompok usia anak-
anak dan lansia mempengaruhi reaksi terhadap nyeri.
11. Jenis Kelamin
Secara umum pria dan wanita tidak berbeda secara bermakna dalam
merespon nyeri dan tingkat kenyamanannya.
12. Kebudayaan
Keyakinan dan nilai-nilai kebudayaan mempengaruhi cara individu
mengatasi.
1.4 Diagnosa Keperawatan
a. Nyeri Akut (D. 0077)
b. Ketidakstabilan Kadar Glukosa Darah (D.0027)
c. Risiko Infeksi (D. 0142)
1.5 Konsep keperawatan
1.1.1 Pengkajian
a. Identitas Klien
1. Data umum pasien meliputi: nama, umur, jenis kelamin,
agama, suku, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan,
alamat, no.RM, diagnosa medis, tanggal pengkajian, tanggal
masuk RS, DII.
2. Identitas penanggung jawab meliputi: Nama, umur, pekerjaan,
alamat dan hubungan dengan klien.
b. Riwayat Kesehatan
1. Keluhan utama
Selama pengumpulan riwayat kesehatan, perawat menanyakan
kepada pasien tentang tanda dan gejala yang dialami oleh
pasien. Setiap keluhan harus ditanyakan dengan detail kepada
pasien. disamping itu diperlukan juga pengkajian mengenai
keluhan yang disarasakan meliputi lama timbulnya.
2. Riwayat Penyakit Sekarang
Pada riwayat penyakit sekarang, perawat mengkaji apakah
gejala terjadi pada waktu yang tertentu saja, seperti sebelum
atau sesudah makan, ataupun setelah mencerna makanan
pedas dan pengiritasi dan setelah mencerna obat tertentu atau
setelah mengkonsumsi alhohol.
3. Riwayat kesehatan masa lalu
Untuk mengkaji riwayat penyakit dahulu atau riwayat
penyakit sebelumnya, perawat harus mengkaji apakah gejala
yang berhubungan dengan ansietas, stress, alergi, makan atau
minum terlalu banyak, atau makan terlalu cepat. Selain itu
perawat juga harus mengkaji adakah riwayat penyakit
lambung sebelumnya atau pembedahan lambung
4. Riwayat kesehatan keluarga
Dalam riwayat kesehatan keluarga perawat mengkaji riwayat
keluarga yang mengkonsumsi alkohol, mengidap gastritis,
mananyakan tentang penyakit yang pernah dialami oleh
keluarga.
c. Pola Hidup
1. Pola Persepsi
Kesehatan persepsi terhadap adanya arti kesehatan,
penatalaksanaan kesehatan serta pengatahuan tentang praktek
kesehatan.
2. Pola nutrisi
Mengidentifikasi masukan nutrisi dalam tubuh, balance cairan
serta elektrolit. Pengkajian meliputi: nafsu makan, pola
makan, diet, kesulitan menelan, mual, muntah, kebutuhan
jumlah zat gizi.
3. Pola eliminasi
Menjelaskan tentang pola fungsi ekskresi serta kandung kenih
dan kulit. Pengkajian yang dilakukan meliputi: kebiasaan
deddekasi, ada tidaknya masalah defekasi, masalah miksi
(oliguria, disuri), frekuensi defekasi dan miksi. Karakteristik
urine dan feses, pola input cairan, masalah bau badan.
4. Pola latihan-aktivitas
Menggambarkan tentang pola latihan, aktivitas, fumgsi
pernapasan. Pentingnya latihan atau gerak dalam keadaan
sehat maupun sakit, gerak tubuh dan kesehatan berhubungan
dengan satu sama lain. Kemampuan klien dalam menata
dirinya sendiri apabila tingkat kemampuannya: 19 0: mandiri,
1: dengan alat bantu, 2: dibantu orang lain, 3: dibantu orang
lain dan alat, 4: tergantung dalam melakukan ADL, kekuatan
otot dan ROM, riwayat penyakit jantung, frekuensi, irama dan
kedalaman napas, bunyi napas, riwayat penyakit paru.
5. Pola kognitif perseptual
Menjelaskan tentang persepsi sendori dan kognitif. Pola ini
meliputi pengkajian fungsi penglihatan, pendengaran,
perasaan, pembau dan kompensasinya terhadap tubuh. Dan
pola kognitif memuat kemampuan daya ingat klien terhadap
peristiwa peristiwa yang telah lama atau baru terjadi.
6. Pola istirahat dan tidur
Menggambarkan pola tidur serta istirahat pasien. Pengkajian
yang dilakukan pada pola ini meliputi: jam tidur siang dan
malam. pasien, masalah selama tidur, insomnia atau mimpi
uruk, penggunaan obat serta mengaluh letih.
7. Pola konsep diri-persepsi diri
Menggambarkan sikap tentan diri sendiri serta persepsi
terhadap kemampuan diri sendiri dan kemampuan konsep diri
yang meliputi: gambaran diri, harga diri, peran, identitas dan
ide diri sendiri.
8. Pola peran dan hubungan
Menggambarkan serta mengatahui hubungan pasien serta
peran pasien terhadap anggota keluarga serta dengan
masyarakat yang berada dalam lingkungan sekitar tempat
tinggalnya.
9. Pola reproduksi atau seksual
Menggambarkan tentang kepuasan yang dirasakan atau
masalah yang dirasakan dengan seksualitas. Selain itu
dilakukan juga pengkajian yang meliputi: dampak sakit
terhadap seksualitas, riwayat haid, pemeriksaan payudara
sendiri, riwayat penyakit hubungan seks, serta pemeriksaan
genetalia.
10. Pola keyakinan dan nilai
Menggambarkan tentang pola nilai dan keyakinan yang
dianut. Menerangkan sikap serta keyakinan yang dianaut oleh
klien dalam melaksanakan agama atau kepercayaan yang
dianut.
11. Pengkajian psikososial
Perubahan integritas ego yang ditemukan pada klien adalah
klien menyangkal, takut mati, perasaan ajal sudah dekat,
marah pada penyakit/perawatan yang tak perlu, kuatir tentang
keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Kondisi ini ditandai
dengan sikap menolak, menyangkal, cemas, kurang kontak
mata, gelisah, marah, perilaku menyerang, dan fokus pada diri
sendiri.
Interaksi sosial dikaji terhadap adanya stress karena
keluarga, pekerjaan, kesulitan biaya ekonomi dan kesulitan
koping dengan sresor yang ada, kegelisahan dan kecemasan
terjadi akibat gangguan oksigenasi jaringan,stress akibat
kesakitan bernapas dan pengetahuan bahwa jantung tidak
berfungsi dengan baik. Penurunan lebih lanjut dari curah
jantung dapat terjadi ditandai dengan adanya keluhan
insomnia atau tampak kebingungan.
d. Pemeriksaan Fisik
1. Ekspresi wajah
a. Menutup mata rapat-rapat
b. Buka matamu lebar-lebar
c. Menggigit bibir dibawah
2. Lisan
a. Menangis
b. Berteriak
3. Tanda-tanda Vital
a. Tekanan darah
b. Nadi
c. Pernapasan
4. Ekstremitas
Amati gerak tubuh pasien untuk mengalokasi tempat atau rasa
yang tidak nyaman.
1.1.2 Diagnosa Keperawatan, Kriteria Hasil dan Intervensi
Diagnosa
No. Tujuan dan Kriteria Hasil Intervensi
Keperawatan
1. Nyeri Akut Tingkat Nyeri (L.08066) Manajemen Nyeri
(D.0077) Tujuan: (I.08238)
Setelah dilakukan intervensi Tindakan:
selama 3x24 jam, maka tingkat Observasi
nyeri menurun, dengan kriteria 1. Identifikasi
hasil: lokasi,
Kriteria Hasil SA ST karakteristik,
Keluhan nyeri 2 5 durasi, frekuensi,
Meringis 2 5 kualitas,
Gelisah 2 5 intensitas nyeri
Kesulitan Tidur 2 5 2. Identifikasi skala
nyeri
3. Identifikasi
Ket: respons nyeri non
1 : Meningkat verbal
2 : Cukup meningkat 4. Identifikasi faktor
3 : Sedang yang
4 : Cukup menurun memperberat dan
5 : Menurun memperingan
nyeri
5. Identifikasi
pengetahuan dan
keyakinan tentang
nyeri
Terapeutik
1. Berikan Teknik
nonfarmakologis
untuk mengurangi
nyeri (mis:
TENS, hypnosis,
akupresur, terapi
music,
biofeedback,
terapi pijat,
aromaterapi,
Teknik imajinasi
terbimbing,
kompres
hangat/dingin,
terapi bermain)
2. Kontrol
lingkungan yang
memperberat rasa
nyeri (mis: suhu
ruangan,
pencahayaan,
kebisingan)
Edukasi
1. Jelaskan
penyebab,
periode, dan
pemicu nyeri
2. Jelaskan strategi
meredakan nyeri
3. Anjurkan
memonitor nyeri
secara mandiri
4. Anjurkan
menggunakan
analgetik secara
tepat
Kolaborasi
1. Kolaborasi
pemberian
analgetik, jika
perlu
2. Ketidakstabilan Kestabilan Kadar Glukosa Manajemen
Kadar Glukosa Darah (L.03022) Hiperglikemia
Darah (D.0027) Tujuan: (I.03115)
Setelah dilakukan intervensi Tindakan:
selama 3x24 jam, maka Observasi
kestabilan kadar glukosa 1. Identifikasi
darah meningkat, dengan kemungkinan
kriteria hasil: penyebab
Kriteria Hasil SA ST hiperglikemia
Koordinasi 2 5 2. Identifikasi situasi
Kadar glukosa 2 5 yang
dalam darah menyebabkan
kebutuhan insulin
Ket: meningkat (mis:
1 : Menurun penyakit
2 : Cukup menurun kambuhan)
3 : Sedang 3. Monitor kadar
4 : Cukup meningkat glukosa darah, jika
5 : Meningkat perlu
Terapeutik
1. Berikan asupan
cairan lokal
2. Konsultasi dengan
medis jika tanda
dan gejala
hiperglikemia
tetap ada atau
memburuk
Edukasi
1. Monitor kadar
glukosa darah, jika
perlu
2. Anjurkan
kepatuhan
terhadap diet dan
olahraga
3. Ajarkan
pengelolaan
diabetes (mis:
penggunaan
insulin, obat oral,
monitor asupan
cairan,
penggantian
karbohidrat, dan
bantuan
professional
kesehatan
Kolaborasi
1. Kolaborasi
pemberian insulin,
jika perlu
2. Kolaborasi
pemberian cairan
IV, jika perlu.
3. Risiko Infeksi Tingkat Infeksi (L.14137) Pencegahan Infeksi
(D.0142) Tujuan: (I.14539)
Setelah dilakukan intervensi Tindakan:
selama 3x24 jam, maka tingkat Observasi
infeksi menurun, dengan 1. Monitor tanda dan
kriteria hasil: gejala infeksi lokal
Kriteria Hasil SA ST dan sistemik.
Demam 1 5 Terapeutik
Kemerahan 1 5 1. Batasi jumlah
Nyeri 1 5 pengunjung
Bengkak 1 5 2. Berikan perawatan
kulit pada area
Ket: edema
1 : Meningkat 3. Cuci tangan
2 : Cukup meningkat sebelum dan
3 : Sedang sesudah kontak
4 : Cukup menurun dengan pasien dan
5 : Menurun lingkungan pasien
4. Pertahankan
teknik aseptic pada
pasien berisiko
tinggi.
Edukasi
1. Jelaskan tanda dan
gejala infeksi
2. Ajarkan cara
mencuci tangan
dengan benar
3. Anjurkan
meningkatkan
asupan nutrisi
Kolaborasi
1. Kolaborasi
pemberian
imunisasi, jika
perlu
DAFTAR PUSTAKA
Brunner & Suddarth. 2015. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah Edisi 12,
Volume 1. Jakarta: EGC.
Tim Pokja SDKI PPNI. 2017. Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia Edisi 1.
Dewan Pengurus Pusat PPNI: Jakarta Selatan.
Tim Pokja SLKI PPNI. 2018. Standar Luaran Keperawatan Indonesia Edisi 1.
Dewan Pengurus Pusat PPNI: Jakarta Selatan.
Tim Pokja SIKI PPNI. 2018. Standar Intervensi Keperawatan Indonesia Edisi 1.
Dewan Pengurus Pusat PPNI: Jakarta Selatan
Anda mungkin juga menyukai
- LP KDP Rasa Aman Dan NyamanDokumen14 halamanLP KDP Rasa Aman Dan NyamanPrima Regina100% (1)
- LP KDM Nyeri YahyaDokumen28 halamanLP KDM Nyeri YahyaGoogle GoogleBelum ada peringkat
- Askep TTG Rasa Aman Dan NyamanDokumen10 halamanAskep TTG Rasa Aman Dan NyamanSunardiBelum ada peringkat
- LP Keamanan Dan Kenyamanan PasienDokumen6 halamanLP Keamanan Dan Kenyamanan PasienMay MayBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan Kebutuhan Rasa Aman Dan Nyaman NyeriDokumen12 halamanLaporan Pendahuluan Kebutuhan Rasa Aman Dan Nyaman Nyerinovitri susantyBelum ada peringkat
- LP KDM 8Dokumen11 halamanLP KDM 8fatimatus ZahroBelum ada peringkat
- LAPORAN PENDAHULUAN ZuhermiDokumen14 halamanLAPORAN PENDAHULUAN Zuhermiahmad muhaiminBelum ada peringkat
- Makalah Sosiologi Dan Antropologi KesehatanDokumen18 halamanMakalah Sosiologi Dan Antropologi KesehatanDias JameelaBelum ada peringkat
- Konsep Sehat Sakit Paradigma (Recovered)Dokumen19 halamanKonsep Sehat Sakit Paradigma (Recovered)Chichin FazaroqhBelum ada peringkat
- Kep Das Present 3Dokumen10 halamanKep Das Present 3only meBelum ada peringkat
- Materi KDM 2Dokumen18 halamanMateri KDM 2Kirana TumiBelum ada peringkat
- Materi KDM 2Dokumen18 halamanMateri KDM 2Kirana TumiBelum ada peringkat
- LP KelompokDokumen16 halamanLP KelompokTriyasBelum ada peringkat
- Pemenuhan Rasa Aman Dan Nyaman - Semester 1Dokumen31 halamanPemenuhan Rasa Aman Dan Nyaman - Semester 1Fia HsnhBelum ada peringkat
- Antro KP 12Dokumen12 halamanAntro KP 12dayu ernaBelum ada peringkat
- Wa0005.Dokumen11 halamanWa0005.ZASKIAHBelum ada peringkat
- PERSEPSIDokumen12 halamanPERSEPSIRisca RetnoBelum ada peringkat
- Resume KONSEP KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN - FNTDokumen5 halamanResume KONSEP KEBUTUHAN RASA AMAN DAN NYAMAN - FNTValen MaselaBelum ada peringkat
- Materi Psikologi KesehatanDokumen97 halamanMateri Psikologi Kesehatanrifqi hamdaniBelum ada peringkat
- Antropologi KesehatanDokumen14 halamanAntropologi KesehatantaniaBelum ada peringkat
- Filosofi Keperawatan: Ns. Efrizal, S. Kep., M. SiDokumen37 halamanFilosofi Keperawatan: Ns. Efrizal, S. Kep., M. Simaharanidelta 6Belum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan NYERI AKUTDokumen7 halamanLaporan Pendahuluan NYERI AKUTChintya RahmawatiBelum ada peringkat
- Klasifikasi Kebutuhan Keselamatan Atau KeamananDokumen3 halamanKlasifikasi Kebutuhan Keselamatan Atau KeamananRIKA DEA ARIATI100% (1)
- Askep Gangguan Rasa NyamanDokumen29 halamanAskep Gangguan Rasa NyamanFaricha OktarinaBelum ada peringkat
- Definisi Konsep Sehat Sakit Menurut Dasar KeperawatanDokumen11 halamanDefinisi Konsep Sehat Sakit Menurut Dasar KeperawatanRida NintamiBelum ada peringkat
- Format Konsultasi KDM, LPDokumen28 halamanFormat Konsultasi KDM, LPMIFTAH JBR 124Belum ada peringkat
- Bab 2Dokumen47 halamanBab 2Indri Niza AnastasyahBelum ada peringkat
- Diva Intan Syalsabila - LP - Kebutuhan Rasa Aman Dan NyamanDokumen9 halamanDiva Intan Syalsabila - LP - Kebutuhan Rasa Aman Dan NyamanDiva SyalsabilaBelum ada peringkat
- Perkuliahan Psikologi KesehatanDokumen97 halamanPerkuliahan Psikologi KesehatanLihat SayaBelum ada peringkat
- Definisi Sehat Dan SakitDokumen5 halamanDefinisi Sehat Dan SakitPutri CahyatiBelum ada peringkat
- Rasa Nyaman LLLDokumen17 halamanRasa Nyaman LLLBagas RomadhoniBelum ada peringkat
- Persepsi Sehat Sakit Perilaku Sakit - IkaDokumen29 halamanPersepsi Sehat Sakit Perilaku Sakit - IkaSemangat BelajarBelum ada peringkat
- Konsep Sehat Dan SakitDokumen20 halamanKonsep Sehat Dan Sakitipannatanael05Belum ada peringkat
- (H7) LP GGN Rasa Aman NyamanDokumen16 halaman(H7) LP GGN Rasa Aman NyamanIni Ichy100% (1)
- Konsep Sehat SakitDokumen11 halamanKonsep Sehat Sakitputu ayu masrianiBelum ada peringkat
- Konsep Sehat SakitDokumen10 halamanKonsep Sehat SakitNdy Helper2Belum ada peringkat
- Tugas 2 Peran Dan Perilaku Respon SakitDokumen17 halamanTugas 2 Peran Dan Perilaku Respon SakitIndri RahmawattyBelum ada peringkat
- Kelompok 3A - Antropologi Kesehatan.Dokumen19 halamanKelompok 3A - Antropologi Kesehatan.Uuz razeansyahBelum ada peringkat
- Materi Kelompok 2Dokumen25 halamanMateri Kelompok 2ashfiana wirdhiaBelum ada peringkat
- Peran Dan Perilaku PasienDokumen31 halamanPeran Dan Perilaku PasienRosa IstiqomahBelum ada peringkat
- Sehat Sakit - Psikososial Dan Budaya PT IDokumen65 halamanSehat Sakit - Psikososial Dan Budaya PT ICinta MeilikaBelum ada peringkat
- Konsep Sehat Dan Sakit (Paradigma) TK1Dokumen23 halamanKonsep Sehat Dan Sakit (Paradigma) TK1bella febriantiBelum ada peringkat
- Makalah Konsep Sehat - SakitDokumen15 halamanMakalah Konsep Sehat - SakitAnisa Laras AfrianingrumBelum ada peringkat
- Falsafah Dan Paradigma (Konsepkep Manusia Dan Sehat Sakit)Dokumen23 halamanFalsafah Dan Paradigma (Konsepkep Manusia Dan Sehat Sakit)Elya AulanivaBelum ada peringkat
- LP Keamanan Dan Kenyamanan PDFDokumen10 halamanLP Keamanan Dan Kenyamanan PDFMun100% (2)
- MODUL 4 Aktifitas Fungsional Dan RekreasiDokumen8 halamanMODUL 4 Aktifitas Fungsional Dan RekreasiHuzni AuliyaBelum ada peringkat
- Konsep Sehat Sakit Dalam Paradigma KepDokumen11 halamanKonsep Sehat Sakit Dalam Paradigma KepLeli OktaviaBelum ada peringkat
- Konsep Perilaku Sehat SakitDokumen17 halamanKonsep Perilaku Sehat SakitnilasariBelum ada peringkat
- Konsep Sehat SakitDokumen15 halamanKonsep Sehat SakitM Wahyu GunawanBelum ada peringkat
- Persepsi Sehat Dan SakitDokumen18 halamanPersepsi Sehat Dan Sakitshildiane putriBelum ada peringkat
- Persepsi Sehat SakitDokumen10 halamanPersepsi Sehat SakitsusanBelum ada peringkat
- Makalah HematuriaDokumen24 halamanMakalah HematuriaNugraheni Desiree100% (1)
- Sistem MedisDokumen54 halamanSistem MedisMarwan Baits0% (1)
- c5228 Konsep Sehat SakitDokumen40 halamanc5228 Konsep Sehat Sakitmelati ceria22Belum ada peringkat
- LP KDP NurulDokumen15 halamanLP KDP Nurulayudiah lestariBelum ada peringkat
- Kesehatan mental dan gangguan psikologis: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandKesehatan mental dan gangguan psikologis: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Dari EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanDari EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- PSIKOLOGI KECEMASAN Mengetahui untuk memahami mekanisme fungsinyaDari EverandPSIKOLOGI KECEMASAN Mengetahui untuk memahami mekanisme fungsinyaPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (8)