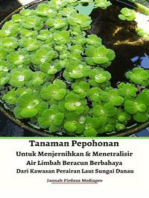SKSN FINAL-Sksn (Rev)
SKSN FINAL-Sksn (Rev)
Diunggah oleh
Khoirul AnwarJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
SKSN FINAL-Sksn (Rev)
SKSN FINAL-Sksn (Rev)
Diunggah oleh
Khoirul AnwarHak Cipta:
Format Tersedia
Review Penelitian
dan Kakao
1 (1) 2013,
63-80
PotensiKopi
dan teknologi
diversifikasi
limbah kopi
menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
POTENSI DAN TEKNOLOGI DIVERSIFIKASI LIMBAH KOPI
MENJADI PRODUK BERMUTU DAN BERNILAI TAMBAH
Potency and Technology of Coffee Trash Diversification Product
to Increase Good Quality and Added Value
Sukrisno Widyotomo1*)
1)
Pusat Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia, Jl. PB. Sudirman No. 90, Jember, Indonesia
*)
Alamat penulis (Corresponding Author): swidyotomo@gmail.com
Naskah diterima (received) 29 Oktober 2012, disetujui (accepted) 21 Nopember 2012
Abstrak
Kopi merupakan salah satu komoditas penyegar utama yang sangat
potensial di Indonesia. Salah satu permalasahan utama dalam proses pengolahan
kopi adalah penanganan limbah padat dan cair. Dalam setiap ton buah basah
akan diperoleh 200 kg kulit kopi kering, dan diperlukan air untuk pengolahan
sebanyak 20 l/kg kopi pasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengolahan kopi
primer cara basah akan menghasilkan limbah padat maupun cair yang sangat besar.
Kulit kopi memiliki kandungan nutrisi dan senyawa yang potensial untuk dapat
diubah menjadi produk bernilai tambah. Tulisan ini bertujuan mengulas potensi
dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah.
Beberapa penelitian telah dilakukan untuk menghasilkan suatu teknologi yang
dapat mengubah limbah pengolahan menjadi produk pangan dan non pangan
dengan mutu serta nilai yang lebih baik. Bentuk diversifikasi produk yang dapat
dihasilkan antara lain papan partikel, amelioran tanah, media tanam, kompos organik,
minuman ringan beralkohol, minuman dengan kadar gula tinggi, media produksi
protein sel tunggal C. utilis, pakan ternak, bioetanol, biodiesel, biogas, bahan
bakar sumber panas proses pengeringan dan lain-lain. Teknologi diversifikasi
tersebut sudah dapat diterapkan, namun masih ada beberapa teknologi yang perlu
dikaji lebih mendalam untuk memperoleh kondisi optimum proses.
Abstract
Coffee is one of main beverage comodities that very potential in
Indonesia. One of main problems in coffee processing is to handle liquid and
solid waste accuratly. In one ton of wet coffee cherries will be produce 200 kg
of dried coffee pulp, and need water supply for primery processing about
20 liters per a kilogram green beans. Its indicated that primery coffee processing using fully wet method will be produce high waste, i.e. solid and liquid.
Coffee pulp has nutrition content and potential chemical compound to convert as adde value product. The aims of this paper is to give an explanation of
coffee waste potency and diversification technology that produce high quality
and give more added value. Several research programs to develop technology
that converted primery processing waste as diversification product (food and
non food product) with high quality and added value have be done.
Deversification products such as particleboard, soil amelioran, artificial soil
of plant, organic compost, soft drink by low alcohol, water with high sugar
63
Widyotomo
content, production media for C. utilis single cell, feed for animal, bioethanol,
biodiesel, biogas, energy source for drying process, etc. Its diversification technology have been applied, but few of technologies should be continouing by
complete analysis to determine optimum process condition.
Key words: coffee, waste, technology, diversification, quality, added value.
PENDAHULUAN
Kopi merupakan salah satu penghasil
sumber devisa Indonesia, dan memegang
peranan penting dalam pengembangan
industri perkebunan. Dalam kurun waktu
20 tahun luas areal dan produksi perkebunan
kopi di Indonesia, khususnya perkebunan
kopi rakyat mengalami perkembangan yang
sangat signifikan. Pada tahun 1980, luas areal
dan produksi perkebunan kopi rakyat
masing-masing sebesar 663 ribu hektar dan
276 ribu ton, dan pada tahun 2009 terjadi
peningkatan luas areal dan produksi yang
masing-masing sebesar 1.241 juta hektar dan
676 ribu ton (Ditjenbun, 2010). Tahun 2010
luas areal kopi di Indonesia mencapai
1.210.000 ha dengan produksi 686.920 ton,
ekspor 433.600 ton dengan nilai USD 814,3
juta. Sedangkan pada tahun 2011 angka
sementara luas areal kopi 1.677.000 ha
dengan produksi 633.990 ton, ekspor
387.870 ton dengan nilai USD 1.198,9 juta.
Rata-rata laju pertumbuhan luas areal kopi,
jumlah produksi, volume ekspor dan nilai
ekspor selama 2007-2010 masing-masing
sebesar 0,25%; 0,2%; 13,31% dan 12,61%.
Intensifikasi kopi Arabika dan Robusta tahun
2012 mencapai 13.510 ha yang tersebar di
provinsi NAD, Sumatera Utara, Bali, Nusa
Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Selain
program tersebut, pada tahun yang sama
dilakukan perluasan areal kopi Arabika
sebesar 1.650 ha dan peremajaan kopi
Robusta sebesar 2.950 ha. Tahun 2012
luas areal kopi ditarget kan mencapai
1.354.000 ha dengan nilai produksi dan
produktivitas masing-masing 733.000 ton dan
743 kg/ha (Azwar, 2012).
64
Delapan puluh dua persen luasan areal
perkebunan kopi Indonesia didominasi oleh
kopi jenis Robusta, sedangkan sisanya sebesar
18% berupa kopi Arabika. Harga kopi
Robusta di pasaran domestik maupun
internasional lebih murah jika dibandingkan
dengan kopi Arabika (Gambar 1), kendati
volume Arabika di pasar dunia mencapai
70%, sedangkan kopi Robusta hanya 30%.
Berbeda dengan kondisi di Indonesia,
produksi kopi Robusta mencapai 80%,
sedangkan Arabika hanya 20% dari total
produksi kopi (Barani, 2009). Biji kopi yang
dihasilkan oleh petani kopi Indonesia dikenal
dengan sebutan kopi asalan karena
umumnya memiliki mutu yang rendah
dengan nilai cacat lebih dari 225 (Misnawi
& Sulistyowati, 2006). Wijaya (2003)
melaporkan bahwa dari 280.405 ton kopi
Robusta yang diekspor Indonesia ke
mancanegara dalam kurun waktu 1997-2001,
sebanyak 35.354 ton/tahun atau 12,6%
diantaranya bermutu grade VI yang mulai
dilarang diperdagangkan di pasar internasional berdasarkan resolusi ICO (International Coffee Organization) No.147.
Peningkatan luas areal dan produksi kopi
Indonesia yang didominasi oleh kopi Robusta
dari perkebunan rakyat serta peluang pasar
dunia merupakan potensi besar dalam
peningkatan kesejahteraan petani Indonesia.
Susila (1999) melaporkan bahwa perdagangan dan perkembangan industri kopi
dunia, sedang dan akan terus mengalami
perubahan sebagai akibat liberalisasi
perdagangan yang berpangkal dari General
Agreement on Tariff and Trade (GATT)
Putaran Uruguay yang ditandatangani pada
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
Panen
buahkopi
kopi
Panen buah
Penerimaan
Penerimaan
Tangki Shipon
Shipon
Pulping
Buahkopi
kopihijau
hijau
Buah
Kotoran
Kotoran
Pulp
Pulp
Fermentasi
Fermentasi
Pencucian
Pencucian
Pengeringan
Pengeringan
Pengeringan
Pengeringan
Gelondong
kering
Gelondong kering
Kulit berkulit
berkulitcangkang
cangkang (HS)
Kopi
(HS) kering
kering
Lendir
Lendir
Pembersihan
Pembersihan
Pengupasan
kulit
Pengupasan kulit
kering
kering
Kulitgelondong
gelondong
Kulit
kering/kulit
kering/kulit
cangkang
cangkangkering
kering
Grading ukuran
ukuran
Grading
Sortasi
Sortasi
(densitas/warna)
(densitas/warna)
Kopi
beans)
Kopipasar
pasar (green
(green beans)
Penyimpanan
Penyimpanan
Gambar 1. Tahapan pengolahan kopi cara kering dan basah serta produk limbah yang dihasilkan
Figure. 1.
Coffee dry and wet processing steps and its by products
65
Widyotomo
tanggal 15 Desember 1993. Secara garis
besar perubahan produksi atau stok akan
segera diikuti oleh perubahan harga.
Perubahan harga umumnya tidak secara
cepat dapat diikuti dan direspon dengan baik
oleh perubahan produksi atau konsumsi.
Resistensi produk terhadap fluktuasi harga
pasar kopi internasional perlu ditingkatkan
salah satunya dengan pengembangan
diversifikasi produk kopi yang memberikan
bernilai tambah (Zaenudin & Abdoellah,
2003). Beberapa penelitian telah dilakukan
untuk menghasilkan suatu teknologi yang
dapat mengubah limbah kopi menjadi bentuk
diversifikasi produk yang lebih bermanfaat
dan bernilai ekonomi tinggi. Tulisan ini akan
mengulas potensi limbah kopi yang
dihasilkan dari suatu proses pengolahan kopi
dan teknologi diversifikasi limbah kopi
menjadi produk samping yang lebih
bermanfaat dan bernilai ekonomis tinggi yang
akan memberikan peningkatan pendapatan,
dan peluang usaha di sektor perkebunan kopi
rakyat.
Pengolahan Kopi
Saat ini dikenal dua cara pengolahan
kopi dari bentuk buah segar sampai siap untuk
dikonsumsi, yaitu cara basah (fully wet process) dan cara kering (dry process) dengan
tahapan proses pengolahan sebagaimana
ditampilkan pada Gambar 1 (Clarke &
Macrae, 1989).
Pada jaman kolonial Belanda, cara
pengolahan kering dikenal dengan istilah
Gewone Bereiding (GB), Droge Bereiding
(DB), atau Oost Indische Bereiding (OIB)
(Ismayadi, 2000). Pengolahan cara kering
masih banyak diterapkan oleh petani kopi
Robusta, dan perusahaan perkebunan besar
untuk buah kopi inferior, yaitu buah muda,
kering dan mengapung. Pengolahan kopi
cara kering relatif lebih sederhana jika
dibandingkan dengan pengolahan cara basah.
66
Tahapan pengolahan cara kering adalah panen
buah kopi, pengeringan gelondong basah,
pembersihan, pengupasan kulit kering,
klasifikasi mutu berdasarkan ukuran (grading), klasifikasi mutu berdasarkan densitas
dan warna (sortation) serta penyimpanan.
Ada pendapat bahwa pengolahan cara
basah diterapkan dengan tujuan untuk
mempercepat proses pengolahan. Pada
pengolahan cara kering diperlukan waktu
lebih dari 15 hari untuk proses pengeringan
buah kopi basah. Pada jaman kolonial
Belanda, cara pengolahan basah dikenal
dengan istilah West Indische Bereiding (WIB)
atau Natte Bereiding (NB) (Ismayadi, 2000).
Tahapan pengolahan cara basah adalah panen
buah kopi, penerimaan buah, tangki siphon
untuk proses pemisahan buah matang dari
buah mudah dan terserang hama penyakit,
pengupasan kulit buah basah (pulping),
fermentasi kopi basah berkulit cangkang,
pencucian (washing), pengeringan kopi
berkulit cangkang tanpa lapisan lendir,
pembersihan, pengupasan kulit kering
(hulling), klasifikasi mutu berdasarkan ukuran
(grading) (Widyotomo & Sri-Mulato, 2005;
Widyotomo et al., 2006), klasifikasi mutu
berdasarkan densitas dan warna (sortation)
serta penyimpanan (Clarke & Macrae, 1989).
Pengupasan kulit buah kopi (pulping)
merupakan salah satu tahapan proses
pengolahan kopi yang membedakan antara
pengolahan kopi cara basah dengan kering.
Mesin pengupas kulit buah kopi basah
(pulper) digunakan untuk memisahkan atau
melepaskan komponen kulit buah dari bagian
kopi berkulit cangkang (Widyotomo, 2010).
Pada pengolahan cara kering, buah kopi hasil
panen segera dikeringkan baik dengan cara
penjemuran maupun menggunakan pengering
mekanis sampai diperoleh kadar air antara
12-13%. Buah kopi kering atau gelondong
kering dan kopi berkulit cangkang kering
dikupas dengan menggunakan mesin
pengupas (huller) untuk memisahkan biji
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
kopi dari komponen kulit buah keringnya
sebelum siap untuk dikemas dan dijual
(Widyotomo & Mulato, 2004).
Potensi Limbah Kopi
Potensi limbah yang diperoleh jika dilihat
dari tahapan pengolahan kopi cara kering
maupun basah adalah kulit buah basah, limbah
cair yang mengadung lendir, dan kulit
gelondong kering maupun cangkang kering.
Buah kopi atau sering juga disebut sebagai
kopi gelondong basah hasil panen memiliki
kadar air antara 60-65%. Biji kopi masih
terlindung oleh kulit buah, daging buah,
lapisan lendir, kulit tanduk dan kulit ari.
Kulitcangkang
Kulit
cangkang
Kulit
luarluar
Kulit
Kulit
buah
Kulit
buah
BijiBiji
Biji
Biji
Tangkai
Tangkai
Kulit ariari
Kulit
Gambar 2. Anatomi buah kopi
Hasil analisis kesetimbangan massa buah
kopi diperoleh bahwa dari 100 kg buah kopi
yang diolah kering akan diperoleh 29 kg
(29%) gelondong kering yang terdiri dari
15,95 kg biji kopi (55%) dan 13,05 kg kulit
gelondong kering (45%). Kulit gelondong
kering terdiri kulit cangkang, lendir dan
kulit buah dengan perbandingan bobot kering
11,9 : 4,9 : 28,7. Kulit gelondong kering
mengandung gula reduksi, gula non pereduksi
dan senyawa pektat masing-masing sebesar
12,4%; 2,02% dan 6,52% (Wilbaux, 1963)
dan 10,7% protein kasar serta 20,8% serat
kasar (Elias, 1979). Lendir (muchilage)
kering mengandung pektin 35%, gula
pereduksi 30%, gula non pereduksi 20% serta
selulosa dan abu 17% (Bressani, 1979).
Lebih lanjut Elias (1979) melaporkan bahwa
buah kopi kering terdiri atas 55,4% biji kopi
pasar, 28,7% kulit buah (pulpa) kering,
11,9% kulit cangkang, dan sisanya sebesar
4,9% berupa lendir kering. Pulpa kopi kering
terdiri dari 12,6% air; 21% serat kasar; 8,3%
abu; 12,4% gula pereduksi; 44,4% ekstrak
nitrogen. Kulit cangkang kering terdiri dari
7,8% air; 77% serat kasar; 0,5% abu, dan
18,9% ekstrak nitrogen.
Jika mengikuti proses pengolahan basah
secara penuh, konsumsi air dapat mencapai
7-9 m3 per ton buah kopi yang diolah.
Kebutuhan air untuk proses pencucian
berkisar antara 5-6 m3 per ton biji kopi
berkuit cangkang. Wahyudi & Yusianto
(1993) melaporkan bahwa untuk setiap ton
biji kopi kering dihasilkan sekitar 20 m3
limbah cair. Lebih lanjut Mulato et al. (1996)
melaporkan bahwa dari tiap satu ton buah
basah akan diperoleh lebih kurang 200 kg
kulit kopi kering. Jumlah limbah kopi yang
perlu ditangani sebesar 44,6% dari berat buah
kopi kering (Bressani, 1979). Penelitian lain
melaporkan bahwa limbah kulit buah kopi
yang dihasilkan dari proses pengolahan cara
basah mencapai 43% bobot buah (Ismayadi
et al., 1997), dan air yang diperlukan untuk
pengolahan mencapai 20 l/kg kopi pasar
(green beans) (Ismayadi, 2000). Lebih lanjut
Ditjenbun (2006) melaporkan bahwa dalam
1 ha areal pertanaman kopi akan memproduksi limbah segar sekitar 1,8 ton setara
dengan produksi tepung limbah 630 kg. Oleh
karena itu, limbah padat dan cair yang
dihasilkan dari tahapan pengolahan kopi basah
sangat tinggi. Upaya pemanfaatan limbah
pengolahan kopi baik dalam bentuk padat
maupun cair menjadi produk yang memiliki
nilai ekonomi lebih tinggi perlu dilakukan
67
Widyotomo
sekaligus untuk menekan dampak negatif
limbah terhadap pencemaran lingkungan.
Diversifikasi Limbah Kopi
Limbah padat dan cair pengolahan kopi
mengandung materi organik yang cukup
tinggi dan sangat potensial sebagai media
tumbuh mikroorganisme untuk dapat diubah
menjadi produk bernilai tambah (Pandey
et al., 2000). Pusat Penelitian Kopi dan Kakao
Indonesia secara intensif melakukan kegiatan
penelitian dan pengembangan untuk
memperoleh teknologi diversifikasi produk
limbah pengolahan kopi menjadi produk
bermutu dan bernilai tambah. Beberapa
bentuk diversifikasi produk dari bahan baku
limbah pengolahan kopi yang telah
dikembangkan adalah sebagai berikut :
Papan Partikel
Papan partikel merupakan salah satu
produk komposit yang sangat diperlukan
dalam industri furniture dan bahan bangunan
yang dibuat dengan cara diikat dengan
perekat sintetis dan dikempa panas (Maloney,
1993). Pada umumnya papan partikel dibuat
dengan bahan dasar kayu, dan dengan
persediaan kayu dari hutan alam yang
semakin berkurang, maka diperlukan inovasi
teknologi produksi papan partikel dengan
bahan dasar yang potensial dan ramah
lingkungan. Braham & Bressani (1979)
melaporkan bahwa buah kopi tersusun atas
55,4% biji kopi pasar, 28,7% kulit buah
kering, dan 11,8% kulit cangkang. Penelitian
pemanfaatan kulit buah kopi menjadi salah
satu bahan baku pembuatan papan partikel
telah dilakukan oleh Yusianto et al. (1999).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa papan
partikel yang dibuat dari kulit cangkang kopi
memiliki kualitas yang lebih baik jika
dibandingkan dengan papan partikel yang
dibuat dari kulit buah kopi. Komposisi
68
campuran perekat yang digunakan adalah
66,73% urea formaldehida, 5,53% NH4Cl
(kadar 15%), 1,53% NH4OH (kadar 25%),
dan 26,21% emulsi parafin (kadar 20%).
Karakteristik papan partikel yang dihasilkan
baik menggunakan kulit tanduk maupun kulit
kopi adalah kuat rekat internal, kuat lentur,
kuat tekan tegak lurus dan kuat pegang paku
skrup masing-masing sebesar 1,07-4,29 kg/
cm2, 38,56-123,59 kg/cm2, 117,33-205 kg/
cm2 dan 11,4-24,85 kg. Haygreen & Bowyer
(1996) melaporkan bahwa pada dasarnya
sifat papan partikel dipengaruhi oleh bahan
baku penyusunnya, jenis perekat dan
formulasi yang digunakan serta proses
pembuatannya.
Amelioran Tanah
Amelioran tanah merupakan suatu materi
atau bahan yang mampu memperbaiki atau
membenahi kondisi fisik dan kesuburan tanah.
Limbah kulit buah kopi dapat dimanfaatkan
sebagai sumber bahan baku amelioran tanah
alami yang berfungsi untuk meningkatkan
daya dukung tanah bagi pertumbuhan dan
produksi tanaman. Pujiyanto (2007) melaporkan bahwa amelioran tanah dapat dibuat dari
kulit buah kopi segar (90% b/b) yang telah
dicampur dengan 10% (b/b) bubuk bahan
mineral berupa 50% zeolit dan 50% fosfat
alam, diproses dengan cara penghalusan
sampai membentuk pasta. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa limbah kulit buah kopi
dapat dimanfaatkan sebagai amelioran tanah
alami untuk meningkatkan daya dukung tanah
bagi pertumbuhan dan produksi tanaman.
Komposisi amelioran 90% pasta kulit buah
kopi dengan 10% mineral memiliki karakter
fisik dan kimia yang baik, yaitu memiliki
kapasitas retensi air, kapasitas tukar kation,
kadar C-organik, dan kadar P yang tinggi
sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki
tanah. Amelioran kulit buah kopi dengan
pupuk buatan bekerja secara sinergis dalam
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
meningkatkan pertumbuhan tanaman. Aplikasi
amelioran kulit buah kopi meningkatkan
keefektifan aplikasi pupuk anorganik.
Media Tanam
Media tanam merupakan tempat hidup
tanaman yang sesuai dengan persyaratan
hidupnya. Menentukan media tanam yang
tepat untuk suatu jenis tanaman merupakan
hal yang sulit sehingga media tanam yang
akan digunakan harus disesuaikan dengan
jenis tanaman yang akan ditanam. Secara
umum, media tanam harus dapat menjaga
kelembaban daerah sekitar akar, menyediakan
cukup udara, dan dapat menahan ketersediaan
unsur hara. Limbah kulit buah kopi
mengandung bahan organik dan unsur hara
yang potensial untuk digunakan sebagai media
tanam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kadar C-organik kulit buah kopi adalah
45,3%, kadar nitrogen 2,98%, fosfor 0,18%
dan kalium 2,26% (Ditjenbun, 2006).
Wibowo (2010) telah melakukan penelitian
pemanfaatan limbah padat kopi sebagai media
tanam Anthurium plowmanii Scoat, dan hasil
penelitian menunjukkan bahwa komposisi
media tanam kompos kulit buah kopi dan
kulit buah kopi kering dengan perbandingan
1 : 1 dapat digunakan sebagai media tanam
alternatif dan memberikan pertumbuhan
yang baik.
Kompos Organik
Kompos adalah hasil penguraian parsial/
tidak lengkap dari campuran bahan-bahan
organik yang dapat dipercepat secara artifisial
oleh populasi berbagai macam mikroba dalam
kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan
aerobik atau anaerobik (Isroi, 2007). Bahan
baku untuk pembuatan kompos banyak
tersedia di perkebunan kopi, diantaranya
limbah kulit buah kopi, dan kulit cangkang/
tanduk yang dapat digunakan langsung
sebagai kompos jika telah memenuhi syarat,
terutama nisbah C/N-nya tidak lebih dari 15
(Rathinavelu & Graziosi, 2005; Baon et al.,
2003). Beberapa penelitian yang berkaitan
dengan diversifikasi limbah kulit kopi
menjadi kompos organik telah dilakukan.
Winaryo et al. (1995) melaporkan bahwa
pengomposan kulit kopi selama 3 bulan
dengan komposisi bahan baku 130 kg kulit
kopi, 10 kg kulit tanduk kopi, 10 kg sekam
padi, 5 kg kapur, 25 kg vertiver, 25 sampah
organik dan 15 kg pupuk kandang akan
menghasilkan kompos dengan kualitas baik.
Erwiyono et al (2001) melaporkan bahwa
kompos organik yang diproduksi dari kulit
buah kopi memiliki kandungan karbon (C)
dan nitrogen (N) yang terus menyusut dari
minggu pertama hingga minggu keenam dan
dengan C/N rasio yang relatif stabil pada
periode yang sama. Melawati (2002)
melaporkan bahwa limbah pabrik kopi dapat
diolah menjadi pupuk organik dengan bantuan
cacing tanah dengan lama proses
pengomposan 9 minggu termasuk proses
fermentasi. Kualitas kompos organik yang
dihasilkan setara dengan kualitas kompos
organik komersial. Campuran yang mengandung 25-50% limbah kopi dalam kotoran sapi
dapat menghasilkan kompos organik dengan
struktur yang baik.
Pemanfaatan aktivator hayati dan
anorganik dalam pengomposan kulit buah
maupun kulit tanduk diantaranya telah
dilakukan oleh Baon et al. (2000) dan Baon
et al. (2005). Baon et al. (2005) melaporkan
bahwa pemberian aktivator anorganik,
khususnya ammonium sulfat, menghasilkan
laju dan kualitas kompos yang lebih baik
dibandingkan aktivator hayati. Pulpa buah
kopi menghasilkan kompos dengan kualitas
yang baik serta laju pengomposan yang lebih
cepat dibandingkan dengan bahan mentah
pengomposan yang lain. Laju pengomposan
untuk mencapai nisbah C/N<15 untuk pulpa
kopi sebagai bahan mentah hanya empat
69
Widyotomo
minggu dibandingkan kulit tanduk kopi yang
memerlukan lebih dari delapan minggu. Lebih
lanjut Baon et al. (2003) melaporkan bahwa
laju pengomposan kulit buah kopi jauh lebih
cepat dibandingkan dengan kulit tanduk
maupun campuran keduanya. Penggunaan
aktivator anorganik masih lebih baik jika
dibandingkan dengan aktivator hayati.
Bahan Baku Minuman
Salah satu alternatif diversifikasi kulit
buah kopi yang potensial adalah proses
produksi minuman ringan beralkohol
(Rathinavelu & Graziosi, 2005). Pemanfaatan
limbah kulit buah kopi basah sebagai sumber
bahan baku minuman telah dilakukan oleh
Muchlis (2011) dan Ismayadi et al. (1997).
Muchlis (2011) memproses limbah kulit buah
kopi basah dengan penambahan lemon
menjadi sebuah minuman instan beraroma.
Daulay (1991) dan Ismayadi et al. (1997)
melaporkan bahwa kulit buah kopi
mempunyai potensi sebagai bahan baku
pembuatan minuman semacam cider, yaitu
minuman dengan citarasa asam dan manis
disamping rasa alkoholik. Cider dapat dibuat
dari kulit buah kopi dengan konsentrasi zat
padat terlarut 3% brix, inokulum Saccharomyces cerevisiae ditambah amonium sulfat
0,33 g/l. Hasil proses pemecahan gula adalah
asam laktat dan asam asetat. Senyawa asam
yang dihasilkan dari proses fermentasi kulit
buah kopi adalah etanol, asam butirat dan
propionat. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kombinasi terbaik untuk pembuatan
cider adalah penambahan gula sebanyak 25%,
dan proses fermentasi dilakukan pada suhu
25-28 o C selama tiga hari. Cider yang
dihasilkan memiliki kadar alkohol sekitar
8,35%, kadar gula pereduksi 6,17%, asam
total 7,68 meq/100 ml, pH 3,81, zat padat
terlarut total 11,75% brix.
70
Sumber Bahan Baku Cairan Gula
Sukrosa merupakan salah satu komponen penting yang terdapat di dalam daging
buah kopi. Kadar gula akan meningkat
dengan cepat selama proses pematangan
buah yang dapat diidentifikasikan dengan
peningkatan rasa manis. Wilbaux (1963)
melaporkan bahwa 40,17% buah kopi terdiri
dari komponen kulit dan daging buah dengan
kandungan gula total sebesar 45,8%. Limbah
kulit buah kopi basah dapat diolah menjadi
sumber gula cair dengan cara memanaskan
air hasil cucian dan pengempaan kulit buah
basah selama 3 jam dan kemudian akan
terpisah antara air dengan gula. Rasio proses
memasak air cucian 1 kg buah kopi akan
menghasilkan 150 ml gula cair. Kadar
sukrosa dalam gula kopi sebanyak 4,68%
sedangkan dalam gula biasa kadar sukrosanya
mencapai 99,8% (Ramadhanu & Putri,
2012).
Media Produksi Protein Sel Tunggal
Candida utilis
C. utilis merupakan salah satu jenis ragi
(yeast) yang banyak digunakan dalam proses
produksi minuman beralkohol (bir) maupun
makanan (tape) karena memiliki ukuran sel
yang besar dengan laju perbanyakan yang
cukup tinggi dalam kondisi aerobik. Limbah
cair proses produksi bir (brewer) banyak
dimanfaatkan sebagai sumber protein untuk
makanan hewan dan makanan dengan nutrisi
tambahan karena masih mengandung protein dengan kadar 40-60% (Rodiah, 2007).
Pemanfaatan ekstrak kulit buah kopi sebagai
media produksi protein sel tunggal C. utilis
dalam sistem kultur sinambung telah
dilakukan oleh Ismayadi et al. (1987). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
konsentrasi substrat akan menurunkan
efisiensi konversi substrat menjadi sel,
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
sedangkan hasil massa sel kering dan
produktivitasnya semakin meningkat. Kondisi
optimum proses diperoleh pada konsentrasi
substrat 5% padatan terlarut total dan laju
pengenceran 0,2/jam.
Pakan Ternak
Beberapa penelitian menyebutkan bahwa
limbah kulit buah kopi dapat menggantikan
20% kebutuhan konsentrat komersial yang
digunakan sebagai pakan ternak, dan
menekan biaya pakan hingga 30% (Rathinavelu & Graziosi, 2005). Dengan kandungan nutrisi yang cukup baik, maka kulit buah
kopi berpotensi untuk dikonversi menjadi
sumber bahan baku pakan ternak (Braham
& Bressani, 1979). Beberapa hasil penelitian
pemanfaatan kulit buah kopi untuk dikonversi
menjadi pakan ternak ruminansia (kambing
dan sapi) dan unggas (ayam) adalah sebagai
berikut :
a. Pakan kambing
Zainuddin & Murtisari (1995) melaporkan bahwa kulit buah kopi ini cukup potensial
untuk digunakan sebagai bahan pakan ternak
ruminansia termasuk kambing. Kandungan
zat nutrisi yang terdapat pada kulit buah kopi
seperti; protein kasar sebesar 10,4%, serat
kasar sebesar 17,2% dan energi metabolis
14,34 MJ/kg relatif sebanding dengan zat
nutrisi rumput. Hasil penelitian lain
melaporkan bahwa penggunaan limbah kopi
sebanyak 200 g/ekor/hari dan enzym philazim
sebanyak 2,5 g/ekor/hari dapat meningkatnya
produksi susu kambing Peranakan Etawah
(PE atau Etawah grade goats). Penggunaan
limbah kopi terfermentasi untuk pakan
penguat mampu memberikan peningkatan
berat badan dari rata-rata 68,41 g/ekor/hari
menjadi 102.92 g/ekor/hari (Guntoro et al.,
2002). Lebih lanjut Guntoro et al. (2004)
melaporkan bahwa fermentasi limbah kopi
dengan Aspergillus niger dapat meningkatkan kandungan gizi limbah kopi. Penggunaan
tepung limbah kopi terfermentasi sebanyak
100 g/ekor/hari prasapih dan 200 g/ekor/hari
pasca sapih dapat meningkatkan pertumbuhan anak kambing dari rata-rata 65 g/ekor/
hari (tanpa limbah kopi) menjadi 98 g/ekor/
hari.
Perlakuan fermentasi limbah kulit kopi
dengan Aspergillus niger mampu meningkatkan nilai gizi limbah kopi yang ditunjukkan
dengan meningkatnya protein dari 6,67%
menjadi 12,43% dan menurunkan kadar serat
kasar dari 21,4% menjadi 11,05%. Pengamatan di lapangan menunjukkan tidak ada
satupun ternak yang diberi asupan limbah
hasil fermentasi menunjukkan gejala sakit
ataupun mati; sehingga limbah kopi terfermentasi aman digunakan untuk pakan
kambing (Guntoro et al., 2002). Kulit kopi
baik dalam kondisi tanpa diproses ataupun
yang telah difermentasi layak untuk
dimanfaatkan sebagai komponen pakan
penggemukan ternak domba (Prawirodigdo
et al., 2005). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penambahan 200 g limbah kulit kopi
kering dalam susunan pakan tidak berpengaruh negatif terhadap pertambahan
bobot hidup ternak domba. Hal tersebut
menunjukkan bahwa limbah kulit kopi kering
dapat digunakan untuk membantu mengatasi
kesulitan pakan ternak domba. Untuk dapat
menghasilkan tingkat pertumbuhan ternak
domba yang lebih baik, maka diperlukan
proses pengolahan lebih lanjut terhadap
kulit kopi sebelum diberikan kepada
ternak (64 g/hari kulit kopi tanpa proses dan
101 g/hari kulit kopi yang difermentasi)
(Prawirodigdo et al., 2007). Londra & Andri
(2009) melaporkan bahwa pemberian limbah
kopi terfermentasi dapat meningkatkan nilai
keuntungan sebesar Rp. 244.620/ekor untuk
pemeliharaan ternak kambing PE selama
150 hari.
71
Widyotomo
Proses produksi pakan ternak dapat
dilakukan dengan cara kimia yang sering
disebut amoniasi, yaitu menggunakan
amoniak (NH3). Beberapa keuntungan dari
metode ini adalah mudah dilakukan, murah,
tidak mencemari lingkungan, meningkatkan
daya cerna sekaligus meningkatkan kadar
protein, dan dapat menghilangkan aflatoksin.
Kulit kopi yang telah diamonasi mempunyai
kandungan protein 17,88%, kecernaan 50%
(dari 40%), VFA 143 mM (dari 102 mM)
dan NH3 12,04 mM (dari 4,8 mM)
(Tampoebolon, 2004). Selain itu telah
ditemukan teknologi pembuatan kulit buah
kopi dalam bentuk tepung dan teknologi silase
yang merupakan teknologi altematif untuk
mengawetkan kulit buah kopi sehingga dapat
disimpan lebih lama untuk digunakan sebagai
sumber bahan pakan ternak ruminansia.
Tepung kulit buah kopi dan silase kulit buah
kopi yang menggunakan bahan aditif
molasses dan tepung tapioka sangat potensial
digunakan sebagai bahan pakan temak
kambing, dan dapat menggantikan sebagian
komponen sumber serat (Simanihuruk,
2010).
untuk meningkatkan keserasian gizi dari
keseluruhan pakan. Satu kilogram kulit kopi
dapat ditambahkan dalam 2-3 kg konsentrat
yang akan diberikan untuk pakan sapi dara
dan bunting tua (Mariyono & Romjali, 2007).
Penelitian yang membahas tingkat
kelayakan penggunaan limbah kopi untuk
penggemukan sapi potong juga telah
dilakukan oleh Parwati et al. (2006) di
Kabupaten Bangli. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pada tingkat discount
factor 18% pada usaha penggemukan sapi
dengan dedak kopi diperoleh nilai NPV
(Net Present Value) Rp. 5.334.785,43;
IRR (Internal Rate of Return) 23% dan
B/C rasio 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa
pembesaran sapi dengan dedak kopi layak
untuk dikembangkan. Hernaman et al. (2005)
melaporkan bahwa penggunaan kulit kopi
sebesar 6% pada pakan ternak sapi potong
tidak mempengaruhi kecernaan bahan kering
dan organik. Semakin tinggi penggunaan kulit
kopi akan menurunkan kecernaan bahan
kering dan organik berturut-turut dengan
pola persamaan regresi linear Y = 41,66
0,17X, R2 = 0,57, dan Y = 43,02-0,23X,
R2 = 0,70.
b. Pakan sapi
Pakan ternak ruminansia terdiri dari
komponen hijauan yang yang identik dengan
sumber serat mencapai 60-70%. Teknologi
pakan murah lengkap telah dikembangkan
oleh indutri pakan komersial sejak 2002
karena semakin terbatasnya ketersediaan
hijauan alami di lapangan. Pakan murah
lengkap dikembangkan dalam bentuk
konsentrat dengan kandungan air maksimum
13%, protein kasar minimum 12%, lemak
kasar maksimum 5%, serat kasar maksimum
15%, kadar abu maksimum 10%, Total
Digestible Nutrient (TDN) minimum 63%,
Ca 0,9% dan P 0,5%. Konsentrat merupakan
suatu bahan pakan dengan nilai gizi tinggi
yang dipergunakan bersama bahan pakan lain
72
c. Pakan ayam
Usaha tani ayam buras memiliki prospek
masa depan yang cukup baik dengan
semakin meningkatnya permintaan daging
dan telur karena peningkatan pendapatan dan
pengetahuan tentang pemenuhan gizi
keluarga. Salah satu komponen terbesar
dalam usaha tani ternak ayam buras adalah
pakan yang mencapai 60-80% dari total
biaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kebutuhan zat gizi ayam buras lebih rendah
dibandingkan dengan kebutuhan ayam ras
karena sifat genetik dan pola pertumbuhannya
berbeda. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu
diberikan formula ransum khusus ayam buras
agar diperoleh tingkat pertumbuhan dan
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
produksi telur yang maksimal (Santoso,
1996).
Zaenudin & Murtisari (1995) melaporkan bahwa kandungan protein kasar yang
terdapat di dalam kulit buah kopi mencapai
10,4% yang mendekati kandungan protein
yang terdapat pada bekatul. Penelitian yang
membahas potensi limbah kulit kopi sebagai
pakan ayam telah dilakukan oleh Muryanto
et al. (2006). Hasil penelitian menunjukkan
bawa bobot ayam umur 60 hari yang diberi
pakan tanpa penggunaan kulit kopi memberikan hasil yang tidak berbeda nyata jika
dibandingkan dengan pakan yang disusun
menggunakan 5% limbah kulit. Komposisi
pakan terdiri dari 20% konsentrat, 35%
jagung kuning, 40% bekatul, dan 5% limbah
kulit kopi. Biaya pembuatan 1 kg pakan ternak
tersebut sebesar Rp. 1.702,-. Berdasarkan
analisis input-output usaha, ditunjukkkan
bahwa keuntungan yang diperoleh dari
pembesaran ayam selama 60 hari dengan
pakan kontrol dan pakan yang mengandung
5% limbah kulit kopi adalah Rp. 1.401,-/ekor
dan Rp. 1.345,-/ekor dengan nilai B/C rasio
sama yaitu 1,16.
Bahan Baku Bioetanol
Bioetanol merupakan salah satu sumber
energi baru yang memiliki kelebihan
dibanding dengan Bahan Bakar Minyak
(BBM), diantaranya memiliki kandungan
oksigen yang lebih tinggi (35%) sehingga
terbakar lebih sempurna, nilai oktan lebih
tinggi, dapat diproduksi oleh mikroorganisme
secara terus menerus dan lebih ramah
lingkungan karena emisi gas CO yang
dihasilkan lebih rendah 19-25% (Indartono,
2005; Sarjoko, 1991). Produksi bioetanol di
berbagai negara telah dilakukan dengan
menggunakan bahan baku yang berasal dari
hasil pertanian dan perkebunan (Sarjoko,
1991).
Siswati et al. (2012) melaporkan bahwa
bioetanol dapat diproduksi dari proses
fermentasi limbah kulit kopi. Kandungan
selulosa di dalam limbah kulit kopi sebesar
65,2 % dan bahan selulosa memiliki potensi
sebagai bahan baku alternatif pembuatan
etanol. Tahap awal proses pembuatan
bioetanol adalah dengan menghidrolisis kulit
kopi menjadi glukosa. Proses hidrolisis kulit
kopi dilakukan dengan menggunakan katalis
HCl konsentrasi 20% (v/v) dan akan menghasilkan glukosa dengan kadar 10,04%.
Proses fermentasi dengan penambahan starter
11% dan waktu fermentasi 7 hari menghasilkan bioetanol berkadar 9,04%. Pada
proses fermentasi ini bakteri Z. mobilis
mampu mengkonversi glukosa sebesar
97,99%, dan yield etanol diperoleh sebesar
51,02%. Proses destilasi yang dilakukan
selama 8 jam akan menghasilkan bioetanol
dengan kadar 38,68%. Gunasekaran (1999)
melaporkan bahwa bioetanol hasil fermentasi
dapat dimurnikan lagi dengan proses destilasi
pada suhu 80 oC sesuai dengan kadar yang
diinginkan.
Z. mobilis adalah bakteri yang berbentuk
batang, termasuk dalam bakteri gram negatif,
tidak membentuk spora, dan merupakan
bakteri yang dapat bergerak (Lee et al.,
1979). Z. mobilis memiliki beberapa kelebihan
dibandingkan dengan S. cerevisieae yaitu:
dapat tumbuh secara anaerob fakultatif,
mempunyai toleransi suhu yang tinggi,
mempunyai kemampuan untuk mencapai
konversi yang lebih tinggi, tahan terhadap
kadar etanol yang tinggi dan pH yang rendah,
dan mampu menghasilkan yield etanol 92%
dari nilai teoritisnya. Penelitian yang
membahas metabolime gula dan tingkat
produksi alkohol yang dihasilkan dari proses
hidrolisis limbah kulit buah kopi dengan
menggunakan beberapa jenis yeast telah
dilakukan oleh Musatto et al. (2012). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa produksi
73
Widyotomo
etanol terbaik sebesar 11,7 g/l dan efisiensi
50,2% diperoleh dari proses hidrolisis ampas
bubuk kopi (spent coffee grounds/SCG)
dengan menggunakan yeast S. cerevisiae.
Bahan Baku Biodiesel
Salah satu bioenergi yang terus dikembangkan untuk mengatasi krisis bahan
bakar berbasis minyak bumi adalah biodiesel.
Biodiesel memiliki sifat yang sangat mirip
dengan petrodiesel (bahan bakar fosil), tetapi
memiliki energi pembakaran dan angka oktan
yang lebih tinggi sehingga proses pembakaran
menjadi lebih efisien dengan gas buang yang
ramah lingkungan (Iqbal et al., 2011). Canaki
& Gerpen (2001) melaporkan bahwa di
dalam minyak kopi terkandung komponen
utama triglesirida sebanyak 81,3% yang
dapat digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan biodiesel. Mukhriza (2010)
melakukan studi potensi kulit kopi dan biji
kopi kualitas rendah sebagai bahan baku
biodiesel. Iqbal et al. (2011) melakukan
penelitian pemanfaatan limbah kopi sebagai
bahan baku pembuatan biodiesel dengan
metode ekstraksi minyak kopi menggunakan
pelarut. Tahapan proses diawali dengan
proses ekstraksi minyak kopi menggunakan
pelarut dan dilanjutkan dengan degumming
dan penyaringan sampai diperoleh minyak
bebas gum. Analisis bilangan asam dilakukan
sebelum dilakukan proses transesterifikasi
dan pencucian yang akan menghasilkan
biodiesel kotor. Tahap pemurnian perlu
dilakukan agar diperoleh produk akhir
biodiesel dengan tingkat kemurnian yang
maksimum.
Bahan Baku Biogas
Biogas merupakan gas yang dihasilkan
dari proses penguraian bahan-bahan organik
dalam kondisi anaerobik. Biogas tersusun dari
74
gas metana (CH4), karbondioksida (CO 2),
nitrogen (N2), hidrogen (H2), hidrogen sufida
(H2S) dan oksigen (O 2) dengan komposisi
bervariasi tergantung asal bahan baku
biomassa yang digunakan. Nilai kalori 1 m3
biogas setara dengan 6.000 Wh atau 0,5 l
minyak diesel dan biogas sangat cocok
digunakan sebagai bahan bakar alternatif yang
ramah lingkungan pengganti bahan bakar
minyak, LPG, batu bara, dan bahan-bahan
lain yang berasal dari fosil.
Limbah cair pengolahan kopi mengandung bahan-bahan organik yang dapat
dimanfaatkan sebagai medium pertumbuhan
mikroorganisme dalam proses biofermentasi
(Wahyudi & Yusianto, 1993). Penelitian
pemanfaatan limbah pengolahan kopi sebagai
bahan baku proses produksi biogas telah
banyak dilakukan (Neves et al., 2005;
Rathinavelu & Graziosi, 2005; Dinsdale,
1996, Calzada et al., 1984). Kegiatan
penelitian dan pengembangan proses produksi
biogas dengan bahan baku limbah padat dan
cair pengolahan kopi secara intensif dalam
lima tahun terakhir telah dilakukan oleh Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao Indonesia.
Beberapa tipe reaktor biogas telah dikembangkan dengan berbagai kombinasi
bahan konstruksi dan kapasitas tampung
bahan baku antara 150 l sampai dengan
30 m 3. Biogas yang dihasilkan telah
digunakan sebagai sumber energi panas
proses pengolahan kopi, penerangan dan
penggerak pompa sirkulasi (Mulato et al.,
2006).
Sumber Panas Pengeringan
Limbah kulit kopi kering memiliki
potensi sebagai sumber energi panas (Saenger
et al., 2001), dan dapat digunakan dalam
proses pengeringan kopi (Rathinavelu &
Graziosi, 2005). Reaksi pembakaran senyawa
organik yang terkandung di dalam 1 kg kulit
kopi kering dengan oksigen akan melepaskan
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
energi panas antara 3.100-3.300 kKal
tergantung kadar airnya. Kulit kopi dapat
dimanfaatkan sebagai bahan bakar proses
pengeringan tembakau (Soepeno, 1989) dan
kopi denga sistem fluidisasi (Mulato et al.,
1996). Penggunaan kulit kopi sebagai bahan
bakar sumber panas proses pengeringan
tembakau cerutu Besuki dapat menekan
biaya pengeringan sebesar Rp. 33.000,- per
100 kg krosok dengan kenampakan daun
yang baik (Soepeno, 1989). Pembakaran
10 kg kulit kopi/jam dengan udara 200 m3/
jam menghasilkan suhu gas pembakaran
antara 250-275oC dan mampu memanaskan
udara pengering 1.500 m3/jam pada suhu
antara 45-50 oC dengan kelembaban relatif
20-25%. Udara panas tersebut mampu
mengeringkan satu ton buah kopi dari kadar
air 65% menjadi 12% dalam waktu 65 sampai
70 jam (Sri-Mulato et al., 1996).
Selain dalam bentuk bulky, diversifikasi
limbah kulit kopi kering sumber energi panas
dalam bentuk briket telah dilakukan oleh
Nurlela & Supranto (2011) dan hasil
penelitian menunjukkan bahwa kondisi
optimal untuk pembuatan briket dengan
bahan baku limbah kulit kopi Robusta adalah
ukuran partikel 120 mesh, perbandingan
perekat 1 : 8, dan suhu pirolisis 450C.
Karakteristik briket yang diperoleh adalah
kadar air 6,34%; kadar abu 7,6%, volatile
matter 5,34%, karbon terikat 81,72%, dan
nilai kalor 5.626,183 kalori/g.
Potensi Diversifikasi Produk Lain
Kegiatan penelitian dan pengembangan
untuk memperoleh teknologi diversifikasi
limbah padat dan cair pengolahan kopi masih
terus dilakukan untuk memperoleh ragam
produk dengan proses produksi yang efisien
dan peningkatan nilai tambah yang lebih baik.
Wahyudi & Yusianto (1993) melaporkan
bahwa limbah cair pengolahan kopi dapat
diproses menjadi makanan ternak berprotein
tinggi melalui proses biofermentasi, dan
produksi asam cuka. Prata & Oliveira (2007)
menggunakan kulit cangkang kopi sebagai
sumber bahan baku potensial untuk
menghasilkan antosianin. Rufford et al.
(2008) membuat elektrode karbon nanoporos
dari limbah padat biji kopi yang berfungsi
sebagai superkapasitor dengan performa
tinggi. Pengembangan proses gasifikasi
limbah kulit cangkang kopi dengan suhu
udara tinggi dilakukan oleh Wilson et al.
(2010). Akasaka et al. (2011) memanfaatkan
limbah padat kopi sebagai bahan baku
fabrikasi karbon porous yang berfungsi
untuk menyimpan hidrogen. Zuorro &
Lavecchia (2011) memproses limbah padat
bubuk kopi menjadi sumber campuran
senyawa fenol dan bioenergi. Ekstraksi
minyak kopi dari bahan baku limbah padat
biji kopi dilakukan oleh Al-Hamamre et al.
(2012) yaitu sebagai sumber bahan baku
terbarukan melalui proses produksi asam
lemak metil ester.
PENUTUP
Limbah padat dan cair pengolahan kopi
memiliki potensi untuk dapat diolah lanjut
menjadi produk pangan dan non pangan
dengan mutu serta nilai tambah yang lebih
baik. Bentuk diversifikasi produk yang dapat
dihasilkan antara lain papan partikel,
amelioran tanah, media tanam, kompos
organik, minuman ringan beralkohol,
minuman dengan kadar gula tinggi, media
produksi protein sel tunggal C. utilis, pakan
ternak, bioetanol, biodiesel, biogas, bahan
bakar sumber panas proses pengeringan dan
lain-lain. Beberapa teknologi diversifikasi
produk dapat diaplikasikan di lapangan
disesuaikan dengan skala produksi dan
prioritas fungsionalnya. Namun beberapa
teknologi diversifikasi masih perlu dikaji lebih
mendalam, terutama kajian awal skala
laboratorium untuk memperoleh kondisi
75
Widyotomo
optimum proses jika diaplikasikan pada skala
yang lebih besar. Diversifikasi produk dengan
sumber bahan baku berupa limbah
pengolahan kopi diharapkan dapat menekan
serendah mungkin dampak negatifnya
terhadap lingkungan dan memberikan
peningkatan pendapatan, serta peluang usaha
di sektor perkebunan kopi rakyat.
DAFTAR PUSTAKA
Akasaka, H.; T. Takahata; I. Toda; H. Ono;
S. Ohshio; S. Himeno; T. Kokubu &
H. Saitoh (2011). Hydrogen storage
ability of porous carbon material fabricated from coffee bean wastes. International Journal of Hydrogen Energy,
36, 580585.
Al-Hamamre, Z.; S. Foerster; F. Hartmann;
M. Krger & M. Kaltschmitt (2012).
Oil extracted from spent coffee
grounds as a renewable source for
fatty acid methyl ester manufacturing.
J. of Fuel, 96, 7076.
Azwar A.B. (2012). Intensifikasi kopi jadi
program unggulan baru. Media Perkebunan, 99, 16-17.
Baon, J.B.; R. Sukasih; Nurkholis & S.
Abdoellah (2000). Role of inorganic
and bio-activators and raw material
composition in the rate of decomposition and quality of coffee shell composts. Paper presented at The International Congress and Symposiumon
Southeast Asian Agricultural Science.
Bogor. Indonesia.
Baon, J.B.; R. Sukasih & Nurkholis (2005). Laju
dekomposisi dan kualitas kompos
limbah padat kopi: pengaruh aktivator
dan bahan baku kompos. Pelita
Perkebunan, 21, 31-42.
Baon, J.B.; S. Abdoellah; Pujiyanto; A. Wibawa;
R. Erwiyono; Zaenudin; A.M. Nur;
E. Mardiono & S. Wiryadiputra (2003).
Pengelolaan kesuburan tanah perkebunan kopi untuk mewujudkan
76
usaha tani yang ramah lingkungan.
Warta Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia, 19, 107-123.
Braham, J.E. & R. Bressani (1979). Coffee Pulp,
Composition, Technology and Utilization. International Development
Research Centre, Ottawa.
Bressani, R. (1979). Potential uses of coffee
berry by products. p. 17-24. In: J.E.
Braham & R. Bressani. Coffee Pulp,
Composition, Technology and Utilization. International Development
Research Centre, Ottawa.
Calzada, J.F.; E. de Porres; A. Yurrita; M.C. de
Arriola; F. de Micheo; C. Rolz; J.F.
Mench & A. Cabello (1984). Biogas
production from coffee pulp juice:
One- and two-phase systems. Agricultural Wastes, 9, 217230.
Canaki, M. & J.V. Gaspen (2001). Biodiesel from
oils and fats with hight free fatty
acids. Trans. Am. Soc. Automotive
Engine, 44, 1429-1436.
Clarke R.J. & R. Macrae (1989). Coffee Technology. Vol. 2. Elsevier Applied Science.
London and New York.
Daulay, D. (1991). Pebuatan cider kopi (Coffea
sp.). Skripsi. Departemen Teknologi
Pangan. Fakultas Teknologi Pertanian,
IPB.
Dinsdale, R.M.; F.R. Hawkes & D.L. Hawkes
(1996). The mesophilic and thermophilic anaerobic digestion of coffee
waste containing coffee grounds.
J of Water Research, 30, 371-377.
Ditjenbun (2006). Pedoman pemanfaatan limbah
dari pembukaan lahan. Direktorat
Jenderal Perkebunan. Departemen
Pertanian.
Elias, L.G. (1979). Chemical composition of
coffee berry by product. p. 11-16. In:
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
J.E. Braham & R. Bressani. Coffee Pulp,
Composition, Technology and Utilization. International Development
Research Centre, Ottawa.
Erwiyono, R.; Nurkholis & J.B. Baon (2001).
Laju perombakan kulit buah kopi,
jerami, dan cacahan kayu dengan
perlakuan mikroorganisme dan kualitas
kompos yang dihasilkan. Pelita
Perkebunan, 17, 64-71.
fermentasi rumen dan kecernaan in
vitro. Bionatura, 7, 46-58.
Indartono, Y. (2005). Bioethanol, alternatif energi
terbarukan: Kajian Prestasi Mesin dan
Implementasi di lapangan. Fisika, LIPI.
Iqbal, A.; A. Adri & D.A. Kartika (2011).
Pemanfaatan limbah kopi sebagai
bahan baku pembuatan biodiesel.
Usulan Program Kreativitas Mahasiswa. IPB. Bogor.
Gunasekaran, P. & K.C. Raj (1999). Ethanol
Fermentation Technology Zymomonas mobilis. Current Science, 77,
56-68.
Ismayadi, C. (2000). Perkembangan teknologi
pengolahan kopi arabika di Indonesia.
Warta Pusat Penelitian Kopi dan
Kakao Indonesia, 16, 239-251.
Guntoro, S. & I.M.R. Yasa (2005). Pengaruh
penggunaan limbah kopi terfermentasi
terhadap produktivitas susu kambing.
Prosiding Seminar Nasional Pemasyarakatan Inovasi Teknologi
Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan
di Lahan Marginal, Mataram 30-31
Agustus 2005. PSE, Bogor, p. 562-565.
Ismayadi, C.; T. Bantacut; A.A. Darwis &
B. Djatmiko (1987). Optimasi produksi
protein sel tunggal dari Candida utilis
dalam ekstrak kulit buah kopi dengan
kultur sinambung. Pelita Perkebunan,
2, 97-102.
Guntoro, S.; I.M.R. Yasa; Rubiyo & I.N. Suyasa
(2004). Optimasi integrasi usaha tani
kambing dengan tanaman kopi.
Prosiding Seminar Nasional Sistem
Integrasi Tanaman-Ternak, Denpasar,
20-22 Juli 2004, Haryanto, B.; Mathius
I.W.; Prawiradiputra B.R.; Lubis D.; A.
Priyanti & A. Djajanegara (eds.).
Puslitbangnak, Bogor, p. 389-395.
Guntoro, S.; M.R. Yasa & I Md. Londra (2002).
Hasil Pengkajian Pemanfaatan Limbah
Perkebunan (kakao dan kopi) Untuk
Pakan Ternak: Laporan Penelitian
Kerjasama BPTP Bali dengan Bappeda
Prop. Bali, Denpasar.
Ismayadi, C.; T. Wahyudi; A. Pratiwi & D.
Mangunwidjaja (1997). Kajian awal
pemanfaatan kulit buah kopi untuk
pembuatan minuman cider. Pelita
Perkebunan, 13, 40-50.
Isroi (2007). Pengomposan limbah kakao.
Materi Pelatihan TOT Budidaya Kopi
dan Kakao Staf BPTP di Pusat
Penelitian Kopi dan Kakao, Jember,
25 30 Juni 2007.
Lee, K.J.; D.E. Tribe & P.L. Rogers (1979).
Biotechnol. pp. 421. In: Lee, K.J.; Suku,
D.E.; Rogers, P.L. 1979. Biotechnol.
Lett., 1, 421.
Haygreen, J.G. & J.L. Bowyer (1996). Hasil
Hutan dan Ilmu Kayu: Suatu
Pengantar. Cetakan ketiga. Sutjipto
A. Hadikusumo, penerjemah. Yogyakarta, UGM Press.
Londra, I.M. & K.B. Andri (2009). Potensi
pemanfaatan limbah kopi untuk pakan
penggemukan kambing peranakan
Etawah. Prosiding Seminar Nasional:
Inovasi untuk Petani dan Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian,
p. 536-542.
Hernaman, I.; U.H. Tanuwiria & M.F. Wiyatna
(2005). Pengaruh penggunaan berbagai
tingkat kulit kopi dalam ransum
penggemukan sapi potong terhadap
Maloney, T.M. (1993). Modern Particleboard
and Dry Process Fiberboard Manufacturing. Miller Freeman, Inc. San
Fransisco.
77
Widyotomo
Mariyono & E. Romjali (2007). Petunjuk teknis
teknologi inovasi pakan murah
untuk usaha pembibitan sapi potong.
Puslitbang Peternakan. Badan Litbang
Pertanian. Departemen Pertanian RI.
Melawati, J. (2002). Reduksi biologi dari limbah
pabrik kopi menggunakan cacing tanah
Eisenia foetida. Buletin Kimia,
Puslitbang Teknologi Isotop dan
Radiasi, 2, 28-34.
Muchlis. (2011). Pemanfaatan limbah kopi
Robusta dan penambahan lemon
sebagai bahan baku pembuatan
minuman instan beraroma. Agricultural
Product Technology, Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara.
Mukhriza, T. (2010). Studi potensi kulit kopi
dan biji kopi kualitas rendah sebagai
bahan baku biodiesel. Kegiatan
Penelitian Dosen Muda Sumber Dana
Hibah APBA 2010. LPPM Universitas
Syiah Kuala. NAD.
Muryanto; U. Nuschati; D. Pramono & T.
Prasetyo (2006). Potensi limbah kulit
kopi sebagai pakan ayam. Prosiding
Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi Dalam Mendukung Usaha
Ternak Unggas Berdayasaing. BPTP
Jawa Tengah. p.111-116.
Musatto, S.I.; E.M.S. Machado; L.M. Carneiro
& J.A. Teixeira (2012). Sugars metabolism and ethanol production by different yeast strains from coffee industry
wastes hydrolysates. Journal of
Applied Energy, 92, 763768.
Neves, L.; R. Ribeiro; R. Oliveira & M.M. Alves
(2005). Anaerobic digestion of coffee
waste. Volume 1: Session 6b: Process
engineering, ADSW2005 Conference
Proceedings.
Nurlela & Supranto (2011). Pemanfaatan limbah
kulit kopi sebagai bahan bakar
alternatif dalam bentuk briket dan uji
unjuk kerjanya. Tesis. Magister Sistem
Teknik, Pascasarjana, UGM.
Pandey, A.; C.R. Soccol; P. Nigam; D. Brand;
R. Mohan & S. Roussos (2000). Bio-
78
chemical Engineering Journal, 6,
153162.
Parwati, I.A.; N. Suyasa & M. Rai Yasa (2006).
Kelayakan penggunaan limbah kopi
untuk penggemukan sapi potong di
Kabupaten Bangli. Prosiding Seminar
Nasional Pemasyarakatan Inovasi
Teknologi Pertanian sebagai
Penggerak Ketahanan Pangan,
Mataram, 5-6 September 2006. BBP2TP,
p. 359-365.
Prata, E.R.B.A. & L.S. Oliveira (2007). Fresh
coffee husks as potential sources of
anthocyanins. Food Science and
Technology, 40, p. 15551560.
Prawirodigdo, S.; B. Utomo & T. Herawati
(2007). Prospek intensifikasi penggunaan kulit kopi dalam diet ternak
domba di daerah marginal. Prosiding
Inovasi dan Alih Teknologi Pertanian
untuk Pengembangan Agribisnis
Industrial Pedesaan di Wilayah
Marjinal: Inovasi Teknologi Produksi, Semarang, 8 Nov 2007. p. 316322. In: Muryanto; T. Prasetyo; S.
Prawirodigdo; Yulianto; A. Hermawan
E. Kushartanti; S. Mardiyanto; Sumardi
& T. Herawati (eds.). BBP2TP Bogor.
Prawirodigdo, S.; T. Herawati; B. Utomo;
Muryanto; J. Purmianto & Sudarto
(2007). Teknologi pembuatan formula
pakan ternak domba dari limbah kopi.
Prosiding Seminar Nasional Teknologi
Peternakan dan Veteriner, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Bogor. p. 316-322.
Prawirodigdo, S.; T. Herawati & B. Utomo (2005)
Pemanfaatan kulit kopi sebagai
komponen pakan seimbang untuk
penggemukan ternak domba. Prosiding Seminar Nasional Teknologi
Peternakan dan Veteriner. p. 438-444.
In: I.W. Mathius; S. Bahri; Tarmudji;
L.H. Prasetyo; E. Triwulanningsih;
B. Tiesnamurti; I. Sendow &
Potensi dan teknologi diversifikasi limbah kopi menjadi produk bermutu dan bernilai tambah
Suhardono (eds.). Puslit-bangnak,
Bogor, 12-13 Sep 2005.
Pujiyanto (2007). Pemanfaatan kulit buah kopi
dan bahan mineral sebagai amelioran
tanah alami. Pelita Perkebunan, 23,
104-117.
Ramadhanu, S. & I Putri (2012). Pemanfaatan
Daging Buah Kopi Sebagai Alternatif
Pengganti Gula Pasir Untuk Mengurangi Risiko Terkena Diabetes.
Karya Ilmiah ISPO. SMAN 1 Takengon
Acah Tengah.
Rathinavelu, R. & G. Graziosi (2005). Potential
alternative uses of coffee wastes and
by-products. ICS-UNIDO, Science
Park, Department of Biology, University of Trieste, Italy.
Rodiah (2007). Pengesktrakan dan sifat-sifat
ekstrak yis daripada Candida utilis.
Tesis Sarjana Sains. Universiti Sains
Malaysia.
Rufford, T.E.; D. Hulicova-Jurcakova; Z. Zhu
& G. Qing Lu (2008). Nanoporous carbon electrode from wastecoffee beans
for high performance supercapacitors.
J. of Electrochemistry Communications, 10, 15941597.
Saenger, M.; E.-U Hartge; J. Werther; T. Ogada,
& Z. Siagi (2001). Combustion of
coffee husks. J. of Renewable Energy,
23, 103-121.
meningkatkan laju pertumbuhan > 30%
dan efisiensi pakan > 20% pada
kambing Boerka. Laporan Akhir
Penelitian Program Insentif Riset
Terapan. Puslitbang Ternak. Loka
Penelitian Kambing Potong Sei Putih.
Sumatera Utara.
Siswati, N.D.; M. Yatim & R. Hidayanto (2012).
Bioetanol dari limbah kulit kopi dengan
proses fermentasi. Skripsi. Jurusan
Teknik Kimia, Fakultas Teknologi
Industri, Universitas Pembangunan
Nasional Veteran, Jawa Timur.
Soepeno (1989). Limbah kulit buah kopi sebagai
bahan bakar dalam pengeringan
tembakau Besuki Na-Oogst. Warta
Balai Penelitian Perkebunan Jember,
8, 27-31.
Sri-Mulato; O. Atmawinata & Yusianto (1996).
Perancangan dan pengujian tungku
pembakaran kulit kopi sistem fluidisasi.
Pelita Perkebunan, 12, 108-118.
Tampoebolon (2004). Amoniasi kulit kopi. Lab.
Teknologi Makanan Ternak, Jurusan
Nutrisi dan Makanan Ternak. Fakultas
Peternakan. Universitas Diponegoro.
Wahyudi, T. & Yusianto (1993). Karakteristik
limbah cair pabrik pengolahan kopi.
Pelita Perkebunan, 9, 113-123.
Wibowo R. (2010). Pemanfaatan limbah kulit
buah kopi sebagai media tanam
alternatif untuk pertumbuhan tanaman
anthurium (Anthurium plowmanii
Scoat). Skripsi. Jurusan Budidaya
Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Brawijaya.
Santoso (1996). Pakan Ayam Buras. Instalasi
Penelitian dan Pengkajian Teknologi
Pertanian. Badan Litbang Pertanian.
DKI Jakarta.
Widyotomo, S. (2010). Evaluasi kinerja mesin
pengupas kulit buah kopi basah tipe
silinder horisontal. Jurnal Enjiniring
Pertanian, 8, 27-38.
Sardjoko (1991). Bioteknologi Latar Belakang
dan Beberapa Penerapannya. Gramedia
Pustaka Umum-Jakarta.
Widyotomo, S.; Sri-Mulato & E. Suharyanto
(2006). Optimasi mesin sortasi biji kopi
tipe meja konveyor untuk meningkatkan kinerja sortasi manual. Pelita
Perkebunan, 22, 57-75.
Simanihuruk, K. (2010). Perakitan pakan komplit
berbasis kulit kopi (sumber serat NDF
dan ADF), kecernaan > 60% dan
Widyotomo, S. & Sri-Mulato (2004). Kinerja
mesin pengupas kulit kopi kering tipe
79
Widyotomo
silinder horisontal. Pelita Perkebunan,
20, 75-96.
Widyotomo, S. & Sri-Mulato (2005). Kinerja
mesin sortasi biji kopi tipe meja getar.
Pelita Perkebunan, 21, 55-72.
Wilbaux R. (1963). Coffee Processing. Food
and Agriculture Organization of United
Nation. Rome.
Wilson, L.; G.R. John; C.F. Mhilu; W. Yang &
W. Blasiak (2010). Coffee husks gasification using high temperature air/
steam agent. Fuel Processing Technology , 91, 1330-1337.
Winaryo; Usman & S. Mawardi (1995).
Pengaruh komposisi bahan bakudan
lama pengomposan terhadap mutu
kompos. Warta Pusat Penelitian Kopi
dan Kakao, 11, 26-32.
Yusianto; S. Widyotomo & Sri-Mulato (1999).
Studi pembuatan papan partikel dari
kulit kopi kering. Pelita Perkebunan,
15, 188-202.
80
Zaenudin & S. Abdoellah (2003). Program
pengembangan teknologi dalam rangka
mendukung perkopian nasional yang
tangguh. Warta Pusat Penelitian Kopi
dan Kakao Indonesia, 19, 39-44.
Zainuddin, D. & T. Murtisari (1995). Penggunaan
limbah agro-industri buah kopi (kulit
buah kopi) dalam ransum ayam
pedaging (Broiler). Pros. Pertemuan
IImiah Komunikasi dan Penyaluran
Hasil Penelitian. Semarang. Sub Balai
Penelitian Klepu, Puslitbang Petemakan,
Badan Litbang Pertanian, p. 71-78.
Zuorro, A. & R. Lavecchia (2011). Spent
coffee grounds as a valuable source
of phenolic compounds and bioenergy.
Journal of Cleaner Production, 34,
49-56.
*********
Anda mungkin juga menyukai
- Paper Kopi CelupDokumen11 halamanPaper Kopi CelupLarasati GandaningarumBelum ada peringkat
- Perancangan Produksi Bersih Pada Industri KopiDokumen9 halamanPerancangan Produksi Bersih Pada Industri KopiRian Hakim Oi RayaBelum ada peringkat
- Laporan PuslitkokaDokumen12 halamanLaporan PuslitkokaHilda Febrinda SariBelum ada peringkat
- Tugas 3 Sandonela AngginiDokumen13 halamanTugas 3 Sandonela AngginiSandonela AngginiBelum ada peringkat
- Rantek Lindri&Iranda TP12Dokumen22 halamanRantek Lindri&Iranda TP12Lindri Roesly FiameldaBelum ada peringkat
- Proposal Project Kelompok 4Dokumen4 halamanProposal Project Kelompok 4pirangj977Belum ada peringkat
- Kopi Instan BubukDokumen34 halamanKopi Instan BubukAflah Athallah MajidBelum ada peringkat
- Bio Etanol Dari Limbah Kulit KopiDokumen11 halamanBio Etanol Dari Limbah Kulit KopiRizanti FadilahBelum ada peringkat
- Makalah Pengolahan Limbah Industri KopiDokumen16 halamanMakalah Pengolahan Limbah Industri KopiChilvya Natasya D'frivers100% (1)
- Perkebunan Yang Tidak MengebunkanDokumen16 halamanPerkebunan Yang Tidak MengebunkanAriq AmanullohBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian PDFDokumen20 halamanProposal Penelitian PDFMeisy TriyaBelum ada peringkat
- KopiDokumen16 halamanKopiZella PurnamaningtyasBelum ada peringkat
- Laporan Field Trip MSDDokumen11 halamanLaporan Field Trip MSDMuhammad Syaiful GunawanBelum ada peringkat
- Laporan Magang Di PTPN XII KebDokumen14 halamanLaporan Magang Di PTPN XII KebDio Yanuarsyah ArinandaBelum ada peringkat
- Makalah KopiDokumen12 halamanMakalah KopiZacky Zafiri DurarBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok Teknologi LimbahDokumen10 halamanMakalah Kelompok Teknologi LimbahRodiJumadilAkhirBelum ada peringkat
- Laporan Kopi Robusta FixDokumen14 halamanLaporan Kopi Robusta FixDessy Putri SonaBelum ada peringkat
- Proposal KopiDokumen7 halamanProposal KopiAndimuplihaqBelum ada peringkat
- Tugas Besar Pabrik KopiDokumen33 halamanTugas Besar Pabrik KopiSukamto BapakBelum ada peringkat
- Jurnal Serambi Engineering-Produksi BioetanolDokumen8 halamanJurnal Serambi Engineering-Produksi BioetanolsaisaahmadBelum ada peringkat
- Kelompok 2 Manajemen Agribisnis KopiDokumen14 halamanKelompok 2 Manajemen Agribisnis KopiNandaNWBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum TPTP 1 PrijuDokumen14 halamanLaporan Praktikum TPTP 1 PrijuPriju HarpentaBelum ada peringkat
- Penerapan Teknologi Pascapanen Untuk Meningkatkan Kualitas Kopi IndonesiaDokumen11 halamanPenerapan Teknologi Pascapanen Untuk Meningkatkan Kualitas Kopi Indonesiaaeneaann456Belum ada peringkat
- Tugas Besar Pabrik KopiDokumen34 halamanTugas Besar Pabrik KopiArsyl CobesBelum ada peringkat
- KOPI MateriDokumen178 halamanKOPI Materisanti dwiBelum ada peringkat
- Penggunaan Enzim PektinaseDokumen10 halamanPenggunaan Enzim PektinaseDaniall AbdanBelum ada peringkat
- Sirup Kopi Instan Sebagai Inovasi ProdukDokumen27 halamanSirup Kopi Instan Sebagai Inovasi ProdukMuhammad Ihsan RismulidanBelum ada peringkat
- Perkebunan Kopi Teh KakaoDokumen14 halamanPerkebunan Kopi Teh KakaoAriq AmanullohBelum ada peringkat
- Makalah Alat Dan Mesin Pengolah KopiDokumen12 halamanMakalah Alat Dan Mesin Pengolah KopiTeddy AFBelum ada peringkat
- Review JurnalDokumen11 halamanReview JurnalDinda HersandiBelum ada peringkat
- Laporan PraktikumDokumen25 halamanLaporan PraktikumDhevhy CHristhBelum ada peringkat
- Bulletproof Coffee OkeDokumen36 halamanBulletproof Coffee OkeSumeyyatun WahyuneiBelum ada peringkat
- RADAR Vol02 No01 September 2021Dokumen7 halamanRADAR Vol02 No01 September 2021Renggo DarsonoBelum ada peringkat
- Tugas PenyegarDokumen19 halamanTugas PenyegarNatya Laksmi PutriBelum ada peringkat
- KP 2011 669 Proposal PDFDokumen51 halamanKP 2011 669 Proposal PDFSulili Nurdin100% (1)
- 1 Sistem Produksi Agroindustri Kopi ArabikaDokumen13 halaman1 Sistem Produksi Agroindustri Kopi ArabikaAuliannissa FitrianBelum ada peringkat
- Kelompok 6 - Praktek Manajemen Agroindustri PerkebunanDokumen16 halamanKelompok 6 - Praktek Manajemen Agroindustri PerkebunanNatasya Fajrianti NurainiBelum ada peringkat
- Format Laprak THPDokumen16 halamanFormat Laprak THPUKM GSSTFBelum ada peringkat
- Kop IDokumen30 halamanKop ISagitaa DwiiBelum ada peringkat
- Tugas KOPIDokumen21 halamanTugas KOPIsilviaputrimrzBelum ada peringkat
- Makalah Limbah TahuDokumen12 halamanMakalah Limbah TahuLia ChoirunnisaBelum ada peringkat
- Proses Pengolahan KopiDokumen23 halamanProses Pengolahan KopiranrobertBelum ada peringkat
- Laporan Pengolahan KopiDokumen4 halamanLaporan Pengolahan KopiYatikBelum ada peringkat
- Laporan Pemangkasan KopiDokumen13 halamanLaporan Pemangkasan KopiYurni ArrangBelum ada peringkat
- Makalah Limbah TahuDokumen13 halamanMakalah Limbah TahuMuhammadWajjahBelum ada peringkat
- Tugas 3 - Sasaran Dan Titik Kritis Budidaya Tanaman Kopi - Kelompok 7Dokumen3 halamanTugas 3 - Sasaran Dan Titik Kritis Budidaya Tanaman Kopi - Kelompok 7Risma Wahyu Hidayah100% (1)
- Kelompok 1 Limbah Tahu KesmasDokumen21 halamanKelompok 1 Limbah Tahu KesmasAndreas CollinBelum ada peringkat
- Pengolahan KopiDokumen17 halamanPengolahan Kopideden_soleh100% (1)
- Makalah Pengelolaan PerkebunanDokumen19 halamanMakalah Pengelolaan PerkebunanAzizMantongNanLonBelum ada peringkat
- MAKALAH KBS Barat WetanDokumen13 halamanMAKALAH KBS Barat WetanM Gilang alfasha AlBelum ada peringkat
- Teknologi Bersih Kimia Layla Putri-1Dokumen15 halamanTeknologi Bersih Kimia Layla Putri-1Laila PutriBelum ada peringkat
- Kelompok 7 - Penyeduhan Kopi Arabika - T.P. KopiDokumen14 halamanKelompok 7 - Penyeduhan Kopi Arabika - T.P. KopiMarta IndrianiBelum ada peringkat
- Makalah AmkeeDokumen22 halamanMakalah AmkeeRubel rizky mahesaBelum ada peringkat
- Proposal KopiDokumen11 halamanProposal KopiRuli KayladafaBelum ada peringkat
- Proses Pengolahan KopiDokumen25 halamanProses Pengolahan KopiNyekti Priasti100% (2)
- Makalah Kopi. Prombakan Biji KopiDokumen31 halamanMakalah Kopi. Prombakan Biji Kopigading ananda putra pratamaBelum ada peringkat
- Tanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauDari EverandTanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauBelum ada peringkat