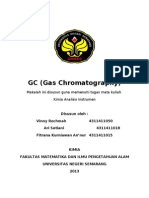Cara Menentukan Letak Perusahaan
Cara Menentukan Letak Perusahaan
Diunggah oleh
Cici RidianingsihJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Cara Menentukan Letak Perusahaan
Cara Menentukan Letak Perusahaan
Diunggah oleh
Cici RidianingsihHak Cipta:
Format Tersedia
Cara Menentukan Letak Perusahaan
Secara umum terdapat 2 (dua) macam cara untuk menentukan lokasi
perusahaan yaitu :
1. Cara Kualitatif
Cara ini diadakan penilaian secara kualitatif terhadap faktor-faktor yang dianggap
relevan atau memegang peranan pada setiap pilihan lokasi. Ukuran penilaian dinyatakan
dalam : baik sekali (bs), baik (b), sedang (s), kurang (k), dan kurang sekali (ks).
Misalnya suatu industri baik akan memilih 4 (empat) kota sebagai lokasi perusahaan :
1. Solo
2. Yogyakarta
3. Semarang
4. Purwokerto
Faktor yang dinilai ialah : bahan baku, tenaga kerja, tenaga pembangkit listrik,
transportasi, pasar (konsumen).
Faktor-Faktor
Bahan baku
Tenaga kerja
Listrik
Transportasi
Pasar
Lokasi
Solo
b
bs
b
bs
bs
Yogyakarta
bs
b
b
s
k
Semarang
b
s
b
b
b
Purwokerto
bs
bs
s
k
k
Dari hasil analisis pada masing masing alternatif tersebut dapat disimpulkan lokasi
yang paling ideal adalah Solo.
2. Cara Kuantitatif (sederhana)
Dengan cara ini hasil analisis kualitatif dikuantifikasikan dengan cara memberikan skor
(nilai) pada masing masing kiteria. Dengan contoh pada tabel 1, ditetapkan nilai untuk
masing masing kriteria : bs=5 , b=4, s=3, b=4, s=3, k=2, ks=1. keadaan selanjutnya
dapat dilihat pada tabel berikut.
FAKTORFAKTOR
LOKASI
SOLO
JUMLAH
NILAI
YOGYAKARTA
SEMARANG
PURWOKERTO
KEADAAN
b
bs
b
bs
bs
NILAI
4
5
4
5
5
KEADAAN
bs
b
b
s
k
NILAI
5
4
4
3
2
KEADAAN
b
s
b
b
b
NILAI
4
3
4
4
4
KEADAAN
bs
bs
s
k
k
NILAI
5
5
3
2
2
23
18
19
17
Dapat dilihat bahwa, kota PEKALONGAN memang mempunyai nilai tertinggi
dibandingkan dengan ke tiga kota lainnya.
Penetapan Lokasi Perusahaan menurut Teori Alfred Weber
Dalam teorinya, Weber mengemukakan ada dua faktor yang mempengruhi penetapan
lokasi perusahaan, yaitu :
Biaya Pengangkutan
Biaya Tenaga Kerja
1.
2.
Titik tolak analisis weber terletak pada faktor biaya pengangkutan, kemudian
diperhatikan pula biaya tenaga kerja. Apabila suatu industri menganggap biaya
pengangkutan menjadi faktor utama dalam menetapkan lokasi perusahaan, maka
perusahaan akan didirikan pada suatu titik pada garis lurus yang menghubungkan Tempat
Bahan Mentah (TBM) dan Daerah Konsumen (DK).
(TBM)x..x (DK)
Untuk dapat menetapkan Tempat Kediaman Perusahaan (TKP) antara TBM dan DK,
maka menurut Weber harus dilihat sifat bahan mentah yang digunakan perushaan dan
corak proses produksinya.
1.
Sifat bahan mentah dan corak proses produksinya dapat dibedakan sebagai berikut :
Ubikuitas mutlak
Yaitu bahan baku yang tersedia dalam jumlah tidak terbatas dan terdapat dimana saja.
Misalnya udara bagi pabrik gas.
2.
Ubikuitas Relatif
Yaitu bahan baku yang tersedia dalam jumlah tidak terbatas, tetapi hanya ada di beberapa
tempat tertentu saja. Misalnya tanah liat untuk pabrik batu bata. Ubikuitas Relatif ini ada
dua jenis yaitu:
-
bahan baku seluruhnya habis dipakai dalam proses produksi
bahan baku hanya sebagian saja yang dipakai dalam proses produksi atau
terdapat kemerosotan berat bahan baku.
3. Dibutuhkan berbagai bahan baku yang tempatnya terpisah-pisah.
Apabila jenis bahan baku yang digunakan oleh perusahaan adalah
Ubikuitas Mutlak maka tentu saja TKP akan berada di DK sebab jika diluar DK berarti
perusahaan akan mengeluarkan biaya pengangkutan hasil produksi ke DK. Jika bahan baku
yang diperlukan perusahaan terdapat juga di DK maka perusahaan cenderung memilih TKP
mendekati DK.
Apabila seluruh bahan mentah habis digunakan dalaln proses produksi
yaitu jenis Ubikuitas Relatif, maka TKP akan berada di DK atau pada tiap-tiap titik antara
TBM dan DK. Jadi disini misalkan digunakan 300 kg ahan mentah yang dimasukkan kedalam
proses produksi maka akan dihasilkan 300 kg barang jadi. Oleh karena itu mengangkut bahan
mentah resikonya lebih kecil dibanding jika mengangkut barang jadi, maka perusahaan
cenderung menempatkan TKP dan DK.
CONTOH :
Jarak antara TBM-DK=200 km
Biaya pengangkutan untuk 1 kg/200 km=Rp 200,00
Jumlah bahan mentah yang digunakan= 400 kg
Penyelesaian :
1. Apabila TKP berada di DK, maka besarnya biaya pengangkutan yang dikeluarkan
hanyalah biaya pengangkutan bahan mentah dari TBM ke DK yaitu sebesar : 400
x Rp. 200,00 = Rp. 80.000,00
2. Apabila TKP berada 100 km dari TBM dan dari Dk (TKP berada ditengah jarak
TBM-DK), maka biaya pengangkutan yang dikeluarkan ialah untuk mengankut
bahan mentah dari TBM ke TKP serta biaya pengankutan barang jadi dari TKP ke
DK.
200 km
TBM
TKP
DK
Jadi biaya yang dikeluarkan :
400 kg bahan mentah @ Rp 100,-/100 km
= Rp 40.000,400 kg bahan jadi @ RP 100.-/100 km
= Rp 40.000,Jumlah biaya pengangkutan
= RP 80.000,Dari contoh diatas maka TKP akan berada di DK maupun pada setiap titik antara TBM
dan DK.
o
Apabila hanya sebagian saja dari bahan mentah akan menjadi barang jadi, maka TKP
akan berada di TBM.
CONTOH :
150 kg bahan mentah yang diproses akan menjadi 90 kg barang jadi.
Biaya pengangkutan bahan mentah tiap kg/tiap km =Rp 100,00
Biaya pengangkutan barang jadi tiap kg/km
=150,00
Jarak TBM-DK=100 km.
Dalam hal ini kita akan mencoba mencari TKP antara TBM-DK yang mempunyai biaya
pengangkutan paling rendah:
TBM
50 km
25 km
DK
TKP I
TKP II
TKP III
100 km
Misalkan :
Kita ambil TKP 1 di TBM, maka biaya pengangkutan bahan mentah menjadi barang jadi
sebesar: (150x0xRp 100,-)+(90x100xRp 150,-) = Rp 1.350.000,00
2. Kita ambil TKP II di tengah-tengah jarak TBM-DK yaitu 50 km dari TBM dan 50 km
dari DK; maka biaya pengangkutan bahan mentah dan barang jadi sebesar:
(150x50xRp 100,-)+(90x50xRp 150,-) =Rp. 1.425.000,00
3. Kita ambil TKP III di titik sejauh 75 km dari TBM dan 25 km dari DK, maka biaya
pengangkutan bahan mentah dan barang jadi sebesar:
(150x75xRp 100,-)+(90x25xRp 150,-) = Rp 1.462.500,00
1.
Kesimpulan:
1. Biaya pengangkutan paling rendah sebesar Rp 1.350.000,- yaitu apabila TKP terletak di
TBM
2. Terlihat apabila semakin jauh TKP dari TBM (atau semakin mendekati DK), maka biaya
total pengangkutan semakin besar, karena terdapat kemerosotan berat bahan mentah yang
cukup besar sehingga berat barang jadi lebih kecil dari berat bahan mentahnya.
o Apabila dibutuhkan berbagai bahan mentah yang tempatnya terpisah-pisah, maka
TKP seperti dalam contoh berikut ini akan berada dimana: ax+by+cz adalah terkecil.
X km
TBM I
TKP
a. kg bahan mentah
b. kg bahan pembantu
c kg barang jadi
z km
DK
TBM II
Y km
1.
2.
3.
Dari TBM I di dapat a kg bahan mentah; jarak TBM TKP=x km
Dari TBM II diperoleh b kg bahan pembantu; jarak TBM II TKP=y km
Kedua bahan tersebut diproses di TKP dan menghasilkan c kg barang jadi; jarak TKP
DK=z km
Maka pada saat ax + by + cz = angka paling kecil, ini disebut Titik Biaya Total
Pengangkutan yang optimal atau merupakam TKP terbaik.
INDEKS MATERIAL
Indeks material merupakan hasil bagi antara berat bahan mentah ditambah berat bahan
pembantu dibagi berat barang jadi.
Indeks material = ( a + b )/c
1.
2.
Ketentuan :
Jika indeks material lebih besar daripada satu berarti tidak semua bahan yang digunakan
dalam proses produksi menjadi barang jadi atau terdapat sisa dari bahan yang tidak dapat
dipergunakan. Dalam hal ini maka TKP akan cenderung berada di TBM.
Apabila indeks material sama dengan satu, berarti semua bahan yang digunakan dalam
proses produksi dipakai (tidak ada sisa bahan). Dalam hal ini TKP didirikan dimanapun
sama saja. Hanya karena pertimbangan resiko kerusakan barang, maka lebih baik TKP
berada di DK saja.
CONTOH :
Berat bahan baku =120 Ton; berat bahan pembantu=160 ton; berat barang jadi=200 ton.
Maka indeks mateialnya adalah= (120+160)/200=1,4 atau >1.
Berat bahan baku =120 ton; berat bahan pembantu =80 ton; berat barang jadi=200 ton.
Maka indeks materialnya adalah = (120+80)/200=1
Anda mungkin juga menyukai
- EkonomiDokumen4 halamanEkonomiMiftahudinBelum ada peringkat
- Kelompok 2 Perilaku Kelompok Dan Interpersonal @@@@Dokumen14 halamanKelompok 2 Perilaku Kelompok Dan Interpersonal @@@@Adinda Novia SariBelum ada peringkat
- Makalah Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian NasioanalDokumen15 halamanMakalah Koperasi Sebagai Soko Guru Perekonomian NasioanalAlifia dewi arimurti 118Belum ada peringkat
- Implementasi Etika Bisnis Sabana Fried ChickenDokumen15 halamanImplementasi Etika Bisnis Sabana Fried ChickenDara puspitaBelum ada peringkat
- Fungsi PersonaliaDokumen13 halamanFungsi PersonaliaBayu Terayana100% (2)
- Marketing Mix (9P) - 2Dokumen2 halamanMarketing Mix (9P) - 2ria paramita100% (1)
- Sejarah Perkembangan Dan Tantangan MSDMDokumen15 halamanSejarah Perkembangan Dan Tantangan MSDMcapt.sigitwBelum ada peringkat
- Buku BesarDokumen20 halamanBuku BesarikaBelum ada peringkat
- Manjemen Keuangan PiutangDokumen11 halamanManjemen Keuangan PiutangNi Wayan AmbaryatiBelum ada peringkat
- Kelompok 7 - Sia - KasusDokumen11 halamanKelompok 7 - Sia - KasusSaniya SafiraBelum ada peringkat
- Jenis Jenis Letak PerusahaanDokumen4 halamanJenis Jenis Letak Perusahaaningka diaseviBelum ada peringkat
- Paper Koperasi Kelompok 4Dokumen11 halamanPaper Koperasi Kelompok 4Wid Wid Widya0% (1)
- Soal Remidi Akuntansi BiayaDokumen1 halamanSoal Remidi Akuntansi BiayaYohanes Anton NugrohoBelum ada peringkat
- Analisis Modal Kerja Terh. Laba Pada PT. Prima Karya Manunggal (Syamsiah)Dokumen33 halamanAnalisis Modal Kerja Terh. Laba Pada PT. Prima Karya Manunggal (Syamsiah)Hajar BscBelum ada peringkat
- Makalah MSDM Kelompok 6Dokumen14 halamanMakalah MSDM Kelompok 6Bagus PutraBelum ada peringkat
- Abstrak: Penelitian Berjudul Analisis Tingkat Kesehatan KSP KOPDIT Solidaritas Sta. Maria Assumpta Kupang Tahun 2018-2020 Bertujuan Untuk MengetahuiDokumen5 halamanAbstrak: Penelitian Berjudul Analisis Tingkat Kesehatan KSP KOPDIT Solidaritas Sta. Maria Assumpta Kupang Tahun 2018-2020 Bertujuan Untuk MengetahuiDamiyana werangBelum ada peringkat
- MAKALAH AsuransDokumen7 halamanMAKALAH AsuransRahman HadiBelum ada peringkat
- RESUME - Ekonomi ManajerialDokumen5 halamanRESUME - Ekonomi ManajerialAgiantini Malida Atori0% (1)
- Data DayaDokumen7 halamanData DayaDeni100% (1)
- Manajemen Produksi Dan Operasi Modul 1Dokumen10 halamanManajemen Produksi Dan Operasi Modul 1Taufiqurrahman SholehBelum ada peringkat
- KTI Peranan KPN Siantar MatrobaDokumen27 halamanKTI Peranan KPN Siantar Matrobaaldi silalahi789Belum ada peringkat
- Makalah Analisis Laporan Keuangan - BRISDokumen14 halamanMakalah Analisis Laporan Keuangan - BRISQiroati SyarifahBelum ada peringkat
- Laporan Hasil Wawancara Sia Siklus MSDMDokumen20 halamanLaporan Hasil Wawancara Sia Siklus MSDMAdinda ChristikaBelum ada peringkat
- Kasus PT CampinaDokumen1 halamanKasus PT CampinaAjiwBelum ada peringkat
- Contoh Makalah Karya Tulis Ilmiah Tentang Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi IndonesiaDokumen14 halamanContoh Makalah Karya Tulis Ilmiah Tentang Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi IndonesiaLaura AmeliaBelum ada peringkat
- Tugas 4Dokumen23 halamanTugas 4Hasdar NsrdnBelum ada peringkat
- "Perencanaan Sistem Persediaan Bahan Baku GunaDokumen9 halaman"Perencanaan Sistem Persediaan Bahan Baku GunaAji StoreBelum ada peringkat
- Makalah Eko KopDokumen33 halamanMakalah Eko KopHengkyBelum ada peringkat
- Fungsi Penawaran (Suppply)Dokumen22 halamanFungsi Penawaran (Suppply)Alfian SyahputraBelum ada peringkat
- KELOMPOK 4 BAB 10, 11 12 BaruDokumen10 halamanKELOMPOK 4 BAB 10, 11 12 BarumarseliusjonathanprasetioBelum ada peringkat
- Pengantar Bisnis Bab 11 Manajemen Sumber Daya ManusiaDokumen6 halamanPengantar Bisnis Bab 11 Manajemen Sumber Daya ManusiabalaranBelum ada peringkat
- Pubk Kelompok 1Dokumen20 halamanPubk Kelompok 1ReginaBelum ada peringkat
- Restrukturisasi Organisasi & Keterlibatan KaryawanDokumen26 halamanRestrukturisasi Organisasi & Keterlibatan KaryawanBintang Prasetyo AnastoBelum ada peringkat
- Makalah MSDM NadiaDokumen10 halamanMakalah MSDM Nadianadia sihalohoBelum ada peringkat
- Dana PensiunDokumen22 halamanDana PensiunAbdu ArrahmanBelum ada peringkat
- Tugas SIMDokumen12 halamanTugas SIMRika Ajalah21Belum ada peringkat
- Kasus Bank Century Kelompok 3Dokumen6 halamanKasus Bank Century Kelompok 3sheneedzBelum ada peringkat
- Analisis Perilaku Dan Motivasi Karyawan Akan Memengaruhi Kualitas Operasional KaryawanDokumen7 halamanAnalisis Perilaku Dan Motivasi Karyawan Akan Memengaruhi Kualitas Operasional KaryawanRafi Latifah FitriBelum ada peringkat
- BKP Dan JKPDokumen12 halamanBKP Dan JKPantia saraswatiBelum ada peringkat
- PROSEDUR MENDIRikan PerusahaanDokumen20 halamanPROSEDUR MENDIRikan PerusahaanAswar AnasBelum ada peringkat
- Teori Manajemen OperasionalDokumen12 halamanTeori Manajemen OperasionalRyo ChoeplizBelum ada peringkat
- Kombis Lintas Budaya (295,296,298)Dokumen12 halamanKombis Lintas Budaya (295,296,298)AryaPratamaPutraBelum ada peringkat
- Kasus Pelanggaran Etika (Agung Rahadi Y 20010000014) PDFDokumen4 halamanKasus Pelanggaran Etika (Agung Rahadi Y 20010000014) PDFAgung RahadiBelum ada peringkat
- Latihan Soal Lap KeuDokumen8 halamanLatihan Soal Lap KeuDedi SetiawannBelum ada peringkat
- Bab 4 BENTUK-BENTUK ORGANISASI BISNIS BY BUYUNG LUHUR PAMBUDIDokumen16 halamanBab 4 BENTUK-BENTUK ORGANISASI BISNIS BY BUYUNG LUHUR PAMBUDIBuyung Luhur PambudiBelum ada peringkat
- Pentingnya Manajemen Sumber Daya ManusiaDokumen5 halamanPentingnya Manajemen Sumber Daya ManusiaPratiwi SaputriBelum ada peringkat
- Analisis Faktor EksternalDokumen5 halamanAnalisis Faktor EksternalLeni RosiyaniBelum ada peringkat
- Latihan Soal PE Mikro - BAG-1Dokumen6 halamanLatihan Soal PE Mikro - BAG-1Gunawan Setio Purnomo100% (2)
- MAKALAH Kelompok 6 KPSBUDokumen70 halamanMAKALAH Kelompok 6 KPSBURheza RahmanBelum ada peringkat
- Makalah Etika Bisnis Kelompok 1 Offering EDokumen21 halamanMakalah Etika Bisnis Kelompok 1 Offering E2Achmad Rifal TurmujiBelum ada peringkat
- Jenis SahamDokumen14 halamanJenis SahamRama SidhimantraBelum ada peringkat
- Diskusi 12 Hukum BisnisDokumen1 halamanDiskusi 12 Hukum BisnisEga Pamungkas DawamiBelum ada peringkat
- Contoh Kasus Pelanggaran Etika BisnisDokumen2 halamanContoh Kasus Pelanggaran Etika BisnisGhina Zahida100% (1)
- Sim Bab 8Dokumen10 halamanSim Bab 8ridhia melliyaniBelum ada peringkat
- Makalah Model Resiko Multifaktor EquityDokumen26 halamanMakalah Model Resiko Multifaktor EquityIkhwaan ArchiitectureBelum ada peringkat
- 4866 10013 1 PBDokumen16 halaman4866 10013 1 PBMuhammad Dylan100% (1)
- Analisa Biaya Proyek - Ir. Muji IndarwantoDokumen11 halamanAnalisa Biaya Proyek - Ir. Muji IndarwantoAbhoe StankBelum ada peringkat
- Laporan Wujud ZatDokumen7 halamanLaporan Wujud ZatDantiArdhitaBelum ada peringkat
- Laporan Drainase Inlet TlogodendoDokumen40 halamanLaporan Drainase Inlet TlogodendoidecausaprimapitoyoBelum ada peringkat
- Makalah Kromatografi GasDokumen12 halamanMakalah Kromatografi GasAri SetianiBelum ada peringkat
- Akuntansi Untuk Operasi CabangDokumen4 halamanAkuntansi Untuk Operasi CabangCici RidianingsihBelum ada peringkat
- Sap 12 Lap. Arus Kas LPDDokumen8 halamanSap 12 Lap. Arus Kas LPDCici RidianingsihBelum ada peringkat
- Audit Bab 20Dokumen19 halamanAudit Bab 20chez_jonesBelum ada peringkat
- Sap 8 - LPDDokumen12 halamanSap 8 - LPDCici RidianingsihBelum ada peringkat
- Audit Bab 20Dokumen19 halamanAudit Bab 20chez_jonesBelum ada peringkat
- Tugas Sia Kelompok 1Dokumen4 halamanTugas Sia Kelompok 1Cici RidianingsihBelum ada peringkat
- KewirausahaanDokumen8 halamanKewirausahaanCici Ridianingsih0% (1)
- Sap 11 Ak LPD - Pendapatan Dan BebanDokumen5 halamanSap 11 Ak LPD - Pendapatan Dan BebanCici RidianingsihBelum ada peringkat
- RMK Sistem Informasi AkuntansiDokumen11 halamanRMK Sistem Informasi AkuntansiCici RidianingsihBelum ada peringkat
- Dasar-Dasar Komunikasi BisnisDokumen9 halamanDasar-Dasar Komunikasi BisnisCici RidianingsihBelum ada peringkat
- Manajemen StrategikDokumen10 halamanManajemen StrategikCici RidianingsihBelum ada peringkat