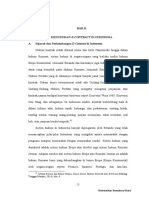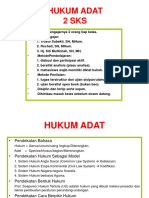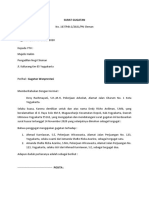7 Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan
7 Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan
Diunggah oleh
Inumaru Ryuusuke0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
606 tayangan379 halamanHak Cipta
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
606 tayangan379 halaman7 Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan
7 Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan
Diunggah oleh
Inumaru RyuusukeHak Cipta:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Format Tersedia
Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 379
iv
UCAPAN TERIMA KASIH
Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Wataala, Raja Yang
Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Mengaruniakan keamanan, Yang
Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, Yang Memiliki
Segala Keagungan. Atas perkenan serta izin Allah Subhanahu Wataala,
Disertasi yang mengusung tema Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa
Komersial Untuk Penegakan Keadilan, akhirnya selesai disusun.
Tema di atas, penulis angkat untuk diteliti dalam rangka penulisan
disertasi tatkala negeri ini dihimpit berbagai masalah yang cukup berat. Di
antaranya: tatkala penegakan hukum dirasakan orang sangat carut-marut,
ketika disiplin orang-orang hanya menjadi harapan, pada saat kejujuran sudah
dianggap aneh, tatkala kebenaran tertukar dengan merasa benar, tatkala
keadilan hanya menjadi ungkapan, tatkala kehidupan dunia dianggap lebih
baik dari kehidupan akhirat, dan tatkala bermegah-megah dengan harta dan
pengikut telah melalaikan manusia dari taat kepada Allah. Keadilan hanya
menjadi ungkapan memang bukan isapan jempol, karena pengadilan malah
dianggap paling pintar dalam memutar-balikan keadilan. Keadaan itu bahkan
telah menjadi rahasia publik di negeri ini. Betapa mahalnya harga sebuah
keadilan terlebih untuk si miskin. Betapa mengerikannya tatkala hakim harus
berlindung di balik kepala putusan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa namun tidak mampu berlaku adil.
Dalam kaitan itu pula penelitian serta kajian terhadap pilihan forum
arbitrase dalam menyelesaikan sengketa untuk penegakan keadilan
menginspirasi penulis untuk menyusun disertasi ini. Kajian ini penulis
lakukan karena ternyata forum arbitrase merupakan wahana tersembunyi
yang belum banyak dikenal orang namun telah menyediakan diri untuk
membantu menyelesaikan sengketa yang sedang dihadapi orang-orang. Di
v
sini, di forum arbitrase ini, secercah harapan untuk memperolehan keadilan
yang di sana-sini semakin susah untuk didapat masih ditunggu banyak orang.
Namun sayang, tidak setiap permasalahan orang-orang dapat dihadapkan
kepada forum arbitrase untuk meminta keadilan, karena kewenangan arbitrase
untuk itu sangat terbatas dan dibatasi.
Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan doa
restu maupun dukungan motivasi serta aliran dana selama menyusun disertasi
ini. Semoga Allah Subhanahu Wataala berkenan membalas kebajikan
berbagai pihak itu dengan balasan pahala yang berlipat ganda.
Pertama, terima kasih dan penghargaan penulis sampaikan kepada
yang amat terpelajar Prof. Dr. Satjipto Rahardjo,S.H., yang semasa beliau
menjadi Ketua Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas
Diponegoro, telah berkenan menerima penulis untuk menjadi peserta program
S3.
Kedua, kepada Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H. almarhum yang amat
terpelajar yang di sela-sela kesibukan beliau sebagai Sekretaris Program
Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro, beliau berkenan
meluangkan waktu untuk membimbing penulis. Kini tatkala disertasi ini
selesai disusun dan siap untuk diajukan ke hadapan dewan penguji, pada hari
Jumat, 26 September 2003 beliau telah dipanggil menghadap untuk selama-
lamanya ke haribaan Allah Yang Maha Kuasa. Penulis hanya mampu
memanjatkan doa ke hadirat-NYA, semoga Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.,
diterima amal-ibadah serta Iman-Islamnya, diampuni segala dosa dan
kekhilafannya, serta di alam Baqa beliau mendapat nikmat qubur. Kemudian
untuk segenap keluarga beliau, semoga Allah SWT menganugrahkan
kesabaran dan keteguhan Iman dalam menerima ujian ini.
vi
Ketiga, terima kasih ingin disampaikan kepada yang amat terpelajar
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, S.H., yang di sela-sela kesibukan beliau sebagai
Ketua Muda Mahkamah Agung RI, beliau masih berkenan membimbing dan
menerima penulis, baik di Mahkamah Agung maupun di kediaman beliau di
Jakarta untuk dapat berkonsultasi mengenai penulisan maupun materi
disertasi ini.
Keempat, terima kasih penulis sampaikan juga kepada yang amat
terpelajar Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih Pujirahayu,S.H.,M.S., yang dengan
telaten telah membimbing penulis sekaligus memahamkan penulis mengenai
seluk beluk metodologi penelitian dan penulisan serta teori-teori ilmu sosial
yang berkaitan dengan penulisan disertasi ini. Di tengah-tengah kesibukan
beliau sebagai Rektor Universitas Pekalongan, beliau juga masih berkenan
menerima penulis di Kantor beliau maupun di kediaman beliau di Pekalongan
untuk membimbing dan menerima konsultasi penulis. Demikian pula tatkala
beliau memberikan kuliah pada Program Pascasarjana Universitas Islam
Bandung, penulis selalu diberi kesempatan untuk dapat berkonsultasi dengan
beliau. Banyak hal yang penulis peroleh dari beliau, baik berupa nasihat-
nasihat keilmuan serta moral akademik, nasihat tentang ke-Islaman, juga
sejumlah literatur yang diperlukan penulis dalam menunjang penulisan
disertasi ini.
Kelima, terima kasih juga ingin penulis sampaikan kepada yang amat
terpelajar Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA yang telah dengan tulus
memberikan dasar-dasar teoretis mengenai metodologi penelitian hukum,
sehingga memberikan pencerahan kepada penulis dalam membekali penulis
untuk melakukan penelitian dalam rangka menulis disertasi ini.
Keenam, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada seluruh
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, baik yang
langsung mengampu mata kuliah yang penulis ikuti selama menjadi peserta
vii
program studi ilmu hukum, maupun yang memberikan masukan untuk
penyempurnaan naskah sejak Ujian Kualifikasi, kemudian ketika Seminar
Proposal Penelitian, dan tatkala Seminar Hasil Penelitian Disertasi. Segala
bentuk masukan, nasihat, dan kritik beliau telah sangat bermanfaat dalam
rangka penyusunan disertasi ini. Oleh karena itu, kepada yang amat terpelajar
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, S.H., Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H.,
Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., saya sangat mengucapkan terima
kasih. Kepada para Guru Besar yang amat terpelajar yang telah melakukan
penelaahan Disertasi penulis pada Ujian Kelayakan Disertasi penulis, yaitu:
Yang amat terpelajar Prof. Ronny Hanitijo Soemitro,S.H., Prof. IGN
Sugangga,S.H., dan Prof. Dr. Moempeoeni Moelatingsih Martojo, S.H,
disampaikan terima kasih atas segala nasihat serta segala impresinya ketika
memeriksa Disertasi penulis pada Ujian Kelayakan. Kepada Prof. Dr. Nindyo
Pramono,S.H.,M.S. dari Universitas Gadjah Mada sebagai penguji eksternal,
penulis menghaturkan terima kasih.
Ketujuh, terima kasih hendak penulis sampaikan pula kepada yang
amat terpelajar Prof. Ir. H. Eko Budiardjo, M.Sc., Rektor Universitas
Diponegoro Semarang beserta seluruh staf dan jajarannya, atas berbagai
fasilitas kemudahan yang memungkinkan penulis mengikuti program ini
dengan baik dan lancar. Rektor Undip ini sangat piawai berpuisi dengan
sambutannya yang kas penuh canda ria namun bermakna amat dalam karena
sarat dengan nasihat. Dalam kaitan itu pula penulis mengucapkan terima
kasih yang amat dalam kepada beliau atas nasihat yang demikian menyentuh
pada sambutan penutupan Ujian Promosi penulis.
Kedelapan, ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada yang
amat terpelajar Prof. Dr. Soeharjo Hadisaputro, dr., Sp.PD-KT, Direktur
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. Demikian pula
viii
kepada seluruh staf beliau yang telah memberikan pelayanan, kemudahan,
dan fasilitas, sehingga memperlancar penulis dalam menyelesaikan studi.
Kesembilan, kepada Prof. Dr. Muladi, S.H., yang tatkala penulis
memasuki tahap Ujian Pra Promosi, beliau telah dikukuhkan sebagai Ketua
Program Doktor Ilmu Hukum, dan ketika penulis mengikuti kuliah beliau
mengampu mata kuliah Transformasi Global, penulis ucapkan terima kasih.
Juga kepada seluruh jajaran staf Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana
Universitas Diponegoro, sejak kepemimpinan yang amat terpelajar Prof. Dr.
Satjipto Rahardjo,S.H., kemudian dilanjutkan oleh Prof. Dr. I.S. Susanto,
S.H. (alm) yang sejak tahun 1999 memfasilitasi penulis dalam menempuh
program studi ini. Kepada yang amat terpelajar Prof. Dr. Moempoeni
Moelatingsih Martojo,S.H., sebagai Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro, juga seluruh staf Program Doktor Ilmu Hukum,
mbak Supadmi, mbak Alvi Rachmawati, mbak Diah Susanto, mas Mintarno,
mas Jumadi, dan mas Juli, yang telah dengan cara dan bidangnya masing-
masing memberikan layanan administratif dengan ramah, gesit, dan penuh
rasa kekeluargaan sehingga penulis dan juga peserta lainnya sangat merasa
puas. Boleh jadi selama saya menjadi mahasiswa (S1, S2, dan S3) serta
menjadi guru di berbagai perguruan tinggi, baru saya jumpai di Program
Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang para staf
administratif-nya mampu memperlakukan para mahasiswa sebagai raja
yang mesti dilayani keperluannya. Sungguh saya sangat terkesan.
Kesepuluh, terima kasih juga disampaikan kepada seluruh Staf
Program Pascasarjana, Mas Aji, mbak Heni, Ibu Uun dan seluruh staf yang
telah membantu kelancaran proses studi penulis pada program Doktor Ilmu
Hukum Undip ini. Terutama pada segala bentuk upaya dan perhatian yang
sangat intensif tatkala penulis menghadapi Ujian Pra Promosi. Oleh karena
itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis mengucapkan terima kasih
ix
yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu
kelancaran urusan penulis.
Kesebelas, ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kang Uus,
staf pada Direktorat Jenderal Pendirikan Tinggi Departemen Pendidikan
Nasional dan juga Drs. Encep Sudirjo, S.Pd., M.Pd., Dosen Universitas
Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, sahabat sekaligus teman diskusi
penulis untuk metodologi penelitian. Kepada mereka berdua penulis sangat
berterima kasih atas segala bantuan yang telah diberikan pada awal-awal
penulis memasuki program S3 di Universitas Diponegoro. Semoga Allah
Yang Maha Pemurah membalas segala kebaikan mereka.
Keduabelas, terima kasih secara khusus juga ingin penulis
sampaikan kepada Prof. H. Abdullah Himendra Wargahadibrata, dr., Sp An-
KIC, Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, atas izin dari beliau penulis
dapat melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas
Diponegoro ini. Juga kepada Prof. Dr. Tanwir J. Mukawi, dr, SpPA, ketika
saya megajukan permohonan izin untuk melanjutkan studi ini beliau sedang
memangku jabatan Pembantu Rektor I Universitas Padjadjaran. Ucapan
terima kasih juga disampaikan kepada Prof. Dr. H. Man S. Sastrawidjaja,
S.H.,S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Atas izin dari
beliau saya dapat menempuh studi pada Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang.
Last but not least, penghargaan dan rasa hormat tentu saja saya harus
sampaikan kepada ayahanda penulis, Almarhum Sueb Nana Suryana, yang
telah mengasuh, membimbing, serta mendidik penulis dengan disiplin kuat
untuk terus belajar dan atas restu dari beliaulah penulis menerima tawaran
Ny. Retnowulan Sutantio,S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa
Barat di Bandung untuk menjadi asisten beliau di Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 1982 yang lalu. Sejak saat itu
x
sampai sekarang penulis tetap istiqamah mengabdi sebagai seorang guru pada
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Penghargaan dan rasa
hormat, penulis sampaikan juga kepada ibunda penulis Ny. Djasiti, yang di
hari tua beliau sebagai seorang pensiunan guru tetap menasihati dan
mendoakan penulis untuk tetap menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam
menjalani hidup dan kehidupan ini. Tanpa kasih sayang dan didikan ibunda
tentu saja saya tidak akan menjadi orang seperti sekarang ini. Untuk jasa
beliau saya berdoa ke hadirat Allah Subhanahu Wataala, semoga beliau
senantiasa dianugerahi rasa syukur untuk tetap mampu beribadah dalam
keadaan sehat jasmani dan ruhani seraya menapaki hari-hari di usia tuanya
sambil mengasuh dan membimbing cucu-cucu dan cicit beliau.
Kepada family saya di Negeri Belanda, Keluarga Jose Soehaja di
Delft, kemudian Keluarga Tommy S. Patty di Den Haag. Sejak penulis
melakukan studi dan Sandwich Programme di Leiden tahun 1990 dan 1997,
perhatian dan kasih sayang mereka telah sangat penulis rasakan dan terima.
Bahkan atas segala bantuan materiil maupun dorongan moril yang diberikan
menjelang penulis menyelesaikan studi Doktor pada PDIH Undip ini. Atas
semuanya itu penulis sangat berhutang budi dan mengucapkan terima kasih.
Penulis sangat gembira karena keluarga Jose Soehaja dari Delft dapat
menghadiri pada waktu Ujian Terbuka Promosi Doktor penulis.
Kepada teman-teman Angkatan V Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro Semarang diucapkan terima kasih yang setulus-
tulusnya atas kehangatan serta persahabatan dalam kebersamaannya,
menjalani suka dan duka selama satu tahun di kelas, termasuk ketika tour ke
Bali yang sangat mengesankan itu. Ucapan terima kasih secara khusus
disampaikan juga kepada sahabat karib penulis, Aang Batara Winarnu
Panornari Pardede, S.H. beserta keluarganya, penulis sangat berterima kasih
xi
yang tak terhingga serta penulis selalu mendoakan semoga mereka tetap sehat
dan dikaruniai kebahagiaan selalu oleh Allah Subahanau Wataala.
Paling akhir, dengan penuh rasa rasa syukur, ucapan terima kasih
serta penghargaan yang tulus ini pun ingin disampaikan kepada isteri penulis
tercinta, Dra. Ella Dewi Laraswati, yang dengan segala doa serta daya
upayanya tak henti-henti memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan
sekolahnya. Terima kasih juga disampaikan kepada kedua anakku tercinta
Risa Dewi Angganiawati dan Anggiani Dewi Rahmawati yang dengan
penuh pengertian dan caranya masing-masing membantu serta memberi
inspirasi kepada ayahnya untuk segera menyelesaikan disertasinya. Oleh
karena selama bertahun-tahun mereka terpaksa harus merelakan tersita
haknya untuk memperoleh perhatian yang semestinya. Selayaknya ucapan
terima kasih dan penghargaan yang tulus ini disampaikan pula kepada
ayahanda mertua penulis, Bapak R. Suyud dan ibunda mertua Ny. O.
Rochaeni atas doa restu yang selalu menyertai penulis dalam menapaki
perjalanan hidup ini.
Kepada seluruh karib kerabat, handai taulan, serta relasi yang tidak
mungkin saya sebutkan satu persatu, penulis juga mengucapkan terima kasih
atas segala doa restu serta dukungannya. Penulis menyadari disertasi ini
masih sangat tidak sempurna. Ibarat kata pepatah: tak ada gading yang tak
retak; Kalau tak retak maka bukan gading namanya. Oleh sebab itu, saran
dan kritik dari berbagai pihak untuk memperbaiki kekurangan disertasi ini,
penulis terima dengan senang hati.
Bandung, 30 Januari 2004
Penulis,
Lman Suparman
PILIHAN FORUM ARBITRASE
DALAM SENGKETA KOMERSIAL
UNTUK PENEGAKAN KEADILAN
Dr. EMAN SUPARMAN, S.H.,M.H.
xix
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................... iv
Abstrak .............................................................................................................. xi
Abstract.. ........................................................................................................... xii
Ringkasan ......................................................................................................... xiii
Daftar Isi .......................................................................................................... xix
Daftar Ragaan ................................................................................................. xxi
Daftar Singkatan .............................................................................................. xxii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan ....................................................... 1
B. Perumusan Masalah ...................................................................... 21
C. Kerangka Pemikiran ...................................................................... 23
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ................................................... 62
E. Pendekatan Studi ........................................................................... 66
F. Metode Penelitian ......................................................................... 73
G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan ........................ 89
BAB II PILIHAN FORUM ARBITRASE SEBAGAI TEMPAT
PENYELESAIAN SENGKETA BERKEADILAN ............. 105
A. Tujuan Pilihan Forum Arbitrase dan Keadilan .................... 109
B. Konsekuensi Pilihan Forum Arbitrase terhadap
Kompetensi Hakim Pengadilan Negeri .............................. 123
C. Pilihan Forum Arbitrase Sebagai Fenomena
Penyelesaian sengketa ......................................................... 139
BAB III SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA KOMERSIAL
DI DALAM FORUM ARBITRASE ................................... 148
A. Pihak-Pihak Berperkara dalam Forum Arbitrase ................... 148
B. Sengketa yang dapat Diklaim Melalui Forum Arbitrase ......... 159
C. Struktur dan Proses Penyelesaian Sengketa lewat Arbitrase .. 164
1. Arbitrase Institusional ....................................................... 173
2. Arbitrase Ad hoc ............................................................... 178
D. Keadilan Menurut Pihak-pihak Bersengketa .......................... 182
xx
BAB IV PILIHAN FORUM ARBITRASE, BUDAYA HUKUM,
DAN KEADILAN ................................................................. 195
A. Pilihan Forum Arbitrase dan Budaya Hukum di Indonesia .... 194
B. Faktor Internal Pengadilan Negeri dan Pilihan Forum
Arbitrase ................................................................................. 212
C. Kewenangan Eksekutorial Forum Arbitrase untuk Putusan
Final dan Mengikat serta Dilema Perolehan Keadilan ........... 228
D. Perspektif Historis dan Futuristik Arbitrase sebagai Model
Penyelesaian Sengketa Berkeadilan ....................... 239
BAB V EKSEKUSI PUTUSAN FORUM ARBITRASE GAMBARAN
DILEMA PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA ......... 268
A. Makna dan Kekuatan Putusan Menurut Pengadilan Negeri
Serta Para Pihak Bersengketa .................................................... 267
1. Kekuatan Mengikat ............................................................... 276
2. Kekuatan Pembuktian ........................................................... 278
3. Kekuatan Eksekutorial ......................................................... 280
B. Interpretasi, Koreksi, dan Pergeseran Makna Putusan
Arbitrase ................................................................................... 283
C. Diskresi Hakim dalam Masalah Eksekuatur Putusan
Arbitrase .................................................................................... 291
D. Eksekusi Putusan Arbitrase dalam Penegakan Keadilan .......... 303
BAB VI P E N U T U P ........................................................................... 333
A. Simpulan ................................................................................. 333
B. Rekomendasi ........................................................................... 340
DAFTAR PUSTAKA .................................................................. 344
xxiii
DAFTAR RAGAAN
1. Three types of law menurut Philippe Nonet & Philip Selznick; 41.
2. Hierarchy of Types of Dispute Resolution menurut Gerald Turkel; 60.
3. Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif ; 81
4. Prinsip-prinsip dalam Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase; 169.
5. Pemohon tidak hadir dan Upaya perdamaian; 170.
6. Perubahan dan Penambahan Tuntutan & Jangka Waktu
Penyelesaian; 171.
7. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli; 172.
xxiv
DAFTAR SINGKATAN
AAA American Arbitration Association
ADR Alternative Dispute Resolution
AFTA ASEAN Free Trade Area
AJM Access to Justice Movement
APS Alternatif Penyelesaian Sengketa
BANI Badan Arbitrase Nasional Indonesia
BKPM Badan Koordinasi Penanaman Modal
B.W. Burgerlijk Wetboek
CLS Critical Legal Studies
HAG Hukum Antar Golongan
HIR het Herziene Indonesisch Reglement
HPI Hukum Perdata Internasional
ICC International Chamber of Commerce
ICSID International Centre for Settelement of Investment Disputes
I.S. Indische Staatsregeling
KADIN Kamar Dagang dan Industri
KNY Konvensi New York
KPN Ketua Pengadilan Negeri
KUHP Kitab Undang-undang Hukum Perdata
LCIA London Court of International Arbitration
MA-RI Mahkamah Agung Republik Indonesia
NAFTA North American Free Trade Agreement
PERMA PeraturanMahkamah Agung
PPA Peraturan Prosedur Arbitrase
PPAT Pejabat Pembuat Akte Tanah
R.O. Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid Der
Justitie in Indonesie
RvJ Raad van Justitie
S.A. Saksi Ahli
SAW Sholallohu Alaihi Wassalam
SEC Single European Community
SWT Subhanahu Wataala
UAR UNCITRAL Arbitration Rules
UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law
WvK Wetboek van Koophandel
IHWAL PENULIS
Eman Suparman, lahir dan dibesarkan di Kuningan, 23 April 1959. Usai
menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (1970), Sekolah Menengah Pertama
Negeri (1973), dan Sekolah Menengah Atas Negeri (1976) kesemuanya di Kuningan Jawa
Barat, kemudian melanjutkan studi di Universitas Padjadjaran Bandung.
Pendidikan universiternya diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, jurusan
Hukum Perdata, lulus tahun 1982.
Pada tahun 1985 melanjutkan pendidikan S2 pada Fakultas Pascasarjana Universitas Gadjah
Mada Yogyakarta, dengan bidang kajian Hukum Acara Perdata, dan lulus sebagai Magister
Hukum pada tahun 1988 dengan Tesis Keharusan Mewakilkan Dalam Menunjang Proses
Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.
Pada tahun 1990/1991 dalam rangka Sandwich Programme memperoleh kesempatan
studi lanjutan, penelitian, dan studi perbandingan untuk bidang kajian Hukum Perdata
Internasional dan Hukum Arbitrase di Rijksuniversiteit Leiden, The Netherlands.
Dilanjutkan sebagai Visiting Scholar for the European Council Session at
Strasborough, France (1991).
Awal 1997 atas stipend ABWPP & Associates kembali menjadi Visiting Scholar at de
Hoge Raad der Nederlanden; The Hague, The Netherlands (March 1997); Visiting
Academic and Research Programme, organised by The Departement of Law The
University of Nottingham, UK. (April 1997); Visiting at The 7th Annual Writers
Festival Prague 97 at Franz Kafka Centre on Pragues Old Town Square, Prague,
Czech Republic (April 1997). Tahun 1999, mengikuti S3 pada Program Doktor Ilmu
Hukum (PDIH) Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang dan lulus sebagai Doktor
Ilmu Hukum pada bulan Februari 2004 dengan Disertasi bertajuk Pilihan Forum
Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan.
Pengabdiannya sebagai pendidik pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung
diawali sejak tahun 1983 dan mengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, Hukum
Perselisihan, dan Praktik Penanganan Perkara Perdata. Di samping melakukan berbagai
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, juga menulis Buku, di antaranya: (1)
INTISARI HUKUM WARIS INDONESIA, diterbitkan CV Mandar Maju, Bandung, 1995.
(2) HUKUM DAN BIROKRASI (sebagai salah satu penulis), diterbitkan Walisongo
Reseach Institute, Semarang, April 2001. Sejak masih mahasiswa kegiatan ilmiah berupa
menulis artikel hukum dalam media cetak telah banyak dilakukan. Oleh karena itu, kini
sejumlah artikel ilmiah juga telah ditulis dalam Jurnal Terakreditasi Nasional.
Dari pernikahannya dengan Dra. Ella Dewi Laraswati dikaruniai 2 (dua) orang putri.
(1) Risa Dewi Angganiawati (Sarjana Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung) dan
(2) Anggiani Dewi Rahmawati (Mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas
Padjadjaran Bandung).
iii
KATA PENGANTAR
Buku yang sedang Anda baca ini pada mulanya adalah sebuah disertasi
penulis yang telah berhasil dipertahankan di hadapan Sidang Terbuka Senat Guru
Besar Universitas Diponegoro, pada tanggal 16 Februari 2004 dengan wibawa
Rektor Universitas Diponegoro Prof. Ir. Eko Budihardjo, M.Sc.
Dorongan dari berbagai pihak agar disertasi tersebut dapat dibaca khalayak
yang lebih luas, memotivasi penulis untuk mencari serta menghubungi penerbit yang
diharapkan berkenan menerima naskah disertasi tersebut untuk diterbitkan. Pilihan
jatuh kepada PT. Tatanusa yang penulis kenal. Oleh karena itu, ucapan terima kasih
disampaikan kepada PT. Tatanusa yang memberikan sambutan positip dan telah
bersedia untuk menerbitkan naskah disertasi tersebut.
Bagi para Mahasiswa S1 dan S2 Ilmu Hukum yang sedang mengikuti
perkuliahan Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional (HKI 615), Hukum
Alternatif Penyelesaian Perselisihan (ADR) [HKB 674], dan mata kuliah
Arbitrase & Penyelesaian Sengketa Alternatif (S1), disarankan memiliki jurnal
yang secara periodik menyajikan mengenai topik tersebut sebagai pendamping buku
ini. Demikian pula kepada para Mahasiswa S3 Ilmu Hukum yang sedang mengikuti
perkuliahan Hukum Penyelesaian Sengketa Perniagaan (HKD 813) buku ini
semoga dapat membantu anda dalam menemukan masalah yang sedang ditelusuri.
Kiranya buku ini dapat menjadi salah satu sumbangsih penulis kepada
khazanah hukum Indonesia, khususnya bagi perkembangan hukum arbitrase sebagai
salah satu forum tempat penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan serta
bermartabat. Menyadari sepenuh hati akan segala kekurangan buku ini, untuk itu
segala kritik dan saran dari pembaca, insya Allah akan sangat dihargai.
Last but not least, kepada semua pihak yang telah memungkinkan
diterbitkannya buku ini, penulis mengucapkan terima kasih.
Taruna Parahiangan, Bandung, 13 April 2004
Lman Suparman
Ya Allah,
tambahkanlah kepadaku
Ilmu Pengetahuan
(Q.S. 20:JJ4)
Allah akan meninggikan
orang-orang yang beriman di antaramu
dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat
(Q.S. 58: JJ)
Kepada:
Isteri dan anak-anakku tercinta,
Llla Dewi Laraswati
Risa Dewi Angganiawati
Anggiani Dewi Rahmawati
2
Kata-kata Bestari:
Orang yang berbudi pekerti tinggi akan malu untuk menyatakan
ketinggian ilmunya, karena ilmu itu sesungguhnya pemberian Allah
Subhanahu Wata'ala
Kejujuran membawa Keberkahan
Keberkahan membawa Ketenangan
Artinya: Kejujuran membawa Ketenangan
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan
Perkembangan masyarakat serta laju dinamis dunia bisnis saat ini
berlangsung demikian pesat. Dinamika dan kepesatan yang terjadi di dalam
kegiatan ekonomi dan bisnis itu ternyata telah membawa implikasi yang
cukup mendasar terhadap pranata
1
maupun lembaga
2
hukum. Implikasi
terhadap pranata hukum disebabkan sangat tidak memadainya perangkat
norma untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis yang sedemikian
pesat. Kondisi tersebut kemudian diupayakan untuk diatasi dengan
melakukan reformasi hukum di bidang kegiatan ekonomi. Berbagai upaya
1
Kendati pada dataran perundang-undangan primer kita tidak dapat melihat terjadinya
perubahan besar, tetapi pada dataran yang lebih rendah perubahan tersebut
berlangsung dengan intensif. Paket-paket deregulasi tidak terjadi melalui undang-
undang, melainkan lewat keputusan-keputusan pemerintah. Keadaan tersebut menarik
untuk diikuti oleh karena kita tidak tahu sudah sampai seberapa jauh sebenarnya efek
dari perkembangan di tingkat bawah itu mempengaruhi penataan hukum nasional.
Lihat Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi
Global; dalam Problema Globalisasi Perspektif Sosiologi Hukum, Ekonomi, &
Agama. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000, h. [3-19] 13.
2
Sementara itu implikasi terhadap lembaga hukum tampak antara lain dari persepsi
pihak-pihak pelaku bisnis terhadap lembaga pengadilan yang dianggap kurang mampu
memenuhi harapan mereka. Fakta tersebut dapat disimak dari pernyataan berikut ini:
Ternyata dalam perkembangnnya, penyelesaian sengketa menggunakan Pengadilan
dihinggapi formalitas yang berlebihan, tidak efisien dan efektif, mahal, perilaku hakim
yang memihak, dan hasil putusan hakim yang seringkali mengecewakan pencari
keadilan. Puncak dari kekecewaan tersebut telah menyebabkan masyarakat tidak
menaruh hormat, yang kemudian menimbulkan krisis kewibawaan dan kepercayaan
pada pengadilan. Lihat Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma Penyelesaian
Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif Penyelesaian
Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual; Disertasi, Semarang: PDIH, 2002, h. 4.
2
dilakukan melalui pembaharuan atas substansi produk-produk hukum yang
sudah tertinggal maupun dengan membuat peraturan perundang-undangan
baru mengenai bidang-bidang yang menunjang kegiatan ekonomi dan bisnis.
3
Sementara itu, implikasi dari kegiatan bisnis yang pesat terhadap
lembaga hukum berakibat juga terhadap pengadilan
4
yang dianggap tidak
profesional untuk menangani sengketa-sengketa bisnis, tidak independen,
bahkan para hakimnya telah kehilangan integritas moral
5
dalam menjalankan
profesinya. Akibatnya, lembaga pengadilan yang secara konkret mengemban
3
Lihat Normin S. Pakpahan, Pembaharuan Hukum di Bidang Kegiatan Ekonomi.
Makalah pada Temu Karya Hukum Perseroan dan Arbitrase; Jakarta, 22-23
Januari 1991, h. [29-37] 31. ...Yang disebut hukum nasional dalam era globalisasi di
samping mengandung local characteristics seperti Ideologi bangsa, kondisi-kondisi
manusia, alam dan tradisi bangsa, juga harus mengandung kecenderungan-
kecenderungan internasional (international trends) yang diakui oleh masyarakat dunia
yang beradab. Yang menjadi masalah adalah sampai berapa jauh kecenderungan-
kecenderungan internasional ini memberikan warna di dalam kehidupan hukum
nasional, baik dalam pembentukan hukum, penegakan hukum, maupun kesadaran
hukum. Lihat, Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997, h. 63.
4
Pengadilan yang kadang-kadang juga disebut Badan Peradilan memiliki makna
ganda. Pertama, berarti organisasi (lembaga) pengadilan; Kedua, berarti suatu
proses kerja dari unsur-unsur yang ada di dalam organisasi pengadilan itu dalam rangka
memeriksa dan menjatuhkan putusan hukum. Sedangkan kata Pengadilan (dalam
arti: lembaga) juga berarti badan yang oleh penguasa dengan tegas diberi tugas untuk
memeriksa pengaduan tentang gangguan hak (hukum) atau memeriksa gugatan dan
badan itu memberi putusan hukum. Jadi Pengadilan atau Badan Peradilan adalah
badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau
siapa pun untuk pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak dengan cara
memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah eigenrichting.
Lihat Sudikno Mertokusumo, Sistem Peradilan di Indonesia; JURNAL HUKUM,
No. 9, Vo. 4, 1997, h. [1-8], 2.
5
Secara jujur harus diakui, impresi ihwal buruknya kondisi peradilan di Indonesia
sebagian besar disebabkan pengadilan Indonesia yang tidak memiliki independensi,
sehingga mengancam integritasnya sebagai penjaga tegaknya rule of law. Jika dipilah-
pilah, persoalan tentang independensi peradilan yang dihadapi saat ini, terdiri atas
masalah: kemadirian hakim (bebas dari campur tangan eksekutif), integritas (moral
3
tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan ketika menerima, memeriksa,
mengadili, serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan, dianggap
sebagai tempat menyelesaikan sengketa yang tidak efektif dan efisien.
6
Gambaran tentang kondisi pengadilan semacam itulah yang selama ini
dipahami oleh kalangan pengusaha, terutama pengusaha asing yang berbisnis
di Indonesia. Di samping itu masih ditambah pula dengan kondisi objektif
lainnya dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan, yaitu bahwa
menyelesaikan sengketa melalui pengadilan di Indonesia sesungguhnya
merupakan rangkaian yang sangat panjang
7
dari sebuah proses upaya
pencarian keadilan. Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kalangan dunia
usaha, terutama pengusaha asing, yang senantiasa mengupayakan segala
urusan dengan serba cepat,
8
ketika menghadapi sengketa akan berusaha
para hakim), dan profesionalisme. Lihat Mas Achmad Santosa, Independensi
Peradilan dan TAP MPR RI No. X/MPR/1998; Kompas, 11 Januari 1999.
6
Adi Sulistiyono, Mengembangkan Op. Cit., h. 4 - dst.
7
Sebagai akibatnya maka proses persidangan dari sebuah perkara hingga terbitnya
putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap dapat berlangsung hingga enam
tahun. Selain lambat, putusan hakim juga sering dinilai kontradiktif dan tidak jarang
putusan hakim itu tidak dapat dieksekusi. Lihat HP Panggabean, Kelambanan Proses
Peradilan Dikeluhkan; Kompas, 23 April 1999.
8
Pengadilan terdiri atas berbagai instansi atau tingkatan. Diperolehnya putusan pada
tingkat pertama, belum berarti sengketa tersebut selesai, karena pihak yang merasa tidak
puas dengan putusan tersebut masih dapat melakukan upaya hukum banding ke
pengadilan tinggi. Bahkan bila masih belum merasa puas juga dengan putusan banding,
yang bersangkutan masih dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Tak ada jaminan dari pihak mana pun bahwa penyelesaian sengketa pada setiap
tingkatan pengadilan itu akan berlangsung dengan cepat. Apabila semua tingkatan
peradilan itu dapat selesai ditempuh dalam jangka waktu satu tahun enam bulan (yang
berarti: satu instansi enam bulan), maka itu sudah dapat dikatakan sangat cepat.
Ditambah lagi dengan sejumlah tunggakan (kongesti) perkara-perkara yang
menyebabkan penyelesaian perkara di pengadilan semakin lamban. Lihat R. Subekti,
Arbitrase Perdagangan. Bandung: Binacipta, 1981, h. 4.
4
memilih forum penyelesaian sengketa yang menurut kriteria mereka lebih
dapat dipercaya dan sesuai dengan budaya bisnis.
9
Forum penyelesaian
sengketa dimaksud biasanya memiliki karakteristik: (i) menjamin kerahasiaan
materi sengketa; (ii) para pihak yang bersengketa mempunyai kedaulatan
untuk menetapkan arbiter, tempat prosedur beracara, dan materi hukum; (iii)
melibatkan pakar-pakar (arbiter) yang ahli dalam bidangnya; (iv) prosedurnya
sederhana dan cepat; dan (v) putusan forum tersebut merupakan putusan yang
terakhir serta mengikat (final and binding). Di samping itu, faktor yang
tidak kalah penting adalah putusan dari forum tersebut, baik sengaja
maupun tidak sengaja, sama sekali tidak terpublikasikan
10
kepada khalayak
secara luas tanpa ijin para pihak yang bersengketa. Adapun forum
penyelesaian sengketa yang karakteristiknya semacam itu tidak lain adalah
forum arbitrase (arbitration).
11
9
Lihat Adi Sulistiyono, MengembangkanOp. Cit., h. 88.
10
Berbeda dengan asas yang dianut oleh pengadilan dalam memutus sengketa, yakni
pemeriksaan perkara dan pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang terbuka
untuk umum, sedangkan pemeriksaan yang dianut oleh forum arbitrase (arbitration
institution) menganut asas pintu tertutup, sehingga ICSID (International Centre for
Settlement of Investment Disputes) sebagai Badan Arbitrase Bank Dunia di dalam
Rules of Procedure for Arbitration Proceedings (Arbitration Rules) pasal 48 ayat (4)
menentukan: The Centre shall not publish the award without the consent of the
parties. The Centre may, however, include in its publication excerpts of the legal rules
applied by the Tribunal. Baca ICSID Basic Documents, Washington DC, 1985, h. 83.
11
Arbitration, is a method for settling controversies or disputes whereby an unofficial
third party hears and considers arguments and determines an equitable settlement.;
Lihat Peter J. Dorman (eds), Running Press Dictionary of Law. Philadelphia: Running
Press, 1976, h. 19. Arbitrase yang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 30
Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan cara
penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian
tertulis dari pihak yang bersengketa. Berdasarkan Penjelasan Umum UU Nomor 30
5
Sebagai salah satu cara menyelesaikan sengketa hukum di luar
pengadilan, forum arbitrase bukan sesuatu yang baru dalam sistem
penyelesaian sengketa hukum di Indonesia. Di masa lalu, arbitrase kurang
menarik perhatian dan kurang populer walaupun sesungguhnya sudah lama
diatur dalam sistem hukum di Indonesia.
12
Bahkan pada kurun awal
kemerdekaan Indonesia, arbitrase pun telah lazim dipraktikan di kalangan
para usahawan.
13
Dewasa ini, arbitrase dipandang sebagai pranata hukum yang penting
sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa bisnis di luar pengadilan.
Bahkan meningkatnya peranan arbitrase pun bersamaan dengan
Tahun 1999, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau
ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Oleh karena itu, arbitrase
menurut UU tersebut bukan merupakan salah satu dari ADR, melainkan sebuah metode
penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga di luar pengadilan umum.
12
Meski tidak dijumpai kasus sengketa yang pernah diputus oleh forum arbitrase sebelum
Indonesia merdeka, namun kaidah umum tentang arbitrase ketika itu telah merupakan
bagian dari Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Raad van Justitie (RvJ) di masa
kolonial Belanda, yakni dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) S.
1847 No. 52 jo S. 1849 No. 63. Kaidah tersebut terdapat dalam pasal-pasal 615-651 Rv.
Pasal 615 ayat (1) Rv antara lain menentukan: Ieder kan de geschillen omtrent de
regter waarover hij de vrije beschikking heeft, aan de uitspraak van scheidsmannen
onderwerpen. (Adalah diperkenankan kepada siapa saja, yang terlibat dalam suatu
sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk
melepaskannya, untuk menyerahkan pemutusan sengketa tersebut kepada seorang atau
beberapa orang wasit). R. Subekti, Loc. Cit., h. 39.
13
Salah satu buktinya adalah ketika itu ada diantara perkumpulan para pedagang yang
memiliki panitia arbitrase sendiri. Dapat dikemukakan di sini, misalnya: Panitia
Arbitrase dari Organisasi Exporteur Hasil Bumi Indonesia, disingkat O.E.H.I. Nama
ini diketahui dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1/1959 Pem. Put. Wst. tanggal
5 September 1959, Putusan Wasit dalam perkara antara Indonesia Cotton Trading Co.
Ltd. lawan Firma Rayun; dalam Majalah Hukum dan Masyarakat No. 1-2-3 Tahun
1962, hlm. 164. Periksa, Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara
Perdata. Bandung: Alumni, 1992, h. 71.
6
meningkatnya transaksi niaga, baik nasional maupun internasional.
Kompleksitas dan tingginya persaingan di dalam transaksi niaga, baik
nasional maupun internasional tersebut sangat berpotensi menimbulkan
sengketa. Beragam sengketa yang timbul dari kegiatan bisnis atau aktivitas
komersial itu secara umum dapat disebut sebagai sengketa bisnis atau
sengketa komersial
14
(selanjutnya disebut dengan sengketa komersial).
Demikian luasnya pengertian komersial sehingga meliputi seluruh aspek
kegiatan bisnis. Oleh sebab itu, dalam rangka penulisan disertasi ini, sengketa
komersial tidak ditetapkan secara spesifik. Sengketa komersial dimaksud
diambil secara random (acak) dari kasus yang ada berdasarkan kebututuhan
kajian ini. Bahkan sengketa komersial dimaksud tidak ditentukan berdasarkan
jenis objek sengketanya maupun ragam kontrak bisnisnya.
Sengketa komersial di dalam penulisan disertasi ini semata-mata
dikaji berdasarkan perbedaan subjek-subjek sengketanya, sehingga hanya
dibedakan atas dua prototipe sengketa komersial. Pertama, sengketa
14
Seperti dapat disimak dari The United Nations Commission on International Trade
Law (UNCITRAL Arbitration Rules atau disingkat UAR Model Law on International
Commercial Arbitration, June 21, 1985) istilah komersial dapat dibaca sebagai
berikut: The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover
matters arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or
not. Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following
transactions; any trade transactions for the supply or exchange of goods or services;
distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing;
construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing;
banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other
forms of industrial or business co-operation; carriage of goods or passanger by
air,sea, rail or road. Periksa, Alan Redfern & Martin Hunter, Law and Practice of
International Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 1991, h. 21.
7
komersial domestik, yaitu sengketa yang terjadi antara subjek-subjek atau
para pihak orang Indonesia yang melakukan kontrak bisnis satu sama lain,
dan objek sengketanya terletak di dalam negeri. Kedua, sengketa komersial
internasional (international commercial disputes),
15
yaitu sengketa yang
melibatkan pihak-pihak atau subjek-subjek asing, baik individu maupun
lembaga swasta yang berlainan kewarganegaraan, sengketa tersebut terjadi
dari kontrak
16
bisnis internasional.
Berdasarkan perspektif cara yang dipilih untuk menyelesaikan kedua
prototipe sengketa tersebut di muka adakalanya juga memiliki perbedaan.
Sengketa komersial domestik pada umumnya, bahkan hampir dapat
dipastikan subjek-subjek sengketanya cenderung membawa sengketa mereka
untuk diselesaikan di pengadilan negeri. Memilih forum arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa komersial tipe yang pertama belum menjadi bagian
15
International disputes covers not only disputes between states as such, but also other
cases that have come within the ambit of international regulation, being certain
categories of disputes between states on the one hand, and individuals, bodies
corporate, and non-state entities on the other". Jadi suatu sengketa tergolong
internasional bilamana menyangkut: (i) negara dengan negara; (ii) negara di satu
pihak dengan individu di lain pihak; (iii) negara dengan organisasi atau badan hukum
(bodies corporate); dan (iv) antara lembaga swasta atau individu satu sama lain.
Semuanya itu sepanjang berada dalam lingkup pengaturan internasional. Atau
sepanjang menyangkut pihak-pihak yang berlainan kebangsaannya. Lihat J.G. Starke,
Introduction to International Law. Ninth Edition, 1984, h. 463.
16
Kontrak internasional dalam pengertian ini, adalah "... contracts with elements in two
or more nation-states. Such contracts may be between states, between a state and a
private party, or exclusively between private parties..." Lihat Hans Smit et al.,
International Contracts. Parker School of Foreign and Comparative Law,
Columbia University, Matthew Bender, 1981, h. 4.
8
dari perilaku para pihak domestik.
17
Sementara itu memilih forum arbitrase
umumnya dilakukan oleh pihak asing dalam rangka menyelesaikan sengketa
komersial internasional. Dari pembacaan beberapa literatur diketahui bahwa
praktik pada beberapa negara maju menunjukkan bahwa untuk
mempersiapkan penyelesaian sengketa tipe kedua itu hampir setiap kontrak
bisnis internasional mencantumkan klausula
18
pemilihan forum arbitrase.
Bahkan dalam kaitannya dengan pilihan forum arbitrase ini, A.J. van den
Berg secara ekstrim menyebutkan bahwa "...bevat ongeveer 90 % van de
internationale contracten een arbitraal beding."
19
Untuk kasus negara-
negara lain sinyalemen tersebut mungkin saja benar seperti itu. Namun
belum dapat dipastikan apakah keadaan di Indonesia juga semacam itu. Oleh
17
Di Indonesia kehadiran Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) ternyata belum
mampu merangsang pelaku bisnis yang bersengketa untuk memberikan kepercayaan
pada lembaga arbitrase. Keadaan tersebut dapat disaksikan dari data yang ada di BANI,
sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 2001 ternyata hanya terdapat 211 kasus yang
masuk. Dari 211 kasus tersebut yang berhasil diputus sebanyak 129 kasus. Kemudian
yang dicabut atau batal (tanpa diketahui alasannya) sebanyak 58 kasus, dan yang dalam
proses administrasi atau ditunda sebanyak 24 kasus. Data di atas diperoleh dari BANI
pada tanggal 15 Juli 2002. Bdgk. Adi Sulistiyono, MengembangkanOp. Cit., h. 89.
18
Millions of contracts, insurance policies, leases, franchise and employment agreement,
and other business and personal arrangements include arbitration clause. Such clauses
bind the parties to arbitrate disputes that may arise over the meaning or application of
the language in the contract. Lihat Robert Coulson, Business Arbitration What You
Need to Know. (revised third edition), New York: AAA, 1987, h. 9.
19
Lihat A.J. van den Berg et al., Arbitrage Recht. W.E.J. Tjeenk Willink - Zwolle,
1988, h.137; Sudargo Gautama seakan memperkuat sinyalemen di atas dengan
menyebutkan: Menurut kenyataan kontrak-kontrak dagang Internasional hampir
seluruhnya memuat suatu klausula arbitrase. Arbitrase memang sengaja telah dipilih
oleh mereka yang berkecimpung dalam perdagangan internasional karena mereka
umumnya kurang mempercayai badan-badan peradilan negara-negara berkembang,
termasuk juga sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Lihat S. Gautama, Masalah-
Masalah Baru HPI. Alumni, 1984, h. 45-46. Cf., The Hon. Mr. Justice KERR,
International Arb. v. Litigation; The Journal of Business Law. 1980, h. 165.
9
karena adakalanya juga, kontrak bisnis internasional yang disepakati oleh
pengusaha swasta asing dengan pengusaha swasta Indonesia tidak
mencantumkan klausula arbitrase sebagaimana lazimnya.
Kalau pun pilihan-pilihan untuk menyelesaikan sengketa komersial
internasional itu diarahkan kepada forum arbitrase dengan jalan
mencantumkan klausula arbitrase di dalam kontrak bisnis, boleh jadi hal itu
karena pihak-pihak dihadapkan kepada pilihan yang tidak mudah.
20
Di
samping itu, seandainya yang dikehendaki oleh para pihak itu tidak sekedar
penyelesaian sengketa melainkan para pihak juga menghendaki adanya
putusan yang mengikat dari penyelesaian sengketa tersebut, maka pilihan
tentu tidak akan diarahkan kepada penyelesaian sengketa alternatif yang
tergolong non-adjudicatory procedures.
21
Oleh karena penyelesaian
20
Sejak zaman Orde Baru, sistem hukum dan peradilan di Indonesia memang dianggap
kurang dapat memberikan rasa keadilan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Hal
demikian sangat dirasakan oleh pihak-pihak terlebih lagi oleh pihak asing manakala
berperkara di pengadilan di Indonesia. Kondisi semacam itu ditambah pula oleh
informasi yang kurang bertanggung jawab yang sengaja atau tidak disampaikan oleh
sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan dengan pihak asing yang bersengketa di
Indonesia. Bahkan disinyalir ada sejumlah kantor konsultan hukum di Indonesia
yang tidak segan-segan memberi advis hukum kepada pengacara di luar negeri dengan
membeberkan keadaan yang dianggap kurang memadai dari sistem hukum dan peradilan
di Indonesia. Lebih dari itu bahkan ada sementara kantor konsultan hukum yang
mengatakan: di Indonesia fihak asing tidak akan mendapatkan peradilan yang baik.
Pilihan jurisdiksi peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta dianggap sebagai kurang
memberikan kepastian bagi pihak luar negeri. Lihat S.Gautama, Masalah-Masalah
Baru Hukum Perdata Internasional. Bandung:Alumni, 1984, h. 46-47.
21
Serupa dengan Negotiation, Mediation, Conciliation, sebagai cara alternatif
penyelesaian sengketa, di dalam penyelesaian sengketa internasional juga dikenal cara-
cara yang termasuk dalam Non-Adjudicatory procedures diantaranya adalah Enquiry,
Good Offices, dan UN involvement. Lihat David H. Ott, Peaceful Settlement of
Disputes; dalam Public International Law in the Modern World. London: The Bath
Press, 1987, h. 333-335.
10
sengketa alternatif semacam negosiasi, mediasi, dan konsiliasi sudah jelas
tidak dapat menghasilkan putusan (award) yang mengikat para pihak.
Memang mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang paling
sederhana dan biasanya prosesnya juga paling cepat adalah melalui
negosiasi
22
di antara para pihak atau para penasihat (adviser) mereka. Bahkan
negosiasi di antara para pihak dianggap paling mendekati penyelesaian
sengketa secara damai, karena para pihak sendiri yang paling mengetahui
kekuatan serta kelemahan dari kasus mereka masing-masing. Apabila
mereka memerlukan nasihat mengenai sengketa yang dihadapi, mereka selalu
dapat meminta nasihat dari para konsultan hukum (lawyers), para akuntan,
para ahli teknik (engineers), maupun ahli-ahli yang lainnya. Namun
demikian, negosiasi sangat memerlukan sikap yang netral serta objektif di
samping tentu saja kehendak untuk berkompromi. Di samping itu, negosiasi
selalu mungkin untuk dilakukan, bahkan setelah metode penyelesaian
sengketa yang lain dijalankan.
22
Negosiasi (negotiation), termasuk ke dalam kelompok non-adjudicatory methods of
settlement, secara esensial negosiasi berarti pertukaran pendapat dan usul antar pihak
sengketa untuk mencari kemungkinan tercapainya penyelesaian sengketa secara damai.
Negosiasi tergolong metode yang paling tua yang dikenal di dalam hubungan
internasional. Metode ini pun diterima secara universal dan yang paling umum
dipakai untuk menyelesaikan sengketa internasional. Negosiasi merupakan suatu proses
yang di dalamnya secara eksplisit diajukan usul secara nyata untuk tercapainya suatu
persetujuan. Negosiasi melibatkan diskusi langsung antar pihak sengketa. Periksa,
Mohd. Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional. Yogyakarta: Liberty,
1990, h. 108.
11
Namun demikian, meski secara teoretis negosiasi memang tergolong
cara penyelesaian sengketa komersial yang dianggap paling sederhana dan
paling cepat, akan tetapi seperti dikemukakan di atas, kadang-kadang para
pihak menghendaki agar sengketa mereka diputus oleh lembaga yang
putusannya mengikat. Oleh karena itu, para pihak biasanya akan menempuh
jalan lain, baik melalui pengadilan atau bahkan secara khusus memilih
penyelesaian lewat forum arbitrase.
Sesungguhnya persoalan penyelesaian sengketa bagi para pelaku
bisnis, itu bukan merupakan fokus utama perhatian mereka. Sejak awal tujuan
mereka memang berbisnis dan sama sekali bukan untuk bersengketa.
Perhatian utama para pelaku bisnis adalah pada pemenuhan prestasi atau
pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan bukan pada
sengketa maupun upaya penyelesaiannya.
Akan tetapi, di dalam kehidupan ini, apalagi dalam interaksi bisnis,
kadang-kadang sesuatu peristiwa yang tidak diduga terjadi dan sama sekali
tidak dapat dihindari. Apabila dari peristiwa itu kemudian berkembang
menjadi suatu pertikaian tentang berbagai masalah bisnis dan semakin
kompleks, apalagi sudah menyangkut hal-hal yang sangat substansial dalam
interaksi mereka, maka perselisihan semacam itu tidak dapat dibiarkan. Oleh
karena itu, tatkala timbul keadaan semacam itu sebagai akibat dari
pelaksanaan hak dan kewajiban mereka, pada umumnya mereka terlebih
12
dahulu akan membawa hal tersebut untuk dibahas bersama penasihat hukum
(lawyer) mereka. Dalam pembicaraan tersebut tentu saja termasuk
menentukan di mana sengketa tersebut hendak diselesaikan.
Demikian pula ketika awal kesepakatan bisnis dibuat dan kontrak
bisnis disepakati, pada umumnya para pelaku bisnis tidak secara khusus
memikirkan untuk memilih forum penyelesaian sengketa. Bagi mereka
klausula penyelesaian sengketa yang dituangkan di dalam setiap kontrak
bisnis, bukanlah sesuatu yang terlalu dipersoalkan, sehingga hal itu seringkali
dianggap sebagai sesuatu yang ada secara built-in di dalam setiap kontrak
dan tidak harus selalu merupakan kehendak dari para pihak.
Anggapan tersebut memperoleh pembenaran dari sejumlah konsultan
hukum pengusaha yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini. Bahwa
sejak kontrak bisnis disepakati, untuk menentukan klausula penyelesaian
sengketa, pelaku bisnis senantiasa menyerahkan kepada konsultan hukumnya.
Walaupun hal itu tidak berarti para pelaku usaha tidak memiliki kehendak
untuk memilih forum lain sebagai tempat menyelesaikan sengketa selain
pengadilan negeri, namun setidaknya merupakan indikasi bahwa terhadap
persoalan di luar persoalan bisnis, acapkali para pengusaha tidak hendak
terlalu jauh mencampuri. Dengan demikian forum mana pun yang dipilih dan
dijadikan sebagai klausula penyelesaian sengketa di dalam kontrak, bagi
13
pihak-pihak materil,
23
dalam hal ini para pengusaha, hampir tidak ada
masalah. Yang paling utama bagi mereka sesungguhnya adalah tidak
terganggunya kegiatan bisnis oleh berbagai perselisihan di antara mereka.
Pada umumnya para pengusaha hanya menghendaki agar sengketa yang
dihadapi dengan mitra usahanya tidak menyebabkan terganggunya kegiatan
bisnis mereka. Mereka juga tidak ingin bila kasus sengketa yang melibatkan
dirinya terbuka luas diketahui pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan,
sehingga berakibat tidak menguntungkan aktivitas bisnisnya.
Mengingat komitmen dan orientasi para pengusaha itu semata-mata
terhadap profit dan bukan pada sengketa atau pun proses penyelesaiannya,
maka menjadi tugas para konsultannya untuk memberitahu apa yang
seharusnya dan sebaiknya dilakukan. Salah satu tugas yang dilakukan
konsultan hukum pengusaha tentu saja memberi informasi tentang berbagai
hal kepada kliennya secara baik dan benar. Demikian pula dalam konteks
penyelesaian sengketa bisnis yang akan atau sedang dihadapi. Para konsultan
tentu akan dan harus berusaha untuk meyakinkan kliennya agar menempuh
upaya yang relatif lebih kecil risiko
24
bisnisnya. Bila memilih pengadilan
23
Pihak materiil dalam perkara adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung di
dalam perkara bersangkutan, baik sebagai claimant (orang yang membuat
tuntutan/penggugat) maupun sebagai respondent (orang yang dijadikan sebagai
tertuntut/tergugat). Periksa, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata
Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1985 h. 47-48. Bdgk. M. Yahya Harahap, Arbitrase.
Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 132-133.
24
Secara etimologi, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan,
membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Periksa, Kamus Besar Bahasa
14
sebagai tempat penyelesaian sengketa dianggap oleh para pelaku bisnis
memiliki risiko bisnis yang besar, maka memilih arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa bisnis dianggap memiliki risiko bisnis relatif lebih
kecil. Itulah yang kemudian dikenal secara umum bahwa mekanisme
penyelesaian sengketa lewat arbitrase dianggap memiliki keunggulan.
25
Namun demikian, memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan
sengketa bisnis dengan asumsi lebih menguntungkan karena arbitrase
memiliki keunggulan dan risiko bisnisnya relatif lebih kecil, faktanya belum
tentu selalu demikian. Ambil contoh satu hal saja, berkenaan dengan
putusan arbitrase. Sebagaimana diketahui bahwa forum arbitrase tidak
memiliki kewenangan publik untuk dapat mengeksekusi sendiri setiap
putusan yang dijatuhkannya. Dengan demikian, suatu putusan arbitrase, di
mana pun putusan tersebut dijatuhkan, akan selalu tidak memiliki titel
Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 751. Jadi yang dimaksud dengan risiko
bisnis dalam konteks pembahasan pilihan forum penyelesaian sengketa di muka
adalah: akibat yang merugikan atau membahayakan kegiatan bisnis yang akan dialami
oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku bisnis,
apabila mereka keliru menentukan pilihan forum dalam rangka menyelesaikan
sengketa yang sedang dihadapi.
25
Keunggulan arbitrase di antaranya: (i) para pihak yang bersengketa dapat memilih para
arbiternya sendiri yang dipercayai memiliki integritas (integer =utuh/keutuhan pribadi),
kejujuran, keahlian, dan profesionalisme di bidangnya masing-masing (namun
demikian, sama sekali tidak mewakili pihak yang memilihnya). Artinya, orang tersebut
adalah independen dan bukan penasihat hukumnya; (ii) proses pemeriksaan sengketa
dalam majelis arbitrase itu konfidensial, sehingga menjamin rahasia serta tidak ada
publisitas yang tidak dikehendaki; (iii) tata cara arbitrase lebih informal dibandingkan
dengan beracara di pengadilan, sehingga hubungan komersial para pihak di kemudian
hari setelah proses penyelesaian sengketa tidak harus terganggu seperti halnya jika
penyelesaian sengketa dilakukan lewat pengadilan dengan segala formalitas
15
eksekutorial (executoriale titel)
26
sebelum putusan tersebut diserahkan dan
didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
27
Bahkan untuk putusan arbitrase internasional ditentukan setelah putusan
tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada
Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan baru dapat dilaksanakan di
Indonesia setelah memperoleh eksekuatur (exequatur)
28
dari Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
29
Berbicara mengenai keterlibatan pengadilan negeri di dalam rangkaian
proses arbitrase tidak sekedar menyangkut persoalan eksekuatur untuk
kepentingan eksekusi putusan arbitrase. Bahkan pengadilan negeri terlibat di
dalam rangkaian proses arbitrase sejak awal sampai dengan pelaksanaan
putusan. Artinya kewenangan pengadilan negeri tidak sekedar sebagai
penerima pendaftaran dan pemberi eksekuatur, melainkan juga menunjuk
arbiter atau majelis arbitrase,
30
apabila para pihak tidak dapat mencapai
kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada ketentuan yang
beracaranya. H. Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian
Sengketa. Jakarta: Fikahati Aneska-BANI, 2002, h. 63-64.
26
Titel eksekutorial adalah alas hak eksekutorial, tulisan yang memberikan dasar untuk
penyitaan dan lelang sita. Putusan yang mempunyai kekuatan pasti (kracht van
gewijsde).
27
Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999.
28
Adalah pernyataan dapat dilaksanakan suatu keputusan pengadilan; khusus pernyataan
setuju dengan pelaksanaan keputusan (fiat executie), dari Ketua Pengadilan Negeri atas
putusan wasit. Lihat N.E. Algra et al., Fockema Andreae Kamus Istilah Hukum.
Bandung: Binacipta, 1977, h. 129.
29
Pasal 67 ayat (1) juncto Pasal 66 huruf d UU Nomor 30 Tahun 1999.
30
Pasal 13 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999.
16
dibuat mengenai pengangkatan arbiter. Demikian pula dalam suatu arbitrase
ad hoc, setiap ketidaksepakatan dalam penunjukan seorang atau beberapa
orang arbiter, para pihak dapat mengajukan permohonan kepada Ketua
Pengadilan Negeri untuk menunjuk seorang atau lebih arbiter.
31
Di dalam praktik, pihak yang dikabulkan tuntutannya atau penasihat
hukumnya biasanya memasukkan putusan arbitrase untuk didaftarkan
berdasarkan surat kuasa dari para arbitrator. Surat kuasa yang memberi
kewenangan kepada pihak yang dikabulkan tuntutannya atau penasihat
hukumnya untuk mendaftarkan putusan arbitrase itu biasanya sudah
termasuk di dalam putusan. Namun demikian, menurut Hukum Indonesia,
surat kuasa untuk keperluan tersebut harus berisi kata-kata yang tegas yang
menyatakan luas lingkup dari kewenangan yang didelegasikan oleh para
arbiter kepada pihak yang menang atau penasihat hukumnya.
Apabila pihak yang harus melaksanakan putusan arbitrase tidak
bersedia melaksanakannya, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat
memerintahkan agar pihak yang bersangkutan melaksanakan putusan
arbitrase dimaksud atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
32
Akan tetapi sebelum Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk
melaksanakan putusan, terlebih dahulu memeriksa apakah putusan arbitrase
31
Pasal 13 ayat (2).
32
Pasal 61 UU Nomor 30 tahun 1999.
17
dimaksud memenuhi ketentuan pasal 4 dan pasal 5, serta tidak bertentangan
dengan kesusilaan, dan ketertiban umum.
33
Dalam hal putusan arbitrase
tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 ayat (2),
Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan putusan dan
terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak ada upaya hukum
apa pun.
34
Berdasarkan hasil penelitian yang diadakan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada bulan Januari 2002 berkenaan dengan putusan arbitrase
nasional yang didaftarkan untuk dilaksanakan, menunjukkan bahwa jumlah
putusan yang didaftarkan turun dari 19 putusan pada tahun 1999 menjadi
hanya enam putusan saja pada tahun 2001, walaupun perintah pelaksanaan
diberikan sembilan kali pada tahun 1999 dan tidak ada sama sekali pada
tahun 2000 dan 2001.
35
Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa yang
berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
36
Berkaitan dengan persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan
arbitrase, terutama putusan arbitrase internasional di Indonesia, sejak dahulu
33
Pasal 62 ayat (2).
34
Pasal 62 ayat (3).
35
Mulyana, et al., Indonesias New Framework For International Arbitration: A Critical
Assessment of the Law and Its Application by the Court; Mealeys International
Arbitration Report. January, 2002, h. (1-32) 23.
36
Pasal 65 UU No. 30/1999.
18
tidak pernah ada kepastian hukum.
37
Padahal sejak Indonesia meratifikasi
Konvensi New York 1958,
38
sejak saat itu pula banyak pihak menaruh
harapan jika putusan arbitrase asing akan dapat dilaksanakan di Indonesia.
Namun faktanya permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase
asing selalu kandas dan ditolak. Putusan berikut ini merupakan salah satu
contoh kasus yang permohonan pelaksanaannya ditolak oleh Mahkamah
Agung. Secara ringkas, kronologis penolakan tersebut dapat disimak berikut
ini:
London Arbitration Awards No. 1950, tanggal 12 Juli 1978, kasus
antara PT Nizwar Jakarta vs Navigation Maritime Bulgare, varna, Blvd.
Chervenoermeiski. Putusan tersebut dimintakan fiat eksekusi melalui
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dengan penetapan No.2288/1979 P.,
tanggal 10 Juni 1981 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan
permohonan pemohon. Artinya putusan Arbitrase London itu dapat
dieksekusi. Namun demikian PT Nizwar Jakarta selaku termohon eksekusi
mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Melalui putusannya Nomor 2944
K/Pdt/1983 Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan arbitrase asing
37
Sejak dasawarsa delapan puluhan, tatkala arbitrase sebagai salah satu forum tempat
penyelesaian sengketa, mulai populer digunakan oleh kalangan pengusaha sebagai
forum alternatif di luar pengadilan negeri, sampai dengan tahun 1990, tatkala
diterbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990, persoalan
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, keadaannya masih tidak menentu.
38
Dengan instrumen ratifikasi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1981.
19
seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Di antara alasan penolakan
Mahkamah Agung, sehingga putusan arbitrase London itu tidak dapat
dilaksanakan ketika itu, antara lain karena belum atau tidak ada peraturan
pelaksanaan (implementing regulation) untuk Konvensi New York 1958.
39
Bila dibandingkan dengan keadaan di waktu yang lalu, setelah
undang-undang arbitrase diundangkan pun, berkenaan dengan mekanisme,
serta prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
tampaknya masih sama saja dengan keadaan tatkala masih berlaku Peraturan
Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1990.
40
Kalau pun ada yang
berbeda, sesungguhnya perbedaan itu tidak memiliki arti. Oleh karena itu,
39
Pada dasarnya untuk Konvensi New York 1958 yang disahkan oleh Pemerintah RI
dengan instrumen ratifikasi berupa Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada
prinsipnya tidak perlu implementing regulation. Namun demikian pertimbangan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 2944 K/Pdt/1983 antara lain menyebutkan: Bahwa
selanjutnya mengenai Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus
1981 dan lampirannya tentang mengesahkan Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Arbitral Awards sesuai dengan praktik hukum yang berlaku
masih harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan eksekusi
putusan hakim arbitrase dapat diajukan langsung pada pengadilan negeri, kepada
pengadilan negeri yang mana ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui
Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut
tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban umum di Indonesia.
Lihat S. Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional. Bandung: Alumni, 1986,
hlm. 112-113. Bdgk. Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan.
Jakarta: Chandra Pratama, 2001, h. 40.
40
Ketika itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung PERMA Nomor 1 Tahun 1990,
putusan arbitrase asing hanya diakui serta dapat dilaksanakan di dalam wilayah hukum
Republik Indonesia apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (i) dijatuhkan oleh
suatu badan arbitrase atau arbiter perorangan di suatu negara yang bersama-sama
dengan Indonesia terikat dalam suatu konvensi internasional perihal pengakuan serta
pelaksanaan putusan arbitrase asing. Pelaksanaannya didasarkan atas asas timbal balik
(resiprositas); (ii) putusan-putusan yang menurut hukum Indonesia termasuk dalam
20
seandainya maksud para pihak melakukan pilihan forum arbitrase hanya
didasari oleh asumsi karena arbitrase memiliki keunggulan dan terjamin dari
publisitas yang kurang menguntungkan, alasan itu saja belum cukup. Fakta
di muka cukup membuktikan bahwa, putusan arbitrase belum mandiri,
belum final, dan belum mengikat.
Bukti bahwa putusan arbitrase belum mandiri, dapat ditengok dari
ketentuan mengenai putusan arbitrase terlebih dahulu harus diserahkan
dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri, dengan ancaman sanksi
tidak dipenuhinya ketentuan dalam pasal 59 ayat (1) berakibat putusan
arbitrase tidak dapat dilaksanakan.
41
Norma tersebut tidak hanya menjadi
bukti bahwa putusan arbitrase belum mandiri, namun sekaligus secara tegas
telah mensubordinasikan putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan
negeri. Kemudian, putusan arbitrase juga ternyata masih belum final.
Buktinya: Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan secara
sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua
Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.
42
Hakikat dari ketentuan itu sebenarnya merupakan upaya hukum yang
diberikan kepada pihak yang bersengketa dalam forum arbitrase, tatkala
ruang lingkup Hukum Dagang; (iii) putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban
umum; (iv) setelah memperoleh exequatur dari Mahkamah Agung RI.
41
Pasal 59 ayat (1) juncto ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999.
21
pihak lawannya tidak secara sukarela melaksanakan putusan yang telah
dijatuhkan. Apalagi bila diperhatikan ketentuan berikutnya,
43
akan tampak
sekali betapa putusan arbitrase itu baru dapat dilaksanakan setelah putusan
arbitrase itu dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri. Artinya, dalam
keadaan salah satu pihak tidak secara sukarela melaksanakan putusan
arbitrase, maka forum arbitrase sebagai pemutus sama sekali tidak memiliki
kewenangan apa pun untuk dapat memaksakan putusan yang dijatuhkannya
agar dapat dilaksanakan oleh pihak yang menolak untuk melaksanakannya.
B. Perumusan Masalah
Ketika kondisi lembaga peradilan semakin mengalami krisis
kepercayaan dan krisis kewibawaan dari masyarakat, kajian tentang pilihan
forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa komersial memiliki alasan
yang memadai untuk dilakukan. Untuk itu tema studi dalam rangka
penyusunan disertasi ini adalah Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa
Komersial untuk Penegakan Keadilan.
Terdapat tiga permasalahan yang hendak dikaji melalui penulisan
disertasi ini, yaitu: Pertama, apakah benar forum arbitrase dipilih untuk
menyelesaikan sengketa komersial oleh kalangan bisnis atas dasar alasan
42
Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999.
43
Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan
sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Lihat, Pasal 64 UU No. 30/1999.
22
agar materi sengketa dan para pihak terjamin kerahasiaannya serta
putusannya dianggap lebih memuaskan bila dibandingkan dengan putusan
pengadilan? Kedua, benarkah terdapat faktor-faktor internal dari pengadilan
negeri yang selama ini dianggap kurang menguntungkan oleh komunitas
pelaku bisnis sehingga mereka lebih suka memilih forum arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa mereka? Ketiga, benarkah putusan forum arbitrase
itu bersifat final dan mengikat para pihak karena tidak mengenal upaya
hukum banding dan kasasi, sehingga melalui forum arbitrase para pihak
dapat lebih cepat memperoleh hak yang dituntutnya bila dibandingkan
dengan menuntut hak melalui pengadilan negeri?
Bertolak dari ketiga masalah di muka, studi ini dapat diproyeksikan
dalam masalah utama sebagai berikut:
Mungkinkah forum arbitrase di masa depan dapat dikembangkan
sebagai salah satu forum khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa
komersial di luar pengadilan negeri yang memiliki kewenangan publik untuk
mengeksekusi putusannya, sehingga putusan arbitrase lebih mencerminkan
penegakan keadilan substansial yang bermartabat?
23
C. Kerangka Pemikiran
Sebagai suatu fenomena sosial, sengketa atau konflik
44
akan selalu
dijumpai dalam kehidupan manusia atau kehidupan bermasyarakat.
45
Dalam
setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana
sengketa ditangani. Sengketa tidak hanya dapat diatasi dengan jalan
mengajukannya ke forum pengadilan, melainkan terdapat aneka ragam cara
yang dapat ditempuh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.
46
Dalam
menyelesaikan sengketa, masyarakat dapat menempuh berbagai cara, baik
44
Konflik adalah segala bentuk interaksi yang bersifat oposisi atau suatu interaksi yang
bersifat antagonistis (berlawanan, bertentangan atau berseberangan). Konflik terjadi
karena perbedaan, kesenjangan, dan kelangkaan kekuasaan, perbedaan atau kelangkaan
posisi sosial dan posisi sumberdaya atau disebabkan sistem nilai dan penilaian yang
berbeda secara ekstrim." Lihat Kusnadi et al., Teori dan Manajemen Konflik
(Tradisional, Kontemporer & Islam). Malang: Taroda, 2001, h. 11.
45
Georg Simmel antara lain mengungkapkan: the individual does not attain the unity
of his personality exclusively by an exhaustive harmonization, On the contrary,
contradiction and conflict not only precede this unity but are operative in it. Lihat,
Valerine J.L.Kriekhoff, Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum); dalam
T.O. Ihromi (ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 1993, h. 224. Sementara itu Schuyt memperkenalkan bentuk-bentuk
penyelesaian konflik yang terbagi dalam 6 (enam) sub kategori, yaitu: Kelompok
Pertama, Penyelesaian sepihak (penyerahan sementara, menghindarkan
diri/meninggalkan, penyerahan); Kelompok kedua, Dikelola sendiri (dengan undian,
kesepakatan, perundingan); Kelompok ketiga, Pra-juridis (pemakaian jasa penengah,
sidang/musyawarah, perdamaian, pengaduan); Kelompok keempat, Juridis normatif
(proses pidana, proses perdata, proses administratif, sidang pengadilan, proses singkat,
arbitrase); Kelompok kelima, Juridis-politis (bertahap tanpa kekerasan, tindakan politik
dan aksi sosial, pembentukan keputusan legislatif, penyelesaian melalui saluran
pemerintah); Kelompok keenam, Penyelesaian dengan kekerasan (kekerasan). Lihat
dalam Ronny Hanitijo Soemitro, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik.
Masalah-Masalah Hukum No. 2 Tahun 1993, h. 26-30.
46
Kebudayaan manusia untuk menampung, mengatasi atau menyelesaikan sengketa-
sengketa dapat terdiri atas: (1) Membiarkan saja (lumping it), (2) Mengelak
(avoidance), (3) Paksaan (coercion), (4) Perundingan (negotiation), (5) Mediasi
(mediation), (6) Arbitrase (arbitration), (7) Peradilan (adjudication). Periksa T.O.
Ihromi, Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan dalam
24
melalui forum formal yang telah disediakan oleh negara, seperti halnya
pengadilan, atau melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh
negara.
47
Dalam hubungan dengan aneka ragam cara yang dapat ditempuh
manusia untuk menyelesaikan sengketa di atas, terdapat beberapa teori yang
dapat digunakan sebagai sarana melakukan kajian berkaitan dengan hal
tersebut. Menurut teori voluntaristik dari aksi (voluntaristic theory of action)
dari Talcott Parsons,
48
individu selaku aktor memiliki cara-cara tertentu
untuk mencapai tujuannya. Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana
norma-norma mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk
mencapai tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap
cara atau alat, tetapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih.
Kemampuan itulah yang oleh Parsons disebut sebagai voluntarism. Dalam
pengertian lain, voluntarism adalah kemampuan individu melakukan tindakan
dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia
dalam rangka mencapai tujuannya.
Antropologi Hukum; di dalam T.O. Ihromi (ed), Antropologi HukumIbid., h. 210-
212.
47
Dalam bahasa A.J. van den Berg, pengadilan disebut dengan overheidsrechtspraak
(peradilan pemerintah) dan hakimnya disebut overheidsrechter (hakim pemerintah),
karena baik lembaga maupun hakimnya secara resmi disediakan oleh negara.
Sedangkan forum yang tidak resmi disediakan oleh negara, misalnya forum arbitrase
disebut dengan particuliere rechtspraak (peradilan swasta). Lihat A.J. van den Berg,
ArbitrageOp. Cit., h. 7.
48
George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. (Penyadur:
Alimandan), Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 48-49. Bdgk. Soerjono Soekanto,
Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif. Jakarta: CV Rajawali, 1986, h. 25-27.
25
Berdasarkan pada teori Parsons tersebut, manusia selaku aktor
adalah pelaku aktif, kreatif, dan evaluatif serta mempunyai kemampuan
menilai dan memilih alternatif tindakan, meskipun kondisi dan norma serta
situasi penting lain kesemuanya membatasi kebebasan aktor. Oleh karena itu,
tindakan melakukan pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa di luar
pengadilan pemerintah, merupakan ekspresi kemauan bebas dari aktor dalam
memilih berbagai alternatif tindakan dalam rangka mencapai tujuannya.
Di samping itu, memilih forum untuk menyelesaikan sengketa di luar
pengadilan pada dasarnya merupakan hasil dari interaksi sosial dalam
masyarakat yang terjadi berdasarkan penafsiran fenomenologi, yaitu
berlangsung atas maksud, pemaknaan, dan tujuan, bukan didasarkan atas
proses mekanik dan otomatik. Selain itu tentu saja pilihan forum
penyelesaian sengketa merupakan salah satu bentuk keterlibatan langsung
manusia sebagai anggota masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Sedangkan
keterlibatan manusia dalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya
hubungan antara budaya dan hukum. Budaya hukum inilah yang menentukan
sikap, ide-ide, nilai-nilai seseorang terhadap hukum di dalam masyarakat.
49
Budaya hukum adalah tanggapan umum yang sama dari masyarakat
tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan
pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum
49
Op. Cit., h. 11.
26
menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat
yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan
hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.
50
Budaya hukum sebagai
sesuatu yang menjadi buah pikiran dan keyakinan manusia, keadaannya tidak
statis melainkan berubah-ubah mengikuti perubahan dalam masyarakat.
51
Dengan demikian yang disebut budaya hukum itu tidak lain adalah
keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh
tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum. Oleh
karena itu, budaya hukum tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen
tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas. Akan tetapi diartikan
sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut
sikap yang mempengaruhi hukum. Jadi termasuk rasa respek atau tidak
respek kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan, atau
tidak menggunakan pengadilan
52
(karena lebih memilih cara-cara informal
untuk menyelesaikan sengketa), dan juga sikap-sikap serta tuntutan-tuntutan
50
Hilman Hadikusuma, Antropologi Hukum Indonesia. Bandung: Alumni, 1986, h. 51.
51
Lawrence M. Friedman, American Law an Introduction; Hukum Amerika sebuah
Pengantar, (alih bahasa: Wishnu Basuki). Jakarta: Tatanusa, 2001, h. 173.
52
Di negara-negara berkembang, pengadilan adakalanya dianggap perpanjangan tangan
kekuasaan, bahkan di beberapa negara pengadilan dianggap tidak bersih, sehingga
putusan-putusannya dianggap telah memihak yang mendatangkan ketidakadilan.
Alasan-alasan budaya, menyebabkan masyarakat cenderung mengesampingkan
pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul di antara mereka. Lihat,
Erman Rajagukguk, Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di Luar
Pengadilan dalam Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 4, Okt. 2000, h. 1-15 [1-2].
27
pada hukum yang diajukan oleh kelompok etnik, ras, agama, dan kelas-kelas
sosial yang berbeda.
53
Budaya hukum
54
bukan merupakan budaya pribadi, melainkan budaya
menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan
perilaku. Untuk itu sebagaimana diutarakan di muka, kesepakatan dalam
penyelesaian suatu perselisihan hukum tidak terlepas dari pola orientasi
hukum yang umum dalam masyarakat,
55
yang merupakan pencerminan
budaya hukum, yaitu pencerminan dari nilai-nilai budaya mengenai hukum
dan keadilan yang dirasakan masyarakat, yang dikehendaki, dan dibenarkan
oleh masyarakat bersangkutan.
56
Apabila dua orang atau dua pihak bersengketa mengenai sesuatu hal
atau sesuatu kepentingan, kemudian mereka mencari penyelesaian melalui
53
Lawrence M. Friedman, On Legal Development. Rutgers Law Review, (alih bahasa:
Rachmadi Djoko Soemadio), 1969, h. 27-30.
54
Budaya hukum merupakan kekuatan dalam masyarakat yang pada akhirnya akan
menentukan bagaimana hukum itu diterima dan dijalankan di situ. Kekuatan tersebut
berakar pada tradisi, pada sistem nilai-nilai yang dianut, yang pada akhirnya
menentukan sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukumnya.
Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan
Budaya Hukum; Makalah pada Lokakarya Pembangunan Bidang Hukum
Repelita VII. Jakarta BPHN, Juli 1997, h. 1-13, [3].
55
Masyarakat Timur seperti Cina dan Jepang, secara tradisional tidak suka pada
pengadilan. Pengadilan dianggap sebagai tempat orang-orang jahat, yang tidak
mematuhi hukum. Secara tradisional orang-orang Cina dan Jepang amat segan untuk
membawa sengketa-sengketa perdata mereka ke depan pengadilan. Lihat, Erman
Rajagukguk, Op. Cit. h. 1-2.
56
Hilman Hadikusuma, Op. Cit., h. 53. Di samping itu untuk menjaga harmoni serta
karena alasan-alasan praktis, penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti arbitrase,
dan juga forum non litigasi seperti: negosiasi, mediasi, dan konsiliasi semakin
berkembang di Amerika Serikat maupun di Jepang. Lihat, Linda R. Singer, Settling
Disputes - Conflict Resolution in Business, Families, and The Legal System. San
Fransisco, 1994, dalam Erman Rajagukguk, Op. Cit., h. 2.
28
institusi hukum di luar pengadilan, artinya pihak-pihak bersangkutan
memiliki persepsi tertentu terhadap institusi hukum itu. Di samping karena
keyakinannya, tuntutannya, serta dorongan kepentingan, masih terdapat
faktor-faktor lain, seperti harapan dan juga penilaian positif terhadap institusi
yang dipilih tersebut.
57
Oleh karena menyelesaikan sengketa di luar proses
pengadilan hasilnya dianggap lebih memenuhi rasa keadilan bagi para
pemilihnya, sehingga memilih forum penyelesaian sengketa merupakan
asumsi fundamental, yakni apa yang dianggap adil dan tidak oleh
masyarakat, sehingga memilih forum merupakan komponen substansif dari
budaya hukum.
58
Tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian suatu sengketa hukum
tidak terlepas dari pola orientasi hukum yang umum dalam masyarakat, yang
merupakan pencerminan budaya hukum. Yaitu pencerminan dari nilai-nilai
budaya mengenai hukum dan keadilan yang dirasakan masyarakat, yang
dikehendaki, dan dibenarkan oleh masyarakat bersangkutan.
59
Oleh karena
budaya hukum itu meliputi orientasi pribadi yang berlatar belakang pada
pengetahuan dan pengalaman seseorang yang menyebabkan adanya
57
Satjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 167.
58
Esmi Warassih, Op. Cit., h. 11-12. Budaya hukum berhubungan dengan sikap dan
perilaku. Dapat disaksikan betapa budaya hukum dan perilaku hukum menjadi faktor
penentu yang penting, sehingga dapat dikemukakan bahwa ketertiban dan keteraturan
dalam masyarakat atau negara tidak berakar pada hukum dan perundang-undangan,
melainkan juga pada perilaku substansial dari warga negara di situ. Lihat, Satjipto
Rahardjo, Peningkatan Wibawa Hukum Op. Cit., h. 1-3.
59
Hilman Hadikusuma, Op. Cit., h. 53.
29
penilaian, sehingga ia menyetujui atau menolak, atau mendiamkan peristiwa-
peristiwa hukum yang terjadi. Disebabkan hal di atas, penilaian dan persepsi
pihak-pihak dalam masyarakat tentang adil atau tidak adil, menguntungkan
atau tidak dari proses penyelesaian sengketa lewat pilihan forum merupakan
pencerminan budaya hukum masyarakat.
Di samping merupakan pencerminan budaya hukum masyarakat,
tindakan manusia untuk melakukan pilihan forum penyelesaian sengketa
erat kaitannya dengan persoalan perilaku dan keyakinan individu yang
melakukannya. Untuk itu masih dalam konteks pilihan forum ini, dapat pula
disebutkan teori tindakan beralasan (theory of reason action) dari Icek Ajzen
dan Martin Fishbein, yang kemudian dimodifikasi sendiri oleh Ajzen dengan
nama teori perilaku terencana (theory of planned behavior).
Menurut teori perilaku terencana, di antara berbagai keyakinan yang
akhirnya akan menentukan intensi dan perilaku tertentu adalah keyakinan
mengenai tersedia tidaknya kesempatan dan sumber yang diperlukan.
Keyakinan itu dapat berasal dari pengalaman dengan perilaku yang
bersangkutan di masa lalu, dapat juga dipengaruhi oleh informasi tak
langsung mengenai perilaku itu umpama melihat pengalaman teman atau
orang lain yang pernah melakukannya.
60
Di samping berbagai faktor penting
seperti hakikat stimulus itu sendiri, latar belakang pengalaman individu,
30
motivasi, status kepribadian, dan sebagainya, memang sikap individu ikut
memegang peranan dalam menentukan bagaimanakah perilaku seseorang di
lingkungannya. Pada gilirannya, lingkungan secara timbal balik akan
mempengaruhi sikap dan perilaku. Interaksi antara situasi lingkungan dengan
sikap, dengan berbagai faktor di dalam maupun di luar diri individu akan
membentuk suatu proses kompleks yang akhirnya menentukan bentuk
perilaku seseorang.
61
Namun memang, perilaku manusia itu tidaklah sederhana untuk
dipahami dan diprediksikan. Begitu banyak faktor, internal dan eksternal dari
dimensi masa lalu, saat ini, dan masa datang yang ikut mempengaruhi
perilaku manusia. Adapun tampilan teori perilaku terencana di atas
dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa pada dasarnya perilaku manusia
itu tidak secara mekanik dan deterministik akan tetapi reaksi manusia masih
lebih terikat pada hukum-hukum stimulus-respons yang berlaku.
62
Oleh
karena itu, teori psikologi mengenai perilaku
63
manusia juga memiliki
60
Saifuddin Azwar, Sikap Manusia - Teori dan Pengukurannya. (edisi kedua),
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 11-13.
61
Ibid., h. 14
62
Ibid., h. 14-15.
63
Berkenaan dengan perilaku dan keyakinan manusia dapatlah disimak dasar psikologis
dari hukum berikut ini: Dalam diri manusia terdapat tiga hasrat atau nafsu, yaitu
hasrat yang individualistis (egoistis atau atomistis), hasrat yang kolektivistis
(transpersonal atau organis), dan hasrat yang bersifat mengatur atau menjaga
keseimbangan. Hasrat yang individualistis dan hasrat yang kolektivistis selalu saling
bertentangan dan bertolak belakang, sehingga hidup ini akan selalu merupakan
pertentangan terus menerus yang tajam antara dua hasrat tersebut. Oleh karena itu,
dalam diri manusia juga ada hasrat yang bersifat mengatur atau mengkompromikan.
Hasrat ketiga itu bersifat mengatur atau menjaga keseimbangan, sehingga kedua hasrat
31
relevansi dalam rangka memahami tindakan manusia untuk melakukan
pilihan forum penyelesaian sengketa.
Mencarikan penyelesaian sengketa atau konflik di dalam masyarakat,
dengan hanya menggunakan pendekatan ilmu hukum semata-mata untuk
mengadakan analisis dan evaluasi kerapkali tidak memadai. Untuk itu maka
menggunakan pendekatan yang lazim dalam ilmu-ilmu sosial terutama
sosiologi diharapkan dapat memberikan penjelasan dan cara pemecahannya.
Hal itu disebabkan hukum merupakan abstraksi dari interelasi dan interaksi
sosial yang dinamis.
64
Salah satu pendekatan yang relevan dengan konteks
penulisan disertasi ini adalah pendekatan konflik. Pandangan para penganut
pendekatan konflik bertolak pangkal dari anggapan dasar bahwa konflik
merupakan gejala yang melekat pada setiap masyarakat. Sedangkan setiap
masyarakat selalu berada dalam proses perubahan yang tidak pernah
berakhir. Setiap unsur dalam suatu masyarakat memberikan sumbangan
untuk terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial. Oleh karena
itu, menurut penganut pendekatan konflik, dalam setiap masyarakat selalu
terdapat konflik antara kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan
yang saling bertentangan itu dapat dikendalikan. Hasrat yang bersifat mengatur itu
menciptakan keserasian dan bersifat sintetis serta merupakan dasar psikologis dari
hukum.Lihat, Sudikno Mertokusumo, Mengenal HukumOp. Cit., h. 27-28.
64
Lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, Studi Hukum dan Masyarakat. Bandung: Alumni,
1985, h. 20-37.
32
otoritatif,
65
yaitu kepentingan untuk memelihara dan mengukuhkan status
quo pola hubungan kekuasaan yang ada, dengan kepentingan golongan yang
tidak memiliki kekuasaan otoritatif. Itulah sebabnya mengapa para penganut
pendekatan konflik yakin bahwa konflik merupakan gejala kemasyarakatan
yang selalu melekat pada kehidupan setiap masyarakat.
Seiring dengan pendekatan konflik di muka, maka salah satu teori
sosial yang digunakan sebagai sarana analisis hasil penelitian ini adalah
Teori Konflik dari Ralf Dahrendorf. Menurut Teori Konflik, masyarakat
senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan
yang terus menerus di antara unsur-unsurnya. Setiap elemen memberikan
sumbangan terhadap disintegrasi sosial,
66
sementara itu keteraturan yang
terdapat dalam masyarakat hanyalah disebabkan oleh adanya tekanan atau
pemaksaan kekuasaan
67
dari atas oleh golongan yang berkuasa. Kekuasaan
65
Pembagian wewenang (authority) yang tidak merata mengakibatkan timbulnya dua
kategori sosial di dalam masyarakat, yaitu golongan yang memiliki wewenang dan
golongan yang tidak memiliki wewenang. Pembagian wewenang yang bersifat
dikotomis demikian itu dianggap oleh para penganut pendekatan konflik menjadi
sumber terjadinya konflik-konflik sosial, karena menimbulkan kepentingan-
kepentingan yang berlawanan secara substansial maupun berlawanan dalam arahnya.
Ronny Hanitijo Soemitro, Loc. Cit., h. 27.
66
Lihat, George Ritzer, Sosiologi.. Op. Cit., h. 25-26. Bdgk. Ralf Dahrendorf, Class and
Class Conflict in Industrial Society. London: Routledge & Kegan Paul, 1959. Edisi
Indonesia diterjemahkan oleh Ali Mandan, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat
Industri. Jakarta: CV Rajawali, 1986, h. 197-198.
67
Kekuasaan dan otoritas merupakan sumber-sumber yang menakutkan dan mereka yang
memegangnya memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo. Dahrendorf
mengatakan hal itu merupakan kepentingan objektif, yang terbentuk di dalam peran-
peran itu sendiri, bersamaan dengan kepentingan atau fungsi dari semua peran dalam
mepertahankan organisasi itu sebagai keseluruhan Lihat, Ian Craib, Modern Social
Theory: from Parson to Habermas (Teori-Teori Sosial Modern: dari Parson sampai
33
dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi
bawah dalam setiap struktur. Oleh karena itu, Dahrendorf menyebut
masyarakat sebagai persekutuan yang terkoordinasi secara paksa
(imperatively coordinated association).
68
Dunia sosial karenanya distruktur
ke dalam kelompok-kelompok yang secara potensial mengandung konflik.
Dahrendorf
69
membedakan golongan yang terlibat konflik itu atas dua tipe.
Pertama, Kelompok semu (quasi-group) yaitu kumpulan dari para pemegang
kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk
karena munculnya kelompok kepentingan. Kedua, Kelompok kepentingan
(interest group) terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok
kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan, serta
anggota yang jelas. Kelompok kepentingan itulah yang menjadi sumber
nyata terjadinya konflik di dalam masyarakat.
Pada kasus penelitian tentang pilihan forum arbitrase dalam sengketa
komersial ini, kedua tipe kelompok yang dibedakan Dahrendorf di muka
dipastikan kedua kelompok tersebut merupakan bagian dari adanya konflik.
Pertama konflik yang terjadi di antara anggota komunitas kelompok
kepentingan (interest group) satu sama lain. Dalam hal ini para pelaku bisnis
Habermas); Penerjemah: Paul S. Baut dan T. Effendi. Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1994, h. 92-94.
68
Ralf Dahrendorf, Konflik dan Konflik...Op. Cit., h. 204.
69
George Ritzer, Sosiologi.. Op. Cit., h. 27.
34
yang memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa komersial,
mereka merupakan bagian dari konflik antar kelompok kepentingan yang
masing-masing memperjuangkan kepentingan dalam bisnisnya untuk
menyelesaikan pertikaian di antara mereka.
Selanjutnya ketika putusan arbitrase telah diperoleh dan akan
dimohonkan pelaksanaan, potensi konflik terjadi di dalam kelompok semu.
Konflik kewenangan terjadi antara badan arbitrase sebagai pemutus sengketa
dengan pengadilan negeri sebagai pemberi eksekuatur. Hal itu sulit untuk
dihindarkan karena secara normatif eksplisit diatur sebelum putusan badan
arbitrase dilaksanakan, terlebih dahulu lembar asli atau salinan otentik
putusan arbitrase harus diserahkan dan didaftarkan kepada Panitera
Pengadilan Negeri.
Memilih forum arbitrase dalam rangka menegakkan keadilan pada
hakikatnya merupakan upaya untuk menegakkan ide-ide serta konsep-konsep
yang notabene adalah abstrak. Oleh karena itu, penegakan keadilan adalah
mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide
itu pada dasarnya merupakan hakikat dari penegakan hukum. Apabila
berbicara mengenai perwujudan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan,
maka sebetulnya sudah memasuki bidang manajemen (management).
70
Dalam suasana yang demikian maka peranan serta kehadiran organisasi
35
dalam penyelenggaraan hukum dewasa ini merupakan keniscayaan.
Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Satjipto Rahardjo,
71
problema-
problema yang ada sekarang ini tidak bisa disamakan dengan yang terjadi
pada 100 tahun yang lalu ketika tingkat perkembangan sosial masih
sederhana, kehidupan hukum pun masih bersifat intim, dan lebih personal.
Sedangkan sekarang ini, beragam problema sudah menjadi makin besar,
melibatkan sejumlah banyak orang, tugas-tugas yang harus dilaksanakan
juga semakin menggunung, maka dibutuhkan suatu cara penanganan
bersama. Kalau suatu kegiatan sudah melibatkan kompleksitas yang begitu
tinggi dan jumlah orang begitu banyak, maka tidak bisa lain kecuali harus
menjalankannya dalam konteks organisasi. Apabila sudah berbicara
mengenai organisasi, tentu hal pokok yang dipikirkan adalah bagaimana
organisasi itu harus berjalan dengan baik. Sebagaimana telah diutarakan di
muka, apabila pembicaraan sudah memasuki persoalan menyangkut suatu
proses dalam orgaisasi berarti merupakan kegiatan manajemen. Dalam kaitan
ini, Schrode & Voich,
72
mengartikan manajemen sebagai seperangkat
kegiatan atau suatu proses untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan
penggunaan sumber-sumber daya dengan maksud untuk mencapai tujuan
70
Lihat, Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis.
Bandung: Sinar Baru, TT, h. 15.
71
Ibid., h. 16.
72
Satjipto Rahardjo, Loc. Cit.,
36
organisasi melalui orang-orang, teknik-teknik, dan informasi serta dijalankan
dalam kerangka suatu struktur organisasi.
Begitu pula dalam rangka mewujudkan hukum dan keadilan sebagai
ide-ide yang abstrak, ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup
kompleks. Negara harus campur tangan dalam mewujudkan hukum yang
abstrak itu dan harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan
tersebut, sehingga dikenal ada Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian,
Pemasyarakatan, dan juga Badan Perundang-undangan. Melalui organisasi
serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat menerima
perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan, misalnya, kini tidak lagi
merupakan konsep yang abstrak, melainkan benar-benar diberikan kepada
anggota masyarakat dalam bentuk pensahan sesuatu aksi tertentu. Demikian
pula kepastian hukum dapat terwujud melalui putusan-putusan hakim yang
menolak tindakan-tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh anggota
masyarakat. Oleh karena itu, membicarakan hukum dalam konteks organisasi
membuka pintu bagi pengkajian tentang bagaimana lembaga hukum yang
diserahi tugas untuk mewujudkan dan menegakkan hukum itu bekerja.
Pertanyaan lebih lanjut: Mengapa pengorganisasian itu demikian
penting? Menurut J. Winardi,
73
organisasi efektif, dilaksanakan melalui apa
73
J. Winardi, Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2003, h. 20-21.
37
yang dinamakan Sinergisme (Synergism), dimana anggota-anggota sesuatu
organisasi, mengkombinasikan upaya mereka secara kolektif guna
melaksanakan tugas-tugas yang akan jauh melampaui jumlah dari upaya-
upaya individual mereka. Sinergi dicapai melalui pengintegrasian tugas-
tugas yang terspesialisasi. Atas dasar hal tersebut, maka efektivitas
organisasi terjadi bila tujuan yang dibuat oleh organisasi tersebut tercapai
dengan memperimbangkan faktor-faktor efisien, keseimbangan hubungan
antar organisasi dan lingkungannya, serta kesiapan organisasi itu
menghadapi perubahan.
74
Dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai organisasi dan
pengorganisasian penegakan hukum, pengadilan sebagai salah satu lembaga
pemutus konflik dalam perkembangannya hampir tidak mungkin
menghindari terjadi konflik kewenangan dengan lembaga pemutus konflik
lainnya. Apabila hal tersebut dihubungkan dengan pandangan kontemporer,
konflik bukan saja sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, melainkan ia
merupakan suatu kondisi yang perlu untuk orang-orang dan organisasi-
organisasi supaya mereka dapat bersikap adaptif terhadap perubahan.
Tingkat perubahan tertentu diperlukan bagi ketahanan dan pertumbuhan
keorganisasian, sehingga dalam hubungan ini konflik dapat bermanfaat
74
Ginung Pratidina, Manajemen Konflik dalam Menigkatkan Efektivitas Organisasi;
dalam Wawasan Tridharma Nomor 10 Tahun XV Mei 2003, h. 4.
38
sebagai sebuah elemen yang menunjang perubahan tersebut.
75
Mengingat
konflik itu pun memiliki peranan yang potensial yang bermanfaat, maka
menurut pandangan kontemporer, konflik itu perlu di-manaje.
Manajemen konflik (conflict management) mengandung arti bahwa
konflik dapat memainkan peranan dalam rangka upaya pencapaian sasaran-
sasaran secara efisien serta efektif. Konflik sebaiknya tidak sekedar
dihindari, dikurangi atau diatasi, melainkan konflik perlu dimanaje.
Memanaje konflik dapat mengandung arti secara aktif mencari konflik,
atau menciptakan secara positif kondisi-kondisi yang menyebabkan
timbulnya konflik.
76
Marry Parker Follett,
77
seorang pakar manajemen
terkenal pada zamannya pernah mengajukan konsep pemikiran tentang tiga
macam cara pokok untuk menghadapi dan menangani konflik, yakni melalui:
- dominasi (domination);
- kompromis (compromise); dan
- integrasi (integration).
75
J. Winardi, Teori... Loc. Cit., h. 273.
76
Pandangan demikian cukup banyak penganutnya, di antaranya Stephen Robbins dalam
bukunya Managing Organizational Conflict: A Non-Traditional Approach.
Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1974; antara lain menyebutkan ...Managing
conflict may mean stimulating and creating it as well as diminishing or channeling it.
Lihat dalam J. Winardi, Teori... Loc. Cit., h. 275.
77
Lihat dalam J. Winardi, Teori... Loc. Cit., h. 288-289. Bdgk., William Hendricks, How
to Manage Conflict; Bagaimana Mengelola Konflik (Penerjemah: Arif Santoso).
Jakarta: Bumi Aksara, 2001, h. 54-55.
39
Dominasi merupakan sebuah gaya yang digunakan oleh seorang
yang beroperasi dari posisi kekuasaan tertentu. Dewasa ini dominasi
dinamakan gaya menang-kalah (the win-lose style), dan gaya ini diakui
memiliki kelemahan-kelemahan. Adapun kompromis memiliki makna
sebagaimana dikenal dewasa ini. Sedangkan integrasi sangat mendekati
pandangan modern tentang manajemen konflik. Konsep pemikiran
integrasi selaras dengan apa yang dikenal dewasa ini dengan gaya
manajemen konflik menang-menang (win-win conflict management
style).
78
Meskipun demikian memilih forum arbitrase yang diyakini sebagai
model penyelesaian konflik yang win-win solution dalam praktiknya tidak
jarang justru menimbulkan konflik kewenangan antara pengadilan negeri
dengan arbitrase. Akan tetapi konflik semacam itu apabila dihubungkan
dengan teori manajemen konflik di muka, konflik kewenangan tersebut tidak
selalu berdampak negatif. Berdasarkan pemikiran kontemporer tentang
manajemen konflik bahwa konflik dapat juga fungsional yang dapat
dimanfaatkan, sehingga mengacu pada pemikiran tersebut konflik yang
terjadi dalam konteks pilihan forum tentu tidak selamanya berkonotasi
78
Penyelasain konflik menang-menang umumnya dicapai melalui konfrontasi isu dan
penggunaan penyelesaian persoalan untuk melakukan rekonsiliasi perbedaan. Jika
pihak-pihak yang berkonflik sama-sama sangat kuat dan sangat sulit untuk dijatuhkan
dan masing-masing pihak secara terus menerus mempertahankan untuk tidak mau
mengalah sedikit pun, maka penyelesaian yang terbaik adalah kedua belah pihak
40
negatif. Bahkan menurut pandangan interaksionis dalam manajemen konflik,
konflik tidak selalu bekonotasi negatif karena dalam beberapa kasus
kehadiran konflik seringkali menyebabkan perubahan ke arah perbaikan.
Konflik yang fungsional dapat dimanfaatkan untuk memprakarsai pencarian
cara-cara baru yang lebih baik karena seringkali perubahan yang diinginkan
terjadi setelah terlebih dahulu timbul konflik.
79
Untuk itu maka konflik
kewenangan antara pengadilan negeri dengan arbitrase berdasarkan teori
manajemen konflik harus dipandang sebagai konflik yang fungsional yang
diharapkan akan membawa perubahan paradigma dalam penyelesaian
sengketa. Perubahan yang diharapkan terutama adalah adanya kesetaraan
kompetensi antara berbagai model penyelesaian sengketa yang ada dengan
kompetensi yang dimiliki oleh lembaga pengadilan.
Pada sisi yang lain, berdasarkan telaah sifat atau karakter produk
hukum, pilihan forum untuk menyelesaikan sengketa terjadi tidak semata-
mata merupakan refleksi budaya hukum masyarakat serta perilaku dan
keyakinan individu anggota masyarakat. Hal itu juga berkaitan cukup erat
dengan sifat atau karakter produk hukum sebagaimana dikemukakan oleh
Phillippe Nonet dan Philip Selznick.
80
Dalam hubungan ini, Nonet dan
berbagi keinginan yang diharapkan secara proporsional. Lihat Kusnadi et al., Teori dan
Manajemen Konflik. Malang: Taroda, 2001, h. 60.
79
Ginung Pratidina, Manajemen Konflik.... Wawasan... Op. Cit., h. 4-5.
80
Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society in Transition: Toward Responsive
Law. New York: Harper & Row, 1978, h. 14-16.
41
Selznick mengajukan suatu teori yang bertujuan untuk menjelaskan
hubungan sistematik dalam hukum dan konfigurasi-konfigurasi khusus
dimana hubungan-hubungan dalam hukum itu terjadi.
81
Selengkapnya hal
tersebut dapat disimak pada ragaan 1 berikut ini.
Ragaan 1
Three Types of Law
82
_________________________________________________________________
Repressive Law Autonomous Law Responsive Law
ENDS OF LAW Order Legitimation Competence
LEGITIMACY Social defence and Procedural fairness Substantial justice
raison detat
RULES Crude and detailed Elaborate; held to bind Subordinated to prin-
but only weakly rulers as well as ruled ciple and policy
binding on rule
makers
REASONING Ad hoc; expedient Strict adherence to legal Purposive;enlarge-
and particularistic authority; vulnerable to ment of cognitive
formalism and legalism competence
DISCRETION Pervasive; opportu- Confined by rules; narrow Expanded, but ac-
nistic delegation countable to purpose
COERCION Extensive; weakly Controlled by legal re- Positive search for
restrained straints alternatives, e.g., in-
centives, self-sus-
taining systems of
obligations
MORALITY Communal morality; Institutional morality; Civil morality; mo-
Legal moralism: i.e., preoccopied with rality of coopera-
morality of con- the integrity of legal tion
straint process
81
Nonet dan Selznick membedakan tiga keadaan dasar mengenai hukum dalam
masyarakat, yaitu: (1) Hukum represif, yaitu hukum sebagai alat kekuasaan represif;
(2) Hukum Otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampu menetralisasikan
represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri; dan (3) Hukum responsif, yaitu
hukum sebagai suatu sarana respon terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-
aspirasi masyarakat. Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, Gambaran tentang Fungsi-
fungsi Hukum di Dalam Masyarakat, Sebagai Hasil Tinjauan terhadap Hukum dari
Beberapa Perspektif; dalam Masalah-Masalah Hukum Nomor 5 Tahun 1991, h.
41-46 [44-45].
82
Lihat Philippe Nonet & Philip Selznick, Law and Society ...Op. Cit., h. 16.
42
POLITICS Law subordinated Law independent of Legal and political
to power politics politics; separation of aspirations inte-
powers grated; blending of
powers
EXPECTATIONS Unconditional; dis- Legally justified rule Disobedience as-
OF OBEDIENCE obedience per se departures, e.g., to test sessed in light of
punished as defiance validity of statutes of substantive harms;
orders perceived as raising
issues of legitimacy
PARTICIPATION Submissive compli- Access limited by es- Access enlarged by
ance; criticism as tablished procedures; integration of legal
disloyalty emergence of legal cri- and social advocacy
ticism.
Selama beberapa dasawarsa karakter produk hukum represif atau
menindas telah menjadi salah satu identitas dari Pemerintahan Orde Baru di
Indonesia. Bahkan kondisi tersebut telah menempatkan peran dan fungsi
hukum termasuk lembaga peradilan sebagai supporting system untuk
tercapainya stabilitas politik dan tujuan pembangunan. Sebagai akibat dari
cara pandang atau persepsi yang dominan terhadap peran dan fungsi hakim
seperti itu maka lembaga yudikatif bersifat kaku, kurang terbuka, serta
kurang tanggap terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat karena secara
sepihak hukum merupakan pantulan persepsi sosial dan kepentingan para
pengambil kebijakan dan dengan demikian hakim (kekuasaan kehakiman)
harus tunduk pada kebijakan semacam itu. Dalam konstelasi seperti itu sulit
diharapkan hakim berani untuk mengambil keputusan yang berbeda dari
ketentuan yang dicantumkan dalam produk hukum dan perundang-
43
undangan
83
pada saat menghadapi kasus-kasus konkret di pengadilan. Hakim
pada dasarnya adalah bagian dari aparatur pemerintahan. Oleh karena itu,
fungsi serta peran yang dijalankan kekuasaan kehakiman diorientasikan pada
upaya untuk mendukung dan mensukseskan program-program pembangunan
yang ditetapkan pemerintah atau eksekutif.
84
Seperti dapat diketahui dari tabel karakteristik hukum yang
menindas
85
dan hukum yang otonom, ketertiban merupakan tujuan dari tata
hukum, sehingga untuk mempertahankan ketertiban maka tuntutan-tuntutan
dan pertimbangan-pertimbangan lain dikesampingkan. Padahal di samping
ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan, yang
berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.
86
83
Padahal sesungguhnya penegakan hukum yang baik itu tidak sekedar ditentukan oleh
substansi perundang-undangannya, melainkan lebih banyak ditentukan oleh kultur
hukum (sebagaimana didefinisikan Lawrence M. Friedman: yakni mencakup opini-
opini, kebiasaan-kebiasaan, cara bertindak, dan cara berfikir dari seseorang yang
bertalian dengan segala hal yang berbau hukum), warga masyarakat maupun para
penegak hukum dan penguasanya. Lihat, Achmad Ali, Bercermin pada Penegakan
Hukum Jepang; Kompas, 15 April 2002.
84
Benny K. Harman, Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.
Jakarta: Elsam, 1997, h. 56-57.
85
Nonet dan Selznick mencoba menjelaskan, bagaimana sampai terjadi suatu pemerintah
terjatuh kepada pola penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas. Bahwa
penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas terdapat pada masyarakat yang masih
berada pada tahap pembentukan suatu tatanan politik tertentu (in the formative stages of
political society). Pada saat seperti itu tujuan utama adalah menciptakan ketertiban
dalam masyarakat; tujuan yang hendak dicapai dengan usaha apa pun.Philippe Nonet &
Philip Selznick, Op. Cit., h. 29-52.
Bdgk. Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran
tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung:
Sinar Baru, 1985, h. 75.
86
Mochtar Kusumaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan
Nasional; dalam PADJADJARAN (Majalah Ilmu Hukum & Pengetahuan
Masyarakat), Jilid III, Nomor 1, September 1970, h. 5-16 [7].
44
Sedangkan pada karakteristik hukum yang menindas atau represif ketertiban
adalah merupakan substansi tujuan, maka ketertiban itulah yang menjadi
pokok perhatian, sedangkan persoalan tentang cara-cara untuk mencapainya,
terdorong ke belakang. Akibat dari ketertiban sebagai substansi tujuan
hukum, maka di masa lalu tampak sekali integrasi yang kuat antara hukum
dan politik, sebagaimana disebutkan di dalam ragaan dari Nonet bahwa
hukum ditundukkan kepada politik kekuasaan (law subordinated to power
politics).
87
Dalam konstelasi dan konstruksi seperti itu, bolehlah secara bebas
dikatakan di sini bahwa hukum di Indonesia dalam perkembangannya di
akhir abad ke-20 ini benar-benar secara sempurna menjadi government social
control dan berfungsi sebagai tool of social engineering. Walhasil, hukum
perundang-undangan sepanjang sejarah perkembangan pemerintahan Orde
Baru telah menjadi kekuatan kontrol di tangan pemerintah yang terlegitimasi
(secara formal-yuridis), dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan,
87
Namun setelah komunitas politik tersusun dengan baik, maka keleluasaan untuk
menggunakan kekuasaan pun menjadi semakin terbatas, karena orang sekarang akan
selalu menanyakan dan mempersoalkan alasan dan dasar-dasar penggunaan kekuasaan
tersebut. Perburuan legitimasi (the quest for legitimacy) itu menunjukkan ciri-ciri
perkembangan ke arah perkembangan hukum yang otonom. Pada saat keadaan seperti
itu tercapai, maka dapat dikatakan telah terjadi pemisahan antara hukum dan politik.
Politik sekarang tidak lagi mendominasi hukum, dan hukum pun tidak lagi ditundukkan
di bawah politik. Lihat, Satjipto Rahardjo, Beberapa PemikiranOp. Cit., h. 78.
45
asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang sebenarnya, sebagaimana yang
sesungguhnya hidup di dalam kesadaran hukum masyarakat awam.
88
Oleh karena itu, tidak terlalu mengherankan apabila pada masa
karakter hukum sedemikian represif serta badan peradilan ditundukkan pada
politik kekuasaan, dan tatkala tujuan hukum semata-mata ketertiban, maka
muncul fenomena untuk memilih forum lain sebagai alternatif untuk tidak
menyelesaikan sengketa lewat pengadilan negeri. Kondisi tersebut kemudian
menjadi salah satu indikator bahwa pada kalangan pencari keadilan telah
muncul fenomena ketidaksediaan untuk menggunakan pengadilan dalam
rangka proses penyelesaian sengketa.
Namun demikian, seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial
yang terjadi dalam masyarakat, dewasa ini karakter produk hukum telah
bergeser ke arah perkembangan hukum yang otonom (autonomous law).
89
Hukum telah diupayakan untuk bebas dari politik, dalam arti terdapat
pemisahan kekuasaan, demikian pula tujuan hukum bukan lagi semata-mata
88
Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika
Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994, h. 247.
89
Law is institutionally autonomous to the extent that its rules are applied by
specialized institutions whose main task is adjudications. Thus, the distinction between
state and society is complemented by a contrast within the state itself among
legislation, administration, and adjudication. Lihat, Roberto M. Unger, Law in
Modern Society Toward a Criticism of Social Theory. London: The Free Press,
1976, h. 53. Hukum yang mandiri berarti hukum itu berlaku bagi pihak yang
mengeluarkan hukum itu maupun bagi pihak terhadap siapa hukum itu semula
ditujukan. Lihat juga, Charles Himawan, Ekonomi dan Hukum Rintangan
Potensial; dalam Kompas, 10-08-2001.
46
ketertiban, melainkan legitimasi. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri kalau
hingga saat ini masih dapat dijumpai sisa-sisa produk hukum yang masih
berkarakter represif, umpamanya masih didapati adanya undang-undang
yang tetap saja mencitrakan bahwa tujuan hukum itu semata-mata ketertiban.
Sebagai contoh, norma positif mengenai pengakuan dan pelaksanaan
putusan forum arbitrase internasional. Secara eksplisit norma itu masih
menentukan,Putusan Arbitrase Internasionalhanya dapat dilaksanakan
di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum.
90
Sementara itu kriteria dan makna mengenai ketertiban
umum itu sendiri sama sekali tidak pernah ditemukan penjelasannya secara
rinci. Mengingat tidak adanya pedoman yang jelas dan tegas mengenai
kriteria ketertiban umum, maka dalam rangka memperlancar mekanisme dan
proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional (international arbitration
award) agar persoalan ketertiban umum tidak selalu menjadi faktor
penghambat (barrier) untuk dieksekusinya putusan arbitrase internasional di
Indonesia, sesungguhnya hakim pada pengadilan yang ditunjuk sebagai
eksekutor putusan arbitrase tersebut dimungkinkan untuk melakukan
tindakan diskresi (discretion). Diskresi yang dimaksud bermakna sebagai:
...Kemerdekaan dan/atau otoritas/kewenangan untuk membuat
keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang dianggap tepat/sesuai
90
Pasal 66 huruf c UU No. 30/1999.
47
dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang dilakukan secara bijaksana
dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang
memungkinkan.
91
Sementara itu yang dimaksud dengan diskresi hakim (judicial
discretion) menurut Aharon Barak
92
adalah the power the law gives the
judge to choose among several alternatives, each of them being lawful or
to choose among a number of lawful option.
Oleh karena itu, ketika seorang hakim harus mempertimbangkan
dalam rangka memutus diberikan tidaknya eksekuatur terhadap suatu
putusan arbitrase internasional yang meminta untuk dieksekusi di Indonesia,
apakah putusan itu bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak berada
pada konteks kajian diskresi hakim (judicial discretion). Diskresi hakim
untuk kondisi semacam itu, menurut Barak tergolong pada tipe the
application of a given norm karena menyangkut the choice among a
number of alternative ways of applying a norm to a given set of facts.
93
91
Lihat, Erlyn Indarti, Diskresi Polisi. Semarang: BP-UNDIP, 2000, h. 12.
92
these options may refer to three matters. The first is the fact. Judicial discretion
chooses from among the set of facts those that it deems necessary for making a
decision in the conflict. The second area is the application of a given norm. Judicial
discretion selects from among the different methods of application that the norm
provides the one that it finds appropriate. The third area of discretion chooses from
among the normative possibilities the option that it deems appropriate. Lihat, Aharon
Barak, Judicial Discretion. New York: Yale University Press, 1989, h. 12-13.
93
Frequently, a legal norm gives the judge the power to choose among different
courses of action that are fixed in its framework. This grant of authority may be
explicit, as when the norm is actually phrased in terms of discretion. The grant may
also be implicit, such as when the norm refers to a standard (for example, negligence
48
Berdasarkan pemahaman terhadap hal di atas dan mengingat bahwa norma
hukum itu merupakan sesuatu yang abstrak, maka hanya hakim pengadilan
yang memiliki otoritas/kewenangan untuk menerjemahkan
94
atau
menafsirkan setiap norma hukum yang akan diterapkan pada kasus-kasus
yang dihadapkan padanya. Dalam konteks pelaksanaan putusan arbitrase
internasional di Indonesia, diskresi hakim muncul dalam hal-hal tatkala
Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pemberi eksekuatur terhadap
putusan arbitrase internasional harus mempertimbangkan penerapan norma
hukum berkenaan dengan ketertiban umum
95
sebagai salah satu syarat agar
putusan arbitrase internasional tersebut dapat dipertimbangkan untuk
dilaksanakan di Indonesia.
Masih berkaitan dengan konteks pembahasan teori tentang pilihan
forum penyelesaian sengketa, H.L.A. Hart mengemukakan teori berkenaan
dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa, yang didasarkan pada
pembedaan masyarakat secara dikotomis melalui struktur kehidupan
or reasonableness) or to a goal (such as the defense of the state, public order, the best
interests of the child). Ibid., h. 14.
94
Berkaitan dengan persoalan penafsiran atas norma-norma hukum, Justice Sussman
mengemukakan sebagaimana dikutip Barak di dalam Bukunya: The law is an abstract
norm and only the judgment of the court translates the rule of the legislature into an
obligatory act that is enforced on the public. The judge gives the law its real and
concrete form. Therefore one can say that the statute ultimately crystallizes in the
shape the judge gives it. Aharon Barak, Loc. Cit., h. 14.
95
Periksa Pasal 66 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
49
normatifnya. Kedua tatanan normatif masyarakat tersebut adalah: Primary
rules of obligation dan Secondary rules of obligation.
96
Masyarakat yang berada pada peringkat primary rules of obligation,
ditandai dengan kondisi seperti berikut: (1) komuniti kecil, (2) didasarkan
pada ikatan kekerabatan, (3) memiliki kepercayaan dan sentimen umum, dan
(4) berada di tengah-tengah lingkungan yang stabil. Dalam kondisi seperti
itu masyarakatnya tidak mengenal peraturan terperinci, hanya mengenal
standar tingkah laku, dan tidak ada diferensiasi dan spesialisasi badan-badan
penegak hukum. Penyelesaian sengketa pada masyarakat semacam ini relatif
masih sangat sederhana. Hal itu disebabkan masyarakatnya berupa
komunitas kecil yang didasarkan atas kekerabatan, sehingga mekanisme
kontrol sosial yang ada telah dapat menjalankan fungsinya secara efektif.
97
Sedangkan pada masyarakat dengan peringkat secondary rules of
obligation, masyarakatnya mempunyai kehidupan terbuka, luas, dan
kompleks. Kondisi tersebut menandai lahirnya dunia hukum dan
ditinggalkannya dunia pra hukum, bersamaan dengan munculnya tiga macam
kaidah, yaitu: (1) rules of recognition, (2) rules of change, dan (3) rules of
adjudication. Masing-masing kaidah (rules) tersebut memegang otoritas
96
H.L.A. Hart, The Concept of Law. London: Oxford University Press, 1972, h. 89-96.
Bdgk. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.
Bandung: Sinar Baru, TT, h. 43-45.
97
Esmi Warassih Pujirahayu, Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum; dalam
Masalah-Masalah Hukum No. 2 Tahun 1995, h. 20.
50
untuk menentukan apa yang merupakan hukum, bagaimana mengubahnya,
dan bagaimana menyelesaikan suatu sengketa. Berdasarkan teori yang
dikemukakan Hart di muka, maka masyarakat yang berada pada peringkat
secondary rules of obligation itu tergolong masyarakat yang modern.
98
Berkaitan dengan teori yang dikemukakan Hart di atas, pada pihak
lain, Daniel S. Lev
99
dalam tinjauannya mengenai kultur hukum di Indonesia,
memperhatikan bahwa cara-cara penyelesaian konflik mempunyai
karakteristiknya sendiri disebabkan adanya dukungan nilai-nilai tertentu.
Satuan masyarakat yang kecil-kecil yang di dalamnya hubungan tatap muka
lebih menonjol cenderung menekankan pada penyelesaian perselisihan
secara kekeluargaan (konsiliasi) dan kompromi (penyelesaian perselisihan
melalui jalan tengah). Sebaliknya, hubungan yang tidak akrab menjadikan
keputusan pihak ketiga dengan status resmi adalah lebih tepat. Padahal dalam
masyarakat manapun sebenarnya banyak sengketa diselesaikan sendiri oleh
orang yang bersangkutan dengan bantuan orang-orang yang ada di
sekitarnya.
100
Oleh karena itu, dalam suatu masyarakat ada berbagai pilihan
98
Adapun salah satu ciri penegakan hukum dalam masyarakat modern yang dianggap
menonjol adalah sifat birokratisnya, sebab penegakan hukum birokratis ini merupakan
jawaban masyarakat modern dalam menghadapi tantangan untuk dapat membuat
keputusan dengan tingkat rasionalitas maksimal dalam pengambilan keputusan serta
efisiensi kerja yang berjalan secara otomatis. Lihat dalam Satjipto Rahardjo, Hukum
dan Masyarakat., Bandung: Angkasa, 1981, h. 74.
99
Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan Perubahan.
Jakarta: LP3ES, 1990, h. 156.
100
T.O. Ihromi (ed), Antropologi dan HukumOp. Cit., h. 16.
51
yang tersedia bagi orang-orang yang mempunyai keluhan untuk
menyelesaikan masalahnya. Jadi, tidak benar semua sengketa dapat
diselesaikan dengan satu jenis pemecahan. Bahkan hasil penelitian
Gluckman yang meneliti tentang sistem hukum dari orang Lozi di Afrika
(kini menjadi Zambia), diketahui bahwa jenis-jenis relasi antara orang-orang
bersengketa banyak pengaruhnya pada cara penyelesaian sengketa yang
dipilih.
101
Demikian juga pada berbagai masyarakat adat di Indonesia, dapat
dijumpai beragam proses penyelesaian sengketa.
102
Di Minangkabau
misalnya, terdapat berbagai lembaga yang dapat menangani sengketa yang
mendapat kewenangannya dari adat atau suatu sistem aturan Minangkabau
yang normatif serta kebiasaan.
103
Jika terjadi sengketa-sengketa antara
101
Hubungan antara orang yang bersengketa bisa saja bersifat apa yang disebut simpleks
yaitu mereka yang mempunyai hanya satu jenis hubungan, hubungan majikan pekerja,
misalnya, atau bersifat multipleks, yaitu mempunyai hubungan yang beragam-ragam
misalnya dengan tetangga, pada saat yang sama juga berhubungan sebagai keluarga.
Bila terjadi sengketa maka hubungan yang simpleks, pemecahan yang tidak
memungkinkan lagi dilanjutkannya hubungan yang semula dapat saja ditempuh. Pada
hubungan yang simpleks, cara adjudikasi misalnya akan dapat ditempuh, karena tidak
membahayakan hubungan-hubungan sosial yang lebih luas. Sedangkan pada hubungan
yang multipleks pilihan yang pada umumnya akan ditempuh adalah pemecahan
masalah yang masih memungkinkan hubungan-hubungan yang multipleks itu berlanjut,
misalnya dengan negosiasi, dimana kompromi akan menonjol. Lihat, T.O. Ihromi,
Beberapa Catatan Mengenai Metode; dalam T.O. Ihromi (ed) Antropologi
Hukum Sebuah Bunga RampaiOp. Cit., h. 194-213 [212].
102
Di daerah Toraja, warga masyarakat biasanya pertama-tama mengajukan sengketa
kepada suatu dewan yang disebut hadat yang sejak dahulu telah berfungsi untuk
menyelesaikan sengketa. Lihat, T.O. Ihromi, Antropologi dan Op. Cit., h. 17-18.
103
Keebet von Benda-Beckmann, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat. Jakarta:
Grasindo, 2000, h. 64.
52
penduduk pada masyarakat di pedesaan, jarang sekali mereka membawa
masalah tersebut ke pengadilan negara untuk diselesaikan. Mereka yang
bersengketa dengan senang hati dan lebih suka membawanya ke forum-
forum atau lembaga-lembaga yang tersedia pada masyarakat di pedesaan
untuk diselesaikan secara damai.
104
Salah satu keuntungan penyelesaian
perselisihan oleh pihak-pihak yang berselisih itu sendiri ialah bahwa
perhatian pihak ketiga penyelesai perkara yang tidak berpihak (impersonal)
dapat diabaikan.
Sementara itu, di Jawa dan Bali kecenderungan memilih konsiliasi
adalah bersifat memaksa dan merupakan nilai yang merata dalam
masyarakat. Dengan perasaan relativisme yang mendalam atau yang menurut
istilah Anderson, tenggang rasa (tolerance)
105
gaya penyelesaian perselisihan
yang dianjurkan oleh nilai-nilai tersebut adalah gaya yang dalam istilah
hukum lebih memperhatikan prosedur daripada substansinya. Bahkan Lev
mengakui bahwa kecenderungan budaya untuk berkompromi bila timbul
perselisihan pribadi tetap kuat dan sama sekali tidak terbatas pada orang-
104
HMG. Ohorella & H.Aminuddin Salle, Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada
Masyarakat di Pedesaan Sulawesi Selatan; dalam Felix O. Soebagjo & Erman
Rajagukguk (eds), Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, h. 105-
120 [106].
105
Orang Jawa cenderung sangat hati-hati dalam hubungan pribadi, menaruh perhatian
kepada orang lain, diplomatis, menahan diri, dan hormat kepada kedudukan sosial.
Mereka berupaya keras menghindarkan perselisihan pribadi, dan bila hal terjadi,
menutupinya dengan cara yang halus dalam hubungan sosial, menunggu didapatkannya
penyelesaian yang paling tidak merugikan dan tidak mempermalukan. Lihat, Daniel S.
Lev, Hukum danOp. Cit., h. 158-159.
53
orang-orang desa saja. Nilai seperti itu meresap hampir pada semua lapisan
masyarakat Jawa.
106
Akan tetapi perubahan besar yang terjadi dalam sejarah peradaban
manusia, telah menyebabkan munculnya negara dan hukum modern sekitar
dua ratus tahun yang lalu. Akibatnya, hukum modern itulah yang kini
mendominasi dan dipakai di dunia termasuk Indonesia.
107
Hukum modern
memiliki ciri di antaranya bersifat tertulis, universal, bersifat teritorial,
formal, dan rasional. Pola penegakan hukum modern ini antara lain ditandai
dengan adanya diferensiasi dan spesialisasi fungsi-fungsi penegakan hukum,
yang pada gilirannya menyebabkan dibentuknya badan-badan khusus, seperti
kepolisian, pengadilan, dan sebagainya. Keadaan tersebut telah membawa
akibat semakin memudarnya nilai-nilai musyawarah yang diyakini
masyarakat untuk menyelesaikan sengketa.
108
Dalam kaitan itu Satjipto
Rahardjo menyatakan, Memang tak dapat disangkal bahwa musyawarah
untuk mufakat itu merupakan sebagian dari kekayaan kebudayaan kita.
Namun di dalam konteks masyarakat yang menjadi semakin terbuka dan
106
Daniel S. Lev, Hukum..Loc. Cit., h. 161.
107
Lihat Satjipto Rahardjo, Supremasi Hukum yang Benar; Kompas, 6 Juni 2002;
Hukum modern ini mengharuskan adanya struktur, format, dan prosedur yang keras
(rigid). Birokratisasi penegakan hukum sebagai ciri dari pola penegakan hukum
modern yang menonjol, menyebabkan penegakan hukum lalu merupakan jaringan
jabatan-jabatan yang cukup kompleks. Pola penegakan hukum birokratis ini merupakan
jawaban masyarakat modern terhadap tantangan untuk mengambil keputusan dengan
tingkat rasionalitas maksimal. Lihat pula, Satjipto Rahardjo, Masalah
PenegakanOp. Cit., h. 45-46.
108
Adi Sulistiyono, Mengembangkan ParadigmaOp. Cit., h. 19.
54
individualistis serta pengorganisasian masyarakat secara modern rasional,
maka pranata tersebut masih membutuhkan penyempurnaan secara
kelembagaan serta penghayatan oleh masyarakat Indonesia sendiri.
109
Sementara itu menurut Chambliss & Seidman,
110
terdapat dua unsur yang
merupakan faktor yang turut menentukan dalam hubungannya dengan
pranata yang dipakai oleh suatu masyarakat untuk menyelesaikan sengketa-
sengketa di antara para anggotanya, yaitu:
Pertama, tujuan yang hendak dicapai oleh penyelesaian sengketa
itu. Bila tujuan yang hendak dicapai adalah untuk merukunkan para pihak
sehingga mereka selanjutnya dapat hidup bersama kembali dengan baik
sesudah penyelesaian sengketa, maka penekanannya akan lebih diletakan
pada cara-cara mediasi dan kompromi. Sebaliknya, bila tujuannya untuk
melakukan penerapan peraturan, maka cara penyelesaian yang bersifat
birokratis akan lebih banyak dipakai.
Kedua, tingkat perlapisan yang terdapat di dalam masyarakat.
Semakin tinggi tingkat perlapisan yang terdapat di dalam masyarakat,
semakin besar pula perbedaan kepentingan dan nilai-nilai yang terdapat di
situ. Dalam keadaan demikian, maka lapisan atau golongan yang dominan
109
Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat..Op. Cit., h. 52.
110
William J. Chambliss & Robert B. Seidman, Law, Order and Power. Reading,
Massachusetts: Addison-Westley, 1971, h. 33-34, Bdgk. Satjipto Rahardjo, Hukum
dan MasyarakatLoc. Cit., h. 52-54.
55
akan mencoba untuk mempertahankan kelebihannya dengan cara
memaksakan berlakunya peraturan yang menjamin kedudukannya. Berbeda
dengan keadaan pada masyarakat sederhana, yang tingkat pemakaian
teknologi dan pembagian kerja di dalamnya masih rendah, kesepakatan nilai-
nilai masih mudah dicapai. Dalam keadaan ini, perukunan merupakan pola
penyelesaian sengketa yang cocok.
Dihubungkan dengan kedua unsur yang dikemukakan Chambliss &
Seidman di atas, dapat dikatakan bahwa dewasa ini masyarakat Indonesia
telah berada pada tingkat pelapisan yang tinggi dan lebih kompleks, sehingga
kecenderungannya ada pada penerapan peraturan-peraturan. Keadaan
tersebut menimbulkan perilaku masyarakat untuk melakukan gugat
menggugat melalui pengadilan dalam upaya penyelesaian sengketa.
Dikaji dari sudut perspektif organisasi, perilaku gugat menggugat
melalui pengadilan tersebut memiliki korelasi yang cukup signifikan dengan
persoalan beban pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pengadilan.
111
Akibatnya terjadi kelambanan proses peradilan, sehingga sejak perkara mulai
disidangkan sampai dengan terbitnya putusan hakim yang memiliki kekuatan
hukum tetap dapat berlangsung hingga enam tahun. Bahkan masalahnya
111
Dalam hubungan ini Lawrence M, Friedman mengatakan, bahwa sekalipun
persoalan yang dihadapi oleh pengadilan itu bukan merupakan sesuatu yang baru, akan
tetapi apabila jumlahnya terlalu banyak, maka lembaga pengadilan akan menghadapi
suatu krisis. Lihat Satjipto Rahardjo, Masalah PenegakanOp. Cit., h. 87-88.
56
tidak sampai di situ, selain lambat, putusan hakim juga sering dinilai
kontradiktif serta tidak jarang putusan hakim tidak dapat dieksekusi.
112
Berkenaan dengan hal di atas, Friedman
113
mengemukakan beberapa
pengaruh yang ditimbulkan akibat meningkatnya jumlah penduduk,
kemakmuran, serta industri-industri komersial terhadap pengadilan, sehingga
penanganan masalah di luar sidang pengadilan merupakan salah satu cara
yang dapat ditempuh tatkala pengadilan menghadapi krisis kepercayaan dan
krisis kewibawaan. Salah satu langkah yang disebutnya adalah
pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien di luar sistem
pengadilan yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian sengketa
melalui konsiliasi dan arbitrase memiliki sumber dukungan lain di samping
kecenderungan budaya. Sejak tahun 1983 upaya ke arah pengadaan
pengaturan mengenai arbitrase
114
telah dilakukan, meski baru tahun 1999
112
Sebagai contoh, kasus sengketa tanah Henoch Hebe Ohee melawan Gubernur Irian
Jaya sudah berlangsung sejak tahun 1991. Pengadilan Negeri Jayapura telah
memutuskan agar Gubernur Irian jaya membayar ganti rugi Rp 18,6 milyar kepada
Ohee. Akan tetapi sampai dengan tahun 1999 putusan hakim pada tingkat Peninjauan
Kembali (PK) belum bisa dieksekusi. Lihat Kelambanan Proses Peradilan
Dikeluhkan; dalam Kompas, 23 April 1999.
113
Lihat Satjipto Rahardjo, Masalah PenegakanOp. Cit., h. 88.
114
Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang
Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan, melalui Proyek Pengembangan
Hukum Ekonomi dan Penyempurnaan Sistem Pengadaan Proyek ELIPS, sejak tahun
1991 diantaranya dalam rangka melakukan pembaharuan hukum perseroan dan hukum
arbitrase dalam rangka mengganti peraturan yang tidak sesuai lagi dengan kemajuan
perekonomian masyarakat yang amat pesat. Oleh karena itu, kedua hukum yang sangat
dominan dalam menunjang perkembangan perekonomian dalam masyarakat dapat
diwujudkan.Lihat, Muhammad Abduh, Serangkaian Pembahasan bagi Pembaharuan
Hukum Ekonomi di Indonesia. (Kerjasama antara Kantor Menko Ekuin dan Wasbang
bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
57
dapat disahkan dan diundangkan.
115
Adapun tujuan utama dari Undang-
undang arbitrase tersebut adalah menyediakan payung hukum bagi
penyelesaian sengketa bisnis di luar forum pengadilan.
116
Namun untuk mengembangkan serta membangun model penyelesaian
sengketa di luar pengadilan melalui arbitrase jelas sekali bukan merupakan
proses yang mudah. Sejumlah faktor sangat signifikan berpengaruh terhadap
pengembangan arbitrase.
117
Oleh karena itu, walaupun diyakini penyelesaian
sengketa melalui arbitrase lebih menguntungkan, namun disebabkan faktor-
faktor yang berpengaruh itu, maka penyelesaian sengketa melalui arbitrase
belum dapat berkembang di Indonesia. Untuk itu perlu upaya-upaya
membangun kepercayaan serta minat masyarakat terutama kalangan
pengusaha agar bersedia menggunakan forum arbitrase dalam menyelesaikan
sengketa bisnis mereka. Membangun kepercayaan berarti mengubah perilaku
Yayasan Pusat Pengkajian Hukum); dalam Temu Karya Hukum Perusahaan dan
Arbitrase, Jakarta: 22-23 Januari 1991.
115
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, disahkan dan diundangkan pada tanggal 12 Agustus 1999.
116
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21,
Oktober-November 2002, h. 3.
117
(i) Penyelesaian sengketa lewat arbitrase harus didasarkan pada prinsip solusi menang-
menang (win-win solution), bukan menang kalah (win-loose), tanpa sikap tersebut
penyelesaian sengketa tidak berarti apa-apa, bahkan dapat gagal; (ii) Pihak yang kalah
harus mau secara sukarela untuk mengeksekusi putusan, jika tidak, eksekusi harus
melibatkan pengadilan; (iii) Pihak yang kalah pada arbitrase cenderung mengajukan
banding ke pengadilan, padahal putusan arbitrase bersifat mengikat dan final; (iv)
Pihak yang kalah juga sering meminta pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan; (v)
Sering pula para pihak yang sebelumnya telah menerima adanya klausula arbitrase di
dalam kontrak, tetapi ketika terjadi perselisihan, salah satu pihak mengajukan perkara
itu ke pengadilan; dan (vi) Pengadilan sendiri seringkali tidak konsisten menyikapi
58
manusia, dan lebih tinggi lagi mengubah kultur. Mengubah perilaku dan
kultur itu merupakan pekerjaan yang berat dan memerlukan waktu yang
panjang.
118
Hal tersebut di atas perlu mendapat perhatian, karena perilaku
masyarakat bisnis dalam menyelesaikan sengketa acapkali berada di luar
bingkai yang dikemukakan oleh sejumlah pakar.
119
Sementara para ahli
mengaitkan antara struktur dan pelapisan masyarakat dengan pola
penyelesaian sengketa di dalamnya. Dalam konteks semacam itu, mestinya
masyarakat bisnis menurut katagori Chambliss & Seidman, terletak pada
tingkat pelapisan sosial yang tinggi dan lebih kompleks. Sedangkan menurut
tesisnya Hart masyarakat bisnis sejatinya berada pada peringkat secondary
rules of obligation, yang ditandai dengan kehidupan masyarakat yang
terbuka, luas, dan kompleks. Pada kondisi struktur masyarakat semacam itu
semestinya kecenderungan penyelesaian sengketa berada pada penerapan
peraturan melalui lembaga pengadilan. Seperti halnya yang dikemukakan
Yehezkel Dror, bahwa tindakan-tindakan di dalam masyarakat yang semata-
mata bersifat instrumental seperti dalam kegiatan komersial, dengan nyata
sekali dapat menerima pengaruh dari peraturan-peraturan hukum yang baru
pilihan forum (jurisdiksi) arbitrase tersebut. Lihat, Editorial, Jurnal Hukum
BisnisOp. Cit., h. 4.
118
Satjipto Rahardjo, Mengubah Perilaku dan Kultur Polisi; dalam Kompas, 1-7-2002.
119
Lihat, Adi Sulistiyono, MengembangkanOp. Cit., h. 24.
59
dibandingkan dengan bidang-bidang kehidupan sosial yang erat
hubungannya dengan kepercayaan.
120
Akan tetapi pada aras praksis,
realitanya terbukti berbeda dengan teorinya. Masyarakat bisnis kadang-
kadang tidak menyukai mekanisme penyelesaian sengketa yang terlalu
formal, rasional, serta birokratis. Pada masyarakat bisnis yang tergolong
masyarakat modern, justru muncul kecenderungan terjadinya privatisasi
121
penyelesaian sengketa yang mengarah pada model win-win solution dan
bukan lagi menganut pola win-loose sebagaimana yang berlangsung pada
lembaga pengadilan.
Mekanisme penyelesaian sengketa pada masyarakat sebagaimana
disebutkan di muka bila dianalisis berdasarkan teori struktur masyarakat dari
Hart akan mendapatkan gambaran seperti berikut ini. Pada kondisi
masyarakat yang telah sampai pada tahap secondary rules of obligation
seperti sekarang ini, peranan pengadilan merupakan tumpuan utama, namun
demikian ketika pengadilan sedang mengalami krisis dan gagal menjalankan
tugas dan fungsinya, maka perangkat-perangkat yang ada pada tahapan
primary rules of obligation, seperti mediasi, konsiliasi, atau perangkat yang
120
Satjipto Rahardjo, Hukum dan MasyarakatOp. Cit., h. 121.
121
Lihat Priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya
terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dalam Jurnal Hukum
Bisnis, Volume 21, Oktober-November 2002, h. 5-15, [9].
60
lain akan muncul menjadi alternatif.
122
Sementara itu Gerald Turkel
123
membuat klasifikasi mengenai tipe-tipe penyelesaian sengketa secara
hierarki atau berjenjang (Hierarchy of Dispute Resolution). Penjenjangan
dibuat dari tipe penyelesaian sengketa yang paling rasional informal dan
tidak berdasarkan hukum (the most informal and nonlegally rational type of
dispute resolution) sampai dengan tipe yang paling rasional formal dan
berdasarkan hukum (the most formal and legally rational type). Hal tersebut
dapat disimak pada ragaan 2 berikut ini.
Ragaan 2
Hierarchy of Types of Dispute Resolution
124
Informal, Nonlegally Rational Formal, Legally Rational
Negotiation Mediation Arbitration Litigation
Sumber: Gerald Turkel, Law and Society...(1996:208)
Dalam menyelesaikan sengketa, para pihak dapat menggunakan tipe-
tipe penyelesaian sebagaimana disebutkan di atas mulai dari tipe yang paling
informal sampai dengan tipe yang paling formal rasional. Oleh karena itu,
apabila negosiasi tidak berhasil untuk menyelesaikan sengketa, para pihak
dapat melanjutkan pada mediasi. Apabila mediasi juga tidak berhasil, mereka
122
Lihat, Adi Sulistiyono, Op. Cit., h. 26.
123
Gerald Turkel, Law and Society: Critical Approaches. Needham Heights: A Simon &
Schuster Company, 1996, h. 208.
124
Ibid., h. 208.
61
dapat melanjutkan pada arbitrase. Akhirnya, apabila arbitrase pun tidak
berhasil, maka para pihak dapat melanjutkan kepada adjudikasi. Sebagai
tahap paling awal dalam hierarki penyelesaian sengketa, negosiasi dan
mediasi dilakukan dengan menggunakan metode dan interaksi yang
berlangsung secara informal, sukarela, serta didasarkan pada akal sehat.
Selanjutnya hierarki penyelesaian sengketa, bergerak ke arah arbitrase dan
kemudian litigasi dengan struktur yang lebih formal, baik peran maupun
prosedur, tidak berlangsung secara sukarela, dan lebih dibatasi oleh alasan-
alasan hukum serta alat-alat pembuktian. Oleh sebab itu, penyelesaian
sengketa menjadi lebih bersifat perlawanan, lebih terbuka kepada masyarakat
umum, dan semakin diatur oleh kaidah-kaidah hukum. Meskipun arbitrase
tergolong lebih formal bila dibandingkan dengan negosiasi dan mediasi,
namun Turkel menyatakan bahwa ...Arbitration does not have formal rules
of evidence and is not subject to technical legal rules. While the parties play
adversarial roles in the arbitration hearing, their communication is not
completely formal and controlled by legal procedure.
125
Berdasarkan seluruh uraian di muka, dapatlah dikemukakan bahwa
memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa komersial di luar
pengadilan ternyata memiliki landasan teoritis serta legitimasi konseptual
125
Gerald Turkel, Law and Society...Loc. Cit., h. 215
62
yang cukup memadai. Terlebih dalam kondisi pengadilan yang dirasakan
semakin tidak mampu mendengarkan persoalan bangsanya, sehingga
masyarakat kehilangan kepercayaan kepada lembaga pengadilan.
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Idealnya setiap sengketa dalam kehidupan masyarakat mendapatkan
penyelesaian yang adil dan bermartabat. Namun faktanya tidak selalu
demikian, karena tidak setiap upaya manusia untuk menyelesaikan sengketa
berakhir dengan hasil yang memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak.
Penelitian mengenai pilihan forum dalam menyelesaikan sengketa komersial
ini bertujuan antara lain untuk menemukan jawaban atas permasalahan
sebagaimana diuraikan di muka, sehingga diharapkan:
Pertama, dapat menjelaskan secara rinci dan mendalam mengenai
sejumlah alasan serta faktor-faktor yang mendorong munculnya fenomena
pilihan forum arbitrase dalam upaya menyelesaikan sengketa komersial,
khususnya pada kalangan bisnis. Dipahaminya alasan dan faktor pendorong
tersebut akan membantu untuk memahami tentang seberapa jauh putusan
forum arbitrase telah memuaskan rasa keadilan pihak-pihak yang
bersengketa di dalamnya.
63
Kedua, melalui penelitian ini diharapkan pula dapat menjelaskan
kepada publik, baik ilmuwan hukum, kaum praktisi, maupun masyarakat
luas lainnya bahwa di dalam lembaga pengadilan itu ada sejumlah faktor
internal yang sangat tidak menguntungkan pihak-pihak yang bersengketa di
dalamnya. Apalagi bila yang bersengketa itu kalangan masyarakat bisnis
yang sangat menghargai waktu, mengutamakan efisiensi, dan tidak
menghendaki sejumlah formalitas yang bertele-tele. Faktor-faktor internal
dimaksud mungkin sebagai akibat dari hukum acara yang sangat imperatif
sehingga tidak mungkin dihindari atau mungkin juga karena sikap mental
dari sumberdaya manusia personil lembaga peradilan yang sangat kurang
baik dan bermoral rendah.
Ketiga, memperoleh sejumlah informasi dari berbagai kepustakaan
sumber maupun norma-norma yang menjelaskan bahwa putusan forum
arbitrase bersifat final dan mengikat bagi para pihaknya karena tidak
mengenal upaya hukum banding maupun kasasi. Berdasarkan informasi
tersebut diharapkan di masa depan forum arbitrase dapat dikembangkan
menjadi forum khusus untuk menyelesaikan sengketa-sengketa komersial di
luar pengadilan. Akan tetapi dengan satu syarat, kepada forum arbitrase itu
harus diberikan kewenangan publik, sehingga dapat melakukan eksekusi
sendiri putusannya tanpa bantuan pengadilan negeri. Dengan demikian
64
forum arbitrase diharapkan akan mampu menjadi forum yang dapat
menegakkan keadilan secara substansial.
2. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini setidaknya memiliki dua kegunaan, yaitu (a)
kegunaan keilmuan atau kegunaan teoritis dan (b) kegunaan pragmatis atau
kegunaan praktis.
(a) Kegunaan keilmuan atau kegunaan teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan akan memperkaya konsep, metode,
maupun teori dalam studi hukum, khususnya bidang hukum penyelesaian
sengketa komersial.
Pilihan forum arbitrase juga diharapkan mampu menembus dinding
pembatas yang selama ini membentuk citra seakan-akan hanya lembaga
pengadilan tempat sengketa diselesaikan dan tempat keadilan dapat
diperoleh.
Hasil penelitian ini pun diharapkan menjadi salah satu sumber informasi
ilmiah yang dapat dijadikan bahan rujukan ketika pihak-pihak yang
bersengketa hendak melakukan pilihan forum atau pilihan yurisdiksi
untuk menyelesaikan sengketa mereka.
65
(b) Kegunaan pragmatis atau kegunaan praktis
Walaupun penelitian ini tidak dilakukan dalam rangka menyusun
kebijakan eksekutif maupun legislatif untuk menetapkan perundang-
undangan, namun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi
kontribusi terhadap upaya semua pihak yang menghendaki agar
penyelesaian sengketa komersial dilakukan oleh forum yang berbasis
kultural, sehingga pada gilirannya apa pun namanya forum tempat
sengketa komersial itu diselesaikan, diharapkan mampu menjawab
tuntututan kebutuhan masyarakat serta dapat memuaskan pihak-
pihak yang menggunakannya.
Untuk itu penelitian tentang pilihan forum arbitrase dalam
penyelesaian sengketa komersial diharapkan merupakan salah satu
upaya untuk menemukan model alternatif penyelesaian sengketa di
luar format yang telah ada namun model tersebut lebih memiliki basis
kultural dengan mengutamakan mekanisme perdamaian atau
musyawarah ketimbang sebuah pertentangan.
Dibukanya peluang untuk melakukan pilihan forum arbitrase bagi
sengketa-sengketa komersial, diharapkan akan mengurangi secara
signifikan beban menumpuknya perkara yang masuk untuk diputus
oleh lembaga peradilan. Bila beban perkara berkurang, pada
66
gilirannya para hakim akan lebih fokus untuk menangani sengketa-
sengketa lainnya secara cermat dan bertanggung jawab, sehingga
keluarannya berupa putusan yang berkualitas serta dapat memenuhi
rasa keadilan substansial untuk para pencarinya.
E. Pendekatan Studi
Kajian mengenai pilihan forum arbitrase ini berada pada ranah
sosiologi hukum (sociology of law). Di sini hukum bukan dikonsepkan
sebagai normatif (rules), melainkan sesuatu yang nomologik atau sebagai
regularities yang menekankan pada realitas yang terjadi di alam pengalaman
dan/atau sebagaimana yang tersimak di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini
hukum adalah perilaku-perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia yang
secara aktual telah dan/atau yang secara potensial akan terpola.
126
Oleh
karena pilihan forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa di luar
pengadilan negeri juga merupakan realitas sosial yang terkonstruksi dari
perilaku atau aksi dan interaksi pihak-pihak yang melakukannya, maka
pilihan forum merupakan realitas sosial yang terobservasi di alam
pengalaman indrawi yang empirik. Untuk itu maka kajian berikut ini hendak
126
Soetandyo Wignjosoebroto, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum
Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan Konseptualnya. Makalah.
Semarang, TT, h. 13.
67
menggunakan paradigma
127
konstruktivisme, karena realitas merupakan
konstruksi sosial. Melalui pengamatan langsung kepada pelaku sosial dalam
setting kehidupan sehari-hari yang alamiah, sehingga mampu memahami dan
menafsirkan bagaimana pelaku pilihan forum yang bersangkutan mengelola
kepentingan mereka.
Secara ontologis, paradigma ini menyatakan bahwa realitas
merupakan konstruksi sosial, ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi
mental, berdasarkan pengalaman sosial, dan tergantung pada orang yang
melakukannya.
128
Sebagai konsekuensi metodologis dari penetapan
paradigma tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Critical Legal Studies (CLS).
129
Adapun yang menjadi pertimbangan
sehingga menggunakan pendekatan CLS ini antara lain bertolak dari
pemahaman bahwa baik dalam pembentukan hukum positif (in abstracto)
maupun dalam penerapannya (in concreto), hukum adalah hasil interpretasi
127
Seperangkat keyakinan mendasar yang memandu tindakan-tindakan kita, baik
tindakan keseharian maupun dalam penyelidikan ilmiah. Sementara itu, paradigma
pencarian ilmu pengetahuan (discipline inquiry paradigm), yaitu suatu keyakinan dasar
yang digunakan berbagai kalangan untuk mencari kebenaran realitas menjadi suatu
ilmu atau disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Lihat, Agus Salim, Teori dan
Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya). Yogyakarta:
Tiara Wacana, 2001, h. 33-34.
128
Ibid., h. 41.
129
Teori kritis di bidang hukum tersebut sangat relevan dipakai untuk mengkritik praktik
hukum di Indonesia. Banyak terjadi keanehan-keanehan dalam yurisprudensi liberal di
Indonesia sekarang ini, yang oleh para pemimpin berhati nurani tinggi menyebutnya
sebagai tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Praktik hukum liberal di banyak
negara sekarang ini sudah meninggalkan filsafat keadilan, baik oleh para yurisnya, para
penuntut keadilannya, dan malahan telah digunakan secara semena-mena oleh banyak
68
yang tak pernah selesai dan amat berpotensi untuk mendistorsi
(menyimpangi) prosesnya sebagai logika formal.
130
Di samping itu karena
konteks kelahiran CLS itu sendiri memang datang dari pengalaman negara-
negara (dimana negara berperan secara minimal), tidak dominan seperti
Indonesia di masa Orde Baru. Oleh karena itu, tatkala penyelesaian sengketa
tidak lagi semata-mata merupakan monopoli institusi negara (baca:
pengadilan negeri) melainkan terbuka melalui pilihan forum di luar
pengadilan negeri, maka melalui kajian ini terbuka pula suatu opsi untuk
melakukan analisis kritis terhadap hukum dan proses penegakannya dengan
melihat relasi antara suatu doktrin hukum dengan realitas, dan kemudian
mengungkapkan kritiknya.
Oleh karena hukum dalam konteks pilihan forum ini dikonsepkan
sebagai perilaku-perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) dalam hal ini antara
para pihak atau para pelaku bisnis yang menghendaki sengketanya tidak
diputus oleh pengadilan negeri, maka teori yang digunakan dalam kajian ini
adalah interaksionisme simbolik (symbolic interactionism). Teori tersebut
memiliki pandangan bahwa kenyataan sosial mestinya didasarkan pada
definisi subjektif individu dan interpretasinya. Tindakan-tindakan individu
pihak. Periksa, H. Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Rake Sarasin, 2000, h. 206.
130
Ifdhal Kasim, Mempertimbangkan Critical Legal Studies dalam Kajian Hukum di
Indonesia; Jurnal Ilmu Sosial Transformatif WACANA, Edisi 6 Tahun II 2000, h.
21-33 (25-26).
69
serta pola-pola interaksinya dibimbing atau diarahkan oleh definisi bersama
yang serupa, yang dibangun melalui suatu interpretasi.
131
Interaksionisme
simbolik menunjuk pada sifat khas dari interaksi antar manusia.
Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling
mendefinisikan tindakannya. Interaksi antar individu, di antarai oleh
penggunaan simbol-simbol, interpretasi atau dengan saling berusaha untuk
saling memahami maksud dari tindakan masing-masing.
132
Interaksi
simbolik mengejar makna di balik yang sensual, mencari fenomena yang
lebih esensial daripada sekedar gejala. Karena itu landasan filosofik dari
interaksi simbolik adalah phenomenologi.
133
Penentuan pendekatan CLS dalam konteks pilihan forum arbitrase
untuk penyelesaian sengketa oleh kalangan pelaku bisnis, di samping karena
pilihan forum merupakan proses aplikasi hukum dalam kasus-kasus konkrit,
juga karena kajian hukum tidak lagi terbatas pada materi-materi primer dan
131
H.R. Riyadi Soeprapto, Interaksionisme SimbolikPerspektif Sosiologi Modern.
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, h. 88-89. Bdgk. Sudarwan Danim, Menjadi
Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Setia, 2002, h. 65-66.
132
George Ritzer, Sosiologi ... Op. Cit., h. 52.
133
Pada awal perkembangannya interaksi simbolik lebih menekankan studinya tentang
perilaku manusia pada hubungan interpersonal, bukan pada keseluruhan masyarakat
atau kelompok. Karena itu, sementara ahli menilai bahwa interaksi simbolik hanya
tepat diterapkan pada phenomena mikrososiologik atau pada perspektif psikologi sosial.
Pada perkembangan selanjutnya interaksi simbolik juga mengembangkan studi pada
perspektif sosiologiknya, sehingga kritik tersebut menjadi tidak tepat lagi, karena
pendekatan mikrososiologik juga telah diterapkan. Proposisi paling mendasar dari
interaksi simbolik adalah: perilaku dan interaksi manusia itu dapat diperbedakan
karena ditampilkan lewat simbol dan maknanya. Mencari makna dibalik yang
sensual menjadi penting dalam interaksi simbolik. Lihat, H. Noeng Muhadjir, Op.
Cit., h. 183-184.
70
sekunder hukum (seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan
pendapat ahli hukum) tetapi juga mencakup konteks sosial-politik, ideologi,
ekonomi, dan nilai-nilai yang berada di luarnya.
134
Menurut kalangan CLS,
hukum bukanlah ranah yang esoterik dari wacana moral, ekonomi, dan
politik pada umumnya. Oleh karena itu, melakukan analisis hukum tidak lagi
semata-mata bertumpu pada teks, tetapi harus diarahkan pada konteks
dimana hukum itu eksis, dan melihat hubungan kausal antara teks (doktrin
hukum) dengan realitas.
135
Bertolak dari teori pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini,
selanjutnya akan dilakukan analisis kausal mengenai doktrin dan institusi
legal tentang penyelesaian sengketa dalam hubungannya dengan penegakan
keadilan. Persoalan penegakan keadilan, adalah sesuatu yang sangat
mendasar. Oleh karena pengadilan negeri sebagai institusi formal milik
negara tempat sengketa diperiksa dan diputus, berindikasi tidak mampu
menjalankan amanah.
136
Akibatnya, segala proses yang berlangsung di
134
Ifdhal Kasim, Op. Cit., h. 27-29.
135
Ibid., h. 28. Oleh karena itu, dominasi pendidikan hukum dogmatik dalam pandangan
pemikir CLS (Studi Hukum Kritis) merupakan ganjalan utama yang harus dibongkar
karena telah membelenggu kreativitas individual dalam menghadapi persoalan-
persoalan khas negara di masa krisis, seperti Indonesia. Lihat, Anom Surya Putra,
Manifesto Hukum Kritis Teori Hukum Kritis, Dogmatika dan Praktik Hukum;
dalam Wacana Edisi 6 Tahun II 2000, h. 69-84.
136
Pengertian kata amanah disesuaikan dengan konteksnya dalam ayat-ayat Al Quran yang
memuat kata itu. Pertama, kata amanah dikaitkan dengan larangan menyembunyikan
kesaksian atau keharusan memberikan kesaksian yang benar; Kedua, kata amanah
dikaitkan dengan keadilan atau pelaksanaan hukum secara adil; Ketiga, kata amanah
dikaitkan dengan sifat khianat; Keempat, kata amanah dikaitkan dengan salah satu sifat
manusia yang mampu memelihara kemantapan (stabil) rohaninya, tidak berkeluh kesah
71
pengadilan dan keluarannya (output) berupa putusan dirasakan telah tidak
mampu memenuhi rasa keadilan terhadap para pencarinya.
Indikasi tersebut sekurang-kurangnya dapat dipahami melalui dua
faktor berikut ini: Pertama, putusan hakim pengadilan tidak mungkin dapat
memuaskan kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga selalu akan
mencerminkan ada pihak yang kalah dan pihak yang menang.
137
Kedua,
dalam realitas lembaga pengadilan tidak lagi semata-mata sebagai tempat
mencari keadilan tetapi juga menjadi ajang jual beli putusan, sehingga
putusan hakim seringkali sulit untuk diramalkan (unpredictable) dan tidak
mampu memberikan solusi secara adil pada pihak-pihak yang bersengketa
maupun mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
138
Terkait erat dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
yakni Critical Legal Studies (CLS), maka salah satu teori lainnya yang
digunakan dalam rangka penyelidikan tentang pilihan forum ini adalah teori
kritis. Dari sisi filsafat ilmu, teori kritis termasuk postpositivisme yang
bila ditimpa kesusahan, dan tidak melampaui batas ketika mendapat kesenangan;
Kelima, kata amanah dipahami dalam pengertian yang sangat luas, baik sebagai tugas
keagamaan maupun tugas kemanusiaan umumnya. Lihat Ensiklopedi Islam 1. Jakarta:
PT Ichtiar Baru, 1994, h. 133-134.
137
Memang ketika seorang hakim hendak menjatuhkan putusan, ia akan selalu berusaha
agar putusannya nanti seberapa mungkin dapat diterima oleh kedua belah pihak yang
berperkara. Namun hal itu tidak mungkin terjadi, kecuali dalam hal putusan itu
merupakan putusan perdamaian, dimana tidak ada pihak yang dimenangkan atau
dikalahkan. Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Op. Cit., h. 168-169.
Lihat pula, Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.
Bandung: Mandar Maju, 2000, h. 192.
138
Lihat Adi Sulistiyono, Mengembangkan Op. Cit., h. 20.
72
landasan filsafatnya sebagian phenomenologik dan sebagian lain realisme
metaphisik.
Patti Lather
139
mengemukakan bahwa pendekatan teori kritis termasuk
pendekatan yang mencari makna di balik empirik, dan menolak valuefree.
Pendekatan teori kritis mempunyai komitmen yang tinggi kepada tata sosial
yang lebih adil. Dua asumsi dasar yang menjadi landasannya, yaitu: pertama,
ilmu sosial bukan sekedar memahami ketidakadilan dalam distribusi
kekuasaan dan distribusi resources, melainkan berupaya untuk membantu
menciptakan kesamaan dan emansipasi dalam kehidupan; kedua, pendekatan
teori kritis memiliki keterikatan moral untuk mengkritik status quo dan
membangun masyarakat yang lebih adil.
Tatkala banyak pihak menjadikan paradigma pemikiran hukum
dinyatakan netral, sedangkan politik memanfaatkannya untuk kepentingan
dirinya. Teori hukum liberal menyatakan bahwa hukum itu menggunakan
prinsip keputusan objektif, sedangkan politik menggunakan prinsip
keputusan subjektif. Oleh karena itu, realitas yang terjadi dalam kehidupan di
Indonesia dewasa ini menunjukkan bahwa praktik hukum tidak dapat
dipisahkan dari praktik politik.
140
139
H. Noeng Muhadjir, Op. Cit., h. 196-197. Bdgk. Alan Hunt, Kritisi Hukum: Apa yang
Kritis dalam Studi Hukum Kritis? dalam Wacana Edisi 6Tahun II 2000, h. 34-53.
140
H. Noeng Muhadjir, Loc. Cit., h. 207.
73
Dari sudut pandang teori kritis, fenomena pilihan forum untuk
penyelesaian sengketa yang tumbuh dan berkembang pada komunitas
pengusaha, tentu dapat diberi makna sebagai salah satu wujud ketidaksediaan
(resistance) mereka terhadap lembaga pengadilan, karena dianggap praktik-
praktik hukum di dalamnya tidak sesuai lagi dengan rasa keadilan
masyarakat. Maka kajian mengenai fenomena pilihan forum dimaksud, antara
lain dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori kritis. Oleh karena
teori kritis mengkonstruk konsep keadilan setelah mencermati ketidakadilan
empirik.
141
Melalui mekanisme pilihan forum di luar pengadilan itulah
kemudian pihak-pihak berupaya untuk mencari dan menemukan keadilan
yang hilang. Namun demikian, masih perlu dikaji terus menerus, benarkah
upaya pencarian dan penegakan keadilan lewat pilihan forum itu dapat
direalisasikan di dalam kenyataan? Dalam konteks itu pula teori kritis
digunakan sebagai salah satu alat analisis hasil penelitian ini.
F. Metode Penelitian
1. Paradigma Penelitian dan Pendekatannya
Sebagaimana telah disebutkan di muka bahwa penelitian mengenai
pilihan forum arbitrase dalam sengketa komersial untuk penegakan keadilan
termasuk dalam ranah sosiologi hukum (sociology of law) yang
141
Ibid., h. 208.
74
mengkonsepkan hukum bukan sekali-kali normatif sebagai rules, melainkan
sesuatu yang nomologik sebagai regularities yang terjadi di alam empirik.
Oleh karena itu, untuk keperluan penelitian ini model paradigma
(paradigm)
142
yang digunakan adalah naturalistik dengan metode
kualitatif.
143
Ada sejumlah pertimbangan, sehingga metode kualitatif dipilih untuk
digunakan dalam penelitian ini di antaranya adalah: Pertama, studi tentang
pilihan forum
144
arbitrase sumber datanya adalah manusia atau orang-
142
Thomas Kuhn mendefinisikan paradigma (paradigm) sebagai: ...universally recognized
scientific achievements that for a time provide model problems and solutions to a
community of practitioners. Lihat, Thomas Kuhn, The Structure of Scientific
Revolutions. Chicago: The University of Chicago Press, 1970, h. viii. Sedangkan
Soetandyo Wignjosoebroto menyebutnya: Hasil pilihan yang tak perlu diperdebatkan
lagi kebenarannya inilah yang dalam wacana-wacana akademik disebut paradigma.
Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, Teori: Apakah itu? Sebuah Pengantar; Bahan
Kuliah Teori Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Tujuh
Belas Agustus 1945 Semarang, 2002, h. 2. Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo
mengemukakan: Paradigma adalah suatu konsep tentang hal-hal yang besar dan
mendasar. Seringkali paradigma dipakai sebagai sinonim dari model. Lihat, Satjipto
Rahardjo, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif Sejarah; Makalah
dalam Simposium Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia. PDIH Undip,
Semarang, 10 Februari 1998, h. 6. Sementara itu Liek Wilardjo mengatakan:
...Paradigma ialah model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan keilmuannya untuk
menentukan jenis-jenis persoalan yang perlu digarap, dan dengan metode apa serta
melalui prosedur yang bagaimana penggarapan itu harus dilakukan. Lihat, Liek
Wilardjo, Peran Paradigma dalam Perkembangan Ilmu; Makalah dalam
Simposium Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia. PDIH Undip, Semarang, 10
Februari 1998, h. 1. Masih ada diskusi lain tentang Paradigma, seperti dalam Erlyn
Indarti, Paradigma: Jati Diri Cendekia; Makalah Diskusi Ilmiah Program Doktor
Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang, 1 Desember 2000.
143
Peneliti kualitatif memilih metode-metode kualitatif karena metode-metode inilah yang
lebih mudah diadaptasikan dengan realitas yang beragam dan saling berinteraksi...
Lihat A. Chaedar Alwasilah, Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang dan
Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya, 2003, h. 105.
144
Yang dimaksud forum dalam konteks pilihan forum arbitrase, merujuk pada lembaga
atau badan, dan bukan pada kewenangannya. Oleh karena masalah kewenangan suatu
forum atau lembaga itu terkait erat dengan persoalan jurisdiksi (jurisdiction). Jadi,
75
orang,
145
baik orang-orang yang merupakan pihak materiil maupun pihak
formal dalam pilihan forum penyelesaian sengketa, maupun pihak-pihak lain
yang dianggap tepat untuk dijadikan sebagai informan
146
berkenaan dengan
studi yang dilakukan. Kedua, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa kajian
tentang pilihan forum untuk penegakan keadilan ini sangat relatif. Artinya,
setiap orang dapat melakukan pengamatan maupun penilaian terhadap
fenomena tersebut berdasarkan pandangannya masing-masing. Penelitian ini
tentu saja tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang mutlak. Oleh
karena, kebenaran yang dicari melalui penelitian kualitatif bukan kebenaran
mutlak. Kebenaran bergantung pada dunia realitas empirik dan konsensus
dalam masyarakat ilmuwan.
147
Ketiga, penelitian naturalistik lebih
mengutamakan dan menaruh perhatian kepada pandangan responden
(mengutamakan perspektif emic). Dengan demikian, peneliti dapat belajar
pilihan forum, berarti pilihan terhadap lembaga atau badan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam
rangka mengajukan tuntutan pengembalian hak terhadap pihak yang dianggap telah
melanggar dan/atau merugikan hak pihak yang mengajukan tuntutan.
145
Penelitian kualitatif pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan
hidupnya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka
tentang dunia sekitarnya. Periksa: S. Nasution, Metode Penelitian Op. Cit., h. 5. Di
samping itu ada alasan lain mengapa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.
Salah satu pertimbangannya adalah: karena penelitian yang dilakukan bertujuan untuk
memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan
sesuatu yang sulit untuk diketahui atau difahami. Lihat, Basrowi & Sukidin, Metode
Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro. Surabaya: Insan Cendekia, 2002, h. 8.
146
Dalam penelitian ini orang yang dijadikan sebagai informan adalah para arbiter, para
lawyer yang pernah menjadi kuasa hukum pihak-pihak materiil dalam pilihan forum
penyelesaian sengketa, atau bahkan pihak-pihak yang mengorganisasikan institusi atau
forum arbitrase.
147
S. Nasution, Metode Op. Cit., h. 6.
76
sangat banyak dari segenap pandangan maupun informasi yang diperoleh dari
responden dan/atau para informan di lapangan. Untuk mengkaji fenomena
pilihan forum penyelesaian sengketa, sejak semula telah disadari bahwa
pihak-pihak atau orang-orang yang menjadi subjek utama penelitian tidak
mudah untuk dijumpai, sehingga metode kualitatif inilah pilihan yang paling
mungkin untuk digunakan.
Disebabkan sifat dari subjek penelitian yang sedemikian, maka tidak
mungkin menentukan sampel secara ketat, karena tidak mudah pula untuk
menentukan populasi pelaku pilihan forum. Kondisi tersebut juga merupakan
alasan sehingga memilih metode kualitatif dalam kajian ini. Kebutuhan akan
informan sangat bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri yang diketahui
dan ditentukan oleh peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian.
Meskipun demikian, untuk menjamin keabsahan data yang terkumpul dari
kemungkinan terkontaminasi oleh faktor-faktor subjektivitas peneliti, dalam
penelitian naturalistik dikenal adanya perangkat pengawas yang dinamakan
triangulasi
148
atas data yang dikumpulkan.
148
Adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar
data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Denzin, membedakan empat macam teknik ini, yaitu: triangulasi dengan sumber,
metode, penyidik, dan teori. Periksa, Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.
Bandung, Remaja Karya, 1989, h. 195.
77
2. Unit Analisis
149
Unit analisis untuk penelitian tentang pilihan forum arbitrase dalam
penyelesaian sengketa komersial ini adalah orang-orang atau pihak-pihak
dari kalangan pelaku usaha, khususnya orang-orang yang dalam
menyelesaikan sengketa komersial mereka melalui forum lain di luar
pengadilan. Seperti telah disebutkan di muka bahwa pihak-pihak itu dapat
terdiri atas pihak materiil, yakni orang yang berkepentingan langsung dalam
perkara, atau pihak formal, yaitu para lawyer atau advokat yang menjadi
kuasa hukum pihak materiil, atau mungkin juga para informan yang
dianggap kompeten memberikan informasi yang dikumpulkan.
Adapun objek penelitian dalam kajian ini adalah pilihan forum
penyelesaian sengketa di luar badan pengadilan sebagai suatu interaksi yang
dilakukan oleh pihak-pihak tersebut. Sedangkan sumber data yang dijadikan
sebagai sasaran pengumpulan informasi penelitian, selain orang-orang atau
pihak-pihak pelaku pilihan forum (sepanjang memungkinkan untuk
dilakukan),
150
juga para arbiter, dan para informan lainnya yang dianggap
149
Adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian yang menjadi
sasaran pengumpulan data. Periksa, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998, h. 132-133.
150
Perlu diketahui bahwa orang-orang yang termasuk katagori pengusaha atau apa pun
profesinya yang pernah menyelesaikan sengketa lewat forum lain di luar pengadilan,
mereka tidak mau dihubungi. Alasan mereka, kami memilih forum di luar pengadilan
justeru untuk menghindarkan publisitas atas proses penyelesaian sengketa kami kepada
78
memiliki kompetensi untuk ditimba informasinya bagi pengumpulan data
dalam penelitian ini.
3. Pengumpulan Data
151
Sebagai instrumen utama dalam penelitian ini, penulis melakukan
pengumpulan informasi melalui wawancara dan diskusi mendalam (indepth
interview) dengan para responden dan informan yang penentuannya
dilakukan melalui sampel bertujuan (purposive sample). Metode
pengumpulan data semacam itu dilakukan mengingat sumber datanya adalah
human resources, yaitu subjek-subjek sasaran penelitian yang terdiri atas
pihak-pihak pelaku pilihan forum dan/atau orang-orang yang memiliki
kompetensi berkenaan dengan persoalan penyelesaian sengketa di luar
pengadilan.
Sementara itu penelusuran informasi dari sumber data yang bukan
manusia (non-human resources) juga dilakukan sekadar untuk melengkapi
informasi dari subjek-subjek sasaran penelitian. Sumber informasi yang
khalayak yang tidak berkepentingan yang pada akhirnya dapat mengganggu dan
merugikan eksistensi hubungan dengan mitra bisnis kami. Demikian informasi yang
diperoleh dari pihak-pihak yang dihubungi sebagai informan yang paling tidak pernah
mengetahui proses penyelesaian sengketa pihak-pihak dimaksud. Pada tahap ini,
peneliti mewawancarai informan (responden) yang menjadi sumber penelitian
(menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya). Lihat, Sanapiah
Faisal, Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999, h.
32-33.
151
Kerja lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dari para informan dilakukan
penulis sejak bulan April 2002 sampai dengan akhir Agustus 2002.
79
bukan manusia itu umumnya berupa bahan-bahan hukum primer yang terdiri
atas peraturan perundang-undangan dan putusan hakim (yurisprudensi).
4. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian naturalistik, data dikumpulkan oleh peneliti sendiri
secara pribadi. Oleh karena itu, pengumpulan informasi lebih banyak
bergantung pada diri peneliti sebagai alat pengumpul data.
152
Namun
demikian pada pelaksanaannya, tentu saja peneliti sangat memerlukan alat
bantu dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan. Alat bantu untuk
melakukan wawancara dengan para informan dibuat dalam bentuk protokol
wawancara. Alat tersebut dibuat dalam bentuk pertanyaan terbuka atau
tidak berstruktur. Model demikian sengaja dipilih dengan beberapa alasan
153
berikut ini: Pertama, penulis menyadari bahwa para responden atau
informan yang digali informasinya termasuk katagori orang penting;
Meski penulis tidak dapat menemukan penjelasan lebih jauh tentang makna
orang penting tersebut, namun dalam pemahaman penulis setiap subjek
sasaran penelitian sebagai informan seyogianya diperlakukan sebagai orang
penting. Satu dan lain hal karena di samping sifat penelitian kualitatif ini
152
Lexy J. Moleong, Metodologi..Op. Cit., h. 21. Bdgk. S. Nasution, MetodeOp. Cit.,
h. 54.
153
Lexy J. Moleong, Loc. Cit., h. 152.
80
yang lebih mengutamakan perspektif emic, juga setiap responden yang
terpilih tentu dianggap paling memiliki pengetahuan, mendalami situasi, dan
mengetahui informasi yang diperlukan oleh peneliti; Kedua, sebagai
peneliti, penulis hendak menanyakan perihal pilihan forum arbitrase sebagai
forum tempat penyelesaian sengketa secara lebih mendalam kepada seorang
informan yang dianggap sangat kompeten untuk mengungkapkan hal
tersebut; Ketiga, penulis amat tertarik untuk mengungkapkan maksud atau
penjelasan dari para responden yang melakukan pilihan forum di luar
pengadilan dalam rangka menyelesaikan sengketa mereka.
Sebagai instrumen utama, peneliti merupakan sentral dari seluruh
aktivitas penelitian. Di samping sebagai perencana, sekaligus juga pelaksana
pengumpulan data atau informasi, yang melakukan analisis data, penafsir
data, dan pada akhirnya sebagai pelapor hasil penelitian. Oleh karena itu,
peneliti berusaha lebih peka serta sedapat mungkin menyesuaikan diri untuk
mampu berinteraksi dengan sumber data. Untuk itu, peneliti berupaya agar
lebih mampu memahami konteks data secara holistik, sehingga dapat
menemukan hal-hal baru.
81
5. Analisis Data
Sebagaimana diketahui bahwa data yang dikumpulkan melalui aneka
macam cara dalam penelitian kualitatif (observasi, wawancara, intisari
dokumen, pita rekaman) berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.
154
Oleh karena itu, analisis data kualitatif juga tetap menggunakan kata-kata,
yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas. Menurut Matthew B.
Miles & A. Michael Huberman, yang dimaksud dengan analisis itu terdiri
atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu: reduksi data,
penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi). Ketiga alur kegiatan
tersebut dapat disimak dalam ragaan berikut ini:
Ragaan 3
Komponen-komponen Analisis Data: Model Interaktif
155
154
Lihat, Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif
(Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press, 1992, h. 15-21.
155
Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Loc Cit., h. 20.
Pengumpulan
data
Reduksi
data
Penyajian
data
Simpulan-simpulan:
Penarikan/Verifikasi
82
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang
muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan ini berlangsung
terus menerus selama kegiatan penelitian kualitatif ini berlangsung. Reduksi
data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,
mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan
cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan finalnya dapat ditarik dan
diverifikasi.
Penyajian data, yang dimaksud adalah suatu penyajian sebagai
sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya
penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Melalui penyajian itulah kita
akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan
lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas
pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
Menarik simpulan/verifikasi, kegiatan ketiga yang penting adalah
menarik simpulan dan verifikasi. Penarikan simpulan merupakan sebagian
dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Simpulan-simpulan juga
diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari
data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni
yang merupakan validitasnya. Jika tidak demikian, maka akan merupakan
sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas kebenaran dan kegunaannya.
83
6. Validitas Data
Dalam mengumpulkan informasi berkenaan dengan pilihan forum
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang subjek-subjeknya terdiri atas
pihak-pihak eksklusif para pelaku bisnis, penulis menyadari sepenuhnya
bahwa metode kualitatif memiliki sejumlah kelemahan seperti halnya juga
metode penelitian yang lainnya. Di antara kelemahan yang acapkali
dipersoalkan dalam penelitian kualitatif terutama berkenaan dengan masalah-
masalah: validitas
156
(kesahihan), reliabilitas
157
(keandalan), dan
objektivitas
158
dari data yang berhasil dikumpulkan dan diperoleh. Ketiga
masalah tersebut seringkali diusik persoalan keterpenuhannya. Akibatnya
hasil penelitian kualitatif tidak dipandang ilmiah oleh banyak ilmuwan
156
Validitas, berkaitan dengan ukuran bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai
dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan. S. Nasution, Op. Cit., h.
105. Validitas itu memang lebih abstrak dan lebih sulit diukur daripada reliabilitas.
Oleh karena itu, untuk mengukur validitas suatu karya ilmiah harus dilakukan dengan
memperhatikan beberapa jenis validitas, yaitu: (i) validitas isi (content validity), (ii)
validitas konstrak (construct validity), (iii) validitas antar budaya (cross-cultural
validity), (iv) validitas internal dan eksternal (internal and external validity), (v)
validitas prediktif (predictive validity), dan (vi) validitas muka (face validity).
Periksa, Peter Hagul, Reliabilitas dan Validitas; dalam Masri Singarimbun &
Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, 1982, h. 87-102 [96].
157
Sedangkan reliabilitas berkenaan dengan masalah konsistensi atau ketaatasasan
pengukuran dan ukuran yang digunakan. Artinya, apakah penelitian itu dapat diulangi
atau direplikasi oleh peneliti lain dan menemukan hasil yang sama bila ia
menggunakan metode yang sama, sehingga dapat dipercaya. S. Nasution, Op. Cit., h.
108. Bdgk. Lexy J. Moleong, Op. Cit., h. 188.
158
Masalah objektivitas inilah tampaknya yang paling krusial di dalam penelitian
kualitatif. Terdapat anggapan bahwa data hanya dapat dianggap objektif bila diperoleh
berdasarkan kesamaan hasil pengamatan sejumlah peneliti dan dapat dicek
kebenarannya oleh orang lain. S. Nasution, Loc. Cit., h. 110.
84
sebagai karya ilmiah karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat
159
tersebut di atas.
Meskipun demikian, secara metodologis sesungguhnya untuk peneliti
dalam penelitian kualitatif telah disediakan piranti teoritis yang dapat
digunakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan tersebut. Peneliti dipandu
untuk mengikuti serangkaian teknik metodologis untuk memeriksa keabsahan
data,
160
sehingga informasi yang terkumpul pada penelitian kualitatif dapat
dibuktikan telah memenuhi syarat-syarat pokok dalam penilaian ilmiah.
Selama proses pengumpulan informasi dari sumber-sumber yang
ditentukan sebagai subjek sasaran penelitian, setidaknya beberapa teknik
telah dilakukan untuk memeriksa keabsahan data yang terkumpul. Satu di
antara teknik yang dilakukan adalah triangulasi. Triangulasi dengan sumber,
berupa membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan dengan persoalan pilihan forum, selalu penulis lakukan segera
setelah data wawancara diperoleh. Kemudian triangulasi dengan metode,
juga dilakukan dengan jalan mengecek derajat kepercayaan beberapa sumber
data dengan metode yang sama. Demikian pula triangulasi dengan
memanfaatkan peneliti, selama pengumpulan informasi dari sumbernya juga
159
Periksa S. Nasution, Op. Cit., h. 105.
160
Setidaknya terdapat 10 (sepuluh) jenis teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat
dilakukan peneliti, yaitu sebagai berikut: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan
pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, (6)
85
penulis lakukan dengan jalan meminta bantuan teman penulis (asisten
penulis) di fakultas hukum, ia diminta bantuannya untuk melakukan
wawancara dengan materi yang serupa kepada para informan yang telah
pernah diwawancarai penulis sebelumnya.
Penggunaan teknik pemeriksaan sejawat melalui diskusi atau bertukar
pikiran dilakukan penulis secara berkala selama pengumpulan informasi.
Diskusi, tukar pikiran, dan sejenisnya itu dilakukan dengan rekan-rekan
sesama pengajar fakultas hukum, bahkan dengan sesama peserta program
meski berbeda kajian. Cara ini dilakukan terutama untuk memperoleh
koreksi, kritik, pertanyaan atau masukan dari rekan-rekan sesama pengkaji
hukum yang penulis manfaatkan untuk melengkapi informasi yang telah
terhimpun. Di samping itu semua, penulis juga melengkapi catatan lapangan
pengumpulan informasi dari para subjek sasaran penelitian dengan rekaman
wawancara
161
yang dilakukan dalam bentuk cassette recorder (rekaman
dalam pita kaset) yang setiap saat dapat penulis putar untuk didengarkan
kembali.
kajian kasus negatif, (7) pengecekan anggota, (8) uraian rinci, (9) audit
kebergantungan, (10) audit kepastian; Lihat Lexy J. Moleong, Op. Cit., h. 192-206.
161
Mendekati responden dan membina hubungan baik dengan responden untuk
melaksanakan wawancara tidaklah mudah. Apabila dilihat secara sepintas, menemui
seseorang untuk menanyakan tentang berbagai topik, nampaknya tidak sulit. Namun
dalam kenyataannya komunikasi itu tidaklah sederhana. Komunikasi dalam wawancara
sangat rumit, karena di sini berinteraksi dua kepribadian yaitu pewawancara dan
responden. Karena itu dalam melaksanakan tugas wawancara, pewawancara harus
selalu sadar bahwa dialah yang memerlukan dan bukan sebaliknya. Lihat, Irawati
86
7. Sekitar Pengalaman Lapangan
Lebih kurang sebelas bulan sejak dilakukannya penelitian
pendahuluan, penulis ke sana ke mari dalam rangka mengumpulkan
sejumlah informasi berkaitan dengan masalah pilihan forum arbitrase
sebagai forum penyelesaian sengketa. Kesulitan dan kemudahan penulis
jumpai silih berganti selama pengumpulan informasi di berbagai tempat dan
dari berbagai orang yang menjadi sasaran penelitian. Suatu ketika penulis
menghadapi persoalan dalam pengumpulan informasi yang ternyata tidak
terlalu mudah untuk mengatasinya. Saat itu, tatkala penulis mengetahui
bahwa ternyata pihak-pihak materiil
162
dalam penyelesaian sengketa melalui
forum arbitrase sama sekali tidak mungkin dapat ditemui untuk dijadikan
sebagai informan utama. Alasannya karena mereka tidak ingin diketahui
siapa pun, kecuali pihak-pihak yang menjadi kuasa hukumnya dan para ahli
yang diangkat sebagai panel wasit (arbiter) yang ditunjuk untuk menjadi
pemutus sengketa mereka.
Singarimbun, Teknik Wawancara; dalam Masri Singarimbun et al., Metode
Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES, 1982, h. [145-166] 152-153.
162
Pihak materiil dalam perkara adalah orang yang mempunyai kepentingan langsung di
dalam perkara bersangkutan, baik sebagai claimant (orang yang membuat
tuntutan/penggugat) maupun sebagai respondent (orang yang dijadikan sebagai
tertuntut/tergugat). Periksa Sudikno Mertokusumo, Hukum AcaraOp. Cit., h. 47-
48. Bdgk. M. Yahya Harahap, Arbitrase. Jakarta: Sinar Grafika, 2001, h. 132-133.
87
Atas dasar alasan tidak ingin diketahui siapa pun di antaranya para
pihak materiil melakukan pilihan forum di luar pengadilan negeri untuk
menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Tampaknya dengan cara itu
pula pihak-pihak materiil tersebut dapat berlindung di balik alasan
confidential untuk tidak diketahui atau dihubungi siapa pun dan bagi
kepentingan apa pun, termasuk untuk kepentingan pengumpulan informasi
penelitian. Akan tetapi, untuk tidak kehilangan kesempatan dalam
memperoleh informasi yang sedang ditelusuri, penulis mencari akal dengan
jalan mencari sumber informasi atau subjek-subjek sasaran penelitian
penggantinya. Adapun pihak-pihak yang paling mungkin untuk dipilih dan
dapat dijadikan pengganti sebagai sasaran penelitian dalam mengumpulkan
informasi tentang pilihan forum arbitrase sebagai tempat penyelesaian
sengketa di luar pengadilan adalah pihak formal, yaitu para lawyer atau
advokat yang pernah menjadi kuasa hukum pihak-pihak materiil, dan juga
para ahli yang pernah menjadi panel wasit atau arbiter yang pernah
menengahi serta memutuskan sengketa pihak-pihak dimaksud.
Dalam praktiknya upaya itu pun tidak terlalu mudah, karena tuntutan
kode etik serta kepentingan untuk melindungi kerahasiaan dan hak-hak
kliennya, pihak-pihak formal yang dipilih sebagai informan itu pun tidak
dapat bahkan tidak diperkenankan untuk menyampaikan informasi yang
sifatnya terlalu subjektif mengenai pihak-pihak materiil yang pernah
88
diwakilinya. Sejauh pertanyaan penelitian yang diajukan sifatnya umum
berkenaan dengan pilihan forum penyelesaian sengketa, pada prinsipnya
para informan tidak keberatan untuk digali informasinya.
Demikian pula para informan dari kalangan ahli yang profesinya
sebagai wasit atau arbiter. Pada dasarnya mereka tidak berkeberatan
menjadi subjek sasaran pengumpulan informasi penelitian, sejauh kepada
mereka tidak diajukan pertanyaan mengenai kasus yang sedang atau pernah
ditanganinya dan pihak-pihak yang pernah atau sedang bersengketa. Untuk
alasan tersebut, penulis memahami posisi mereka para informan, sehingga
arah pertanyaan penelitian juga tidak bersifat subjektif tentang pihak-pihak
maupun substansi sengketanya.
Kepada penulis, para informan yang terpilih dan telah menjadi
sumber informasi dalam penelitian ini, berpesan dengan sangat, sebaiknya
identitas mereka tidak dimunculkan dalam penulisan laporan penelitian,
apalagi di dalam penulisan disertasi. Untuk hal tersebut, sepenuhnya penulis
dapat memahami. Di samping itu juga penulis tidak melihat urgensinya,
untuk menghadirkan identitas para informan secara jelas. Oleh karena bukan
itu pula yang dimaksud dengan paparan tentang keadaan sosial (social
setting) dari pihak-pihak pelaku pilihan forum.
89
G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan
Penulisan Disertasi ini direncanakan terdiri atas enam bab. Sebagai
satu kesatuan gagasan pemikiran, setiap bab diupayakan untuk memiliki
keterhubungan satu sama lain, sehingga secara keseluruhan muatan disertasi
ini akan merupakan satu jalinan makna yang diupayakan untuk menjadi satu
hasil kerja yang komprehensif dan utuh.
Bab I, sebagaimana lazimnya bab ini merupakan maket dari suatu
disertasi. Di dalamnya diawali oleh paparan mengenai ide dasar yang melatar
belakangi munculnya permasalahan sehingga mendorong untuk mengadakan
penelitian dalam rangka melakukan penulisan disertasi ini. Seperti telah
dipahami banyak pihak bahwa praktik penyelesaian sengketa komersial
melalui pengadilan negeri di Indonesia dirasakan sangat tidak
menguntungkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Banyak faktor yang
menjadi penyebab mengapa keadaannya seperti itu. Beberapa diantaranya: (i)
Untuk menyelesaikan sengketa melalui lembaga pengadilan harus mengikuti
berbagai formalitas beracara yang tidak jarang menyulitkan para pihak yang
bersengketa. (ii) Pemeriksaan perkara pada lembaga pengadilan
dimungkinkan upaya hukum kepada tingkat peradilan yang lebih tinggi,
sehingga untuk mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum
pasti (kracht van gewijsde) para pihak dapat menghabiskan waktu bertahun-
90
tahun. (iii) Akibat berlarut-larutnya penyelesaian sengketa semacam itu,
upaya para pihak untuk memperoleh keadilan mungkin saja terbengkalai. (iv)
Disinyalir banyak pihak bahwa lembaga peradilan di Indonesia dewasa ini
semakin tidak amanah. Oleh karena itu, bagi masyarakat yang dalam
interaksi sosialnya berpotensi memiliki konflik namun tidak memiliki cukup
waktu untuk mengikuti liku-liku beracara pada lembaga pengadilan,
kemudian menciptakan budaya penyelesaian sengketa lewat pilihan forum.
Budaya penyelesaian sengketa semacam itu kini semakin terbuka peluang
maupun kesempatan untuk menggunakannya. Keadaan itu antara lain telah
menginspirasi untuk mengangkat tema utama disertasi Pilihan Forum
Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan.
Sebagaimana telah diutarakan, paparan awal pada bab sat ini tentang Latar
Belakang Permasalahan, menyajikan uraian tentang fakta dan fenomena
yang diasumsikan merupakan latar belakang munculnya budaya melakukan
pilihan forum arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa, khususnya
sengketa-sengketa komersial. Disertasi ini mencoba mengangkat tiga
permasalahan. Ketiganya terkait erat satu sama lain dan selanjutnya ketiga
permasalahan tersebut menjadi pengusung permasalahan utama. Adapun
permasalahan utamanya adalah: Mungkinkah forum arbitrase di masa depan
dapat dikembangkan sebagai salah satu forum khusus untuk menyelesaikan
sengketa-sengketa komersial di luar pengadilan negeri yang memiliki
91
kewenangan publik untuk mengeksekusi putusannya, sehingga putusan
arbitrase lebih mencerminkan penegakan keadilan substansial yang
bermartabat? Untuk menghindari keleliruan para pembaca disertasi dalam
memahami pengertian dari sejumlah istilah yang muncul dalam penulisan
disertasi ini, di dalam bab satu ini pun penulis berusaha memberikan
penjelasan atas sejumlah istilah. Sebagai contoh, istilah forum, arbitrase
(arbitration), komersial, negosiasi, kontrak internasional,
international disputes, pengadilan (badan peradilan), risiko, pihak
materiil, titel eksekutorial, exequatur, budaya hukum, diskresi
(discretion). Penjelasan atas sejumlah istilah tersebut memang tidak
dilakukan dalam satu sub bab tersendiri, melainkan dibuat pada catatan kaki.
Hal itu dilakukan atas dasar pertimbangan praktis ketika penulisan dan juga
membantu mempermudah pembaca ketika menjumpai istilah tersebut dapat
langsung menemukan uraiannya di dalam catatan kaki tersebut. Beberapa
teori yang digunakan, baik teori hukum maupun teori-teori sosial yang
dipinjam dalam rangka melakukan analisis atas temuan informasi hasil
penelitian disajikan di dalam bab satu ini. Pada bagian awal ini pula
dipaparkan mengenai tujuan serta kegunaan penelitian meski uraian tentang
hal ini dirasakan penulis sebagai terlalu ideal. Namun demikian, tanpa
bermaksud pesimis, penulis masih tetap memiliki harapan kiranya hasil-hasil
penelitian dalam rangka menyusun disertasi ini, kelak dapat bermanfaat dan
92
dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang membawa kemaslahatan, khususnya
dalam pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum, terutama hukum
penyelesaian sengketa di Indonesia. Uraian mengenai metode penelitian
menyajikan paradigma, pendekatan studi dan metode yang digunakan dalam
melakukan pengumpulan informasi dari para informan sebagai subjek
sasaran penelitian. Menggunakan paradigma naturalistik dengan metode
kualitatifnya didasarkan pada pertimbangan sumber data atau informasi yang
dikumpulkan adalah sejumlah orang (manusia). Orang-orang itulah yang
digali informasi dan pandangannya, sehingga penulis sebagai peneliti
sepenuhnya mengutamakan dan menaruh perhatian terhadap apa pun
pandangan dan informasi yang diberikan oleh informan di lapangan. Atas
pertimbangan serta alasan untuk melakukan kritik terhadap praktik hukum di
Indonesia yang telah menunjukkan banyak keanehan-keanehan, sebagai tidak
sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, maka pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah Critical Legal Studies (CLS).
Bab II, berisi paparan mengenai informasi yang dapat dijadikan titik
tolak dalam melakukan pembahasan serta analisis atas sejumlah masalah
dalam disertasi ini yang akan diuraikan pada bab-bab berikutnya. Bab ini
diberi judul Pilihan Forum Arbitrase Sebagai Tempat Penyelesaian
Sengketa Berkeadilan. Uraiannya diawali dengan sub bab mengenai
Tujuan Pilihan Forum dan Keadilan. Menyadari sepenuhnya bahwa untuk
93
memahami tujuan pihak-pihak pelaku pilihan forum memang tidak mudah,
karena hampir sulit ditemukan dalam literatur hukum mana pun yang secara
eksplisit menguraikan hal tersebut. Untuk itu upaya yang dilakukan dalam
rangka menemukan jawaban tentang apa yang menjadi tujuan pihak-pihak
dalam melakukan pilihan forum antara lain dilakukan melalui penelusuran
atas sejumlah asumsi berdasarkan beberapa indikator berikut ini: (i) Para
pihak yang bersengketa, terutama pelaku bisnis menghendaki bentuk
penyelesaian sengketa yang berlangsung cepat, akurat, namun putusannya
lebih mencermikan rasa keadilan. Ekspektansi mengenai hal tersebut sulit
dapat diperoleh dari lembaga pengadilan; (ii) Para pelaku bisnis yang
menjadi pihak dalam sengketa menghendaki agar penyelesaian sengketanya
tidak menghambat atau menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis mereka.
Oleh karena itu, para pelaku bisnis sangat tidak menyukai proses
penyelesaian sengketa yang berlarut-larut; dan (iii) Pelaku bisnis juga tidak
menghendaki bila putusan tentang penyelesaian sengketa dipublikasikan
secara luas kepada masyarakat. Oleh karena putusan penyelesaian sengketa
semacam itu sangat tidak menguntungkan bagi kelangsungan bisnis diantara
mereka. Putusan yang adil dan bermartabat dari setiap penyelesaian
sengketa merupakan harapan yang ditunggu setiap orang. Smith
menyatakan, keadilan adalah syarat niscaya bagi keberadaan dan
kelangsungan hidup masyarakat mana pun. Oleh karena itu, keadilan adalah
94
keutamaan moral yang utama dan niscaya, dalam pengertian bahwa
masyarakat tidak mungkin ada tanpa keadilan. Mengamati fenomena
masyarakat pencari keadilan yang bergelut dengan persoalan penyelesaian
sengketa memang menarik dan senantiasa aktual untuk dikaji. Namun yang
tak kalah menariknya adalah mengamati fenomena lembaga pengadilan
yang dirasakan semakin tidak dapat berbuat banyak untuk mendatangkan
keadilan kepada masyarakat (bringing justice to the people). Apabila
kondisi sedemikian itu terus berlangsung, dikhawatirkan pengadilan secara
perlahan-lahan menjadi lembaga yang disfungsional, yang akan berdampak
cukup luas. Dampak serius akan dirasakan apabila para investor asing
sama sekali enggan masuk ke Indonesia karena kondisi pengadilan tidak
lebih baik. Demikian pula para pengusaha domestik yang berpotensi
memiliki konflik sudah enggan untuk berperkara di pengadilan.
Keprihatinan terhadap kondisi pengadilan yang telah dianggap tidak
reliable and credible itu tidak hanya dirasakan oleh para pengusaha, baik
asing maupun domestik, namun masyarakat luas juga sudah mulai banyak
kehilangan kepercayaan kepada pengadilan Indonesia. Tidak mengherankan
apabila kemudian rakyat pencari keadilan beralih perhatian untuk
menyelesaikan konflik mereka tidak melalui pengadilan akan tetapi
memilihan forum selain pengadilan. Sub bab selanjutnya berjudul
Konsekuensi Pilihan Forum Arbitrase terhadap Kompetensi Hakim
95
Pengadilan Negeri. Di sini disajikan uraian yang menggambarkan bahwa
pilihan forum ternyata membawa akibat terciptanya kompetensi pada forum
yang dipilih. Artinya apabila forum arbitrase yang dipilih sebagai tempat
sengketa diselesaikan, maka sengketa yang timbul akan ditarik keluar dari
yurisdiksi hakim pengadilan negeri dan akan menjadi kewenangan forum
arbitrase untuk memeriksa dan memutusnya. Sebagai konsekuensinya
pengadilan negeri menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa
bersangkutan. Akhirnya, sebagai penutup uraian bab dua disajikan sub bab
yang memaparkan mengenai Pilihan Forum Arbitrase sebagai Fenomena
Penyelesaian Sengketa. Fakta menunjukkan bahwa lambannya proses
penyelesaian sengketa melalui pengadilan telah mendorong para pihak yang
berpotensi memiliki konflik dari interaksi sosialnya, untuk bersepakat
melakukan pilihan forum di luar pengadilan dalam rangka menyelesaikan
sengketa yang kemungkinan akan timbul di kemudian hari. Pactum de
compromittendo dan Acte van compromise (akta kompromis) adalah dua
cara yang secara teoretik dikenal dalam konteks pilihan forum arbitrase. Di
antara keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Memilih forum
dengan cara pactum de compromittendo bermakna, ketika para pihak
bersepakat memilih forum, sama sekali belum terjadi sengketa (disputes).
Kesepakatan dibuat dengan asumsi sengketa diantara para pihak benar-benar
akan terjadi di kemudian hari. Sedangkan pada akta kompromis, para pihak
96
memilih forum ketika sengketa tersebut benar-benar sudah terjadi. Dengan
demikian akta kompromis pada dasarnya merupakan kebalikan dari pactum
de compromittendo.
Bab III, menggunakan judul Subjek dan Objek Sengketa Komersial
di dalam Forum Arbitrase. Pada bab ini dideskripsikan tentang keadaan
sosial (social setting) dari subjek-subjek sengketa yaitu pihak-pihak dalam
sengketa yang melakukan pilihan forum arbitrase dalam menyelesaikan
konflik mereka. Demikian pula objek sengketa komersial yang diselesaikan
lewat forum arbitrase. Objek sengketa dalam forum arbitrase yang dimaksud
adalah jenis sengketa atau konflik yang dalam praktik biasanya diperiksa
dan diputus oleh forum arbitrase. Oleh karena sejauh yang dapat diketahui,
tidak setiap jenis sengketa atau perselisihan lazim diperiksa dan diputus oleh
forum arbitrase. Ada sejumlah sengketa dalam bidang hukum tertentu yang
penyelesaiannya memang tidak lazim kalau pun di Indonesia tidak ada
larangan untuk membawa dan menyelesaikannya lewat forum arbitrase.
Umpamanya saja, sengketa dalam bidang hukum keluarga dan waris,
sengketa tentang perburuhan dan ketenagakerjaan, serta sengketa mengenai
perumahan. Ketiga jenis sengketa yang tersebut bukan hanya tidak lazim
diselesaikan lewat forum arbitrase, akan tetapi lebih didasarkan pada
pertimbangan bahwa untuk sengketa-sengketa tersebut telah disediakan
forum khusus untuk menyelesaikannya. Pengadilan Negeri dan/atau
97
Pengadilan Agama adalah forum yang disediakan untuk sengketa Hukum
Keluarga dan Waris; Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat
dan/atau Daerah (P4P dan/atau P4D) adalah forum untuk menyelesaian
sengketa perburuhan dan ketenagakerjaan; dan sengketa perumahan
diselesaikan lewat panitia penyelesaian sengketa perumahan. Oleh karena
itu, sejauh dapat diketahui dari informasi yang terkumpul, untuk kasus di
Indonesia forum arbitrase hanya lazim menyelesaikan sengketa-sengketa
komersial. Seperti yang dinyatakan di dalam Undang-undang Arbitrase dan
APS, yaitu: putusan arbitrase ...terbatas pada putusan yang menurut
ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum
perdagangan. (Pasal 66 huruf a dan b UU Nomor 30 Tahun 1999).
Kemudian. di dalam sub bab selanjutnya diuraikan tentang Struktur dan
Proses Penyelesaian Sengketa lewat Arbitrase. Seperti diketahui struktur
kelembagaan pengadilan dan arbitrase sangat berbeda. Demikian pula
mekanisme dan proses penyelesaian sengketa di dalamnya tentu saja
berlainan. Struktur penyelesaian sengketa pada forum arbitrase maksudnya
adalah cara bagaimana penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase itu
disusun, dirumuskan, dan dilangsungkan. Sedangkan proses penyelesaian
sengketa melalui arbitrase maksudnya adalah rangkaian tindakan melalui
fase-fase yang secara objektif sistematik mesti dilalui oleh para pihak
maupun para pemutus sengketa (para wasit/arbiter) sampai dengan diperoleh
98
konklusi untuk menjatuhkan putusan. Dilihat dari struktur kelembagaan
badan peradilan negara terdiri atas dua tingkat, yaitu: (i) tingkat pertama
(original jurisdiction) dan (ii) tingkat banding (appellate jurisdiction).
Sedangkan forum arbitrase berdasarkan strukturnya terdiri atas dua jenis,
yaitu: (i) Arbitrase Institusional (arbitrase permanen) dan (ii) Arbitrase Ad
hoc (Arbitrase perorangan). Dari sudut mekanisme dan proses penyelesaian
sengketanya Laura Nader menyebut penyelesaian sengketa lewat lembaga
peradilan sebagai winner takes all yaitu the decision is that one party
is right and the other wrong. Dengan kata lain mekanisme dan prosesnya
menggunakan pendekatan pertentangan yang mempertaruhkan win-loose.
Sedangkan mekanisme dan proses melalui forum arbitrase dalam istilah
Laura Nader sebagai give a little, get a little. Atau dengan kata lain
mekanisme dan proses arbitrase menggunakan pendekatan konsensus yang
mengarah pada posisi win-win. Bab ini diakhiri dengan sub bab yang
memaparkan tentang Keadilan Menurut Pihak-pihak Bersengketa. Dalam
memaparkan persoalan ini penulis mengutip apa yang dikemukakan Esmi
Warassih dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Fakultas Hukum
Undip, antara lain: Persoalan keadilan tidak pernah akan selesai secara
tuntas dibicarakan orang, bahkan persoalan keadilan semakin mencuat
seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan
kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan satu sama lain. Persoalan
99
keadilan merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks, sebab
menyangkut hubungan antar manusia dari segala aspek kehidupannya.
Setiap masyarakat dengan sistem sosial tertentu memiliki tolok ukur atau
pedoman yang berlainan satu sama lain dalam menentukan makna keadilan
bagi masyarakatnya. Oleh sebab itu, kita sulit menemukan rumusan keadilan
yang berlaku secara universal. Begitu pula makna keadilan menurut para
pihak yang bersengketa. Masing-masing pihak memiliki tolok ukurnya
sendiri-sendiri, sehingga tidak mudah juga untuk menemukan makna
keadilan yang dapat diterima kedua belah pihak secara seimbang.
Bab IV, mengusung tema Pilihan Forum Arbitrase, Budaya Hukum,
dan Keadilan. Sebagian besar substansi bab ini merupakan deskripsi serta
analisis hasil penelitian. Diawali dengan sub bab yang memaparkan tentang
Pilihan Forum Arbitrase dan Budaya Hukum di Indonesia. Budaya hukum
dalam arti keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum,
termasuk di dalamnya rasa respek atau tidak respek kepada hukum,
kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan
pengadilan. Oleh sebab itu, memilih arbitrase sebagai forum tempat
penyelesaian sengketa terkait erat dengan komponen substansif dari budaya
hukum yang terdiri atas asumsi-asumsi fundamental mengenai apa yang
dianggap adil dan tidak oleh masyarakat. Kondisi semacam itu tidak terlepas
dari faktor internal pengadilan sendiri yang selama ini telah dianggap dan
100
dirasakan oleh para pencari keadilan sebagai sangat merugikan upayanya
dalam mencari dana menegakan keadilan. Untuk itu maka dalam sub bab
berikutnya diuraikan dan dianalisis tentang 'Faktor Internal Pengadilan
Negeri dan Pilihan Forum Arbitrase.' Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh
informasi yang mengungkapkan bahwa faktor internal pengadilan negeri
terkait cukup erat dengan kecenderungan para pelaku bisnis untuk
melakukan pilihan forum arbitrase. Tidak hanya menyangkut persoalan
integritas, kejujuran, keahlian, dan profesionalisme aparatur pengadilan
yang diragukan oleh para pelaku bisnis untuk dapat menyelesaikan sengketa
mereka secara adil, tetapi yang paling krusial adalah sinyalemen terjadinya
jual beli hukum atau jual beli putusan yang biasa berlangsung di
pengadilan. Namun demikian, forum arbitrase tampaknya tetap saja
dikondisikan oleh Undang-undang sebagai forum yang tidak memiliki
kewenangan publik untuk mengeksekusi putusannya. Untuk menganalisis
masalah ini dalam sub bab berikutnya dibahas tentang Kewenangan
Eksekutorial Forum Arbitrase untuk Putusan Final dan Mengikat serta
Dilema Perolehan Keadilan. Meski secara formal putusan arbitrase
dikatagorikan sebagai final dan mengikat (final and binding), namun dalam
kenyataannya karena forum arbitrase sama sekali tidak memiliki
kewenangan eksekutorial untuk melaksanakan putusannya sendiri, maka
pelaksanaan putusan arbitrase baik yang berasal dari dalam negeri (arbitrase
101
nasional) maupun putusan arbitrase internasional masih diperlukan
penyerahan dana pendafatran putusan arbitrase kepada Pantera Pengadilan
Negeri. Ketentuan itu disertai ancaman sanksi bila penyerahan dan
pendaftaran putusan arbitrase itu tidak dilakukan, maka putusan tersebut
tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk menutup uraian pada bab
empat ini, disajikan mengenai Perspektif Historis dan Futuristik Arbitrase
sebagai Model Penyelesaian Sengketa Berkeadilan. Maksud dari sub bab
ini antara lain hendak menyajikan sejumlah pemikiran tentang
kemungkinan-kemungkinan diberikannya kewenangan publik kepada forum
arbitrase, sehingga forum tersebut seperti halnya pengadilan dapat
melaksanakan putusan yang dijatuhkannya sendiri. Tidak seperti keadaan
sekarang dimana forum arbitrase masih bergantung pada exequatur yang
diberikan oleh pengadilan negeri.
Bab V, hendak menggambarkan betapa eksekusi putusan arbitrase
akan mencerminkan tentang kondisi penegakan keadilan di Indonesia. Oleh
karenanya, tema yang diangkat dalam bab ini adalah Eksekusi Putusan
Forum Arbitrase Gambaran Dilema Penegakan Keadilan di Indonesia. Sub
bab yang pertama, menyajikan tentang Makna dan Kekuatan Putusan
Menurut Pengadilan Negeri serta Para Pihak Bersengketa. Di sini hendak
dipaparkan tentang bagaimana sesungguhnya pengadilan memberikan
makna terhadap putusan dan bagaimana pula pihak-pihak bersengketa
102
memberi makna terhadap putusan. Dikhawatirkan selama ini kedua belah
pihak, dalam hal ini pengadilan dan pihak-pihak bersengketa memaknai
putusan itu berlainan, sehingga terus menerus terjadi divergensi pemaknaan
yang tidak pernah akan bertemu pada satu titik persamaan makna. Atau
malah terjadi pergeseran makna dan status putusan, sehingga dalam sub bab
selanjutnya akan dikaji tentang Interpretasi, Koreksi, dan Pergeseran
Makna Putusan Arbitrase. Seandainya memang terjadi pergeseran makna,
tentu harus dipahami seberapa jauh hal itu terjadi serta apa saja faktor
penyebabnya. Selanjutnya menyangkut persoalan pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia salah satu
syaratnya putusan arbitrase internasional itu tidak bertentangan dengan
ketertiban umum. Tidak jarang syarat tersebut menjadi barrier bagi
putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui dan dieksekusi di
Indonesia. Oleh karena itu, dalam konteks pembahasan mengenai hal ini,
sub bab ketiga dari bab lima ini bertema Diskresi Hakim dalam Masalah
Eksekuatur Putusan Arbitrase. Di sini akan diuraikan tentang seberapa jauh
kewenangan/otoritas hakim pengadilan negeri pemberi eksekuatur dalam
konteks diskresi hakim pada waktu melakukan penafsiran (interpretasi) atas
kriteria ketertiban umum yang dipersyaratkan tersebut. Persoalannya apabila
pengadilan negeri menolak memberikan eksekuatur terhadap putusan
arbitrase internasional, maka putusan dimaksud tidak dapat diakui dan
103
dieksekusi di Indonesia. Persoalan ini erat sekali kaitannya dengan masalah
penegakan keadilan. Untuk itu diakhir bab lima ini ditutup dengan sub bab
yang mengetengahkan tema Eksekusi Putusan Arbitrase dalam Penegakan
Keadilan. Di sini akan diuraikan betapa permohonan eksekusi putusan
arbitrase yang ditolak itu sama saja dengan tidak ditegakannya keadilan
yang telah diupayakan dengan susah paya oleh para pihak yang bersengketa.
Dalam keadaan semacam itu yang dihadapi para pencari keadilan tidak lebih
dari sebuah dilema. Dilema dalam penegakan dan perolehan keadilan,
karena proses penyelesaian sengketa yang telah ditempuhnya di luar
pengadilan harus bermuara kembali di pengadilan. Dalam keadaan seperti
ini, pemohon eksekusi boleh jadi menghadapi pilihan yang amat sulit. Posisi
tawarnya sangat lemah, upayanya untuk mendapatkan keadilan kembali
terbentur pada otoritas pengadilan yang reputasi buruknya sudah amat
dikenal, sehingga tidak heran bila para pemohon eksekusi akhirnya bukan
memperoleh keadilan melainkan hanya sekedar memperoleh lembaran-
lembaran berkas putusan yang tidak memiliki nilai ekonomis apa pun.
Beberapa kasus yang sengketanya telah diputus oleh forum arbitrase namun
kemudian putusannya menemui hambatan tatkala dimintakan
pelaksanaannya di pengadilan negeri juga akan disajikan sekaligus dalam
rangka menutup seluruh uraian pada bab lima ini.
104
Bagian terakhir dari disertasi ini adalah Bab VI, sebagai penutup dari
keseluruhan substansi disertasi setelah serangkaian pokok bahasan dikaji
serta dianalisis. Bab VI Penutup yang terdiri atas Simpulan serta
Rekomendasi. Informasi yang disajikan dalam paparan Simpulan akan
merupakan jawaban atas sejumlah permasalahan sebagaimana telah
dikemukakan pada bagian pertama. Sementara itu uraian tentang
Rekomendasi akan ditujukan baik kepada pihak-pihak yang berpotensi
memiliki konflik serta lazim menyelesaikan konfliknya pada forum di luar
pengadilan, maupun kepada badan peradilan sebagai pemegang otoritas
kewenangan publik sekaligus pelaku eksekusi putusan arbitrase.
Rekomendasi juga ditujukan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan
Rakyat sebagai pemegang otoritas dalam melakukan perubahan atau
amandemen terhadap undang-undang. Hal itu perlu dilakukan karena
ternyata sejumlah pasal di dalam Undang-undang Arbitrase dan APS
diketahui masih bersifat ambivalen, sehingga forum arbitrase tercitrakan
masih disubordinasikan terhadap kewenangan pengadilan negeri. Bahkan
lebih dari itu dijumpai adanya kaidah yang secara tegas memandulkan fungsi
dan peran arbitrase sebagai forum tempat penyelesaian sengketa.
105
BAB II
PILIHAN FORUM ARBITRASE SEBAGAI TEMPAT
PENYELESAIAN SENGKETA BERKEADILAN
Secara etimologi,
163
kata forum memiliki beragam makna. Forum
dapat bermakna lembaga atau badan,
164
dapat juga berarti sidang,
165
bahkan
dalam konteks yang lain, forum memiliki makna tempat pertemuan untuk
bertukar pikiran secara bebas. Menyimak ragam makna istilah forum di
atas, dalam kaitannya dengan tema Bab II disertasi ini, kata forum dalam
Pilihan Forum Arbitrase sebagai Tempat Penyelesaian Sengketa
Berkeadilan, kiranya lebih mendekati makna lembaga atau badan atau dapat
pula berarti sidang beserta segenap kewenangan atau kompetensi yang
dimilikinya.
Sementara itu, membicarakan masalah kewenangan suatu forum atau
lembaga terkait erat dengan persoalan jurisdiksi (jurisdiction).
166
Dalam
kaitan itu, pilihan forum berarti pilihan terhadap jurisdiksi lembaga atau
163
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Etimologi adalah cabang ilmu bahasa yang
menyelidiki asal-usul kata serta perubahan-perubahan dalam bentuk dan makna.
164
A court, specific court in which an action is brought Sementara itu kata action pada
pengertian forum di atas berarti A judicial remedy to enforce a right or to punish an
offender; a lawsuit.
165
Sidang dapat berarti pertemuan untuk membicarakan sesuatu; atau juga berarti dewan
atau majelis.
166
Jurisdiction: The extent of the legitimate authority of the court. The authority of the
court. The right to decide a question properly presented to the court. Jurisdiksi adalah
kekuasaan atau kompetensi hukum (negara) terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum).
Jurisdiksi juga meruakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah,
menciptakan atau mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum. Bdgk., Malcolm Shaw,
International Law. London: Butterworths, 1986, h. 342.
106
badan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama dalam rangka mengajukan tuntutan
pengembalian hak terhadap pihak yang dianggap telah melanggar dan/atau
merugikan hak pihak yang mengajukan tuntutan.
Pilihan forum atau pilihan hakim (Choice of forum, atau Choice of
court) kerapkali dapat dijumpai dalam yurisprudensi Hukum Antar
Golongan (HAG)
167
maupun Hukum Perdata Internasional (HPI). Bahkan
di dalam HAG, pilihan forum atau pilihan hakim (Choice of court) ini tidak
jarang justru disalah-pahamkan dengan pilihan hukum (Choice of law),
padahal di antara keduanya memiliki arti serta maksud yang berlainan.
Dalam hubungan ini Sudargo Gautama
168
mengemukakan, kesalah-pahaman
demikian terjadi karena hubungan yang demikian erat antara pilihan hakim
atau pilihan forum (Choice of court, Choice of forum) dengan pilihan hukum
(Choice of law).
169
Contoh berikut ini berasal dari cabang HAG yang dapat
167
Cabang Ilmu Hukum Antar Golongan (HAG) ini, pada beberapa Fakultas Hukum
merupakan salah satu mata kuliah dengan nama Hukum Perselisihan. Cabang Ilmu
Hukum ini adalah khas Indonesia. Dikatakan khas, oleh karena hanya dikenal di
Indonesia sebagai salah satu negara bekas jajahan Belanda dan muncul sebagai akibat
politik hukum Pemerintah Kolonial Belanda yang ketika itu melakukan pembagian
golongan penduduk atau golongan rakyat (bevolkingsgroepen) seperti diketahui dari
pasal 131 juncto 163 Indische Staatsregeling (I.S. Stb. 1855 No. 2). Lihat S. Gautama,
Hukum Antar Tata Hukum. Bandung: Alumni, 1977, h. 8.
168
Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Hukum yang Hidup. Bandung:
Alumni, 1983, h. 53.
169
Pilihan hukum (choice of law) sangat erat kaitannya dengan masalah pilihan forum
atau pilihan yurisdiksi (choice of forum atau choice of jurisdiction). Kedua kata ini,
forum dan yurisdiksi sering disamakan artinya dan penggunaannya sering
dipertukarkan. Lihat Setiawan, Kontrak Bisnis Internasional Choice of Law &
107
menggambarkan betapa kesalah-pahaman antara pilihan forum dengan
pilihan hukum sangat mudah terjadi: Seseorang yang berasal dari golongan
rakyat Bumi Putera (Inlanders) hendak beracara perdata dengan memilih
tempat kediaman hukum (domisili) pada kantor Panitera Raad van Justitie
(RvJ).
170
Tindakan orang Bumi Putera tersebut telah disalah-pahamkan,
sehingga ia dianggap seolah-olah telah melakukan pilihan hukum ke arah
hukum yang biasanya sehari-hari diberlakukan oleh Raad van Justitie, yakni
hukum perdata tertulis BW (Burgerlijk Wetboek) dan WvK (Wetboek van
Koophandel).
171
Padahal berdasarkan ketentuan pasal 131 juncto pasal 163
IS (Indische Staatsregeling),
172
untuk orang-orang Bumi Putera tidak
berlaku hukum perdata tertulis BW maupun WvK, melainkan berlaku
hukum adatnya masing-masing.
173
Dari contoh kasus di muka tampak jelas
Choice of Jurisdiction; dalam Varia Peradilan, Tahun IX No. 107, Agustus 1994, h.
125-137 [125].
170
Pada masa Hindia Belanda, Raad van Justitie merupakan lembaga pengadilan atau
hakim sehari-hari untuk orang-orang yang berasal dari golongan rakyat Eropa dan
Timur Asing.
171
Sebagai contoh, umpamanya seseorang yang berasal dari golongan rakyat Bumi Putera
memilih Raad van Justitie untuk keperluan penyelesaian konflik tertentu di antara
mereka, maka dalam kasus yang demikian, dianggap orang Bumiputera tersebut secara
diam-diam telah menghendaki pula bahwa hukum yang biasanya berlaku untuk
golongan rakyat Eropa dan Timur Asing yaitu hukum perdata tertulis (BW dan WvK)
adalah hukum yang berlaku terhadap mereka. Lihat Sudargo Gautama, Hukum
Perdata InternasionalOp. Cit., h. 52-53.
172
S. 1855 Nomor 2.
173
...Kebijakan hukum Hindia Belanda pada paruh kedua abad ke 19 di antaranya
kebijakan untuk menghormati hak-hak kultural penduduk pribumi. Proyeksinya dalam
perkembangan kebijakan hukum kolonial ialah, lebih dipilihnya cara untuk sedapat
mungkin mempertimbangkan eksistensi kaidah-kaidah agama serta lembaga dan adat
kebiasaan yang (masih) dianut rakyat pribumi, tanpa memandang agama atau
kepercayaannya,.... Lihat dalam Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum
Kolonial...Op. Cit., h. 8.
108
betapa tipisnya batas antara pilihan forum dengan pilihan hukum. Bahkan
kesalah-pahaman antara pilihan forum dengan pilihan hukum dapat terjadi
boleh jadi karena kekeliruan penafsiran yang dilakukan oleh kalangan
hukum sendiri; Seperti dalam kasus orang Bumi Putera di atas, pihak RvJ
telah keliru membuat penafsiran terhadap maksud dari pihak atau orang
Bumi Putera yang telah melakukan pilihan domisili pada Panitera RvJ,
padahal belum tentu maksud orang Bumi Putera itu hendak melakukan
pilihan hukum terhadap BW atau WvK.
Sedangkan di dalam HPI yang dimaksud dengan pilihan hakim atau
pilihan forum (Choice of Court, Choice of forum) adalah pemilihan yang
dilakukan terhadap instansi peradilan atau instansi lain yang oleh para pihak
ditentukan sebagai instansi yang akan menangani sengketa mereka jika
terjadi di kemudian hari.
174
Para pihak di dalam HPI dianggap memiliki
kebebasan untuk melakukan pilihan forum, sehingga pihak-pihak dapat atau
diperkenankan untuk menyimpangi kompetensi relatif
175
badan pengadilan
174
Para pihak di dalam suatu kontrak dapat menyepakati sebuah klausula yang isinya
menentukan bahwa, apabila di kemudian hari timbul sengketa dari substansi kontrak
yang mereka sepakati tersebut, sengketa dimaksud akan dibawa untuk diselesaikan oleh
sebuah lembaga peradilan yang mereka pilih selain pengadilan negeri di Indonesia.
Pilihan dapat dilakukan terhadap lembaga tempat penyelesaian sengketa yang ada, baik
di dalam negeri maupun di luar negeri. Lihat S. Gautama, Hukum Perdata
Internasonal...Op. Cit., h. 53-54.
175
Yaitu kewenangan horisontal yang dimiliki oleh badan pengadilan yang sejenis untuk
memeriksa dan memutus perkara gugatan atau tuntutan hak yang diajukan kepadanya
berkaitan dengan wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau dimana tergugat
mempunyai alamat, atau berdomisili. Lihat, Ny. Retnowulan Sutantio, Hukum Acara
Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1997, h. 11. Bdgk.
109
yang sesungguhnya secara relatif memiliki kewenangan untuk memeriksa
dan memutus sengketa mereka. Di dalam HPI pilihan forum umumnya
terbuka untuk perkara-perkara perdata dan/atau perkara dagang yang
memiliki karakter internasional (international nature),
176
yang mungkin
terjadi di antara para pihak berkenaan dengan suatu hubungan hukum
tertentu.
A. Tujuan Pilihan Forum Arbitrase dan Keadilan
Sejauh ini belum pernah dijumpai kepustakaan hukum arbitrase yang
secara eksplisit menyebut mengenai tujuan orang-orang yang terlibat dalam
suatu sengketa bisnis memilih forum arbitrase untuk menyelesaikan
sengketanya. Sebaliknya, yang dijumpai dari sejumlah literatur hukum
arbitrase justru alasan mengapa para pelaku bisnis memilih forum arbitrase
dan bukan tujuan memilih forum arbitrase. Padahal antara alasan
177
dan
tujuan atau maksud sesungguhnya memiliki makna yang sedikit
berlainan meskipun nuansanya memang tidak mudah untuk dibedakan
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,
1985, h. 60.
176
Suatu perkara dianggap memiliki karakter internasional atau international nature,
apabila salah satu subjek hukumnya sebagai pihak atau objek hukum dalam perkara
tersebut merupakan unsur asing atau unsur luar negeri (foreign element). Baca: S.
Gautama, HPI Hukum Yang HidupOp.Cit., h.52. Bdgk. HPI Indonesia (Buku
kedelapan). Bandung: Alumni, 1987, h. 233-237.
177
Alasan artinya sesuatu hal yang menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu atau tidak
berbuat sesuatu. Sedangkan tujuan (maksud) adalah kehendak, kemauan, keinginan
atau hasrat.
110
secara jelas. Dari pembacaan atas sejumlah kepustakaan hukum abitrase,
178
penulis mendapatkan informasi justru mengenai alasan dari orang-orang
memilih forum arbitrase dan sama sekali bukan mengenai tujuan.
Berbagai macam alasan mengapa orang-orang memilih forum arbitrase
sebagai cara penyelesaian sengketa secara privat di antaranya dapat
diketahui sebagai berikut:
179
(i) Kebebasan, Kepercayaan, dan Keamanan;
Arbitrase pada umumnya menarik bagi para pengusaha, pedagang, dan
investor sebab arbitrase memberikan kebebasan dan otonomi yang
sangat luas kepada mereka.
(ii) Keahlian (expertise);
Para pihak yang bersengketa memiliki kepercayaan yang lebih besar
pada keahlian arbiter mengenai persoalan yang disengketakan
dibandingkan dengan kepada pengadilan.
(iii) Cepat dan Hemat Biaya;
178
Literatur hukum arbitrase dimaksud dapat disebutkan diantaranya: Priyatna Abdurrasyid,
Arbitrase & APS. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002; Erman Rajagukguk, Arbitrase
dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra Pratama, 2001; M. Yahya Harahap,
Arbitrase Ditinjau dari: Rv, BANI Rules, ICSID, UNCITRAL Arb. Rules, NY
Convention, PERMA 1 Th. 1990. Jakarta: Sinar Grafika, 2001; Sudargo Gautama,
Arbitrase Dagang Internasional. Bandung: Alumni, 1986.
179
Gary Goodpaster, Felix O. Soebagjo, Fatmah Jatim, Tinjauan Terhadap Arbitrase
Dagang Secara Umum dan Arbitrase Dagang di Indonesia; dalam Felix O. Soebagjo
& Erman Rajagukguk (eds), Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995,
h. 19-42 [19-22].
111
Sebagai suatu proses, arbitrase tidak terlalu formal sehingga
mekanismenya lebih fleksibel
180
dibandingkan dengan prose litigasi di
pengadilan. Dengan demikian arbitrase proses pengambilan
keputusannya lebih cepat sehingga biaya penyelesaian sengketa relatif
lebih murah daripada litigasi, sebab untuk putusan arbitrase tidak ada
kemungkinan upaya hukum banding.
(iv) Bersifat Rahasia;
Oleh karena arbitrase lebih bersifat privat dan tertutup dibandingkan
pengadilan, pemeriksaan sengketa di dalam forum arbitrase bersifat
rahasia. Sifat itu melindungi para pihak dari publisitas
181
yang
merugikan serta segala akibatnya, seperti kehilangan reputasi bisnis.
Sementara itu, publisitas dalam penyelesaian sengketa di pengadilan
negeri sulit dihindarkan karena pengadilan negeri terikat oleh asas sifat
180
Bahwa forum selain pengadilan dianggap lebih fleksibel didasarkan pada asumsi yang
menyebutkan antara lain: (a) menyelesaikan sengketa melalui forum selain pengadilan
lebih memberi keleluasaan dan kesempatan kepada para pihak untuk: memilih sendiri
hakim (arbiter) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan jenis sengketa
yang hendak diperiksa dan diselesaikan oleh forum dimaksud, sementara di pengadilan
biasa memilih hakim sangat tidak mungkin dilakukan; (b) kemampuan serta keahlian
arbiter tersebut akan sangat berpangaruh pada kecepatan dalam memahami isu-isu yang
menonjol dari suatu sengketa, baik segi fakta maupun hukumnya, sehingga bagi para
pihak hal itu akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan dalam penyelesaian
sengketa mereka. (c) bila demikian adanya maka para pihak dapat menggantungkan
harapan terhadap forum tersebut untuk memperoleh putusan yang pantas dan adil (fair
and sensible award). Lihat. Alan Redfern & Martin Hunter, Law and Practice of
International Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 1991, h. 23.
181
S. Gautama, Arbitrase DagangOp. Cit., h. 197.
112
terbukanya persidangan, yang memungkinkan setiap orang dapat hadir
dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan.
(v) Pertimbangan putusan arbitrase lebih bersifat privat;
Dalam mempertimbangkan penyelesaian sengketa privat, pengadilan
dan arbitrase sangat berbeda. Pengadilan adalah lembaga publik,
sehingga ketika menyelesaikan sengketa privat pun seringkali
memanfaatkan momentum penyelesaian sengketa privat untuk
mengutamakan kepentingan umum, sementara kepentingan privat
menjadi pertimbangan kedua. Sebaliknya, forum arbitrase merupakan
lembaga privat, oleh sebab itu para arbiter dalam mempertimbangkan
penyelesaian sengketa yang ditanganinya juga lebih bersifat privat
daripada bersifat publik/umum.
(vi) Kecenderungan yang Modern;
Dalam dunia perdagangan internasional, kecenderungan yang terlihat
adalah liberalisasi peraturan/undang-undang arbitrase untuk lebih
mendorong penggunaan arbitrase daripada penyelesaian sengketa
dagang melalui badan peradilan umum.
182
(vii) Putusan Arbitrase Final dan Mengikat;
182
Gary Goodpaster et al, TinjauanOp. Cit., h. 22. Sebagai contoh saja, dalam kontrak-
kontrak penting antara pengusaha-pengusaha Indonesia dan pengusaha luar negeri
seringkali dicantumkan klausula arbitrase, sebab sebagai pengusaha asing mereka
kurang mengenal sistem hukum di Indonesia dan kurang paham akan formalitas acara
113
Sesuai dengan kehendak dan niat dari para pihak pelaku bisnis yang
menghendaki putusan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase
bersifat final dan mengikat (final and binding) kedua belah pihak.
Sedangkan putusan pengadilan masih terbuka berbagai upaya hukum,
sehingga untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap,
memerlukan waktu yang cukup lama.
Serangkaian alasan di muka dicoba untuk dipahami dalam kaitannya
dengan tujuan pihak-pihak memilih forum arbitrase sebagai jalur
penyelesaian sengketa. Diperoleh gambaran kiranya yang menjadi tujuan
memilih forum arbitrase antara lain: agar konflik yang sedang dihadapi
dapat diselesaikan dengan proses yang cepat, terjamin kerahasiaannya,
ditangani oleh arbiter atau wasit yang ahli dalam bidangnya, sehingga
sengketanya dapat diputuskan menurut keadilan dan kepatutan (ex aequo et
bono). Pada akhirnya, tujuan memilih forum arbitrase akan bermuara pada
tujuan akhir dalam penyelesaian sengketa yakni untuk mendapatkan
keadilan substansial yang lebih bermartabat, dan tidak sekadar memperoleh
keadilan formal yang tidak memiliki makna apa pun.
Namun demikian, berbicara masalah keadilan tidak hanya sangat sukar
melainkan juga sangat luas karena keadilan sangat beragam maknanya. Oleh
berperkara di pengadilan negeri di Indonesia. Lihat S. Gautama, Arbitrase
DagangOp. Cit., h. 196.
114
karena itu, Majid Khadduri
183
di dalam The Islamic Conception of Justice,
membahas keadilan dalam beberapa bab dengan judul-judul: Political
Justice, Theological Justice, Philosophical Justice, Legal Justice, Justice
among Nations, dan Social Justice. Sementara itu, di dalam Ensiklopedi
Hukum Islam, keadilan maknanya lebih dititikberatkan pada pengertian
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ibnu Qudamah, mengatakan bahwa
keadilan merupakan sesuatu yang tersembunyi, motivasinya semata-mata
karena takut kepada Allah Subhanahu Wataala.
184
Adil dalam ajaran
Islam ada dua macam. Pertama, adil mutlak, yang tidak terikat. Manusia
sangat membutuhkan fungsi akal untuk mengetahui kebaikan atau keadilan
itu. Adil dalam konteks ini lebih dekat pada pengertian kebaikan atau
kebenaran. Oleh karena tidak terikat (mutlak), adil dalam pengertian ini
tidak pernah dihapuskan hukumnya sepanjang masa, dari satu syariat
185
ke
syariat yang lain. Pelaksanaannya merupakan kewajiban, sehingga adil ini
183
Secara harfiah kata adl (sebagai kata benda abstrak) berasal dari kata kerja adala yang
berarti: Pertama, meluruskan atau jujur; Kedua, menjauh, meninggalkan dari satu jalan
salah menuju jalan yang benar; Ketiga, menjadi sama (to be equal or equivalent),
menjadi sama atau sesuai (to be equal atau match) atau menyamakan; Keempat,
membuat seimbang atau menyeimbangkan (to balance or counter balance)
menimbang, atau dalam keadaan seimbang. Lihat Topo Santoso, Menggagas Hukum
Pidana Islam Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas. Bandung:
Asy Syaamil, 2001, h. 82-83.
184
Ensiklopedi Hukum Islam Buku I, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996, h. 25.
185
Syariat adalah segala tuntunan yang diberikan Allah SWT dan Rasul-Nya melalu
perkataan, perbuatan, dan takrir (ketetapan). Tuntunan itu menyangkut baik hubungan
yang berkaitan dengan masalah akidah, maupun hukum-hukum perseorangan,
hubungan manusia dengan Khalik, hubungan manusia dengan sesamanya, atau
hubungan yang bertalian dengan etika pergaulan dan sikap terhadap diri sendiri dan
atau orang lain. Lihat dalam Ensiklopedi Islam ; Op. Cit., h. 346.
115
tidak sama dengan balas membalas. Kedua, adil yang hanya diketahui
melalui Al-Quran atau Hadis Nabi Muhammad SAW. Adil dalam pengertian
ini dalam perjalanan sejarah agama-agama Allah SWT dapat mengalami
perubahan atau penghapusan hukum karena ajaran agama yang baru.
186
Adil adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh manusia dalam
rangka menegakkan kebenaran kepada siapa pun tanpa kecuali, walaupun
akan merugikan dirinya sendiri. Secara terminologis, adil berarti
mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari
segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak
berbeda satu sama lain.
187
Pada sisi yang lain, John Rawls, di dalam A
Theory of Justice, mengkonsepkan keadilan sebagai fairness, yang
mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional
yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya
hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan
186
Suplemen Ensiklopedi Islam 1 A-K, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1993, h. 19.
187
Lihat Ensiklopedi Hukum Islam ; Op. Cit., h. 25. Pada bagian lain Esmi Warassih
mengemukakan: Persoalan keadilan tidak pernah akan selesai secara tuntas
dibicarakan orang, bahkan persoalan keadilan semakin mencuat seiring dengan
perkembangan masyarakat itu sendiri karena tuntutan dan kepentingan yang berbeda
bahkan bertentangan satu sama lain. Persoalan keadilan yang terjadi dalam masyarakat
tradisional akan berbeda dengan masyarakat yang sedang berkembang maupun
masyarakat yang telah maju, karena setiap masyarakat dengan sistem sosial tertentu
memiliki tolok ukur atau pedoman dalam menentukan keadilan bagi masyarakatnya.
Oleh sebab itu, kita sulit menemukan rumusan keadilan yang berlaku secara universal.
Lihat dalam Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan
Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan); PidatoOp. Cit., h. 14.
116
memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk
memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.
188
Teori keadilan Rawls secara khusus merupakan kritik terhadap teori-
teori keadilan sebelumnya yang menurutnya telah gagal memberikan suatu
konsep keadilan yang tepat bagi kita. Kegagalan teori-teori terdahulu itu
disebabkan oleh substansinya yang sangat dipengaruhi oleh utilitarisme
maupun intuisionisme. Sebagaimana dapat diketahui dari kata pengantar
buku A Theory of Justice, Rawls antara lain mengemukakan:
189
Secara
umum utilitarisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau
tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau
tindakan tertentu yang dilakukan. Oleh karena itu, baik buruknya tindakan
manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi
tindakan tersebut bagi manusia. Sebagai teori yang oleh Ronald Dworkin
disebut goal-based theory, utilitarisme gagal untuk menjamin keadilan
sosial karena lebih mendahulukan asas manfaat (the good) hingga
melupakan asas hak (the right) yang merupakan aspek fundamental dari
prinsip-prinsip moral, khususnya prinsip keadilan. Agaknya pandangan
utilitarisme melalui pendekatan teleologis,
190
berupaya menjembatani jurang
188
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986, h. 51.
189
Lihat Andre Ata Ujan, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John
Rawls. Yogyakarta: Kanisius, 2001, h. 21.
190
Teori moral teleologis melihat hasil dari tindakan sebagai norma untuk menilai adil
tidaknya, atau baik buruknya suatu tindakan dari segi moral. Sedangkan teori moral
117
antara prinsip hak (the right) dan prinsip manfaat (the good), namun dalam
praktiknya paham ini gagal memainkan perannya. Oleh karena apabila
utilitarisme tetap beranggapan bahwa kesejahteraan sosial dengan sendirinya
mengandaikan kesejahteraan anggota masyarakat sebagai individu, maka
muncul pertanyaan: Apa jaminannya bahwa peningkatan kesejahteraan
masyarakat sebagai keseluruhan akan dengan sendirinya mengangkat tingkat
kesejahteraan anggota masyarakat sebagai individu? Bisa saja terjadi, demi
manfaat yang lebih besar bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat, hak
individu justru sengaja dikorbankan. Apabila demikian, maka utilitarisme
gagal menjamin setiap orang untuk mendapatkan apa yang seharusnya
menjadi haknya. Lebih dari itu, utilitarisme mengancam bahkan menyangkal
kebebasan individual, sehingga mengindikasikan bahwa utilitarisme gagal
memperlakukan setiap orang sebagai pribadi (person) yang mempunyai hak
untuk diperlakukan secara adil dan sama. Akibat kegagalan tersebut maka
utilitarisme tidak tepat apabila dijadikan sebagai basis untuk membangun
deontologis mengatakan bahwa kualitas moral tindakan tidak tergantung pada hasil dari
tindakan, melainkan pada kualitas tindakan itu sendiri. Suatu tindakan akan dengan
sendirinya dianggap baik atau buruk secara moral hanya karena tindakan itu dalam
dirinya sendiri memang baik atau buruk secara moral. Jadi, keharusan moral menurut
teori etika teleologis tergantung pada konsekuensi dari tindakan, sedangkan keharusan
moral bagi etika deontologis ditentukan oleh hakikat dari tindakan itu sendiri. Lihat
dalam Andre Ata Ujan, Keadilan dan... Op. Cit., h. 157-158.
118
suatu konsep keadilan, karena tidak dapat memperjuangkan dan
menciptakan keadilan sosial.
191
Bagi Rawls sikap dasar utilitarisme sungguh bertolak belakang dengan
prinsip keadilan sebagai fairness. Keadilan sebagai fairness menuntut bahwa
orang pertama-tama harus menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai
basis yang melandasi pengaturan kesejahteraan sosial. Dalam kalimat lain,
setiap keputusan sosial yang mempunyai akibat bagi semua anggota
masyarakat harus dibuat atas dasar hak (right-based weight) daripada atas
dasar manfaat (good-based weight).
192
Berdasarkan argumen di muka,
Rawls hendak menegaskan bahwa keadilan sebagai fairness bermakna:
(i) prinsip hak dan kebebasan setiap orang harus mendapat prioritas
dibandingkan dengan prinsip manfaat;
191
Keadilan sosial dalam arti keadilan yang pelaksanaannya tergantung pada struktur
proses-proses ekonomis, politis, sosial, budaya, dan ideologis dalam masyarakat.
Struktur-struktur itu merupakan struktur-struktur kekuasaan dalam dimensi-dimensi
utama kehidupan masyarakat. Susunan struktur-struktur itu menentukan kedudukan
masing-masing golongan sosial, apa yang mereka masukkan dan apa yang amereka
peroleh dari proses-proses itu. Lihat dalam Franz Magnis-Suseno, Etika Politik
Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia, 1999, h. 332.
Bdgk. Henry B. Veatch, Human Rights, Facts or Fancy. Baton Rouge and London:
Lousiana State University Press, 1968, h. 55. Andre Ata Ujan, Keadilan dan... Op.
Cit., h. 31.
192
Right-based weight adalah pertimbangan yang didasarkan pada hak-hak tertentu,
seperti hak atas suara hati yang bebas, sebagai dasar untuk mengambil keputusan,
terutama keputusan-keputusan politik yang mempunyai dampak bagi kehidupan orang
banyak. Sedangkan good-based weight adalah pertimbangan-pertimbangan yang
mengambil sasaran-sasaran tertentu, misalnya manfaat yang sebesar-besarnya bagi
jumlah masyarakat yang sebanyak-banyaknya, sebagai basis fundamental untuk
mengambil keputusan. Lihat Ronald Dworkin, The Original Position; dalam
Reading Rawls, Critical Studies on Rawls A Theory of Justice; Norman Daniels
(Ed.), Oxford: Basil Blackwell, 1975, h. 38-43; Sebagaimana dimuat pula dalam Andre
Ata Ujan, Keadilan dan... Op. Cit., h. 158.
119
(ii) setiap anggota masyarakat mempunyai hak yang sifatnya tidak
dapat diganggu gugat dan secara mendasar dilindungi oleh prinsip
keadilan;
193
(iii)hak dan kebebasan individual itu begitu mendasar, sehingga
keduanya tidak bisa dikorbankan meskipun pengorbanan seperti itu
dianggap penting demi manfaat sosial dan ekonomis yang lebih
besar.
Sedangkan terhadap teori intuisionisme, Rawls mengkritik karena
intuisionisme dianggap tidak memberi tempat memadai pada asas
rasionalitas. Dalam konteks keadilan, intuisionisme pada pokoknya
beranggapan bahwa kemampuan intuitif dapat membantu kita untuk
mengatasi problem keadilan. Pendekatan intuitif bisa menjadi sangat
problematis terutama karena beragamnya sudut pandang yang bisa
diterapkan dalam melihat suatu masalah. Menghadapi realitas seperti itu,
pendekatan intuitif terhadap suatu masalah, khususnya masalah keadilan,
pasti bukan jalan keluar yang memadai.
194
Dalam proses pengambilan
keputusan (moral), intuisionisme lebih mengandalkan kemampuan intuisi
manusia. Oleh karena itu, pandangan ini juga tidak memadai apabila
193
Lihat John Rawls, A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard University
Press, 1971, h. 28. Bdgk. Andre Ata Ujan, Keadilan dan...Loc.Cit., h. 32.
194
John Rawls, A Theory of...Op. Cit., h. 35-40. Bdgk. Andre Ata Ujan, Keadilan dan...
Op. Cit., h. 32.
120
dijadikan pegangan dalam mengambil keputusan, terutama pada waktu
terjadi konflik di antara norma-norma moral. Dalam perspektif ini juga,
pelbagai generalisasi etis dapat disebut benar meskipun tidak didukung oleh
argumen yang sungguh-sungguh dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya
pertimbangan-pertimbangan dan keputusan-keputusan moral akan menjadi
subjektif atau kehilangan objektivitasnya.
195
Belajar dari kegagalan teori-teori keadilan sebelumnya, Rawls merasa
tertantang untuk membangun sebuah teori keadilan yang mampu
menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan
secara objektif. Oleh karena itu, suatu teori keadilan yang memadai harus
dibentuk dengan pendekatan kontrak dalam hal ini prinsip-prinsip keadilan
yang dipilih sebagai pegangan bersama sungguh-sungguh merupakan hasil
kesepakatan bersama dari semua person yang bebas, rasional, dan sederajat.
Berkaitan dengan hal tersebut di muka, pada Editors Foreword buku
Justice as Fairness A Restatement, antara lain diutarakan: According to
justice as fairness, the most reasonable principles of justice are those that
would be the object of mutual agreement by person under fair condition.
Justice as fairness thus develops a theory of justice from the idea of a social
195
Andre Ata Ujan, Keadilan dan... Op. Cit., h. 21.
121
contract.
196
Hanya melalui pendekatan kontrak itulah sebuah teori
keadilan mampu menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan
kewajiban secara adil bagi semua orang. Dalam arti itulah keadilan bagi
Rawls adalah fairness.
197
Artinya, tidak hanya mereka yang memiliki talenta
dan kemampuan yang lebih baik saja yang berhak menikmati pelbagai
manfaat sosial lebih banyak, tetapi keuntungan tersebut juga sekaligus harus
membuka peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk meningkatkan
prospek hidupnya. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban moral atas
kelebihan dari mereka yang beruntung juga harus ditempatkan dalam
bingkai kepentingan kelompok orang yang kurang atau tidak memiliki
talenta dan kemampuan sebaik yang mereka miliki. Dalam arti itu, keadilan
sebagai fairness sangat menekankan asas resiprositas, tetapi pasti tidak
dalam arti simple reciprocity yang bermakna distribusi kekayaan dilakukan
tanpa melihat perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat.
198
Keadilan adalah ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan
terhadap objek di luar diri kita. Objek yang ada di luar diri kita ini adalah
manusia, sama dengan kita. Oleh karena itu, ukuran tersebut tak dapat
dilepaskan dari arti yang kita berikan kepada manusia atau kemanusiaan,
196
John Rawls, Justice as Fairness A Restatement; (Edited by Erin Kelly).Cambridge,
Mass.: Harvard University Press, 2001, h. xi.
197
Andre Ata Ujan, Keadilan dan... Op. Cit., h. 22.
198
Andre Ata Ujan, Loc. Cit., h. 25.
122
tentang konsep kita mengenai manusia.
199
Persoalan keadilan memang
merupakan masalah yang cukup rumit dan kompleks, sebab menyangkut
hubungan antar manusia dari segala aspek kehidupannya. Pemahaman
keadilan menjadi lebih jelas, apabila terlebih dahulu kita memahami
hukum.
200
Suatu pendapat mengatakan, bahwa hukum itu merupakan
mekanisme yang mengintegrasikan kekuatan-kekuatan dan proses-proses di
dalam masyarakat. Dalam hubungannya dengan pendapat ini, maka
pengadilan pastilah merupakan lembaga yang terutama sekali menjadi
pendukung dari mekanisme itu. Di dalam lembaga itulah sengketa-sengketa
yang terdapat dalam masyarakat diselesaikan.
201
Sedangkan pekerjaan
untuk mewujudkan ide dan konsep keadilan ke dalam bentuk-bentuk yang
konkrit sehingga diterima oleh masyarakat, merupakan pekerjaan penegak
hukum terutama para hakim. Hakim diharapkan memiliki kemampuan
menerjemahkan nilai-nilai keadilan dalam persoalan-persoalan yang
dihadapkan kepadanya melalui putusan-putusannya.
202
Para hakim
hendaknya berani melihat undang-undang itu sebagai instrumen untuk
merumuskan keadilan bagi masyarakat dan bangsanya. Itu berarti, bahwa
hakim hendaknya senantiasa gelisah untuk menguji hukum yang ada, oleh
199
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum...Op. Cit., h. 51.
200
Esmi Warassih, Pemberdayaan.... Op. Cit., h. 16.
201
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Bandung: Alumni,
1980, h. 106.
202
Esmi Warassih, Pemberdayaan... Op. Cit., h. 18.
123
karena hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Manakala
pengadilan tidak mampu mendengarkan persoalan bangsanya, maka ia akan
menjadi suatu anomali, yang menyebabkan masyarakat kehilangan salah
satu lembaga yang penting yang menjadi simpul produktivitas proses-proses
dalam masyarakat.
203
Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan realitas
persoalan penegakan dan perolehan keadilan melalui lembaga pengadilan,
tujuan pilihan forum arbitrase dalam rangka penyelesaian sengketa ini
memiliki sandaran teoritis maupun praksis yang sangat memadai.
B. Konsekuensi Pilihan Forum Arbitrase terhadap Kompetensi
Hakim Pengadilan Negeri
Seperti telah disinggung di muka, bahwa pilihan forum arbitrase
memiliki kaitan yang cukup erat dengan ragam aktivitas perniagaan. Bahkan
aktivitas perdagangan antar bangsa yang semakin intensif dewasa ini sangat
diwarnai oleh semakin banyak kesepakatan yang dibuat dalam bentuk
kontrak internasional (international contracts). Menurut Hans Smith,
204
kontrak internasional (international contracts) adalah: "...contracts with
203
Satjipto Rahardjo,Rekonstruksi Strategi Pembangunan Hukum Menuju Pembangunan
Pengadilan yang Independen dan Berwibawa; Makalah Seminar pada Universitas
Ahmad Dahlan, Yogyakarta, 28 Maret 2000, h. 2-4.
204
Lihat Hans Smit et al, International Contracts. Parker School of Foreign and
Comparative Law, Columbia University, Matthew Bender, 1981, h. 4. Dalam kaitan ini
kontrak-kontrak internasional yang dibuat antar negara tidak termasuk di dalam kajian
124
elements in two or more nation-states. Such contracts may be between
states, between a state and a private party, or exclusively between private
parties."
Hukum Indonesia mengartikan kontrak serupa dengan perjanjian atau
persetujuan. Namun demikian, kontrak memiliki lingkup pengertian yang
lebih sempit karena hanya berarti perjanjian tertulis.
205
Sedangkan
perjanjian atau persetujuan meliputi baik yang dibuat secara tertulis maupun
lisan. Dalam rangka memelihara sikap taat asas dalam penulisan Disertasi
ini, selanjutnya akan digunakan istilah kontrak untuk menyebut perjanjian
206
tertulis. Ada sejumlah alasan dan pertimbangan mengapa istilah kontrak
relatif dianggap lebih tepat untuk digunakan apalagi dalam konteks
pembicaraan mengenai perjanjian yang melibatkan unsur asing (foreign
element) sebagai salah satu pihak di dalamnya. Alasan-alasan dimaksud
antara lain sebagai berikut:
Baik kaidah hukum nasional maupun hukum internasional, menyebut
kontrak untuk perjanjian (agreement) yang dibuat secara tertulis oleh
pihak-pihak swasta (private parties);
Disertasi ini. Pembahasan akan dibatasi hanya berkenaan dengan kontrak-kontrak
yang dibuat antar pihak-pihak swasta (private parties) satu sama lain.
205
R. Subekti, Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1979, h. 1.
206
Yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Lihat R. Subekti, Loc. Cit.,
125
Untuk membedakan antara kontrak internasional
207
dengan perjanjian
internasional (treaty),
208
karena di antara keduanya memiliki
perbedaan makna yang sangat kontras;
Merujuk pada rumusan dari Hans Smith, bahwa persetujuan
(agreement) antara dua pihak swasta atau lebih (exclusively between
private parties), yang berlainan kebangsaan disebut kontrak
internasional.
Sementara itu, hingga saat ini basis rujukan hukum kontrak di
Indonesia adalah Buku Ketiga BW (Burgerlijk Wetboek) atau KUH Perdata
tentang Perikatan. Seperti telah dimaklumi bahwa hukum kontrak di dalam
BW Indonesia menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak
(beginsel der contractsvrijheid).
209
Berdasarkan asas tersebut para pihak
diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk mengadakan kontrak apa saja,
207
"...contracts with elements in two or more nation-states. Such contracts may be between
states, between a state and a private party, or exclusively between private parties. Hans
Smith et al., International ContractsOp. Cit., h. 4.
208
"Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara negara-negara,
perjanjian antara negara dengan organisasi internasional, dan perjanjian antara suatu
organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya sebagai anggota
masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum
tertentu. Lihat Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional.
Bandung: Binacipta, 1978, h. 109-116.
209
Lihat R. Subekti, Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni 1981, h. 16. Sistem yang
dianut BW adalah sistem terbuka. Artinya, para pihak dapat mengadakan persetujuan-
persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW atau WvK (KUHD) atau Undang-
undang lainnya. Namun demikian ketentuan-ketentuan umum BW Buku III titel I
sampai dengan IV masih tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya perjanjian (Pasal
1320). Lihat dalam Sri Gambir Melati Hatta, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak
Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahakamah Agung Indonesia.
Bandung: Alumni, 1999, h. 3.
126
asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
210
Atas dasar alasan
demikian, kaidah hukum di dalam Buku ketiga BW adalah "hukum
pelengkap" (optional law).
211
Para pihak dimungkinkan untuk
mengesampingkan kaidah-kaidah hukum materiil tentang perikatan
sepanjang hal itu disepakati oleh mereka. Persoalan ini merupakan
konsekuensi dari pengakuan terhadap prinsip "pacta sunt servanda"
212
(perjanjian harus ditaati). Bahkan di dalam hukum internasional prinsip
pacta sunt servanda diakui amat fundamental, sehingga menjadi norma
imperatif dalam praktik perjanjian internasional.
213
210
Lihat R. Subekti, Hukum PerjanjianOp. Cit., h. 13.
211
Benar-benar pasal-pasal dari Hukum Perjanjian itu dapat dikatakan melengkapi
perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tidak lengkap, dan biasanya orang yang
mengadakan suatu perjanjian tidak mengatur secara terperinci semua persoalan yang
bersangkutan dengan perjanjian itu. Biasanya mereka hanya menyetujui hal-hal yang
pokok saja, dengan tidak memikirkan soal-soal lainnya. Lihat R. Subekti, Hukum
Perjanjian...Loc.Cit., h. 13.
212
"Pacta" berasal dari sebuah kata bahasa Latin "pactum" yang artinya perjanjian atau
persetujuan (agreement). Dari kata pactum itu lahirlah ungkapan pacta sunt
servanda yang berkembang dan diangkat menjadi kaidah hukum yang mengandung
makna Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi para pihak yang membuatnya, oleh sebab itu harus dilaksanakan dengan iktikad
baik (good faith). Di Indonesia, asas pacta sunt servanda dapat dijumpai dalam kaidah
hukum, sebagaimana dapat diketahui dalam Hukum Perjanjian [Buku Ketiga BW
Pasal 1338 ayat (1)], yaitu: Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Periksa M. Yahya Harahap,
Arbitrase Ditinjau dariOp. Cit., h. 87-88.
213
Perjanjian internasional dalam hal ini adalah perjanjian internasional menurut Viena
Convention 1969 on The Law of Treaties, Lihat Budiono Kusumohamidjojo, Suatu
studi terhadap aspek operasional Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum
Perjanjian Internasional. Bandung: Binacipta, 1986, hal. 15. Periksa pula Viena
Convention on the law of treaties and international organization or between
international organization., dalam International Legal Materials. Volume XXV,
Number 3, May 1986, h. 543-592.
127
Pada prinsipnya asas kebebasan berkontrak (freedom of contract)
tidak hanya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengajukan
poin-poin menyangkut pokok kontrak, akan tetapi meliputi pula kebebasan
untuk menyepakati langkah penyelesaian sengketa. Oleh karena itu,
melakukan pilihan forum atau pilihan jurisdiksi di luar pengadilan untuk
menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi tergolong dalam ruang
lingkup asas kebebasan berkontrak. Pilihan forum atau pilihan jurisdiksi
dapat dilakukan dengan cara-cara:
(i) mencantumkan suatu klausula atau ketentuan yang merupakan
bagian dari substansi kontrak yang berisi kesepakatan tentang
pilihan forum arbitrase tertentu yang berwenang menyelesaikan
sengketa, atau
(ii) para pihak membuat kesepakatan tersendiri dalam suatu akte
terpisah dari kontrak utama yang ditandatangani oleh para
pihak setelah terjadi sengketa
214
yang berisi kesepakatan untuk
menyelesaikan sengketa melalui forum arbitrase tertentu.
Di dalam arbitrase komersial internasional, pilihan forum atau pilihan
jurisdiksi sebagai perwujudan dari asas kebebasan berkontrak dinamakan
214
Klausula sebagaimana tersebut dalam poin (i) disebut pactum de compromitendo,
sedangkan akte sebagaimana tersebut dalam poin (ii) disebut acta compromis.
Bandingkan dengan Pasal 1020 ayat (2) Vierde Boek van Nederland Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering; dalam MOJ de Folter et al., Burgerlijke Rechtsvordering
en aanverwante Regelingen. Kluwer-Deventer, 1990, h. 198.
128
perjanjian arbitrase (agreement to arbitrate). Bahkan perjanjian arbitrase itu
merupakan dasar yang fundamental bagi para pihak yang menunjukkan
kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui forum arbitrase.
Oleh karena itu, perjanjian arbitrase seperti halnya perjanjian-perjanjian
yang lainnya, harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian.
215
Artinya,
kata sepakat
216
dalam perjanjian arbitrase tidak boleh cacat atau tidak sah.
Terdapat dua macam perjanjian arbitrase. Pertama, "agreement to
submit future disputes to arbitration," atau lazim dinamakan klausula
arbitrase (arbitration clause)
217
sebagai bagian tak terpisahkan dari kontrak
utama (principal agreement) para pihak. Kedua, "agreement to submit
existing disputes to arbitration" atau secara singkat disebut "submission
agreement."
218
Bentuk yang pertama yakni klausula arbitrase (arbitration clause),
berkenaan dengan sengketa yang baru akan terjadi di kemudian hari. Oleh
sebab itu, rumusan klausula arbitrase tidak selalu dapat dibuat secara rinci,
215
Pasal 1320 BW tentang syarat sahnya suatu perjanjian: (i) sepakat mereka yang
mengikatkan diri, (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (iii) suatu hal
tertentu, dan (iv) suatu sebab yang halal.
216
Kata sepakat dalam perjanjian arbitrase dianggap cacat apabila mengandung unsur-
unsur kekeliruan (dwaling), paksaan (dwang), dan/atau adanya penipuan (bedrog);
Lihat juga Pasal 1321 BW.
217
...which deals with disputes which may arise in the future, does not usually go into
too much detail, since it is not known what kind of disputes will arise and how they
should best be handled. Lihat, Alan Redfern, Law and Practice of... Op. Cit., h. 130.
218
...deals with an existing dispute and can be tailored exactly to fit the circumstances
and to provide in detail how the arbitral tribunal should deal with the dispute. A
submission agreement may take the form of a brief agreement to submit an existing
129
karena belum dapat diketahui sengketa apa yang kelak akan terjadi dan
belum diketahui pula bagaimana para pihak akan menyelesaikan sengketa
tersebut dengan cara yang paling baik. Bentuk ini disebut dengan pactum de
compromittendo. Sebaliknya, model yang kedua adalah submission
agreement, berkenaan dengan sengketa yang telah terjadi, sehingga rumusan
substansi agreement tersebut dapat disusun secara pasti dan rinci sesuai
dengan keadaan sengketanya, sekaligus pula dapat dirancang bagaimana
lembaga arbitrase akan menyelesaikan sengketa tersebut. Model yang kedua
ini dinamakan akta kompromis.
219
Kedua bentuk perjanjian arbitrase (agreement to arbitrate) di muka,
baik pactum de compromittendo maupun akta kompromis pada dasarnya
memiliki tujuan serta konsekuensi hukum yang sama. Artinya, perjanjian
arbitrase akan melahirkan kompetensi absolut
220
atau kewenangan mutlak
dispute to the procedures of an arbitral institution. Lihat, Alan Redfern, Law and...
Loc. Cit., h. 130.
219
Adalah perjanjian yang disepakati oleh para pihak bahwa perselisihan yang telah
terjadi diantara mereka diselesaikan melalui forum arbitrase. Syarat sahnya diatur
dalam Pasal 618 Rv, diantaranya sebagai berikut: (i) pembuatan akta kompromis
dilakukan setelah timbul sengketa; (ii) bentuknya harus akta tertulis, tidak boleh
dengan persetujuan lisan; (iii) harus ditandatanagani oleh kedua belah pihak. Bila para
pihak tidak dapat menandatangani, akta kompromis harus dibuat di depan notaris; (iv)
isi akta kompromis harus terdiri atas: a) masalah yang disengketakan; b) nama dan
tempat tinggal para pihak; c) nama dan tempat tinggal arbiter; dan d) jumlah arbiter
yang ditunjuk, harus ganjil. Lihat dalam M. Yahya Harahap, Abitrase Ditinjau... Op.
Cit., h. 66-67.
220
Mahkamah Agung berpendirian bahwa klausula arbitrase dengan sendirinya berbobot
kompetensi absolut, sehingga yurisdiksi mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian,
dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi kewenangan absolut Mahkamah
Arbitrase (arbitral tribunal). Oleh karena itu, setiap pengadilan menghadapi kasus
gugatan yang seperti itu, ada atau tidak ada eksepsi, harus tunduk pada ketentuan Pasal
130
forum arbitrase untuk memeriksa sengketa para pihak. Sebagai konsekuensi
hukumnya penyelesaian sengketa dimaksud akan ditarik keluar dari
yurisdiksi hakim pengadilan negeri dan selanjutnya menjadi kewenangan
forum arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Sebaliknya pengadilan negeri
menjadi tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa bersangkutan.
221
Namun demikian, kompetensi absolut forum arbitrase itu dapat gugur
serta beralih kembali menjadi kompetensi pengadilan negeri apabila ternyata
memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam bagian terakhir artikel II
ayat (3) Konvensi New York (KNY).
222
Artikel II ayat (3) KNY
selengkapnya dapat disimak berikut ini:
"The Court of a Contracting State, when seized of an action in a
matter in respect of which the parties have made an agreement within the
meaning of this article shall, at the request of one of the parties, refer the
parties to arbitration, unless if finds that the said agreement is null and
void, inoperative or incapable of being performed.
134 HIR, dan menyatakan dirinya tidak berwenang untuk mengadili. Lihat M. Yahya
Harahap, Arbitrase...Op. Cit., h. 87.
221
Lihat Pasal 3 Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS. Dari
Yurisprudensi MA pada waktu yang lalu, sebelum Indonesia memiliki Undang-undang
Arbitrase dapat diberikan contoh antara lain: Putusan Mahkamah Agung Nomor 2424
K/Sip/1981 tanggal 22 Februari 1982 dalam kasus Ahju Forestry Company Ltd.;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 dalam
kasus PT Asuransi Ramayana; dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 794
K/Sip/1982 tanggal 27 Januari 1983 dalam kasus PT Asuransi Royal Indrapura;
Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah Agung tentang Arbitrase. Mahkamah
Agung, Proyek Yurisprudensi, 1989.
222
Indonesia mensahkan "Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards" yang ditandatangani di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai
berlaku tanggal 7 Juni 1959, dengan memakai instrumen ratifikasi berupa Keputusan
Presiden RI No. 34 Tahun 1981 tanggal 5 Agustus 1981 LNRI Thn. 1981 No. 40.
131
Kompetensi forum arbitrase sebagai akibat adanya pilihan jurisdiksi
melalui perjanjian arbitrase (agreement to arbitrate), baik melalui klausula
arbitrase (arbitration clause) maupun melalui submission agreement, secara
implisit diakui dan dinyatakan dalam artikel II ayat (3) KNY. Bahwa
pengadilan dari negara penandatangan konvensi harus merujuk para pihak
ke forum arbitrase, menunjukkan betapa akibat adanya pilihan forum
pengadilan negeri menjadi tidak berwenang memeriksa sengketa dimaksud,
kecuali apabila ternyata dapat dibuktikan bahwa "... the said agreement is
"null and void, inoperative or incapable of being performed".
223
Namun
demikian kata-kata "the said agreement" dalam artikel II ayat (3) di atas,
ternyata tidak ditemukan penjelasannya. Apakah yang dimaksud dengan
agreement oleh konvensi adalah kesepakatan para pihak yang dituangkan
di dalam kontrak utama (main contract) yang di dalamnya termasuk memuat
klausula arbitrase (arbitration clause), ataukah yang dimaksud adalah
submission agreement yang dibuat secara terpisah dari kontrak utama.
Berdasarkan pembacaan lebih lanjut, tampaknya agreement
sebagaimana dimaksud dalam artikel II (3) KNY itu bukan agreement
dalam arti kontrak utama (main contract) sebagaimana disepakati para pihak,
223
A.J. van den Berg, menyatakan The last part of Article II (3) provides that a
court must refer the parties to arbitration unless the arbitration agreement is "null
and void, inoperative or incapable of being performed". Lihat dalam A.J. van den
Berg, "The New York Arbitration Convention of 1958 Towards a Uniform Judicial
Interpretation. The Hague: TMC Asser Institute, 1981, h. 154.
132
melainkan maksudnya adalah "agreement to arbitrate" atau perjanjian
arbitrase.
224
Oleh karena dalam Undang-undang Arbitrase Indonesia yang
baru jelas disebutkan bahwa perjanjian arbitrase itu dapat berupa klausula
arbitrase (arbitration clause) atau perjanjian tersendiri yang dibuat setelah
terjadi sengketa (submission agreement). Atas dasar pemahaman tersebut
maka mungkin saja terjadi suatu kontrak utama (main contract) berlaku sah,
sedangkan perjanjian arbitrasenya (agreement to arbitrate) "null and void,
inoperative or incapable of being performed."
Null and void, dapat diinterpretasikan "... where the arbitration
agreement is affected by some invalidity right from the beginning. It would
then cover matters such as the lack of consent due to misrepresentation,
duress, fraud or undue influence".
225
Sebagai contoh tidak adanya kehendak
yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak. Dapat juga
terjadi karena adanya unsur paksaan (duress), penipuan (fraud), atau
penyalahgunaan keadaan (undue influence). Undue influence atau misbruik
van omstandigheden, dapat terdiri atas dua unsur, pertama, menimbulkan
kerugian yang sangat besar dan kedua, menyalahgunakan kesempatan.
226
Kata "inoperative", diartikan bilamana "... the arbitration agreement
has ceased to have effect. The ceasing of effect of the arbitration agreement
224
Sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Thn. 1999.
225
Lihat A.J. van den Berg, The New York.., Op. Cit., h. 156.
133
may occur for a variety of reasons. One reason may be that the parties
have implicitly or explicitly revoked the agreement to arbitrate.
227
Sebagai
contoh misalnya, sengketa yang sama di antara pihak-pihak yang sama
pula telah diputus oleh arbitrase atau telah diputus oleh suatu pengadilan
tertentu (res judicata atau nebis in idem). Oleh karenanya arbitration
agreement itu tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat.
Sedangkan kata-kata "incapable of being performed", diartikan
bilamana "... the arbitration cannot be effectively set into motion. This may
happen where the arbitral clause is too vaguely worded, or other terms of
the contract contradict the parties intention to arbitrate.
228
Untuk hal ini
umpamanya perjanjian arbitrase disusun dalam kata-kata yang tidak jelas
atau tidak lengkap.
Berbicara mengenai masalah kompetensi atau kewenangan badan
peradilan untuk memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, bersangkut-
paut dengan norma hukum acara perdata. Persoalan kompetensi mengadili di
dalam hukum acara perdata berada pada ruang lingkup pembagian
kewenangan memeriksa perkara di antara badan peradilan yang tidak sejenis.
Hukum Acara Perdata di Indonesia menetapkan bahwa dalam hal-hal
terjadi perselisihan mengenai kewenangan mengadili atas suatu sengketa
226
Lihat Setiawan, Aneka Masalah...Op. Cit., h. 181.
227
A.J. van den Berg, Op. cit., h. 158.
228
Ibid,. h. 159.
134
yang karena sesuatu sebab menjadi tidak masuk kewenangan pengadilan
negeri, maka pengadilan harus tunduk pada ketentuan pasal 134 HIR.
229
Karenanya, hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk
mengadili. Ini berarti bahwa hakim karena jabatannya (ex officio) dapat
menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang
diajukan, meskipun tidak ada eksepsi
230
(tangkisan) dari pihak lawan.
Namun demikian, keadaan tidak berwenangnya hakim pengadilan negeri
untuk memeriksa sengketa yang timbul dari suatu kontrak yang
mencantumkan klausula pilihan forum arbitrase tidak mutlak sama sekali.
Artinya, pada suatu ketika hakim pengadilan negeri akan kembali berwenang
atau berkompeten untuk memeriksa sengketa yang terjadi, dalam hal-hal
sebagai berikut:
(a) apabila para pihak secara tegas mencabut klausula pilihan forum;
(b) apabila sengketa yang timbul nyata-nyata di luar substansi kontrak;
231
229
Pasal 134 HIR menyatakan: "Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu
perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap saat pemeriksaan
perkara itu boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim
sendiri wajib mengakui itu karena jabatannya."
230
Mengenai eksepsi dan kewenangan hakim dalam mengadili ini secara rinci lebih jauh
dapat dibaca di dalam Buku: Hugenholtz/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands
Burgerlijk Procesrecht - (Vijftiende druk). s-Gravenhage: VUGA Uitgeverij B.V.,
1988, h. 169-174.
231
Frans Liemena, Klausula Arbitrase dihubungkan dengan Kompetensi Pengadilan
Negeri; dalam Varia Peradilan, Tahun III Nomor 29, Februari 1988, h. 188. Bdgk.
Erman Rajagukguk, Keputusan Pengadilan Mengenai Beberapa Masalah Arbitrase;
dalam Abdul Rahman Saleh et al., Arbitrase Islam Di Indonesia. Jakarta: BAMUI &
Bank Muamalat, 1994, h. 75.
135
(c) putusan yang dijatuhkan di luar kewenangan forum arbitrase atau
bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan yang berlaku,
sehingga hakim menganggap kausanya tidak halal.
Sedangkan apabila sengketa yang timbul itu sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak, maka forum arbitrase yang dipilih itu tetap akan
memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa dimaksud.
Berkaitan dengan hal di atas, berikut ini dapat disimak putusan
pengadilan yang menggambarkan tentang kompetensi hakim pengadilan
negeri dalam kaitannya dengan klausula arbitrase. Putusan yang dimaksud
antara lain putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
232
dalam kasus antara
PT Balapan Jaya (penggugat) dengan Ahju Forestry Ltd (tergugat). Di
dalam eksepsinya tergugat (Ahju Forestry Ltd.) antara lain menyatakan
bahwa: "...karena adanya arbitration clausule yang sudah disetujui kedua
belah pihak dan karenanya mengikat mereka sebagai Undang-undang
(Pasal 1338 BW), maka sengketa ini tidak dapat diperiksa oleh pengadilan
tetapi harus diselesaikan oleh forum arbitrase yang telah dimufakati dalam
perjanjian para pihak itu. Atas dasar itu pula Pengadilan Negeri Jakarta
Utara harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara
ini." Akan tetapi di dalam diktum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara,
232
Tanggal 18 Desember 1980, Nomor 113/1980.G.
136
antara lain disebutkan: "menyatakan eksepsi tergugat, baik tentang
kompetensi absolut maupun kompetensi relatif tidak beralasan hukum,
karenanya ditolak."
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 18 Desember 1980 Nomor
113/1980.G di atas. Dengan demikian Pengadilan Tinggi Jakarta,
233
juga
menolak eksepsi tergugat/pembanding (Ahju Forestry Co.Ltd) mengenai
kompetensi absolut forum arbitrase. Sedangkan pada permohonan kasasi,
penggugat untuk kasasi dahulu tergugat/pembanding (Ahju Forestry
Co.Ltd.), mengajukan keberatan. Di dalam memori kasasinya antara lain
menyatakan bahwa: Sesuai dengan pasal 15 Basic Agreement for Joint
Venture, para pihak telah mengadakan persetujuan bahwa setiap sengketa
yang timbul akan diselesaikan melalui forum arbitrase. Oleh karena itu,
putusan judex facti telah melanggar ketentuan mengenai kompetensi
absolut.
Berdasarkan alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung mengabulkan
permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi. Dalam
pertimbangannya, Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwa
keberatan pemohon kasasi pada pokoknya dapat dibenarkan, judex facti
233
Tanggal 7 Mei 1981 Nomor 57/1981 P.T. Perdata, dalam Sudargo Gautama, Aneka
Masalah Hukum ...Op. Cit., h. 180.
137
telah salah menerapkan hukum, sesuai eksepsi penggugat untuk
kasasi/tergugat asal, pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili
perkara ini.
234
Mahkamah Agung memutuskan
235
(i) menerima permohonan
kasasi dari Ahju Forestry Co.Ltd.; (ii) membatalkan putusan Pengadilan
Tinggi Jakarta; dan (iii) menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara
tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut.
Demikian pula halnya dalam kasus PT Maskapai Asuransi Ramayana
vs. Sohandi Kawilarang,
236
Mahkamah Agung juga telah membatalkan
putusan judex facti (Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi
Jakarta). Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung antara lain
menyatakan, bahwa polis asuransi kecelakaan tanggal 10 Agustus 1978
Nomor 210.PA/20.318, di bawah ketentuan umum dicantumkan (sub 7)
bahwa "pertikaian berkenaan dengan polis ini, diselesaikan dalam tingkat
tertinggi di Jakarta oleh 3 (tiga) orang juru pisah (arbiter)."
237
Dengan demikian pengadilan negeri tidak berwenang memeriksa dan
mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 14 tahun 1970, khususnya memori penjelasan pasal tersebut.
Selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun hal itu tidak
234
Himpunan Putusan MA tentang Arbitrase; Op. Cit., h. 34.
235
Tanggal 22 Februari 1982 Nomor 2924 K/Sip/1981. Ibid., h. 185.
236
PT Asuransi Ramayana sebagai tergugat dalam konvensi pada Pengadilan Negeri
Jakarta Barat dengan putusan tanggal 2 Juli 1980 Nomor 333/1979; Putusan Banding
Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Nopember 1981 Nomor 236/1980.
138
diajukan sebagai eksepsi oleh pihak tergugat namun berdasarkan pasal 134
HIR, hakim berwenang untuk menambahkan pertimbangan dan alasan
hukum secara jabatan.
Kemudian putusan yang serupa juga dapat dijumpai pada kasus PT
Asuransi Royal Indrapura.
238
Mahkamah Agung di dalam pemeriksaan
kasasi terhadap kasus ini mengemukakan alasan antara lain, di dalam polis
tanggal 10 Agustus 1978 No. 49/00137/08, pada bagian bawah tentang
conditions diuraikan bahwa: All differences arising out of this policy shall
be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the
parties in difference or if they can not agree upon a single arbitrator".
Mahkamah Agung berpendapat, seandainya para pihak hendak
menyimpang dari ketentuan polis tersebut, maka harus secara tegas
dikemukakan oleh para pihak pada waktu mengajukan gugatan di
pengadilan negeri. Dari beberapa putusan Mahkamah Agung di muka,
diperoleh suatu gambaran bahwa pada dasarnya Mahkamah Agung
menganut prinsip pacta sunt servanda. Artinya, klausula arbitrase mengikat
secara mutlak terhadap para pihak yang membuatnya, sehingga klausula
arbitrase langsung melahirkan kompetensi absolut forum arbitrase sesuai
237
Putusan tersebut dimuat dalam Yurisprudensi Indonesia 3. Jakarta: Ichtiar Baru
Hoeve, 1990, h. 6.
238
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Juli 1980 Nomor 869/1979.G.;
Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Nopember 1981 Nomor 225/1980/PT.
Perdata; Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Januari 1983, Nomor 794 K/Sip/1982.
139
pilihan para pihak. Sikap Mahkamah Agung semacam itu dinyatakan pada
saat memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak
yang gugatannya diajukan kepada pengadilan negeri sedangkan kontrak
bersangkutan mencantumkan klausula arbitrase.
239
Sikap Mahkamah Agung yang dalam tingkat kasasi telah membatalkan
putusan judex facti yang telah mengabulkan gugatan penggugat, sedangkan
kontrak para pihak mencantumkan klausula arbitrase, merupakan bukti
bahwa badan peradilan tertinggi di Indonesia itu masih senantiasa
mengapresiasi kebebasan para pihak untuk melakukan pilihan forum.
C. Pilihan Forum Arbitrase sebagai Fenomena Penyelesaian Sengketa
Arbitrase sesungguhnya tidak termasuk bentuk alternatif penyelesaian
sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) karena arbitrase
pada dasarnya tergolong kelompok Adjudicatory methods of settlement atau
adjudication,
240
yang terdiri atas dua prototipe yakni litigasi di pengadilan
239
Bandingkan pula putusan Mahkamah Agung dalam perkara PT. Arpeni Pratama Ocean
Line melawan PT. Shorea Mas, Nomor 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988; Lihat
dalam Yurispudensi Indonesia 3. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, h. 103;
Putusan tersebut juga mengenai ketidakwenangan pengadilan dalam hal adanya
klausula arbitrase.
240
Menurut Goldberg, Sander & Roger, Adjudication is a process in which disputans
present proofs and arguments to a neutral third party who has the power to hand down
a binding decision, generally based on objective standards. Lihat Christian Buhring
Uhle, Arbitration and Mediation in International Business. The Hague: Kluwer
Law International, 1996, h. 43. Bdgk. Sofyan Mukhtar, Mekanisme Alternatif Bagi
Penyelesaian Sengketa Perdata-Dagang (Dispute Resolution); dalam Varia
Peradilan No. 48, 1989, h. 126.
140
(public adjudication) dan arbitrase (private adjudication). Sedangkan
metode ADR termasuk dalam kelompok non-adjudicatory methods of
settlement,
241
yang meliputi mediasi (mediation) dan konsiliasi
(conciliation).
242
Oleh karena itu, berbeda dengan arbitrase, mediasi dan
konsiliasi tidak dapat menghasilkan putusan yang mengikat yang dapat
dilaksanakan. Mediator tidak dapat memaksa para pihak untuk mencapai
penyelesaian; begitu pula konsiliator tidak memiliki kekuasaan untuk
menjatuhkan putusannya kepada para pihak.
243
Persoalannya lalu mengapa arbitrase menjadi fenomena
244
dalam
penyelesaian sengketa, sehingga orang memilih arbitrase sebagai forum bagi
penyelesaian sengketanya? Benarkah karena arbitrase berproses cepat dan
241
Meliputi negosiasi (negotiation), konsiliasi (conciliation), mediasi (mediation), dan lain-
lain. Lihat David H. Ott, Public International Law... Op. Cit., h. 333-334. Bdgk. Liem
Lei Theng, Court Connected ADR in Singapore; Makalah Seminar Court
Connected ADR, Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 21 April 1999. Namun demikian
penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (ADR) memang bukan
merupakan panacea yang mampu mengatasi semua sengketa. Lihat Arthur Mariot,
The Role of ADR in the Settlement of Commercial Disputes; dalam Asia Pacific Law
Review, Vol. 1 Summer 1994, h. 1-19.
242
Menurut Hakim Manly O. Hudson, Conciliation is a process of formulating proposals
of settlement after an investigation of the facts and an effort to reconcile opposing
contentions, the parties to the dispute being left free to accept or reject the proposals
formulated. Periksa, J.G. Starke, Introduction...Op. Cit., h. 489
243
Alan Redfern selanjutnya mengemukakan: If the parties are seeking a decision on
their dispute, as opposed to a negotiated settlement, then mediation or conciliation is
not for them. Parties may try mediation or conciliation first and then, if this fails,
resort to arbitration. Nor should the mediator or conciliator change his role and act as
an arbitrator. Lihat Alan Redfern et.al., Law and Practice...Op. Cit., h. 27.
244
Fenomena dalam arti fakta atau kenyataan yang dapat disaksikan dengan pancaindera
dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah. Lihat Kamus Besar Bahasa
Indonesia.
141
berbiaya murah? Ternyata bukan itu yang menjadi alasan utama.
245
Yang
menjadi andalan pihak-pihak yang memilih arbitrase adalah justru kualitas
(quality) dari para arbiter berupa keahlian dalam bidang masing-masing
arbiter. Keahlian merupakan salah satu jaminan terhadap kepercayaan.
Tanpa ada kepercayaan, forum arbitrase tidak akan dapat berfungsi dengan
baik.
246
Demikian pula dengan lembaga pengadilan, sebagai lembaga tempat
menyelesaikan beragam sengketa di dalam masyarakat, pengadilan akan
dapat menjalankan tugas dengan baik apabila mendapat kepercayaan dari
pihak-pihak yang bersengketa.
247
Pengadilan bukanlah diartikan semata-
mata sebagai badan untuk mengadili, melainkan sebagai pengertian yang
abstrak, yaitu hal memberikan keadilan. Hal memberikan keadilan
berarti yang bertalian dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam
245
Banyak proses pemeriksaan arbitrase berlangsung bertahun-tahun lamanya dan tidak
perlu diherankan bahwa oleh karenanya memakan biaya yang cukup besar. Lihat
Setiawan, Klausula Arbitrase dalam Teori dan Praktek; dalam Varia Peradilan
Tahun IX No. 104, Mei 1994, h. 125-139 [127].
246
Forum arbitrase pada asasnya memiliki fungsi yang sama dengan lembaga peradilan.
Keduanya merupakan pihak ketiga yang (seharusnya) tidak memihak. Kedua-duanya
bersandar pada satu sendi pokok yang sama, yaitu kepercayaan. Tanpa adanya
kepercayaan, kedua lembaga itu tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Lihat
Setiawan, Kalusula ...Loc Cit., h. 128.
247
Satjipto Rahardjo mengemukakan: warga masyarakat bersedia untuk membawa perkara-
perkaranya itu ke pengadilan, karena: (i) Percaya bahwa di tempat itu mereka akan
memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; (ii) Percaya bahwa pengadilan
merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak
korup, dan nilai-nilai utama lainnya; (iii) Percaya bahwa waktu dan biaya yang mereka
keluarkan tidak sia-sia; dan (iv) Percaya bahwa pengadilan merupakan tempat bagi
orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum. Periksa Satjipto Rahardjo,
Hukum, Masyarakat dan Pembangunan. Bandung: Alumni, 1980, h. 106-107.
Demikian pula Setiawan menyatakan: ...bahwa tiang utama lembaga peradilan adalah
prinsip kepercayaan. Para pencari keadilan menyerahkan penyelesaian perkara kepada
142
memberi keadilan, yaitu memberikan kepada yang bersangkutan, konkretnya
kepada yang mohon keadilan, apa yang menjadi haknya atau apa
hukumnya.
248
Pengadilan berfungsi amat vital dalam menopang ide-ide
hukum (das sollen) menjadi kenyataan hukum (das sein). Oleh karena itu,
hakim sebagai aktor penegak hukum utama di pengadilan harus benar-benar
melakukan konkretisasi hukum dengan tetap memperhitungkan perasaan
keadilan masyarakat. Persoalan utama yang dihadapi lembaga peradilan kita
adalah cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan normatif-
prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Hakim hanya menangkap
apa yang disebut keadilan hukum (legal justice), tetapi gagal menangkap
keadilan masyarakat (social justice).
249
Hakim telah meninggalkan
pertimbangan hukum yang berkeadilan dalam putusan-putusannya.
Akibatnya, kinerja pengadilan sering disoroti karena sebagian besar dari
putusan-putusan pengadilan masih menunjukkan lebih kental bau
formalisme-prosedural ketimbang kedekatan pada rasa keadilan warga
pengadilan, karena percaya bahwa mereka akan memperoleh keadilan. Lihat,
Setiawan, Aneka Masalah Hukum...Op. Cit., h. 370.
248
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di
Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia.
Bandung: Kilatmadju, 1971, h. 2.
249
Oleh karena itu, kohesivitas (paduan) antara hukum positif dan nilai-nilai keadilan
dalam masyarakat menjadi conditio sine qua non untuk menghindari keadaan dimana
hukum ada di puncak menara gading yang jauh dari jangkauan pemahaman keadilan
masyarakat. Lihat, A. Ahsin Thohari, Dari Law Enforcement ke Justice
Enforcement, dalam Kompas, Rabu, 3 Juli 2002.
143
masyarakat.
250
Oleh sebab itu, sulit dihindari bila semakin hari semakin
berkembang rasa tidak percaya dan sikap sinis masyarakat terhadap institusi
pengadilan.
251
Ternyata keluhan terhadap lembaga peradilan tidak hanya menyangkut
perolehan keadilan semata sebagaimana diuraikan di muka, melainkan juga
berkaitan dengan proses peradilan yang lamban. Diakui oleh seorang hakim
agung bahwa sebuah proses persidangan dapat berlangsung hingga enam
tahun sampai ada putusan hakim yang berkekuatan tetap.
252
Padahal
Mahkamah Agung sendiri sesungguhnya telah menyadari bahwa apabila
penyelesaian perkara lambat dapat berakibat: (i) menenggelamkan
kebenaran dan keadilan ke dalam lembah yang curam, sehingga sulit diraih
oleh masyarakat pencari keadilan; (ii) menimbulkan ketidakpastian
(uncertainty) yang berlarut-larut di antara para pihak yang berperkara, yang
membuat mereka berada dalam keresahan yang berkepanjangan; (iii) para
250
Achmad Ali, Pengadilan yang yang tak Berkeadilan; dalam Kompas, Jumat, 08 Juni
2001; Berkenaan dengan hal tersebut, Satjipto Rahardjo mengemukakan: Sejak
hukum modern memberi peluang besar terhadap berperannya faktor prosedur, atau
formalitas, atau tata cara dalam proses hukum, perburuan terhadap keadilan menjadi
semakin rumit. Kerusakan dan kemerosotan dalam perburuan keadilan melalui hukum
modern disebabkan permainan prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan
apakah pengadilan itu tempat mencari keadilan atau kemenangan? Lihat Satjipto
Rahardjo,Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif; dalam Kompas, Sabtu, 12
Oktober 2002.
251
Masyarakat Indonesia kini cenderung menjadi bad trust society. Konsekuensi
logisnya, menyebar dimana-mana perilaku kekerasan dan tindakan main hakim
sendiri. Lihat Achmad Ali, Pengadilan yang...Loc. Cit.,.
252
Selain lambat, putusan hakim juga sering dinilai kontradiktif dan tidak jarang putusan
hakim itu tidak dapat dieksekusi. Pernyataan dari seorang Hakim Agung HP
144
pihak yang berperkara mengalami kerugian ekonomis yang tidak sedikit,
sehingga keadaan semacam itu memberi kesan seolah-olah badan peradilan
telah menjadi alat kekuasaan yang berperan menghambat laju perkembangan
ekonomi sosial.
253
Namun demikian, kelambatan penyelesaian perkara
melalui pengadilan karena proses pemeriksaan yang berbelit dan formalistik,
itu bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupakan problema yang
menyeluruh di semua negara.
254
Oleh karena itu, agar sistem peradilan menjadi baik sehingga
memberikan jaminan untuk melahirkan putusan hakim yang benar-benar
dapat mentransformasikan ide keadilan, maka menurut Richard Meredith
Jackson
255
dalam bukunya yang berjudul The Machinery of Justice in
England, ada tiga prasyarat utama bagi suatu (sistem) peradilan yang baik,
Panggabean, Kelambanan Proses Peradilan Dikeluhkan. dalam Kompas, Jumat, 23
April 1999.
253
M. Yahya Harahap, Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara; dalam Varia
Peradilan Tahun XI No. 121, Oktober 1995, h. 100-119 [100].
254
Dicontohkannya, di Jepang yang dianggap sebagaia negara maju, proses penyelesaian
perkara di peradilan Jepang sangat lama. Rata-rata memakan waktu 10 sampai dengan
15 tahun. Bahkan di tingkat pertama saja rata-rata 3 sampai 5 tahun. Di Korea Selatan,
Hongkong, dan Singapura, proses penyelesaian perkara melalui badan peradilan
dianggap lama dan biayanya tinggi. Begitu pula yang terjadi di Amerika Serikat. Di
samping proses persidangan memakan waktu lama, kebanyakan masyarakat Amerika
berpendapat, penyelesaian perkara perdata melalui sistem peradilan perdata terkesan:
(i) tidak adil (unfair), karena lebih memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga
besar atau orang kaya; (ii) secara tidak wajar menghalangi rakyat biasa (ordinary
citizens) untuk berperkara di pengadilan; Lihat, M. Yahya Harahap, Citra Penegakan
Hukum; dalam Varia Peradilan Tahun X Nomor 117, Juni 1995, h. 143-161 [149 -
150]. Pengadilan memang tidak didesain untuk melakukan pekerjaan yang efektif dan
efisien. Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa dengan cara litigasi bisa bertahun-tahun.
Bahkan sampai puluhan tahun. Lihat pula, M. Yahya Harahap, Pengadilan Tak
Efektif Selesaikan Perkara; dalam Kompas, 16 Juli 1999.
145
yaitu: ...they have a known procedure, their behaviour is fairly predictable
and they are eminently respectable. Akan tetapi ketiga prasyarat untuk
sistem peradilan yang baik itu pun mustahil dapat diwujudkan apabila
komponen lain dalam proses penegakan hukum tidak menunjang ke arah
upaya perbaikan sistem peradilan tersebut. Persoalannya, bukan semata-mata
lembaga pengadilan dan hakim yang menyebabkan perilaku dan proses
peradilan menjadi unfair serta unpredictable, melainkan juga
disebabkan oleh pihak-pihak lain yang langsung maupun tidak langsung
bersinggungan dengan proses hukum dan peradilan.
256
Menghadapi realita proses penyelesaian perkara pada badan peradilan
sebagaimana diuraikan di atas, maka pencarian dan pelembagaan model-
model penyelesaian sengketa yang lain
257
menjadi fenomena pada
masyarakat pencari keadilan. Demikian pula penggunaan arbitrase sebagai
bentuk lain dalam penyelesaian sengketa komersial pada dasarnya
merupakan konsekuensi logis dari realita yang berkembang. Di samping itu
juga karena arbitrase telah lebih populer dibandingkan model penyelesaian
255
Setiawan, Putusan Hakim Sebagai Transformasi Ide Keadilan; dalam Varia
Peradilan Tahun VII No. 80, Mei 1992, h. 136-146 [146].
256
Mereka yang langsung bersinggungan misalnya: jaksa, polisi, dan advokat. Sementara
pihak-pihak lain yang disinyalir berpotensi memberikan pengaruh seperti pihak militer,
pejabat sipil, pengusaha, calo perkara, dan keluarga. Bahwa campur tangan pihak-
pihak tersebut telah sedemikian jauh dan besar sehingga bukan mustahil kalau
pengaruh jeleknya lebih besar terhadap proses penegakan hukum. LihatLembaga
Pengadilan, Toko Hukum, Pasar Hukum. Di dalam Kompas, Senin, 15 Maret 1999.
146
sengketa alternatif lainnya, serta mekanisme arbitrase dengan segala
kelemahan dan kelebihannya, paling mendekati proses berperkara di
pengadilan.
258
Perbedaan arbitrase dengan proses di pengadilan di antaranya:
Pertama, arbitrase bukan berlandaskan yuridis formal tetapi kebenaran dan
kepatutan (ex aequo et bono). Kedua, keahlian dan integritas yang dimiliki
arbiter yang harus merujuk pada kualitas yang patut dibanggakan, sehingga
arbiter dituntut harus mampu meyakinkan pihak-pihak yang berperkara
sebagai pihak yang bebas dan tidak memihak.
259
Di sinilah antara lain letak
perbedaannya arbitrase dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan
negeri.
Walaupun penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase bukan suatu
hal baru di Indonesia, akan tetapi penggunaan arbitrase sebagai suatu metode
penyelesaian sengketa masih terbatas dalam bidang hukum perikatan,
khususnya dalam sengketa-sengketa komersial. Sedangkan pada negara-
257
Seperti bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa melalui Mediasi, Mini Trial,
Konsiliasi, Adjudication; Lihat M. Yahya Harahap, Citra Penegakan...Op. Cit., h.
152-158.
258
Putusan yang diambil arbitrase langsung final dan mengikat, meski putusan arbitrase
harus diserahkan dan didaftarkan kepada panitera pengadilan negeri, namun pada
dasarnya putusan arbitrase (arbitral award) terkandung kekuatan eksekutorial. Oleh
karena apabila pihak yang kalah tidak menaati dan memenuhi putusan secara sukarela,
pihak yang menang dapat meminta eksekusi melalui pengadilan negeri. Sedangkan
penyelesaian perkara melalui Mediasi, Mini Trial, Konsiliasi, dan Adjudikasi, tidak
dapat meminta eksekusi melalui pengadilan. Untuk mengatasi kelemahan tersebut,
para pihak dapat membuat kesepakatan dalam bentuk klausula, apabila Mediasi, Mini
Trial, Konsiliasi, atau Adjudikasi gagal, maka Mediator, Konsiliator, dan Adjudikator,
langsung bertindak sebagai Arbitrator. Lihat, M. Yahya Harahap, Citra
Penegakan... Loc. Cit., h. 160.
259
Komar Kantaatmadja, Beberapa Permasalahan... Op. Cit., h. 67.
147
negara lain, misalnya di Amerika Serikat, arbitrase telah dipakai sebagai
metode alternatif (alternative dispute resolution),
260
dalam berbagai bidang.
Robert Coulson dalam bukunya Business Arbitration-What You Need to
Know, mengemukakan:Many business disputes are resolved by
arbitration.
261
Di dalamnya disebutkan bidang-bidang apa saja yang
sengketanya dapat diselesaikan dengan menggunakan forum arbitrase.
Umpamanya, bidang industri konstruksi, industri logam, tekstil, asuransi,
dan juga perdagangan internasional. Bahkan tidak hanya itu, Coulson masih
menegaskan, "... Many thousands of other controversies are also
arbitrated...". Sebagai contoh disebutkan, individual employee grievances,
partnership and private corporation problems, patent and licensing disputes,
and disagreement between author and publishers. Many cases originate
from the real estate industry, the securities industry, and from computer
disputes. Lebih dari itu, sengketa dalam bidang hukum keluarga seperti
halnya perceraian (divorce settlement) juga dapat diselesaikan melalui
proses arbitrase.
262
260
Steven C. Nelson, Alternatives to Litigation of International Disputes, dalam The
International Lawyer, Vol. 23, No. 1, 1989, h. 187.
261
Lihat Robert Coulson, Business Arbitration-What You Need to Know., New York:
American Arbitration Association, 1987, h. 10.
262
Robert Coulson, Business Arbitration... Loc Cit., h. 11.
148
BAB III
SUBJEK DAN OBJEK SENGKETA KOMERSIAL
DALAM FORUM ARBITRASE
A. Pihak-Pihak Berperkara dalam Forum Arbitrase
Pada dasarnya pihak-pihak berperkara dalam proses arbitrase tidak
berbeda dengan pihak-pihak dalam sengketa perdata pada umumnya di
pengadilan negeri, yaitu sekurang-kurangnya terdapat dua pihak. Yang
berbeda adalah persoalan istilah penyebutan pihak-pihak yang berperkara.
Para pihak
263
dalam sengketa perdata pada pengadilan negeri disebut
penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam proses pemeriksaan sengketa
pada forum arbitrase penyebutan pihak-pihak dalam perkara sedikit berbeda.
Penyebutan pihak-pihak dalam forum arbitrase telah dibakukan dan standar,
baik dalam literatur maupun dalam arbitration rules. Sebutan untuk pihak
yang membuat tuntutan adalah claimant
264
sedangkan sebutan untuk
263
Dalam sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat
(eiser, plaintiff) yang mengajukan gugatan, dan pihak tergugat (gedaagde, defendant).
Dan biasanya orang yang langsung berkepentingan sendirilah yang aktif bertindak
sebagai pihak di muka pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat,
mereka ini merupakan pihak materiil, karena mereka mempunyai kepentingan langsung
di dalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus juga merupakan pihak formal,
karena merekalah yang beracara di muka pengadilan. Mereka bertindak untuk
kepentingan dan atas namanya sendiri. Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum
Acara...Op. Cit., h. 47-48.
264
Claimant adalah seseorang yang membuat tuntutan yang lazim disebut penggugat
atau plaintiff. Dalam pengertian hukum, claimant sebagaimana disebut dalam Article
3 UNCITRAL Arbitration Rules:The party initiating recourse to arbitration
(hereinafter called the claimant) shall give to the other party (hereinafter called the
respondent) a notice of arbitration. Lihat Alan Redfern et al, Law and
149
pihak tertuntut adalah respondent.
265
Sementara itu di dalam Peraturan
Prosedur Arbitrase (PPA) Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau
dikenal dengan BANI Rules, pihak-pihak yang bersengketa disebut dengan
istilah pemohon
266
untuk claimant dan termohon
267
untuk
respondent. Sesungguhnya penggunaan istilah-istilah pemohon dan
termohon dalam forum arbitrase kurang sejalan dengan sifat penyelesaian
perkara dalam forum arbitrase itu sendiri yang tergolong jurisdictio
contentiosa.
268
Oleh karena istilah pemohon dan termohon itu lebih tepat
digunakan untuk kasus-kasus yang sifatnya tidak mengandung sengketa atau
termasuk dalam jurisdictio voluntaria.
269
Walaupun sebenarnya istilah
sukarela untuk jurisdictio voluntaria itu pun kurang tepat, karena pada
dasarnya peradilan contentiosa pun sesungguhnya bersifat sukarela.
Bukankah ada tidaknya suatu perkara yang masuk untuk diperiksa di
Practice...Op. Cit., h. 690. Oleh karena itu, pihak yang mengambil inisiatif
mengajukan tuntutan kepada seseorang melalui forum arbitrase dinamakan claimant.
Lihat M. Yahya Harahap, Arbitrase...Op. Cit., h. 133.
265
Respondent, adalah orang yang dituntut atau orang yang dijadikan sebagai tertuntut
dan lazim disebut tergugat. Dari segi pengertian hukum respondent adalah pihak
yang ditarik atau yang dijadikan sebagai tergugat oleh pihak yang menggugat dalam
suatu proses pemeriksaan badan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan
memutus suatu persengketaan. Lihat, M. Yahya Harahap, Arbitrase...Loc. Cit., h. 133.
266
Lihat Pasal 2 ayat (3) Peraturan Prosedur Arbitrase (PPA) BANI.
267
Lihat Pasal 7 ayat (1) PPA BANI.
268
Jurisdictio contentiosa yaitu peradilan yang menyelesaikan perselisihan antara dua
pihak yang bertentangan pendirian dan kepentingan, atau perkara yang mengandung
sengketa. Lihat Fockema Andreaes Rechtsgeleerd Handwoordenboek. Bandung:
Binacipta, 1983, h. 228.
269
Jurisdictio voluntaria adalah peradilan sukarela yang tidak melakukan pekerjaan
menyelesaikan atau memutuskan perkara. Fockema Andreaes...Loc. Cit., h. 228.
150
pengadilan itu pun terserah kepada pihak yang berkepentingan untuk
mengajukan atau tidak tuntutan haknya, baik berupa permohonan maupun
gugatan ke pengadilan. Artinya, diajukan tidaknya suatu tuntutan hak ke
pengadilan sepenuhnya terserah kepada pihak yang berkepentingan.
270
Memang diakui bahwa arbitrase sendiri merupakan badan volunter,
karena sebagai lembaga swasta jurisdiksi arbitrase lahir berdasarkan
kesepakatan sukarela dari para pihak. Namun demikian, sekalipun kelahiran
atau eksistensi arbitrase bersifat volunter, sekali forum arbitrase lahir, forum
tersebut formal dan legal sebagai badan kuasa yang berwenang mutlak
untuk menyelesaikan dan memutus sengketa. Oleh karena itu, tidak tepat
juga untuk mengidentikkan sifat keberadaan volunternya dengan sifat
persengketaan. Sifat permasalahan persengketaan tetap saja berbobot
contentiosa, tidak berubah menjadi gugat yang berbobot volunter. Demikian
pula jika ditinjau dari segi doktrin dan tata tertib beracara, menggunakan
istilah pemohon dan termohon untuk menyebut para pihak dalam perkara
pada forum arbitrase sangat tidak sesuai. Penyebutan pihak-pihak dengan
istilah itu memberi kesan seolah-olah perkara yang diajukan kepada forum
arbitrase bersifat volunter dan putusan yang dapat dijatuhkan hanya bersifat
270
Pembedaan peradilan sesungguhnya dengan peradilan volunter disebabkan karena
perbuatan hakim dalam peradilan volunter lebih merupakan perbuatan di bidang
administratif, sehingga putusannya merupakan satu penetapan (Pasal 236 HIR, 272
Rbg.). Bahwa yang termasuk peradilan volunter adalah semua perkara yang oleh
151
declaratoir.
271
Padahal arbitrase mempunyai wewenang penuh untuk
menjatuhkan putusan yang mengandung amar condemnatoir.
272
Faktor lain yang perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak dalam
forum arbitrase menyangkut masalah kualifikasi cakap
273
menurut hukum.
Mengingat forum arbitrase itu terbentuk atas dasar kesepakatan para pihak,
baik melalui pactum de compromittendo maupun akta kompromis,
maka sebelum menjadi claimant maupun respondent, pihak-pihak yang
hendak berperkara di hadapan forum arbitrase tentu saja harus tergolong
cakap untuk membuat suatu kontrak. Seseorang yang dianggap cakap
menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum apa pun, maka yang
undang-undang ditentukan harus diajukan dengan permohonan, sedang selebihnya
termasuk peradilan contentiosa. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Op. Cit., h. 4
271
Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan, menegaskan
suatu keadaan hukum semata-mata. Contohnya: putusan yang menyatakan mengenai
seorang anak yang menjadi sengketa adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang
sah. Atau setiap putusan yang bersifat menolak gugatan tergolong putusan declaratoir.
Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Loc Cit., h. 189.
272
Putusan condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan
untuk memenuhi prestasi. Hukuman yang dimaksud di dalam putusan semacam ini
hanya terjadi berhubungan dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan atau
undang-undang, yang prestasinya terdiri atas: memberi, berbuat, dan tidak berbuat.
Pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah
uang. Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara... Op. Cit., h. 189. Bdgk. M. Yahya
Harahap, Arbitrase Op. Cit., h. 133.
273
Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baligh dan sehat pikirannya,
adalah cakap menurut hukum. Hanya orang-orang yang secara eksplisit ditentukan oleh
hukum saja yang tidak tergolong cakap menurut hukum, yaitu: (1) orang-orang yang
belum dewasa, (2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, (3) orang perempuan
dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-undang dan semua orang yang menurut
Undang-undang telah dilarang untuk membuat perjanjian tertentu. Lihat Pasal 1330
BW; dalam R. Subekti, Hukum Perjanjian...Op. Cit., h. 17.
152
bersangkutan mutatis mutandis
274
akan tergolong cakap pula untuk menjadi
pihak dalam forum arbitrase.
275
Artinya, setiap orang dewasa yang sehat
pikirannya serta tidak dikecualikan oleh undang-undang untuk melakukan
perbuatan hukum, maka orang tersebut dapat menjadi pihak di dalam
sengketa di depan forum arbitrase. Sama juga dengan pihak-pihak dalam
perkara perdata pada pengadilan negeri, di dalam forum arbitrase juga
dikenal ada istilah pihak materiil
276
dan pihak formal.
277
Proses penyelesaian sengketa di hadapan forum arbitrase bersifat
sangat tertutup dan rahasia, sehingga keberadaan pihak-pihak materiil tidak
dapat diketahui oleh orang-orang yang tidak memiliki kepentingan langsung
dengan sengketa bersangkutan. Oleh karena itu, ketika proses penelitian ini
berlangsung dan pengumpulan informasi sedang dilakukan, pihak materiil
tidak pernah dapat dihubungi karena keberadaan mereka sangat rahasia
(confidential). Informasi untuk keperluan mendeskripsikan keadaan sosial
274
Mutatis mutandis (Lat): with necessary changes in points of detail. I.e., matters will
remain generally the same, with only substitutions of names and the like, such as would
not distort anyof the substantive meaning. Lihat Peter J. Dorman, Running Press
Dictionary...Op. Cit., h. 115.
275
Parties are allowed to submit to arbitration any right of which they are qualified to
dispose, or in other formulas, parties must be qualified to enter a contract, or to make
promises, or to make settlements or to sell, or they must not be under some disability
under the law. Lihat Rene David, Arbitration in International Trade. Deventer:
Kluwer Law Publishers, 1985, h. 174.
276
Adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan langsung di dalam perkara yang
bersangkutan. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Op. Cit., h. 48.
277
Yaitu mereka yang beracara langsung di muka pengadilan, biasanya mereka bertindak
untuk dan atas nama pihak materiil. Pihak formal ini bisa merangkap juga sebagai
pihak materiil, namun biasa juga dia bukan pihak materiil melainkan orang yang
menjadi kuasa hukum pihak materiil.
153
(social setting) para pihak materiil yang bersengketa di hadapan forum
arbitrase, tidak pernah dapat diperoleh langsung dari pihak materiil. Oleh
sebab itu, sejumlah informasi yang diperlukan dari pihak materiil, akhirnya
hanya diperoleh dari pihak-pihak yang pernah menjadi pihak formal sebagai
kuasa hukum dari pihak materiil yang berkenan dijadikan sebagai informan
penelitian. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari para informan itulah
kemudian diketahui, tidak hanya subjek-subjek yang bersengketa pada
forum arbitrase, melainkan juga jenis sengketa yang lazim dibawa untuk
diselesaikan melalui forum arbitrase. Informasi tersebut menjadi salah satu
pemandu untuk memahami tentang asal-usul dari pihak-pihak materiil yang
bersengketa, sehingga dapat dipastikan kalangan mana saja yang paling
sering memanfaatkan arbitrase sebagai tempat menyelesaikan sengketa.
Indikator lain yang digunakan untuk memahami pihak-pihak materiil dalam
arbitrase adalah nilai atau besaran pokok sengketa. Meski tidak mutlak,
nilai atau besaran pokok sengketa dalam beberapa situasi dapat dijadikan
sebagai salah satu petunjuk untuk memahami identitas maupun stratifikasi
pihak-pihak materiil bersangkutan. Berbekal informasi yang disebutkan di
muka, selanjutnya dapat diketahui bahwa jenis sengketa yang lazim dan
paling banyak diselesaikan melalui forum arbitrase ternyata adalah sengketa
komersial (commercial dispute).
278
154
Mengamati informasi tentang nilai atau besaran pokok sengketa
juga telah memberikan gambaran betapa pihak-pihak yang melakukan
pilihan forum arbitrase ternyata sangat bervariasi. Pihak-pihak materiil bisa
seorang pengusaha besar, bisa juga pengusaha menengah atau bahkan
pengusaha kecil. Lebih dari itu, pihak materiil tidak hanya terdiri atas orang
perorangan (individu) melainkan bisa juga terdiri atas sekelompok orang
atau organisasi, atau badan usaha, dan bahkan negara sebagai badan hukum
publik. Sekadar gambaran dalam mendeskripsikan demikian beragamnya
pihak-pihak materiil dalam arbitrase, para informan mengilustrasikan bahwa
nilai perkara terkecil yang pernah diselesaikan lewat forum arbitrase bernilai
5 (lima) juta rupiah, dan nilai perkara terbesar sebesar 1,3 (satu koma tiga)
milyar dollar Amerika Serikat.
Informasi tersebut sekaligus menyangkal bahwa pilihan forum
arbitrase hanya dapat dilakukan oleh kalangan pengusaha dengan kapital
besar. Faktanya tidak demikian, pengusaha-pengusaha dengan kapital
278
The term commercial should be given a wide interpretation so as to cover matters
arising from all relationships of a commercial nature, whether contractual or not.
Relationships of a commercial nature include, but are not limited to, the following
transactions; any trade transactions for the supply or exchange of goods or services;
distribution agreement; commercial representation or agency; factoring; leasing;
construction of works; consulting; engineering; licensing; investment; financing;
banking; insurance; exploitation agreement or concession; joint venture and other
forms of industrial or business co-operation; carriage of goods or passanger by
air,sea, rail or road. Lihat, Alan Redfern et al., Law and Practice of...Op. Cit., h. 21.
Maka yang dimaksud dengan sengketa komersial adalah setiap sengketa atau
perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari hubungan yang bersifat
komersial (arising from all relationships of a commercial nature).
155
menengah atau bahkan kecil pun ternyata dapat pula memilih forum
arbitrase untuk menyelesaikan sengketa. Sebuah contoh dari Jawa Timur,
seorang pengusaha pabrik kerupuk di Sidoarjo di dalam suatu kontrak bisnis
pernah membuat kesepakatan untuk mencantumkan klausula pilihan forum
arbitrase untuk menyelesaikan sengketa bisnis dengan mitranya dari luar
negeri. Klausula arbitrase tersebut memilih forum Arbitrase ICC
(International Chamber of Commerce) yang berkedudukan di Paris
Perancis. Namun demikian, sengketa dagang tersebut akhirnya tidak jadi
diperiksa di sana karena faktor biaya yang terlalu mahal. Kasus di atas
menjadi salah satu bukti petunjuk, betapa pilihan forum arbitrase dapat
dilakukan oleh siapa saja bahkan dari kalangan pengusaha mana saja.
Seperti telah disebutkan di muka, tidak hanya para pelaku usaha
swasta yang dapat menjadi pihak dalam forum arbitrase, melainkan juga
negara sebagai badan hukum publik dapat menjadi pihak di depan forum
arbitrase. Arbitrase yang melibatkan negara sebagai pihak, dapat terdiri atas
dua kemungkinan, yakni (i) Arbitrase antar negara, yaitu apabila pihak-
pihaknya terdiri atas dua negara atau lebih; dan/atau (ii) Arbitrase yang
melibatkan negara sebagai salah satu pihaknya.
Jenis yang pertama, arbitrase antar negara, yaitu apabila suatu
negara berdaulat berhadapan dengan negara berdaulat lainnya sebagai
pihak-pihak dalam sengketa di hadapan forum arbitrase. Dalam kasus
156
semacam itu biasanya forum arbitrase bukan dimaksudkan untuk
menyelesaikan persoalan yang sifatnya murni sengketa komersial,
279
melainkan lebih merupakan sengketa publik internasional yang tidak dapat
diselesaikan melalui perdamaian bilateral. Sedangkan pada jenis yang
kedua, yakni arbitrase yang melibatkan negara sebagai salah satu pihak.
Biasanya forum arbitrase macam ini dilangsungkan ketika suatu negara
berdaulat di satu pihak berhadapan dengan perusahaan swasta
280
di lain
pihak (biasanya pihak tersebut adalah perusahaan transnasional) di dalam
kasus sengketa penanaman modal.
Dalam hal negara berdaulat di satu pihak berhadapan dengan perusahaan
transnasional di lain pihak pada forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa
279
Arbitrations between states are not usually concerned with purely commercial
disputes. Nevertheless, the practice followed in such arbitrations has had an important
influence on the general development of the modern practice of international
commercial arbitration. Dalam kasus ini dicontohkan kasus yang terjadi antara
Colombia dan Ecuador pada tahun 1907, sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase
tersebut menyangkut masalah garis perbatasan diantara kedua negara berkenaan
dengan keberadaan perjanjian dan perubahan yang ditetapkan oleh konvensi yang
ditunjuk oleh para arbitrator. Lihat, Alan Redfern et al., Law and Practice of... Op.
Cit., h. 40.
280
Perkara yang cukup terkenal untuk contoh Arbitrase ini adalah kasus antara Amco Asia
Corporation, Pan American Development Limited and PT Amco Indonesia vs.
Republik Indonesia di hadapan Forum Arbitrase ICSID (International Center for the
Settlement of Investment Dispute) di Washington. Kasus ini berkenaan dengan
pencabutan lisensi penanaman modal Hotel Kartika Plaza Jakarta oleh Pemerintah
Republik Indonesia. Akibat pencabutan lisensi tersebut, kemudian pada tanggal 15
Januari 1981 Pemerintah Indonesia dituntut oleh pihak investor di hadapan Forum
Arbitrase ICSID. Pemeriksaan perkara tersebut memakan waktu tidak kurang dari 12
tahun. Sampai akhirnya pada tanggal 3 Desember 1992 dibuat putusan tingkat
pemeriksaan keempat, hingga putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang
pasti. Lihat Sudargo Gautama, Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal
Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara Hukum Perdata.
Bandung: Alumni, 1994, h. 1.
157
komersial, muncul permasalahan berkaitan dengan imunitas negara (state
immunity). Masalahnya adalah, apakah benar ketika suatu negara bertindak
sebagai pihak dalam suatu kontrak komersial, kemudian aktivitas komersial
tersebut mengecualikan berlakunya imunitas negara (state immunity)?
281
Sebagai
konsekuensi logis dari keadaan itu maka negara berdaulat tersebut dapat
dituntut oleh pihak swasta dalam suatu forum arbitrase dalam rangka
penyelesaian sengketa komersial dimaksud. Untuk memahami masalah tersebut,
berikut ini dapat disimak Article 12 paragrap (1) The European Convention on
State Immunity, bukan sebagai kaidah imperatif melaikan sebagai norma hukum
internasional yang berlaku umum, meskipun konvensi tersebut sesungguhnya
tidak berlaku mengikat untuk Indonesia. Norma tersebut adalah sebagai berikut:
Where a Contracting State has agreed in writing to submit to arbitration a dispute
which has arisen or may arise out of a civil or commercial matter, that State may
not claim immunity from the jurisdiction of a court of another Contracting State on
the territory or according to the law of which the arbitration has taken or will take
place in respect of any proceedings relating to: (a) the validity or interpretation of
the arbitration agreement; (b) the arbitration procedure; (c) the setting aside of the
award. Unless the arbitration agreement otherwise provides.
282
Oleh karena itu, tatkala Republik Indonesia menjadi pihak
respondent di hadapan forum Arbitrase International Centre for Settlement
of Investment Disputes (ICSID) dengan claimant investor Amco Asia
281
Menurut C. Christoph H. Schreuer, The vast majority of arbitration between States
and non-State partners envisaged here will deal with commercial activities. In fact,
some of the provisions in the recent codifications treating arbitration as an exception
to sovereign immunity explicitly restrict this effect to arbitration dealing with
commersial claims.Lihat, C. Christoph H. Schreuer, State Immunity: Some Recent
Development. Cambridge: Grotius Publication, 1988, h. 68.
282
Periksa, C. Christoph H. Schreuer, State Immunity...Loc. Cit. h. 65.
158
Corporation, Pan American Development Limited, dan PT Amco Indonesia
pada tanggal 15 Januari 1981,
283
pihak Republik Indonesia telah
mengemukakan pendirian sebagai berikut:
284
(i) Mengenai consent (persetujuan) yang diberikan oleh suatu
negara berdaulat untuk tunduk pada arbitrase menurut Konvensi
itu harus ditafsirkan secara restriktif;
(ii) Kiranya jurisdiksi dari Dewan Arbitrase ICSID tidak dapat
diperluas hingga mencakup suatu Badan Hukum yang
mempunyai kewarganegaraan dari Negara peserta Konvensi
yang sedang dalam sengketa sekarang ini. Dalam hal ini PT
Amco Indonesia, adalah suatu Badan Hukum dan dapat
dipandang berkewarganegaraan Indonesia pula secara hukum,
hingga tidak dapat diajukan soal ini kepada arbitrase di muka
ICSID; Kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa karena foreign
control, para pihak telah menyetujui bahwa Badan Hukum ini
harus diperlakukan sebagai warga negara dari suatu negara
peserta ICSID lain untuk maksud Konvensi ini (Pasal 25 ayat (2)
sub b dari ICSID Convention). Pasal 9 dari Aplikasi Investasi
yang telah diajukan pada BKPM tidak mengandung persetujuan
secara jelas dari pihak RI untuk memperlakukan PT Amco
sebagai warga negara dari negara lain;
(iii) Juga tidak diketemukan bukti secara formal dan nyata dalam klausula arbitrase berkenaan dengan
negara peserta mana para pihak telah menyetujui untuk memperlakukan PT Amco sebagai warga
negara asing.
Namun demikian Dewan Arbitrase ICSID ternyata tidak menyetujui
pendirian pihak RI. Anggota Panel Arbitrase ICSID menyatakan
pendapatnya dengan mendasarkan pada prinsip pacta sunt servanda. Bahwa
Konvensi ICSID tidak seharusnya ditafsirkan secara restriktif tetapi harus
283
Sengketa tersebut timbul berkenaan dengan telah dicabutnya lisensi penanaman modal
oleh pejabat Ketua BKPM terhadap pihak investor dalam Hotel Kartika Plaza yakni
Amco Asia Corporation. Lihat Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase
Internasional. Bandung: Alumni, 1986, h. 1-2.
284
Sudargo Gautama, Indonesia dan... Loc Cit., h. 8-9.
159
secara luas. Harus didasarkan atas prinsip pacta sunt servanda yang
dianggap sebagai prinsip yang dianut oleh semua sistem hukum, baik
hukum nasional maupun hukum internasional.
285
Di samping itu juga setiap
Konvensi untuk mengadakan arbitrase harus ditafsirkan dan dilaksanakan
dengan itikad baik (good faith).
286
Ini berarti bahwa semua konsekuensi dan
komitmen para pihak yang dianggap secara layak harus diperhatikan dan
diperhitungkan terlebih dahulu.
B. Sengketa yang dapat diklaim Melalui Forum Arbitrase
Interaksi antar manusia yang berlangsung secara terus menerus
dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan hidup. Oleh
karena itu, menjadi sifat pembawaan setiap manusia untuk selalu hidup
dalam masyarakat, sebab manusia tidak mungkin hidup tanpa masyarakat,
dan sebaliknya masyarakat juga tidak mungkin ada tanpa manusia. Namun
demikian, mengingat kepentingan manusia itu sangat banyak dan beragam,
maka di dalam melakukan interaksi satu sama lain, manusia selalu
dihadapkan pada potensi-potensi untuk terjadi konflik
287
atau sengketa. Hal
285
Lihat Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase...Op. Cit., h. 10.
286
Not infrequently States enter into agreements to arbitrate in much the same way as
private parties, especially in the course of commercial dealings. Such agreements with
non-State partners create certain expectations of good faith and cooperation. Lihat,
C. Christoph H. Schreuer, State Immunity...Op. Cit. h. 63.
287
Conflict might be defined as a situation where the interests of two or more persons are
opposed in a manner that makes it impossible for all of the respective interests to be
160
itu dapat terjadi karena kepentingan manusia tidak jarang saling
bertentangan satu dengan yang lainnya. Potensi untuk terjadi konflik atau
sengketa antar manusia tentu saja tidak boleh dibiarkan berlangsung terus,
melainkan harus dicegah sebab konflik akan mengganggu keseimbangan
tatanan masyarakat. Oleh karena itu, ketika konflik terjadi dan
menyebabkan keseimbangan tatanan masyarakat terganggu, maka
keseimbangan yang terganggu itu harus dipulihkan kembali seperti keadaan
semula (restitutio in integrum).
288
Sama seperti kepentingan hidup manusia, sengketa atau konflik juga
banyak ragamnya,
289
demikian pula faktor yang menyebabkan terjadinya
maupun objek yang disengketakan. Masing-masing sengketa juga memiliki
karakteristik yang berbeda satu sama lain, sehingga adakalanya suatu
fully satisfied... Lihat, Christian Buhring Uhle, Arbitration and Mediation...Op.
Cit., h. 218. Menurut Paul Wehr, dilihat dari segi proposisi sentral: (i) bahwa konflik
merupakan pembawaan sejak lahir di dalam binatang sosial; (ii) bahwa konflik
ditimbulkan oleh sifat masyarakat dan cara mereka dibentuk; (iii) bahwa konflik adalah
disfungsi dalam sistem sosial dan sebuah gejala ketegangan patologis; (iv) bahwa
konflik adalah ciri yang tidak terhindarkan dari kepentingan negara dalam kondisi
anarki internasional; (v) bahwa konflik adalah hasil kesalahan persepsi dan komunikasi
yang buruk; (vi) bahwa konflik adalah proses alami yang umum bagi semua
masyarakat. Lihat Hugh Miall et al., Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 103.
288
Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1986, h. 4.
289
Berdasarkan pelaku (actors); konflik atau sengketa dibedakan atas (a) sengketa antar
dua pihak dan sengketa antar banyak pihak, (b) sengketa antar perorangan dan sengketa
antar kelompok, (c) sengketa antar organisasi dan sengketa di dalam organisasi, (d)
sengketa yang langsung direct conflicts dan sengketa yang ditengahi oleh perantara
atau perwakilan (conflicts mitigated by agents and representatives). Sedangkan
berdasarkan kesadaran para pihak (consciousness of the parties) sengketa dapat
dibedakan atas: sengketa yang nyata (manifest conflicts) dan sengketa yang
tersembunyi (underlying conflicts). Lihat, Christian Buhring Uhle, Arbitration and
Mediation...Loc. Cit.,
161
sengketa tertentu hanya dapat diselesaikan melalui lembaga tertentu pula.
290
Artinya, tidak semua jenis sengketa dapat diselesaikan melalui satu bentuk
penyelesaian sengketa atau melalui lembaga yang sama. Bentuk
penyelesaian sengketa yang sangat dikenal dan sudah lama digunakan orang
adalah penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Kekuasaan pengadilan
untuk menyelesaikan perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak
milik atau hak-hak yang timbul karenanya atau hak-hak keperdataan
lainnya,
291
kecuali apabila dalam undang-undang ditetapkan pengadilan
lain
292
untuk memeriksa dan memutusnya.
290
Sebagai contoh perkara perceraian bagi mereka yang beragama Islam menjadi
wewenang Pengadilan Agama (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 juncto UU Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan); Sengketa perburuhan diselesaikan oleh P4D atau
P4P; dan Perkara sewa menyewa rumah semula sepenuhnya menjadi wewenang
Kepala Kantor Urusan Perumahan (PP 49 Tahun 1963). Kemudian dengan PP Nomor
55 Tahun 1981 tentang Perubahan atas PP Nomor 49 Tahun 1963 tentang hubungan
sewa menyewa perumahan, khususnya mengenai penghentian hubungan sewa
menyewa perumahan tanpa kata sepakat kedua belah pihak, hanya dapat dilakukan
dengan putusan pengadilan negeri. Jadi sengketa khususnya mengenai penghentian
sewa menyewa tanpa kata sepakat menjadi wewenang pengadilan negeri. Tetapi
sengketa mengenai harga sewa masih tetap menjadi wewenang Panitia Perumahan.
Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Op. Cit., h. 58.
291
Pasal 2 ayat (1) Reglement op de Rechterleijke Organisatie en het Beleid Der Justitie
in Indonesie (RO) S. 1847 No. 23 jo 1848 No. 57. Selengkapnya Pasal 2 ayat (1) RO
dapat disimak berikut ini: De kennisneming en beslissing van alle geschillen over
eigendom of daaruit voortspruitende regten, over schuldvorderingen of burgerlijke
regten, en de toepassing van alle soort van wettig bepaalde straffen, zijn bij uitsluiting
opgedragen aan de regterlijke magt, volgens de verdeelingen van regtsgebied, de
regterlijke bevoegdheid, en de wijze bij dit reglement omschreven.
292
Pengadilan lain yang dimaksud adalah bentuk penyelesaian sengketa maupun lembaga
atau badan tempat menyelesaikan sengketa perdata selain pengadilan negeri. Seperti
telah disebutkan, misalnya Pengadilan Agama untuk sengketa perdata di kalangan umat
Islam, P4D atau P4P untuk sengketa perburuhan, dan Panitia Perumahan untuk
sengketa mengenai harga sewa. Di samping itu masih ada lembaga lain seperti halnya
lembaga arbitrase yang memang dapat dipilih oleh pihak-pihak di luar pengadilan
untuk menyelesaikan sengketa perdata atau sengketa dagang (komersial).
162
Arbitrase sebagai bentuk penyelesaian sengketa pada dasarnya
serupa dengan penyelesaian sengketa lewat pengadilan negeri.
Menyelesaikan sengketa melalui pengadilan maupun melalui arbitrase,
kedua bentuk tersebut, merupakan adjudicatory methods dengan pendekatan
pertentangan (adversarial).
293
Faktor yang menyebabkan kedua lembaga
tersebut berbeda adalah karena unsur yang melahirkan kompetensi dari
kedua lembaga itu juga berbeda. Kompetensi pengadilan lahir karena
ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kompetensi arbitrase lahir
melalui kesepakatan para pihak yang memilih forum arbitrase tersebut.
Meskipun demikian, arbitrase tetap dianggap sebagai bentuk lain dari
ajudikasi, yakni ajudikasi privat.
294
Meski di antara kedua lembaga
penyelesaian sengketa itu memiliki kemiripan, namun tidak semua sengketa
perdata yang dapat diselesaikan melalui pengadilan secara otomatis dapat
pula diselesaikan melalui arbitrase. Di Indonesia, sengketa yang dapat
diperiksa dan diselesaikan melalui arbitrase sangat limitatif. Undang-undang
Arbitrase Indonesia yang baru secara eksplisit menentukan jenis sengketa
293
Laura Nader menyebut bentuk ini dengan winner takes all yaitu ...the decision is
that one party is right and the other wrong. Lihat, William J. Chambliss & Robert B.
Seidman, Law, Order, and...Op. Cit., h. 28. Bdgk. Lon L. Fuller, Sistem
Perlawanan; dalam Harold J. Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum
Amerika Serikat. Jakarta: PT Tatanusa, 1996, h. 27. [27-37].
294
Para pihak dapat memilih hakim yang mereka inginkan, sehingga dapat menjamin baik
kenetralan maupun keahlian yang dianggap perlu dalam sengketa mereka. Para pihak
juga dapat memilih hukum yang akan diterapkan pada sengketa tersebut, sehingga
tidak perlu merasa takut atau tidak yakin terhadap hukum substantif dari yurisdiksi
163
yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu hanya sengketa di bidang
perdagangan (commercial law) dan mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa.
295
Sedangkan sengketa yang menurut undang-undang tidak
dapat diadakan perdamaian, tidak dapat diselesaikan melalui forum
arbitrase.
296
Berbeda dengan di negara lain,
297
arbitrase telah digunakan untuk
menyelesaikan berbagai persengketaan. Tidak hanya sengketa yang terjadi
dalam bidang perdagangan atau bidang komersial, melainkan juga sengketa-
sengketa lainnya, umpamanya: sengketa dalam bidang industri konstruksi,
sengketa klaim asuransi, sengketa dalam bidang industri tekstil dan pakaian,
bahkan penyelesaian tentang perceraian (divorce settlement)
298
juga dapat
tertentu. Lihat Gary Goodpaster, Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa dalam
Felix O. Soebagijo et al. (eds), Arbitrase di Indonesia...Op. Cit., h. 7-8.
295
Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999.
296
Sengketa tersebut umumnya meliputi: hukum keluarga (family law), terutama yang
berkenaan dengan status sipil dan kemampuan seseorang; tentang pailit; penyelesaian
susunan pengurus dan perubahan permodalan dalam Anggaran Dasar Perseroan. Lihat
M. Yahya Harahap, Beberapa Catatan... dalam Jurnal Hukum Bisnis...Op. Cit., h.
27. Lihat pula Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 1999.
297
Di Amerika Serikat misalnya, The American Arbitration Association (AAA) is a public
service to encourage the use of arbitration and other techniques of voluntary dispute
settlement. Bahkan menurut Robert Coulson, di Amerika Serikat: Many thousands of
cases are arbitrated each year. Arbitration is popular with the American people.
Rather than being a system of second-class justice, it is the first choice of many
people. Arbitration takes cases out of the courts. It saves public money. It puts the
control of dispute settlement into the hands of the parties. Lihat Robert Coulson,
Business Arbitration...Op. Cit., h. 9.
298
Marital separation agreements provide another example of the flexibility of
arbitration. Lihat, Robert Coulson, Business Arbitration...Op. Cit., h. 11.
164
dilakukan melalui arbitrase. Keadaan tersebut sama sekali tidak
dimungkinkan terjadi di Indonesia karena kaidah hukum arbitrase Indonesia
membatasi secara limitatif jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui
arbitrase, yaitu hanya sengketa di bidang perdagangan.
C. Struktur dan Proses Penyelesaian Sengketa lewat Arbitrase
Sebagai salah satu bentuk ajudikasi privat yang menggunakan
pendekatan pertentangan (adversarial), proses penyelesaian sengketa lewat
arbitrase juga memiliki kesamaan dengan proses yang harus ditempuh jika
melalui pengadilan. Akan tetapi struktur dalam arti susunan kelembagaan,
antara arbitrase dengan pengadilan memang sangat berlainan. Lembaga
pengadilan sebagai peradilan umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum
dilaksanakan oleh pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.
299
Sedangkan
arbitrase di samping tidak mengenal struktur kelembagaan yang berjenjang
semacam pengadilan, arbitrase juga bukan merupakan pelaksana kekuasaan
kehakiman, melainkan merupakan suatu cara penyelesaian sengketa perdata
di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang
299
Lihat Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Unadang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum, LN 1986 Nomor 20.
165
dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.
300
Pembedaan
arbitrase yang selama ini diketahui semata-mata untuk menunjukkan bahwa
secara struktural keberadaan arbitrase itu tidak berjenjang seperti pengadilan
melainkan masing-masing arbitrase berbeda bentuk satu sama lain. Oleh
karena itu, baik di dalam praktik maupun literatur dapat dijumpai
pembedaan bentuk
301
arbitrase, yaitu: (i) arbitrase terlembaga (institutional
arbitration)
302
dan (ii) arbitrase ad hoc.
303
Pembedaan bentuk arbitrase
tersebut tidak bermakna struktural melainkan lebih bersifat fungsional.
Artinya eksistensi kedua bentuk arbitrase itu bukan saja tidak merupakan
struktur bertingkat seperti halnya pengadilan, melainkan secara fungsional
kedua bentuk arbitrase itu memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan
tujuan pembentukannya dalam rangka penyelesaian sengketa bidang
perdagangan maupun sengketa perdata pada umumnya.
300
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
301
There are two main forms of arbitration available to the participants of international
commerce: Institutional arbitration and ad hoc arbitration. Lihat, Julian D.M. Lew,
Applicable Law in International Commercial Arbitration. Oceana Publication Inc.
1978, h. 19.
302
An institutional arbitration is one which is administered by one of the many specialist
arbitral institutions: amongst the better known are the American Arbitration
Association (AAA), the International Centre for the Settlement of Investment Disputes
(ICSID), the London Court of International Arbitration (LCIA), the International
Chamber of Commerce (ICC). Lihat, Alan Redfern et. al., Law And ...Op. Cit., h. 13.
303
An ad hoc arbitration is conducted under rules of procedure which are adopted for
the purpose of the arbitration, normally after a dispute has arisen. These rules of
procedure may be those drawn up by one of the non-commercial international
organisations. (The best known example is the UNCITRAL Arbitration Rules). Alan
Redfern et. al., Law And...Loc. Cit., Lihat juga Pasal 6 ayat (9) UU No.30 Th. 1999.
166
Sebagaimana telah disebutkan di muka, proses penyelesaian
sengketa melalui arbitrase tidak berbeda dengan berperkara melalui
pengadilan. Surat klaim pada forum arbitrase harus diajukan oleh claimant
dalam bentuk tertulis seperti halnya gugatan yang diajukan oleh penggugat
melalui pengadilan negeri. Bentuk tertulis
304
itu merupakan syarat formal
yang harus dipenuhi oleh pihak claimant sebagai pihak materiil maupun
kuasa hukumnya sebagai pihak formal pada forum arbitrase. Oleh karena
itu, menyelesaikan sengketa pada forum arbitrase mirip dengan sistem
procureur (procureur stelling) sebagaimana dianut oleh Reglement op de
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)
305
yang berlaku pada Raad van Justitie
(RvJ) pada waktu yang lalu. Setelah Raad van Justitie (RvJ) dihapuskan
306
304
Oleh karena itu, mengajukan klaim secara lisan melalui forum arbitrase sama sekali
tidak dimungkinkan. Alasannya sangat logis, karena baik pihak claimant maupun
respondent umumnya adalah orang-orang yang berkecimpung dalam dunia bisnis,
sehingga dapat dipastikan kedua belah pihak yang bersengketa didukung oleh
kemampuan dan kecerdasan yang sangat memadai. Lihat, M. Yahya Harahap,
Arbitase...Op. Cit., h. 134.
305
Verplichte procureurstelling merupakan asas pokok dalam beracara pada Raad van
Justitie (RvJ) berdasarkan Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv S. 1847
No. 52 jo S 1849 No. 63). Asas tersebut pada pokoknya mengharuskan bahkan
mewajibkan para pihak yang berperkara untuk diwakili oleh seorang advokat atau
procureur. Lihat, Eman Suparman, Keharusan Mewakilkan dalam Menunjang
Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan; Tesis S2,
Yogyakarta: FPS-UGM, 1988.
306
Berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951, LN Nomor 9, antara lain
ditetapkan: penghapusan beberapa pengadilan yang tidak lagi sesuai dengan suasana
Negara Kesatuan. Penghapusan pada pokoknya bermaksud mengadakan unifikasi itu
meliputi: a) Mahkamah Justisi ("Hof van Justitie"); b) Apelraad; c) segala Pengadilan
Negara dan Landgerecht gaya baru dan alat penuntut umumnya; d) Segala
Pengadilan Magistraat. Setelah penghapusan badan-badan pengadilan tersebut di atas
maka hanya Pengadilan Negeri sajalah yang berkuasa memeriksa dan memutus dalam
peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan segala perkara pidana, sehingga
167
terjadilah unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara pada pengadilan negeri
307
dan pengadilan tinggi di Indonesia. Akibat penghapusan tersebut, maka
hanya pengadilan negeri yang berkuasa memeriksa dan memutus dalam
peradilan tingkat pertama segala perkara perdata dan segala perkara pidana.
Demikian pula kemiripan dalam proses antara mengajukan claim
melalui arbitrase dengan gugatan melalui pengadilan, terjadi dalam gugatan
melalui Raad van Justitie (RvJ) menurut Rv, dan bukan dengan gugatan
melalui pengadilan negeri berdasarkan HIR. Oleh karena HIR sebagai
hukum acara pada pengadilan negeri sama sekali tidak menganut asas
verplichte procureurstelling sebagaimana dianut oleh Rv ketika masih
berlaku RvJ.
Sama seperti syarat formal suatu gugatan di pengadilan, surat claim
atau statement of claim di depan forum arbitrase, selain harus
mencantumkan identitas para pihak, juga harus memuat dalil konkrit tentang
adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan dari gugatan
dengan demikian Pengadilan Negeri adalah hakim sehari-hari biasa untuk seluruh
penduduk RI. Lihat Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan...Op. Cit., h. 86-87.
307
Hukum acara yang berlaku pada pengadilan negeri sampai saat ini adalah HIR (het
Herziene Indonesisch Reglement). Ketentuan itu memang sudah sangat tua
(diumumkan pada S. 1848-16 jo. 57, diumumkan lagi pada S. 1926-559, dan pada S.
1941-44). Sudah pasti dewasa ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan
masyarakat Indonesia. Akan tetapi kenyataan menunjukkan demikian, bahkan Konsep
Rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata Indonesia yang disusun
oleh Tim Inti Pembahasan dan Penyusunan RUU Hukum Acara Perdata BPHN-
Departemen Kehakiman, sejak 1984 sampai sekarang tidak jelas nasibnya, jangankan
menjadi Undang-undang, sedangkan mendapat giliran untuk dibahas pun tidak.
168
(fundamentum petendi atau posita), serta tuntutan atau petitum. Namun
terhadap substansi pokok tersebut dapat juga dicantumkan tambahan
proposal tentang: (i) jumlah arbiter yang akan ditunjuk (satu atau tiga)
orang, apabila mengenai hal ini belum disepakati dalam perjanjian; (ii)
penunjukan calon arbiter yang dikehendaki; (iii) atau proposal tentang
penyerahan penunjukan arbiter kepada arbitrase institusional yang
bersangkutan. Sebagai hukum formal yang memandu pihak-pihak dalam
melakukan penyelesaian sengketa pada forum arbitrase adalah Undang-
undang tentang Arbitrase dan APS.
308
Untuk itu gambaran tentang struktur
dan rangkaian proses penyelesaian sengketa lewat arbitrase berikut ini akan
dipaparkan di dalam bentuk ragaan-ragaan. Masing-masing ragaan tersebut
yakni: Ragaan 3 prinsip-prinsip dalam penyelesaian sengketa melalui
arbitrase; Ragaan 4 pemohon tidak hadir dan upaya perdamaian; Ragaan 5
perubahan dan penambahan tuntutan, serta jangka waktu penyelesaian;
Ragaan 6 pemeriksaan saksi dan saksi ahli.
308
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.
169
INTERVENSI DIAJUKAN
SEWAKTU PROSES
PENYELESAIAN BERJALAN
Ragaan 4
Prinsip-prinsip dalam Penyelesaian Sengketa
YANG DAPAT
MELAKUKAN INTERVENSI
PEMERIKSAAN
SECARA TERTUTUP
=PASAL 27=
MENGGUNAKAN
BAHASA INDONESIA
=PASAL 28=
AUDI ALTERAM
PARTEM
=PASAL29=
DAPAT DIWAKILI
KUASA
=PASAL 29 (2)=
SYARAT INTERVENSI
KEBEBASAN MEMILIH RULE
DICANTUMKAN DALAM
KLAUSULA
ARBITER BERWENANG
MEMPERPANJANG
JANGKA WAKTU
=PASAL33=
PASAL 48 MENENTUKAN
BATAS WAKTU
=TIME LIMIT=
APABILA ADA PILIHAN
RULE, HARUS
MENENTUKAN HAL-HAL
BERIKUT
Sesuai dengan asas confidential semua proses
bersifat : closure,
Pemerksaan dan putusan tidak boleh
dipublikasikan
Prinsip : semua proses dengan bahasa
Indonesia,
Atas persetujuan arbiter dapat dipilih bahasa
lain.
Para pihak mempunyai hak dan kesempatan
yang sama
Must give the same opportunity
Pemberian kuasa dalam bentuk surat kuasa
khusus.
1) Terdapat unsur kepentingan yang terkait
2) Disepakati oleh para pihak yang bersengketa,
3) Disetujui oleh arbiter atau Majelis Arbitrase.
Boleh memilih rule manapun,
Asal tidak bertentangan dengan UU ini,
Apabila para pihak tidak memilih suatu rule,
pemeriksaan tunduk pada UU ini.
1) Time limit = jangka waktu penyelesaian,
2) Principle place = tempat diselenggarakan
arbitrase.
Bila tidak ada : arbitrase yang menentukan
Paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis
arbitrasi terbentuk.
Pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase.
a) Apabila diajukan p[ermohonan oleh salah satu
pihak mengenai hak khusu tertentu,
b) Sebagai akibat ditetapkan putusan provisional,
c) Dianggap perlu oleh arbiter
=PASAL; 30=
MEMBUKA
SISTEM
INTERVENSI
= PASAL 31 =
BEBAS
MENENTUKAN
CARA
ARBITRASE
BATAS
WAKTU
PENYELESAIAN
BEBERAPA
PRINSIP
PEMERIKSAAN
170
Ragaan 5
Pemohon tidak hadir dan
TERMOHON TIDAK MEMBERI
JAWABAN
=PASAL 41=
TERMOHON DAPAT
MENGAJUKAN TUNTUTAN
BALASAN
=PASAL 42=
TIDAK DATANG MENGHADAP
TANPA ALASAN YANG SAH
I. PEMOHON TIDAK HADIR :
SURAT TUNTUTAN
DIGUGURKAN
TERMOHON TIDAK HADIR :
JATUHKAN PUTUSAN
VERSTEK
UU INI TIDAK MENGATUR
VERZET TEGEN VERSTEK
PARA PIHAK DATANG
MENGHADAP PADA HARI YANG
DITENTUKAN
UU INI MEMPERKENALKAN
PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN
=PASAL 45=
Bila dalam tempo 14 hari termohon tidak menyampaikan
jawaban :
Termohon dipanggil untuk menghadap
persidangan
Tuntutan balasan = rekonpensi = counter claim
Pengajuan : dalam jawaban, selambat-lambatnya pada
sidang pertama,
Pemohon : diberi kesempatan untuk menanggapi,
Tata cara pemeriksaan : diperiksa dan diputuskan
bersama-sama dengan pokok sengketa
Lazim disebut : unreasonable default.
Pemohon tanpa alasan yang sah tidak datang
menghadap : (Ps. 43)
Sudah dipanggil dengan patut, tapi tidak datang,
Surat tuntutannya dinyatakan gugur,
Dan tugas arbiter : dianggap selesai :
Apakah ini fakultatif atau imperatif ?
Rumusan Ps. 43 bersifat imperatif !
Termohon tanpa alasan yang sah tidak datang
menghadap (Ps. 44)
Sudah dipanggil secara patut, tetapi tidak datang,
Lakukan panggilan sekali lagi,
Dalam tempo 10 hari setelah pemanggilan kedua diterima,
tanpa alasan yang sah tidak juga datang :
Pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya
termohon,
Dan tuntutan pemohon dikabulkan seluruhnya,
kecuali tuntutan :
Tidak beralasan, atau
Tidak berdasar hukum.
Para pihak datang menghadap :
Arbiter lebih dahulu mengusahakan perdamaian,
Bila tercapai perdamaian :
Arbiter membuat : akta perdamaian.
Sifatnya final dan mengikat,
Dan memerintahkan para pihak untuk
memenuhi ketentuan perdamaian
tersebut.
Bila tidak dilaksanakan dengan sukarela, dapat
diminta eksekusi ke PN,
Jadi akta perdamaian = enforceable =
executable.
171
Ragaan 6
Perubahan dan Penambahan Tuntutan &
Jangka Waktu Penyelesaian
= PASAL 46 =
TIDAK TERCAPAI
PERDAMAIAN PROSES
DILANJUTKAN
MEMERIKSA POKOK
SENGKETA
=PASAL 47=
PENCABUTAN
PERMOHONAN
ARBITRASE SERTA
PERUBAHAN DAN
PENAMBAHAN TUNTUTAN
=PASAL 48=
BATAS JANGKA WAKTU
PENYELESAIAN
SENGKETA
=TIME LIMIT=
BILA USAHA PERDAMAIAN TIDAK TERCAPAI :
Lanjutkan pemeriksaan pokok perkara,
Pada kesempatan terakhir :
Diberi hak kepada para pihak menjelaskan pendirian msing-masing
= kesimpulan = secara tertulis,
Tindakan dn hak itu dietai dengan pengjuabn bukti-bukti yang
dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya,
Pengajuan tersebut disampaikan sesuai jangka waktu yang
ditetapkan arbiter.
Arbiter berhak meminta kepada para pihak :
1. Penjelasan tambahan secara tertulis (additional statement),
2. dokumen atau bukti lain yang dianggap perlu (additional evidence).
harus disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan arbiter.
Pemohon dapat mencabut permohonan arbitrase dengan syarat sebelum
ada jawan dari Termohon,
Apabila sudah ada jawan Termohon:
Pencabutan harus atas persetujuan Termohon.
Perubahan atau penambahan tuntutan.
sebelum ada jawaban Termohon: dapat dilakukan Pemohon,
sesudah ada jawaban Termohon: hanya dapat diperbolehkan
atas persetujuan Termohon.
perubahan atau penambahan yang dibolehkan:
hanya yang menyangkut: hal-hal yang bersifat fakta saja,
tidak boleh menyangkut: dasar-dasar hukum yang menjadi
dasar permohonan.
Tujuan time limit = untuk menjamin kepastian jangka waktu
penyelesaian arbitrase,
Batas jangka waktunya = 180 hari dari tanggal pembentukan Majelis
Arbitrase.
dapat diperpanjang : prolongable.
1. atas persetujuan para pihak,
2. atas kewenangan arbiter atau Majelis Arbitrase berdasar Pasal 33:
a. apabila salah satu pihak mengajukan permohonan mengenai hal
khusus tertentu (seperti permohonan provisi)
b. sebagai akibat dijatuhkan putusan provisi,
c. bila dianggap perlu oleh arbiter atau majelis untuk kepentingan
pemeriksaan.
172
Ragaan 7
Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli
dapat atas peintah arbiter / Majelis,
atau permintaan para pihak,
jumlahnya: dapat seorang atau beberapa orang
saksi atau saksi ahli.
dilakukan pada persidangan yang ditentukan,
memberi keterangan secara lisan = oral hearing.
sebelum memberi keterangan wajib
mengucapkan sumpah.
Dibebankan kepada pihak yang berhak!
Bagaimana kalau atas perintah arbiter? siapa
yang memikul biaya?
Sebaiknya: dipikulkan kepada kedua belah pihak.
atas perintah arbiter atau majelis arbitrase, atau,
atas permintaan para pihak.
berbentuk keterangan tertulis,
mengenai persoalan khusus yang behubungan
dengan pokok sengketa.
Memberikan segala keterangan yang diminta dan
diperlukan saksi ahli.
Arbiter / majelis: meneruskan salinan keterangan
S.A. kepada para pihak,
para pihak berhak memberi tanggapan:
secara tertulis,
untuk disampaikan kepada arbiter.
apabila ada hal yang kurang jelas dalam
keterangan tersebut,
para pihak yang berkepentingan dapat meminta
agar saksi ahli yang bersangkutan:
didengar keterangannya di muka sidang
dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.
PASAL 49
PEMERIKSA
AN
SAKSI DAN
SAKSI AHLI
PASAL 50
TATA CARA
PEMBERIAN
KETERANG
AN SAKSI
AHLI
SECARA
TERTULIS
YANG DAPAT MEMINTA
PEMERIKSAAN
CARA PEMERIKSAAN
BIAYA PEMANGGILAN
DAN PERJALANAN
PIHAK YANG DAPAT
MEMINTA
CARA PEMBERIAN
KETERANGAN
KEWAJIBAN PARA
PIHAK
PARA PIHAK BERHAK
MEMBERI TANGGAPAN
SECARA TERTULIS
PARA PIHAK BERHAK
MEMINTA
PENJELASAN SECARA
LISAN DI
PERSIDANGAN ATAS
KETERANGAN
TERTULIS SAKSI AHLI
173
1. Arbitrase Institusional
Arbitrase institusional adalah suatu badan atau lembaga yang
sengaja didirikan secara permanen
309
sebagai sarana penyelesaian sengketa.
Lembaga tersebut ada yang didirikan dan merupakan bagian dari organ
pemerintah suatu negara tertentu namun ada pula yang sifatnya partikelir.
Arbitrase institusional partikelir biasanya didirikan oleh atau atas prakarsa
individu warganegara maupun kelompok individu, biasanya kalangan
pengusaha swasta. Lembaga arbitrase partikelir sudah tentu bukan
merupakan bagian dari organ atau institusi pemerintah, sehingga lembaga
tersebut biasanya terlepas dari campur tangan pemerintah suatu negara.
Biasanya setiap lembaga arbitrase diorganisasikan dengan
manajemen yang teratur oleh para ahli dalam berbagai bidang. Di samping
diorganisasikan secara teratur, arbitrase terlembaga ini pun umumnya
memiliki perangkat ketentuan hukum formal (set of rules of arbitration)
sendiri sebagai hukum acara dalam rangka proses dan prosedur
arbitrasenya.
Untuk memahami pengertian arbitrase institusional, berikut ini
pengertian arbitrase institusional sebagaimana dikemukakan Alan Redfern,
309
Article I ayat (2) Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign
Arbitral Awards, menyebut arbitrase institusional ini dengan istilah "permanent
arbitral bodies," sebagai kebalikan makna dari arbitrase ad hoc yang disebut dengan
174
sebagai berikut: "An institutional arbitration is one which is administered
by one of the many specialist arbitral institutions under its own rules of
arbitration."
310
Tujuan pendirian lembaga arbitrase semacam itu biasanya diketahui
dari statuta lembaga tersebut. Secara umum tujuan pendirian arbitrase
institusional adalah dalam rangka menyediakan sarana penyelesaian
sengketa alternatif, di luar sarana penyelesaian sengketa konvensional yang
dikenal dengan pengadilan. Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI)
adalah salah satu contoh arbitrase institusional yang didirikan di Indonesia.
Berdasarkan anggaran dasarnya, BANI didirikan dengan tujuan
memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa
perdata yang timbul mengenai soal-soal perdagangan, industri, dan
keuangan, baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat
internasional.
311
Di Indonesia, sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui
arbitrase masih berkisar pada bidang hukum perikatan atau hukum kontrak.
Sedangkan pada negara-negara lain ternyata tidak hanya sengketa yang
termasuk bidang hukum perikatan yang dapat diselesaikan melalui
istilah "arbitrators appointed for each case." Bdgk. M. Yahya Harahap, Arbitrase
Ditinjau dari:...Op.Cit.," h. 151.
310
Alan Redfern, Law and Practice... Op. Cit., h. 13.
311
Lihat pasal 1 Anggaran Dasar Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI); dalam R.
Subekti, Arbitrasi Perdagangan. Bandung: Binacipta, 1981, h. 51.
175
arbitrase, melainkan juga sengketa-sengketa di dalam bidang hukum yang
lainnya. Seperti dikonstatir oleh Robert Coulson bahwa: "...Marital
separation agreements provide another example of the flexibility of
arbitration."
312
Hal itu berarti bahwa apabila para pihak menghendaki
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka masalah yang berada di
dalam cakupan hukum keluarga sekali pun dapat diselesaikan melalui
arbitrase.
Di muka telah disebutkan bahwa arbitrase institusional itu suatu
lembaga yang didirikan secara permanen.Yang dimaksud dengan permanen
di sini adalah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap,
keberadaannya juga terus menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Di samping itu keberadaan lembaga tersebut tidak hanya bergantung
kepada adanya sengketa. Artinya, apakah ada sengketa yang harus
diselesaikan atau tidak ada sengketa yang masuk, lembaga tersebut tetap
berdiri dan tidak akan bubar, bahkan setelah sengketa yang ditanganinya
telah selesai diputus sekali pun.
Seperti halnya suatu pengadilan nasional dari suatu negara, pada
dasarnya setiap arbitrase institusional selalu mempunyai hubungan dengan
312
Lihat Robert Coulson, Business Arbitration...Op. Cit., h. 11.
176
jurisdiksi
313
suatu negara tertentu. Artinya, setiap arbitrase institusional
memiliki nasionalitas atau status kewarganegaraan dari suatu negara
tertentu. Sekurang-kurangnya terdapat tiga faktor mengapa nasionalitas
suatu arbitrase institusional penting untuk diketahui. Julian D.M. Lew
314
menyebutkan alasan-alasan tersebut yaitu: Pertama, untuk menentukan lex
arbitri, yaitu hukum yang mengatur tentang proses arbitrase dan hukum
yang menentukan pokok sengketa apakah yang harus dipertimbangkan
oleh para arbiter; Kedua, untuk menentukan pengadilan nasional negara
mana yang memiliki jurisdiksi terhadap arbitrase tersebut. Hal itu
penting karena pengadilan suatu negara pada dasarnya memiliki
kewenangan untuk mengawasi, bahkan bila perlu mencampuri proses
arbitrase yang berlangsung pada negara tersebut;
315
dan Ketiga, untuk
mengetahui prosedur yang harus diikuti dalam rangka pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.
313
Adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa
(hukum). Jurisdiksi merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan
derajat negara, dan prinsip tidak campur tangan. Jurisdiksi juga merupakan suatu
bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau
mengakhiri suatu hubungan atau kewajiban hukum. Lihat, Shaw, International Law;
dalam H. Adolf, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Indternasional. Jakarta:
Rajawali, 1991, h. 143.
314
Julian D.M. Lew, Applicable Law...Op. Cit., h. 13.
315
Dalam kaitan ini, Dr Johannes Trappe antara lain menyatakan: Beside the fact that the
Court appoints an arbitrator for a party who fails to do so the Court may have
functions to fulfil during the proceedings. Lihat J. Martin Hunter, Judicial assistance
for the arbitrator; dalam Julian DM Lew (ed), Contemporary Problems in
International Arbitration. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987, h. 202.
177
Mengapa hal itu dianggap penting? Oleh karena persoalan yang
seringkali terjadi dalam kaitannya dengan yang disebut terakhir itu adalah
menyangkut sulitnya pelaksanaan putusan arbitrase terutama putusan
arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri atau arbitrase internasional. Sudah
menjadi citra bahwa putusan arbitrase nasional (domestik) pelaksanaannya
relatif lebih mudah, bahkan hampir tidak ada masalah bila dibandingkan
dengan eksekusi putusan arbitrase internasional (foreign arbitral
awards).
316
Walaupun demikian, untuk menentukan apakah suatu arbitrase
itu tergolong arbitrase nasional atau arbitrase internasional tidak selalu
mudah. Hal itu disebabkan banyak faktor yang turut menentukan. Sebagai
panduan dalam rangka memahami apakah sesuatu forum arbitrase itu
tergolong arbitrase nasional atau arbitrase internasional, serta dimana letak
perbedaannya, dapat disimak dari pengertian yang diberikan oleh Redfern
berikut ini: Domestic arbitrations usually take place between the
citizens or residents of the same state, as an alternative to proceedings
before the courts of law of that state.
317
Dari rumusan di atas tampak bahwa faktor-faktor kebangsaan atau
tempat tinggal para pihak yang bersengketa antara lain menjadi indikasi
untuk menentukan apakah suatu arbitrase itu termasuk arbitrase nasional
316
Julian D.M. Lew, Applicable Law...Op. Cit., h. 13.
317
Alan Redfern et al., Law and Practice...Op. Cit., h. 14.
178
atau arbitrase internasional. Beberapa faktor lain yang juga dapat dijadikan
indikasi untuk menentukan apakah suatu arbitrase termasuk arbitrase
nasional atau internasional antara lain: (i) pokok sengketa, (ii) kebangsaan
atau tempat tinggal para pihak dan para arbiternya, (iii) hukum yang
digunakan, dan (iv) tempat pemeriksaan arbitrase dilangsungkan. Berkaitan
dengan yang disebut terakhir yaitu tempat arbitrase dilangsungkan, ada
pendapat bahwa: The arbitration may be totally domestic but for one
element, e.g. the place of arbitration.
318
1. Arbitrase Ad Hoc
Sebagai bentuk alternatif dari arbitrase institusional adalah arbitrase
ad hoc. Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan "arbitrase ad hoc
adalah arbitrase yang tidak diselenggarakan atau tidak melalui suatu badan
atau lembaga arbitrase tertentu (institutional arbitration)."
319
Menurut Alan Redfern, arbitrase ad hoc adalah: "...arbitration
without designating any arbitral institution and without referring to any
318
Sebagai contoh umpamanya di dalam the English case International Tank and Pipe
SAK v. Kuwait Aviation Fuelling Co. KSC (1975). Para pihak di dalam kontrak
tersebut adalah bangsa Kuwait, seluruh kontrak dibuat dan diberlakukan di Kuwait,
akan tetapi di dalam kontrak ditetapkan bahwa arbitrase akan diselenggarakan di
London berdasarkan ketentuan ICC Arbitration. Ternyata menurut Hukum Inggris
(Arbitration Act 1950), pengadilan di Inggris memiliki yurisdiksi untuk melakukan
campur tangan atas proses arbitrase tersebut. Lihat Julian D.M. Lew, Applicable Law...
Op. Cit., h. 13 dan h. 38, Note No. 19.4.
319
E.J.Cohn, M. Domke, F. Eisemann (eds.), Handbook of Institutional Arbitration in
international trade; Preface, h. v; Lihat dalam Sudargo Gautama, Arbitrase
Dagang Internasional...Op. Cit., h. 19.
179
particular set of institutional rules."
320
Sebagai bentuk lain dari arbitrase
institusional, arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang sifatnya tidak
permanen. Artinya, keberadaan atau eksistensi arbitrase tersebut sangat
bergantung pada kebutuhan pihak-pihak yang bertikai, yang menghendaki
penyelesaian sengketa mereka melalui arbitrase ad hoc tersebut. Pada
arbitrase ad hoc pihak-pihak yang bersengketa tidak hanya dapat bersepakat
untuk menyelesaikan sengketa, melainkan juga para pihak memiliki
kewenangan untuk mengendalikan setiap aspek dan prosedur penyelesaian
sengketa yang akan dilakukan. Dalam arbitrase ad hoc melakukan
pengangkatan arbiter atau para arbiter beserta segala kompetensinya juga
merupakan kewenangan pihak-pihak yang bersengketa. Tempat arbitrase
dilangsungkan juga dapat ditetapkan berdasarkan kehendak para pihak.
Mereka dapat memilih tempat arbitrase dilangsungkan pada tempat tinggal
atau tempat kediaman mereka atau dapat juga memilih tempat tinggal
arbiternya. Bahkan dapat juga memilih tempat lain yang bukan tempat
tinggal para pihak atau arbiter, melainkan tempat dimana asset yang
menjadi objek sengketa berada.
Demikian pula halnya di dalam menetapkan kaidah hukum yang
akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa mereka, para pihak dapat
320
.Alan Redfern, Law and Practice...Op. Cit., h. 56.
180
memilih peraturan prosedur arbitrase (rules of arbitral procedure) sesuai
dengan yang mereka kehendaki. Artinya, para pihak tidak terikat untuk
memakai peraturan prosedur arbitrase dari suatu arbitrase institusional
tertentu. Pilihan untuk menggunakan peraturan prosedur arbitrase dapat
dilakukan terhadap berbagai kaidah arbitrase. Umpamanya saja,
UNCITRAL Arbitration Rules (UAR) sebagai kaidah hukum acara arbitrase
mereka. Perangkat kaidah UNCITRAL Arbitration Rules (UAR) tersebut
disediakan untuk dipergunakan dalam arbitrase ad hoc, karena UAR sendiri
tidak memiliki lembaga arbitrase (arbitral institution) tertentu.
Walaupun demikian apabila para pihak menghendaki, arbitrase ad
hoc dapat juga dilangsungkan pada salah satu arbitrase institusional
tertentu. Dalam hal demikian, para pihak tidak diharuskan memakai
perangkat kaidah arbitrase dari lembaga arbitrase tersebut, melainkan
dapat juga memilih kaidah arbitrase lain misalnya UNCITRAL Arbitration
Rules (UAR) sebagai kaidah hukum acara arbitrasenya. Demikian juga
para arbiter tidak memiliki kewajiban untuk memakai perangkat kaidah dari
lembaga arbitrase tersebut. Artinya lembaga arbitrase bersangkutan akan
mempergunakan kaidah arbitrase UNCITRAL Arbitration Rules (UAR)
yang telah dipilih para pihak. Arbitrase semacam itu disebut dengan
181
arbitrase ad hoc yang diadministrasikan oleh lembaga arbitrase yang sudah
ada (administered ad hoc arbitration).
321
Satu hal yang tidak dapat dilupakan bahwa kaidah arbitrase
UNCITRAL itu sifatnya optional, sehingga tidak ada kewajiban bagi siapa
pun yang hendak menyelesaikan sengketa melalui arbitrase untuk
memakainya. Oleh karena itu, para pihak yang bersengketa bebas untuk
melakukan pilihan, apakah hendak memakai kaidah tersebut atau tidak.
Akan tetapi untuk penyelesaian sengketa pada arbitrase ad hoc, memakai
kaidah yang sifatnya optional seperti halnya kaidah arbitrase UNCITRAL
agaknya lebih tepat. Hal itu seperti juga dikonstatir oleh Alan Redfern,
bahwa: However, it is not advisable to try to adopt or adapt institutional
rules (such as those of the ICC) for use in an ad hoc arbitration, since
such rules make constant reference to the institution concerned and will
not work properly or effectively without it.
322
Hal itu disebabkan
perangkat ketentuan tersebut pada dasarnya hanya bersangkut-paut dengan
arbitrase institusional bersangkutan, sehingga kaidah tersebut belum tentu
dapat efektif dan cocok bila dipakai di dalam arbitrase ad hoc. Sebaliknya,
apabila para pihak dalam penyelesaian sengketa itu sama sekali tidak
melakukan pilihan hukum, maka dewan arbitrase akan memakai hukum
321
Lihat S. Gautama, Arbitrase Dagang...Op. Cit., h. 20.
322
Alan Redfern, Law and Practice...Op. Cit., h. 56.
182
yang telah ditentukan oleh kaidah-kaidah Hukum Perdata Internasional
(HPI) yang dianggap berlaku menurut para arbiter.
323
D. Keadilan Menurut Pihak-pihak Bersengketa
Keadilan berasal dari kata adil yang diambil dari Bahasa Arab
Adl.
324
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata adil diberi arti tidak
323
S. Gautama, Perkembangan...Op. cit., h. 46. Bdgk. Art. 28 (2) UNCITRAL Model
Law on International Commercial Arbitration; as adopted by UNCITRAL on June 21,
1985, dalam Alan Redfern, Law and Practice...Op. Cit., h. 806. Art. 28 (2) antara lain
disebutkan: "Failing any designation by the parties, the arbitral tribunal shall apply
the law determined by the conflict of laws rules which it considers applicable."
324
Kata adl Bahasa Arab itu maknanya tidak dapat dilepaskan dari kandungan ayat-ayat
suci Al Quran. Oleh karena itu meskipun arti keadilan itu beraneka ragam dan
memiliki konteks masing-masing yang berbeda satu sama lain, akan tetapi sumber
rujukannya sama yakni Al-Quran. Sekurang-kurangnya terdapat enam arti kata adil,
seperti yang dapat disimak berikut ini: (i) Adil berarti tebusan, maksud dari tebusan di
sini adalah suatu usaha penyeimbang atau upaya menyamakan sesuatu dengan yang
lain. Arti tebusan di dalam ayat suci Al Quran (QS 2: 48 & 123 serta QS 6: 70) adalah
akibat dari pelanggaran ketentuan hukum di dunia atau sebagai tebusan atas perbuatan
manusia yang selama hidup di dunia mengabaikan peringatan Allah SWT. (ii) Adil
berarti mempersamakan atau memperlakukan secara jujur, dapat disimak pada (QS
4: 3 & 129 serta QS 42:15). Adil dalam makna persamaan hak terlihat dalam
pelaksanaan hukum, sehingga peran hakim menjadi sangat sentral dalam menegakkan
keadilan. Al Maraghi seorang mufasir menegaskan Seorang hakim harus menjunjung
tinggi keadilan yang merupakan neraca keadilan. Keadilan harus berada di atas hawa
nafsu dan kepentingan tertentu, di atas cinta dan permusuhan. Menjauhi keadilan
adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. (iii) Adil berarti
benar, dapat dijumpai dalam QS 2: 282 serta QS 4: 58 & 135. Adil dalam makna benar
ini maksudnya menempatkan posisi keadilan di atas hak-hak individu maupun
kepentingan kelompok, sehingga apa pun strata sosial seseorang, maka tidak boleh
terjadi kepentingan pribadi mengorbankan prinsip kebenaran dan keadilan. (iv) Adil
berarti seimbang atau sederhana, dalam arti seimbang inilah dimensi keadilan banyak
diungkap dalam Al-Quran. Keseimbangan maksudnya baik seimbang lahiriah, yaitu
dalam hal penciptaan manusia maupun seimbang dalam penciptaan alam semesta. Adil
dalam makna ini dapat dijumpai dalam QS 82:7, QS 55:7, QS 25:67, QS 17:67, QS
6:141. (v) Adil berarti nilai atau harga, dalam pengertian ini nilai atau harga dianggap
sebagai unsur penyeimbang yang melengkapi kewajiban manusia, ketika kewajiban itu
tidak sempat tertunaikan. Seperti dapat disimak dari QS 5: 95, intinya denda berupa
puasa yang jumlah harinya disesuaikan dengan nilai atau harga makanan yang harus
diberikan kepada fakir miskin harus ditunaikan oleh seorang muslim yang membunuh
183
berat sebelah (tidak memihak), berpihak kepada kebenaran, berbuat
sepatutnya (tidak sewenang-wenang).
Membicarakan persoalan keadilan tidak sekadar merupakan
persoalan hukum positip
325
dan kajian filsafat,
326
lebih dari itu, masalah
keadilan juga sebagai prinsip teologis.
327
Artinya hakikat pembicaraan
mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari sifat-sifat dan dasar-dasar
kepercayaan kepada Allah Yang Maha Kuasa. Bahkan Al-Quran sebagai
wahyu dan mukjizat memberikan perhatian yang istimewa untuk
binatang ketika sedang ihram. (vi) Adil berarti meng-Esakan Allah, sikap pembenaran
dan ketaatan kepada keesaan Allah SWT yang dilakukan seorang hamba sesungguhnya
telah berbuat adil. Oleh karena Allah SWT juga telah menuntun manusia untuk
berbuat adil, seperti dapat dijumpai dalam QS 16:90. Lihat M. Wildan Yahya,
Keadilan dalam Perspektif Al-Quran; dalam Hikmah, Jurnal Ilmu Dakwah,
Volume 1 Nomor 2, Juli 2002, h. 156-166.
325
Bahwa setiap orang yang karena kedudukan, fungsi atau perbuatannya memenuhi
deskripsi yang dimaksud dalam suatu norma hukum akan diperlakukan menurut norma
hukum itu. Sebagai contoh peraturan lalu lintas akan diberlakukan kepada setiap orang
karena peraturan lalu lintas menyebut barangsiapa pemakai jalan. Oleh karena itu,
siapa saja pemakai jalan akan dikenai aturan lalu lintas. Lihat Franz Magnis-Suseno,
Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 1999, h. 81.
326
Di samping keadilan sebagai keutamaan umum (yaitu ketaatan kepada hukum alam dan
hukum positip) terdapat juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus yang
menentukan sikap manusia pada bidang tertentu. Thomas Aquinas membedakan
keadilan menjadi tiga, yaitu: (i) keadilan distributif (iustitia distributiva), yaitu hal-hal
yang harus dibagi menurut kesamaan geometris. Sebagai contoh hal-hal yang umum,
seperti jabatan, pajak, dan sebagainya. (ii) keadilan tukar menukar (iustitia
commutativa), ukuran keadilan ini bersifat aritmetris. Di sini berlaku suatu hak yang
sungguh-sungguh, yakni hak milik (ius proprietatis). Prinsip dasar dalam keadilan ini
adalah jangan merugikan orang, contoh jual beli; dan (iii) keadilan legal (iustitia
legalis) ini menuntut supaya orang tunduk pada semua undang-undang, oleh karena
undang-undang itu menyatakan kepentingan umum. Lihat Theo Huijbers OSC, Filsafat
Hukum dalam Lintasan Sejarah. Yogyakarta: Kanisius, 1984, h. 43, 76.
327
Dalam medan pemikiran ilmiah Islam, benang hijau yang menghubungkan munculnya
keadilan dalam masyarakat Islam secara ilmiah dan amaliah pertama-tama adalah Al
Quran. Sebagai Kitab Agung Al Quran telah menaburkan benih-benih pemikiran
keadilan pada sanubari dan jiwa manusia, kemudian menyirami dan menumbuhkannya
184
terpeliharanya prinsip keadilan di dalam hukum relatif dan dalam perundang-
undangan. Di dalamnya terdapat penjelasan bahwa tujuan diutusnya para
nabi pada dasarnya adalah untuk menegakkan sistem kemanusiaan dan
memimpin kehidupan manusia atas dasar keadilan.
328
Hukum sebagaimana diterima dan dijalankan di negara-negara di
dunia sekarang ini, pada umumnya termasuk ke dalam kategori hukum yang
modern.
329
Karakteristik yang menonjol pada hukum modern adalah dalam
cara-cara menerapkan keadilan dalam masyarakat. Pada sistem hukum
modern penerapan keadilan sangat menekankan pada struktur yang
birokratis. Dalam sistem hukum modern, penerapan keadilan ditandai oleh
suatu perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur yakni proses
pengalihan dari penerapan keadilan secara pribadi berpindah ke tangan
negara yang kemudian dilembagakan. Berdasarkan proses semacam itu
kemudian muncul istilah law enforcement (pelaksanaan atau penerapan
hukum) dan administration of justice (administrasi keadilan). Sesungguhnya
pembicaraan mengenai administrasi keadilan memang belum lazim
dilakukan di Indonesia, namun biasanya istilah administrasi keadilan dipakai
dalam bentuk pemikiran, filosifis, praktis, dan sosial. Lihat, Mutadha Muthahhari,
Keadilan Ilahi...Op. Cit., h. 34-35.
328
Untuk hal ini dapat disimak dari QS 57:25; Mutadha Muthahhari, Loc. Cit., h. 36.
329
Modernitas itu ditandai dengan ciri-ciri: (1) mempunyai bentuk tertulis; (2) hukum itu
berlaku untuk seluruh wilayah negara, meskipun tidak selalu demikian karena pada
masa-masa yang lalu dalam suatu wilayah negara bisa berlaku berbagai macam hukum
dengan otoritas yang bersaing. (3) Hukum merupakan instrumen yang dipakai secara
185
dalam hubungannya dengan pelaksanaan hukum, khususnya yang dilakukan
melalui pengadilan.
330
Bekerjanya pengadilan dalam hubungan dengan
proses penegakan keadilan, dalam praktik tidak berjalan secara otomatis
sebagaimana telah diatur berdasar prosedur-prosedur formal yang telah
ditentukan dalam hukum acara. Sejak awal keberadaan pengadilan dirancang
sebagai suatu institusi rasional dengan sekalian prosedur dan teknikalitasnya.
Hal itu mengandung makna, bagaimana pun seseorang berkeyakinan bahwa
suatu perkara serta keadilan ada pada dirinya, namun apabila yang
bersangkutan gagal memenuhi dan mengikuti ketentuan dalam proses
berperkara, orang tersebut akan dikalahkan oleh pihak lawan yang dengan
cerdik mampu memanfaatkan sekalian teknikalitas hukum.
331
Oleh karena
itu, untuk memenangkan suatu perkara di depan pengadilan, tidak cukup
hanya mengandalkan posisi keadilan, melainkan harus siap bertempur
secara hukum.
332
Itu berarti, keadilan tidak secara otomatis akan keluar atau
didapat begitu sengketa dimasukkan di pengadilan, melainkan harus
diupayakan sedemikian rupa melalui perjuangan panjang dengan tenaga dan
uang agar pihak berperkara tidak menjadi korban ketidakadilan. Bahwa
keadilan sebagai sebuah konsep belumlah lengkap apabila tugas dan
sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakatnya. Lihat Satjipto
Rahardjo, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986, h. 178-179.
330
Satjipto Rahardjo, Loc. Cit., h. 217-218.
331
Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma...Op. Cit., h. 121.
332
Lihat Satjipto Rahardjo, Dengan Determinasi; dalam Kompas, 17 Oktober 1998.
186
kewajiban, baik moral maupun legal konstitusional tidak terliput secara
integral. Hal itu penting untuk ditekankan karena stabilitas suatu masyarakat
yang ditata dengan baik terletak pada pengakuan dan kepastian pelaksanaan
hak dan kewajiban segenap warga secara seimbang. Menurut Rawls,
333
ada
dua kewajiban natural yang sangat penting: (1) kewajiban untuk mendukung
dan mengembangkan institusi-institusi yang adil; dan (2) kewajiban natural
untuk saling menghargai.
Keadilan merupakan sebuah nilai primer bagi manusia, maka
kewajiban untuk selalu bersikap adil pada pokoknya menuntut bahwa
keadilan harus ditegakkan dengan menggunakan cara-cara yang adil pula.
Hal penting yang harus diperhatikan dalam kaitan tersebut adalah peringatan
Rawls untuk menghindarkan praktik-praktik yang tidak adil, sekalipun
dilakukan atas nama keadilan. Tegasnya, keadilan tidak boleh ditegakkan
dengan cara-cara yang tidak adil. Cara-cara yang tidak adil, meskipun
333
Lihat John Rawls, A Theory of...Op. Cit., h. 333-342. Sementara itu Andre Ata Ujan
memberikan komentar antara lain: ...Ketika berbicara mengenai kewajiban moral,
Rawls menggunakan istilah duty dan ketika berbicara mengenai kewajiban
konstitusional, menggunakan istilah obligation. Rawls sendiri mengakui bahwa bisa
saja ada hubungan antara kedua jenis kewajiban tersebut (kewajiban moral dan
kewajiban legal atau konstitusional), namun keduanya tetap harus dibedakan. Hal itu
mudah dimengerti karena sifat dasar keduanya memang berbeda, tidak hanya dari segi
sumber, tetapi juga prinsip keberlakuannya berbeda. Keberlakuan kewajiban legal atau
konstitusional dapat dipaksakan dari luar, sedangkan kewajiban moral tidak dapat
diperlakukan seperti itu. Kewajiban moral menjadi kewajiban karena merupakan buah
kesadaran dari person yang bersangkutan. Sedangkan kewajiban legal atau
konstitusional berhubungan dengan kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat
atau warga negara tertentu, dalam arti mengatur interaksi sosial di antara anggota
masyarakat baik pada tingkat horizontal maupun vertikal. Lihat Andre Ata Ujan,
Keadilan dan...Op. Cit., h. 165.
187
dilakukan atas nama keadilan, tetap saja bertentangan dengan esensi keadilan
itu sendiri. Oleh karena itu, kewajiban untuk bersikap adil patut diterima
sebagai sebuah tuntutan natural, meskipun tidak berarti adanya kesadaran
akan kewajiban natural seperti itu kemudian pelaksanaan hak dan kewajiban
akan dengan sendirinya berjalan mulus.
Keadilan sebagai fairness tidak akan pernah menjadi kenyataan
dalam kehidupan warga apabila tidak ada kesadaran luas akan pentingnya
saling menghargai sebagai sebuah nilai moral di antara anggota masyarakat.
Oleh sebab itu, sikap saling menghargai harus dapat dilihat juga sebagai
suatu kewajiban natural yang pengungkapannya menjadi bukti nyata dari
saling pengakuan di antara anggota masyarakat sebagai person moral. Rawls
menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat harus tunduk pada batasan-
batasan institusional, tetapi tidak ada tuntutan moral yang dapat dengan
begitu saja muncul dari fakta adanya lembaga-lembaga. Rawls menyadari
dengan baik untuk tetap melihat perbedaan antara tuntutan-tuntutan moral di
satu pihak dengan tuntutan-tuntutan legal institusional di lain pihak. Oleh
karena itu, kendati memberi tekanan yang sangat kuat pada prinsip keadilan
dan sikap saling menghargai sebagai prinsip-prinsip moral yang harus
ditegakkan demi suatu kerjasama yang saling menguntungkan, namun Rawls
tetap percaya bahwa himbauan moral saja tidak mencukupi. Masih
dibutuhkan prinsip-prinsip legal institusional yang memang memiliki
188
kekuatan memaksa individu dari luar untuk bisa bersikap adil dan
menghargai hak pihak lain. Untuk itu bisa dimengerti mengapa Rawls
menyebut dukungan dan kepatuhan pada lembaga-lembaga yang adil sebagai
suatu kewajiban natural manusia.
334
Sebagai contoh umpamanya, seorang
hakim dapat saja menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam
menginterpretasikan hukum, namun tetap harus disadari bahwa apa yang
dilakukannya adalah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan institusional legal.
Yang dilakukan hakim di sini adalah menerapkan hukum, dan sejauh
penerapan ini memenuhi prinsip-prinsip keadilan, hakim mempunyai
kewajiban moral untuk tunduk pada hukum tersebut. Dalam kaitan ini Rawls
menegaskan bahwa seseorang dapat saja baik secara hukum, tetapi belum
tentu ia juga baik secara moral. Dari sudut hukum dapat dikatakan bahwa
suatu hukum dapat saja berlaku dan pada kenyataannya dijadikan perangkat
regulatif bagi warga masyarakat, tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa hukum
tersebut dengan sendirinya adil.
Para peziarah keadilan sekarang harus menemukan kenyataan,
bahwa jalan masuk ke rumah keadilan atau access to justice memang telah
menjadi semakin sempit. Tidak hanya dalam arti spasial, tetapi juga
ekonomis dan intelektual.
335
Sedangkan keadilan merupakan suatu nilai
334
Andre Ata Ujan, Keadilan dan ...Op. Cit., h. 101, 165.
335
Penggunaan sistem peradilan modern sering dianggap sebagai penyebabnya, karena
sistem peradilan yang demikian sangat menekankan kepada format, formalitas,
189
yang teramat tinggi kedudukannya dalam masyarakat, oleh karena itu, perlu
mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya bagi mereka yang mencarinya.
336
Sepenuhnya disadari bahwa keadilan dan pemberian keadilan merupakan
masalah yang kompleks dan rumit. Manajemen keadilan yang bijaksana
tentu akan menanganinya sesuai dengan kompleksitas tersebut. Oleh sebab
itu, model Khadi-justiz sebagaimana disebut oleh Weber adalah suatu istilah
teknis yang menunjuk pada suatu bentuk administrasi keadilan yang tidak
berorientasi pada peraturan-peraturan hukum formal rasional. Para hakim
pada Khadi-justiz memutuskan atas dasar hukum yang substantif-rasional.
337
Namun demikian, administrasi keadilan Khadi-justiz pada dewasa ini telah
digantikan oleh suatu lembaga yang diorganisasikan secara rasional.
Wewenang, susunan, serta prosedur kerjanya telah ditetapkan secara jelas,
prosedur, dan spesialisasi. Arsitektur pengadilan yang demikian itu menjadikan
pengadilan kaku dan lamban karena sarat dengan beban formalitas, prosedur,
birokrasi, dan metodologi yang ketat. Orang tidak mempunyai pilihan lain, kecuali tahu
hukum untuk dapat memasuki pintu keadilan tersebut. Bagi mereka yang tidak tahu
hukum dapat memakai jasa advokat dengan membayar layanan profesi tersebut. Lihat
Satjipto Rahardjo, Membangun Keadilan Alternatif; Kompas, Rabu, 5 April 1995.
336
Pada tahun 70-an (tujuh puluhan) dikenal ada gerakan yang bernama Access to Justice
Movement (AJM), suatu gerakan yang bertujuan meringankan kerasnya sistem
peradilan modern, sehingga pintu keadilan dapat dibuka lebih lebar dan lebih banyak
pula orang yang dapat dilayani. Berkaitan dengan hal itu Weber juga menyinggung
suatu persoalan yang cukup menarik dalam hubungannya dengan kecenderungan
penegakan hukum yang semakin formal-rasional dan birokratis ini, yaitu bahwa
perkembangan dari hukum modern juga menunjukkan tendensi yang anti-formalistis.
Lihat, Satjipto Rahardjo, Membangun...;Ibid. Bdgk. Satjipto Rahardjo, Masalah
Penegakan...Op. Cit., h. 46.
337
Model Khadi-justiz bentuknya informal sehingga dapat menampung proses yang luwes,
bertolak dari konsep ekspertis, serta ditangani oleh orang-orang yang punya integrity.
Di samping itu, hukum yang substantif-rasional itu terdiri atas postulat-postulat etika,
agama, politik, serta sarana-sarana lain yang diterima dan dipakai dalam masyarakat.
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan... Op. Cit., h. 103-104.
190
tegas, dan terinci. Lembaga pengganti yang dimaksud adalah badan peradilan
modern. Badan peradilan kini telah merupakan bagian dari suatu birokrasi
nasional. Usaha untuk memperoleh keadilan sekarang ini menjadi semakin
jauh dari masyarakat umum disebabkan karena persoalan yang bersifat teknis
hukum, prosedur, dan sebagainya. Oleh karena itu, akibat berbelit dan
berlikunya aturan formal yang harus dilalui di dalam badan peradilan, maka
keadilan dan kebenaran yang dicari sering hilang ditelan liku-liku formalitas.
Untuk menggambarkan betapa liku-liku formalitas berperkara di
dalam ruang sidang pengadilan itu telah menyebabkan terjadi distorsi dalam
lembaga peradilan, berikut ini dapat disimak ungkapan novelis Sidney
Sheldon
338
antara lain: Forum persidangan tidak ubahnya seperti
gelanggang aktor. Jaksa lebih cenderung melontarkan kalimat kebencian dan
kejijikan yang hina kepada terdakwa daripada mencari kebenaran dan
keadilan. Pembela lebih menutamakan kecerdikan bersilat lidah memutar
balik kenyataan yang bersifat menjebak daripada membela dan
mempertahankan kebenaran dan keadilan. Sedangkan hakim juga ikut-ikutan
bermain aktor, sehingga lupa akan fungsi utamanya untuk mencari,
338
Nyatanya kata kemenangan dalam suatu perkara bukan hanya cermin dalam praktik dan
budaya peradilan di Amerika. Di Indonesia juga kata kemenangan dalam berperkara
telah membentuk opini dan budaya serta penghayatan kesadaran hukum masyarakat.
Tidak hanya pada kalangan masyarakat bawah, melainkan juga di kalangan masyarakat
elit. Yang dipertahankan dan diburu oleh masyarakat bukan lagi keadilan, melainkan
kemenangan. Lihat M. Yahya Harahap, Dua Sisi Putusan Hakim Tidak Adil Bagi
Yang Kalah dan Adil Bagi Yang Menang; dalam Varia Peradilan, Tahun VIII,
Nomor 95, Agustus 1993, h. 102-111 [103].
191
menemukan, dan menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth
and justice). Walhasil, kata keadilan sering hanya dihormati dalam
pelanggarannya, sementara itu di dalam ruang sidang, baik jaksa penuntut
umum maupun pembela tidak mencari keadilan; pokok permainannya adalah
untuk menang.
Bagi pihak yang menang perkara, merasa puas dan sangat setuju
terhadap putusan yang dijatuhkan meskipun putusan mengandung
ketidakadilan. Sebaliknya, bagi pihak yang kalah, putusan yang dijatuhkan
tetap dituduh tidak benar meskipun putusan yang bersangkutan benar-benar
adil. Seperti itulah kira-kira gambaran persepsi tentang keadilan menurut
pihak-pihak yang bersengketa. Bahkan gambaran itu pula yang
mencerminkan masyarakat pencari keadilan yang dihadapi oleh dunia
peradilan di Indonesia. Setiap kemenangan identik dengan keadilan,
sementara itu setiap kekalahan yang bagaimana pun adil dan manusiawi tetap
saja dianggap zalim dan tidak adil.
Meskipun demikian, merupakan tugas seorang hakim setelah
memeriksa perkara sengketa selanjutnya harus menjatuhkan putusan yang
mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Apa pun yang terjadi, hakim tidak
dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya telah diperiksa.
Bahkan apabila suatu perkara telah diajukan kepadanya, meski belum
192
diperiksa, seorang hakim tidak wenang untuk menolak perkara tersebut.
339
Dari seorang hakim diharapkan sikap tidak memihak dalam menentukan
siapa yang benar dan siapa yang tidak dalam suatu perkara dan mengakhiri
sengketa atau perkara.
Ketika hendak menjatuhkan putusan, seorang hakim selalu akan
berusaha agar putusannya seberapa mungkin dapat diterima oleh masyarakat,
setidak-tidaknya berusaha agar lingkungan orang yang akan dapat menerima
putusan itu seluas mungkin.
340
Hakim akan merasa lebih lega apabila ia
dapat memuaskan semua pihak dengan putusannya. Meskipun demikian
hakim jarang sekali dapat memberi putusan yang saling memenangkan dan
mengalahkan kedua belah pihak. Oleh karena sudah menjadi kelaziman
dalam praktik hukum, hakim harus dan mesti menjatuhkan pilihan dalam
bentuk memenangkan salah satu pihak dan dengan sendirinya pula akan
mengalahkan pihak yang lain.
339
Periksa Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman; L.N. Tahun 1999 Nomor 147.
340
Para pihak yang berperkara tentu saja yang terutama mendapat perhatian dari hakim,
karena ia harus menyelesaikan atau memutuskannya. Hakim harus memberi tanggapan
terhadap tuntutan para pihak. Ia akan berusaha agar putusannya itu tepat dan tuntas.
Secara objektif putusan yang tepat dan tuntas berarti akan dapat diterima bukan hanya
oleh penggugat melainkan juga oleh tergugat. Hakim akan lebih puas apabila
putusannya memenuhi keinginan dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang
berperkara. Pada umumnya hal itu memang tidak mungkin terjadi, kecuali dalam hal
putusan perdamaian, karena dalam putusan semacam itu tidak ada yang dimenangkan
atau dikalahkan. Sedangkan pada putusan yang bersifat menghukum (condemnatoir)
dimana ada pihak yang dikalahkan dan ada pihak yang dimenangkan, pada umumnya
pihak yang dikalahkan akan merasa tidak puas dan menganggap putusan tersebut tidak
adil atau tidak tepat. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Op. Cit., h. 168-169.
193
Idealnya setiap putusan hakim yang dijatuhkan merupakan putusan
yang objektif dan berwibawa. Akan tetapi rasa keadilan pihak-pihak yang
bersengketa selalu sebaliknya, yakni sangat subjektif. Oleh karena itu, dalam
setiap sengketa yang diputuskan oleh hakim akan selalu dijumpai suatu
keadaan dimana yang dikalahkan akan merasa tidak puas dan menganggap
putusan tersebut tidak adil atau tidak tepat, dan sebaliknya, hanya pihak yang
dimenangkan oleh hakim yang akan merasa putusan tersebut adil dan tepat.
194
BAB IV
PILIHAN FORUM ARBITRASE
BUDAYA HUKUM DAN KEADILAN
A. Pilihan Forum Arbitrase dan Budaya Hukum di Indonesia
Seperti telah diutarakan di muka bahwa proses penyelesaian
sengketa bisnis yang diupayakan pihak-pihak melalui forum lain di luar
pengadilan, merupakan realita perubahan kecenderungan manusia dalam
masyarakat yang harus diterima. Apabila selama ini mekanisme
penyelesaian sengketa mengikuti pola yang terstruktur melalui pengadilan
negeri, maka pilihan forum lebih mengedepankan kebebasan para pihak
dalam menetapkan bentuk lain dari proses yang serupa, namun melalui
mekanisme yang lebih sederhana dan diharapkan di dalam mekanisme
tersebut tidak terjadi distorsi pada penegakan hukum sehingga hasilnya
dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
Penggunaan sistem peradilan modern sebagai sarana pendistribusi
keadilan terbukti menjumpai sangat banyak hambatan. Adapun yang
menjadi faktor penyebab adalah karena peradilan modern sarat dengan
beban formalitas, prosedur, birokrasi, serta metodologi yang ketat. Oleh
karena itu, keadilan yang didistribusikan melalui lembaga peradilan
diberikan melalui keputusan birokrasi bagi kepentingan umum karenanya
195
cenderung berupa keadilan yang rasional. Oleh sebab itu, keadilan yang
diperoleh masyarakat modern tidak lain adalah keadilan birokratis.
341
Penyelesaian sengketa menggunakan pengadilan telah terbukti
banyak menimbulkan ketidakpuasan pada pihak-pihak yang bersengketa
maupun masyarakat luas. Ketidakpuasan masyarakat dilontarkan dalam
bentuk pandangan sinis, mencemooh, dan menghujat terhadap kinerja
pengadilan karena dianggap tidak memanusiakan pihak-pihak yang
bersengketa, menjauhkan pihak-pihak bersengketa dari keadilan, tempat
terjadinya perdagangan putusan hakim, dan lain-lain hujatan yang ditujukan
kepada lembaga peradilan.
Kalangan masyarakat bisnis yang memerlukan kepastian hukum
serta keamanan di dalam investasi maupun aktivitas perdagangannya tatkala
terjadi sengketa menyangkut bisnis mereka, sangat kuatir terhadap kondisi
badan peradilan yang dianggap telah carut marut semacam itu.
Dilatarbelakangi oleh kondisi semacam itulah, muncul keinginan dari
341
Keadilan birokratis adalah keadilan yang diperoleh melalui keputusan birokrasi yang
dirancang untuk melayani kepentingan umum dan didasarkan pada perangkat-
perangkat peraturan yang rasional dan pasti. Sedangkan hukum itu sendiri tidak lain
hanyalah berisi janji. Janji-janji kepada masyarakat yang diwujudkan melalui
keputusan birokrasi. Sementara ide dasar hukum dan ketertiban adalah janji-janji untuk
memberikan keadilan, yakni janji untuk memperbaiki mekanisme perubahan melalui
hukum - terhadap alokasi ganjaran, struktur-struktur kesempatan, dan jalan masuk pada
cara-cara kehidupan kita secara adil. Ini berarti bahwa lembaga peradilan mempunyai
kewajiban untuk memberikan dan menjaga terwujudnya janji-janji hukum dan keadilan
melalui keputusan-keputusan yang meliputi segala aspek kehidupan. Lihat I.S. Susanto,
Lembaga Peradilan dan Demokrasi; Makalah pada Seminar Nasional tentang
Pendayagunaan Sosiologi Hukum dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi
Global, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember 1996, h. 3.
196
komunitas bisnis khususnya, untuk kemudian berpaling dan memilih model
lain dalam penyelesaian sengketa. Meskipun bentuk penyelesaian yang
dipilih itu tergolong masih serumpun dengan mekanisme pada badan
peradilan, namun forum lain yang dipilih itu dianggap dapat memberikan
alternatif serta ruang kebebasan kepada pihak-pihak dalam menentukan
penyelesaian sengketa bisnis mereka. Pada gilirannya model yang dipilih
tersebut diharapkan lebih memberikan peluang untuk mendapatkan rasa
keadilan yang lebih manusiawi dan bermartabat.
Mengkritisi keadaan badan peradilan di Indonesia yang sudah seperti
itu, Satjipto Rahardjo
342
berpendapat, untuk menyebarkan fora pemberian
keadilan tidak semestinya terkonsentrasi pada satu lembaga yang bernama
pengadilan. Marc Galanter memberikan tamsil yang sangat bagus, yaitu
hendaknya ada justice in many rooms.
343
Gagasan Alternative Dispute
Resolution (ADR) sudah tersimpan lama sejak gelombang gerakan Access to
Justice Movement (AJM), terutama gelombang ketiga yang menghendaki
adanya jalur alternatif di luar pengadilan negara.
344
Masalahnya karena
342
Satjipto Rahardjo, Membangun Keadilan Alternatif... Kompsa Op. Cit.,
343
Lihat, Marc Galanter, Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan, Penataan
Masyarakat serta Hukum Rakyat: dalam T.O. Ihromi (ed), Antropologi Hukum
Sebuah...Op. Cit., h. 94-138.
344
Kita harus mengkaji lembaga paradilan dalam konteks saingan-saingannya dan para
mitranya. Untuk dapat melakukan hal itu, maka harus mengesampingkan perspektif
sentralisme hukum yang telah biasa kita terapkan, yaitu sebuah gambaran dimana
alat-alat perlengkapan negara (dan ajaran-ajaran mereka) menempati titik sentral dari
kehidupan hukum dan memiliki kedudukan pengawasan yang hierarkis terhadap penata
197
masyarakat dapat mengalami keadilan atau ketidakadilan bukan saja melalui
forum-forum yang disponsori oleh negara, akan tetapi dapat juga melalui
lokasi-lokasi kegiatan primer. Lokasi kegiatan primer tersebut dapat
berwujud pranata seperti rumah, lingkungan ketetanggaan, tempat bekerja,
kesepakatan bisnis, dan sebagainya (termasuk aneka latar penyelesaian
khusus yang berakar di lokasi-lokasi tersebut).
Keberadaan lembaga peradilan sebagai salah satu pendistribusi
keadilan tidak dapat dilepaskan dari penerimaan dan penggunaan hukum
modern di Indonesia. Hukum modern di Indonesia diterima dan dijalankan
sebagai suatu institusi baru yang didatangkan atau dipaksakan (imposed)
dari luar.
345
Padahal secara jujur, dilihat dari optik sosio kultural, hukum
modern yang kita pakai tetap merupakan semacam benda asing dalam
tubuh kita. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi kesulitan yang dialami
bangsa Indonesia disebabkan menggunakan hukum modern, adalah
menjadikan hukum modern sebagai kaidah positif menjadi kaidah
norma lain yang lebih rendah kedudukannya, seperti misalnya keluarga, korporasi,
jaringan bisnis. Kebiasaan bahwa semua fenomena hukum senantiasa dikaitkan dengan
negara oleh Griffiths dianggap sebenarnya tidak mutlak ...secara empiris tidak
beralasan bahwa negara mempunyai tuntutan yang lebih dari bagian-bagian lain dari
sistem untuk menjadi pusat dari seluruh fenomena hukum. Lihat, Marc Galanter,
Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan..; Antropologi...Loc. Cit.,
Bdgk. Satjipto Rahardjo, Membangun Keadilan Alternatif;...Kompas...Loc. Cit.,
345
Keadaan atau perkembangan seperti itu tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia,
melainkan umumnya negara-negara di luar Eropa dan khususnya di Asia Timur, yang
di dalam itu Indonesia termasuk. Keadaan seperti itu terjadi pula di Cina, Korea,
Jepang, dan lain-lain. Lihat, Satjipto Rahardjo, Supremasi Hukum dalam Negara
Demokrasi dari Kajian Sosio Kultural; dalam Makalah Seminar Nasional
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis, 27 Juli 2000, h. 5-6.
198
kultural.
346
Persoalannya, karena sistem hukum
347
modern yang liberal itu
tidak dirancang untuk memikirkan dan memberikan keadilan yang luas
kepada masyarakat, melainkan untuk melindungi kemerdekaan individu.
348
Di samping itu juga, akibat sistem hukum liberal tidak dirancang untuk
memberikan keadilan substantif, maka seorang dengan kelebihan materiel
akan memperoleh keadilan yang lebih daripada yang tidak.
349
346
Jepang merupakan kasus studi yang sangat menarik karena kemampuannya untuk
menggunakan dan menyerap hukum modern dan pada waktu yang sama menjaga
kelangsungan tatanan sendiri. Masalahnya, bagaimana pun, hukum modern dan Rule of
Law (ROL) mengandung muatan kultural Barat yang sangat kuat. Oleh karena itu,
untuk menjadikan hukum modern suatu kaidah kultural bagi bangsa kita, diperlukan
usaha terus menerus berupa suatu internal cultural discourse and cross-cultural
dialogue. Satjipto Rahardjo, Loc. Cit.,
347
Berbicara mengenai sistem hukum, Adi Sulistiyono menguraikan bahwa, yang
tertangkap dalam pikiran masyarakat adalah hukum positif yang berlaku di suatu
negara, atau para legislator yang membuat undang-undang, atau kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh para pejabat hukum. Padahal sistem hukum tidak hanya berisi
materi hukum, tetapi masih ada unsur lain yang selama ini kurang disadari oleh
masyarakat. Lihat, Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma,...Op. Cit., h. 46.
348
Pikiran liberal ini berpusat pada kemerdekaan individu dengan menata suatu kehidupan
dimana kemerdekaan individu tersebut dijamin keberadaan dan kelanjutan keberadaan
tersebut. Nilai liberal, kemerdekaan individu, menjadi paradigma dalam sistem hukum.
Hal tersebut memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita. Pelajaran itu
adalah, bahwa sistem hukum liberal terutama dirancang untuk memberikan
perlindungan terhadap kemerdekaan individu. Lihat, Satjipto Rahardjo, Rekonstruksi
Pemikiran Hukum di Era Reformasi; dalam Makalah Seminar Nasional
Menggugat Pemikiran Hukum Positivistik di Era Reformasi, PDIH-Undip-
Angkatan V, Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000, h. 6-7.
349
Satjipto Rahardjo, Ibid., h. 8. Sistem yang lebih mengunggulkan kemerdekaan individu
daripada mencari kebenaran dan keadilan memakan banyak korban di Amerika Serikat
dan salah satu perkara yang disebut-sebut sebagai perkara abad ini adalah Perkara O.J.
Simpson yang diputus not guilty. Lihat, Alan M. Derschowitz, Reasonable Doubts.
New York: Simon & Schuster, 1996, h. 42. Bahkan di Indonesia, fenomena orang
yang memiliki banyak uang dapat membeli kemenangan di pengadilan telah menjadi
rahasia bersama para pencari keadilan. Tawar menawar antara hakim pemutus dengan
kuasa hukum pihak-pihak ketika putusan hendak dijatuhkan adalah cerita yang sangat
memilukan sekaligus memalukan dalam proses penegakan keadilan. Oleh sebab itu,
apa yang dipaparkan Galanter telah menjadi kenyataan di Indonesia. Lihat, Marc
Galanter ,Why The Haves Come Out Ahead: Speculations on The Limits of Legal
Change; Law and Society, Fall 1974, h. 95-151.
199
Apabila kita terus menerus berpegang kepada doktrin liberal
tersebut, maka kita akan tetap berputar-putar dalam pusaran kesulitan untuk
mendatangkan atau menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam rangka
melepaskan diri dari doktrin liberal itulah, maka gagasan orang-orang atau
pihak-pihak untuk mencari dan menemukan keadilan melalui forum
alternatif di luar lembaga pengadilan modern sesungguhnya merupakan
upaya penolakan terhadap cara berpikir hukum yang tertutup.
350
Hal itu
disebabkan para pencari keadilan masih sangat merasakan, betapa pun tidak
sekuat seperti pada abad ke-sembilanbelas, filsafat liberal dalam hukum
dewasa ini masih sangat besar memberi saham terhadap kesulitan
menegakkan keadilan substansial (substantial justice).
351
Sebagaimana telah diutarakan di muka bahwa hukum modern di
Indonesia diterima dan dijalankan sebagai suatu institusi baru yang
350
Praktik hukum kita sekarang pada dasarnya masih didasarkan pada positivisme abad
ke-sembilanbelas, sedang filsafat yang ada di belakang adalah liberalisme atau pikiran
hukum liberal. Filsafat hukum liberal bertumpu kepada perlindungan kebebasan dan
kemerdekaan manusia. Sekalian konstruksi, asas, doktrin, disiapkan untuk menjaga,
mengamankan dan melestarikan paradigma nilai tersebut. Persamaan di hadapan
hukum menjadi pilar utama. Dalam perumusan secara positif maka tidak boleh ada
peraturan yang memuat diskriminasi. Hanya sampai disitulah liberalisme
menghantarkan masyarakat memasuki dunia hukum. Proses-proses hukum selanjutnya
harus patuh menjunjung persamaan dan non-diskriminasi. Ini menjadi tugas penting
dari hukum, tetapi lebih dari itu juga merupakan tugas satu-satunya. Dengan demikian
filsafat hukum liberal menganggap bahwa tugasnya sudah selesai apabila sudah
berhasil untuk mempertahankan dan menjaga paradigma nilai liberal tersebut. Apabila
keadilan menjadi taruhan dalam hukum, maka filsafat hukum liberal beranggapan,
bahwa dengan cara demikian itu keadilan sudah diberikan. Lihat, Satjipto Rahardjo,
Rekonstruksi... Op. Cit., h. 21-23.
351
Oleh karena itu, Soetandyo Wignjosoebroto antara lain menyatakan: transitional
justice merupakan jalan tengah sebuah pendekatan win-win solution, sehingga
200
didatangkan atau dipaksakan (imposed) dari luar, yakni melalui kebijakan
kolonial di Hindia-Belanda.
352
Padahal suatu peralihan dari status sebagai
bangsa terjajah menjadi bangsa merdeka sungguh merupakan suatu
momentum yang cukup krusial. Dalam kehidupan hukum di masa Hindia-
Belanda, bangsa Indonesia tidak mengambil tanggung jawab sepenuhnya
dalam masalah penegakan, pembangunan, dan pemeliharaan hukumnya,
melainkan hanya sekadar menjadi penonton dan objek kontrol oleh hukum.
Sedangkan sejak hari kemerdekaannya, bangsa Indonesia terlibat secara
penuh ke dalam sekalian aspek penyelenggaraan hukum, mulai dari
pembuatan sampai kepada pelaksanaannya di lapangan.
353
Akibat berlangsungnya transplantasi sistem hukum
354
asing (Eropa)
ke tengah tata hukum (legal order) masyarakat pribumi yang otohton
kompromi tidak bisa dihindarkan. Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Keadilan
Komutatif, win-win Solution, dalam Kompas 25 Nopember 2000.
352
Kebijakan itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan de bewuste rechtspolitiek.
Kebijakan untuk membina tata hukum kolonial secara sadar ini berefek di satu pihak
mengontrol kekuasaan dan kewenangan raja dan aparat eksekutif atas daerah jajahan,
dan di lain pihak akan ikut mengupayakan diperolehnya perlindungan hukum yang
lebih pasti bagi seluruh lapisan penduduk yang bermukim dan/atau berusaha di daerah
jajahan. Kebijakan yang disebut de bewuste rechtspolitiek tersebut khususnya yang
bertalian dengan langkah-langkah tindakan yang diambil para politisi eksponennya di
bidang perundang-undangan, pemerintahan, dan pengadilan. Lihat, Soetandyo
Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial...Op. Cit., h. 19-20.
353
Lihat, Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-
proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi; Makalah Seminar
Nasional Sosiologi Hukum dan Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia.
Semarang, 12-13 Nopember 1996, h. 5-7.
354
Istilah transplantasi sistem hukum adalah sebutan yang digunakan oleh Soetandyo
Wignjosoebroto di dalam paparannya mengenai berlangsungnya proses introduksi dan
proses perkembangan suatu sistem hukum asing ke/di dalam suatu tata kehidupan dan
tata hukum masyarakat pribumi yang otohton. Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, Dari
Hukum Kolonial...Op. Cit., h. 1-7.
201
tersebut, maka ada konsekuensi yang mesti dipikul bangsa Indonesia ketika
harus terlibat penuh dalam penyelenggaraan hukum. Konsekuensi tersebut
berupa keniscayaan untuk membangun dan mengembangkan perilaku
hukum (legal behavior)
355
baru dan budaya hukum untuk mendukung
perubahan status dari jajahan ke kemerdekaan. Dalam kaitan itu, Satjipto
Rahardjo
356
menyatakan, tidak mudah untuk mengubah perilaku hukum
bangsa Indonesia yang pernah dijajah menjadi bangsa yang merdeka, karena
waktu lima puluh tahun belum cukup untuk melakukan perubahan secara
sempurna.
Membicarakan mengenai perilaku hukum dan budaya hukum tentu
tidak dapat menghidarkan diri dari pembicaraan tentang sistem hukum,
karena perilaku dan budaya hukum keduanya merupakan unsur dari sistem
hukum. Di samping kedua unsur tersebut, Kees Schuit
357
menguraikan
unsur-unsur yang termasuk dalam suatu sistem hukum, yaitu:
1. Unsur idiil. Unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum,
yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas.
Unsur inilah yang oleh para yuris disebut sistem hukum.
355
Perilaku hukum (legal behavior) adalah perilaku yang dipengaruhi oleh aturan,
keputusan, perintah, atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan
wewenang hukum. Lihat, Lawrence M. Friedman, American Law...Op. Cit., h. 280.
356
Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum...Op. Cit., h. 7.
357
Lihat, J.J. H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum; terjemahan Arief Sidharta.
Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, h. 140. Sementara itu John Henry Merryman
mengungkapkan pengertian A legal system, is an operating set of legal institution,
202
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-
organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu
sistem hukum. Yang termasuk ke dalamnya adalah juga para
pengemban jabatan (ambtsdrager), yang berfungsi dalam
kerangka suatu organisasi atau lembaga.
3. Unsur aktual. Unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan
perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem
makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun
dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem
hukum itu.
Sementara itu L.M. Friedman
358
mengungkapkan tiga komponen dari
sistem hukum. Ketiga komponen dimaksud adalah: (1) struktur, (2)
substansi, dan (3) kultur atau budaya. Pertama, sistem hukum mempunyai
struktur,
359
yaitu kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang
menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Struktur terdiri atas:
jumlah serta ukuran pengadilan, jurisdiksinya (jenis perkara yang diperiksa
serta hukum acara yang digunakan), termasuk di dalam struktur ini juga
procedures, and rules." Lihat, dalam The Civil Law Tradition. Stanford University
Press, Stanford, California, 1969, h. 1.
358
Lawrence M. Friedman, The Legal System. New York: Russel Sage Foundation, 1975,
h. 11-16. Bdgk. L.M. Friedman, American Law...Op. Cit., h. 6-11.
359
Is its skeletal framework; it is the permanent shape, the institutional body of the
system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds.
203
mengenai penataan badan legislatif. Kedua, substansi,
360
yaitu aturan,
norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu.
Termasuk ke dalam pengertian substansi ini juga produk yang dihasilkan
oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka
keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Ketiga, adalah kultur
361
atau
budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum
kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum ini pun
dimaknai sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang
menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.
Selanjutnya Friedman
362
merumuskan budaya hukum sebagai sikap-sikap
dan nilai-nilai yang ada hubungan dengan hukum dan sistem hukum, berikut
sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun
negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Demikian juga
kesenangan atau ketidak senangan untuk berperkara adalah bagian dari
budaya hukum. Oleh karena itu, apa yang disebut dengan budaya hukum itu
tidak lain dari keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem
hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik
360
The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions
should behave.
361
Legal culture refers to public knowledge of and attitudes and behavior patterns
toward the legal system. Do people feel and act as if courts are fair? When are they
willing to use courts? What parts of the law do they consider legitimate? What do they
know about the law in general? The term legal culture roughly describes attitudes
about law, more or less analogous to the political culture.
362
Lihat, Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma...Op. Cit., h. 47-48.
204
masyarakat umum. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa yang
disebut budaya hukum adalah keseluruhan sikap dari warga masyarakat dan
sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana
seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.
Friedman
363
juga membedakan budaya hukum menjadi external and
internal legal culture. Menurut Esmi Warassih
364
budaya hukum seorang
hakim (internal legal culture) akan berbeda dengan budaya hukum
masyarakat (external legal culture). Bahkan perbedaan pendidikan, jenis
kelamin, suku, kebangsaan, pendapatan, dan lain-lain dapat merupakan
faktor yang mempengaruhi budaya hukum seseorang. Budaya hukum
merupakan kunci untuk memahami perbedaan-perbedaan yang terdapat di
dalam sistem hukum yang lain. Selanjutnya dikemukakan, penerapan suatu
sistem hukum yang tidak berasal atau ditumbuhkan dari kandungan
masyarakat merupakan masalah, khususnya di negara-negara yang sedang
berubah karena terjadi ketidakcocokan antara nilai-nilai yang menjadi
pendukung sistem hukum dari negara lain dengan nilai yang dihayati oleh
anggota masyarakat itu sendiri.
365
Mengacu pada pendapat tersebut, tidak
ada keraguan kalau penggunaan lembaga pengadilan sebagai tempat
363
The external legal culture is the legal culture of general population; the internal legal
culture is the legal culture of those members of society who perform specialized legal
task. L.M. Friedman, The Legal...Op. Cit., h. 223.
364
Lihat, Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat...Op. Cit., h. 11.
365
Esmi Warassih, Ibid., h. 12.
205
penyelesaian sengketa sesungguhnya tidak cocok dengan nilai-nilai yang
hidup dan dihayati masyarakat pribumi Indonesia. Masalahnya, seperti telah
diungkapkan di muka dilihat dari optik sosio kultural, hukum modern yang
digunakan dewasa ini merupakan hasil transplantasi
366
sistem hukum asing
(Eropa) ke tengah tata hukum (legal order) masyarakat pribumi Indonesia,
sehingga sangat wajar apabila lembaga pengadilan yang merupakan bagian
sekaligus penyangga dari sistem hukum modern itu meski telah
dintroduksikan ke dalam sistem hukum Indonesia selama enam dekade
367
sejak tahun 1942, namun tetap saja merupakan semacam benda asing
dalam tubuh kita.
Bertolak dari serangkaian fakta di muka, tentu harus diakui sebab
bagaimana pun seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia telah
banyak terbangun dan terstruktur secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-
asas yang telah digariskan sejak lama sebelum kekuasaan kolonial tumbang.
366
Soetandyo Wignjosoebroto, Op. Cit., supra (catatan kaki no. 256).
367
Di zaman pendudukan Jepang sistem peradilan Indonesia mengalami perubahan yang
revolusioner, yang pada pokoknya menuju kepada penyederhanaan dan peningkatan
kecepatan jalannya peradilan sistem hakim tunggal dan penghapusan dualisme serta
sifat koloialistis dari sistem peradilan pada waktu itu. Lihat Sudikno Mertokusumo,
Sejarah Peradilan...Op. Cit., h. 25. Sementara itu Soetandyo Wignjosoebroto
menyatakan, ...Kontribusi paling penting yang diberikan oleh Jepang kepada sistem
hukum Indonesia adalah dihapuskannya dualisme dalam tata peradilan. Kini hanya ada
satu sistem peradilan saja untuk semua golongan penduduk (kecuali untuk orang-orang
Jepang). Badan pengadilan tertinggi adalah Hooggerechtshof yang kini (maksudnya
pada masa pendudukan Jepang: pen.) disebut Saikoo Hooin, dan kemudian berturut-
turut adalah Raad van Justitie (Kootoo Hooin), Landraad (Tihoo Hooin), Landgerecht
(Keizai Hooin), Regentschapsgerecht (Ken Hooin), dan Districtsgerecht (Gun Hooin).
Residentiegerecht, yang pada masa kekuasaan Hindia Belanda mempunyai yurisdiksi
206
Sementara itu budaya hukum para yuris yang mendukung beban kewajiban
membangun hukum nasional amat sulit untuk menemukan pemikiran-
pemikiran yang lateral dan menerobos.
368
Selanjutnya Soetandyo
Wignjosoebroto
369
menyatakan: Berguru kepada guru-guru Belanda dalam
situasi kolonial, pemikiran para yuris nasional ini pun mau tak mau telah
diprakondisi oleh dotrin-doktrin yang telah ada. Para perencana dan para
pembina hukum nasional juga sekalipun mereka itu mengaku bersitegak
sebagai eksponen hukum adat dan hukum Islam adalah sesungguhnya
pakar-pakar yang terlanjur terdidik dalam tradisi hukum Belanda, dan
sedikit banyak akan ikut dicondongkan untuk berpikir dan bertindak
menurut alur-alur-alur tradisi ini, dan bergerak dengan modal sistem hukum
positif peninggalan hukum Hindia Belanda (yang tetap dinyatakan berlaku
berdasarkan berbagai aturan peralihan).
Padahal hukum yang dibutuhkan oleh dan untuk negeri berkembang
yang tengah berubah lewat upaya-upaya pembangunan seperti Indonesia ini
adalah hukum yang dapat berfungsi sebagai pembaharu, dan bukan sekadar
sebagai pengakomodasi perubahan seperti yang diimplisitkan dalam ajaran
khusus untuk mengadili perkara orang-orang Eropa saja, kemudian dihapuskan. Lihat,
Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial...Op. Cit., h. 184.
368
Soetandyo Wignjosoebroto, Ibid., h. 188.
369
Soetandyo Wignjosoebroto, Loc. Cit.,
207
the sociological jurisprudence Roscoe Pound.
370
Ditengarai oleh Robert
Seidman bahwa pengalaman hukum yang melahirkan institusi-institusi
hukum modern itu sesungguhnya cultural bound dalam konteks tradisi
hukum Barat. Hukum yang dibingkai oleh tradisi dan konfigurasi kultural
Barat ini nyata-nyata tidak mudah untuk dengan begitu saja dipakai untuk
mengatasi permasalahan hukum dan permasalahan pembangunan pada
umumnya di negeri-negeri berkembang non-Barat
371
yang memiliki aset-
aset sosio-kultural yang berbeda. Inilah kenyataan yang ditengarai oleh
Robert B. Seidman sebagai the Law of the Nontransferability of law.
372
370
Ajaran hukum Roscoe Pound tidak hanya mengukuhkan eksistensi the common law
system, dan kemudian juga tetap memperkuat pengakuan akan peran dan otonomi
profesi hukum (yang mengkonsentrasikan aktivitasnya, di dalam fungsi peradilan yang
terlindung dari berbagai kemungkinan intervensi politik). Akan tetapi juga mencabar
dan mempertanyakan kemampuan ajaran the analytical jurisprudence atau die Reine
Rechtslehre (yang kedua-duanya mendasari civil law system yang dianut di negeri-
negeri Eropa Kontinental dan negeri-negeri bekas jajahannya) untuk secara progresif
juga memutakhirkan hukum dan fungsinya di tengah-tengah perubahan kehidupan
yang terjadi. Lihat, Soetandyo Wignyosoebroto, Sebuah Pengantar ke Arah
Perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II; Makalah
disampaikan pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi
Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, BPHN, Jakarta, 10-21 Juli 1995; dimuat
dalam Majalah Hukum Trisaksi Edisi Khusus, TT, h. 37-44 [39].
371
Benturan antara sistem hukum modern dengan nilai-nilai budaya masyarakat semacam
ini tidak hanya dialami dan terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami oleh India dan
juga Jepang. Lihat Marc Galanter, Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum
India Modern; dalam AAG Peters & Koesriani Siswosoebroto (eds), Hukum dan
Perkembangan Sosial Buku II...Op. Cit., h. 146-191. Untuk kasus Jepang dapat
diketahui dari paparan yang dilakukan oleh Dan Fenno Henderson. Lihat dalam Dan
Fenno Henderson. Modernisasi Hukum dan Politik di Jepang; dalam AAG Peters &
Koesriani Siswosoebroto (eds), Hukum dan Perkembangan Sosial Buku II... Loc.
Cit., h. 25-94.
372
Pada dasarnya memang tidak mudah untuk mentransfer begitu saja suatu sistem hukum
tertentu, dalam hal ini sistem hukum modern, kepada masyarakat lain yang mempunyai
latar belakang budaya yang berlainan. Dalam kaitan ini Robert B. Seidman
mengemukakan: ...a rule transferred from one culture to another simply cannot be
208
Melengkapi uraian di muka, Esmi Warassih juga mengemukakan,
Secara umum dapat dikatakan bahwa lapisan pengambil keputusan
umumnya menjatuhkan pilihannya kepada sistem hukum yang modern
rasional, sementara hal tersebut tidak selalu sejalan dengan kesiapan
masyarakat di dalam menerima sistem tersebut. Oleh karena itu, dapat
dipahami jika penggunaan hukum modern beserta segenap institusi-institusi
hukumnya kemudian menimbulkan persoalan yang cukup krusial di dalam
masyarakat. Apalagi ketika lembaga pengadilan sebagai pranata dan
penyangga sistem hukum modern terbukti tidak mampu menjawab
tantangan perubahan yang tengah berlangsung di negara ini terutama dalam
tugasnya menegakkan dan mendistribusikan keadilan kepada masyarakat.
Pengalaman sesudah kemerdekaan, para pengusaha merasakan
betapa pengadilan tidak bersimpati terhadap masalah dan kebutuhan para
pengusaha. Menurut Daniel S. Lev
373
perubahan sosial dan ekonomi yang
cukup luas juga menyebabkan perubahan dalam budaya hukum masyarakat.
Prosedur peradilan menjerakan para pengusaha untuk menggunakan
pengadilan. Berkaitan dengan hal itu, dikutipnya secara lengkap komentar
seorang advokat yang termasuk angkatan tua dari Bandung, yang
expected to induce the same sort of role-performance as it did in the place of ...origin.
Lihat, L.M. Friedman, The Legal System...Op. Cit., h. 195.
373
Daniel S. Lev, Hukum dan Politik...Op. Cit., h.165.
209
mengatakan: ...Para hakim dewasa ini kurang memahami hukum dan
kurang menaruh perhatian. Saya menulis alasan-alasan yang lengkap untuk
perkara-perkara saya, tetapi para hakim muda sering marah karena alasan
tersebut terlalu panjang untuk dibaca. ...Maka terlepas dari tidak adanya rasa
senang saya di pengadilan, tidak ada pentingnya bagi perusahaan yang saya
wakili untuk mengajukan perkaranya ke pengadilan kecuali kalau hal itu
mutlak perlu. Dan tidak hanya pengadilan yang sulit, tetapi keseluruhan
prosesnya pun berliku-liku. Kita harus memberi uang tidak resmi kepada
panitera untuk memperoleh dokumen eksekusi bila putusan pada akhirnya
sudah dijatuhkan. Terlalu banyak saluran yang harus dilalui agar segala
sesuatunya dikerjakan, dan kesemuanya itu perlu biaya. Dalam semua
kontrak yang saya tulis untuk perusahaan klien saya, saya masukkan
klausula arbitrase sehingga terhindar dari urusan dengan pengadilan.
Komentar di atas betapa pun menjukkan bahwa penghindaran
penyelesaian peselisihan melalui pengadilan di kalangan pelaku bisnis
tampaknya mempunyai sumber dukungan lain di samping kecenderungan
budaya. Arbitrase menjadi forum alternatif yang menjadi pilihan dan
tumpuan yang dipercaya oleh para pelaku bisnis untuk menyelesaikan
sengketa mereka di luar pengadilan, karena para pelaku bisnis terutama yang
berasal dari negara-negara maju meyakini bahwa arbitrase mempunyai
210
karakteristik yang sesuai dengan budaya bisnis. Seperti dikemukakan oleh
Robert Coulson:
374
Business executives are losing patience with judicial solutions that
take years to achive results and that leave both parties exhausted by delays
and legal expenses. Many people like what alternative dispute resolution
can offer. They are finding that commercial arbitration and mediation are
sensible ways to resolve business dispute.
Pada dasarnya tidak ada pelaku bisnis yang hendak kehilangan
peluang berbisnis hanya karena menghadapi penyelesaian sengketa dengan
mitranya yang berlarut-larut di pengadilan. Oleh karena itu, walaupun
arbitrase sesungguhnya merupakan institusi penyelesaian sengketa yang
menggunakan pendekatan pertentangan (adversarial) dengan hasil win-lose
seperti juga pengadilan,
375
akan tetapi arbitrase tetap dianggap berbeda
dengan pengadilan. Yang dianggap sebagai perbedaan cukup penting oleh
para pelaku bisnis antara arbitrase dengan pengadilan adalah, dalam
arbitrase mereka mempunyai kedaulatan untuk menetapkan arbiter yang
terdiri atas pakar-pakar yang ahli di bidangnya untuk memeriksa dan
374
Robert Coulson, Business Arbitration...Op. Cit., h. 32.
375
Di dalam literatur, arbitrase dikenal dengan sebutan particuliere rechtspraak; Lihat,
A.J. van den Berg et al., Arbitrage recht...Op. Cit., h. 7. Arbitrase adalah suatu bentuk
peradilan, yaitu peradilan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dibebani
kewajiban untuk melakukan peradilan oleh undang-undang. Alasan bahwa arbitrase
adalah suatu bentuk peradilan karena arbitrase memenuhi ciri-ciri pengadilan
sebagaimana dikemukakan oleh F.F. van der Haijden. Dalam tesisnya van der Haijden
mengemukakan bahwa peradilan memiliki 4 (empat) ciri, yaitu: (1) there should be a
settlement of a conflict; (2) the conflict must be decided on the basis of law; (3) it
should be decided by a third party; (4) and the parties to the conflict should be bound
by the decision. Lihat, Setiawan, Aneka Masalah Hukum...Op. Cit., h. 4.
211
memutus sengketa mereka. Sedangkan kedaulatan para pihak semacam itu
sama sekali tidak mungkin diekspresikan di depan badan peradilan umum.
Namun demikian perkembangan dan penggunaan arbitrase sebagai
forum penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan di Indonesia masih
terhambat oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor penghambat tersebut
diungkapkan Adi Sulistiyono,
376
sebagai berikut: (1) ketentuan hukum yang
mengatur masalah arbitrase
377
di Indonesia belum banyak diketahui dan
dipahami oleh pelaku bisnis; (2) belum ada budaya arbitration minded di
kalangan pengusaha Indonesia; (3) banyak di antara mereka yang belum
berani membawa sengketa yang dialaminya keluar dari jalur ajudikasi
publik (baca: peradilan). Hal itu disebabkan selama ini mereka belum
mengetahui keberhasilan arbitrase atau BANI dalam menangani sengketa
bisnis; (4) profesionalitas dan kredibilitas arbiter, baik itu selaku pribadi
maupun dalam menyelesaikan sengketa di Indonesia belum banyak
diketahui oleh para pelaku bisnis; (5) belum banyak konsultan hukum
Indonesia yang mau memperkenalkan/mengarahkan kliennya untuk
bersengketa melalui arbitrase; (6) tidak mudah membawa dan menyadarkan
376
Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma...Op. Cit., h. 90.
377
Sebagai perangkat normatif untuk memberikan rujukan dalam hal pihak-pihak
menghendaki untuk melakukan pilihan forum di luar pengadilan untuk menyelesaikan
sengketa, sejak tahun 1999 Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Disahkan dan
diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1999, LN RI Tahun 1999 Nomor 138.
212
pihak-pihak yang bersengketa agar menyelesaikan sengketa melalui
arbitrase dengan itikad baik. Seringkali pihak-pihak telah sepakat membawa
sengketanya ke arbitrase, namun setelah sengketa tersebut diputuskan oleh
arbiter, pihak yang merasa kalah tidak mau secara sukarela melaksanakan
putusan tersebut; dan (7) hakim-hakim kurang memahami tentang masalah
arbitrase, sehingga seringkali suatu sengketa yang berdasarkan klausula
arbitrase seharusnya diselesaikan melalui arbitrase, namun pengadilan
negeri tetap saja menangani sengketa tersebut.
Menyimak tujuh faktor yang disinyalir sebagai penghambat
perkembangan arbitrase di Indonesia, maka bagaimana pun juga arbitrase
hanya bisa tumbuh dan berkembang apabila didukung oleh kalangan para
usahawan itu sendiri. Pembuat Undang-undang telah cukup mengakomodasi
perangkat normanya. Pada akhirnya pilihan forum ke arah arbitrase hanya
akan bermanfaat dan memberi keuntungan dibandingkan dengan berperkara
di pengadilan, seandainya sejak semula sudah dapat ditentukan bahwa pihak
yang akan dikalahkan akan dengan sukarela menaati dan melaksanakan
putusan arbitrase tersebut.
B. Faktor Internal Pengadilan Negeri dan Pilihan Forum Arbitrase
Pengadilan di sini bukan diartikan semata-mata sebagai badan untuk
mengadili, melainkan sebagai pengertian yang abstrak, yaitu hal
213
memberikan keadilan. Hal memberikan keadilan berarti yang bertalian
dengan tugas badan pengadilan atau hakim dalam memberi keadilan, yaitu
memberikan kepada yang bersangkutan konkritnya kepada yang mohon
keadilan apa yang menjadi haknya atau apa hukumnya.
378
Eksistensi
pengadilan sebagai lembaga yang berfungsi menyelenggarakan proses
peradilan dalam menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa masyarakat,
tugas-tuganya diwakili oleh hakim. Oleh karena itu, kepercayaan
masyarakat terhadap hukum serta institusi peradilan di negara ini ditentukan
oleh kredibilitas dan profesionalitas hakim dalam menjalankan tugasnya
menyelesaikan sengketa serta menegakkan keadilan.
379
Jadi, para hakim dituntut untuk secara total melibatkan dirinya pada
saat membuat putusan, bukan hanya mengandalkan kemahirannya mengenai
perundang-undangan. Menurut Roeslan Saleh,
380
seorang hakim diharapkan
senantiasa menempatkan dirinya dalam hukum, sehingga hukum baginya
merupakan hakekat dari hidupnya. Hakim tidak boleh menganggap hukum
sebagai suatu rangkaian dari larangan dan perintah yang akan mengurangi
378
Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan...Op. Cit., h. 2.
379
Kita sebaiknya menjadi lebih mengerti, bahwa teriakan supremasi hukum (the cry for
supremacy of law) itu adalah seruan ke arah pengadilan atau hukum yang berkeadilan.
Oleh karena itu, sekarang kita tahu, bahwa apabila kita bicara tentang supremasi
hukum, maka yang ada dalam pikiran kita adalah keunggulan dari keadilan dan
kejujuran. Bukan undang-undang yang kita pikirkan tetapi keadilan itulah. Lihat,
Satjipto Rahardjo, Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang; Kompas, Rabu, 24
Mei 2000.
380
Roeslan Saleh, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta: Aksara Baru,
1979, h. 29.
214
kemerdekaannya, melainkan sebaliknya hukum harus menjadi sesuatu yang
mengisi kemerdekaannya. Oleh karena hukum itu bukan semata-mata
peraturan atau undang-undang, tetapi lebih daripada itu: perilaku. Undang-
undang memang penting dalam negara hukum, akan tetapi bukan segalanya
dan proses memberi keadilan kepada masyarakat tidak begitu saja berakhir
melalui kelahiran pasal-pasal undang-undang.
381
Seperti telah diutarakan di muka, bahwa dalam sistem hukum di
mana pun di dunia, keadilan selalu menjadi objek perburuan melalui
lembaga pengadilannya. Namun demikian kerusakan dan kemerosotan
dalam perburuan keadilan melalui hukum modern disebabkan permainan
prosedur yang menyebabkan timbul pertanyaan apakah pengadilan itu
tempat mencari keadilan atau kemenangan?
382
Keadilan memang barang
yang abstrak dan karena itu perburuan terhadap keadilan merupakan usaha
yang berat dan melelahkan. Sementara itu, pengadilan sebagai institusi
pendistribusi keadilan telah menjadi institusi modern yang dirancang secara
spesifik bersamaan dengan munculnya negara modern sekitar abad ke
delapan belas. Oleh karena itu, pekerjaan mengadili tidak lagi hanya bersifat
381
Undang-undang tidak berisi petunjuk absolut yang tinggal dioperasikan oleh manusia,
melainkan ia memuat semacam ruang kebebasan yang tidak kecil. Apabila ruang
kebebasan itu tidak ada, maka tentu tidak akan berbicara mengenai perilaku. Melalui
perilaku inilah pengoperasian undang-undang tidak dijadikan medan dimana manusia
menjadi tawanan undang-undang. Lihat, Satjipto Rahardjo, Tidak Menjadi Tawanan
Undang-undang; Kompas, Kamis, 25 Mei 2000.
382
Satjipto Rahardjo, Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif; Kompas., Sabtu, 12
Oktober 2002...Op. Cit.
215
mengadili secara substansial - seperti pada masa lampau ketika Khadi
Justice, yaitu suatu peradilan yang tidak berorientasi kepada fixed rules of
formally rational law, melainkan kepada hukum substantif yang bertolak
dari postulat-postulat etika, religi, politik, dan lain-lain pertimbangan
kemanfaatan. Setelah menjadi institusi modern, pengadilan merupakan
penerapan dari prosedur yang ketat.
383
Berdasarkan optik sosiologi hukum yang lebih memperhatikan
fungsi dari badan yang menjalankan fungsi mengadili, maka dalam rangka
menemukan keadilan serta dimana keadilan diputuskan, faktor lembaga atau
badan pemutus keadilan yang diakui menjadi tidak penting. Putusan tentang
keadilan dapat dilakukan dimana saja dalam masyarakat, tidak perlu harus
di pengadilan.
384
Oleh sebab itu, menegakkan dan menemukan keadilan
tidak semata-mata harus dilakukan melalui struktur formal lembaga
383
Menurut Weber, sebelum hadir negara modern, rasionalisasi belum masuk ke dalam
pengadilan, sehingga tidak ada perpecahan antara formal justice dengan substantial
justice. Sementara itu pengadilan modern mempunyai arsitektur yang demikian formal-
rasional sebagai bagian dari karakteristik hukum modern yang disebut tipe legal
domination. Oleh karena itu, pengadilan muncul sebagai hasil rancangan artifisial yang
rasional seperti yang kita kenal sekarang, sehingga berbicara tentang keadilan, dikenal
terdapat dua macam, yaitu (i) keadilan substansial (substantial justice) dan (ii) keadilan
formal (formal justice atau legal justice). Sedangkan pada masa lampau, pembedaan
keadilan seperti itu tidak ada, oleh karena tidak ada peraturan yang kompleks yang
mengatur bagaimana putusan pengadilan diberikan. Pada waktu itu mengadili adalah
memberikan putusan secara substansial. Lihat, Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum:
Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah. Surakarta: Muhammadiyah
University Press, 2002, h. 134 -136.
384
Bahkan Jerold S. Auerbach antara lain mengatakan: ...As dissatisfaction with legal
institutions increased during the early decades of the twentieth century, there was
renewed interest in alternatives to litigation, especially conciliation and arbitration.
Both were touted as speedy, inexpensive procedures to dispense with lawyers and
216
pengadilan. Fungsi mengadili dapat dilakukan dan berlangsung di banyak
lokasi, sehingga Marc Galanter
385
mengungkapkan dengan sebutan justice
in many rooms. Atas dasar hal itu, maka memilih forum arbitrase untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis merupakan kecenderungan
beralihnya minat masyarakat pencari keadilan dari menggunakan jalur
litigasi pada pengadilan kepada jalur lain yang formatnya lebih tidak
terstruktur secara formal. Namun demikian, bentuk yang disebut terakhir itu
diyakini oleh para penggunanya akan mampu melahirkan keadilan
substansial. Padahal selama beberapa dekade masyarakat di sejumlah
negara,
386
termasuk di Indonesia memberikan kepercayaan kepada lembaga
pengadilan untuk mengelola sengketa yang sedang dihadapi, dengan
harapan akan memperoleh keadilan sebagaimana secara normatif dan
eksplisit disebutkan dalam ketentuan perundang-undangan.
387
Akan tetapi
faktanya lembaga pengadilan telah terbukti tidak mampu memenuhi harapan
reduce the acrimonius, costly delay that suffused litigation. Lihat Jerold S. Auerbach,
Justice Without Law? New York: Oxford University Press, 1983, h. 96.
385
Marc Galanter, Justice in Many Rooms; dalam Maurio Cappelletti (ed), Access to
Justice and The Welfare State. Italy: European University Institute, 1981, h. 147-182.
386
Kecuali pada masyarakat Jepang, penggunaan cara litigasi telah dicap sebagai salah
secara moral, subversif, dan memberontak, karena proses litigasi menghasilkan
disorganisasi dari kelompok-kelompok sosial yang tradisional. Dalam proses litigasi
kedua belah pihak berusaha untuk membenarkan posisinya berdasarkan standar
objektif, dan dibuatnya putusan pengadilan berdasarkan hal itu cenderung untuk
mengubah kepentingan situasional ke dalam kepentingan yang diteguhkan dengan
kuat dan berdiri sendiri. Lihat, Takeyoshi Kawashima, Penyelesaian Pertikaian di
Jepang Kontemporer; dalam AAG Peters & Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan
Perkembangan...Buku II...Op. Cit., h. 99.
387
Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
217
masyarakat pencari keadilan. Banyak faktor yang menyebabkan pengadilan
menjadi seperti itu.
388
Adi Andojo Soetjipto,
389
(mantan Ketua Muda Mahkamah Agung)
mengungkapkan sejumlah faktor-faktor yang menjadi indikasi betapa
kondisi buruk lembaga peradilan di Indonesia diawali oleh terpuruknya
moralitas para hakim. Berikut ini serangkaian indikasi dimaksud
sebagaimana disarikan dari paparan Adi Andojo dalam tulisannya, antara
lain: (i) untuk memperoleh jabatan hakim, seorang calon hakim telah
menggunakan jalan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya,
maka bisa diduga bahwa orang itu kelak setelah menjadi hakim juga akan
tidak punya pegangan etika. Kedaan itu akan merusak segala-galanya, baik
penegakan hukumnya maupun keadilannya, bahkan sistem peradilannya
akan runtuh; (ii) akibat hakim tidak lagi memegang etika, sehingga banyak
hakim yang mencari rezeki dari perkara yang ditanganinya; (iii) hakim telah
banyak yang lupa bahwa sesungguhnya mereka memiliki pegangan etika
yang sangat mendasar sebab dia dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia
dalam memberikan keadilan. Faktor ini barangkali merupakan faktor
388
Mardjono Reksodiputro, antara lain menyatakan bahwa ketidakpercayaan
masyarakat kepada pengadilan adalah salah satu kendala besar dalam mewujudkan
Indonesia sebagai negara hukum. Lihat Mardjono Reksodiputro, Pembaharuan
Hukum Sebaiknya dari Pembenahan Peradilan. dalam Kompas, 1 Mei 1999.
389
H. Adi Andojo Soetjipto, Etika Profesi; dalam Varia Peradilan, Tahun VIII, Nomor
95, Agustus 1993, h. 134 141.
218
terpenting karena menyangkut ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Para hakim terikat oleh kewajiban moral kepada Tuhannya karena putusan
yang dihasilkannya berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Apabila hakim mempermainkan keadilan, berarti dia
mempermainkan ketaqwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa serta
merendahkan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya oleh Tuhan,
Negara, dan masyarakat.
Mencoba bangun dari keterpurukan dalam menegakkan hukum dan
keadilan, Satjipto Rahardjo,
390
mengajak untuk menggunakan kecerdasan
spiritual. Oleh karena menjalankan hukum di Indonesia kini terancam
kedangkalan berpikir. Hal itu disebabkan orang lebih banyak membaca
huruf undang-undang daripada berusaha menjangkau makna dan nilai yang
lebih dalam. Sudah semestinya hal-hal berikut ini menjadi pemandu aparatur
yang terlibat dalam penegakan hukum terutama hakim sebagai ujung
tombak pendistribusi keadilan kepada masyarakat. Pertama, berani mencari
jalan baru (rule breaking) dan tidak membiarkan diri terkekang cara
menjalankan hukum yang lama dan tradisional yang jelas-jelas lebih
banyak melukai rasa keadilan; Kedua, kita semua dalam kapasitas masing-
masing (sebagai hakim, jaksa, birokrat, advokat, pendidik, dan lain-lain)
390
Lihat, Satjipto Rahardjo, Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual; dalam
Kompas, Senin, 30 Desember 2002.
219
didorong untuk selalu bertanya kepada nurani tentang makna hukum lebih
dalam. Apa makna peraturan, prosedur, asas, doktrin, dan lainnya itu?
Ketiga, hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja,
tetapi dengan perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan (compassion)
kepada bangsa kita yang sedang menderita.
Perasaan kepedulian dan semangat keterlibatan dalam proses
penegakan hukum dan keadilan terutama harus dimiliki oleh seorang hakim,
karena jabatan hakim menurut John P. Dawson
391
adalah jabatan terhormat,
sehingga hakim merupakan anggota masyarakat setempat yang terkemuka
dan terhormat. Melekat pada predikatnya sebagai insan yang terhormat,
suatu keniscayaan bagi seorang hakim untuk memayungi dirinya dengan
etika spiritual dan moral
392
dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil
Tuhan di dunia dalam memberikan keadilan. Etika spiritual dan moral ini
tercitrakan pada jiwa, semangat, dan nilai mission sacre kemanusiaan.
391
John P. Dawson, Peranan Hakim di Amerika Serikat; dalam Harold J. Berman,
Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat. Terjemahan Gregory
Churchill. Jakarta: PT Tatanusa, 1996, h. 22.
392
Perspektif etika spiritual dan moral dalam interaksi sosial kemanusiaan menjadi
penting, ketika diniscayakan adanya upaya lain untuk merespon realitas dan dinamika
kehidupan sosial kemanusiaan yang terus menerus mengalami erosi dan krisis yang
berkepanjangan. ...Perspektif ini juga menjadi penting ketika dihadapkan kepada krisis
sosial kemanusiaan yang makin serius dan mengemuka dalam berbagai krisis yang
kompleks dan multidimensional. Segi-seginya menyentuh setiap aspek kehidupan, baik
sosial, politik, ekonomi, teknologi, kesehatan, maupun lingkungan hidup. Krisis-krisis
tersebut merupakan krisis dalam dimensi-dimensi intelektual, moral, dan spiritual,
yang terjadi di mana-mana secara global, dan belum pernah terjadi sebelumnya dalam
sejarah umat manusia. Lihat, Hj. Ummu Salamah Musaddad, Perspektif Etika
220
Suatu keterpanggilan dan pertanggungjawaban suci dari umat manusia
dalam mengaktualisasikan sense of vision dan sense of mission
kekhilafahan ilahiyah manusia, yang terindikasikan dalam kehidupan
masyarakat yang demokratis (democratization), mampu menegakkan
keadilan dan hukum (law enforcement), memiliki kebanggaan diri baik
secara individual maupun kolektif (human dignity), toleran, sehingga dapat
menerima dan memberi di dalam perbedaan budaya (multicultural), serta
mendasarkan diri pada kehidupan beragama.
393
Bertolak dari paparan di muka, maka sulit untuk dibantah ketika
hakim tidak lagi menggunakan etika spiritual dan moral sebagai sandaran
vertikal sekaligus horizontal dalam pelaksanaan tugasnya, buktinya adalah
krisis telah melanda lembaga pengadilan. Akibat dari krisis yang cukup
serius yang dialami lembaga pengadilan, konsekuensi ikutan yang tidak
kalah seriusnya adalah surutnya kepercayaan dan hilangnya kewibawaan
pengadilan di mata masyarakat. Bahkan hasil pengumpulan informasi dari
para informan penelitian diketahui bahwa para pengusaha, terutama
pengusaha asing telah sedemikian merasa khawatir dan menganggap
pengadilan di Indonesia sangat diragukan independensinya dalam
memeriksa dan memutus suatu kasus. Mereka beranggapan peran
Spiritual dan Moral dalam Interaksi Sosial Kemanusiaan di Era Globalisasi; dalam
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FISIP-Unpas, Bandung, 5 April 2003, h. 2-3.
393
Ibid., h. 4.
221
pengadilan di Indonesia tidak lagi sebagai tempat mencari keadilan,
melainkan sebagai tempat untuk mencari kemenangan dengan segala cara,
dan sebagai tempat jual beli putusan.
394
Keadaan semacam itu disikapi berbeda oleh para pengusaha
nasional. Hasil interview dengan para informan diketahui bahwa para
pengusaha nasional justru berpikir sebaliknya. Di mata pengusaha nasional
beracara di depan pengadilan negeri justru dapat mencari dan menciptakan
peluang-peluang untuk memenangkan perkara. Memanfaatkan kondisi
seperti itu mereka justru menggunakan kelemahan moralitas petugas,
termasuk para hakim yang mengangani sengketa mereka, untuk bermain
agar hakim yang memeriksa sengketa tersebut memenangkan sengketa yang
sedang diperiksa.
Berkaitan dengan sikap pengusaha asing sebagaimana telah
diutarakan di muka, para informan juga menjelaskan, sebenarnya sebelum
pengusaha asing itu menjalin hubungan bisnis dengan mitranya di
Indonesia, pada dasarnya mereka telah memiliki meski sedikit pengetahuan
tentang kondisi hukum dan pengadilan di Indonesia. Berbekal pengetahuan
mengenai hukum dan lembaga pengadilan di Indonesia yang sedikit itulah
394
Adi Sulistiyono, Mengembangkan Paradigma...Op. Cit., h. 116.
222
deal bisnis terjadi antar pengusaha asing dan pengusaha nasional. Ketika
kontrak bisnis disepakati, giliran menyepakati klausula penyelesaian
sengketa seringkali pengusaha asing yang justru memulai mendesakkan
keinginan kepada mitranya dari Indonesia agar tidak memilih pengadilan
negeri sebagai forum tempat penyelesaian sengketa bisnis mereka
seandainya terjadi di kemudian hari. Namun demikian, umumnya mereka
tidak mengemukakan alasan yang jelas perihal keinginannya tersebut,
sehingga diduga mereka sesungguhnya tidak mengetahui secara pasti apa
yang harus dijadikan alasan. Tampaknya hal itu terjadi semata-mata karena
pemahaman yang bersifat umum saja terhadap kondisi hukum dan peradilan
di Indonesia, kemudian para pengusaha asing itu kurang setuju dan selalu
merasa khawatir jika persoalan hukumnya yang timbul dari kontrak
bersangkutan akan diputus oleh hakim di Indonesia. Dalam kondisi yang
demikian, kemudian mereka lebih menyukai untuk memilih mekanisme
penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase di luar negeri daripada harus
beracara melalui pengadilan di Indonesia.
Lain lagi yang dikemukakan seorang lawyer pengusaha asing
sebagai informan. Menurutnya, setelah transaksi bisnis antar pihak-pihak
pengusaha nasional dan asing terjadi, dirinya sebagai lawyer mempunyai
kewajiban untuk menyampaikan segala sesuatu secara rinci dan benar,
termasuk hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa
223
melalui pengadilan di Indonesia. Terutama bagi pihak asing, yang
bersangkutan harus memahami betul seluk beluk berperkara di pengadilan.
Oleh karena proses di pengadilan rangkaiannya panjang serta berjenjang.
Selesai pada tingkat pengadilan negeri, masih dimungkinkan upaya hukum
banding, kasasi, dan/atau kalau mungkin peninjauan kembali ke Mahkamah
Agung. Rangkaian proses tersebut memerlukan waktu yang sangat lama,
sehingga dapat dipastikan untuk memperoleh keadilan melalui lembaga
pengadilan juga memerlukan waktu yang sangat lama. Apalagi jika pihak-
pihak yang terlibat dalam sengketa terus menerus menggunakan haknya
untuk melakukan upaya hukum yang tersedia. Selain memerlukan waktu
yang lama, proses pemeriksaan perkara serta putusan pengadilan dilakukan
dalam sidang yang terbuka untuk umum, sehingga seluruh rangkaian
pemeriksaan perkara dapat dihadiri oleh masyarakat luas.
Setelah kondisi objektif berperkara pada lembaga peradilan
disampaikan untuk dipahami, biasanya pihak asing kemudian
menyampaikan alasan bahwa dia tidak mungkin membuang waktu berlama-
lama hanya untuk urusan penyelesaian pertikaian. Tujuan utama yang
bersangkutan adalah berbisnis serta mencari untung, sama sekali tidak untuk
bersengketa. Seandainya pun sengketa itu terpaksa terjadi di tengah
perjalanan bisnis dia, tentu saja tidak boleh menjadi penghambat aktivitas
224
bisnis, karena siapa pun yang berbisnis termasuk dirinya sama sekali tidak
menghendaki terjadinya kerugian.
Berdasarkan informasi di muka, dapat dimengerti apabila kalangan
dunia usaha selalu menuntut segala sesuatu urusan diselesaikan dengan
serba cepat,
395
dan mereka senantiasa berupaya mencari penyelesaian
sengketa yang tidak menyebabkan terganggunya aktivitas bisnis
bersangkutan. Sebagaimana diketahui forum ajudikasi di luar pengadilan
yang prosedur beracaranya lebih sederhana adalah arbitrase (arbitration).
396
Maka tidak heran apabila arbitrase kemudian menjadi salah satu pilihan
395
Pengadilan terdiri atas berbagai instansi atau tingkatan. Diperolehnya putusan pada
tingkat pertama, belum berarti sengketa tersebut selesai, karena pihak yang merasa
tidak puas dengan putusan tersebut masih dapat melakukan upaya hukum banding ke
pengadilan tinggi. Bahkan bila masih belum merasa puas dengan putusan banding,
yang bersangkutan masih dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.
Tak ada jaminan dari pihak mana pun bahwa penyelesaian sengketa pada setiap
tingkatan pengadilan itu akan berlangsung dengan cepat. Apabila semua tingkatan
peradilan itu dapat selesai ditempuh dalam jangka waktu satu tahun enam bulan (yang
berarti: satu instansi enam bulan), maka itu sudah dapat dikatakan sangat cepat.
Ditambah lagi dengan sejumlah tunggakan (kongesti) perkara-perkara yang
menyebabkan penyelesaian perkara di pengadilan semakin lamban.
396
Arbitration, is a method for settling controversies or disputes whereby an unofficial
third party hears and considers arguments and determines an equitable settlement.;
Lihat Peter J. Dorman (eds), Running Press Dictionary...Op. Cit., h. 19. Lihat pula,
Henry Campbell Black, Blacks Law Dictionary: Definitions of the Terms and
Phrases of American and English Jurisprudence Ancient and Modern. (Sixth
Edition). St. Paul Minn: West Publishing Co., 1990. Arbitrase yang di Indonesia diatur
dalam Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan
umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis dari pihak yang bersengketa.
Berdasarkan Penjelasan Umum dari UU No. 30 Th. 1999, Alternatif Penyelesaian
Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR) adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni
penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi,
konsiliasi, atau penilaian ahli. Oleh karena itu, Arbitrase menurut UU tersebut bukan
merupakan salah satu dari ADR, melainkan sebuah metode penyelesaian sengketa oleh
pihak ketiga di luar pengadilan umum.
225
para pelaku bisnis untuk menyelesaikan dan memutusi sengketa yang terjadi
di antara mereka.
Namun demikian, prosedur arbitrase yang sederhana bukan satu-
satunya alasan pihak-pihak dalam memilih arbitrase. Masih ada unsur lain
yang juga menjadi bahan pertimbangan mereka dalam melakukan pilihan.
Di antara pertimbangan tersebut dapat disebutkan umpamanya: Dalam
menangani sengketa-sengketa perdata pada umumnya, termasuk sengketa
komersial, selama ini banyak pihak merasakan betapa lembaga pengadilan
dianggap terlalu sarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam
memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Agaknya faktor tersebut tidak
lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang amat kaku dan
normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Sedangkan
seyogianya hakim mampu menjadi living interpretator yang mampu
menangkap semangat keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh
kekakuan normatif-prosedural yang ada dalam suatu peraturan perundang-
undangan, karena hakim bukan lagi sekedar la bouche de la loi (corong
undang-undang).
397
Faktor yang lebih bersifat internal kelembagaan pengadilan negeri
itu, secara teoretis juga tidak dapat dilepaskan dari apa yang dikonsepkan
397
A. Ahsin Thohari, Dari Law Enforcement ke Justice...Kompas, 3-7-2002...Op. Cit.,
Bdgk. Benny K. Harman, Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakimandi
Indonesia. Jakarta: ELSAM, 1997, h. 54.
226
oleh Nonet dan Selznick
398
mengenai tiga tipe hukum. Seperti diketahui,
dalam Tabel mengenai tipe hukum yang represif (represive law), hukum
ditempatkan di dalam matriks politik dan pemerintahan (law subsordinated
to power politics). Hukum represif memang bertujuan untuk
mempertahankan status-quo penguasa, yang kerapkali dikemukakan dengan
dalih untuk menjamin ketertiban. Aturan-aturan hukum represif keras dan
terperinci akan tetapi lunak dalam mengikat para pembuat peraturan sendiri.
Hukum tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk patuh bersifat mutlak,
dan ketidak-patuhan dianggap sebagai penyimpangan sedangkan kritik
terhadap penguasa dianggap sebagai suatu ketidak-setiaan.
399
Pada tipe hukum yang menindas atau represif tampak sekali
integrasi yang kuat antara hukum dan politik, dalam bentuk dibawahkannya
lembaga-lembaga hukum secara langsung kepada golongan elit
pemerintahan. Oleh karena itu, dalam konstelasi sedemikian, akan sangat
sulit diharapkan hakim berani untuk mengambil keputusan yang berbeda
dari ketentuan yang dicantumkan dalam produk hukum dan perundang-
undangan pada saat menghadapi kasus-kasus konkret di pengadilan. Hal itu
disebabkan hakim pada dasarnya adalah bagian dari aparatur pemerintahan.
398
Lihat, Philippe Nonet Philip Selznick, Law and Society...Op. Cit., h. 16.
399
Lihat, Ronny Hanitijo Soemitro, Beberapa Perspektif Mengenai Fungsi Hukum di
dalam Masyarakat; dalam Masalah-Masalah Hukum, Nomor 10 Tahun 1993, h. 42.
227
Fungsi serta peran yang dijalankan kekuasaan kehakiman diorientasikan
pada upaya untuk mendukung dan mensukseskan program-program yang
ditetapkan pemerintah atau eksekutif.
Realita lembaga pengadilan sebagaimana digambarkan di muka
semakin memperkuat alasan serta kecenderungan pihak-pihak yang
bersengketa untuk melakukan pilihan forum di luar pengadilan. Telah
semakin nyata pula kalau harapan untuk mendapatkan keadilan
400
sangat
sulit diperoleh melalui pengadilan. Oleh karena hakim juga tidak memiliki
cukup keberanian untuk mengambil keputusan yang berbeda dengan
ketentuan normatif undang-undang, sehingga keadilan substansial selalu
saja sulit diwujudkan melalui putusan hakim pengadilan, sebab hakim dan
lembaga pengadilan hanya akan memberikan keadilan formal. Sementara
itu, forum lain di luar pengadilan masih mungkin untuk diharapkan mampu
menegakkan keadilan substansial, ketimbang sekedar putusan formal yang
secara nyata tidak mampu memenuhi tuntutan rasa keadilan bagi kedua
belah pihak.
400
Pada umumnya keadilan merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang
menerima perlakauan saja. Para justiciabelen (pencari keadilan) pada umumnya pihak
yang dikalahkan dalam perkara perdata, menilai putusan hakim tidak adil. Demikian
pula buruh atau karyawan yang diputuskan hubungan kerjanya merasa diperlakukan
tidak adil oleh majikannya, juga dalam pencabutan hak atas tanah atau pemungutan
pajak warganegara, yang bersangkutan merasa diperlakukan tidak adil oleh
pemerintahnya. Jadi penilaian tentang keadilan itu pada umumnya hanya ditinjau dari
228
C. Kewenangan Eksekutorial Forum Arbitrase untuk Putusan Final
dan Mengikat serta Dilema Perolehan Keadilan
Kewenangan eksekutorial pada dasarnya merupakan suatu
kewenangan yang dimiliki oleh pengadilan negeri untuk melaksanakan atau
mengeksekusi suatu putusan hakim. Oleh karena itu, putusan hakim
mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa
yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara.
401
Dalam bidang hukum perdata eksekusi suatu putusan adalah tindakan
hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam
suatu perkara. Eksekusi merupakan tindakan lanjutan dari keseluruhan
proses pemeriksaan perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari rangkaian proses beracara pada suatu pengadilan. Hakikat dari eksekusi
putusan hakim adalah realisasi dari kewajiban pihak yang ber-
sangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan
tersebut. Atau dengan kata lain, eksekusi adalah pelaksanaan isi putusan
pengadilan yang dilakukan secara paksa dengan bantuan dari pengadilan,
apabila pihak yang kalah tidak mau melaksanakannya secara suka rela.
Tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan atau dieksekusi
dalam arti kata yang sebenarnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Pada
satu pihak saja, yaitu pihak yang menerima perlakuan. Lihat, Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1986, h. 58.
401
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata ... Op. Cit., h. 211.
229
asasnya hanya putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang pasti (kracht van gewijsde) yang dapat dieksekusi. Di samping telah
memperoleh kekuatan hukum yang pasti, putusan yang perlu dieksekusi
hanya putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, yaitu putusan hakim
yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi
prestasi. Adapun prestasi yang wajib dipenuhi dalam rangka pelaksanaan
putusan condemnatoir dapat terdiri atas memberi, berbuat, dan tidak
berbuat. Pada umumnya juga putusan condemnatoir itu berisi hukuman ter-
hadap pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang.
402
Sedangkan
putusan hakim jenis lainnya yaitu yang bersifat constitutif dan yang bersifat
declaratoir pada umumnya tidak dapat dilaksanakan dalam arti kata seperti
tersebut di muka, karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu.
Seiring dengan uraian mengenai kewenangan eksekutorial dari
pengadilan negeri di muka, kajian yang hendak dilakukan berikut ini adalah
seberapa mungkin forum arbitrase dapat memiliki kewenangan eksekutorial
terhadap putusan yang dibuatnya sendiri sebagai suatu putusan yang final
dan mengikat. Persoalannya, akibat dari forum arbitrase tidak memiliki
kewenangan eksekutoral, perolehan keadilan selalu menjadi dilema yang
dihadapi pihak-pihak yang bersengketa.
402
Sudikno Mertokusumo, Loc. Cit., h. 189.
230
Berkaitan dengan pembahasan tentang kewenangan eksekutorial
forum arbitrase, hasil pengumpulan informasi dari para informan walau
dengan latar belakang mereka berlainan, namun ternyata sudut pandang para
informan mengenai hal itu diketahui senada. Menurut mereka, pada
dasarnya lembaga arbitrase tidak mungkin memiliki kewenangan untuk
mengeksekusi sendiri putusannya, karena forum arbitrase adalah lembaga
peradilan swasta, sehingga sejak awal arbitrase tidak pernah dilengkapi
dengan petugas yang bernama jurusita seperti halnya pengadilan negeri. Di
samping itu, secara normatif ketentuan perundang-undangan juga secara
eksplisit telah menetapkan bahwa: Semua peradilan di wilayah Republik
Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-
undang.
403
Jadi meskipun arbitrase pada dewasa ini telah diatur dalam
sebuah undang-undang tersendiri, akan tetapi undang-undang tersebut sama
sekali tidak menetapkan lembaga arbitrase sebagai bentuk peradilan
negara.
404
Arbitrase hanyalah sebuah cara yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Bahkan
sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase itu pun telah secara
limitatif disebutkan yaitu hanya sengketa perdata. Oleh karena itu, tidak
403
Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970.
404
Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum
yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak
yang bersengketa (lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999).
231
semua sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, melainkan hanya
sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para
pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka.
Fakta di muka meneguhkan pemahaman bahwa lembaga peradilan
yang ditetapkan sebagai badan peradilan negara juga telah secara eksplisit
ditegaskan dalam undang-undang.
405
Atas dasar hal tersebut, maka sudah
jelas kiranya bahwa arbitrase hanya merupakan peradilan swasta yang akan
menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara
hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak untuk
sampai pada putusan yang final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
mengikat para pihak. Ketidaksejajaran arbitrase dengan pengadilan negeri
lebih ditegaskan lagi oleh norma berikut ini yang substansinya antara lain
mempersyaratkan dengan akibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan,
bahwa setiap putusan arbitrase nasional untuk dapat dieksekusi: Dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan
diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan
dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan
Negeri.
406
405
Periksa Pasal 10 UU Nomor 14 Tahun 1970.
406
Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999.
232
Mencermati norma tersebut memberikan kesan demikian kuatnya
kepentingan lembaga peradilan negara untuk melakukan pengawasan
terhadap putusan arbitrase, bahkan terhadap putusan arbitrase nasional yang
hendak dieksekusi. Apalagi ketentuan tentang penyerahan dan pendaftaran
lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada Panitera
Pengadilan Negeri itu diikuti dengan ancaman sanksi, apabila tidak
dipenuhi, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Hal itu
menunjukkan betapa forum arbitrase sangat tidak mungkin memiliki
kewenangan eksekutorial sekalipun terhadap putusan arbitrase yang
bersifat final dan mempunyai kekuatan tetap dan mengikat para pihak.
407
Terhadap masalah ini, para hakim yang dipilih sebagai informan
umumnya berpendapat bahwa masalah penyerahan dan pendaftaran putusan
arbitrase sebelum dilaksanakan itu semata-mata merupakan bentuk
pengintegrasian antara putusan lembaga peradilan swasta terhadap alur
kompetensi badan peradilan negara. Bukti tersebut dikuatkan dengan tidak
diperiksanya alasan atau pertimbangan putusan arbitrase oleh Ketua
Pengadilan Negeri agar putusan arbitrase tersebut benar-benar mandiri,
final, dan mengikat.
408
Pengintegrasian putusan arbitrase terhadap alur
kompetensi badan peradilan negara melalui prosedur yang telah ditetapkan
407
Periksa Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999.
408
Periksa Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999.
233
dimaksudkan agar output putusan meski berasal dari forum pemutus mana
pun, selama putusan tersebut dimintakan untuk dieksekusi di wilayah
hukum Indonesia, akan memiliki titel eksekutorial karena telah melewati
kewenangan publik yang satu yakni pengadilan negeri sebagai badan
peradilan negara. Namun demikian, terhadap ketentuan sanksi manakala
penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase itu tidak dilakukan, sehingga
berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan, para hakim sebagai
informan tidak memberikan tanggapan. Tanggapan justru diberikan oleh
kalangan advokat, melalui komentar dengan ekspresi sangat menyesalkan.
Mereka berpendapat, sesungguhnya aturan semacam itu dikhawatirkan akan
kembali menjadi hambatan terhadap upaya pihak-pihak yang bersengketa
untuk memperoleh keadilan. Oleh karena pada waktu yang lalu, kaidah
semacam itu telah terbukti menjadi kaidah yang sangat kontroversial.
409
409
Kontroversi terjadi tatkala Indonesia belum mensahkan Konvensi New York 1958.
Ketika itu pernah ada putusan arbitrase yang meminta untuk dilaksanakan di Indonesia.
Putusan tersebut dijatuhkan oleh arbiter di London tanggal 12 Juli 1978, kasus antara
Navigation Maritime Bulgare vs. PT Nizwar Jakarta. Pada tingkat pertama, Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat dengan Ketetapan Nomor 2288/1979 P tanggal 10 Juni 1981,
mengabulkan permohonan eksekusi tersebut. Dengan demikian, putusan arbitrase luar
negeri itu dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri di Jakarta. Ketetapan pengadilan
negeri itu merujuk pada Konvensi Jenewa tahun 1927, walaupun hal itu juga sempat
menimbulkan kontroversi. Ternyata sebelum Keppres Nomor 34 tahun 1981 berlaku,
sudah ada Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang membenarkan
pelaksanaan keputusan arbitrase asing. Akan tetapi Mahkamah Agung tidak
sependapat dengan pendirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Melalui Putusan MA
Nomor 2994K/Pdt/1983 tanggal 29 November 1984, Mahkamah Agung memberikan
pertimbangan antara lain sebagai berikut: Bahwa pada asasnya sesuai dengan
yurisprudensi di Indonesia putusan pengadilan asing dan putusan arbitrase asing tidak
dapat dilaksanakan di Indonesia kecuali kalau antara Republik Indonesia dan Negara
Asing yang bersangkutan diadakan perjanjian tentang pelaksanaan putusan pengadilan
234
Ketika itu persoalan eksekuatur menjadi salah satu alat bagi pengadilan
untuk menolak sejumlah putusan arbitrase asing (foreign arbitral awards)
yang dimohonkan untuk dieksekusi di Indonesia.
410
Akan tetapi, setelah
asing/putusan arbitrase asing. Oleh karena Putusan MA tersebut diucapkan setelah
berlakunya Keppres No. 34 Tahun 1981, maka salah satu pertimbangan MA
menyebutkan: "selanjutnya mengenai Keppres Nomor 34 tahun 1981 tanggal 5
Agustus 1981 dan lampirannya tentang pengesahan Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards sesuai dengan praktik hukum yang
masih berlaku harus ada peraturan pelaksanaannya tentang apakah permohonan
eksekusi putusan hakim Arbitrase dapat diajukan langsung pada pengadilan negeri,
kepada pengadilan negeri yang mana, ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui
Mahkamah Agung dengan maksud untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut
tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di Indonesia
bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, permohonan pelaksanaan putusan
Arbitrase seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima".
410
Di bawah ini dipaparkan beberapa putusan arbitrase asing yang pernah dimohonkan
eksekusi di Indonesia, namun ditolak oleh pengadilan sebagai lembaga pemberi
eksekuatur dengan berbagai alasan. Putusan tersebut di antaranya adalah:
i) Arbitration Awards dari Federation of Oils, Seed and Fats Associations
Limited London, kasus antara PT Bakrie & Brothers vs Trading
Corporation of Pakistan Limited, dimintakan fiat eksekusi melalui Pengadilan
Jakarta Selatan, akan tetapi dengan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor
64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 November 1984 dinyatakan tidak dapat
dilaksanakan. Penolakan PN Jak-Sel itu dikuatkan oleh Putusan PT DKI Jakarta
No.512/PDT/1985/PT DKI, tanggal 23 Desember 1985. Kemudian Mahkamah
Agung juga menguatkan putusan kedua pengadilan rendahan itu melalui Putusan
MA No. 4231 K/Pdt/1986, tanggal 4 Mei 1988.
ii) London Arbitration Awards No. 1950, tanggal 12 Juli 1978, kasus antara PT
Nizwar Jakarta vs Navigation Maritime Bulgare, varna, Blvd.
Chervenoermeiski, dimintakan fiat eksekusi melalui PN Jakarta Pusat dan
dengan penetapan No. 2288/1979 P., tanggal 10 Juni 1981 PN Jakarta Pusat
telah mengabulkan permohonan pemohon. Artinya, putusan arbitrase London itu
dapat dieksekusi. Namun demikian PT Nizwar Jakarta selaku termohon eksekusi
mengajukan Kasasi ke MA. Melalui putusannya No.2944 K/Pdt/1983
Mahkamah Agung menyatakan bahwa putusan hakim arbitrase asing seharusnya
dinyatakan tidak dapat diterima.
iii) Awards of The Queens Counsel of The English Bar of London, tanggal 17
November 1989, kasus antara Y. Haryanto vs E.D. & F. Man (Sugar)
Limited. Melalui Penetapan MA No.1 Pen.Exr/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1
Maret 1991, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan exequatur dari
E.D. & F. Man (Sugar) Ltd., selaku pemohon. Akan tetapi kemudian Y.
Haryanto selaku termohon melakukan gugat balik kepada pihak E.D. & F. Man
(Sugar) Ltd., maka dalam putusan Kasasi, MA kemudian meralat penetapannya
sendiri dengan menyatakan melalui Putusan Kasasi No.1203 K/Pdt/1990,
235
Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 berlaku, masalah
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, masih dibebani
syarat-syarat seperti pada waktu yang lalu. Walhasil keadaan serta perlakuan
terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar Indonesia sama sekali
tidak mengalami perubahan yang berarti dibandingkan dengan sebelum
Undang-undang Arbitrase diundangkan. Artinya, untuk dapat diakui dan
dilaksanakan di wilayah hukum Indonesia, putusan arbitrase internasional
masih harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal
66 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Di antara syarat-syarat tersebut
adalah: Putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di
Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban
umum. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan setelah
memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
411
Pada dasarnya, baik putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase
internasional telah diakui sebagai putusan yang bersifat final
412
dan
mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (Pasal 66 UU
Nomor 30/1999). Akan tetapi sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh
tanggal 4 Desember 1991, bahwa penetapan Mahkamah Agung RI tanggal 1
Maret 1991 Nomor 1 Pen.Exr/Arb.Int/Pdt/1991 menjadi irrelevant untuk
dilaksanakan.
411
Periksa Pasal 66 huruf c dan huruf d UU Nomor 30 Tahun 1999.
412
Penjelasan Pasal 60 UU Nomor 30 Tahun 1999 tegas menyebutkan Putusan arbitrase
merupakan putusan final dan dengan demikian tidak dapat diajukan banding,
kasasi atau peninjauan kembali.
236
putusan arbitrase internasional untuk dapat diakui serta dilaksanakan di
wilayah hukum Republik Indonesia, mencitrakan putusan arbitrase
tersubordinasi pada kewenangan pengadilan negeri. Kondisi semacam itulah
yang sangat dirasakan tidak adil oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam
putusan tersebut. Tidak dimilikinya kewenangan eksekutorial oleh forum
arbitrase di Indonesia untuk dapat mengeksekusi putusannya sendiri sangat
menjadi dilema dalam memperoleh keadilan. Oleh karena bagi para pencari
keadilan selalu saja dihadapkan pada situasi yang sulit yang mengharuskan
orang menentukan pilihan antara dua kemungkinan yang sama-sama tidak
menyenangkan atau tidak menguntungkan. Memilih berperkara pada
pengadilan negeri kondisinya sangat sulit diharapkan untuk mendapatkan
keadilan secara maksimal. Sementara memilih berperkara pada forum
arbitrase juga putusannya masih disubordinasikan terhadap kewenangan
pengadilan negeri, terutama apabila para pihak tidak melaksanakan putusan
arbitrase tersebut secara sukarela.
Persyaratan serupa ditetapkan pula untuk putusan arbitrase nasional
yang dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri. Sebelum
memberikan perintah pelaksanaan, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa
terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi ketentuan Pasal 4 dan
Pasal 5, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
Dalam melakukan pemeriksaan atas putusan arbitrase yang dimohonkan oleh
237
salah satu pihak yang bersengketa tersebut Ketua Pengadilan Negeri tidak
memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase. Adapun yang
menjadi alasan tidak diperiksanya pertimbangan putusan arbitrase dimaksud
adalah agar putusan arbitrase benar-benar mandiri, final, dan mengikat.
413
Sedangkan untuk putusan arbitrase internasional permohonan pelaksanaan
putusan dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan
kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam hal putusan
arbitrase internasional itu menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai
salah satu pihak, maka putusan tersebut hanya dapat dilaksanakan setelah
memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung yang selanjutnya
dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rangkaian
keterlibatan kompetensi pengadilan negeri dalam proses pengakuan dan
pelaksanaan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional maupun
internasional, sesungguhnya menunjukkan betapa badan peradilan negara
masih menunjukkan kekuasaan yang cukup dominan dalam melakukan
seleksi terhadap tuntutan pelaksanaan hak yang diperoleh melalui putusan
arbitrase. Apabila putusan arbitrase terus menerus disubordinasikan terhadap
kompetensi pengadilan negeri, pertanyaan selanjutnya adalah, benarkah
putusan arbitrase itu memiliki status mandiri, final, dan mengikat.?
413
Periksa Penjelasan Pasal 62 ayat (4) UU No. 30 Tahun 1999.
238
Khusus mengenai pelaksanaan putusan arbitrase internasional, terkait
sangat erat dengan prinsip timbal balik atau resiprositas (reciprocity
principle).
414
Prinsip tersebut merupakan hal yang wajib dijunjung tinggi oleh
setiap negara dalam hukum perdata internasional. Berkaitan dengan prinsip
resiprositas atau timbal balik ini, Pemerintah Republik Indonesia
sesungguhnya telah menerima dan menggunakan ketika mengesahkan Kon-
vensi New York 1958. Konvensi yang selengkapnya bertajuk Convention
on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,
ditandatangani di New York tanggal 10 Juni 1958 dan mulai berlaku pada
tanggal 7 Juni 1959. Tatkala Pemerintah Indonesia mensahkan Konvensi
New York dengan instrumen ratifikasi berupa Keputusan Presiden Nomor 34
tahun 1981, Indonesia mengajukan dua pensyaratan (reservation) terhadap isi
414
Sebagai suatu doktrin, reciprocity juga merupakan dasar bagi yurisdiksi dalam rangka
pelaksanaan putusan hakim asing. Berdasarkan doktrin reciprocity, "... that
international law required an equality of treatment in respect of judgments rendered
by the enforcing forum and those rendered by the original forum and that the
reciprocal need for protection of interests abroad by the nationals of the various
countries could be enhanced...".Pada prinsipnya doktrin di atas dapat digambarkan
sebagai berikut: Bahwa negara "X" akan mengakui dan melaksanakan putusan hakim
yang dibuat atau berasal dari negara "Y", asal saja negara "Y" juga memperlakukan
hal yang sama terhadap putusan hakim yang dibuat atau berasal dari negara "X". Di
Inggris berlakunya doktrin timbal balik (reciprocity) sebagai dasar yurisdiksi dalam
pelaksanaan putusan hakim asing, masih dibatasi. Inggris memberlakukan doktrin itu
sebatas menyangkut kasus-kasus matrimonial. Sebagai contoh di dalam kasus Travers
v. Holley ternyata pengadilan banding di Inggris telah mengakui putusan hakim
tentang perceraian yang dijatuhkan di New South Wales, Australia. Kenyataan
tersebut agaknya meyakinkan Caffrey, serta mendukung hasil penelitiannya, sehingga
dia menyatakan bahwa "... as a jurisdictional basis to recognition or enforcement
of foreign judgment is not really a satisfactory solution to the problem and,... it
has in England been restricted to matrimonial causes...". Lihat, Bradford A.
Caffrey, Enforcement of Foreign Judgments. Sydney:CCH Australia Limited, 1985,
h. 50-53.
239
ketentuan Konvensi New York Article I (3). Dua pensyaratan dimaksud
adalah: (i) pensyaratan timbal balik (reciprocity reservation) dan (ii)
pensyaratan komersial (commercial-reservation).
Sebagai konsekuensi diajukannya pensyaratan yang pertama yaitu
reciprocity reservation, bahwa negara yang bersangkutan baru akan
menerapkan ketentuan Konvensi apabila keputusan arbitrase tersebut dibuat
di negara yang juga adalah anggota Konvensi New York. Apabila keputusan
tersebut ternyata dibuat di negara yang bukan anggota, maka negara tersebut
tidak akan menerapkan ketentuan Konvensi. Oleh karena itu, ketika Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 masih menetapkan berbagai ketentuan dan
persyaratan dalam rangka pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase
internasional, maka tidak mustahil Indonesia akan dianggap melakukan
International Wrong serta menyalahi asas Pacta Sunt Servanda karena
dianggap tidak mematuhi janjinya sendiri terhadap negara-negara lain sebagai
sesama penandatangan Konvensi New York 1958.
D. Perspektif Historis dan Futuristik Arbitrase sebagai Model
Penyelesaian Sengketa Berkeadilan
Arbitrase sebagai suatu cara penyelesaian sengketa memiliki
perkembangan historis yang cukup panjang. Berdasarkan catatan sejarah
hukum, arbitrase telah diterapkan dalam bidang perjanjian sejak zaman
240
purbakala. Para penulis mengkonstatir bahwa perjanjian Lagash-Umma
ribuan tahun sebelum Masehi
415
misalnya, telah mengandung suatu klausula
arbitrase. Ketika itu arbitrase telah dipakai dalam makna yang serupa dengan
penggunaan arbitrase dewasa ini, yaitu dipakai untuk menyelesaikan
pertikaian akibat terjadinya pelanggaran perjanjian.Tidak berlebihan kiranya
seandainya para penulis mensinyalir bahwa arbitrase dapat menjadi salah
satu lembaga yang paling dihormati dalam kehidupan umat manusia.
Louis B. Sohn,
416
membuat paparan perkembangan arbitrase dan
membagi dalam dua periode zaman, yakni arbitrase zaman Yunani kuno
serta abad pertengahan di satu pihak dan arbitrase modern di pihak lain.
Fakta sejarah juga mencatat jika arbitrase telah dipraktikkan pada zaman
Yunani kuno sebagai cara untuk mencari keadilan.
417
Akan tetapi tentu saja
arbitrase ketika itu masih dalam bentuk yang sangat sederhana. Pada periode
tersebut arbitrase telah digunakan untuk menghindari terjadinya perang di
antara negara-negara kota, berdasarkan kesepakatan pihak-pihak, sengketa
415
Arthur Nussbaum, (Penyadur: Sam Suhaedi), Sejarah Hukum Internasional. h. 3.
Bdgk. Komar Kantaatmadja yang menyatakan "...kalau tidak bisa dikatakan bahwa
arbitrase bermula dari sejarah terjadinya konflik antar manusia sendiri."; dalam
Beberapa Permasalahan Arbitrase Internasional; Makalah Seminar Arbitrase 16
November 1988.
416
Lihat L.B. Sohn, International Arbitration in Historical Perspective: Past and
Present; dalam International Arbitration: Past and Prospects, A Symposium to
Commemorate the Centenary of the Birth of Prof. J.H.W. Verzijl (1888-1987),
Utrecht, October 21, 1988, h. 8. Bdgk. E.K. Nantwi, The Enforcement of
Inernational Judicial Decision and Arbitral Awards in Public International Law,
Leiden: A.W. Sijthoff, 1966, h. 3.
417
Rene David, Arbitration in...Op. Cit., h. 102.
241
yang timbul diselesaikan melalui arbitrase. Praktik penyelesaian sengketa
melalui arbitrase berlangsung pula pada zaman kejayaan Romawi. Bahkan
cara-cara demikian kemudian berkembang dan menyebar ke negara-negara
lainnya di Eropa. Dalam bentuk yang masih sederhana, arbitrase pada
umumnya mempunyai ciri-ciri antara lain sebagai berikut: Pertama, pihak-
pihak hanya akan membawa sengketa untuk diselesaikan melalui arbitrase
setelah sengketa tersebut terjadi. Sedangkan sebelum sengketa terjadi para
pihak tidak melakukan kesepakatan apa pun untuk menyelesaikan sengketa
melalui arbitrase; Kedua, Arbitrator atau arbiter yang dipilih adalah orang-
orang yang benar-benar dipercaya oleh para pihak. Biasanya kriteria yang
dipakai untuk menetapkan pilihan didasarkan pada hubungan atau ikatan
tertentu, misalnya sebagai sahabat atau karena hubungan dekat lainnya;
Ketiga, arbitrase digunakan untuk menyelesaikan sengketa di antara
kerabat, tetangga, atau mereka yang hidupnya bersama-sama dan yang
berkepentingan agar hubungan mereka terjaga baik.
Perkembangan konsep arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa
dalam skala yang lebih luas serta dalam lingkup internasional dengan bentuk
yang modern sebagaimana dikenal dewasa ini, diakui sejak ditandatangani
242
Jay Treaty pada tahun 1794 antara Inggris dan Amerika Serikat.
418
Kesepakatan yang dicapai oleh kedua negara dalam perjanjian tersebut
adalah mengenai penyelesaian sengketa perbatasan antara kedua wilayah
negara melalui arbitrase. Sejak periode itu arbitrase telah diupayakan untuk
diorganisasikan secara teratur. Sedangkan pada kurun waktu sebelumnya
arbitrase memang masih dalam keadaan belum teratur. Selanjutnya
dorongan baru ke arah diterimanya secara bertahap sejumlah ketentuan
dalam praktik arbitrase modern antara lain dijumpai dalam Alabama Claims
Arbitration tahun 1872. Sengketa itu pun berlangsung antara Amerika
Serikat dan Inggris. Dalam kasus tersebut pihak Amerika Serikat menuduh
bahwa Pemerintah Inggris telah bersalah melakukan berbagai pelanggaran
kewajiban untuk bersikap netral terhadap Pemerintah Konfederasi Amerika
Serikat selama Perang Sipil di Amerika. Pada mulanya Inggris menolak
untuk menyelesaikan kasus tersebut menggunakan arbitrase, akan tetapi
melalui Perjanjian Washington tahun 1871, akhirnya Inggris setuju untuk
menyelesaikan sengketa itu pada Komisi Tinggi Arbitrase dengan lima
orang arbitrator.
419
Kemudian pada tahun 1899/1907 dengan The Hague
Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, Permanent
418
Starke, Intoduction ...Op. Cit., h. 465. E.K. Nantwi, The Enforcement of...Op. Cit., h.
3-4.; Christine D. Gray, Judicial Remedies in International Law. New York, Oxford
University Press, 1987, h. 5.
419
E.K. Nantwi, The Enforcement of...Op. cit., h. 5-6.
243
Court of Arbitration didirikan.
420
Pada perkembangan berikutnya, arbitrase
lantas menjadi salah satu cara penyelesaian pertikaian secara damai yang
diatur dalam pasal 33 Piagam PBB.
421
Mengamati perkembangan serta penggunaan arbitrase dari masa ke
masa di muka, ternyata eksistensi arbitrase sebagai salah satu bentuk
ajudikasi yang menggunakan metode pertentangan (adversarial) telah lama
digunakan pihak-pihak untuk beragam kepentingan penyelesaian sengketa.
Artinya arbitrase terbukti memiliki fleksibilitas serta telah diyakini oleh
pihak-pihak yang menggunakannya, baik dalam proses pemeriksaan
sengketa maupun dalam cara memutus sengketa yang ditangani. Oleh
karena itu, tidak heran apabila Setiawan
422
menyebutkan bahwa arbitrase
sangat populer di bidang perdagangan internasional. Dalam menghadapi
sengketa yang melibatkan unsur-unsur antar negara, para pedagang
umumnya cenderung menyerahkan penyelesaian sengketa kepada badan
arbitrase bisnis internasional. Menyerahkan penyelesaian sengketa dagang
internasional kepada arbitrase, para usahawan terhindar dari kesulitan-
420
Lihat article 20 The Hague Convention 1899, antara lain menyebutkan: "With the
object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences,
which it has not been possible to settle by diplomacy, the signatory Powers undertake
to organize a Permanent Court of Arbitration,..."; Lihat, E.K. Nantwi, Loc. Cit., h. 8.
421
Penyelesaian pertikaian secara damai di bawah Pasal 33 Piagam PBB itu pada
dasarnya baru dapat ditempuh apabila telah dilakukan pemberitahuan tertulis disertai
alasan-alasan kepada pihak lainnya dimana pihak lainnya mengajukan keberatan.
Lihat, Yudha Bhakti, Pengertian Jus Cogen dalam Konvensi Wina 1969 tentang
Hukum Perjanjian; Padjadjaran, Kuartal I No. 1, Januari-Maret 1981, h. 49.
422
Setiawan, Aneka Masalah Hukum...Op. Cit., h. 2.
244
kesulitan yang pada umumnya disebabkan oleh keawaman mereka terhadap
sistem hukum dan sistem peradilan suatu negara tertentu.
Seiring pula dengan hadirnya fenomena baru dalam hubungan bisnis
antar masyarakat bangsa-bangsa dalam bentuk semakin ramainya aktivitas
perdagangan internasional. Aktivitas masyarakat dunia dalam bidang
perdagangan internasional dewasa ini teridentifikasi dalam dua pola
hubungan. Pertama, pola hubungan perdagangan antara masyarakat negara
berkembang dengan masyarakat negara-negara industri; dan Kedua, pola
hubungan perdagangan diantara masyarakat negara-negara berkembang satu
sama lain.
423
Bahkan melengkapi perkembangan pola hubungan
perdagangan dan hubungan ekonomi antar negara tersebut di muka, pada
dewasa ini pula telah terjadi pengelompokan negara-negara pada setiap
kawasan regional. Negara-negara tergabung dalam blok-blok perdagangan,
kawasan perdagangan bebas atau pasar tunggal. Umpamanya saja: North
American Free Trade Agreement (NAFTA), Single European Community
(SEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan lain-lain. Perkembangan
tersebut juga menyebabkan semakin terbukanya ekonomi bangsa-bangsa
423
Khusus mengenai pola perdagangan antara Indonesia dengan negara-negara di
kawasan Asia-Pasifik, dibedakan ke dalam empat pola perdagangan, yakni: a)
perdagangan dengan negara-negara industri; b) perdagangan antara negara-negara
dalam kelompok ASEAN; c) perdagangan dengan negara-negara komunis; dan d)
perdagangan dengan negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia-Pasifik.
Lihat Sunarjati Hartono, "Legal Aspect of Indonesian Trade with other Countries in
the Asian-Pacific"; dalam Padjadjaran, Special English Edition, 1984, h. 17.
245
dalam hubungan yang saling tergantung (interdependensi), bahkan menjurus
kepada integrasi ekonomi dunia.
424
Realitas masyarakat dunia yang
cenderung menjadi satu dan terbuka, terutama dalam bidang perdagangan
serta aktivitas bisnis pada umumnya merupakan bagian dari fenomena
globalisasi
425
yang sedang dialami umat manusia sejak beberapa dekade
terakhir ini serta tidak mungkin dibendung.
Benturan kepentingan akibat interaksi manusia yang intensitasnya
semakin padat tak ayal lagi sulit dihindari. Keadaan semacam itu pun
berlangsung dalam lingkungan komunitas pelaku bisnis, sehingga berbagai
jenis sengketa dalam bidang komersial pun terjadi serta merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari aktivitas bisnis manusia di abad ini. Dalam
kondisi serta keberadaan sengketa antar manusia yang semakin bervariasi
seperti sekarang ini, pengadilan tidak lagi dapat diandalkan sebagai satu-
424
.Sambutan Menteri Muda Perdagangan RI pada Simposium Nasional tentang Aspek-
aspek Kerjasama Ekonomi antara negara-negara ASEAN dalam rangka AFTA.
Bandung, 1 Februari 1993.
425
Globalisasi adalah karakteristik hubungan antara penduduk bumi ini yang melampaui
batas-batas konvensioal, seperti bangsa dan negara. Dalam proses tersebut dunia telah
dimampatkan (compressed) serta terjadi intensifikasi kesadaran terhadap dunia sebagai
satu kesatuan utuh. Lihat Satjipto Rahardjo, Pembangunan Hukum di Indonesia
dalam Konteks Situasi Global; dalam Perspektif, Vol. 2 No. 2, Juli 1997, h. 1.
Dalam kaitan ini Djisman S. Simandjuntak mengatakan, ...dalam ekonomi dunia yang
semakin terintegrasi ini, ekonomi-ekonomi yang sukses dalam dasawarsa terakhir
adalah mereka yang berhasil mendorong dan mempertahankan ekspansi perdagangan
yang cepat. Sukses pembangunan akan tetap sangat tergantung pada keberhasilan
dalam persaingan di pasar global. Negara niaga kecil seperti Indonesia sangat
berkepentingan dalam peletakan dan penerapan asas-asas dan aturan-aturan
multilateral yang menjadi hakikat dari proses GATT. Lihat Djisman S. Simandjuntak
et al., GATT 1994 Peluang dan Tantangan Dokumen dan Analisis. (Kumpulan
Dokumen dan Analisis), Jakarta, 14 Juni 1994, h. 1.
246
satunya sarana penyelesaian sengketa. Sedangkan masyarakat awam masih
beranggapan bahwa pengadilan merupakan satu-satunya tempat untuk
menyelesaikan sengketa. Bahkan sebagian besar masyarakat masih sangat
percaya terhadap pengadilan sebagai satu-satunya tempat untuk mencari dan
mendapatkan keadilan. Oleh sebab itu, mungkin juga tidak terlalu banyak
anggota masyarakat yang memahami kalau di luar pengadilan masih
terdapat cara-cara lain yang dapat dipilih dan dijadikan sebagai sarana untuk
menyelesaikan sengketa. Akan tetapi sungguh sangat disesalkan,
pemahaman serta kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan tidak
sebanding dengan fakta yang disajikan oleh pengadilan kepada masyarakat.
Terdapat dugaan bahwa pengadilan pada dewasa ini telah menyimpang dari
tugas utamanya dalam memberikan keadilan kepada setiap pencarinya.
Pengadilan dianggap bukan lagi semata-mata sebagai tempat mencari
keadilan, tetapi juga tempat mencari kemenangan. Keadaan demikian telah
menyebabkan pengadilan memperoleh stigma dari masyarakat sebagai
lembaga yang mengalami krisis teramat parah. Sehubungan dengan hal itu
Adi Sulistiyono
426
menyebutkan beberapa penyebab terjadinya krisis dalam
sistem peradilan Indonesia. Penyebab tersebut di antaranya: (i) adanya
tekanan dari pihak luar terhadap pengadilan dalam memutus perkara; (ii)
rendahnya pengetahuan hakim dalam merespon perkembangan hukum; (iii)
426
Adi Sulistiyono, Mengembangkan...Op. Cit., h. 116.
247
vonis hakim yang tidak bisa dipredisksi dan tidak mencerminkan keadilan
masyarakat; (iv) jual beli vonis hakim; (v) korupsi dan kolusi di lingkungan
pengadilan; (vi) lamanya pihak-pihak yang bersengketa mendapatkan
putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Sampai sekarang krisis yang dialami lembaga pengadilan tersebut
belum bisa teratasi, bahkan banyak pakar yang kesulitan untuk memberikan
solusi karena parahnya krisis yang dialami. Tambahan pula disinyalir
sementara kalangan, krisis yang menimpa lembaga pengadilan disebabkan
rendahnya moralitas hakim sehingga kolusi dan korupsi berlangsung marak
di kalangan hakim. Akibatnya kualitas putusan hakim tidak lagi ditentukan
oleh fakta-fakta dan bukti-bukti materiil melainkan oleh besar kecilnya
jumlah uang yang dinegosiasikan tatkala putusan hendak dijatuhkan.
Keadaan tersebut tentu saja sangat membingungkan dan mencemaskan
pihak-pihak pencari keadilan.
Menyiasati kondisi lembaga pengadilan semacam itu dalam
konstelasi masyarakat global dewasa ini, sebenarnya banyak pilihan-pilihan
yang dapat ditempuh oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di luar
pengadilan. Arbitrase misalnya, merupakan forum yang layak dipilih untuk
menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, karena diyakini merupakan cara
yang cepat sekaligus kredibel yang menjamin kerahasiaan pihak-pihak yang
248
bersengketa. Sayangnya, jalur arbitrase kerap dinodai oleh pihak-pihak yang
beriktikad buruk, terutama oleh pihak yang dikalahkan. Mereka yang
dikalahkan kerap meminta pengadilan untuk campur tangan, terutama saat
eksekusi. Padahal, arbitrase idealnya harus dibebaskan dari anasir
pengadilan.
427
Masalahnya, seringkali pengadilan malah menganggap
arbitrase sebagai saingan yang mengambil lahan ketimbang sebagai mitra.
Akibat persepsi yang keliru dari pengadilan terhadap arbitrase semacam itu,
pengadilan tidak jarang sampai membatalkan putusan arbitrase. Memang
benar, secara normatif pengadilan memiliki kewenangan untuk
membatalkan putusan arbitrase.
428
Namun, alasan pembatalan yang
ditentukan undang-undang dibatasi secara limitatif serta prosedur tertentu
yang harus dipenuhi oleh pengadilan. Memberikan komentar terhadap
persoalan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan, Priyatna
Abdurrasyid
429
menyatakan salah satu penyebab mudahnya pengadilan
membatalkan putusan arbitrase karena ketidak-mengertian hakim terhadap
arbirase itu sendiri. Padahal sesungguhnya lembaga arbitrase memiliki
427
Wawancara Hukumonline_com.htm dengan Priyatna Abdurrasyid: 99,9 % Hakim
Tidak Mengerti Arbitrase. Jumat, 10 Januari 2003.
428
Periksa Pasal 70, 71, dan 72 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal semacam ini
pun terjadi juga di negara-negara Arab Timur Tengah. Seperti dapat disimak dari
paparan Samir Saleh, bahwa: A Considerable number of national laws relating to the
enforcement of foreign awards require a foreign award to be embodied in a judgment.
This does not encourage the enforcement of foreign awards. Lihat Samir Saleh, The
Recognition and Enforcement of foreign arbitral awards in the states of the Arab
Middle East; dalam Julian DM Lew (ed), Contemporary Problems...Op. Cit., h. 351.
429
Wawancara Hukumonline_com.htm,... Op. Cit.,
249
peran yang strategis untuk mengurangi tumpukan perkara
430
di pengadilan.
Seharusnya, para hakim berusaha untuk memberi nasehat kepada para
pencari keadilan agar mereka memilih cara-cara lain untuk menyelesaikan
sengketa di luar pengadilan, sehingga perkara tidak menumpuk di
pengadilan. Meskipun hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap
pasif, namun sesungguhnya hakim secara normatif dibebani oleh undang-
undang untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi
segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang
sederhana, cepat, dan beaya ringan.
431
Bahkan para pihak yang bersengketa
memiliki kebebasan untuk mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan
ke pengadilan, baik berupa perdamaian atau pencabutan gugatan. Di
samping itu, penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian
atau melalui arbitrase juga diperbolehkan.
432
430
Berdasarkan angka-angka berikut ini dapat disimak betapa penumpukan perkara yang
memerlukan penyelesaian sangat membebani kinerja hakim dan lembaga pengadilan.
Perbandingan jumlah perkara masuk dan diputus, sejak tahun 1995-1999 terdapat
71089 perkara perdata yang harus diselesaikan. Jumlah tersebut kurang lebih 4 (empat)
kali lebih banyak dari jumlah perkara pidana sebanyak 19258 perkara. Total tumpukan
perkara perdata dan pidana sejak tahun 1995 sampai dengan 1999 sebanyak 90347
perkara. Artinya, 71089 perkara perdata (78,7 %) dan 19258 perkara pidana (21,3 %).
Terhadap masalah tersebut, Ketua Muda MA, Paulus E. Lotulung mengibaratkan
jumlah perkara yang masuk setiap bulan bagaikan deret ukur, sedangkan
produktivitas pemutusan perkaranya bagaikan deret hitung. Lihat, J. Danny
Zacharias, Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dalam Pemberian
Keadilan, Mampukah MARI Keluar dari Masa Kegelapan dan Bencana
Berkelanjutan; dalam Seminar Court Management di MA-RI dan Diskusi Buku
Fungsi MA dalam Praktik Sehari-hari. Salatiga; FH-UKSW, 2001, h. 7.
431
Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999.
432
Periksa Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.
250
Memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimana pun
sama, hukumnya sama, dan tidak mengenal perbatasan negara. Status para
pihak sama, para pihak berhak memilih arbiter, dapat memilih hukum yang
akan digunakan, maupun prosedur beracaranya. Sebagai konsekuensi dari
pilihan-pilihan tersebut, apabila para pihak telah sepakat untuk memilih cara
penyelesaian melalui arbitrase, maka kesepakatan tersebut harus dipenuhi.
Oleh karena itu, meminta pembatalan putusan arbitrase kepada pengadilan
negeri mengandung arti salah satu pihak melanggar janji. Pihak yang
melanggar janji tentu saja diragukan itikad baiknya. Sedangkan prinsip
bersengketa di hadapan arbitrase sifatnya itikad baik (good faith), non-
konfrontatif, dan kooperatif, sehingga setelah perkara diputus maka
kerjasama atau bisnis yang telah ada di antara para pihak dapat dilanjutkan
kembali.
Menerima permohonan pembatalan
433
putusan arbitrase dari salah
satu pihak merupakan kewenangan pengadilan. Namun demikian Undang-
undang Arbitrase sama sekali tidak mengatur kewenangan pengadilan untuk
433
Putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri apabila mengandung
unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, dapat diajukan
permohonan pembatalan. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut: (a) surat atau
dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu
atau dinyatakan palsu; (b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau (c) putusan diambil dari hasil
tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
251
membongkar perkara yang telah diputus oleh arbitrase.
434
Oleh sebab itu,
kasus pembongkaran putusan arbitrase yang dimintakan pembatalan oleh
pihak yang kalah ke pengadilan lebih disebabkan hukum arbitrase kurang
dikenal, baik oleh hakim maupun oleh masyarakat. Bahkan di Mahkamah
Agung pun, hanya beberapa hakim agung saja yang menguasai arbitrase.
Berkenaan dengan hal tersebut, Priyatna Abdurrasyid menyebutkan 99,9 %
hakim tidak mengerti mengenai arbitrase, karena itu semestinya para hakim
di-upgrade agar mereka memahami arbitrase, sehingga tidak menganggap
arbitrase sebagai saingan atau mengambil lahan pengadilan. Berdasarkan
uraian tersebut serta merujuk pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999, idealnya, upaya untuk menggunakan arbitrase sebagai salah satu cara
menyelesaikan sengketa di luar pengadilan juga seharusnya dinasihatkan
oleh hakim kepada para pencari keadilan, sehingga perkara tidak menumpuk
di pengadilan. Akan tetapi sungguh sangat disesalkan, jangankan menasihati
pihak-pihak untuk memilih arbitrase, sedangkan terhadap sengketa gugatan
dari perjanjian yang mencantumkan klausula arbitrase saja hakim
pengadilan seringkali tidak memperhatikan adanya klausula arbitrase dalam
perjanjian. Akibatnya, ketika gugatan diajukan ke pengadilan, hakim
434
Di Indonesia persoalannya berbeda. Putusan arbitrase yang dimintakan pembatalan oleh
salah satu pihak kepada pengadilan, perkaranya kemudian dibongkar. Bahkan ada
anggota majelis arbitrase yang dipanggil dan diperiksa oleh pengadilan. Arbiter
tersebut setelah putusan keluar, dia tidak berfungsi lagi, tidak mempunyai wewenang
apa-apa lagi. Lihat, Hukumonline_com.htm;...Op. Cit.
252
pengadilan merasa berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Padahal
kalau suatu perkara diajukan kepada hakim yang secara absolut tidak
wenang memeriksa perkara tersebut, maka hakim harus menyatakan dirinya
tidak wenang secara ex officio untuk memeriksanya, dan tidak tergantung
pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang ketidakwenangan itu.
Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan tangkisan bahwa
hakim tidak wenang memeriksa perkara tersebut.
435
Dalam sistem peradilan di Indonesia, kedudukan arbitrase adalah
extra judicial atau peradilan semu (quasi judicial), sedangkan pengadilan
negeri (state court) berperan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman
(judicial power). Oleh karena itu, meskipun undang-undang memberi
wewenang kepada arbitrase untuk menyelesaikan sengketa, hal itu tidak
mengubah status extra judicial yang melekat pada arbitrase. Akibatnya
walaupun ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-undang Arbitrase secara
eksplisit mengakui penerapan jurisdiksi arbitrase, tetapi menerapkan akibat
hukum (legal effect) yang digariskan Pasal 3 secara absolut, tidak selamanya
benar. Menurut M.Yahya Harahap,
436
dalam memahami Pasal 3 Undang-
undang Arbitrase ada pendapat yang mengatakan: asal dalam perjanjian
435
Lihat Pasal 134 HIR, Pasal 160 Rbg, Pasal 132 Rv.
436
M. Yahya Harahap, Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian atas UU No.
30 Tahun 1999; Jurnal Hukum Bisnis Vol. 21, Oktober-November 2002, h. 17.
253
terdapat klausula arbitrase, dengan sendirinya lahir kewenangan absolut
arbitrase untuk menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari perjanjian,
tanpa mempedulikan jangkauan atau ruang lingkup sengketa yang disebut
dalam rumusan klausula arbitrase. Pendapat yang bercorak generalisasi dan
absolut itu adalah keliru atau tidak selamanya benar. Mengapa demikian?
Oleh karena, baik di dalam teori maupun praktik arbitrase dikenal beberapa
format isi klausula arbitrase.
437
Isi klausula arbitrase dapat dirumuskan
dalam dua bentuk, yaitu: pertama, bersifat umum,
438
atau kedua, secara
rinci.
439
Klausula arbitrase yang dirumuskan secara rinci juga dapat disusun
dalam dua bentuk yakni (i) terinci sekali secara menyeluruh dan/atau (ii)
437
Yang dimaksud dengan isi klausula arbitrase adalah hal-hal yang boleh dicantumkan
dalam perjanjian arbitrase atau sampai sejauhmana rumusan yang dapat dicantumkan
dan diperjanjikan. Lihat, M. Yahya Harahap, Arbitrase...Op. Cit., h. 69.
438
Rumusan klausula arbitrase yang bersifat umum biasanya diawali dengan kata-kata
segala sengketa atau setiap sengketa (All disputes or all differences atau any
dispute or any difference). Isi klausula arbitrase yang bersifat umum juga dapat
dirumuskan secara ringkas serta dapat dicantumkan baik dalam perjanjian arbitrase
jenis pactum de compromittendo maupun dalam akta kompromis. Lihat, M. Yahya
Harahap, Arbitrase...Loc. Cit., h. 70-71.
439
Jenis yang kedua ini, yakni kalusula arbitrase secara terinci, disebut juga bentuk
terbatas atau parsial. Tergolong sebagai klausula arbitrase yang terinci sekali atau
mendetail, apabila rumusan kalusula arbitrase itu mencantumkan semua aspek
perjanjian. Hampir semua aspek dideskripsi satu persatu dalam klausula arbitrase,
sengketa apa saja yang menjadi kewenangan arbitrase. Mulai dari masalah perselisihan
yang akan terjadi, tentang keabsahan perjanjian, arti perjanjian, hak-hak dan kewajiban
para pihak dalam apemenuhan perjanjian. Bentuk semacam ini disebut bercorak
enumeratif. Sedangkan klausula secara terinci bentuk yang kedua adalah terinci
mengenai pokok-pokoknya saja (terinci seperlunya) atau terbatas sekali, yaitu
apabila klausula tersebut hanya merumuskan rincian pokok-pokok saja, seperlunya
didasarkan pada ruang lingkup perjanjian pokok. Biasanya klausula hanya menyebut
sengketa mengenai perbedaan penafsiran pelaksanaan perjanjian atau hanya terbatas
mengenai sengketa pengakhiran perjanjian (temination of contract). M. Yahya
Harahap, Arbitrase... Op.Cit., h. 71. Bdgk. M.Yahya Harahap,Beberapa Catatan...;
Jurnal Hukum...Op. Cit., h. 17.
254
terinci mengenai pokok-pokoknya saja. Masing-masing rumusan klausula
arbitrase tersebut di muka memiliki konsekuensi hukum yang berbeda-beda
terhadap lahirnya jurisdiksi arbitrase. Oleh sebab itu, kaidah Pasal 3 dan
Pasal 11 Undang-undang Arbitrase tidak otomatis diterapkan secara
generalisasi dan absolut, karena tidak selalu atau belum tentu setiap
perjanjian arbitrase akan melahirkan jurisdiksi arbitrase. Semuanya sangat
tergantung pada apakah sengketa yang terjadi itu termasuk jenis sengketa
yang disebut dalam klausula atau tidak. Apabila sengketa yang terjadi
termasuk ruang lingkup yang disebut atau dirinci dalam klausula, maka
yang berwenang menyelesaikan adalah arbitrase. Sedangkan sebaliknya,
apabila sengketa yang terjadi itu berada di luar ruang lingkup klausula
arbitrase, maka yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa
tersebut adalah pengadilan negeri. Padahal pemahaman serta opini yang
terbentuk di masyarakat selama ini setiap klausula arbitrase otomatis
langsung mewujudkan jurisdiksi absolut arbitrase tanpa mempedulikan
bentuk klausula yang disepakati.
Pemahaman semacam itu tidak hanya terjadi pada masyarakat
kebanyakan, melainkan juga melanda praktik pengadilan. Ketika sengketa
yang terjadi dan berada di luar ruang lingkup kalusula arbitrase, diajukan ke
pengadilan negeri, ternyata pengadilan negeri mengabulkan eksepsi pihak
lawan dan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa
255
dimaksud, atas alasan para pihak menyepakati klausula arbitrase dalam
perjanjian. Kenyataan yang dilukiskan tersebut merupakan bukti bahwa
hakim pengadilan negeri pun dapat saja membuat kesimpulan yang kurang
akurat terhadap maksud dari ketentuan Pasal 3 dan Pasal 11. Hal itu
kemungkinan karena kedua pasal yang mengatur tentang eksistensi
jurisdiksi arbitrase dirumuskan terlalu umum tanpa diberikan penjelasan
yang cukup memadai. Oleh sebab itu, agar penerapan jurisdiksi yang lahir
karena klausula arbitrase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 dan Pasal
11 tidak menimbulkan permasalahan hukum, maka perlu diatur serta
dijelaskan batas-batas jurisdiksi arbitrase itu sesuai dengan rumusan
klausula. Tanpa pengaturan dan penjelasan mengenai batas-batas jurisdiksi
sebagaimana dikehendaki oleh kalusula, maka kekeliruan memberikan
interpretasi terhadap Pasal 3 dan Pasal 11 akan berlangsung terus.
Seperti telah dikemukakan, kedudukan arbitrase dalam sistem
peradilan di Indonesia tergolong extra judicial atau peradilan semu, namun
tata cara pemeriksaan sengketa pada arbitrase memiliki kemiripan dengan
tata cara di pengadilan. Sedangkan faktor yang membedakan adalah,
pengadilan mengedepankan metode pertentangan (adversarial), sehingga
para pihak yang bertikai bertarung satu sama lain dengan hasil akhir yang
kuat yang akan menang. Sedangkan arbitrase lebih mengutamakan itikad
baik, non-konfrontatif, serta lebih kooperatif. Pada arbitrase para pihak tidak
256
bertarung melainkan mengajukan argumentasi di hadapan pihak ketiga yang
akan bertindak sebagai pemutus sengketa. Oleh karena itu, untuk
mengantisipasi kurang sempurnanya pengadilan dalam menjalankan
tugasnya, seharusnya hukum tanpa harus mengorbankan nilai keadilan dan
kepastian hukum, mampu membuka diri untuk mengaktualisasikan
sistemnya dan meningkatkan peranannya untuk membuka lebar-lebar akses
keadilan bagi masyarakat bisnis tanpa harus terbelenggu pada aturan
normatif yang rigid.
440
Untuk itu, maka model penyelesaian sengketa di luar
pengadilan semacam arbitrase seharusnya diberi kompetensi yang lebih
luas. Artinya, arbitrase jangan hanya diakui sebagai forum pemutus
sengketa, melainkan lebih dari itu, arbitrase juga seharusnya berwenang
penuh untuk mengeksekusi putusan yang dibuatnya. Apabila arbitrase
hanya diberi kewenangan limitatif semata-mata sebagai pemutus sengketa
tanpa memiliki kompetensi melakukan eksekusi terhadap putusan yang tidak
dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan, maka dapat
dipastikan forum arbitrase bernasib sama dengan peradilan agama sebelum
lahir Undang-undang tentang Peradilan Agama.
441
Padahal sebagai salah
440
Adi Sulistiyono, Mengembangkan...Op. Cit., h. 71.
441
Sebelum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, status
Peradilan Agama tidak sejajar dengan Peradilan Umum, sehingga putusan pengadilan
agama sebelum dieksekusi terlebih dahulu harus dikukuhkan atau memperoleh
eksekuatur dari Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 telah menghapuskan hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan
Agama. Kemudian, untuk mematangkan kemandirian Peradilan Agama oleh Undang-
257
satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase telah
memperoleh otoritas sebagai forum pemutus sengketa meskipun sangat
limitatif, yakni hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak
yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
442
Sebenarnya pendelegasian wewenang untuk menyelesaikan sengketa
kepada forum lain di luar pengadilan negeri telah berlangsung dalam
berbagai bidang. Hal itu disebabkan lembaga pengadilan selama ini memang
bukan satu-satunya institusi yang mampu menampung serta menyelesaikan
semua sengketa yang terjadi di dalam masyarakat. Beberapa contoh lembaga
penyelesaian sengketa di luar pengadilan negeri antara lain: badan
penyelesaian sengketa perumahan,
443
badan penyelesaian sengketa pajak,
444
lembaga penyelesaian sengketa lingkungan hidup,
445
lembaga penyelesaian
segketa ketenagakerjaan,
446
lembaga untuk menyelesaikan sengketa
kepailitan,
447
lembaga penyelesaian sengketa pertanahan,
448
badan
undang itu diadakan Juru Sita, sehingga Pengadilan Agama dapat melaksanakan
keputusannya sendiri. Periksa Penjelasan Umum point ke 6 UU No. 7/1989.
442
Periksa Pasal 5 ayat (1) UU No. 30/1999.
443
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981, untuk menyelesaikan sengketa
tentang harga sewa perumahan menjadi kewenangan Kantor urusan Perumahan.
444
Lihat Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
445
Periksa Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Periksa juga,
PP. No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian
Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
446
Periksa Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.
447
Lihat, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan.
448
Periksa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1
Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.
258
penyelesaian sengketa konsumen,
449
dan lembaga penyelesaian sengketa di
bidang perdagangan/bisnis/komersial.
450
Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa pada bidang-bidang tersebut
di atas meski keberadaannya tidak sepopuler pengadilan negeri, namun
secara resmi lembaga-lembaga itu memiliki otoritas serta diakui oleh hukum
dan negara sebagai bagian dari sistem hukum penyelesaian sengketa.
Sebagai contoh umpamanya, Penyelesaian Sengketa Pajak dilakukan oleh
Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14
Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
451
Bahkan Putusan Pengadilan Pajak
merupakan putusan dalam tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa
dan memutus sengketa pajak.
452
Walaupun hukum telah mendelegasikan wewenang untuk
menyelesaikan sengketa kepada lembaga-lembaga selain pengadilan negeri
seperti halnya pada penyelesaian sengketa pajak, akan tetapi dalam
praktiknya akses masyarakat untuk memanfaatkan lembaga-lembaga
semacam itu masih belum optimal. Ada banyak faktor yang kemungkinan
menjadi penyebab. Satu di antara faktor penyebab tersebut kemungkinan
karena sosialisasi berkenaan dengan keberadaan serta fungsi lembaga-
449
Lihat, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
450
Periksa, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
451
Lihat Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
452
Lihat Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2002.
259
lembaga dimaksud tidak cukup memadai. Akibatnya masyarakat tidak
cukup mengetahui keberadaan lembaga-lembaga tempat penyelesaian
sengketa selain pengadilan negeri.
Seperti halnya lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar
pengadilan yang lainnya, arbitrase juga disinyalir kurang dikenal, baik oleh
hakim maupun oleh masyarakat. Bahkan, Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) sendiri yang berdiri sejak tahun 1977 kurang dikenal
sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.
453
Padahal bersengketa melalui arbitrase sesungguhnya bisa cepat dan murah
bila dibandingkan dengan berperkara di pengadilan. Hal itu disebabkan
jangka waktu kerja majelis arbitrase dibatasi oleh undang-undang. Secara
normatif waktu penyelesaian sengketa juga secara eksplisit dibatasi, yaitu:
...harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh)
hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk.
454
Sedangkan
bersengketa pada badan peradilan biasa dapat memakan waktu sampai
puluhan tahun, bahkan sampai 20 tahun lebih. Para pengusaha tidak dapat
berdiam diri dengan menunggu putusan pengadilan, karena usahanya harus
berjalan terus. Apalagi dalam perdagangan internasional, pihak-pihak selalu
453
Salah satu penyebab BANI tidak dikenal karena terdapat kode etik yang melarang
BANI memasang iklan untuk menawarkan jasa. Lihat, Wawancara
hukumonline_com.htm dengan Priyatna Abdurrasyid, 10 Januari 2003;....Op. Cit.,
454
Lihat, Pasal 48 ayat (1) UU No. 30/1999.
260
menghendaki penyelesaian yang cepat. Mereka tidak dapat berbuat lain
kecuali mencari penyelesaian sengketa dengan tidak melalui pengadilan
biasa. Mengapa arbitrase? Oleh karena arbitrase tidak terikat berbagai
formalitas, walaupun tetap dalam batas-batas kewajaran hukum, kejujuran,
kebenaran, keadilan (putusan ex aequo et bono) seraya mampu memberikan
putusan yang adil dan dapat diterima oleh para pihak.
455
Untuk kalangan
bisnis, fasilitas yang disediakan oleh hukum dan negara untuk
menyelesaikan sengketa di antara para pelaku bisnis merupakan faktor yang
sangat penting dalam rangka menjamin diperolehnya kepastian hukum.
Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi orang yang mencari
keadilan dari tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang yang
mencari keadilan akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkannya.
Namun demikian, dalam pemahaman para pelaku bisnis, hukum
senantiasa tercitrakan sebagai penghambat untuk terselenggaranya setiap
kegiatan ekonomi. Hal itu disebabkan hukum seringkali dinilai kaku dan
berbelit-belit, sehingga tidak mampu memenuhi tuntutan kegiatan ekonomi
yang serba cepat. Oleh karena itu, untuk mendukung aktivitas para pelaku
ekonomi, hukum harus menjadi sarana yang mengarahkan berbagai kegiatan
ekonomi dan memasang rambu-rambu, jangan sampai pembangunan
455
Priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia...; dalam Juranl Hukum Bisnis Vol.
21, Oktober-November 2002;...Op. Cit., h. 9.
261
ekonomi menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan keadilan.
456
Oleh
karena menurut Smith,
457
keadilan justru mengontrol manusia untuk tidak
saling merugikan dan sebaliknya saling membantu. Keadilan adalah
prasyarat niscaya bagi berfungsinya relasi bisnis yang baik dan etis dalam
sistem ekonomi pasar bebas dan kondisi tersebut menjadi kondisi yang
memungkinkan berkembangnya bisnis yang baik. Oleh sebab itu, menurut
T.D.Campbell dalam bukunya Adam Smiths Science of Morals, antara lain
menyebutkan, teori Smith tidak hanya menyatakan bahwa keadilan adalah
syarat niscaya bagi kelangsungan suatu masyarakat khusus tertentu,
melainkan bagi kelestarian masyarakat mana pun.
458
Masyarakat mana pun
sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum
faktor keadilan harus diperhatikan di samping faktor lainnya yakni kepastian
hukum dan kemanfaatan. Artinya, penegakan hukum memang harus adil,
meskipun hukum tidak identik dengan keadilan, sebab kalau dalam
penegakan hukum hanya memperhatikan salah satu unsur saja, misalnya
kepastian hukum, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula
jika yang diperhatikan hanya kemanfaatan, maka kepastian hukum dan
456
Lihat, Ismail Saleh, Sambutan Menteri Kehakiman RI pada Acara Temu Karya Hukum
Perusahaan dan Arbitrase; Jakarta: 22 Januari 1991, h. 6.
457
A. Sonny Keraf, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah. Yogyakarta:
Kanisius, 1996, h. 125.
458
Ibid., h. 125.
262
keadilan dikorbankan, dan demikian selanjutnya.
459
Oleh karena itu, ketiga
unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.
Sebagai salah satu sarana penegakan hukum dalam hal terjadi
sengketa bisnis, arbitrase mungkin saja telah dapat memenuhi harapan
keadilan (melalui putusan ex aequo et bono). Akan tetapi apakah juga
putusan arbitrase telah memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum bagi
pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa, itu masih merupakan persoalan.
Persoalan tersebut akan sangat jelas apabila menyimak tata cara pelaksanaan
putusan arbitrase sebagai berikut:
460
(i) arbiter dan kuasanya wajib
mendaftarkan asli atau salinan otentik putusan arbitrase di kantor
Pengadilan Negeri, dilengkapi asli atau salinan otentik pengangkatan
sebagai arbiter; (ii) pelaksanaan putusan arbitrase berdasarkan perintah
(exequatur) Ketua Pengadilan Negeri; (iii) sebelum pemberian exequatur
Ketua Pengadilan Negeri memeriksa dahulu hal-hal berkaitan dengan: a)
ada atau tidaknya perjanjian arbitrase bagi pihak-pihak; dan b) apakah
perjanjian arbitrase berada dalam lingkup hukum perdagangan dan
mengenai hak yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersangkutan.
Tidak dipenuhinya ketentuan mengenai penyerahan dan pendaftaran lembar
asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri
459
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum...Op. Cit., h. 131.
460
Periksa Pasal-Pasal 59, 61, 62 jo Pasal 4 dan Pasal 5 UU No. 30/1999.
263
berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan [Pasal 59 ayat (4)
Undang-undang Arbitrase].
Rangkaian normatif tentang tata cara pelaksanaan putusan yang
harus dipenuhi sebelum putusan arbitrase dilaksanakan menunjukkan bahwa
sesungguhnya arbitrase masih dianggap tidak mandiri serta tidak sejajar
kedudukannya dengan pengadilan negeri, sehingga dianggap tidak matang
untuk dapat mengeksekusi putusannya sendiri. Betapa tidak, apabila
penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase itu tidak dipenuhi, maka
akibatnya putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Kaidah tersebut pada
dasarnya telah mengurangi kedudukan arbitrase seperti halnya kedudukan
pengadilan agama sebelum lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
Oleh karena itu, untuk menjamin diperolehnya kepastian hukum bagi para
pihak yang bersengketa pada forum arbitrase, norma yang terkesan
mensubordinasikan arbitrase dari pengadilan negeri harus dihapuskan dari
undang-undang arbitrase. Perubahan atau amandemen terhadap Undang-
undang Nomor 30 Tahun 1999 merupakan sesuatu yang tidak dapat
dihindarkan. Hal itu disebabkan terdapat beberapa pasal di dalam undang-
undang tersebut yang dianggap memandulkan
461
peran dan fungsi
461
Paulus E. Lotulung (Ketua Muda Mahkamah Agung) antara lain menunjuk Pasal 70
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai pasal yang disebutnya sebagai
memandulkan forum arbitrase. Pasal tersebut antara lain tentang Pembatalan
Putusan Arbitrase. Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan
permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur
264
arbitrase. Norma semacam itu tidak bisa lain kecuali harus diubah dan
diganti. Oleh karena itu, kondisi ambivalensi normatif yang tercipta dari
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 harus segera diakhiri. Di samping
itu, Surat Ketua Mahkamah Agung yang ditujukan kepada seluruh Ketua
Pengadilan Negeri agar para KPN dapat menghormati putusan arbitrase
dalam rangka proses pelaksanaan putusan arbitrase dimaksud. Namun
demikian, kebijakan yang ditempuh Ketua MA tersebut sesungguhnya
apabila dikaji dari aspek independensi badan peradilan rendahan
sesungguhnya merupakan sesuatu yang dapat mengganggu kemandirian
para hakim. Akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung
sebagai otoritas lembaga yudikatif tersebut antara lain agar para ketua
pengadilan negeri dapat menghormati serta membantu dalam proses
pelaksanaan putusan arbitrase.
Selanjutnya, upaya lain yang tidak kalah pentingnya untuk dilakukan
adalah sosialisasi tentang eksistensi badan arbitrase sebagai salah satu forum
tempat penyelesaian sengketa. Sosialisasi merupakan keniscayaan yang
tidak dapat ditunda-tunda. Hal itu disebabkan, selama ini harus diakui
bahwa keberadaan forum arbitrase tidak banyak diketahui publik, sehingga
sebagai berikut:. Untuk itu upaya pembatalan yang dilakukan oleh para pihak
dalam arbitrase selama ini di dalam praktik telah banyak ditolak oleh Mahkamah
Agung. Hal itu dilakukan dalam rangka memberikan tempat dan mengharagai
eksistensi forum arbitrase sebagai badan yang telah memutus sengketa para pihak
tersebut.
265
upaya penyebarluasan informasi mengenai arbitrase dalam rangka
memperkenalkan peran dan fungsi forum tersebut perlu dilakukan lebih
gencar serta lebih intensif lagi.
Memberikan kompetensi terhadap badan arbitrase dalam
melaksanakan putusannya sendiri, sehingga arbitrase menjadi forum yang
mandiri, sejajar dengan badan peradilan, matang, dan berkompeten adalah
conditio sine qua non apabila hendak menjadikan badan arbitrase di
Indonesia sebagai badan penyelesaian sengketa bisnis yang berprospek
internasional. Oleh karena pada abad mendatang interaksi bisnis antar
bangsa telah dirancang untuk tidak lagi tersekat oleh berbagai rintangan
(barrier), baik berupa batas-batas teritorial, norma-norma perdagangan,
maupun rintangan berupa tarif. Sebagai konsekuensi dari keadaan semacam
itu maka terjadinya konflik antar pelaku bisnis pun akan semakin sulit
dihindarkan. Dalam konstelasi dunia bisnis seperti itu maka sangat
mendesak untuk memberi status mandiri dan kompeten terhadap badan
arbitrase agar dapat melaksanakan putusannya tanpa bantuan pengadilan
negeri. Dalam rangka itu semua, yang harus diupayakan adalah melakukan
amandemen perubahan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terutama berkenaan
dengan pelaksanaan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional
maupun arbitrase internasional. Pemberian status mandiri terhadap arbitrase
266
akan membawa konsekuensi hukum yang amat luas. Arbitrase yang telah
memiliki karakter berbeda dengan pengadilan negeri serta prosedur
penyelesaian sengketa yang tidak terikat dengan berbagai formalitas, akan
menjadi lembaga penyelesaian sengketa komersial yang lebih diminati oleh
para pencari keadilan dari kalangan bisnis karena akan lebih mampu
memenuhi tuntutan mereka. Lebih-lebih lagi kalangan bisnis atau usaha
komersial internasional, karena sampai saat ini tidak ada badan pengadilan
yang dapat memeriksa sengketa komersial internasional yang dapat
diandalkan dan efektif.
462
Apabila demikian, tidak diragukan kalau
lembaga arbitrase di masa-masa yang akan datang akan menjadi model
penyelesaian sengketa komersial yang lebih berkeadilan, sekaligus
menjamin kepastian hukum, serta betul-betul bermanfaat bagi penggunanya
karena prosesnya yang cepat dan beayanya yang murah. Hal itu berarti pula
arbitrase sebagai salah satu lembaga pelaksana hukum akan mampu
merealisasikan ketiga unsur dalam penegakan hukum yang harus
diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara
proporsional seimbang.
462
Lihat Priyatna Abdurrasyid, Pengusaha Indonesia... dalam Jurnal Hukum Bisnis
Vol. 21...Op. Cit., h. 9.
267
BAB V
EKSEKUSI PUTUSAN FORUM ARBITRASE
GAMBARAN DILEMA PENEGAKAN KEADILAN
DI INDONESIA
A. Makna dan Kekuatan Putusan Menurut Pengadilan Negeri Serta
Para Pihak Bersengketa
Eksekusi sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan
kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara merupakan aturan dan tata
cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara. Setiap perkara perdata yang
diajukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pengadilan tujuannya untuk
mendapatkan penyelesaian. Oleh karena itu, setiap pemeriksaan perkara
akan diakhiri dengan suatu putusan. Namun demikian putusan dijatuhkan
belum berarti persoalan telah selesai. Putusan atas pemeriksaan perkara
perdata selanjutnya harus dapat dilaksanakan (dieksekusi). Hal itu penting,
oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak
dapat dilaksanakan.
Hakikat dari eksekusi putusan adalah realisasi kewajiban pihak yang
bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan
tersebut. Eksekusi dengan kata lain berarti pula pelaksanaan isi putusan
hakim yang dilakukan secara paksa dengan bantuan pengadilan, apabila
pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.
268
Akan tetapi tidak semua putusan hakim dapat dilaksanakan dalam arti kata
yang sesungguhnya, yaitu secara paksa oleh pengadilan. Pada asasnya hanya
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (kracht
van gewijsde) yang dapat dieksekusi. Selain telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, putusan yang dapat atau perlu dieksekusi hanya putusan-
putusan yang bersifat condemnatoir,
463
yaitu putusan hakim yang bersifat
menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi. Sedangkan
putusan hakim jenis lain, seperti putusan yang bersifat constitutif
464
dan
yang bersifat declaratoir
465
pada umumnya tidak dapat atau tidak perlu
dilaksanakan dalam arti seperti putusan yang bersifat condemnatoir, oleh
karena kedua putusan di muka tidak menetapkan hak atas suatu prestasi
tertentu. Adapun prestasi yang wajib dipenuhi dalam rangka eksekusi
putusan yang bersifat condemnatoir dapat terdiri atas memberi, berbuat,
dan tidak berbuat. Di samping itu juga pada umumnya putusan
condemnatoir berisi hukuman terhadap pihak yang dikalahkan untuk
membayar sejumlah uang.
463
Lihat, Ny. Retnowulan Sutantio, Hukum Acara...Op. Cit., h. 122.
464
Putusan constitutif adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan
hukum. Contoh putusan constitutif misalnya: pemutusan perkawinan, pengangkatan
wali, pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian. Lihat, Sudikno
Mertokusumo, Hukum Acara...Op. Cit., h. 189.
465
Putusan declaratoir adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan
apa yang sah, misalnya bahwa anak yang menjadi sengketa adalah anak yang
dilahirkan dari perkawinan yang sah. Juga tiap putusan yang menolak gugatan
merupakan putusan declaratoir. Ibid,. h. 189-190
269
Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada dasarnya
memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Putusan hakim adalah
pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang
untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.
466
Yang
disebut putusan bukan hanya yang diucapkan, melainkan juga pernyataan
yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim
di persidangan. Putusan yang diucapkan secara lisan di persidangan disebut
uitspraak, sedangkan yang dituangkan dalam bentuk tertulis disebut vonnis.
Pada prinsipnya baik putusan yang diucapkan (uitspraak) maupun yang
tertulis (vonnis) satu sama lain substansinya tidak boleh berbeda. Apabila
ternyata ada perbedaan antara yang diucapkan dengan yang tertulis, maka
yang dianggap sah adalah putusan yang diucapkan. Kedua jenis putusan
tersebut di dalam kepustakaan hukum Belanda dikenal dengan sebutan
vonnis dan gewijsde. Vonnis merupakan sebutan untuk putusan yang belum
mempunyai kekuatan hukum tetap atau dalam beberapa hal disebut juga
voorlopig gewijsde, terhadap putusan semacam ini masih tersedia upaya
hukum biasa. Sedangkan gewijsde adalah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap yang dalam beberapa kepustakaan disebut juga
466
Sudikno Mertokusumo, Loc. cit., h. 172.
270
uiterlijk gewijsde, untuk putusan semacam ini hanya tersedia upaya hukum
khusus atau upaya hukum istimewa.
467
Adapun putusan arbitrase atau arbitral awards:
Means a final award which disposes of all issues submitted to the arbitral
tribunal and any other decision of the arbitral tribunal which finally
determines any question of substance or the question of its competence or
any other question of procedure but, in the later case, only if the arbitral
tribunal terms its decision an award.
468
Baik putusan hakim maupun putusan arbitrase (arbitral awards)
kedua jenis putusan itu mengenal yang dinamakan putusan akhir
(eindvonnis) dan putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela
(tussenvonnis),
469
sering pula disebut putusan antara. Perbedaan prinsipal
antara putusan hakim dengan putusan arbitrase terletak pada sifat dan cara-
467
Yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan atau kekhilafan
yang terjadi dalam suatu putusan-putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang pasti. Jenis upaya hukum ini terdiri atas peninjauan kembali dan perlawanan
pihak ketiga (derden verzet).
468
Lihat Alan Redfern et al., Law and Practice...Op. Cit., h. 359.
469
Putusan sela (tussenvonnis) atau putusan antara adalah putusan yang diucapkan di
dalam persidangan, namun tidak dibuat secara terpisah melainkan ditulis di dalam
berita acara persidangan yang berfungsi untuk memperlancar pemeriksaan perkara.
Beberapa jenis putusan sela antara lain sebagai berikut: (i) Putusan praeparatoir yaitu
putusan yang diucapkan sebagai persiapan putusan akhir tanpa mempunyai pengaruh
atas pokok perkra atau putusan akhir. Contohnya, putusan untuk menggabungkan dua
perkara atau putusan untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi; (ii) Putusan
interlocutoir yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian, misalnya: perintah
untuk pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat. Namun berbeda dengan putusan
praeparatoir yang memiliki sifat tidak mempengaruhi putusan akhir, sedangkan
putusan interlocutoir dapat mempengaruhi putusan akhir; (iii) Putusan insidentil adalah
putusan yang berhubungan dengan insiden, yaitu suatu peristiwa yang menghentikan
prosedur beracara. Umpamanya, putusan yang membolehkan seseorang untuk ikut
serta di dalam perkara (baik vrijwaring, voeging, maupun tussenkomst). (iv) Putusan
provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan pihak
yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan untuk kepentingan
salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
271
cara putusan tersebut dibuat. Di samping itu, perbedaan di antara kedua
jenis putusan itu disebabkan terdapat perbedaan asas yang dianut oleh
masing-masing lembaga tempat kedua putusan tersebut dijatuhkan. Sifat
serta asas pemeriksaan sengketa pada arbitrase adalah close-door and
confidential, sehingga seluruh rangkaian serta proses pemeriksaan sengketa
oleh arbiter sampai dengan putusan diucapkan berlangsung dalam sidang
yang bersifat tertutup, karena itu pula putusan arbitrase tidak boleh
dipublikasikan (shall be closed to the public). Sedangkan asas yang dianut
dalam pemeriksaan perkara di pengadilan adalah terbuka untuk umum,
sehingga putusan hakim harus diucapkan dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum. Apabila putusan hakim diucapkan dalam sidang yang
tidak dinyatakan terbuka untuk umum, berarti putusan itu tidak sah dan
tidak mempunyai kekuatan hukum, bahkan dapat berakibat putusan itu batal
menurut hukum.
Selain sifat dan prosedur menjatuhkan putusan hakim dengan
putusan arbitrase itu berlainan, ternyata status serta eksistensi kedua putusan
itu pun de jure dan de facto dibedakan. Buktinya, di satu pihak secara
normatif (de jure) - undang-undang mengakui putusan arbitrase sebagai
putusan yang telah memiliki status dan kekuatan hukum setara dengan
putusan hakim. Hal tersebut seperti dapat disaksikan dari kaidah yang
272
mengatur tentang substansi dan sistematika putusan arbitrase,
470
yang
menetapkan hal-hal yang harus dimuat dalam putusan arbitrase sama dengan
putusan hakim.
471
Namun di lain pihak, kenyataan dalam praktik (de facto),
perbedaan perlakuan terhadap putusan arbitrase mulai tampak diketahui
ketika putusan arbitrase hendak dieksekusi. Sejumlah syarat normatif yang
imperatif masih harus diikuti dalam rangka eksekusi putusan arbitrase.
Apalagi dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan tersebut secara
sukarela. Padahal disadari atau pun tidak, akibat adanya ketentuan semacam
itu, undang-undang arbitrase dapat dianggap mengukuhkan ambivalensi
norma, karena terbukti menerapkan standar ganda terhadap putusan
arbitrase terutama menyangkut syarat-syarat dan prosedur pelaksanaan
putusan.
Perlakuan ambivalen terhadap putusan arbitrase seharusnya tidak
terjadi apabila secara cermat mengamati substansi Pasal 54 ayat (1) Undang-
470
Pasal 54 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 berisi ketentuan: Putusan arbitrase harus
memuat: (a) kepala putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan
yang Maha Esa; (b) nama lengkap dan alamat para pihak; (c) uraian singkat sengketa;
(d) pendirian para pihak; (e) nama lengkap dan alamat arbiter; (f) pertimbangan dan
kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa; (g) pendapat
tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase; (h)
amar putusan; (i) tempat dan tanggal putusan; dan (j) tanda tangan arbiter atau majelis
arbitrase.
471
Lihat ketentuan-ketentuan yang termuat di dalam Pasal-pasal berikut ini: 183, 184, 187
HIR (194, 195, 198 Rbg), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan juga Pasal 61 Rv. Suatu putusan hakim terdiri atas
4 (empat) bagian yaitu: (1) kepala putusan, (2) identitas para pihak, (3) pertimbangan,
dan (4) amar atau dictum. Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara... Op.Cit., h.
182-188.
273
undang Arbitrase. Dari norma tersebut sesungguhnya sudah jelas bahwa
tidak ada alasan untuk membedakan putusan arbitrase dengan putusan
hakim. Hal itu disebabkan: Pertama, semua unsur yang disyaratkan untuk
substansi dan sistematika putusan arbitrase ditetapkan sama dengan unsur-
unsur yang disyaratkan juga untuk putusan hakim. Kedua, putusan arbitrase
bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para
pihak. Artinya, putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau
peninjauan kembali.
472
Namun pada sisi yang lain, sejumlah norma hukum
dalam undang-undang arbitrase masih berisi kaidah yang mencitrakan
adanya ketergantungan putusan arbitrase terhadap kewenangan pengadilan
negeri. Kesan tersebut demikian kuat, lebih-lebih apabila menelusuri muatan
norma dalam Pasal-pasal 59 sampai dengan 64 untuk putusan arbitrase
nasional dan Pasal-pasal 65 sampai dengan 69 untuk putusan arbitrase
internasional. Bahkan Undang-undang arbitrase telah memberi kewenangan
kepada pengadilan negeri sebagai satu-satunya lembaga yang kompeten
untuk menerima permohonan dan memutus pembatalan putusan arbitrase
yang diajukan oleh para pihak. Kaidah semacam itu tidak dapat dinafikan
telah menjadi salah satu indikator yang nyata-nyata menempatkan putusan
arbitrase sebagai subordinasi dari kompetensi pengadilan negeri.
472
Lihat Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 dan Penjelasannya.
274
Berdasarkan fakta tersebut di muka, tidak dapat dipungkiri jika
ternyata kaidah hukum arbitrase telah menciptakan prakondisi yang kurang
menguntungkan untuk putusan arbitrase. Oleh karena norma hukum
arbitrase telah memungkinkan pengadilan negeri dengan pihak-pihak yang
bersengketa berbeda sudut pandang atau pemahaman mengenai status serta
eksistensi putusan arbitrase. Dari satu segi, para pihak yang bersengketa
akan memahami putusan arbitrase sebagai putusan yang bersifat final dan
mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat mereka. Aturan itu
bermakna, dilaksanakan atau tidak putusan arbitrase secara sukarela oleh
para pihak, mestinya merupakan urusan mereka yang bersengketa serta
forum arbitrase sebagai pemutus. Mestinya tidak harus melibatkan perintah
Ketua Pengadilan Negeri. Oleh karena perintah Ketua Pengadilan Negeri
sebagai syarat normatif dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan
arbitrase secara sukarela, bermakna putusan arbitrase belum final dan belum
mengikat para pihak.
Sedangkan pada sisi lain, ketentuan mengenai penyerahan dan
pendaftaran lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase kepada
Panitera Pengadilan Negeri sebelum putusan dilaksanakan, menjadi salah
satu alasan bagi pengadilan negeri untuk tetap merasa memiliki kewenangan
dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, pengadilan
tetap beranggapan bahwa putusan arbitrase belum memiliki titel
275
eksekutorial. Secara tidak langsung, ketentuan itu pun telah menempatkan
putusan arbitrase sebagai putusan yang tidak mandiri. Akibatnya putusan
arbitrase dikondisikan sebagai putusan yang berketergantungan terhadap
kewenangan pengadilan negeri. Oleh karena itu, ambivalensi normatif yang
terjadi dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana
dipaparkan di muka, tak ayal lagi membawa dampak pada pemaknaan yang
beragam terhadap kaidah hukum arbitrase.Tentu saja melakukan interpretasi
terhadap kaidah hukum bukan sesuatu yang dilarang. Namun apabila
disebabkan norma yang ambivalen berakibat terjadi ambiguitas terhadap
status putusan arbitrase, mestinya hal itu tidak dibiarkan berlangsung terus
menerus. Masalahnya, disadari atau pun tidak keadaan tersebut akan
membawa konsekuensi terhadap persoalan kepastian hukum serta derajat
kepercayaan para pencari keadilan yang hendak menggunakan arbitrase
sebagai forum penyelesaian sengketa.
Pada dataran teoritis, setiap putusan hakim termasuk di dalamnya
putusan arbitrase, pada prinsipnya mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan,
yaitu: (1) kekuatan mengikat, (2) kekuatan pembuktian, dan (3) kekuatan
eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan. Masing-masing kekuatan
putusan dimaksud dapat disimak dalam paparan berikut ini.
276
1. Kekuatan Mengikat
Setiap putusan, baik putusan hakim maupun putusan arbitrase pada
dasarnya merupakan hukum yang mengikat semata-mata terhadap para
pihak yang bersangkutan.
473
Artinya, putusan hakim menentukan hukum
yang konkret bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu peristiwa yang konkret
pula. Seperti halnya kaidah hukum, maka suatu putusan hakim yang telah
dijatuhkan harus dihormati oleh kedua belah pihak. Salah satu pihak tidak
boleh bertindak bertentangan dengan putusan. Oleh karena itu, untuk
menaati suatu putusan dapat dipaksakan melalui lembaga eksekusi. Secara
teoretis para pihak terikat terhadap putusan memiliki dua arti, yaitu: arti
positif dan arti negatif.
474
Arti positif atau het positieve gezag van gewijsde
maksudnya, segala apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar,
sehingga pembuktian lawan tidak dimungkinkan: res judicata pro veritate
habetur.
475
Putusan hakim itu dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi
suatu tuntutan lain.
476
Sedangkan arti negatif atau het negatieve gezag van
gewijsde dari kekuatan mengikat suatu putusan maksudnya, bahwa hakim
473
Lihat, Pasal 1917 ayat (1) BW juncto Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999.
474
Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Op. Cit., h. 177.
475
An adjudicated matter. A matter decided on its merits by a competent court. The
judgment is conclusive unless reversed on appeal. Dictionary of ...Op. Cit., h. 144.
476
Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan
umpamanya bahwa seseorang adalah pemilik sah atas rumah sengketa, dapat dijadikan
sebagai dasar hukum untuk menuntut pembayaran sewa terhadap orang yang selama ini
menempati rumah tersebut. Lihat, Setiawan, Putusan Hakim... dalam Varia
Peradilan Th. VII No. 80, Mei 1992, ...Op. Cit., h. 138.
277
tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara para
pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Artinya, putusan
hakim (dalam perkara perdata) yang telah memperoleh kekuatan hukum
yang tetap, sekali diperoleh menutup kemungkinan bagi para pihak untuk
penuntutan selanjutnya.
477
Di muka telah disebutkan bahwa putusan hakim merupakan hukum
yang mengikat para pihak, maka putusan hakim senyatanya berfungsi
sebagai sumber hukum. Putusan hakim dapat memuat kaidah hukum yang
sebelumnya tidak tercantum dalam ketentuan perundang-undangan tertentu.
Oleh karena itu, menurut Setiawan,
478
putusan hakim dapat memperluas
daya jangkau berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
Sebaliknya, putusan hakim juga dapat mempersempit daya berlakunya suatu
kaidah perundang-undangan tertentu (rechtsverfijning).
479
Dalam
menyempitkan hukum dibentuklah pengecualian-pengecualian atau
477
Sedangkan di dalam hukum pidana hal itu dinamakan dengan asas ne bis in idem,
sebagaimana dapat diketahui dari Pasal 76 KUHPidana, yaitu: ...Seseorang tidak
dapat diadili kedua kalinya dalam perkara yang sama. Lihat Setiawan, Putusan
Hakim..; Ibid., h. 137.
478
Lihat, Setiawan, Publikasi Putusan Hakim; dalam Varia Peradilan Tahun VIII
Nomor 95, Agustus 1993, h. 116-117.
479
Sebagai contoh penyempitan hukum adalah pengertian perbuatan melawan hukum
dalam pasal 1365 BW yang luas lingkupnya dipersempit sehingga menjadi apa yang
kita jumpai dalam yurisprudensi antara lain putusan HR 19 Januari 1919 dalam kasus
Lindenbaum vs. Cohen. Contoh lain misalnya, bahwa undang-undang tidak
menjelaskan apakah kerugian harus diganti juga oleh yang dirugikan yang ikut bersalah
menyebabkan kerugian (Pasal 1365 BW). Akan tetapi yurisprudensi menetapkan
bahwa kalau ada kesalahan pada yang dirugikan ini hanya dapat menuntut sebagian
dari kerugian yang diakibatkan olehnya. Lihat, Sudikno Mertokusumo, Mengenal
Hukum...Op. Cit., h. 150-151.
278
penyimpangan-penyimpangan baru dari peraturan-peraturan yang bersifat
umum. Hal itu semua semakin menunjukkan betapa hukum bukanlah suatu
hal yang statis, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Senyatanya hukum itu berkembang di luar kodifikasi, sehingga tatkala suatu
peraturan dituangkan dalam bentuk tertulis (kodifikasi), maka pada saat itu
pula hukum telah ketinggalan zaman. Oleh sebab itu, suatu undang-undang
sebagai kodifikasi hanya dapat dipahami melalui perkembangan dari
perubahan maknanya melalui yurisprudensi. Lebih-lebih apabila yang
dihadapi adalah undang-undang yang telah berumur puluhan atau bahkan
ratusan tahun seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek). Dalam konteks semacam ini tentu saja menjadi tugas hakim
dalam penegakan hukum untuk melakukan interpretasi historis atau
penafsiran sejarah, baik dalam pengertian sejarah hukum (rechtshistoris)
maupun sejarah undang-undang (wetshistoris).
2. Kekuatan Pembuktian
Putusan yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang dibuat sesuai
dengan peraturan hukum yang berlaku merupakan akta otentik.
480
Oleh
480
Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi
wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap diantara para pihak dan para
ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari padanya tentang yang tercantum di
dalamnya dan bahkan tentang yang tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan
belaka; akan tetapi yang terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat
hubungannya dengan pokok dari akta. Lihat Pasal 165 HIR, 1868 BW, 285 Rbg.
279
karena itu, putusan memberikan pembuktian terhadap apa yang dinyatakan
sebagai peristiwa-peristiwa (feitelijke voorgevallen) dalam putusan tersebut.
Di dalam hukum pembuktian, dari suatu putusan bermakna telah diperoleh
suatu kepastian hukum tentang sesuatu peristiwa sebagaimana dinyatakan
dalam putusan dimaksud. Sebagai akta otentik, putusan dimaksudkan untuk
dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak. Terhadap pihak ketiga,
putusan tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun mempunyai kekuatan
pembuktian.
Selain sebagai akta otentik, suatu putusan dapat juga dianggap
sebagai sumber persangkaan (vermoedens)
481
tentang kebenaran materiil
dari apa yang diterangkan oleh para saksi atau apa yang diakui oleh para
pihak. Putusan merupakan persangkaan bahwa isi putusan itu benar, sebab
yang diputus oleh hakim harus dianggap benar (res judicata pro veritate
habetur).
482
Sebagai akta otentik putusan merupakan bukti yang cukup atau
bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, para ahli warisnya, serta
orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka. Namun demikian akta
otentik juga masih dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan yang kuat.
483
Jadi,
481
Lihat Pasal 1916 ayat (2) no. 3 BW . Persangkaan-persangkaan semacam itu
diantaranya: kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan
hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.
482
Lihat Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara...Op. Cit., h. 181.
483
Umpamanya, apabila dalam suatu akta notaris, pada minuut (akta asli) yang disimpan
oleh notaris, terdapat tanda tangan palsu dan perihal kepalsuan tanda tangan tersebut
dapat dibuktikan, maka gugurlah kekuatan bukti akta notaris tersebut. Lihat Ny.
Retnowulan Sutantio, Hukum Acara...Op. Cit., h. 66.
280
para pihak dalam keterikatan pada isi putusan yang telah diperoleh, masih
dapat atau masih dimungkinkan untuk mengajukan suatu perkara baru pada
forum penyelesaian sengketa mana pun.
3. Kekuatan Eksekutorial
Pada dasarnya hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap yang dapat dieksekusi. Putusan semacam itulah yang
termasuk kategori memiliki kekuatan eksekutorial (executoriale kracht) atau
kekuatan untuk dilaksanakan. Oleh karena putusan itu menetapkan dengan
tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan. Masalahnya,
kekuatan mengikat suatu putusan belum memiliki arti apa pun bagi pihak-
pihak yang bersangkutan apabila putusan tersebut tidak dapat dieksekusi.
Eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan
bantuan alat-alat negara dalam rangka menjalankan putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Tindakan paksa tersebut baru akan
dipilih apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi
putusan secara sukarela. Sedangkan apabila pihak yang kalah bersedia
menaati isi putusan secara sukarela maka tindakan eksekusi tidak dilakukan.
Persoalan selanjutnya adalah, apa yang menjadi persyaratan bagi
suatu putusan untuk memperoleh kekuatan eksekutorial (executoriale
kracht)? Secara normatif setiap putusan, baik putusan pengadilan maupun
281
arbitrase harus memuat kepala putusan
484
yang berbunyi: Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kepala putusan itulah yang
memberi kekuatan eksekutorial terhadap putusan. Tidak hanya putusan
pengadilan atau putusan arbitrase, bahkan akta notariil seperti halnya grose
akta hipotik (grose akta van hypotheek) dan grose akta pengakuan hutang
(notarieele schuldbrieven)
485
harus berkepala Demi Keadilan Berdasarkan
484
Untuk putusan pengadilan, periksa Pasal 4 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999. Sedangkan
untuk putusan arbitrase, periksa Pasal 54 UU No. 30 Tahun 1999. Untuk akta notariil
seperti grose akta hipotik dan grose akta pengakuan hutang diatur di dalam Pasal 224
HIR.
485
Grose akta hipotik dan grose akta pengakuan hutang, kedua jenis akta notariil tersebut
memiliki perbedaan pokok serta masing-masing berdiri sendiri dan sama sekali tidak
boleh dicampur aduk. Perbedaan diantara keduanya terletak pada hal-hal berikut ini:
Pertama, dokumen yang melengkapi keabsahan kedua akta itu berlainan; pada grose
akta pengakuan hutang, keabsahan serta sifat asesor dari dokumen yang melengkapi
akta ini lebih sederhana dan hanya diperlukan dua jenis dokumen, yaitu: (1) dokumen
perjanjian pokok; (2) pernyataan pengakuan hutang oleh pihak debitur yang
dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sedangkan pada grose akta hipotik diperlukan 4
(empat) atau paling sedikit 3 (tiga) dokumen yang melengkapi keabsahannya. Ketiga
dokumen tersebut adalah: (1) dokumen perjanjian pinjaman hutang/kredit sebagai
dokumen pokok yang ditandatangani oleh debitur dan kreditur. Bentuk dokumen ini
bebas, dapat berbentuk akta otentik atau akta di bawah tangan; (2) perjanjian kuasa
memasang hipotik. Perjanjian ini dapat disatukan sekaligus dalam akta perjanjian
hutang/kredit apabila bentuknya akta otentik (akta notaris). Sedangkan apabila
perjanjian hutang/kredit tidak dituangkan dalam bentuk akta otentik, maka perjanjian
kuasa memasang hipotik mutlak harus terpisah dan berdiri sendiri di luar perjanjian
hutang. (3) dokumen akta pemasangan hipotik. Sebagai akta resmi (gerechtelijke akte)
tentang penetapan hipotik dibuat oleh pejabat yang berwenang. Akta ini pun harus
mencantumkan kalimat Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,
agar akta pemasangan hipotik sebagai grose akta memiliki kekuatan eksekutorial.
Harus dibuat dihadapan PPAT (bisa Camat atau Notaris). Minut atau lembar asli akta
hipotik disimpan oleh PPAT, sedangkan lembar kedua berupa salinan (grose)
dikeluarkan satu lembar diserahkan kepada pihak kreditur sebagai bukti penetapan
hipotik. (4) Sertifikat hipotik; ini melalui proses, akta hipotik, sertifikat hak tanah, dan
dokumen lain (akta perjanjian hutang, kuasa memasang hipotik) disampaikan kepada
Kepala Kantor Pendaftaran Tanah/Sub Direktorat Agraria Kabupaten/Kota) yang
bersangkutan untuk didaftarkan dan pendaftarannya dalam Buku Tanah.
Kedua, Prosedur untuk grose akta pengakuan hutang lebih sederhana, tidak
memerlukan pensertifikatan dan pendaftaran di kantor pendaftaran tanah, sedangkan
untuk grose akta hipotik harus didaftarkan dalam register umum sebagaimana
282
Ketuhanan Yang Maha Esa.
486
Kepala akta tersebut merupakan syarat
yang mesti ada agar akta notariil di muka memiliki nilai kekuatan sama
dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Kekuatan eksekutorial selain dimiliki oleh putusan pengadilan dan
putusan arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap serta grose akta
notariil yang berkepala Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa, juga dimiliki oleh akta perdamaian.
487
Akta perdamaian
sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR yang dibuat di
persidangan juga mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan seperti putusan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kedudukan sejajar antara
akta perdamaian dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini
membawa konsekuensi hukum terhadap akta perdamaian itu sendiri.
Konsekuensi tersebut yaitu apabila salah satu pihak ingkar untuk menepati
ditentukan dalam Pasal 1179 BW jo Pasal 22 ayat (3) PP No. 10/1961. Ketiga, berbeda
dalam persoalan hak yang melekat atas benda jaminan. Hak hipotik yang diberikan
debitur kepada kreditur tetap melekat pada benda yang bersangkutan di tangan siapa
pun benda itu berada. Artinya, hak hipotik kreditur tidak lepas/tanggal, sekali pun
debitur (pemilik) menjual atau memindahkannya kepada pihak ketiga. Keempat,
Berbeda beayanya; Untuk grose akta pengakuan hutang tidak diperlukan beaya
pendaftaran akta, hanya ada beaya akta notaris. Sedangkan untuk grose akta hipotik
oleh karena dituntut formalitas prosedur pendaftaran, maka diperlukan beaya berupa:
materai, honor PPAT, dan beaya pendaftaran. Lihat M. Yahya Harahap, Ruang
Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Jakarta: Gramedia, 1988, h. 198-
216.
486
Periksa Pasal 224 HIR (Pasal 258 Rbg).
487
Salah satu bukti bahwa akta perdamaian yang dibuat di dalam sidang memiliki kekuatan
seperti putusan hakim, dapat diketahui dari Pasal 1858 ayat (1) BW: Segala
perdamaian di antara para pihak mempunyai suatu kekuatan seperti suatu putusan
hakim dalam tingkat penghabisan.
283
isi yang dirumuskan dalam akta perdamaian, maka pihak lain dapat
mengajukan permintaan eksekusi ke pengadilan.
B. Interpretasi, Koreksi, dan Pergeseran Makna Putusan Arbitrase
Sebagaimana telah diutarakan di muka, bahwa status putusan
arbitrase secara normatif sudah jelas yakni bersifat final, mempunyai
kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak.
488
Oleh karena itu,
putusan arbitrase tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding,
489
kasasi,
maupun peninjauan kembali. Akan tetapi di dalam praktik, salah satu pihak
dalam sengketa diberi peluang untuk mengajukan permintaan interpretasi
(interpretation)
490
serta koreksi (correction)
491
atas putusan arbitrase kepada
kepada forum yang menjatuhkan putusan tersebut.
Interpretasi putusan arbitrase dapat dimintakan oleh salah satu pihak
apabila putusan yang dijatuhkan mengandung ketidakjelasan arti, maksud,
488
Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.
489
Kecuali menurut ketentuan Pasal 641 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering
(Rv) S. 1847 No. 52 jo 1849 No. 63. Rv sebagai ketentuan hukum acara perdata yang
dahulu berlaku pada Raad van Justitie (RvJ) untuk orang-orang Eropa dan yang
dipersamakan dengan orang Eropa, di dalamnya mengatur perihal perwasitan atau
arbitrase memperkenankan banding kepada Hooggerechtshof untuk putusan-putusan
arbitrase (de uitspraken van scheidsmannen atau putusan-putusan wasit).
490
Seperti dapat dibaca dari Art. 50 (1) ICSID Convention: If any dispute shall arise
between the parties as to the meaning or scope of an award, either party may request
interpretation of the award by an application in writing addressed to the Secretary-
General. Bahkan secara rinci tentang bagaimana permohonan interpretasi, revisi, dan
pembatalan putusan arbitrase itu diajukan dapat diketahui dalam Rule 50 ICSID Rules
of Procedure for the Institution of Conciliation and Arbitration Proceedings (1965).
491
Many developed systems of national law permit the correction of minor clerical or
typographical errors in awards, either at the request of one or both of the parties or
284
atau menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak. Permohonan
interpretasi harus diajukan secara tertulis kepada secretary-general,
492
serta
apabila dimungkinkan permohonan dimasukkan kepada forum arbitrase
yang menjatuhkan putusan tersebut.
493
Sedangkan koreksi (correction) atau
revisi atas putusan (revision of the award) dapat diminta oleh salah satu
pihak yang bersengketa ...on the ground of discovery of some fact of such a
nature as decisively to affect the award....
494
Ketentuan mengenai
permintaan koreksi putusan serupa itu dapat pula dijumpai di dalam United
Nations Commission on International Trade Law Arbitration Rules
(UNCITRAL Arbitration Rules).
495
Masalah koreksi atau revisi putusan
arbitrase, sesungguhnya tidak dapat dianggap sepele. Oleh karena mungkin
by the arbitral tribunal on its own initiative. Lihat, Alan Redfern et al., Law and
Practice...Op. Cit., h. 373.
492
Lihat, Rule 50 ICSID Rules of Procedure.
493
Lihat, Article 50 (2) ICSID Convention.
494
Lihat, Article 51 (1) ICSID Convention.
495
Article 36 (1) UNCITRAL Arbtration Rules tentang Correction of the Award antara lain
menyebutkan: ...either party, with notice to the other party, may request the arbitral
tribunal to correct in the award any errors in computation, any clerical or
typographical errors, or any errors of similar nature. The arbitral tribunal may within
thirty days after the communication of the award make such corrections on its own
initiative. Memperhatikan substansi norma tentang koreksi putusan di dalam Art. 51
ICSID dan Art. 36 UNCITRAL Arbitration Rules, dapat dipahami bahwa koreksi atau
revisi terhadap putusan arbitrase dapat dimintakan oleh salah satu pihak apabila
putusan diketahui mengandung kesalahan atau kekeliruan (error) mengenai: (i) errors
in computation (kesalahan perhitungan jumlah atau salah taksir) (ii) any clerical or
typographical errors (salah penulisan kata atau salah pengetikan); dan (iii) or any
errors of similar nature (atau kesalahan yang sama sifatnya dengan kesalahan yang
disebut terdahulu). Bahkan Mahkamah Arbitrase atas inisiatif sendiri memiliki
wewenang secara ex officio untuk melakukan koreksi walau tanpa ada permintaan dari
salah satu pihak yang bersengketa. Hal itu dapat dilakukan sekiranya Mahkamah
Arbitrase menyadari ada kesalahan-kesalahan dimaksud. Lihat, Yahya Harahap,
Arbitrase...Op. Cit., h. 268-269.
285
saja terjadi salah satu pihak menemukan kesalahan di dalam putusan yang
secara meyakinkan sangat mempengaruhi isi putusan. Dalam keadaan
semacam itu salah satu pihak dapat menjadikan kesalahan dalam putusan
sebagai dasar untuk mengajukan koreksi. Kaidah hukum arbitrase mengatur
tentang permohonan untuk melakukan koreksi putusan yang dapat diajukan
kepada arbiter atau majelis arbitrase dalam waktu paling lama 14 (empat
belas) hari setelah putusan diterima oleh para pihak.
496
Sedangkan mengenai
interpretasi putusan (interpretation of the award), kaidah hukum arbitrase
sama sekali tidak mengatur.
Berdasarkan penelusuran informasi, diketahui ternyata tidak semua
peraturan prosedur arbitrase (rules of arbitral procedure) mengatur
mengenai interpretasi putusan. Sebagai contoh Rv, BANI Rules, serta
Undang-undang Arbitrase Noor 30 Tahun 1999 tidak mengatur masalah
interpretasi putusan. Sedangkan BANI Rules dan Undang-undang Arbitrase
juga tidak membuka peluang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan
banding, kasasi, maupun peninjauan kembali untuk putusan arbitrase.
Putusan arbitrase yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap
serta mengikat para pihak itu apabila ternyata mengandung kesalahan atau
kekeliruan (error) diberi jalan keluar melalui permohonan koreksi putusan
yang dapat diajukan para pihak. Hal itu amat penting, terutama apabila salah
496
Periksa, Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999.
286
satu pihak yang bersengketa menemukan kesalahan di dalam putusan yang
secara meyakinkan sangat mempengaruhi isi putusan.
BANI Rules menyediakan norma yang dapat digunakan oleh
termohon (respondent) untuk mengajukan perlawanan (request for
opposition).
497
Perlawanan dapat diajukan terhadap putusan yang
mengabulkan tuntutan pemohon (claimant) yang dijatuhkan dalam
pemeriksaan tanpa dihadiri termohon (respondent). Sedangkan Undang-
undang Arbitrase selain memberi kesempatan para pihak untuk mengajukan
permohonan koreksi terhadap kekeliruan dalam putusan,
498
para pihak juga
dimungkinkan untuk mengajukan pembatalan putusan (annulment of an
arbitration award).
499
Permohonan pembatalan harus diajukan secara
tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri. Terhadap putusan pengadilan
negeri mengenai pembatalan putusan arbitrase itulah permohonan banding
497
Perlawanan diajukan dengan cara yang sama seperti yang berlaku untuk mengajukan
permohonan untuk mengadakan arbitrase, kecuali bahwa tidak perlu membayar beaya-
beaya pendaftaran dan administrasi/pemeriksaan; [Lihat, Pasal 12 ayat (3) BANI
Rules]. Perlawanan diajukan termohon dalam waktu empat belas hari setelah putusan
diberitahukan kepadanya; [Pasal 12 ayat (2) BANI Rules].
498
Lihat, Pasal 58 UU No. 30 Tahun 1999.
499
Permohonan pembatalan putusan arbitrase (annulment of an arbitration award) dapat
diajukan para pihak, apabila putusan arbitrase diduga mengandung unsur-unsur
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 Undang-undang Arbitrase, yaitu: (a) Surat
atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui
palsu atau dinyatakan palsu; (b) Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang
bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; (c) Putusan diambil dari
hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan kepada Ketua Pengadilan
Negeri; [Lihat, Pasal 72 ayat (1) UU Arbitrase].
287
dapat diajukan ke Mahkamah Agung yang akan memutus dalam tingkat
pertama dan terakhir.
Di samping pengaturan yang memperlakukan putusan arbitrase
semacam itu, di dalam praktik berkembang pula bentuk-bentuk pemaknaan
atau penafsiran terhadap putusan arbitrase berdasarkan sudut pandang
masing-masing pihak. Hal itu berkembang karena tanpa disadari undang-
undang arbitrase telah menghadirkan ambiguitas dalam arti pemberian
makna atau penafsiran yang lebih dari satu terhadap status putusan arbitrase.
Betapa tidak, pada satu sisi putusan arbitrase tegas dinyatakan bersifat
final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat para pihak.
Susunan serta isi putusan arbitrase pun ditentukan sama dengan susunan dan
isi putusan hakim. Bahkan putusan arbitrase pun harus memuat kepala
putusan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Maka sebenarnya tidak ada keraguan lagi terhadap putusan
arbitrase yang diambil oleh arbiter atau majelis arbitrase berdasarkan
ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan, telah
mempunyai kekuatan eksekutorial.
Berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan di muka, tidak dapat
dipungkiri kalau putusan arbitrase sesungguhnya telah memiliki kedudukan
sejajar serta kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Namun
demikian, pada sisi lain norma hukum arbitrase juga menganut standar
288
ganda. Putusan arbitrase yang telah jelas kedudukan, status keberadaan,
serta kekuatan hukumnya, secara tegas diposisikan sebagai putusan yang
masih sangat tergantung pada kewenangan pengadilan negeri. Sejumlah
indikasi mengenai hal tersebut sangat mudah dijumpai dalam undang-
undang arbitrase. Beberapa diantaranya sebagai berikut. Pertama, putusan
arbitrase nasional maupun internasional yang hendak dilaksanakan,
disyaratkan terlebih dahulu lembar asli atau salinan otentik putusan tersebut
untuk diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera
Pengadilan Negeri. Khusus untuk putusan arbitrase internasional hal itu
harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kedua, putusan
arbitrase nasional yang tidak memenuhi ketentuan penyerahan dan
pendaftaran putusan, berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
Ketiga, putusan arbitrase nasional yang tidak dilaksanakan secara sukarela
oleh para pihak, putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua
Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Keempat, khusus
untuk putusan arbitrase internasional, putusan dapat dilaksanakan di
Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat.
Menyimak keempat indikator di muka tidak ada keraguan sama
sekali kalau putusan arbitrase secara normatif sesungguhnya telah
ditempatkan dalam posisi tidak sejajar dengan putusan hakim. Itu berarti
289
kaidah hukum arbitrase telah mengukuhkan ambivalensi norma. Disadari
atau tidak norma semacam itu telah membawa akibat yang cukup serius
terhadap status hukum serta eksistensi putusan arbitrase. Oleh karena di satu
sisi, para pihak yang bersengketa menganggap putusan arbitrase sebagai
putusan yang final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan mengikat
mereka. Sangat wajar dan beralasan apabila pihak-pihak menganggap
putusan semacam itu telah memiliki kekuatan eksekutorial atau kekuatan
untuk dieksekusi. Sedangkan pengadilan negeri menguji putusan arbitrase
dengan menggunakan keempat indikator seperti yang diutarakan di muka.
Hasilnya, telah dapat diduga, yaitu bahwa putusan arbitrase untuk dapat
dieksekusi masih memerlukan keterlibatan kewenangan pengadilan negeri.
Perbedaan sudut padang antara pihak-pihak bersengketa dengan
pihak pengadilan seperti itu akan terus menerus merupakan suatu divergensi
sikap yang tidak pernah akan berakhir. Oleh karena itu, untuk menciptakan
kedua kubu pandangan menjadi konvergen, perlu diupayakan solusi terbaik
melalui cara-cara normatif pula, sebab kondisi itu pun tercipta sebagai
akibat norma yang ambivalen. Upaya yang harus dilakukan dan sekaligus
juga harus dipositifkan di dalam undang-undang arbitrase di antaranya:
(i) Forum arbitrase harus dikukuhkan kemadirian serta kewenangannya
sebagai salah satu lembaga pemeriksa dan pemutus sengketa
komersial atau sengketa perdagangan di luar lembaga pengadilan
290
negeri. Akan tetapi upaya tersebut hendaknya tidak dilakukan
separuh hati sebagaimana yang telah terjadi.
(ii) Berbagai anasir yang dapat mengurangi kedudukan serta wibawa
forum arbitrase semestinya dihapuskan. Oleh karena itu, sudah
saatnya dependensi forum arbitrase terhadap kompetensi pengadilan
negeri dilepaskan sama sekali, sebab hal tersebut langsung atau pun
tidak telah berdampak sangat merugikan eksistensi forum arbitrase
sendiri.
(iii) Terhadap sejumlah pasal di dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 yang telah mencitrakan forum arbitrase tersubordinasikan di
bawah kewenangan pengadilan merupakan conditio sine qua non
untuk dilakukan perubahan atau amandemen. Demikian pula
terhadap pasal yang nyata-nyata telah memandulkan peran dan
fungsi forum arbitrase. Pasal-pasal dimaksud antara lain dapat
disebutkan berikut ini: Pasal 59 ayat (1 sampai dengan 5), Pasal 61,
Pasal 62 ayat (1 sampai dengan 3), Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65,
Pasal 66 huruf d, Pasal 67 ayat (1 dan 2), Pasal 68 ayat (1 sampai
dengan 3), Pasal 69 ayat(1), Pasal 70, pasal 71, dan Pasal 72.
(iv) Putusan arbitrase yang dijatuhkan dimana pun, baik nasional maupun
internasional seyogianya tidak harus didaftarkan dan diserahkan atau
dimintakan eksekuatur dari pengadilan negeri. Persoalannya, cara-
291
cara tersebut telah sangat jelas membuktikan bahwa kewenangan
pengadilan negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap
mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, terkesan telah
mensubordinasikan putusan-putusan arbitrase di bawah kompetensi
pengadilan negeri.
C. Diskresi Hakim dalam Masalah Eksekuatur Putusan Arbitrase
Sebagaimana diketahui bahwa diskresi (discretion) adalah suatu
istilah dalam konteks pelaksanaan kebijaksanaan (policy) yang memiliki
multi makna. Lawrence M. Friedman,
500
antara lain mengemukakan
Discretion commonly refers to a case where a person, subject to a rule,
has power to choose between alternative courses of action. Oleh karena
itu, diskresi merupakan fenomena yang amat penting dan fundamental,
terutama di dalam hal implementasi kebijaksanaan pemerintah. Dalam
kaitan itu Jeffery Jowell mengatakan:Discretion as the room for decisional
manoeuvre possessed by a decision maker.
501
Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada prinsipnya
adalah anggota birokrasi badan peradilan yang diberi kebebasan dalam
500
Discretion is a term with many meaning. Lihat, Lawrence M. Friedman, The
Legal...Op. Cit., h. 32.
501
Lihat, Esmi Warassih, Kegunaan Telaah Kebijaksanaan Publik Terhadap Peranan
Hukum di dalam Masyarakat Dewasa ini (Sebuah Pengantar); dalam Masalah-
Masalah Hukum No. 11 Tahun 1994, h. 23.
292
mengekspresikan kewenangannya. Namun kebebasan tersebut sifatnya tidak
mutlak, karena kekuasaan kehakiman juga dipengaruhi oleh sistem
pemerintahan, sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya.
502
Di
Indonesia, sampai dengan tahun 1999, hakim berada di dalam alur birokrasi
peradilan yang secara hirarkis kewenangannya cukup unik. Dikatakan unik
karena penanganan kekuasaan kehakiman dilakukan secara dualisme
hirarkis. Di satu sisi hirarki badan peradilan berpuncak pada Mahkamah
Agung, yang melakukan pembinaan teknis yustisi kepada para hakim
pengadilan-pengadilan rendahan. Sedangkan pada sisi lain, tugas pembinaan
bidang organisatoris, administratif, dan finansial (keuangan) badan
peradilan dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Keadaan tersebut secara
normatif sekarang telah diubah melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun
1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perubahan
tersebut dapat diketahui melalui norma berikut: Badan-badan peradilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) secara organisatoris,
administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah
Agung.
503
Itu berarti Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 merupakan
tonggak sejarah yang membawa perubahan birokrasi badan peradilan dari
502
Lihat Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum...Op. Cit., h. 113-114.
503
Lihat Pasal 11 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999.
293
sistem hirarki dualisme pada masa yang lalu menuju sistem hirarki monisme
di masa mendatang.
Akan tetapi perubahan yang cukup mendasar terhadap birokrasi
badan peradilan tidak serta merta mengubah status para hakim sebagai
bagian dari birokrasi peradilan. Artinya, baik dalam sistem hirarki dualisme
maupun hirarki monisme, status hakim tetap merupakan aparat birokrasi.
504
Oleh karena itu, hakim adalah birokrat yang menjalankan tugas-tugas negara
dalam organisasi kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan aktivitasnya,
para birokrat mempunyai suatu kebebasan untuk membuat kebijaksanaan
tertentu yang mengenai aspek yuridis disebut sebagai freies ermessen
atau pouvoir discretionnaire.
505
Berkenaan dengan hal tersebut, Francis
E. Rauke
506
dalam bukunya Bureaucracy, Politics and Public Policy,
menggambarkan bahwa: Discretion refers to the ability of an
administrator to choose among alternative to decide in effect law the
policies of the government should be implemented in spesific case. Jadi,
kewenangan yang dimiliki seorang hakim untuk melakukan pilihan dalam
memutuskan berdasarkan kebijaksanaan tertentu ketika menangani kasus-
504
Yahya Muhaimin, dalam bukunya Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru
(1990:23), merumuskan birokrasi sebagai keseluruhan aparat pemerintah, sipil
maupun militer, yang melakukan tugas membantu pemerintah dan mereka yang
menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Lihat dalam Akhmad Setiawan,
Perilaku Birokrasi dalam Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 1998, h. 144.
505
Esmi Warassih, Kegunaan Telaah...Op. Cit., h. 23.
506
Esmi Warassih, Loc. Cit.,
294
kasus yang dihadapkan kepadanya, dinamakan kewenangan diskresioner
hakim (diskresi hakim). Kewenangan diskresioner bermakna: Kewenangan
untuk membuat keputusan serta kemudian mengambil tindakan yang
dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, yang
dilakukan secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala
pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.
507
Berkaitan dengan
pembahasan mengenai diskresi hakim, kemudian muncul pertanyaan,
benarkah pemberian eksekuatur terhadap putusan arbitrase internasional
tergolong diskresi hakim?
Eksekuatur (exequatur) itu sendiri berarti penetapan yang
dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (KPN) yang berisi perintah
eksekusi agar putusan arbitrase dapat dilaksanakan. Undang-undang
Arbitrase menunjuk KPN Jakarta Pusat sebagai pejabat yang memiliki
kewenangan untuk mengeluarkan penetapan eksekuatur terhadap putusan
arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia. Berdasarkan
makna eksekuatur tersebut, dapat dipahami betapa kewenangan yang
diberikan undang-undang kepada KPN demikian besar dalam menentukan
suatu putusan arbitrase internasional dapat atau tidak dieksekusi. Bahkan
KPN seakan memiliki kewenangan penuh untuk menilai benar atau tidak
507
Erlyn Indarti, Diskresi Polisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
2000, h. 12.
295
suatu putusan arbitrase yang dijatuhkan. Dalam rangka melaksanakan
kewenangan, fungsi, serta tanggung jawab semacam itu, maka para hakim,
teristimewa KPN Jakarta Pusat sebagai pejabat yang berwenang memberi
eksekuatur, dituntut untuk memiliki wawasan serta pemahaman yang
komprehensif mengenai ruang lingkup permasalahan hukum arbitrase.
Seandainya sinyalemen Priyatna Abdurrasyid bahwa 99,9 persen
hakim tidak mengerti mengenai hukum arbitrase itu benar adanya, maka
akan sangat berdampak tidak menguntungkan terhadap pihak-pihak yang
bersengketa pada forum arbitrase asing. Oleh karena apabila hakim atau
KPN kurang atau bahkan tidak menguasai dengan saksama kaidah hukum
arbitrase, akan sulit untuk dapat melaksanakan kewenangan diskresioner
dalam memberikan eksekuatur. Dampaknya, putusan arbitrase internasional
akan sulit memperoleh eksekuatur di Indonesia, sehingga bagi setiap hakim
lebih-lebih KPN Jakarta Pusat sebagai pemegang otoritas eksekuatur
merupakan conditio sine qua non untuk benar-benar menguasai serta
memahami kaidah hukum arbitrase secara utuh menyeluruh.
Aharon Barak
508
menyebut kewenangan diskresioner seorang hakim
dengan istilah judicial discretion, yaitu the power given to the judge to
508
these options may refer to three matters. The first is the fact. Judicial discretion
chooses from among the set of facts those that it deems necessary for making a
decision in the conflict. The second area is the application of a given norm. Judicial
discretion selects from among the different methods of application that the norm
provides the one that it finds appropriate. The third area of discretion chooses from
296
choose from among a number of possibilities, each of them lawful in the
context of the system. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa para
hakim dalam menjalankan tugas-tugas judicial diberi kekuasaan (power)
dan kewenangan (authority) untuk melakukan pilihan terhadap sejumlah
alternatif dalam menerapkan norma di antara berbagai kemungkinan.
Selanjutnya Barak
509
mengatakan: the power the law gives the judge to
choose among several alternatives, each of them being lawful or to choose
among a number of lawful options. Adapun yang dimaksud dengan
options dalam pernyataan itu pada prinsipnya merujuk pada tiga
persoalan,
510
yaitu: Pertama, Judicial discretion chooses from among the
set of facts those that it deems necessary for making a decision in the
conflict. Kedua, Judicial discretion selects from among the different
methods of application that the norm provides the one that it finds
appropriate. Ketiga,Judicial discretion chooses from among the
normative possibilities the option that it deems appropriate. Jadi, objek
diskresi hakim pada prinsipnya meliputi fakta, kemudian penerapan norma,
serta norma itu sendiri. Berdasarkan ketiga faktor di muka, maka
among the normative possibilities the option that it deems appropriate. Lihat, Aharon
Barak, Judicial Discretion. New York: Yale University Press, 1989, h. 12-13.
509
Lihat, Aharon Barak, Judicial... Op. Cit., h. 7 & 12.
510
Loc. Cit., h. 13.
297
pemberian eksekuatur terhadap putusan arbitrase termasuk ke dalam opsi
kedua yakni berkenaan dengan penerapan norma terhadap fakta.
Adapun hakikat pemberian eksekuatur adalah berupa penelitian
saksama mengenai putusan arbitrase apakah putusan tersebut sudah benar,
tepat, dan tidak mengandung cacat yuridis. Dalam melaksanakan fungsi
serta kewenangan tersebut, agar tidak bertindak melampaui batas, otoritas
KPN dibatasi oleh rambu-rambu sebagai berikut:
511
1) Bahwa pemberian eksekuatur itu bukan pemeriksaan banding,
sehingga KPN tidak memiliki hak atau kewenangan untuk
meneliti dan memeriksa ulang sengketa secara keseluruhan;
2) Pemberian eksekuatur juga bukan merupakan tindakan fungsi
pengawasan. Dalam kaitan ini, KPN tidak berwenang menilai
kecakapan dan kredibilitas anggota arbiter. KPN juga tidak
berwenang memberi tafsiran, mengoreksi atau merevisi putusan;
3) Kewenangan penelitian dalam rangka memberikan eksekuatur
bersifat formal. Artinya, KPN pada prinsipnya tidak dibenarkan
menilai dan meneliti materi putusan yang akan memberi kesan
sebagai pemeriksaan banding atau kasasi.
511
Lihat, M. Yahya Harahap, Arbitrase...Op. Cit., h. 306-308.
298
Seperti telah diutarakan bahwa pada prinsipnya dalam pemberian
eksekuatur KPN tidak berwenang memeriksa dan menilai benar tidaknya
materi putusan arbitrase. Akan tetapi, terhadap prinsip tersebut dikenal ada
pengecualian. Setidaknya ada dua hal yang dikecualikan, sehingga dalam
rangka melakukan penelitian pemberian eksekuatur KPN Jakarta Pusat
boleh menilai segi-segi materi putusan arbitrase. Pertama, apakah materi
putusan arbitrase tidak melampaui batas yang dibenarkan hukum dan
perundang-undangan. Kedua, apakah putusan arbitrase tersebut tidak
bertentangan dengan ketertiban umum (public policy).
512
Materi putusan arbitrase dianggap melampaui batas yang dibenarkan
hukum dan perundang-undangan apabila forum arbitrase telah memeriksa
dan memutus kasus-kasus sengketa yang secara mutlak tidak termasuk
jurisdiksi arbitrase. Sedangkan Undang-undang Arbitrase telah secara
limitatif menetapkan sengketa yang termasuk dalam jurisdiksi arbitrase.
Sengketa tersebut ...hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai
hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai
sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
513
Oleh karena itu, di luar jenis
512
Article V (2) New York Convention 1958, antara lain menyebutkan: The recognition
and enforcement of an arbitral award may also be refused if the competent authority
in the country where recognition and enforcement is sought finds that: (b) The
recognition or enforcement of the award would be contrary to the public policy of that
country.
513
Periksa Pasal 5 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999. Bandingkan dengan yang ditetapkan
dalam Article 1 (1) UNCITRAL Model Law on International Commercial
299
sengketa yang disebutkan dalam undang-undang arbitrase, kewenangan
memeriksa dan memutus sengketa tersebut mutlak merupakan jurisdiksi
pengadilan. Berikut ini beberapa contoh sengketa yang menurut hukum
Indonesia tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase:
514
(i) pembatalan
perkawinan, (ii) pemisahan harta kekayaan, (iii) perceraian, (iv) pemisahan
meja dan tempat tidur, (v) keabsahan anak, (vi) pembuktian anak sah.
Apabila terjadi perjanjian arbitrase menyangkut bidang-bidang tersebut,
akibatnya perjanjian arbitrase semacam itu diancam batal demi hukum (null
and void). Dalam hal materi putusan arbitrase menyangkut salah satu bidang
yang disebutkan di muka, maka dalam rangka pemberian eksekuatur, KPN
Jakarta Pusat dapat melakukan penelitian bidang formal sekaligus materiil
karena putusan arbitrase dimaksud telah mengandung pelanggaran hukum
materiil.
Berkaitan dengan persoalan ketertiban umum (public policy), KPN
Jakarta Pusat dalam konteks pemberian eksekuatur juga dapat menilai
materi putusan arbitrase. Penilaian dilakukan terhadap setiap putusan
arbitrase internasional yang dimintakan untuk dieksekusi di Indonesia,
apakah putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak.
Arbitration: This Law applies to international commercial arbitration, subject to any
agreement to force between this Sate and any other State or States.
514
Pasal-Pasal 85, 186, 207, 233, 250, 261 BW dan Pasal 25 jo Pasal 39 ayat (1) UU No. 1
Tahun 1974 jo Pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975, jo Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 75 ayat
(1) UU No. 7 Tahun 1989. Lihat, M. Yahya Harahap, Arbitrase...Op. Cit., h. 321.
300
Sebagaimana diketahui istilah ketertiban umum (public policy) memiliki
banyak makna.
515
Meskipun ketertiban umum merupakan asas yang bersifat
universal tetapi di berbagai negara penyebutannya dikenal dengan berbagai
macam istilah.
516
Tidak hanya penyebutan istilah yang beraneka ragam,
bahkan ukuran nilai ketertiban umum antara satu bangsa dengan bangsa lain
juga sangat bervariasi. Oleh sebab itu, tidak ada makna ketertiban umum
yang pasti tetap berlaku untuk segala zaman dan waktu. Melainkan faktor
tempat dan waktu juga sangat berpengaruh terhadap konsep ketertiban
umum. Berkaitan dengan hal tersebut, Kollewijn
517
dalam disertasinya
mengutarakan antara lain sebagai berikut: Zo bleek het ten slotte niet
mogelijk het recht van openbare orde te bepalen. Wij konden konstateren
wanneer en op welke wijze theoretici en rechters zich op de openbare orde
beriepen, maar konden de inhoud der openbare orde niet definieren.
515
Ketertiban umum memiliki makna yang sangat beragam, seperti dapat disimak berikut
ini: (i) ketertiban umum diartikan sebagai ketertiban dan kesejahteraan, keamanan; (ii)
ketertiban umum sebagai pasangan dari istilah kesusilaan baik (goede zeden) seperti
diketahui dari Pasal 1337 BW; (iii) ketertiban umum diartikan pula sebagai ketertiban
hukum (rechtsorde); (iv) dalam beberapa hal ketertiban umum juga bermakna
keadilan; (v) dan kadang-kadang diartikan pula bahwa hakim diwajibkan
mempergunakan pasal-pasal Undang-undang tertentu. Lihat, Sudargo Gautama,
Hukum Perdata Internasional; (HPI) Buku Ke 4. Bandung: Alumni, 1989, h. 56-57.
516
Belanda menyebut istilah ketertiban umum dengan openbare orde, Perancis memakai
istilah ordre public, Jerman menyebut dengan istilah Vorbehaltklausel,
sedangkan negara-negara Anglo Saxon memakai istilah public policy, Italia
menyebut dengan istilah ordine publico, dan Spanyol memakai istilah orden
publico. Baca, Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional (HPI); Buku ke
4... Loc. Cit., h. 3.
517
R.D. Kollewijn, Het beginsel der openbare orde in het international privaatrecht.
Dissertasi, Leiden, 1917; dalam Sudargo Gautama, HPI-Buku ke 4...Loc. Cit., h. 138.
301
Adalah tidak mungkin memastikan hukum yang bersifat ketertiban umum.
Hanya mungkin untuk mengkonstatir mengenai kapan dan dengan cara
bagaimana para sarjana serta para hakim mempergunakan ketertiban umum,
sedangkan substansi ketertiban umum itu sendiri tidak dapat dirumuskan.
Konsep ketertiban umum itu memang tidak pasti serta latent adanya,
selalu berubah-ubah menurut penentuan serta apresiasi hakim yang harus
melaksanakannya. Oleh karena itu pula, Kollewijn sebagaimana dikutip
Gautama selanjutnya mengatakan bahwa hakim tidak mempergunakan
ketertiban umum karena suatu ketentuan hukum dari negaranya bersifat
ketertiban umum, melainkan karena ia (hakim) menganggap ketertiban
umum harus dipergunakan, maka hakim menyebutkan kaidah bersangkutan
bersifat ketertiban umum.
518
Dari konteks pernyataan tersebut tampak
sekali betapa peran hakim demikian besar dalam penentuan substansi
ketertiban umum.
Jadi, kewenangan menilai suatu putusan arbitrase internasional
apakah dianggap bertentangan dengan ketertiban umum atau tidak, termasuk
dalam kewenangan seorang hakim yang tergolong kewenangan diskresioner
518
S. Gautama mengutip pernyataan Kollewijn antara lain sebagai berikut: Niet omdat
een rechtsbepaling van zijn staat van openbare orde was, paste de rechter haar toe,
maar omdat hij haar, op welke grond dan ook toepasselijk achtte, noemde hij haar van
openbare orde. Lihat, S. Gautama, HPI; Buku ke 4...Op. Cit., h. 137.
302
(judicial discretion). Kewenangan semacam itu menurut Aharon Barak
519
tergolong pada the application of a given norm karena menyangkut the
choice among a number of alternative ways of applying a norm to a given
set of facts. Hal tersebut disebabkan norma hukum merupakan sesuatu
yang abstrak, sehingga hanya hakim pengadilan yang memiliki otoritas atau
kewenangan untuk menerjemahkan
520
atau menafsirkan setiap norma yang
akan diterapkan pada kasus-kasus yang dihadapkan kepadanya. Maka di
dalam menentukan isi dan makna ketertiban umum secara konkret
berdasarkan peristiwa demi peristiwa, peran hakim
521
demikian besar.
Bahkan dalam menjalankan kewenangan diskresioner tersebut, acapkali
kewenangan hakim tidak mudah diduga. Hal itu pernah terjadi dalam kasus
pemberian eksekuatur terhadap Putusan Badan Arbitrase Gula The Council
of The Refined Sugar Association yang berkedudukan di London dalam
sengketa antara Yani Haryanto (importir Indonesia) lawan E.D. & F. MAN
519
Frequently, a legal norm gives the judge the power to choose among different
courses of action that are fixed in its framework. This grant of authority may be
explicit, as when the norm is actually phrased in terms of discretion. The grant may
also be implicit, such as when the norm refers to a stand`ard (for example, negligence
or reasonableness) or to a goal (such as the defense of the state, public order, the best
interests of the child). Lihat, Aharon Barak, Judicial...Op. Cit., h. 14.
520
Berkaitan dengan persoalan penafsiran atas norma-norma hukum, Justice Sussman
mengemukakan sebagaimana dikutip Barak di dalam Bukunya: The law is an abstract
norm and only the judgment of the court translates the rule of the legislature into an
obligatory act that is enforced on the public. The judge gives the law its real and
concrete form. Therefore one can say that the statute ultimately crystallizes in the
shape the judge gives it. Aharon Barak, Loc. Cit., h. 14.
521
The judge has wide discretion in this respect... S. Gautama, HPI; Buku ke 4... Op.
Cit., h. 140.
303
Sugar Ltd. London.
522
Akan tetapi, penetapan eksekuatur tersebut tidak
lama kemudian dibatalkan.
Kasus tersebut cukup menarik serta mendapat perhatian karena
Mahkamah Agung dinilai tidak konsisten dan Hukum Indonesia gampang
bergoyang.
523
Pada awalnya MA mengabulkan permohonan eksekuatur
terhadap putusan arbitrase asing dalam kasus kontrak dagang internasional
jual beli gula pasir itu, akan tetapi ternyata kemudian melalui putusan kasasi
MA membatalkan penetapan tersebut. Majelis Hakim Agung yang
menangani kasus tersebut menggunakan alasan ketertiban umum di
Indonesia sebagai dasar pembatalan putusan arbitrase asing dimaksud.
Selengkapnya alasan itu dapat disimak berikut ini, ..karena ternyata
putusan didasarkan kepada kontrak yang mempunyai causa yang dilarang di
Indonesia, sehingga bertentangan dengan Ketertiban Hukum di Indonesia,
maka putusan tersebut tidak mempunyai daya mengikat.
524
D. Eksekusi Putusan Arbitrase dalam Penegakan Keadilan
Eksekusi putusan arbitrase merupakan elemen yang amat penting
dalam keseluruhan rangkaian proses penyelesaian sengketa melalui forum
522
Selengkapnya kasus posisi dari sengketa ini dapat dibaca dalam Pembatalan Kontrak
Dagang Internasional Dewan Arbitrase Dikesampingkan; dalam Varia Peradilan
Tahun VII No. 80, Mei 1992, h. 5-43.
523
Mahkamah Agung Meralat Gengsi; dalam Tempo, 21 Maret 1992, h. 28.
524
Pembatalan...; Varia Peradilan...Op. Cit., h. 12. Bdgk. Huala Adolf, Pembatalan
Putusan Arbitrase Asing; dalam Kompas, Jumat, 29 Mei 1992.
304
arbitrase. Oleh karena yang lebih penting bagi pencari keadilan bukan
sekedar minta putusan yang seadil-adilnya, melainkan putusan tersebut
dapat dilaksanakan apabila perkaranya dimenangkan. Apa artinya sebuah
putusan bagi seseorang yang dimenangkan, tetapi kemudian tidak dapat
dieksekusi. Hanya akan dikatakan menang di atas kertas. Dalam praktik,
eksekusi putusan arbitrase, terutama yang dibuat di luar negeri, sejak dahulu
selalu menghadapi hambatan. Sejumlah faktor diyakini menjadi penyebab,
sehingga permohonan eksekusi putusan arbitrase asing tidak pernah
mencerminkan penegakan keadilan. Beranjak dari fenomena tersebut,
melakukan kajian mengenai eksekusi putusan arbitrase dalam kerangka
penegakan keadilan dipandang masih cukup relevan serta tetap menarik
sampai sekarang ini.
Analisis mengenai hal itu akan dilakukan melalui tiga pembabakan.
Pertama, periode sebelum Indonesia mengesahkan Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. Kemudian
Kedua, periode setelah Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1981
tentang pengesahan Konvensi tersebut di atas, disusul dengan keluar
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tatacara
Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Ketiga, periode sesudah berlaku
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
305
Penyelesaian Sengketa. Mengingat pada periode pertama terkait dengan
suatu masa ketika Tata Hukum di Indonesia masih dalam situasi kebijakan
hukum kolonial Belanda, maka dalam memaparkan periode itu tentu tidak
dapat dihindari akan bersinggungan dengan kaidah hukum yang berasal dari
masa Hindia Belanda.
1) Periode Sebelum Mengesahkan Konvensi New York
Lembaga arbitrase dikenal di Indonesia sejak masa kolonial Belanda.
Pengaturan arbitrase pada masa itu merupakan bagian dari hukum acara
perdata untuk Raad van Justitie yang diatur dalam Reglement op de
Burgerlijke Rechtsvordering (Rv).
525
Akan tetapi Rv sama sekali tidak
menyebut tentang arbitrase asing, sehingga tidak dikenal kaidah yang
mengatur pelaksanaan (eksekusi) putusan arbitrase asing. Putusan arbitrase
asing analog dengan putusan hakim asing. Sebagaimana ditentukan dalam
Pasal 436 Rv pada asasnya putusan hakim asing tidak dapat dieksekusi di
wilayah Indonesia, sehingga putusan arbitrase asing juga tidak dapat
dimohonkan eksekusi di wilayah Indonesia. Pada dekade delapan puluhan
pernah terjadi polemik antara Asikin Kusumah Atmadja ketika itu sebagai
Ketua Muda MA di satu pihak dengan Sudargo Gautama di lain pihak. Pada
525
Pasal 615 651 RV atau Reglement op de Rechtsvordering, atau judul lengkapnya
Reglement op de burgerlijke rechtsvordering voor de raden van justitie op Java en
306
tahun 1927 Pemerintah Belanda menandatangani Konvensi Jenewa tentang
pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase luar negeri. Berdasarakan asas
konkordansi konvensi tersebut juga berlaku di wilayah Hindia Belanda.
Berlakunya konvensi itu setelah Indonesia merdeka kemudian menjadi
polemik kedua tokoh di muka. Asikin Kusumah Atmadja mempertanyakan,
apakah dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase asing dapat dipakai
Voorzieningen voor Indonesie ter uitvoering van het verdrag nopens de
tenuitvoerlegging van in het buitenland gewezen scheidsrechterlijke
uitspraken van Sept. 1927; (KB van 17 Dec. 1932 No. 82); S. 1933 132 jo
133? Konvensi Jenewa yang berlaku secara nyata pada tanggal 28 April
1933 itu setelah Indonesia merdeka tidak berlaku lagi. Alasannya, Republik
Indonesia tidak pernah menyatakan secara tegas dan aktif untuk tetap terikat
pada konvensi tersebut.
526
Sedangkan pada pihak lain, Sudargo Gautama
berpendapat bahwa Konvensi Jenewa 1927 masih berlaku untuk Indonesia.
Argumen yang dikemukakan Sudargo antara lain sebagai berikut:
527
...Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pasal peralihan telah dinyatakan
bahwa berkenaan dengan pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada RI
dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945 zaman
Yogyakarta, maka persetujuan-persetujuan internasional yang berlaku untuk
wilayah RI pada saat penyerahan kedaulatan, tetap akan berlaku untuk RI. Dalam
het hooggerechtshof van Indonesie, alsmede voor de residentiegerechten op Java en
Madura - S. 1847 52 jo 1849 63.
526
Asikin Kusumah Atmadja, Konvensi/Ratifikasi dan Eksekusi Putusan Arbitrase;
Makalah Seminar Sehari. Kerjasama antara ALTRI-KADIN-BANI, Jakarta, 16
Nopember 1988, h. 2-4.
527
Sudargo Gautama, Indonesia dan Arbitrase Internasional. Bandung: Alumni, 1986,
h. 68.
307
hal ini Konvensi Jenewa yang tercakup dalam Staatsblad 1933 No. 132 juga masih
harus dianggap berlaku, kecuali apabila RI telah menyatakan secara tegas untuk
tidak berlaku.
Sebagai sintesa dari dua pendapat tokoh di muka, R. Subekti
528
menyatakan: sukar bagi pengadilan kita untuk memberlakukan konvensi
dalam soal pelaksanaan putusan arbitrase asing. Alasan beliau didasari oleh
adanya pendirian Departemen Luar Negeri RI yang menyebut bahwa
perjanjian-perjanjian internasional yang dulu diadakan oleh Pemerintah
Hindia Belanda, tidak otomatis beralih kepada RI. Akan tetapi harus secara
tegas diperbaharui melalui pernyataan yang tegas (stelsel aktif).
Polemik di atas berimplikasi pada dataran praksis. Seperti dapat
disimak pada kasus berikut ini: London Arbitration Awards No. 1950,
tanggal 12 Juli 1978, kasus antara PT Nizwar Jakarta vs Navigation
Maritime Bulgare, varna, Blvd. Chervenoermeiski. Putusan arbitrase
tersebut dimintakan fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Melalui Penetapan No.2288/1979 P., tanggal 10 Juni 1981 Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan pemohon. Artinya
putusan Arbitrase London itu dapat dieksekusi, sehingga PT Nizwar Jakarta
harus melaksanakan Putusan Arbitrase London Nomor 1950, tanggal 12 Juli
1978. Menanggapi penetapan PN Jakarta Pusat itu PT Nizwar selaku
528
R. Subekti, Arbitrase Perdagangan. Bandung: Binacipta, 1981, h. 29.
308
termohon eksekusi mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Meski
menolak permohonan kasasi itu karena pemohon tidak mengajukan memori
kasasi, namun MA menyatakan bahwa permohonan pelaksanaan putusan
arbitrase asing seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.
Pertanyaannya kemudian, mengapa permohonan fiat eksekusi putusan
arbitrase London itu dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tetapi
kemudian ditolak oleh Mahkamah Agung?
Hal itu diduga terjadi di samping karena PN Jakarta Pusat dengan MA
berbeda sudut pandang, juga karena kedua institusi pemutus itu merujuk
instrumen hukum yang berlainan sebagai landasan pemutus. Ketika
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan penetapan yang
mengabulkan permohonan fiat eksekusi pihak Navigation Maritime
Bulgare, varna, Blvd. Chervenoermeiski, Indonesia belum mengesahkan
Konvensi New York 1958.
529
Maka, salah satu pertimbangan PN Jakarta
Pusat menyebutkan Konvensi Jenewa 1927 masih berlaku, sehingga putusan
arbitrase yang diucapkan di London 12 Juli 1978 dapat dilaksanakan di
Indonesia. Selanjutnya menghukum PT Nizwar Jakarta untuk membayar
jumlah tertentu kepada Navigation Maritime Bulgare. Sementara itu,
pengesahan Konvensi New York dilakukan oleh Pemerintah RI dengan
529
Penetapan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan fiat eksekusi pemohon Navigation
Maritime Bulgare, varna, Blvd. Chervenoermeiski, dikeluarkan tanggal 10 Juni 1981.
309
instrumen ratifikasi Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada
tanggal 5 Agustus 1981. Sedangkan ketika MA menerima permohonan
kasasi PT Nizwar Jakarta yang ditolak karena tidak mengajukan memori
kasasi, terjadi setelah Pemerintah RI mengesahkan Konvensi New York.
Maka pertimbangan MA dalam putusan Nomor 2944 K/Pdt/1983 tanggal 20
Agustus 1984, MA telah menyebut Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun
1981 dan lampirannya tentang pengesahan Convention on the Recognition
and Enforcement of Foreign Arbitral Awards masih harus ada peraturan
pelaksanaannya.
530
Apabila dihubungkan dengan pendapat Asikin Kusumah
Atmadja di muka, sesungguhnya pendirian MA tidak berubah dan tetap
konsisten. Sejak semula Asikin Kusumah Atmadja, baik selaku pribadi
maupun sebagai Ketua Muda MA telah berpendirian bahwa Konvensi
Jenewa 1927 tidak berlaku lagi di Indonesia. Oleh karena itu, putusan
arbitrase asing tidak dapat dieksekusi di Indonesia. Jadi, ketika MA menolak
permohonan fiat eksekusi tentu saja tidak mengherankan. Kebetulan pula
Asikin Kusumah Atmadja ditunjuk sebagai Ketua Sidang Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus kasus tersebut.
530
Lihat, Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam...Op. Cit., h. 287-288.
310
2) Periode setelah Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981
Setelah Pemerintah RI mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres)
Nomor 34 Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958,
banyak pihak menggantungkan harapan dengan disahkan konvensi tersebut
putusan arbitrase asing akan dapat dilaksanakan di Indonesia.
531
Harapan
tersebut kiranya tidak berlebihan karena konvensi itu tegas menyebutkan
bahwa setiap negara penandatangan konvensi akan mengakui dan
melaksanakan putusan arbitrase yang dibuat di negara lain yang bersama-
sama Indonesia terikat dalam Konvensi New York 1958. Di samping itu,
salah satu pensyaratan (reservation) yang dibuat Pemerintah RI sebagai
lampiran Keppres 34/1981 antara lain menyatakan ...The Government of
Indonesia declares that it will apply the Convention on the basis of
reciprocity, to the recognition and enforcement of awards made only in the
territory of another Contracting State.... Oleh karena itu, sesungguhnya
telah cukup bagi Indonesia untuk dapat mengakui serta melaksanakan
putusan arbitrase asing. Namun demikian, praktik masih menunjukkan
sebaliknya. Seperti telah disebutkan di muka, Mahkamah Agung dalam
pertimbangan putusan perkara PT Nizwar menyatakan bahwa Keppres
531
...many people believed that when Indonesia become a party to the New York
Convention a foreign arbitral award would be enforceable in Indonesia. Lihat,
Mulyana, et al., Indonesias New Framework...; dalam Mealeys International
Arbitration Report...Op. Cit., h. 23.
311
34/1981 dan lampirannya tentang pengesahan Convention on the
Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards masih harus ada
peraturan pelaksanaannya. Apakah permohonan eksekusi putusan arbitrase
asing itu dapat diajukan langsung pada pengadilan negeri, kepada
pengadilan negeri yang mana ataukah diajukan melalui Mahkamah Agung.
Maksudnya untuk dipertimbangkan apakah putusan tersebut tidak
mengandung hal-hal yang bertentangan dengan ketertiban hukum di
Indonesia.
Tindakan ratifikasi Konvensi New York 1958 belum memberikan
jalan keluar dari masalah yang selama ini menghambat pelaksanaan putusan
arbitrase asing di Indonesia. Persoalan tersebut tetap tidak jelas sampai
dengan dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun
1990 tentang Tatacara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.
532
Sebagai
kaidah hukum acara, Perma No. 1/1990 antara lain menetapkan bahwa yang
diberi wewenang yang berhubungan dengan pengakuan serta pelaksanaan
putusan arbitrase asing adalah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Artinya, pengadilan negeri yang relatif kompeten menangani masalah
tersebut adalah PN Jakarta Pusat. Oleh karena itu, putusan arbitrase asing
dapat dimintakan pelaksanaan setelah putusan tersebut dideponir di
Kepaniteraan PN Jakarta Pusat. Selanjutnya PN Jakarta Pusat dalam waktu
532
Ditetapkan tanggal 1 Maret 1990.
312
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterima
permohonan tersebut, mengirimkan berkas permohonan eksekusi itu kepada
Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung untuk memperoleh exequatur.
Setelah MA memberikan exequatur, pelaksanaan selanjutnya diserahkan
kepada KPN Jakarta Pusat. Apabila pelaksanaan putusan harus dilakukan di
wilayah hukum lain, maka putusan yang telah memperoleh exequatur
selanjutnya akan diserahkan kepada pengadilan negeri yang relatif
kompeten untuk melaksanakan putusan itu sesuai dengan pasal 195 HIR/206
ayat (2) Rbg.
Dalam periode ini juga dapat disaksikan paling tidak ada dua
putusan arbitrase asing yang ditolak permohonan eksekuaturnya untuk
pelaksanaan putusan tersebut oleh pengadilan negeri di Indonesia. Kedua
putusan tersebut adalah (1) Putusan Arbitrase London dalam perkara antara
Trading Corporation of Pakistan Ltd, melawan PT Bakrie & Brothers. (2)
Putusan Arbitrase London dalam kasus antara E.D. & F.MAN (SUGAR)
Ltd., melawan Yani Haryanto. Uraian tentang kasus posisi untuk putusan
yang pertama dapat disimak sebagai berikut:
533
533
Uraian serta isi putusan selengkapnya sejak Pengadilan Negeri sampai dengan
Mahkamah Agung dapat disimak di dalam Erman Rajagukguk, Arbitrase dalam...Op.
Cit., h. 289-319.
313
Perkara antara Trading Corporation of Pakistan Ltd, pemohon
kasasi dahulu terbantah/pembanding melawan PT Bakrie & Brothers,
termohon kasasi dahulu pembantah/terbanding. Sengketa antara kedua belah
pihak telah diputus oleh Arbitrase dari Federation of Oils, Seeds and Fate
Association Ltd London No. 2282 tanggal 8 September 1981.
Putusan arbitrase tersebut kemudian oleh terbantah diajukan
permohonan eksekusinya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Tanggal 13 Februari 1984 PN Jakarta Selatan mengeluarkan Ketetapan No.
22/48/JS/1983 untuk pendaftaran dan pelaksanaan Award of Arbitration dari
Federation of Oils, Seed and Fats Associations Limited No. 2282 tanggal 8
September 1981. Terhadap Ketetapan PN Jakarta Selatan itu pembantah,
dalam hal ini PT Bakrie & Brothers telah melakukan bantahan. Inti
bantahan didasarkan pada hal-hal antara lain sebagai berikut: (i) dalam
kasus ini negara-negara yang bersangkutan (Contracting States) adalah
Pakistan dan Indonesia, bukan Inggris dan Indonesia; (ii) prosedur
pengambilan putusan oleh badan arbitrase tersebut tidak mengindahkan rasa
keadilan dan kepatutan. Pembantah selaku pihak yang disebut pihak penjual
tidak didengar dan tidak diberi kesempatan membela diri mengapa
pelaksanaan kontrak sampai gagal.
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan Nomor
64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel, mempertimbangkan antara lain sebagai berikut:
314
(i) majelis menganggap bahwa pembantah telah berhasil membuktikan dalil-
dalilnya dan karena itu harus dikabulkan; (ii) karena bantahan dikabulkan,
maka putusan Arbitrase London Nomor 2282 tersebut di atas harus
dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dieksekusi. Putusan PN
Jakarta Selatan itu kemudian dimohonkan Banding ke Pengadilan Tinggi
DKI Jakarta. Dalam putusan Nomor 512/PDT/1985/PT DKI, tanggal 23
Desember 1985 Pengadilan Tinggi DKI menguatkan putusan PN Jakarta
Selatan tanggal 1 Nopember 1984 No. 64/Pdt/G/1984/PN.Jkt.Sel yang
dibanding tersebut.
Terbantah/pembanding, dalam hal ini Trading Corporation of
Pakistan Ltd., kemudian mengajukan kasasi atas putusan PT DKI tersebut di
atas. Dalam putusan Nomor 4231 K/Pdt/1986 tanggal 4 Mei 1988, Ketua
Sidang Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan memutus
kasus tersebut mempertimbangkan antara lain: bahwa berdasarkan apa
yang dipertimbangkan, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan
judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-
undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi:
Trading Corporation of Pakistan Limited tersebut harus ditolak.
Memperhatikan rangkaian kasus di atas, dapatlah dipahami betapa banyak
faktor yang terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya suatu putusan
arbitrase asing dilaksanakan di Indonesia. Oleh sebab itu, ternyata Peraturan
315
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 sebagai peraturan pelaksanaan dari
Keppres 34/1981 dan lampirannya juga belum dapat menciptakan proses
dan prosedur yang sederhana dalam rangka pelaksanaan putusan arbitrase
asing di Indonesia.
Kasus berikut ini cukup heboh dan terkenal disebabkan oleh dua
faktor. Pertama, Mahkamah Agung untuk pertama kalinya memberikan
eksekuatur terhadap putusan arbitrase asing sejak MA mengeluarkan
PERMA 1/1990. Kedua, dalam waktu yang tidak terlalu lama penetapan
MA tentang pemberian eksekuatur itu kemudian dibatalkan sendiri melalui
putusan kasasi. Kasus ini dikenal dengan sebutan Kasus Gula karena
objek sengketa tersebut memang mengenai jual beli gula. Selengkapnya
rangkaian perjalanan permohonan eksekusi putusan arbitrase London dalam
perkara antara E.D. & F.MAN (SUGAR) Ltd., melawan Yani Haryanto,
dapat disimak berikut ini.
Pada tahun 1982 pengusaha Indonesia Yani Haryanto bertindak
sebagai pembeli mengadakan perjanjian jual beli gula dengan eksportir
Inggris E.D. & F, Man Sugar Ltd. Sugar quay London, sebagai penjual.
Perjanjian tersebut dituangkan dalam dua bentuk kontrak dagang, yaitu:
1) Contract for White Sugar No. 7458, tanggal 12 Februari 1982
untuk jual beli gula sebanyak 300.000 metrik ton;
316
2) Contract for White Sugar No. 7527, tanggal 23 Maret 1982
untuk jual beli gula sebanyak 100.000 metrik ton.
Kedua kontrak tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak pada
bulan Februari dan Maret 1982. Dalam kedua kontrak di atas para pihak
bersepakat bahwa segala sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian
jual beli gula ini, kedua belah pihak sepakat diselesaikan oleh suatu Dewan
Arbitrase Gula atau yang disebut The Council of the Refened Sugar
Association yang berkedudukan di London berdasarkan ketentuan dalam
The Rules of the Refened Sugar Association Relating to Arbitration.
Pelaksanaan kontrak ternyata mengalami kegagalan karena Yani
Haryanto menolak melaksanakan perjanjian jual beli tersebut dengan alasan
bahwa import gula itu merupakan kewenangan BULOG (Badan Urusan
Logistik). Sedangkan perorangan tidak dibenarkan melakukan import gula.
Larangan itu tertuang di dalam (i) Keputusan Presiden (Keppres) No. 43
Tahun 1971, tanggal 14 Juli 1971 tentang Kebijaksanaan Pemerintah dalam
bidang pengadaan beras, gula, dan lain-lain oleh BULOG; (ii) Keppres No.
39 Tahun 1978. Ketika perjanjian disepakati kedua belah pihak tidak
mengetahui kedua Keppres tersebut dan baru diketahui setelah perjanjian
hendak dilaksanakan. Atas dasar hal itu maka Yani Haryanto membatalkan
kedua perjanjian jual beli gula yang telah disepakatinya.
317
Akibat tindakan Yani Haryanto membatalkan perjanjian jual beli
yang telah disepakati, maka E.D. & F. Man Sugar Ltd. sebagai pihak
eksportir gula di London menuntut ganti kerugian. Sengketa ini di Inggris
ditangani oleh The English High Court London. Kemudian The English
Court of Appeal London yang memberi putusan bahwa sesuai dengan
kontrak yang disepakati, maka yang berwenang menyelesaikan sengketa ini
adalah Dewan Arbitrase Gula yang disebut The Council of the Refened
Sugar Association di London. Walaupun penyelesaian sengketa itu
diperintahkan untuk diajukan kepada Dewan Arbitrase Gula tersebut tetapi
tidak sempat diajukan.
Pada pihak lain Yani Haryanto (sebagai Penggugat) mengajukan
gugatan perdata kepada E.D. & F. Man Sugar Ltd., London (sebagai
Tergugat) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan
pelaksanaan perjanjian jual beli gula dimaksud. Dalil yang dikemukakan
Penggugat di dalam gugatan antara lain: Karena ada larangan dari
pemerintah mengenai import gula oleh perorangan, artinya perjanjian jual
beli gula tersebut mengandung causa/sebab yang dilarang oleh peraturan,
sehingga menjadi batal demi hukum.
Setelah melalui rangkaian pemeriksaan dan pembuktian, akhirnya
PN Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 499/Pdt/G/VI/1988/PN.JKT.PST.
memutuskan memenangkan Yani Haryanto selaku Penggugat dan
318
membatalkan dengan segala akibat hukumnya Contract for White Sugar No.
7458, tanggal 12 Februari 1982 dan Contract for White Sugar No. 7527,
tanggal 23 Maret 1982.
Dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Jakarta telah menjatuhkan
putusan dalam perkara antara E.D. & F. Man Sugar Ltd., London
(Pembanding semula Tergugat) melawan Yani Haryanto (Terbanding
semula Penggugat). Melalui putusan No. 486/Pdt/1989/PT.DKI, tanggal 14
Oktober 1989 Pengadilan Tinggi Jakarta menguatkan putusan PN Jakarta
Pusat tanggal 29 Juni 1989 No. 499/Pdt/G/1988/PN.Jkt.Pst. yang
dimohonkan banding tersebut.
Tidak puas terhadap kedua putusan pengadilan rendahan
sebelumnya, E.D. & F. Man Sugar Ltd., London (Pembanding semula
Tergugat) mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Pada
dasarnya Mahkamah Agung memberikan putusan No. 1205 K/Pdt/1990,
tanggal 4 Desember 1991 yang intinya menolak permohonan kasasi yang
diajukan oleh E.D. & F. Man Sugar Ltd., London.
Penolakan MA terhadap kasasi di atas barangkali tidak terlalu
istimewa. Yang menarik untuk dicermati adalah lima pertimbangan putusan
tersebut yang diakui sendiri oleh MA pertimbangan dalam perkara ini
walaupun berlebihan, antara lain sebagai berikut:
319
Mahkamah Agung mengaitkan masalah ini dengan Penetapan
Mahkamah Agung RI No. 1/Pen/Exr/Arb.Int/Pdt/1991,
tanggal 1 Maret 1991, yang meskipun dalam perkara ini tidak
disinggung, akan tetapi hal tersebut bertalian erat dengan perkara
tersebut;
Bahwa Penetapan tersebut di atas mengenai mengabulkan
permohonan exequatur terhadap putusan The Queens Council of
the English Bar di London, 17 November 1989;
Bahwa suatu Penetapan exequatur hanya bersifat prima facie,
jadi penetapan tersebut tidak merupakan penilaian hukum
terhadap isi dari perjanjian yang dibuat;
Bahwa suatu Penetapan exequatur ini hanya memberikan titel
eksekutorial bagi Putusan Arbitrase Asing tersebut, yang
pelaksanaannya tunduk kepada Hukum Acara di Indonesia;
Bahwa karena itu, dengan adanya Putusan Mahkamah Agung
dalam perkara ini, maka Penetapan Mahkamah Agung RI No.
1/Pen/Exr/Arb.Int/Pdt/1991 tanggal 1 Maret 1991, menjadi
irrelevant untuk dilaksanakan.
Lima pertimbangan putusan Mahkamah Agung tersebut di atas telah
menimbulkan berbagai komentar yang kontroversi pada berbagai kalangan
di masyarakat. Kontroversi terjadi terutama disebabkan oleh Penetapan
320
Mahkamah Agung RI No. 1/Pen/Exr/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret
1991, yang mengabulkan permohonan exequatur terhadap putusan The
Queens Council of the English Bar di London, 17 November 1989. Pada
awalnya penetapan itu disambut gembira oleh sejumlah kalangan sebagai
sebuah keputusan berani di bidang hukum perdata yang telah diambil oleh
Mahkamah Agung.
534
Komentar yang bernada optimis berdatangan
ditujukan kepada Mahkamah Agung (MA). Oleh karena dalam catatan
sejarah hukum perdata Indonesia, penetapan exequatur dari MA untuk
putusan arbitrase asing terhitung yang pertama kalinya. Setidaknya sejak
MA membuat peraturan tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing,
PERMA 1/1990, tanggal 1 Maret 1990. Menyusul Penetapan Mahkamah
Agung RI No. 1/Pen/Exr/Arb.Int/Pdt/1991, tanggal 1 Maret 1991 yang
mengabulkan permohonan exequatur, Wakil Ketua MA Purwoto S.
Gandasubrata
535
mengemukakan pendapat bahwa, Pelaksanaan putusan
arbitrase tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dalam hal ini
tata hukum dan kepentingan nasional Indonesia. Bagaimana pun hasilnya
nanti, putusan tersebut setidaknya menaikkan citra peradilan Indonesia di
534
Gengsi Baru Mahkamah Agung; dalam Tempo Nomor 2 Tahun XXII, 14 Maret
1992.
535
Tempo...Loc. Cit.,
321
mata internasional. Penetapan itu juga sekaligus menunjukkan keseriusan
Indonesia sebagai anggota Konvensi New York 1958.
Akan tetapi ternyata tonggak baru MA sekaligus gengsi baru
pengadilan Indonesia itu tidak berumur lama. Putusan kasasi dalam kasus
E.D. & F. Man Sugar Ltd., London melawan Yani Haryanto di atas telah
memupuskan harapan pihak asing untuk dapat memperoleh hak-hak yang
telah diperjuangkan berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan berkontrak. Oleh
sebab itu tak pelak lagi putusan di atas mengundang komentar beragam dan
umumnya bernada mengkritik. Umpamanya, Tempo
536
mengulas hal itu
dengan headline Mahkamah Agung Meralat Gengsi. Di dalam ulasan
Tempo itu bahkan Wakil Ketua BANI, HJR Abubakar
537
juga mengaku
tidak habis pikir atas putusan kasasi itu. Beliau mengatakan, kalau sudah
dikeluarkan penetapan, berarti MA sudah menilai keputusan arbitrase asing
itu bisa dilaksanakan karena tak bertentangan dengan tata hukum
Indonesia. Berbeda dengan komentar yang lain, Sudargo Gautama justru
berpendapat sebaliknya. Menurut Gautama keputusan itu sudah tepat,
sebab kedua kontrak itu memang sudah dibatalkan oleh pengadilan di sini.
Lagi pula proses persidangan arbitrase di London tidak memenuhi
536
Mahkamah Agung Meralat Gengsi; dalam Tempo Nomor 3 Tahun XXII, 21 Maret
1992.
537
Tempo,...Loc. Cit.,
322
persyaratan Konvensi New York 1958. Pihak Haryanto tidak pernah diberi
kesempatan untuk membela diri. Jadi, memang tidak ada yang dapat
dieksekusi.
Sebagai Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Ali Said berpendapat
bahwa penetapan exequatur itu menurut kuasa hukum Man mestinya tak
bisa dibanding apalagi kasasi tidak berbeda dengan keputusan sela saja.
Oleh karena itu, adanya keputusan kasasi dengan sendirinya penetapan
exequatur sebelumnya tidak dapat dilaksanakan.
538
Kontroversi mengenai
pelaksanaan putusan arbitrase asing itu bagaimana pun telah mencitrakan
betapa pilihan forum penyelesaian sengketa melalui arbitrase belum
berpihak pada penegakan keadilan. Apabila demikian faktanya, benar apa
yang dikatakan Rene David bahwa: It may happen hoewever that the loser
does not accept the award which has been rendered. He may contest the
validity of the award,... It is then necessary to go to a court; the losing
party may go to court to have the award set aside or reformed.
539
Padahal bagi pihak-pihak yang bersengketa tidak terkecuali pihak
asing, dapat dilaksanakannya putusan yang telah diperoleh, sama dengan
memperoleh jaminan kepastian hukum atas hak-hak yang dituntut. Ini
538
Tempo,...Loc. Cit.,
539
Rene David, Arbitration in International Trade. Kluwer Law Taxation Publisher,
1985, h. 361.
323
merupakan masalah esensial, oleh karena bagi siapa pun, memakai metode
penyelesaian sengketa apa pun, dan dimana pun sengketa itu diputus, tidak
ada artinya sama sekali apabila tidak ada ada jaminan kepastian hukum
untuk merealisasikan hak-hak yang diperoleh. Bukan kemenangan semu di
atas kertas yang dicari pihak-pihak yang bersengketa, melainkan diperoleh
kembali hak yang mereka perjuangkan.
3) Periode sesudah berlaku Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999
Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS
tentu saja berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1
Tahun 1990 tentang tatacara pelaksanaan putusan arbitrase asing. Akan
tetapi dalam beberapa hal substansi UU Arbitrase ternyata masih
mengukuhkan materi hukum yang berasal dari PERMA 1/1990. Ketentuan
tersebut di antaranya, Pasal 66 UU Abitrase substansinya sama persis
dengan Pasal 3 PERMA 1/1990. Kemudian Pasal 67 ayat (2) UU Arbitrase
juga sama dengan Pasal 5 ayat (4) PERMA 1/1990. Selebihnya tentu saja
UU Arbitrase mengatur lebih luas dan komprehensif, sehingga sangat
berbeda dengan PERMA 1/1990. Namun demikian perbedaan prinsipal di
antara keduanya tampak pada pengaturan tentang otoritas pemberi
eksekuatur. Menurut PERMA 1/1990 yang berwenang memberi eksekuatur
adalah Mahkamah Agung, sedangkan di dalam Undang-undang Arbitrase
324
adalah KPN Jakarta Pusat. Dikecualikan apabila Republik Indonesia
menjadi salah satu pihak dalam sengketa, maka eksekuatur tetap merupakan
kewenangan Mahkamah Agung. Pengecualian tersebut sama sekali tidak
diatur di dalam PERMA 1/1990.
Pertanyaan yang muncul adalah: Mengapa pembuat Undang-undang
Arbitrase memilih KPN Jakarta Pusat sebagai otoritas pemberi eksekuatur
menggantikan Mahkamah Agung? Tidak dijumpai jawaban otentik dari
risalah penyusunan Undang-undang mengenai hal itu. Akan tetapi menurut
keterangan dari para informan diperoleh informasi yang cukup relevan
dalam konteks alasan penunjukan tersebut.
Para informan mengemukakan bahwa hakim pada Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat diyakini sebagai figur yang sangat berpengalaman serta
memiliki kemampuan handal dalam menangani berbagai kasus yang
bernuansa transnasional termasuk dalam hal pelaksanaan putusan arbitrase
asing, bila dibandingkan dengan para hakim di pengadilan lain di
Indonesia.
540
Kondisi semacam itu antara lain disebabkan karakter wilayah
Jakarta Pusat yang unik sekaligus rumit. Sebagai bagian dari Ibu Kota
Negara RI, wilayah Jakarta Pusat memiliki kompleksitas permasalahan,
skala aktivitas masyarakat yang sangat bervariasi dan berakselerasi tinggi,
540
Informasi ini diperoleh dari sejumlah informan. Diantaranya kalangan praktisi hukum
termasuk mantan hakim dan yang lainnya dari kalangan akademisi yang juga sebagai
praktisi hukum) di Jakarta.
325
serta populasi yang multi etnik dengan segala dinamikanya. Alasan itu
menurut para informan diperkirakan merupakan salah satu pertimbangan,
sehingga pembuat Undang-undang Arbitrase memilih KPN Jakarta Pusat
sebagai otoritas pemberi eksekuatur untuk pengakuan dan pelaksanaan
putusan arbitrase asing.
Sesudah berlaku UU Arbitrase 30/1999, permohonan eksekuatur
putusan arbitrase asing ternyata masih menjumpai beberapa hambatan,
sehingga hasilnya belum banyak berbeda dengan keadaan sebelumnya.
Permohonan eksekuatur di dalam praktik masih tidak mudah untuk
dikabulkan. Akibatnya, secara umum pelaksanaan putusan arbitrase baik
putusan arbitrase nasional apalagi putusan arbitrase internasional masih
sangat jarang terjadi. Hasil penelitian yang diadakan di Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat pada bulan Januari 2002 berkenaan dengan putusan arbitrase
nasional yang didaftarkan untuk dilaksanakan, menunjukkan bahwa jumlah
putusan yang didaftarkan turun dari 19 putusan pada tahun 1999 menjadi
hanya enam putusan saja pada tahun 2001, walaupun perintah pelaksanaan
diberikan sembilan kali pada tahun 1999 dan tidak ada sama sekali pada
tahun 2000 dan 2001.
541
Untuk mengetahui betapa susahnya putusan
arbitrase asing memperoleh eksekuatur dari pengadilan, paparan berikut ini
merupakan salah satu contohnya.
541
Mulyana, Loc. Cit.,
326
Kasus antara Bankers Trust Company and Bankers Trust
International PLC (together BT) vs. PT Mayora Indah Tbk. (Mayora)
542
mengenaicurrency and interest rate swap transactions based on the
International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Master Agreement
tertanggal 25 April 1997. Sengketa tersebut diputus oleh arbitrator London
pada tahun 1999 berdasarkan the Rules of the London Court of International
Arbitration (LCIA) dan BT dimenangkan. Putusan tersebut menghukum
PT Mayora untuk membayar sejumlah uang kepada BT. Ketika permohonan
pelaksanaan putusan arbitrase London diajukan oleh pihak BT, Ketua
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak untuk melaksanakan putusan
tersebut. Alasan penolakan disebutkan karena BT dan PT Mayora dalam
sengketa yang sama sedang dalam proses pada Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan (Putusan No. 46/Pdt.G/1999 tanggal 9 Desember 1999 yang
memenangkan PT Mayora). Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengatakan
bahwa dalam praktik pengadilan, acara pelaksanaan dari putusan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap (dalam hal ini putusan arbitrase asing)
harus ditunda sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
dimaksud mempunyai kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, KPN Jakarta
Pusat menyatakan bahwa apabila putusan arbitrase yang dibuat di London
542
Ibid., h. 26.
327
dilaksanakan sementara masih menunggu putusan PN Jakarta Selatan, maka
hal itu dapat menghapuskan perjanjian pokok para pihak. Berdasarkan
fakta tersebut, putusan arbitrase internasional akan membingungkan dan
akan bertentangan dengan ketertiban umum.
Setelah PT Mayora dimenangkan, BT kemudian mengajukan kasasi
ke Mahkamah Agung mengenai penetapan KPN Jakarta Pusat. Penetapan
Mahkamah Agung No. 02K/Exr/Arb.Int/Pdt/2000 tanggal 5 September
2000 menguatkan Penetapan KPN Jakarta Pusat tersebut dan menolak untuk
melaksanakan putusan arbitrase asing yang dimohonkan oleh BT.
Mahkamah Agung menyatakan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase asing
harus ditunda sampai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebaliknya, hal itu akan bertentangan
dengan tertib hukum acara.
Kesimpulan dari Mahkamah Agung akan dianggap sebagai putusan
yang tepat apabila kedua kasus antara pihak-pihak yang sama berkenaan
dengan sengketa yang sama dan tunduk pada jurisdiksi pengadilan. Dalam
keadaan seperti itu, putusan pengadilan akan mempunyai kekuatan hukum
tetap dan harus ditunda sampai dengan putusan pengadilan dalam kasus
yang sedang diperiksa juga mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan
pada kasus di atas, para pihak membuat perjanjian arbitrase, sehingga
pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa sengketa tersebut
328
karena pengadilan tidak memiliki jurisdiksi. Namun demikian, di Indonesia,
beracara di depan pengadilan dengan maksud untuk membatalkan perjanjian
yang di dalamnya memuat klausula arbitrase sering digunakan sebagai taktik
untuk membatalkan proses arbitrase, dan membatalkan pembayaran ganti
kerugian atau kompensasi.
543
Berkaitan dengan hal di atas, penelitian yang dilakukan pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada bulan Januari 2002 mengenai jumlah
putusan arbitrase asing yang didaftarkan untuk dilaksanakan antara tahun
1999-2001 menunjukkan hasil seperti berikut: Pada tahun 1999 enam
permohonan pendaftaran putusan arbitrase asing telah diajukan dan tidak
satu pun eksekuatur diberikan. Kemudian pada tahun 2000 terdapat dua
permohonan pendaftaran yang diajukan hanya satu yang memperoleh
eksekuatur. Sedangkan pada tahun 2001 jumlah permohonan pendaftaran
bertambah menjadi empat meskipun hanya tiga eksekuatur yang
diberikan.
544
Seluruh rangkaian cerita dan fakta mengenai permohonan eksekuatur
untuk melaksanakan putusan arbitrase asing, memberi bukti bahwa ternyata
hukum arbitrase positif masih menyisakan celah-celah yang memungkinkan
543
Dikemukakan Mulyana, bahwa: ...The attitude of Indonesian courts to entertain such
lawsuits has been one of the major concerns of the international community in the
operation of the legal system in Indonesia. dalam Mulyana, Loc. Cit., h. 27.
544
Ibid., h. 27.
329
terjadinya konflik. Satu di antara penyebabnya antara lain karena undang-
undang arbitrase menganut standar ganda dalam memperlakukan putusan
arbitrase. Indikator tersebut dengan mudah dapat diketahui. Pertama,
terhadap putusan arbitrase nasional, di satu pihak diakui sebagai putusan
yang bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat
para pihak.
545
Akan tetapi, untuk melaksanakan putusan arbitrase nasional,
undang-undang menentukan sejumlah persyaratan dengan ancaman sanksi
bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan bila syarat yang ditentukan tidak
dipenuhi. Bahkan apabila para pihak tidak melaksanakan putusan secara
sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua
Pengadilan Negeri. Kedua, untuk putusan arbitrase internasional lebih
banyak lagi persyaratan yang ditentukan. Bahkan dari sejumlah syarat
tersebut mengesankan putusan arbitrase internasional sama sekali tidak
memiliki titel eksekutorial sebelum memperoleh eksekuatur dari KPN
Jakarta Pusat. Sedangkan idealnya suatu putusan yang bersifat final,
mempunyai kekuatan hukum tetap, serta mengikat para pihak, dalam
keadaan apa pun harus dapat dieksekusi sendiri tanpa melibatkan institusi
lain kecuali lembaga yang menjatuhkan putusan tersebut. Di samping itu,
hukum arbitrase terkesan diskriminatif terhadap putusan arbitrase
dibandingkan dengan putusan hakim. Oleh karena itu, sesungguhnya
545
Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999..
330
putusan arbitrase itu belum merupakan putusan final, karena tidak memiliki
titel eksekutorial, dan tidak mandiri, sehingga status putusan arbitrase sama
sekali tidak sejajar dengan putusan hakim.
Kedua persoalan di muka merupakan konsekuensi yang harus diterima
sebagai akibat undang-undang arbitrase menentukan keterlibatan pengadilan
negeri terhadap proses dan putusan arbitrase yang demikian luas. Suka atau
pun tidak, fakta di atas harus diterima karena keterlibatan pengadilan
nasional dalam masalah eksekusi putusan arbitrase pada banyak negara juga
merupakan keniscayaan. Seperti yang dikemukakan Christoph H.
Schreuer
546
bahwa: Perhaps the most important aspect of the supportive
role of domestic courts towards arbitration is the enforcement of awards.
...It is only at the last stage, when it comes to enforcement, that the
victorious litigant ultimately depends on the authority of domestic courts.
Walhasil, hampir tidak mungkin putusan arbitrase internasional dapat diakui
serta dieksekusi di Indonesia tanpa memperoleh dukungan kompetensi
pengadilan negeri.
Dihubungkan dengan teori tentang karakteristik produk hukum dari
Nonet, Undang-undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 dapat
dikategorikan ke dalam model hukum represif. Bukan tanpa alasan, karena
546
C. Christoph H. Schreuer, State Immunity: Some Recent Developments. Cambridge:
Grotius Publications Limited, 1988, h. 75.
331
baik kaidah hukum arbitrase maupun lembaga pengadilan sebagai
instrumen dalam pelaksanaan putusan arbitrase masih diarahkan pada
tujuan untuk menjamin ketertiban. Bukti tersebut secara eksplisit tampak
bahwa Putusan arbitrase internasional ...hanya dapat dilaksanakan di
Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan
ketertiban umum.
547
Kaidah hukum itu juga masih mencitrakan hukum
tunduk pada politik kekuasaan, tuntutan untuk patuh bersifat mutlak, dan
ketidak-patuhan dianggap sebagai suatu penyimpangan. Bukti lainnya:
Putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah
memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
548
Ketentuan tentang eksekuatur juga merupakan kaidah imperatif atau aturan
yang bersifat memaksa (dwingend recht) yang sama sekali tidak mungkin
disimpangi. Mengabaikan permohonan eksekuatur berarti putusan arbitrase
asing tidak mungkin dapat dieksekusi.
Dalam konstelasi serta konstruksi semacam itu secara bebas dapat
diungkapkan bahwa norma hukum arbitrase masih menjadi government
social control. Hukum perundang-undangan menjadi kekuatan kontrol di
tangan pemerintah yang terlegitimasi (secara formal-yuridis) yang tidak
merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral, dan wawasan kearifan yang
547
Pasal 66 huruf (c) UU No. 30/1999.
548
Pasal 66 huruf (d) UU No. 30/1999.
332
sebenarnya, sebagaimana yang sesungguhnya hidup di dalam kesadaran
hukum masyarakat awam.
549
Ketertiban merupakan tujuan hukum, sehingga
untuk mempertahankan ketertiban maka tuntutan-tuntutan dan pertimbangan-
pertimbangan lain di kesampingkan. Padahal di samping ketertiban, tujuan
lain dari hukum adalah tercapainya keadilan.
549
Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial...Op. Cit., h. 247.
333
BAB VI
PENUTUP
SIMPULAN DAN REKOMENDASI
A. Simpulan
Sebagai uraian penutup dari seluruh rangkaian pembahasan yang telah
dikemukakan pada bab-bab terdahulu, berikut ini akan diketengahkan simpulan
serta rekomendasi. Berdasarkan analisis serta interpretasi terhadap hasil studi
yang dilakukan mengenai pilihan forum arbitrase dalam sengketa komersial
dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Memilih forum di luar pengadilan negeri untuk menyelesaikan sengketa
komersial dalam bidang perdagangan pada dasarnya merupakan bagian
dari kebebasan para pihak dalam membuat kesepakatan mengenai
berbagai objek perjanjian. Kesepakatan memilih forum dapat dilakukan
melalui dua cara. (i) sebelum terjadi sengketa dan dicantumkan dalam
perjanjian pokok, dinamakan pactum de compromittendo; atau (ii)
sesudah terjadi sengketa, dibuat dalam bentuk tertulis terpisah dari
perjanjian pokok, disebut akta kompromis. Akan tetapi, menurut hukum
Indonesia, tidak setiap sengketa dapat diselesaikan melalui forum
arbitrase yang dipilih para pihak. Sengketa-sengketa di luar sengketa
perdagangan atau sengketa komersial bukan merupakan jurisdiksi forum
334
arbitrase. Hal itu yang membedakan dengan keadaan di negara maju
seperti Amerika Serikat. Di negara itu, berbagai macam sengketa dengan
latar belakang hukum yang berbeda-beda sekalipun pada prinsipnya
dapat diselesaikan melalui arbitrase. Walhasil, tidak hanya sengketa
bisnis atau komersial yang dapat dibawa ke forum arbitrase.
Untuk kalangan pengusaha yang tidak ingin sengketa mereka diketahui
banyak orang, memilih forum arbitrase diakui memberikan jaminan
kerahasiaan terhadap para pihak, baik selama proses pemeriksaan
berlangsung bahkan sampai dengan setelah putusan dijatuhkan. Lebih
dari itu, arbitrase diakui sebagai model penyelesaian sengketa yang
mengedepankan pencapaian keadilan dengan pendekatan konsensus dan
mendasarkan pada kepentingan para pihak dalam rangka mencapai win-
win solution. Akan tetapi di balik semua kelebihan arbitrase, ternyata
ada satu hal yang sangat tidak memuaskan para pihak dari seluruh
rangkaian proses arbitrase. Ketidak-puasan para pihak dalam proses
arbitrase terutama pada saat pelaksanaan (eksekusi) putusan.
Pelaksanaan putusan arbitrase, baik putusan arbitrase nasional apalagi
putusan arbitrase internasional, di Indonesia selalu menghadapi kesulitan
dan hambatan. Kesulitan serta hambatan untuk melaksanakan putusan
arbitrase disebabkan antara lain karena norma hukum yang ambivalen.
Di satu pihak, arbitrase diakui sebagai salah satu model penyelesaian
335
sengketa di luar pengadilan. Akan tetapi di lain pihak, badan peradilan
terkesan belum sepenuhnya memberikan kewenangan dalam
menyelesaikan sengketa komersial kepada forum arbitrase. Oleh karena
itu, peran pengadilan masih sangat dominan dalam keseluruhan proses
arbitrase. Sejak penentuan arbiter sampai dengan pelaksanaan putusan
arbitrase, jurisdiksi pengadilan sangat menentukan. Jurisdiksi pengadilan
semacam itu bahkan dipositifkan melalui aturan yang bersifat imperatif
(dwingend recht). Sebagai konsekuensi dari keadaan tersebut, putusan
arbitrase dianggap belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, tidak
mandiri, belum memiliki titel eksekutorial, dan belum merupakan
putusan final. Salah satunya tegas dinyatakan dalam penjelasan undang-
undang arbitrase bahwa putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan
eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi
(executoir) dari pengadilan.
2. Sejak beberapa dasawarsa yang lalu pengadilan negeri di Indonesia telah
dipercaya dan digunakan oleh masyarakat untuk menyelesaikan sengketa
dalam rangka mendapatkan keadilan (keadilan distributif). Pendekatan
yang digunakan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa bersifat
pertentangan (adversarial), berdasarkan aturan normatif, sangat formal,
rasional, serta birokratis, sehingga hasilnya berupa putusan yang
336
menggambarkan win-lose-solution. Meskipun demikian, sebagian besar
perkara yang terjadi di masyarakat tetap mengalir ke pengadilan untuk
diperiksa dan diputus dalam rangka memperoleh penyelesaian yang adil.
Hal itu disebabkan jumlah serta sebaran pengadilan yang hampir merata
di seluruh pelosok daerah di tanah air. Akan tetapi seiring perkembangan
masyarakat, lalu lintas perdagangan dan dunia usaha nasional maupun
internasional, serta perkembangan hukum itu sendiri, rasio jumlah
perkara yang harus diselesaikan oleh pengadilan semakin tidak
sebanding dengan kapasitas serta kemampuan pengadilan untuk
menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang masuk. Di samping
faktor eksternal semacam itu, ada juga faktor internal pengadilan yang
menyebabkan masyarakat menilai pengadilan serta sumberdaya
manusianya semakin tidak berpihak kepada tuntutan rasa keadilan
masyarakat. Para hakim di Indonesia selama beberapa dekade telah
menjadi bagian hegemoni pegawai negeri sipil yang dikondisikan untuk
mendukung kepentingan politik pihak yang berkuasa. Bahkan sampai
kini disinyalir hakim-hakim di Indonesia masih rentan terhadap upaya
penyuapan, sehingga putusan yang dikeluarkan pengadilan sulit
diramalkan, acapkali memihak penguasa atau orang kaya yang pada
akhirnya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Pengadilan
telah menjadi tempat mencari kemenangan hukum walaupun dengan
337
cara yang bertentangan dengan hukum. Pada gilirannya kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pengadilan semakin tipis, karena
penyelesaian sengketa di pengadilan telah menjauhkan pihak-pihak yang
bersengketa dari nilai-nilai keadilan. Kondisi pengadilan semacam itu
tentu saja sangat tidak menguntungkan, apalagi bagi kalangan pebisnis
yang perfectionist tentu tidak menghendaki aktivitasnya tersita untuk
mengurusi sengketa yang penyelesaiannya sulit diprediksi karena
prosesnya berlarut-larut tanpa kepastian waktu. Oleh karena itu, apabila
pengusaha menghadapi sengketa, tentu saja akan memilih cara-cara yang
lebih sederhana prosedurnya serta ditentukan secara limitatif waktu
penyelesaiannya. Model semacam itu antara lain adalah arbitrase,
meskipun pada waktu putusan arbitrase hendak dieksekusi harus
menghadapi birokrasi jurisdiksi pengadilan. Padahal memilih arbitrase
pada mulanya untuk menghindari mekanisme penyelesaian sengketa di
pengadilan yang memerlukan waktu bertahun-tahun.
3. Putusan arbitrase bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
mengikat para pihak sesungguhnya merupakan konsep normatif yang
harus diwujudkan (ius constituendum) dan sama sekali belum
merupakan norma yang nyatanya telah terwujud (ius constitutum).
Faktanya, putusan arbitrase, baik nasional maupun internasional dalam
338
aras praktik hukum di Indonesia senyatanya belum merupakan putusan
final, tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, dan tidak mandiri. Jadi,
walaupun secara normatif eksplisit ditentukan bahwa putusan arbitrase
tidak dapat dimohonkan upaya hukum banding dan kasasi, namun bukan
itu indikator penentunya. Idealnya, putusan arbitrase yang dikatakan
final dan mengikat itu sekaligus juga memiliki kekuatan eksekutorial,
sehingga putusan tersebut benar-benar mandiri dan tidak dikondisikan
dependen terhadap kewenangan pengadilan negeri. Selama putusan
arbitrase masih harus dideponir dan digantungkan kepada eksekuatur
pengadilan negeri ketika hendak dilaksanakan, maka selama itu pula
tidak layak putusan arbitrase disebut sebagai putusan yang final dan
mengikat apalagi mandiri. Pengertian itulah yang secara sadar telah
disesatkan oleh pembuat undang-undang arbitrase dengan maksud yang
tidak dijelaskan. Akibatnya, pihak-pihak yang pada mulanya memilih
forum arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan harapan akan
mendapatkan keadilan, akhirnya, malang tak boleh ditolak, mujur tak
boleh diraih, keadilan yang digapai pun kandas lagi di pengadilan. Nasib
putusan arbitrase internasional bahkan lebih tidak menentu. Tidak hanya
disebabkan syarat normatif yang ketat dan kaku dari norma hukum yang
masih berkarakter represif, tetapi juga diperparah lagi oleh sikap pihak
yang dikalahkan dalam putusan arbitrase internasional tersebut. Dalam
339
hal pihak termohon eksekusi itu warga negara Indonesia, sering
melakukan tindakan yang kurang terpuji. Dari kasus-kasus yang
dipaparkan pada pembahasan mengenai eksekusi putusan arbitrase di
muka, diketahui bahwa pihak warga negara Indonesia yang dikalahkan
dalam arbitrase internasional sering mengambil upaya lain. Di
antaranya, acara gugatan yang diajukan pihak yang dikalahkan dalam
putusan arbitrase internasional melalui pengadilan negeri untuk
membatalkan kontrak yang di dalamnya mencantumkan klausula
arbitrase, telah sering digunakan sebagai taktik untuk membatalkan
proses arbitrase dan menghindari kewajiban membayar ganti kerugian
atau kompensasi.
Berdasarkan tiga paparan simpulan di muka dapat diproyeksikan seperti
berikut ini: Forum arbitrase hanya mungkin menjadi salah satu forum
khusus yang mandiri di masa depan untuk menyelesaikan sengketa-
sengketa komersial di luar pengadilan, apabila ada kemauan politik dari
pemerintah dan pembuat undang-undang. Kemauan politik (political
will) dimaksud terutama berupa support atau dukungan terhadap
arbitrase dalam maknanya yang luas. Badan peradilan hendaknya tidak
hanya melakukan fungsi pengawasan, yang kaku dengan aturan formal
yang ketat. Dukungan lembaga peradilan hendaknya lebih diwujudkan
dalam bentuk penghormatan dari para hakim terhadap putusan arbitrase
340
sebagai putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, tanpa
harus diintegrasikan ke dalam alur lembaga peradilan untuk memperoleh
eksekuatur. Agar dengan demikian, forum arbitrase baik de jure maupun
de facto menjadi forum yang mandiri serta sejajar dengan pengadilan.
Dalam hal para pihak tidak secara sukarela melaksanakan putusan
arbitrase dimaksud, seyogianya kewenangan untuk mendesak pihak-
pihak agar mau melaksanakan putusan tersebut dikembalikan kepada
forum arbitrase yang memutus sengketanya. Demikian pula, untuk
putusan arbitrase internasional, kewenangan untuk memberikan perintah
pelaksanaan seyogianya dimiliki oleh lembaga arbitrase nasional, bukan
lagi oleh pengadilan negeri.
B. Rekomendasi
1. Arbitrase pada dasarnya memiliki perbedaan prinsipal dengan jenis
penyelesaian sengketa alternatif. Oleh karena model penyelesaian
sengketa alternatif seperti halnya negosiasi, mediasi, dan konsiliasi,
tergolong non-adjudicatory procedures, sedangkan arbitrase termasuk
dalam kelompok adjudicatory procedures. Pada dasarnya dalam
menyelesaikan sengketa, arbitrase menggunakan metode pertentangan
(adversarial), sehingga arbitrase diakui sebagai model ajudikasi semu.
Untuk membedakan arbitrase dengan model penyelesaian sengketa
341
alternatif, disarankan agar arbitrase tidak disebut sebagai metode
alternatif penyelesaian sengketa. Persoalannya, arbitrase sangat
berbeda dengan metode penyelesaian sengketa alternatif. Negosiasi,
mediasi, dan konsiliasi sebagai metode penyelesaian sengketa
alternatif tidak dapat menghasilkan putusan, sedangkan arbitrase
sebagai ajudikasi semu di akhir pemeriksaan sengketa menghasilkan
suatu putusan (award). Alasan lain yang membedakan adalah,
arbitrase dapat berlangsung secara ad hoc dan dapat pula terlembaga
(institusional), sedangkan metode penyelesaian sengketa alternatif
tidak dapat diformat menjadi terlembaga.
2. Apabila arbitrase hendak dikembangkan sebagai salah satu forum
khusus yang mandiri dan berwibawa dalam menyelesaikan sengketa-
sengketa komersial di luar pengadilan, disarankan agar keberadaan
atau eksistensi forum arbitrase, baik ad hoc maupun institusional perlu
dilakukan upaya sosialisasi secara intensif. Tanpa upaya semacam
itu sulit diharapkan forum arbitrase dapat dikenal secara luas dalam
waktu yang relatif cepat. Hal itu disebabkan keberadaan arbitrase tidak
menyebar secara meluas seperti halnya badan peradilan negara. Oleh
karena itu, dukungan dari para hakim pengadilan rendahan di seluruh
wilayah Indonesia merupakan conditio sine qua non dalam
342
mensosialisasikan forum arbitrase ini. Hendaknya para hakim dibekali
pemahaman yang cukup memadai tentang arbitrase, sehingga tidak ada
lagi kesan dari para hakim bahwa forum arbitrase merupakan
kompetitor bagi pengadilan negeri yang dianggap mengambil lahan
dalam penyelesaian sengketa. Sebaliknya, para hakim pengadilan
rendahan semestinya membantu para pencari keadilan dengan jalan
memberi advis untuk memilih forum arbitrase dalam upaya
mendistribusikan penyelesaian sengketa. Upaya demikian diharapkan
dapat membawa manfaat, sehingga pada tingkat kasasi diharapkan
tidak terjadi kongesti atau timbunan perkara yang harus diselesaikan
oleh Mahkamah Agung.
3. Di sadari maupun tidak oleh pembuatnya, Undang-undang Arbitrase
Nomor 30 Tahun 1999 secara nyata di dalamnya terdapat ambivalensi
norma. Untuk mengakhiri kondisi semacam itu tidak ada cara lain
kecuali terhadap undang-undang tersebut harus dilakukan koreksi
dalam bentuk perubahan atau diamandemen. Tanpa melakukan hal itu,
sulit kiranya untuk mengupayakan kedudukan forum arbitrase
sebagaimana yang diharapkan yakni: mandiri serta kompeten untuk
mendesak para pihak dalam memaksakan pelaksanaan putusan.
343
4. Di samping upaya koreksi terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun
1999 dalam bentuk amandemen, perlu pula diatur secara tegas
mengenai standar efektivitas penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
Oleh karena walalaupun sebenarnya undang-undang tersebut telah
secara eksplisit mengatur jangka waktu pemeriksaan sengketa harus
diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari
sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk; [Pasal 48 ayat (1)]. Akan
tetapi faktanya putusan yang telah diperoleh tidak mudah untuk
dieksekusi.
5. Hendakanya pada masa-masa yang akan datang, substansi undang-
undang tidak lagi memuat rumusan pasal yang tidak konsisten
(istiqomah) seperti yang terjadi di dalam undang-undang arbitrase di
atas. Tidak konsisten karena, di satu pihak putusan arbitrase dikatakan
sebagai bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan
mengikat para pihak. Akan tetapi di lain pihak, putusan arbitrase tidak
dapat dilaksanakan jika kewajiban mendaftarkan dan menyerahkan
putusan ke pengadilan negeri tidak dipenuhi.
344
DAFTAR PUSTAKA
ABDUH, Muhammad, Serangkaian Pembahasan bagi Pembaharuan
Hukum Ekonomi di Indonesia. Temu Karya Hukum
Perusahaan dan Arbitrase; Kantor Menko Ekuin dan Wasbang
bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta:
22-23 Januari 1991.
ABDURRASYID, Priyatna, 99,9 % Hakim Tidak Mengerti Arbitrase.
dalam Wawancara Hukumonline_com.htm, Jumat, 10 Januari
2003.
____________, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya
terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa; dalam
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 21, Oktober-November 2002.
____________, Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketasuatu
pengantar. Jakarta: Fikahati Aneska-BANI, 2002.
ADOLF, Huala, Pembatalan Putusan Arbitrase Asing; dalam Kompas,
Jumat, 29 Mei 1992.
____________, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional.
Jakarta: Rajawali Pres, 1991.
ALGRA, N.E., et al., Fockema Andreaes Rechtsgeleerd
Handwoordenboek. Bandung: Binacipta, 1983.
ALI, Achmad, Pengadilan yang yang tak Berkeadilan; dalam Kompas,
Jumat, 08 Juni 2001.
____________, Bercermin pada Penegakan Hukum Jepang; Kompas,
15 April 2002.
ALWASILAH, A. Chaedar, Pokoknya Kualitatif; Dasar-Dasar
Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT
Pustaka Jaya, 2003.
ARIKUNTO, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
ATMADJA, Asikin Kusumah, Konvensi/Ratifikasi dan Eksekusi Putusan
Arbitrase; Makalah Seminar Sehari. Kerjasama antara ALTRI-
KADIN-BANI, Jakarta, 16 Nopember 1988.
AUERBACH, Jerold S., Justice Without Law? New York: Oxford
University Press, 1983.
AZWAR, Saifuddin, Sikap Manusia - Teori dan Pengukurannya. (edisi
kedua), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
BARAK, Aharon, Judicial Discretion. New York: Yale University Press,
1989.
345
BASROWI & Sukidin, Metode Penelitian Kualitatif Perspektif
Mikro. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
BECKMANN, Keebet von Benda, Goyahnya Tangga Menuju Mufakat.
Jakarta: Grasindo, 2000.
___________-F. von Benda, Dari Hukum manusia Primitif sampai ke
Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-masyarakat Kompleks;
dalam T.O. Ihromi (ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga
Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
BERNINI, Giorgio & Albert Jan Van den Berg, The enforcement of
arbitral awards against a state: the problem of immunity from
execution; dalam Julian DM Lew (ed), Contemporary Problems
in International Arbitration. Dordrecht: Martinus Nijhoff
Publishers, 1987.
BERG, A. J. van den et al., Arbitrage Recht. W.E.J. Tjeenk Willink -
Zwolle, 1988.
____________, "The New York Arbitration Convention of 1958
Towards a Uniform Judicial Interpretation. The Hague: TMC
Asser Institute, 1981.
BHAKTI, Yudha, Pengertian Jus Cogen dalam Konvensi Wina 1969
tentang Hukum Perjanjian; Padjadjaran, Kuartal I No. 1,
Januari-Maret 1981.
BLACK, Henry Campbell, Blacks Law Dictionary: Definitions of the
Terms and Phrases of American and English Jurisprudence
Ancient and Modern. (Sixth Edition). St. Paul Minn: West
Publishing Co., 1990.
BLAU, Peter M. & Marshall W. Meyer, Birokrasi dalam Masyarakat
Modern. Jakarta: UI Press, 1987.
BOCKSTIEGEL, Karl-Heinz, States in international arbitral process;
dalam Julian DM Lew (ed), Contemporary Problems in
International Arbitration. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers,
1987.
_____________, Arbitration and State Enterprises; Survey on the
National and International State of Law and Practice. Dordrecht:
Kluwer Publishers, 1989.
BRUGGINK, J.J.H., Refleksi Tentang Hukum; terjemahan Arief
Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
CAFFREY, Bradford A., Enforcement of Foreign Judgments.
Sydney:CCH Australia Limited, 1985.
CAMPBELL, Tom, Tujuh Teori Sosial, Sketsa, Penilaian,
Perbandingan. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
346
CHAMBLISS, William J. & Robert B. Seidman, Law, Order and Power.
Reading, Massachusetts: Addison-Westley, 1971.
COHN, E., M. Domke, F. Eisemann (eds.), Handbook of Institutional
Arbitration in international trade; Preface, dalam Sudargo
Gautama, Arbitrase Dagang Internasional. Bandung: Alumni,
1986.
COULSON, Robert, Business Arbitration What You Need to Know.
(revised third edition), New York: American Arbitration
Association, 1987.
CRAIB, Ian, Modern Social Theory: from Parson to Habermas (Teori-
Teori Sosial Modern: dari Parson sampai Habermas);
Penerjemah: Paul S. Baut dan T. Effendi. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1994.
DAHRENDORF, Ralf, Class and Class Conflict in Industrial Society.
London: Routledge & Kegan Paul, 1959.
DANIM, Sudarwan, Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka
Setia, 2002.
DAVID, Rene, Arbitration in International Trade. Deventer: Kluwer
Law Publishers, 1985.
DAWSON, John P., Peranan Hakim di Amerika Serikat; dalam Harold
J. Berman, Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika
Serikat. Terjemahan Gregory Churchill. Jakarta: PT Tatanusa,
1996.
DERSCHOWITZ, Alan M., Reasonable Doubts. New York: Simon &
Schuster, 1996, h. 42. Marc Galanter ,Why The Haves Come
Out Ahead: Speculations on The Limits of Legal Change; Law
and Society, Fall 1974.
DJIWANDONO, Sudradjat, Sambutan Menteri Muda Perdagangan RI
pada Simposium Nasional tentang Aspek-aspek Kerjasama
Ekonomi antara negara-negara ASEAN dalam rangka AFTA.
Bandung, 1 Februari 1993.
DOBSON, Paul, and Clive M. Schmitthoff, Charlesworths Business
Law. London: Sweet & Maxwell, 1991.
DORMAN, Peter J.(eds), Running Press Dictionary of Law. Philadelphia:
Running Press, 1976.
DWORKIN, Ronald, The Original Position; dalam Reading Rawls,
Critical Studies on Rawls A Theory of Justice; Norman Daniels
(Ed.), Oxford: Basil Blackwell, 1975, dalam Andre Ata Ujan,
Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls.
Yogyakarta: Kanisius, 2001.
347
ENGELBRECHT, W.A.,et. al., De Wetboeken Wetten en Verordeningen
Benevens de Voorlopige Grondwet van de Republiek Indonesie.
Leiden: A.W. Sijthoff Uitgeversmij N.V., 1956.
FAISAL, Sanapiah, Format-Format Penelitian Sosial. Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 1999.
FOLTER, MOJ de, et al., Burgerlijke Rechtsvordering en aanverwante
Regelingen. Kluwer-Deventer, 1990.
FRIEDMAN, Lawrence M., On Legal Development. Rutgers Law
Review, (alih bahasa: Rachmadi Djoko Soemadio), 1969.
____________, American Law an Introduction; Hukum Amerika
sebuah Pengantar, (alih bahasa: Wishnu Basuki). Jakarta:
Tatanusa, 2001.
____________, The Legal System. New York: Russel Sage Foundation,
1975.
FULLER, Lon L., Sistem Perlawanan; dalam Harold J. Berman,
Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika Serikat. Jakarta:
PT Tatanusa, 1996.
GALANTER, Marc,Why The Haves Come Out Ahead: Speculations
on The Limits of Legal Change; Law and Society, Fall 1974.
____________, Hukum Hindu dan Perkembangan Sistem Hukum India
Modern; dalam AAG Peters & Koesriani Siswosoebroto (eds),
Hukum dan Perkembangan Sosial Buku II. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1988.
____________, Justice in Many Rooms; dalam Maurio Cappelletti (ed),
Access to Justice and The Welfare State. Italy: European
University Institute, 1981.
____________, Keadilan di Berbagai Ruangan: Lembaga Peradilan,
Penataan Masyarakat serta Hukum Rakyat: dalam T.O. Ihromi
(ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1993.
GAUTAMA, Sudargo, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional.
Bandung: Alumni, 1985.
____________, Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku
keempat). Bandung: Alumni, 1989.
____________, Hukum Perdata Internasional Indonesia (Buku
kedelapan). Bandung: Alumni, 1987.
____________, Arbitrase Dagang Internasional. Bandung: Alumni,
1986.
____________, Hukum Perdata Internasional Hukum yang Hidup.
Bandung: Alumni, 1983.
348
____________, Indonesia dan Arbitrase Internasional. Bandung:
Alumni, 1986.
____________, Hukum Antar Tata Hukum. Bandung: Alumni, 1977.
____________, Masalah-Masalah Baru Hukum Perdata Internasional.
Bandung:Alumni, 1984.
____________, Arbitrase Bank Dunia tentang Penanaman Modal
Asing di Indonesia dan Jurisprudensi Indonesia dalam Perkara
Hukum Perdata. Bandung: Alumni, 1994.
GOODPASTER, Gary, Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa
dalam Felix O. Soebagijo & Erman Rajagukguk (eds), Arbitrase
di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
GRAY, Christine D., Judicial Remedies in International Law. New
York, Oxford University Press, 1987.
HADIKUSUMA, Hilman, Antropologi Hukum Indonesia. Bandung:
Alumni, 1986.
HAGUL, Peter, Reliabilitas dan Validitas; dalam Masri Singarimbun
& Sofian Effendi, Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES,
1982.
HARAHAP, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang
Perdata. Jakarta: Gramedia, 1988.
____________, Citra Penegakan Hukum; dalam Varia Peradilan
Tahun X Nomor 117, Juni 1995.
____________, Pengadilan Tak Efektif Selesaikan Perkara; dalam
Kompas, 16 Juli 1999.
____________, Beberapa Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian atas
UU No. 30 Tahun 1999; Jurnal Hukum Bisnis Vol. 21, Oktober-
November 2002.
____________, Dua Sisi Putusan Hakim Tidak Adil Bagi Yang Kalah
dan Adil Bagi Yang Menang; dalam Varia Peradilan, Tahun VIII,
Nomor 95, Agustus 1993.
____________, Mencari Sistem Alternatif Penyelesaian Perkara; dalam
Varia Peradilan Tahun XI No. 121, Oktober 1995.
____________, Arbitrase Ditinjau dari: Rv, BANI Rules, ICSID,
UNCITRAL Arb. Rules, NY Convention, PERMA 1 Th. 1990.
Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
____________, Tempat Arbitrase Islam dalam Hukum Nasional; dalam
Abdul Rahman Saleh et al., Arbitrase Islam Di Indonesia.
Jakarta: BAMUI & Bank Muamalat, 1994.
HARMAN, Benny K., Konfigurasi Politik & Kekuasaan Kehakiman di
Indonesia. Jakarta: Elsam, 1997.
349
HART, H.L.A., The Concept of Law. London: Oxford University Press,
1972.
HARTONO, Sunarjati, "Legal Aspect of Indonesian Trade with other
Countries in the Asian-Pacific"; dalam Padjadjaran, Special
English Edition, 1984.
_________________, Serba-Serbi tentang Arbitrase Dagang
Internasional; dalam Serangkaian Pembahasan bagi
Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia. Temu Karya
Hukum Perusahaan dan Arbitrase; Kantor Menko Ekuin dan
Wasbang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum,
Jakarta: 22-23 Januari 1991.
_________________, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad
Ke 20. Bandung: Alumni, 1994.
HATTA, Sri Gambir Melati, Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak
Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahakamah
Agung Indonesia. Bandung: Alumni, 1999.
HENDERSON, Dan Fenno, Modernisasi Hukum dan Politik di Jepang;
dalam AAG Peters & Koesriani Siswosoebroto (eds), Hukum dan
Perkembangan Sosial Buku. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1988.
HENDRICKS, William, How to Manage Conflict; Bagaimana
Mengelola Konflik (Penerjemah: Arif Santoso). Jakarta: Bumi
Aksara, 2001.
HIMAWAN, Charles, Ekonomi dan Hukum Rintangan Potensial;
dalam Kompas, 10-08-2001.
HUIJBERS, Theo OSC, Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah.
Yogyakarta: Kanisius, 1984.
HUGENHOLTZ/Heemskerk, Hoofdlijnen van Nederlands Burgerlijk
Procesrecht - (Vijftiende druk). s-Gravenhage: VUGA Uitgeverij
B.V., 1988.
HUNT, Alan, Kritisi Hukum: Apa yang Kritis dalam Studi Hukum
Kritis? dalam Wacana Edisi 6 Tahun II 2000.
HUNTER, J. Martin H., Judicial Assistance for the arbitrator; dalam
Julian DM Lew (ed), Contemporary Problems in International
Arbitration. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
IHROMI, T.O., Beberapa Catatan Mengenai Metode Kasus Sengketa
yang Digunakan dalam Antropologi Hukum; dalam T.O. Ihromi
(ed), Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai. Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1993.
350
INDARTI, Erlyn, Diskresi Polisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, 2000.
____________, Paradigma: Jati Diri Cendekia; Makalah Diskusi
Ilmiah Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas
Diponegoro. Semarang, 1 Desember 2000.
IRIANTO, Heru & Burhan Bungin, Pokok-Pokok Penting tentang
Wawancara; dalam Burhan Bungin, Metode Penelitian
Kualitatif- Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian
Kontemporer. Jakarta: Rajawali, 2001.
JATIM, Fatmah, Tinjauan Terhadap Arbitrase Dagang Secara Umum
dan Arbitrase Dagang di Indonesia; dalam Felix O. Soebagjo &
Erman Rajagukguk (eds), Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1995.
KANTAATMADJA, Komar, Beberapa Permasalahan Arbitrase
Internasional; Makalah Seminar Arbitrase 16 November 1988.
KASIM., Ifdhal, Mempertimbangkan Critical Legal Studies dalam
Kajian Hukum di Indonesia; Jurnal Ilmu Sosial Transformatif
WACANA, Edisi 6 Tahun II 2000.
KAWASHIMA, Takeyoshi, Penyelesaian Pertikaian di Jepang
Kontemporer; dalam AAG Peters & Koesriani Siswosoebroto,
Hukum dan Perkembangan Sosial - Buku II. Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1988.
KERAF, A. Sonny, Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah.
Yogyakarta: Kanisius, 1996.
________________, Hukum Kodrat dan Teori Hak Milik. Yogyakarta:
Kanisius, 1997.
KERR, The Hon. Mr. Justice, International Arb. v. Litigation; The
Journal of Business Law. 1980.
KOLLEWIJN, R.D., Het beginsel der openbare orde in het international
privaatrecht. Dissertasi, Leiden, 1917; dalam Sudargo Gautama,
Hukum Perdata Internasional-Buku ke 4. Bandung: Alumni,
1989.
KOENTJARANINGRAT, Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
KRIEKHOFF, Valerine J.L., Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi
Hukum); dalam T.O. Ihromi (ed), Antropologi Hukum Sebuah
Bunga Rampai. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
KUHN, Thomas, The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: The
University of Chicago Press, 1970.
KUSNADI et al., Teori dan Manajemen Konflik (Tradisional,
Kontemporer & Islam). Malang: Taroda, 2001.
351
KUSUMAATMADJA, Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum
dalam Pembangunan Nasional; dalam PADJADJARAN
(Majalah Ilmu Hukum & Pengetahuan Masyarakat), Jilid III,
Nomor 1, September 1970.
____________, Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta,
1978.
KUSUMOHAMIDJOJO, Budiono, Suatu studi terhadap aspek
operasional Konvensi Wina tahun 1969 tentang Hukum
Perjanjian Internasional. Bandung: Binacipta, 1986.
LEV, Daniel S., Hukum dan Politik di Indonesia Kesinambungan dan
Perubahan. Jakarta: LP3ES, 1990.
____________, Lembaga Peradilan dan Budaya Hukum di Indonesia;
dalam A.A.G.Peters & Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan
Perkembangan Sosial - Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1988.
LEW, Julian D.M., Applicable Law in International Commercial
Arbitration. Oceana Publication Inc., 1978.
____________, Contemporary Problems in International Arbitration.
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
LIEMENA, Frans, Klausula Arbitrase dihubungkan dengan Kompetensi
Pengadilan Negeri; dalam Varia Peradilan, Tahun III Nomor
29, Februari 1988.
LOMBARD, Denys, Nusa Jawa: Silang Budaya, jilid 1, 2, dan 3.
Jakarta: Gramedia, 1996.
LOTULUNG, Paulus Effendie, Kemandirian dan Independensi
Peradilan; Makalah Seminar Nasional Reformasi Sistem
Peradilan dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia.
Semarang: FH UNDIP, 6 Maret 1999.
LUBIS, T. Mulya, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka Mitos atau
Realitas; dalam Kompas, 16 Oktober 1989.
MANAN, Bagir, Reformasi Mahkamah Agung; dalam Kompas, 14
Nopember 1999.
MANDAN, Ali, Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri.
Jakarta: CV Rajawali, 1986.
MARIOT, Arthur, The Role of ADR in the Settlement of Commercial
Disputes; dalam Asia Pacific Law Review, Vol. 1 Summer 1994.
MEREDITH, Richard Jackson, The Machinery of Justice in England;
dalam Setiawan, Putusan Hakim Sebagai Transformasi Ide
Keadilan; Varia Peradilan Tahun VII No. 80, Mei 1992
MERILLLS, J.G., International Dispute Settlement. London: Sweet &
Maxwell, 1994.
352
MERRYMAN, John Henry, The Civil Law Tradition. Stanford University
Press, Stanford, California, 1969.
MERTOKUSUMO, Sudikno, Sistem Peradilan di Indonesia; JURNAL
HUKUM, No. 9, Vo. 4, 1997.
____________, Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty,
1993.
____________, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di
Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita
Bangsa Indonesia. Bandung: Kilatmadju, 1971.
____________, Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty, 1986.
MIALL, Hugh, Oliver Ramsbotham, Tom Woodhouse, Resolusi Damai
Konflik Kontemporer. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
MILES, Matthew B. & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif;
(Penerjemah: Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI Press, 1992.
MOLEONG, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja
Karya, 1989.
MUHADJIR, Noeng, Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta:
Rake Sarasin, 2000.
MUHAIMIN, Yahya, Beberapa Aspek Pembangunan Orde Baru
(1990:23); dalam Akhmad Setiawan, Perilaku Birokrasi dalam
Pengaruh Paham Kekuasaan Jawa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
1998.
MUKHTAR, Sofyan, Mekanisme Alternatif Bagi Penyelesaian Sengketa
Perdata-Dagang (Dispute Resolution); dalam Varia Peradilan
No. 48, 1989.
MULADI, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana.
Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
MULYANA, et al., Indonesias New Framework For International
Arbitration: A Critical Assessment of the Law and Its Application
by the Court; Mealeys International Arbitration Report.
January, 2002.
MUSADDAD, Hj. Ummu Salamah, Perspektif Etika Spiritual dan Moral
dalam Interaksi Sosial Kemanusiaan di Era Globalisasi; dalam
Orasi Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FISIP-Unpas, Bandung, 5
April 2003.
MUTHAHHARI, Mutadha, Keadilan Ilahi Asas Pandangan Dunia
Islam. Bandung: Mizan, 1992.
NANTWI, E.K., The Enforcement of Inernational Judicial Decision
and Arbitral Awards in Public International Law, Leiden: A.W.
Sijthoff, 1966.
353
NASUTION, S., Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung:
Tarsito, 1996.
NASIKUN, Sistem Sosial Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2000.
NELSON, Steven C., Alternatives to Litigation of International Disputes,
The International Lawyer, Vol. 23, No. 1, 1989.
NONET, Philippe & Philip Selznick, Law and Society in Transition:
Toward Responsive Law. New York: Harper & Row, 1978.
NUSSBAUM, Arthur, (Penyadur: Sam Suhaedi), Sejarah Hukum
Internasional. TT.
OHORELLA, HMG. & H.Aminuddin Salle, Penyelesaian Sengketa
Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan Sulawesi
Selatan; dalam Felix O. Soebagjo & Erman Rajagukguk (eds),
Arbitrase di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
OTT, David H., Peaceful Settlement of Disputes; dalam Public
International Law in the Modern World. London: The Bath Press,
1987.
PAKPAHAN, Normin S., Pembaharuan Hukum di Bidang Kegiatan
Ekonomi. Makalah pada Temu Karya Hukum Perseroan dan
Arbitrase; Jakarta, 22-23 Januari 1991.
PANGGABEAN, HP, Kelambanan Proses Peradilan Dikeluhkan.
dalam Kompas, Jumat, 23 April 1999.
PETERS, A.A.G & Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan Kebudayaan;
dalam A.A.G Peters & Koesriani Siswosoebroto, Hukum dan
Perkembangan Sosial - Buku II. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,
1988.
PRATIDINA, Ginung, Manajemen Konflik dalam Menigkatkan
Efektivitas Organisasi; dalam Wawasan Tridharma Nomor 10
Tahun XV Mei 2003.
PUTRA, Anom Surya, Manifesto Hukum Kritis Teori Hukum Kritis,
Dogmatika dan Praktik Hukum; dalam Wacana Edisi 6
Tahun II 2000.
RAHARDJO, Satjipto, Supremasi Hukum yang Benar; Kompas, 6 Juni
2002.
____________, Dengan Determinasi; dalam Kompas, 17 Oktober
1998.
____________, Hukum dan Masyarakat., Bandung: Angkasa, 1981.
____________, Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, 1986.
____________, Hukum, Masyarakat, dan Pembangunan. Bandung:
Alumni, 1980.
354
____________, Membangun Keadilan Alternatif; Kompas, Rabu, 5
April 1995.
____________, Mengubah Perilaku dan Kultur Polisi; dalam Kompas,
1 Juli 2002.
____________, Menjalankan Hukum dengan Kecerdasan Spiritual;
dalam Kompas, Senin, 30 Desember 2002.
____________, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks
Situasi Global; dalam Problema Globalisasi Perspektif
Sosiologi Hukum, Ekonomi, & Agama. Surakarta:
Muhammadiyah University Press, 2000.
____________, Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks
Situasi Global; dalam Perspektif, Vol. 2 No. 2, Juli 1997.
____________, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami
Proses-proses Sosial dalam Konteks Pembangunan dan
Globalisasi; Makalah Seminar Nasional Sosiologi Hukum dan
Pembentukan Asosiasi Sosiologi Hukum Indonesia. Semarang, 12-
13 Nopember 1996.
____________, Peningkatan Wibawa Hukum Melalui Pembinaan
Budaya Hukum; Makalah pada Lokakarya Pembangunan
Bidang Hukum Repelita VII. Jakarta BPHN, Juli 1997.
____________, Pengadilan dan Publiknya; Forum Keadilan No. 11,
15 September 1994.
____________, Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi;
dalam Makalah Seminar Nasional Menggugat Pemikiran
Hukum Positivistik di Era Reformasi, PDIH-Undip-Angkatan V,
Semarang, Sabtu, 22 Juli 2000.
____________, Supremasi Hukum dalam Negara Demokrasi dari Kajian
Sosio Kultural; dalam Makalah Seminar Nasional Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Kamis, 27 Juli 2000.
____________, Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang; Kompas,
Rabu, 24 Mei 2000.
____________, Tidak Menjadi Tawanan Undang-undang; Kompas,
Kamis, 25 Mei 2000.
____________, Beberapa Pemikiran tentang Ancangan Antar Disiplin
dalam Pembinaan Hukum Nasional. Bandung: Sinar Baru,
1985.
____________, Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis.
Bandung: Sinar Baru, TT.
____________, Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan
Masalah. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002.
355
____________,Indonesia Butuh Keadilan yang Progresif; dalam
Kompas, Sabtu, 12 Oktober 2002.
____________,Rekonstruksi Strategi Pembangunan Hukum Menuju
Pembangunan Pengadilan yang Independen dan Berwibawa;
Makalah Seminar pada Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta,
28 Maret 2000.
____________, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia dalam Perspektif
Sejarah; Makalah dalam Simposium Paradigma dalam Ilmu
Hukum Indonesia. PDIH Undip, Semarang, 10 Februari 1998.
RAJAGUKGUK, Erman, Keputusan Pengadilan Mengenai Beberapa
Masalah Arbitrase; dalam Abdul Rahman Saleh et al., Arbitrase
Islam Di Indonesia. Jakarta: BAMUI & Bank Muamalat, 1994.
____________, Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Perdata di
Luar Pengadilan dalam Jurnal Magister Hukum, Vol. 2 No. 4,
Okt. 2000.
____________, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan. Jakarta: Chandra
Pratama, 2001.
RAWLS, John, A Theory of Justice. Cambridge, Massachusetts: Harvard
University Press, 1971.
____________, Justice as Fairness A Restatement; (Edited by Erin
Kelly).Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2001.
REDFERN, Alan & Martin Hunter, Law and Practice of International
Commercial Arbitration. London: Sweet & Maxwell, 1991.
REKSODIPUTRO, Mardjono, Pembaharuan Hukum Sebaiknya dari
Pembenahan Peradilan; dalam Kompas, 1 Mei 1999.
RITZER, George, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda.
Penyadur: Alimandan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
RIVAI, Veithzal, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2003.
ROBBINS, Stephen, Managing Organizational Conflict: A Non-
Traditional Approach. Prentice Hall, Englewood Cliffs, N.J.,
1974.
SALEH, Ismail, Sambutan Menteri Kehakiman RI pada Acara Temu
Karya Hukum Perusahaan dan Arbitrase; Jakarta: 22 Januari
1991.
SALEH, Roeslan, Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan. Jakarta:
Aksara Baru, 1979.
SALEH, Samir, The Recognition and Enforcement of foreign arbitral
awards in the states of the Arab Middle East; dalam Julian DM
Lew (ed), Contemporary Problems in International Arbitration.
Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1987.
356
SALIM, Agus, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin
Guba dan Penerapannya). Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
SANTOSA, Mas Achmad, Independensi Peradilan dan TAP MPR RI No.
X/MPR/1998; Kompas, 11 Januari 1999.
_______________, Court Connected ADR in Indonesia, Urgensi dan
Prasyarat Pengembangannya; Makalah Seminar Nasional Court
Connected-ADR. Jakarta: Departemen Kehakiman, 21 April 1999.
SANTOSO, Topo, Menggagas Hukum Pidana Islam Penerapan
Syariat Islam dalam Konteks Modernitas. Bandung: Asy
Syaamil, 2001.
SCHREUER, C. Christoph H., State Immunity: Some Recent
Development. Cambridge: Grotius Publication, 1988.
SCHMITTHOFF, Clive M., Finality of arbitral awards and judicial
review; dalam Julian DM Lew (ed), Contemporary Problems in
International Arbitration. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers,
1987.
SETIAWAN, Klausula Arbitrase dalam Teori dan Praktek; dalam
Varia Peradilan Tahun IX No. 104, Mei 1994.
____________, Kontrak Bisnis Internasional Choice of Law & Choice of
Jurisdiction; dalam Varia Peradilan, Tahun IX No. 107, Agustus
1994.
____________, Publikasi Putusan Hakim; dalam Varia Peradilan
Tahun VIII Nomor 95, Agustus 1993.
____________, Putusan Hakim Sebagai Transformasi Ide Keadilan;
dalam Varia Peradilan Tahun VII No. 80, Mei 1992.
____________, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata.
Bandung: Alumni, 1992.
____________, Arbitrase Internasional Dalam Yurisprudensi Indonesia
Suatu Kajian Prospektif; dalam Serangkaian Pembahasan bagi
Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia. Temu Karya
Hukum Perusahaan dan Arbitrase; Kantor Menko Ekuin dan
Wasbang bekerjasama dengan Departemen Kehakiman, Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum,
Jakarta: 22-23 Januari 1991.
____________, Perdagangan dan Hukum: Beberapa Pemikiran Tentang
Reformasi Hukum Bisnis; Makalah Seminar Implikasi
Reformasi Hukum Bisnis Terhadap Perekonomian Indonesia.
Jakarta: Program Magister Manajemen UI, 21 April 1998.
SIDHARTA, Bernard Arief, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum.
Bandung: Mandar Maju, 2000.
357
__________, Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif
Positivis; Makalah Simposium Nasional Ilmu Hukum tentang
Permasalahan Paradigma dalam Ilmu Hukum Indonesia.
Semarang, 10 Februari 1998.
SIMANDJUNTAK, Djisman S. et al., GATT 1994 Peluang dan
Tantangan Dokumen dan Analisis. (Kumpulan Dokumen dan
Analisis), Jakarta: TP, 14 Juni 1994.
SINGARIMBUN, Irawati, Teknik Wawancara; dalam Masri
Singarimbun et al., Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES,
1982.
SINGER, Linda R., Settling Disputes - Conflict Resolution in Business,
Families, and The Legal System. San Fransisco, 1994, dalam
Erman Rajagukguk, Budaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa
Perdata di Luar Pengadilan; dalam Jurnal Magister Hukum,
Vol. 2 No. 4, Okt. 2000.
SIREGAR, Bismar, Pandangan Hakim terhadap Putusan Arbitrase;
dalam Abdul Rahman Saleh et al., Arbitrase Islam Di Indonesia.
Jakarta: BAMUI & Bank Muamalat, 1994.
SMIT, Hans et al, International Contracts. Parker School of
Foreign and Comparative Law, Columbia University, Matthew
Bender, 1981.
SOEKANTO, Soerjono, Talcott Parsons Fungsionalisme Imperatif.
Jakarta: CV Rajawali, 1986.
___________, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat. Jakarta: Rajawali,
1987.
___________, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif. Jakarta:
Rajawali, 1990.
SOEMITRO, Ronny Hanitijo, Beberapa Perspektif Mengenai Fungsi
Hukum di dalam Masyarakat; dalam Masalah-Masalah Hukum,
Nomor 10 Tahun 1993.
____________, Gambaran tentang Fungsi-fungsi Hukum di Dalam
Masyarakat, Sebagai Hasil Tinjauan terhadap Hukum dari
Beberapa Perspektif; dalam Masalah-Masalah Hukum Nomor
5 Tahun 1991.
____________, Hukum dan Masalah Penyelesaian Konflik. Masalah-
Masalah Hukum No. 2 Tahun 1993.
____________, Studi Hukum dan Masyarakat. Bandung: Alumni, 1985.
SOEPRAPTO, Riyadi H.R., Interaksionisme SimbolikPerspektif
Sosiologi Modern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
SOETJIPTO, Adi Andojo, Etika Profesi; dalam Varia Peradilan,
Tahun VIII, Nomor 95, Agustus 1993.
358
__________, Jumlah 60 Orang Hakim Agung Tidak Rasional; Kompas,
7 April 2000.
SOETOPRAWIRO, Koerniatmanto, Pemerintahan & Peradilan di
Indonesia (Asal-usul & Perkembangannya). Bandung: Citra
Aditya Bakti, 1994.
SOHN, L.B., International Arbitration in Historical Perspective: Past
and Present; dalam International Arbitration: Past and
Prospects, A Symposium to Commemorate the Centenary of the
Birth of Prof. J.H.W. Verzijl (1888-1987), Utrecht, October 21,
1988.
STARKE, J.G., Introduction to International Law. Ninth Edition, 1984,
SUBEKTI, R., Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa, 1979.
___________, Aneka Perjanjian. Bandung: Alumni 1981.
___________, Arbitrasi Perdagangan. Bandung: Binacipta, 1981.
___________, Kekuasaan Mahkamah Agung RI. Bandung: Alumni,
1980.
SULISTIYONO, Adi, Mengembangkan Paradigma Penyelesaian
Sengketa Non-Litigasi dalam Rangka Pendayagunaan Alternatif
Penyelesaian Sengketa Bisnis/Hak Kekayaan Intelektual;
Disertasi, Semarang: PDIH, 2002.
SUPARMAN, Eman, Keharusan Mewakilkan dalam Menunjang
Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat, dan Biaya
Ringan; Tesis S2, Yogyakarta: FPS-UGM, 1988.
SURYABRATA, Sumadi, Metodologi Penelitian. Jakarta: Rajawali,
1983.
SUSANTO, I.S., Lembaga Peradilan dan Demokrasi; Makalah pada
Seminar Nasional tentang Pendayagunaan Sosiologi Hukum
dalam Masa Pembangunan dan Restrukturisasi Global,
Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 12-13 Nopember 1996.
SUSENO, Franz Magnis, Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar
Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
SUTANTIO, Ny. Retnowulan, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan
Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1997.
THENG, Liem Lei, Court Connected ADR in Singapore; Makalah
Seminar Court Connected ADR, Jakarta: Departemen Kehakiman
RI, 21 April 1999.
THOHARI, A. Ahsin, Dari Law Enforcement ke Justice
Enforcement, dalam Kompas, Rabu, 3 Juli 2002.
TSANI, Mohd. Burhan, Hukum dan Hubungan Internasional.
Yogyakarta: Liberty, 1990.
359
TURKEL, Gerald, Law and Society: Critical Approaches. Needham
Heights: A Simon & Schuster Company, 1996.
UHLE, Christian Buhring, Arbitration and Mediation in International
Business. The Hague: Kluwer Law International, 1996.
UJAN, Andre Ata, Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik
John Rawls. Yogyakarta: Kanisius, 2001.
UNGER, Roberto M., Law in Modern Society Toward a Criticism of
Social Theory. London: The Free Press, 1976.
______________, Gerakan Studi Hukum Kritis; (Penerjemah: Ifdhal
Kasim). Jakarta: ELSAM, 1999.
VEATCH, Henry B., Human Rights, Facts or Fancy. Baton Rouge and
London: Lousiana State University Press, 1968.
WARASSIH, Esmi, Kegunaan Telaah Kebijaksanaan Publik Terhadap
Peranan Hukum di dalam Masyarakat Dewasa ini (Sebuah
Pengantar); dalam Masalah-Masalah Hukum No. 11 Tahun
1994.
____________, Peranan Kultur Hukum dalam Penegakan Hukum;
dalam Masalah-Masalah Hukum No. 2 Tahun 1995.
____________, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan
Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan);
Pidato Pengukuhan Guru Besar. Fakultas Hukum UNDIP -
Semarang, 14 April 2001.
WIGNJOSOEBROTO, Soetandyo, Dari Hukum Kolonial ke Hukum
Nasional Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan
Hukum di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
____________, Masalah Metodologik dalam Penelitian Hukum
Sehubungan dengan Masalah Keragaman Pendekatan
Konseptualnya. Makalah. Semarang, TT.
____________, Sebuah Pengantar ke Arah Perbincangan tentang
Pembinaan Penelitian Hukum dalam PJP II; Makalah
disampaikan pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum
Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II,
BPHN, Jakarta, 10-21 Juli 1995; dalam Majalah Hukum Trisaksi
Edisi Khusus, TT.
____________, Teori: Apakah itu? Sebuah Pengantar; Bahan Kuliah
Teori Ilmu Hukum. Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang, 2002.
_____________, Keadilan Komutatif, win-win Solution, dalam Kompas
25 Nopember 2000.
_____________, Fenomena Cq Realitas Sosial sebagai Objek Kajian Ilmu
(Sains) Sosial; dalam Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif-
360
Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer.
Jakarta: Rajawali, 2001.
WIJOYANTO, Bambang, Reformasi Hukum di Mahkamah Agung;
Kompas, 25 Oktober 1999.
WILARDJO, Liek, Peran Paradigma dalam Perkembangan Ilmu;
Makalah dalam Simposium Paradigma dalam Ilmu Hukum
Indonesia. PDIH Undip, Semarang, 10 Februari 1998.
WINARDI, J., Teori Organisasi dan Pengorganisasian. Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2003.
YAHYA, M. Wildan, Keadilan dalam Perspektif Al-Quran; dalam
Hikmah, Jurnal Ilmu Dakwah, Volume 1 Nomor 2, Juli 2002.
ZACHARIAS, J. Danny, Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia
(MARI) dalam Pemberian Keadilan, Mampukah MARI Keluar dari
Masa Kegelapan dan Bencana Berkelanjutan; dalam Seminar
Court Management di MA-RI dan Diskusi Buku Fungsi MA
dalam Praktik Sehari-hari. Salatiga; FH-UKSW, 2001.
Kompas, Negara Hukum Tanpa Moral dan Tanpa Disiplin. 23 Februari
1996.
Kompas, Kerusakan Kehidupan Hukum Sudah Serius. 16 April 1998.
Kompas, Wajah Pengadilan Semakin Lebam. 6 Maret 1999.
Kompas, Lembaga Pengadilan, Toko Hukum, Pasar Hukum. 15 Maret
1999.
Kompas, Kelambanan Proses Peradilan Dikeluhkan. 23 April 1999.
Kompas, Pembaharuan hukum Sebaiknya dari Pembenahan Peradilan. 1
Mei 1999.
Kompas, Penegakan Hukum Jalan di Tempat. 8 Mei 1999.
Kompas,Kualitas Aparat Penegak Hukum Memprihatinkan. 24 Mei
1999.
Kompas, Menegakkan Hukum. 14 Juni 1999.
Kompas, Ternyata tak Gampang Membersihkan Pengadilan. 15 Juli
1999.
Kompas, Sebuah Sandiwara Penegakan Hukum. 13 Oktober 1999.
Kompas, Jangan Lagi Jadikan Hukum sebagai Komoditas. 25 Oktober
1999.
Kompas, MA Menyimpan Potensi Bahaya. 2 November 1999.
Kompas, Mengubah Cara-cara Penyelesaian Hukum. 16 November
1999.
Kompas, Mental Tangguh dalam Penegakan Hukum. 9 Desember 1999.
361
Kompas, Pengadilan yang Mengusik Rasa Keadilan. 13 Januari 2000.
Kompas, Mahkamah Agung Bukan Menara Gading. 21 Februari 2000.
Kompas, Mahkamah Agung di Tengah Arus Reformasi. 7 Maret 2000.
Kompas, Sekali Lagi Perihal Membangun Mahkamah Agung yang
Berwibawa. 13 Maret 2000.
Kompas, Ketika Hukum tidak Lagi Berbunyi. 13 Maret 2000.
Kompas, Main Hakim Sendiri dan Budaya Hukum. 19 Juni 2000.
Kompas, Menguji Ketajaman Pedang Keadilan. 4 September 2000.
Kompas, Terapkan Transitional Justice. 24 Oktober 2000.
Kompas, Pembersihan Pengadilan Belum Terwujud. 3 November 2001.
Kompas, Rawa-rawa Hukum Indonesia. 15 Juli 2002.
Media Indonesia, Terus terang, Sulit Hadapi Mafia Peradilan. 30
Desember 2002
Tempo, Gengsi Baru Mahkamah Agung. Nomor 2 Tahun XXII, 14
Maret 1992.
Tempo, Mahkamah Agung Meralat Gengsi. Nomor 3 Tahun XXII, 21
Maret 1992.
Jurnal Hukum Bisnis, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,
Volume 21, Oktober-November 2002.
Varia Peradilan, Pembatalan Kontrak Dagang Internasional Dewan
Arbitrase Dikesampingkan; Tahun VII No. 80, Mei 1992.
Forum Keadilan, Dagang Hukum di Pengadilan. No. 11, 17 September
1992.
Majalah Hukum dan Masyarakat, No. 1-2-3 Tahun 1962.
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering voor de raden van justitie op
Java en het hooggerechtshof van Indonesie, alsmede voor de
residentiegerechten op Java en Madura (Rv) S. 1847 No. 52 jo
1849 No. 63. Rv sebagai ketentuan hukum acara perdata yang
dahulu berlaku pada Raad van Justitie (RvJ) untuk orang-orang
Eropa dan yang dipersamakan dengan orang Eropa.
ICSID Basic Documents, Washington DC, 1985.
Viena Convention on the law of treaties and international organization
or between international organization., dalam International Legal
Materials. Volume XXV, Number 3, May 1986.
Mahkamah Agung RI, Intermanual Himpunan Putusan Mahkamah
Agung tentang Arbitrase. Proyek Yurisprudensi, 1989.
Mahkamah Agung RI, Yurisprudensi Indonesia 3. Jakarta: PT Ichtiar
Baru, 1990.
Suplemen Ensiklopedi Islam 1 A-K, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1993.
Ensiklopedi Islam 1. Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1994.
362
Ensiklopedi Hukum Islam Buku I, Jakarta: PT Ichtiar Baru, 1996.
Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional No 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Penanganan Sengketa Pertanahan.
________________, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981, tentang
Sewa Menyewa.
________________,Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang
Lembaga Penyedia Jasa Pelayanann Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
________________,Undang-Undang No. 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak.
________________,Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup.
________________,Undang-undang No. 25 Tahun 1997 tentang
Ketenagakerjaan.
________________,Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang
Kepailitan.
________________,Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
________________, Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
________________,Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.
________________, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.
________________, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun
1981.
________________, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1
Tahun 1990.
Anda mungkin juga menyukai
- Filsafat Pancasila Dalam Perdagangan BebasDokumen15 halamanFilsafat Pancasila Dalam Perdagangan BebasMuhammad Iftar AryaputraBelum ada peringkat
- Catatan UAS Surga - Compiled 2Dokumen33 halamanCatatan UAS Surga - Compiled 2Neysa SafiraBelum ada peringkat
- Studi Hukum KritisDokumen29 halamanStudi Hukum KritisPirhot NababanBelum ada peringkat
- Rangkuman HPUDokumen32 halamanRangkuman HPUGessica FreshanaBelum ada peringkat
- Tugas Akhir HaperDokumen30 halamanTugas Akhir Hapermika kina sitaBelum ada peringkat
- PRINSIP-prinsip Hukum Waris BWDokumen14 halamanPRINSIP-prinsip Hukum Waris BWAstie Dyah R100% (1)
- FilhumDokumen3 halamanFilhumQuintha Viona ApriletaBelum ada peringkat
- JettyDokumen3 halamanJettydickyBelum ada peringkat
- Skripsi Tentang e CourtDokumen97 halamanSkripsi Tentang e CourtAhmad YaniBelum ada peringkat
- UAS Hukum LingkunganDokumen6 halamanUAS Hukum LingkunganGilang Fardes PratamaBelum ada peringkat
- Anotasi Putusan Perkara Penipuan Jual Beli Batu BaraDokumen54 halamanAnotasi Putusan Perkara Penipuan Jual Beli Batu BaraYehezkiel RomartogiBelum ada peringkat
- Hukum DagangDokumen4 halamanHukum DagangSevty Alystyfan Ikhromy, SHBelum ada peringkat
- Legal Memorandum AtaopinionDokumen16 halamanLegal Memorandum AtaopinionRezky Eka PutriBelum ada peringkat
- Tugas HATAH 2Dokumen2 halamanTugas HATAH 2Vincentsius PuteraBelum ada peringkat
- Proposal Impelemntasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian SampulDokumen84 halamanProposal Impelemntasi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Sampulmohammad ali anwarBelum ada peringkat
- Rangkuman Praptun Untuk Uts PDFDokumen27 halamanRangkuman Praptun Untuk Uts PDFChacha AzzahraBelum ada peringkat
- Tugas Mandiri Hukum PerusahaanDokumen30 halamanTugas Mandiri Hukum PerusahaanAnggra Satria SitindaonBelum ada peringkat
- Skripsi V.02Dokumen32 halamanSkripsi V.02rizki nugroho F100% (1)
- Makalah Pengantar Hpi Oleh Sudargo GautamaDokumen25 halamanMakalah Pengantar Hpi Oleh Sudargo Gautamabayu estuajiBelum ada peringkat
- Argumentasi Hukum Dan Teknik Penyusunan Legal OpinionDokumen24 halamanArgumentasi Hukum Dan Teknik Penyusunan Legal OpinionLiffyBelum ada peringkat
- Kontrak ElektronikDokumen28 halamanKontrak ElektronikSalma NurazizahBelum ada peringkat
- Penjelasan Lengkap Omnibus LawDokumen39 halamanPenjelasan Lengkap Omnibus LawAndi ImranBelum ada peringkat
- 3-Norma Dan Susunan Norma DLM NegaraDokumen12 halaman3-Norma Dan Susunan Norma DLM NegaraIka Adelia Rinanta PutriBelum ada peringkat
- Hukum BisnisDokumen16 halamanHukum Bisnismuhamad kobul100% (1)
- Perbedaan Tergugat Dengan Turut TergugatDokumen1 halamanPerbedaan Tergugat Dengan Turut TergugatDodiMuhammadBelum ada peringkat
- Contoh Format Gugatan PTUNDokumen9 halamanContoh Format Gugatan PTUNAisyah SharifaBelum ada peringkat
- Pengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung PriokDokumen5 halamanPengadilan Ham Ad Hoc Kasus Tanjung Priokendafajar0% (1)
- Tugas Lingkungan 2 (Putusan Perdata)Dokumen30 halamanTugas Lingkungan 2 (Putusan Perdata)Naomi PanggabeanBelum ada peringkat
- Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Mengimplementasikan Norma Hukum Yang Dibatalkan Mahkamah KonstitusiDokumen25 halamanAkibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Mengimplementasikan Norma Hukum Yang Dibatalkan Mahkamah KonstitusiDaniel SamosirBelum ada peringkat
- Kasus PosisiDokumen5 halamanKasus PosisiFarhan AnzilanBelum ada peringkat
- Jurnal Harta WarisanDokumen8 halamanJurnal Harta WarisanChristian WiranataBelum ada peringkat
- Ringkasan Kuliah Hukum PerdataDokumen8 halamanRingkasan Kuliah Hukum PerdataIbnu IzzaBelum ada peringkat
- Sengketa Perdata Internasional KBC - Pertamina - PLNDokumen30 halamanSengketa Perdata Internasional KBC - Pertamina - PLNChikichikoman100% (3)
- EKSEPSIDokumen15 halamanEKSEPSISakti Eko100% (1)
- PRTMN 5-6 Membuat JAWABAN GUGATAN DAN EKSEPSIDokumen12 halamanPRTMN 5-6 Membuat JAWABAN GUGATAN DAN EKSEPSIHermi RukmanaBelum ada peringkat
- Arbitrase PPTDokumen15 halamanArbitrase PPTNariah SafiraBelum ada peringkat
- Perbedaan Citizen Lawsuit Dan Class ActionDokumen3 halamanPerbedaan Citizen Lawsuit Dan Class ActionANTONIUS ANDIKA WANGSABelum ada peringkat
- Hukum Persaingan Usaha s2Dokumen57 halamanHukum Persaingan Usaha s2Khairul Arief RomadhanBelum ada peringkat
- Analisis Putusan Ptun JakartaDokumen21 halamanAnalisis Putusan Ptun JakartaRyanSoetopoBelum ada peringkat
- UAS Jurnal Hukum PerburuhanDokumen25 halamanUAS Jurnal Hukum PerburuhanKilomalikBelum ada peringkat
- PROPOSAL SKRIPSI KepailitanDokumen43 halamanPROPOSAL SKRIPSI KepailitanFaisal Hadi PinemBelum ada peringkat
- Rangkuman Buku SubektiDokumen2 halamanRangkuman Buku SubektiChandra Nico Sorimuda PardedeBelum ada peringkat
- Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar ModalDokumen22 halamanPerlindungan Hukum Terhadap Investor Pasar ModalHerman Andreij AdriansyahBelum ada peringkat
- Arbitrase Penyelesaian SengketaDokumen20 halamanArbitrase Penyelesaian SengketaDimas BadrunBelum ada peringkat
- Modul 2 Alternatif Penyelesaian SengketaDokumen15 halamanModul 2 Alternatif Penyelesaian SengketaArthuria PendragonBelum ada peringkat
- Somasi IDokumen3 halamanSomasi IAtk DwngrhBelum ada peringkat
- Hukum AdatDokumen41 halamanHukum AdatabelBelum ada peringkat
- Kuliah 5 HPI Dhoni YusraDokumen21 halamanKuliah 5 HPI Dhoni YusraudinBelum ada peringkat
- EksekusiDokumen111 halamanEksekusiAntoko KrisBelum ada peringkat
- Surat GugatanDokumen13 halamanSurat GugatanAstiruddin PurbaBelum ada peringkat
- Hak Kekayaan Intelektual (Catatan Rangkuman)Dokumen25 halamanHak Kekayaan Intelektual (Catatan Rangkuman)David Waltin PasaribuBelum ada peringkat
- Surat GugatanDokumen3 halamanSurat GugatanRizal RahmatulohBelum ada peringkat
- KUHPDokumen107 halamanKUHPstalna100% (1)
- Peradilan AdatDokumen81 halamanPeradilan AdatRiczki Rinaldi HutahaeanBelum ada peringkat
- 11010110500040Dokumen53 halaman11010110500040Fikri NugrahaBelum ada peringkat
- Kata PengantarDokumen3 halamanKata PengantarAdi HartonoBelum ada peringkat
- Peradilan AdatDokumen81 halamanPeradilan Adat29Naura Taqiyya MaziBelum ada peringkat
- DAFTAR IS1 SkarangDokumen7 halamanDAFTAR IS1 SkarangMustafa LaboraBelum ada peringkat
- LEGISLASI PENATAAN RUANG Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota SemarangDokumen477 halamanLEGISLASI PENATAAN RUANG Studi Tentang Pergeseran Kebijakan Hukum Tata Ruang Dalam Regulasi Daerah Di Kota SemarangPUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)100% (1)
- RAMA 74201 02011281621153 0028077301 0013048210 01 Front RefDokumen54 halamanRAMA 74201 02011281621153 0028077301 0013048210 01 Front RefCm FeezyBelum ada peringkat