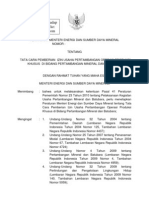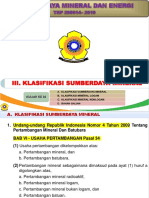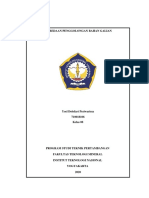Bab Ii
Bab Ii
Diunggah oleh
Rizkylintar LintaRizky BlinkstarD'LinstarJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bab Ii
Bab Ii
Diunggah oleh
Rizkylintar LintaRizky BlinkstarD'LinstarHak Cipta:
Format Tersedia
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1. Pertambangan
Pertambangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan
penggalian ke dalam tanah (bumi) bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang
berupa hasil tambang (Gatot Supramono, 2012). Menurut Undang-Undang
Nomor 4 tahun 2009 pasal 1, pertambangan yaitu sebagian atau seluruh
tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan
mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi
kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian,
pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
Pertambangan mineral dan pertambangan batubara memiliki pengertian
yang berbeda. Menurut UU No 4 tahun 2009, dijelaskan bahwa pertambangan
mineral merupakan bahan tambang berupa kumpulan mineral yang berupa bijih
atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah.
Sedangkan pertambangan batubara merupakan pertambangan endapan karbon
yang terdapat di dalam bumi,termasuk bitumen padat, gambut dan batuan
aspal. Komoditas pertambangan terbagi menjadi beberapa golongan.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang telah dijabarkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, golongan komoditas
tambang adalah sebagai berikut:
a. Mineral Radioaktif
Mineral radioaktif merupakan mineral yang mengandung elemen
uranium dan thorium. Mineral radioaktif dibagi menjadi lima macam
yaitu radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radio
aktif lainnya.
b. Mineral Logam
Mineral logam merupakan mineral yang tidak tembus pandang dan
dapat menjadi penghantar panas dan arus listrik. Mineral logam dibagi
menjadi 59 macam yaitu litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium,
emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel, mangan, platina, bismuth,
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 4
molybdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium,
kromit, antimony, kobalt, tantalum, cadmium, gallium, indium, yytrium,
magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirconium, ilmenit, khrom,
erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium,
neodymium, hafnium, scandium, alumunium, palladium, rhodium,
osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, strontium, germanium
dan zenotin.
c. Mineral Non Logam
Mineral bukan logam dibagi menjadi 40 macam yaitu intan,
korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriorit, yodium,
brom, klor belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker,
fluorit, ball clay, fire clay, zeolite, kaolin, feldspar, bentonit, gypsum,
dolomite, kalsit, rijang, pirofilit, kuarsit,zircon, wolastonit, tawas, batu
kuarsa, perlit, garam batu, clay, dan batu gamping.
d. Batuan dan Batubara
Batuan adalah benda keras dan padat yang berasal dari bumi, yang
bukan logam. Batuan dibagi menjadi 47 macam yaitu pumice, tras, toseki,
obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap, slare, granit,
granodiorit, andesit, garbo, periodit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah
urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase,
kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorite, topas, batu gunung quarry
besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak
tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, sirtu, tanah, urukan tanah setempat,
tanah merah, batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak
mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam
jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Batuan
dibagi menjadi 4 macam yaitu bitumen padat, batuan aspal, batubara dan
gambut.
2.2. Izin Usaha Pertambangan
Izin Usaha Pertambangan biasa disebut dengan istilah IUP yang berasal
dari terjemahan bahasa Inggris yaitu mining permit (Salim, 2012). Menurut
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 1 ayat 7, Izin Usaha Pertambangan
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 5
adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 37, disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:
a. Bupati/Walikota apabila WIUP di dalam satuan wilayah kabupaten/kota.
b. Gubernur apabila WIUP di dalam satuan wilayah kabupaten/kota dalam
satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota
setempat sesuai peraturan perundang-undangan
c. Menteri apabila WIUP di dalam satuan wilayah provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat
sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun dengan adanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, maka yang berwenang memberikan Izin Usaha
Pertambangan adalah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangan yang
dimilikinya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 pasal 38,
disebutkan bahwa Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:
a. Badan Usaha berupa badan usaha swasta, Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah;
b. Koperasi; dan
c. Perseorangan dapat berupa orang perseorangan, perusahaan firma atau
perusahaan komanditer.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2010 pasal 7 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan terdiri dari dua tahap yaitu:
a. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi
IUP Eksplorasi merupakan pemberian izin tahap pertama, dan
kegiatannya meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi
kelayakan. IUP eksplorasi ini diberikan untuk satu jenis mineral dan batu
bara. Pemegang IUP eksplorasi yang bermaksud mengusahakan mineral
lain yang ditemukan di dalam wilayah IUP yang dikelola, wajib
mengajukan permohonan WIUP baru kepada Menteri, Gubernur, dan
Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Apabila pemegang IUP
tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut,
maka wajib menjaga mineral tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain,
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 6
dan apabila diberikan kepada orang lain maka pemberian tersebut hanya
dapat dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi terdiri dari:
1) Mineral logam, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 8 tahun
2) Batubara, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun
3) Mineral Non Logam, izin diberikan paling lama dalam jangka waktu 3
tahun, sedangkan untuk pertambangan mineral bukan logam jenis
tertentu diberikan dalam jangka waktu paling lama 7 tahun.
4) Batuan, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.
b. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai pemberian izin
sesuai IUP Eksplorasi diterbitkan dan kegiatannya meliputi kegiatan
konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan
dan penjualan. Setiap pemegang IUP Eksplorasi dijamin undang-undang
untuk memperoleh IUP Operasi Produksi karena sebagai kelanjutan
kegiatan usaha pertambangannya. IUP Operasi Produksi dapat diberikan
kepada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, koperasi, atau
perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batu bara
yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi terdiri dari:
1) Mineral Logam, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 20
tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.
2) Batubara, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan
dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.
3) Mineral Non Logam, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 10
tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun. Izin
untuk pertambangan mineral non logam jenis tertentu diberikan dalam
jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali
masing-masing 10 tahun.
4) Batuan, izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun dan
dapat diperpanjang dua kali masing-masing 5 tahun.
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 7
2.3. Geolistrik
Penggunaan metode geolistrik pertama kali digunakan oleh Conrad
Schlumberger pada tahun 1912. Geolistrik merupakan salah satu metode
geofisika untuk mengetahui perubahan resistivitas lapisan batuan di bawah
permukaan tanah dengan cara mengalirkan arus listrik DC (Dirrect Current)
yang mempunyai tegangan tinggi ke dalam tanah. Injeksi arus listrik ini
menggunakan 2 buah elektroda arus A dan B yang ditancapkan ke dalam tanah
dengan jarak tertentu. Semakin panjang jarak elektroda AB akan menyebabkan
aliran arus listrik bisa menembus lapisan batuan lebih dalam (Damtoro,
2007:5).
Geolistrik merupakan suatu metoda yang terdapat dalam geofisika.
Geolistrik mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dan cara
mendeteksinya di permukaan bumi. Pendeteksian ini meliputi pengukuran
beda potensial, arus, dan elektromagnetik yang terjadi secara alamiah maupun
akibat penginjeksian arus ke dalam bumi (Kanata dan Zubaidah,2008). Metode
geolistrik dapat menginterprestasi jenis batuan atau mineral di bawah
permukaan berdasarkan sifat kelistrikan dari batuan penyusunnya (Yulianto
dan Widodo, 2008:2). Pendeteksian dilakukan berdasarkan sifat fisika batuan
terhadap arus yang diinjeksikan kedalam tanah, dimana setiap batuan
mempunyai sifat harga hambatan jenis yang berbeda (Astawa, 2009:57).
2.4. Geolistrik Tahanan Jenis/Resistivitas
Salah satu metode geolistrik yang sering digunakan yaitu geolistrik
resistivitas/tahanan jenis. Resistivitas atau tahanan jenis adalah besaran atau
parameter yang menunjukkan tingkat hambatannya terhadap arus listrik,
dengan diketahuinya harga tahanan jenis maka dapat diketahui jenis
materialnya. Hubungan antara panjang bentang elektroda dengan nilai
resistivitas adalah berbanding terbalik sesuai dengan rumus resistivitas. Batuan
yang memiliki resistivitas makin besar, menunjukkan bahwa batuan tersebut
sulit untuk dialiri oleh arus listrik.
Metode tahanan jenis didasari oleh hukum Ohm, bertujuan mengetahui
jenis pelapisan batuan didasarkan pada distribusi nilai resistivitas pada tiap
lapisan. Dengan menginjeksikan arus melalui dua elektroda arus, maka beda
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 8
potensial yang muncul dapat terukur dari elektroda potensial. Variasi harga
tahanan jenis akan didapatkan, jika jarak antara masing-masing elektroda
diubah, sesuai dengan konfigurasi alat yang dipakai. Pada metode tahanan jenis
diasumsikan bahwa bumi bersifat homogen isotropik, dimana nilai tahanan
jenis yang terukur bukan merupakan harga sebenarnya akan tetapi merupakan
nilai tahanan jenis semu (apparent Resistivity) (Arif, 1987; Mukaddas, 2009 ).
Metode yang biasa digunakan pada pengukuran resistivitas secara
umum adalah dengan menginjeksikan arus listrik ke dalam bumi dengan
menggunakan dua elektroda arus (C1 dan C2), dan pengukuran hasil beda
potensial dengan menggunakan dua elektroda potensial (P1 dan P2) (Sunaryo
dkk., 2003). Pengukuran resistivitas normalnya dilakukan dengan
menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah melalui dua elektroda potensial (P1
Dan P2). Besarnya nilai resistivitas didapatkan dari hasil kuat arus (I) dan
besarnya nilai tegangan (V) (Loke, 2000). Berdasarkan nilai arus (I) dan beda
potensial (V) tersebut, nilai resistiivitas (ρ) dapat dihitung dengan persamaan:
ρ = K . V/I
Keterangan:
ρ : resistiivitas atau tahanan jenis (Ω m)
k : faktor geometri yang bergantung pada susunan elektroda
I : arus (ampere)
V : beda potensial/tegangan (Volt)
Berdasarkan metode geolistrik tahanan jenis teknik pengambilan datanya dapat
dibagi menjadi dua kelompok yaitu metode mapping dan sounding.
a. Metode Mapping merupakan metode resistiviti yang bertujuan untuk
mempelajari variasi tahanan jenis lapisan bawah permukaan secara
horizontal. Oleh karena itu, pada metode ini dipergunakan konfigurasi
elektroda yang sama untuk semua titik pengamatan di permukaan bumi.
Setelah itu baru dibuat kontur resistivitasnya. Konfigurasi elektroda yang
biasa dipakai adalah konfigurasi Wenner atau Dipole – dipole.
b. Metode Sounding bertujuan untuk mempelajari variasi resistivitas batuan
di bawah permukaan bumi secara vertikal. Pengukuran pada suatu titik
sounding dilakukan dengan jalan mengubah-ubah jarak elektroda.
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 9
Pengubahan jarak elektroda ini dilakukan secara sembarang, tetapi dimulai
dari jarak elektroda terkecil kemudian membesar secara gradual. Jarak
elektroda ini sebanding dengan kedalaman lapisan batuan yang terdeteksi.
Makin besar jarak elektroda tersebut, maka makin dalam lapisan batuan
yang dapat diselidiki. Konfigurasi elektroda yang biasanya dipakai adalah
konfigurasi Schlumberger.
2.5. Sifat Kelistrikan Batuan
Tahanan jenis batuan yang ada di berbagai macam komposisi mineral
di bumi tidak mempunyai harga tahanan jenis tertentu akan tetapi nilainya
mempunyai jangkauan (range) tertentu. Secara teoritis setiap batuan
mempunyai daya hantar listrik dan harga tahanan jenisnya masing - masing.
Batuan yang sama belum tentu memiliki nilai tahanan jenis yang sama.
Sebaliknya harga tanahan jenis yang sama bisa dimiliki oleh batuan yang
berbeda jenis. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tahanan jenis antara lain:
komposisi mineral pada batuan, kondisi batuan, komposisi benda cair pada
batuan, dan faktor eksternal lainnya (Nugroho M.W,dkk, 2018). Semakin besar
nilai resistivitas suatu batuan maka semakin sulit batuan tersebut
menghantarkan arus listrik, begitu pula sebaliknya (Taib, 2000).
Aliran arus listrik di dalam batuan dan mineral dapat di golongkan
menjadi tiga macam, yaitu konduksi secara elektronik, konduksi secara
elektrolitik, dan konduksi secara dielektrik (Telford, 1982; Arif, 1990).
a. Konduksi secara Elektronik
Konduksi ini adalah tipe normal dari aliran arus listrik dalam batuan
maupun mineral. Konduksi secara elektronik terjadi karena batuan atau
mineral mengandung banyak elektron bebas. Hal tersebut mengakibatkan
arus listrik mudah mengalir pada batuan ini. Salah satu contohnya adalah
batuan yang banyak mengandung logam. Selain itu aliran listrik juga
dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing batuan atau mineral yang
dilaluinya. Salah satu sifat atau karakteristik batuan atau mineral tersebut
adalah resistivitas atau tahanan jenis, yang menunjukkan kemampuan
bahan tersebut untuk menghantarkan arus listrik.
b. Konduksi secara Elektrolitik
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 10
Konduksi ini biasa terjadi pada batuan atau mineral yang bersifat
porous dan memiliki pori-pori yang terisi fluida, terutama air. Hal tersebut
menyebabkan batuan-batuan menjadi konduktor elektrolitik, dimana
konduksi arul listrik tersebut dibawa oleh ion-ion elektrolitik dalam air.
Konduktivitas dan resistivitas batuan porus bergantung pada volume dan
susunan pori-porinya. Konduktivitas akan semakin besar jika kandungan
air dalam batuan bertambah banyak, dan sebaliknya resistivitas akan
semakin besar jika kandungan air dalam batuan berkurang.
c. Konduksi secara Dielektrik
Konduksi ini terjadi pada batuan atau mineral yang bersifat
dialektrik terhadap aliran arus listrik, artinya batuan atau mineral tersebut
memiliki elektron bebas yang sedikit bahkan tidak ada sama sekali. Akan
tetapi dengan adanya pengaruh medan listrik dari luar, maka elektron-
elektron tersebut berpindah dan berkumpul terpisah dari inti yang
menyebabkan terjadinya polarisasi.
Konduktor biasanya didefinisikan sebagai bahan yang memiliki
resistivitas kurang dari 10-8 Ωm, sedangkan isolator memiliki resistivitas lebih
dari 107 Ωm, dan diantara keduanya adalah bahan semi konduktor.
Berdasarkan resistivitasnya, secara umum batuan dan mineral dapat
dikelompokkan menjadi tiga (Telford, 1982):
a. Konduktor baik: 10-8 < ρ < 1 Ωm
b. Konduktor pertengahan: 1 < ρ < 107 Ωm
c. Isolator: ρ > 107 Ωm
Resistivitas menyatakan sifat khas dari suatu bahan, yaitu derajat
kemampuan bahan menghantarkan arus listrik dengan satuan Ωm. Satu Ωm
menyatakan besarnya hambatan pada suatu bahan yang memiliki panjang 1 m
dan luas penampang 1 m2. Hal ini berarti bahwa untuk bahan tertentu, harga
resistivitas juga bernilai tertentu. Akibatnya suatu bahan dengan mineral
penyusun sama tetapi perbandingannya berbeda, maka resistivitasnya akan
berbeda pula. Nilai resistivitas hanya bergantung pada jenis mineral penyusun
dan tidak bergantung pada faktor geometri.
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 11
Tabel 2.1 Resisitivitas Batuan Beku dan Metamorf
Rock Type Resistivity Range (Ωm)
Granite 3 x 102 - 106
Granite Porphyry 4.5 x 103 (wet) – 1.3 x 106 (dry)
Feldspar Porphyry 4 x 103 (wet)
Albite 3 x 102 (wet) – 3.3 x 103 (dry)
Syenite 102 - 106
Diorit 104 - 105
Diorit Porphyry 1.9 x 103 (wet) – 2.8 x 104 (dry)
Porphyryte 10 – 5 x 104 (wet) – 3.3 x 103 (dry)
Carbonatized Porphyry 2.5 x 103 (wet) – 6 x 104 (dry)
Quartz Porphyry 3 x 102 – 9 x 105
Quartz Diorite 2 x 104 – 2 x 106 (wet) – 1.8 x 105 (dry)
Porphyry (Various) 60 - 104
Dacite 2 x 104 (wet)
Andesite 4.5 x 104 (wet) – 1.7 x 105 (dry)
Diabase Porphyry 103 (wet) - 1.7 x 105 (dry)
Diabase (various) 20 – 5 x 107
Lavas 102 – 5 x 104
Gabbro 103 - 106
Basalt 10 – 1.3 x 107 (dry)
Olivine Norite 103 – 6 x 104 (wet)
Peridotite 3 x 103 (wet) – 6.5 x 103 (dry)
Hornfels 8 x 103 (wet) – 6 x 107 (dry)
Schists (calcareous and mica) 20 - 104
Tuffs 2 x 103 (wet) - 105 (dry)
Graphite Schist 10 - 102
Slates (various) 6 x 102 – 4 x 107
Gneiss (various) 6.8 x 104 (wet) – 3 x 106 (dry)
Marble 102 – 2.5 x 108 (dry)
Skarn 2.5 x 102 (wet) – 2.5 x 108 (dry)
Quarzites (various) 10 – 2 x 108
Sumber: Telford, dkk. (1976)
Tabel 2.2 Resistivitas Batuan Sedimen
Rock Type Resistivity Range (Ωm)
Consolidated Shales 20 – 2 x 103
Argillites 10 – 8 x 102
Conglomerates 2 x 103 - 104
Sandstones 1 – 6.4 x 108
Limestones 50 - 107
Dolomite 3.5 x 102 – 5 x 103
Unconsolidated Wet Clay 20
Marls 3 – 70
Clays 1 – 100
Alluvium and Sands 10 – 800
Oil Sands 4 - 800
Sumber: (Telford, dkk., 1976)
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 12
Tabel 2.3 Harga Resistivitas Spesifik Batuan
Material Resistivitas (Ωm)
Air Pemasukan 80 – 200
Airtanah 30 – 100
Silt – Lempung 10 – 200
Pasir 100 – 600
Pasir dan kerikil 100 – 1000
Batu Lumpur 20 – 200
Batu pasir 50 – 500
Konglomerat 100 – 500
Tufa 20 – 200
Kelompok Andesit 100 – 2000
Kelompok Granit 1000 – 10000
Kelompok Chert, Slate 200 – 2000
Sumber: (Suyono, 1978)
2.6. Jenis Konfigurasi Elektroda Geolistrik
Metode resistivitas dalam prakteknya memiliki beberapa macam
konfigurasi peletakan elektroda. Pemilihan konfigurasi yang digunakan pada
survey di lapangan dilakukan berdasarkan tipe dari struktur yang akan
dipetakan, sensitivitas dari alat ukur resistivitas dan latar belakang tingkat
gangguan. Terdapat karakteristik dari setiap konfigurasi yang perlu
diperhatikan, antara lain sensitivitas konfigurasi terhadap perubahan
resistivitas vertikal dan horisontal di bawah permukaan tanah, kedalaman
penyelidikan, liputan data horisontal, dan kekuatan sinyal (Railasha, dkk tahun
2015 dikutip dari Loke, 2013). Jenis-jenis Konfigurasi yang digunakan dalam
metode geolistrik antara lain:
a. Konfigurasi Wenner
Konfigurasi Wenner sangat baik untuk lateral profiling atau lateral
mapping, yaitu pemetaan untuk mengetahui variasi resitivitas secara lateral
atau horizontal. Hal ini dikarenakan pada konfigurasi Wenner, jarak antar
elektroda memiliki jarak yang tetap. Jarak antar elektroda arus listrik yang
dibuat tetap menghasilkan aliran arus listrik yang maksimal pada
kedalaman tertentu sehingga kontras resitivitas lateral atau horizontal dapat
diperkirakan.
Dalam prosedur Wenner pada tahanan jenis mapping, empat
elektroda konfigurasi (C2P2P1C1) dengan spasi yang sama dipindahkan
secara keseluruhan dengan jarak yang tetap sepanjang garis pengukuran.
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 13
Pemilihan spasi terutama tergantung pada kedalaman lapisan yang akan
dipetakan (Sharma, 1997).
Konfigurasi Wenner mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Menurut Burger (2006), kelebihan konfigurasi Wenner adalah dengan lebar
spasi elektroda potensial yang besar maka tidak memerlukan peralatan
yang sensitif. Sedangkan kekurangannya adalah semua elektroda harus
dipindahkan untuk setiap pembacaan data resistivitas. Hal ini untuk
mendapatkan sensitifitas yang lebih tinggi untuk daerah lokal dan variasi
lateral dekat permukaan.
Gambar 2.1. Susunan Elektroda Konfigurasi Wenner (Azharudin, 2013)
b. Konfigurasi Schlumberger
Konfigurasi Schlumberger merupakan konfigurasi yang cocok
digunakan untuk pengukuran sounding atau pengukuran yang bertujuan
untuk mengetahui sebaran titik geolistrik secara Vertical Electrical
Sounding (VES) atau vertikal ke bawah dengan kedalaman yang cukup
dalam (Todd, 1980). Metode resistivitas dengan konfigurasi Schlumberger
dilakukan dengan cara mengkondisikan spasi antar elektrode potensial
adalah tetap sedangkan spasi antar elektrode arus berubah secara bertahap
(Sheriff, 2002 dalam Halik dan Widodo, 2008). Pengukuran resistivitas
pada arah vertikal atau Vertical Electrical Sounding (VES) merupakan
salah satu metode geolistrik resistivitas untuk menentukan perubahan
resistivitas tanah terhadap kedalaman yang bertujuan untuk mempelajari
variasi resistivitas batuan di bawah permukaan bumi secara vertikal
(Telford, et al., 1990 dalam Halik dan Widodo, 2008).
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 14
Prinsip konfigurasi Schlumberger adalah dengan membuat jarak
MN (jarak antara alat dengan elektroda C1-C2) sekecil-kecilnya, sehingga
jarak MN secara teoritis tidak berubah. Tetapi karena keterbatasan
kepekaan alat ukur, maka ketika jarak AB (jarak alat dengan elektrooda P1-
P2) sudah relatif besar maka jarak MN hendaknya dirubah. Perubahan jarak
MN hendaknya tidak lebih besar dari 1/5 jarak AB. Keunggulan
konfigurasi Schlumberger adalah kemampuan untuk mendeteksi adanya
sifat tidak homogen lapisan batuan pada permukaan, yaitu dengan
membandingkan nilai resistivitas semu ketika terjadi perubahan jarak
elektroda MN/2. Kelemahan dari konfigurasi Schlumberger adalah
pembacaan tegangan pada elektroda AB adalah lebih kecil terutama ketika
jarak AB yang relatif jauh, sehingga diperlukan alat ukur multimeter yang
mempunyai karakteristik high impedance dengan mengatur tegangan
minimal 4 digit atau 2 digit dibelakang koma atau dengan cara peralatan
arus yang mempunyai tegangan listrik DC yang sangat tinggi (Broto dan
Afifah, 2008).
Gambar 2.2. Susunan Elektroda Konfigurasi Schlumberger
(Azharudin, 2013)
c. Konfigurasi Dipole
Metode geolistrik resistivitas konfigurasi dipole-dipole dapat
diterapkan untuk tujuan mendapatkan gambaran bawah permukaan pada
obyek yang penetrasinya relatif lebih dalam dibandingkan dengan metode
sounding lainnya seperti konfigurasi wenner dan konfigurasi schlumberger.
Metode ini sering digunakan dalam survei-survei resistivitas karena
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 15
rendahnya efek elektromagnetik yang ditimbulkan antara sirkuit arus dan
potensial (Loke,1999).
Pada konfigurasi dipole-dipole, kedua elektroda arus dan elektroda
potensial terpisah dengan jarak a. Sedangkan elektroda arus dan elektroda
potensial bagian dalam terpisah sejauh na, dengan n adalah bilangan bulat
(Waluyo, 2005). Variasi n digunakan untuk mendapatkan berbagai
kedalaman tertentu, semakin besar n maka kedalaman yang diperoleh juga
semakin besar. Tingkat sensitivitas jangkauan pada konfigurasi dipole-
dipole dipengaruhi oleh besarnya a dan variasi n.
Gambar 2.3. Susunan Elektroda Konfigurasi Dipole-Dipole
2.7. Kajian Empiris
Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai
penggunaan metode geolistrik untuk penentuan bahan tambang di bawah
permukaan bumi. Berdasarkan penelitian oleh Solihin (2013) yang berjudul
Bahan Galian Batu dan Pasir (Quarry) Daerah Puloampel, Kec. Puloampel
Kab. Banter Provinsi Banten dapat diketahui bahwa terdapat beberapa jenis
batuan pada daerah tersebut. Pada soil atau tanah terdapat bongkahan batu
berupa breksi maupun lava, pada Aluvial sungai sebagai material lepas terdiri
dari pasir hingga bongkah, terdapat breksi volkanik matriks support, lava
andesit-basaltis dan breksi volkanik fragment support. Metode penelitian yang
digunakan pada penelitian ini yaitu metode geolistrik dengan konfigurasi
wener.
Karunianto. A. J, Haryanto. D, Syaeful H, Kamajati. D (2019)
melakukan penelitian yang berjudul Interpretasi Bawah Permukaan
berdasarkan Nilai Tahanan Jenis di Daerah Puspitek, Serpong. Metode yang
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 16
digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Geolistrik secara 2D
menggunakan 48 channel dengan konfigurasi Wenner-Schlumberger.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dihasilkan empat
model penampang lintasan yaitu line1, line2, line3 dan line4. Interpretasi
geologi dilakukan pada penampang line-2 dan line-3 yang menggambarkan
keberadaan lapisan A, B dan C. Lapisan A diduga berupa batuan dengan ukuran
butir lempung-lanau yang mengandung material organik dengan rentang nilai
tahanan jenis 2-20 Ωm dan variasi ketebalan sekitar 1-7 m. Lapisan B diduga
berupa batupasir yang memiliki rentang nilai tahanan jenis 10-90 Ωm dengan
variasi ketebalan 5-20 m. Lapisan C diduga merupakan batulempung yang
memiliki rentang nilai tahanan jenis 2-5000 Ωm dengan variasi kedalaman 10-
20 m.
Swastika A, Syafriyono, Caesario D, Pratama. A. Y, dan Kartanegara.
S. M (2018) melakukan penelitian yang berjudul Pola Persebaran dan Estimasi
Cadangan Andesit pada Desa Ciluluk, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten
Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode geolistrik.
Pengambilan data geolistrik dilakukan sebanyak 10 lintasan untuk pengukuran
2D dengan konfigurasi dipole-dipole, dan 4 lintasan untuk pengukuran 1D
dengan konfigurasi Schlumberger. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan dapat diketahui bahwa andesit di daerah penelitian tersebar tidak
merata dan dapat dibedakan menjadi 2 jenis yaitu soft dan hard andesite. Kedua
tubuh andesit ini memiliki pola sebaran barat-timur dengan kenampakan fisik
serta nilai resistivitas yang berbeda dimana hard andesite memiliki nilai
resistivitas yang lebih tinggi (>350 Ωm). Hasil perhitungan cadangan
menunjukkan bahwa cadangan andesit berkisar antara 3.861.267 ton untuk
skenario 1 hingga 9.617.227 ton untuk skenario 2.
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN GEOGRAFI 17
Anda mungkin juga menyukai
- Dokumen Ukl Upl Galian C KudusDokumen46 halamanDokumen Ukl Upl Galian C Kudusagung tri100% (3)
- Rancangan Permen IUP OPkDokumen39 halamanRancangan Permen IUP OPkrichierismyBelum ada peringkat
- Makalah Izin Usaha PertambanganDokumen16 halamanMakalah Izin Usaha PertambanganJonathan Sims67% (3)
- Bab II - SalinDokumen20 halamanBab II - SalinRizkylintar LintaRizky BlinkstarD'LinstarBelum ada peringkat
- PLKH PERIZINAN Pertambangan 2Dokumen34 halamanPLKH PERIZINAN Pertambangan 2Firman Yuli NugrohoBelum ada peringkat
- Penggolongan Bahan Galian Menurut UU NoDokumen8 halamanPenggolongan Bahan Galian Menurut UU Nodicky_permana083091Belum ada peringkat
- Kuasa Pertambangan Genesa Bahan GalianDokumen9 halamanKuasa Pertambangan Genesa Bahan GalianTuremZhageBelum ada peringkat
- Sekilas Pertambangan IndonesiaDokumen26 halamanSekilas Pertambangan IndonesiaArif PramonoBelum ada peringkat
- BAB VI Indikasi Bahan Galian PemetaanDokumen6 halamanBAB VI Indikasi Bahan Galian PemetaanAndi AlfriadiBelum ada peringkat
- K02-Klassifikasi Sumberdaya MineralDokumen43 halamanK02-Klassifikasi Sumberdaya MineralFitri Indania SariBelum ada peringkat
- Makalah PLTDokumen15 halamanMakalah PLTAshabul KahfiBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen27 halamanBab IiextrimewijayaBelum ada peringkat
- Tugas Pengganti Final Lingkungan Pertambangan JoeDokumen32 halamanTugas Pengganti Final Lingkungan Pertambangan JoeAriel PatiungBelum ada peringkat
- Penggolongan Bahan GalianDokumen25 halamanPenggolongan Bahan GalianjokoBelum ada peringkat
- Bersih PNT Mineral Dan BatubaraDokumen21 halamanBersih PNT Mineral Dan BatubaraAndre KoichiBelum ada peringkat
- K03-Klassifikasi Sumberdaya MineralDokumen96 halamanK03-Klassifikasi Sumberdaya MineralAbel Fi ZarroBelum ada peringkat
- Pertambangan - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia BebasDokumen3 halamanPertambangan - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia BebasRehan ZamzamBelum ada peringkat
- Permen Iup Mineral Non Logam Dan Batuan - Bersih - CatDokumen35 halamanPermen Iup Mineral Non Logam Dan Batuan - Bersih - CatNopi Yudi PramonoBelum ada peringkat
- Manajemen TambangDokumen4 halamanManajemen Tambangabd raufBelum ada peringkat
- PP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan BatubaraDokumen57 halamanPP No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan BatubaraJoe ChrisBelum ada peringkat
- UNIKOM - Gilang Gumilang Ramadhan - 11. BAB IIDokumen24 halamanUNIKOM - Gilang Gumilang Ramadhan - 11. BAB IItatang abdulahBelum ada peringkat
- Ayu Budi Arti (r1d115021)Dokumen48 halamanAyu Budi Arti (r1d115021)Ayu Budiarti RahmanBelum ada peringkat
- Makalah Pengolahan Bahan GalianDokumen14 halamanMakalah Pengolahan Bahan GalianNandoBelum ada peringkat
- Alvianto - Tugas 1 Rekayasa Bahan Galian IndustriDokumen2 halamanAlvianto - Tugas 1 Rekayasa Bahan Galian IndustriAlvianto BorotodingBelum ada peringkat
- Yoel Dolofart Pesiwarissa - Tugas RBGIDokumen5 halamanYoel Dolofart Pesiwarissa - Tugas RBGIYoelBelum ada peringkat
- Penggolongan Mineral Logam Dan Non LogamDokumen7 halamanPenggolongan Mineral Logam Dan Non Logamnovi herlindaBelum ada peringkat
- Alvianto - Tugas 1 Rekayasa Bahan Galian Industri PDFDokumen2 halamanAlvianto - Tugas 1 Rekayasa Bahan Galian Industri PDFAlvianto BorotodingBelum ada peringkat
- Keb - Tambang Pert - 10Dokumen6 halamanKeb - Tambang Pert - 10Reza AbdillahBelum ada peringkat
- Tinjauan Hukum Regulasi Dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di DaerahDokumen33 halamanTinjauan Hukum Regulasi Dan Sistem Perizinan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di DaerahMuhammadIhsanBelum ada peringkat
- Pergub No 39 Tahun 2022Dokumen177 halamanPergub No 39 Tahun 2022Muchtar LubisBelum ada peringkat
- K02-Klassifikasi Sumberdaya MineralDokumen43 halamanK02-Klassifikasi Sumberdaya MineralIrvanBelum ada peringkat
- Permen ESDM 12 2011 TTG Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha An Dan Sistem Informasi Wilayah An MinerbaDokumen20 halamanPermen ESDM 12 2011 TTG Tata Cara Penetapan Wilayah Usaha An Dan Sistem Informasi Wilayah An MinerbaBurwanto PaelonganBelum ada peringkat
- Penggolongan Bahan Galian Menurut UndangDokumen3 halamanPenggolongan Bahan Galian Menurut Undangadellaocha069Belum ada peringkat
- Dokumen Ukl Upl Batu Gamping Bogorejo BloraDokumen42 halamanDokumen Ukl Upl Batu Gamping Bogorejo Bloraagung tri0% (1)
- UU Minerba (Perbandingan)Dokumen52 halamanUU Minerba (Perbandingan)shaaxoBelum ada peringkat
- Makalah Akuntansi & Pajak Pertambangan..Dokumen97 halamanMakalah Akuntansi & Pajak Pertambangan..Anonymous XG46hKtDa100% (2)
- Pertambangan 11Dokumen2 halamanPertambangan 11Oktafindo VerdichaBelum ada peringkat
- Prosedur Mendapatkan Izin Usaha Jasa PertambanganDokumen4 halamanProsedur Mendapatkan Izin Usaha Jasa PertambanganSam El Pakpahan100% (2)
- Bauksit (Koreksi)Dokumen8 halamanBauksit (Koreksi)rizkyoctadinata-1Belum ada peringkat
- Bab IiDokumen7 halamanBab Iiroyreinaldy11Belum ada peringkat
- Penggolongan Bahan GalianDokumen11 halamanPenggolongan Bahan Galianyusuf alpianBelum ada peringkat
- Prosedur Pengurusan Izin Usaha PertambanganDokumen9 halamanProsedur Pengurusan Izin Usaha Pertambanganarkent98Belum ada peringkat
- Materi EksplorasiDokumen7 halamanMateri EksplorasiEry FerdyanBelum ada peringkat
- K6 Izin PTMBG BatuanDokumen14 halamanK6 Izin PTMBG Batuananon_691150110Belum ada peringkat
- Al Mualim Tugas GeografiDokumen10 halamanAl Mualim Tugas Geografipermadibachri01Belum ada peringkat
- OdeGentaAS 4012011067 HKM4Dokumen20 halamanOdeGentaAS 4012011067 HKM4Gnta PutraBelum ada peringkat
- Kerangka Regulasi MinerbaDokumen7 halamanKerangka Regulasi Minerbarhes anastasia0% (1)
- Buku Batubara Ika KrisDokumen49 halamanBuku Batubara Ika KrisAyu Budiarti RahmanBelum ada peringkat
- Pokok Perbedaan Uu No 4 THN 2009 Dan No 11 THN 19667Dokumen22 halamanPokok Perbedaan Uu No 4 THN 2009 Dan No 11 THN 19667azar23Belum ada peringkat
- Pertambangan EmasDokumen9 halamanPertambangan EmasHamdy AlallahBelum ada peringkat
- P2 - Regulasi Tambang 2 - Ketentuan Umum PertambanganDokumen17 halamanP2 - Regulasi Tambang 2 - Ketentuan Umum PertambanganGuptaBelum ada peringkat
- 2.penggolongan Bahan Galian Dan Bahan Galian IndustriDokumen34 halaman2.penggolongan Bahan Galian Dan Bahan Galian IndustriINDIBelum ada peringkat
- BAB I MagnesitDokumen11 halamanBAB I MagnesitMas'ulNandaSusantoBelum ada peringkat
- Slide Kuliah UmumDokumen14 halamanSlide Kuliah UmummirzaBelum ada peringkat
- Bab II - SalinDokumen20 halamanBab II - SalinRizkylintar LintaRizky BlinkstarD'LinstarBelum ada peringkat
- Geol I StrikDokumen2 halamanGeol I StrikRizkylintar LintaRizky BlinkstarD'LinstarBelum ada peringkat
- GSP Acr 7Dokumen8 halamanGSP Acr 7Rizkylintar LintaRizky BlinkstarD'LinstarBelum ada peringkat
- Acara 3 KaDokumen9 halamanAcara 3 KaRizkylintar LintaRizky BlinkstarD'LinstarBelum ada peringkat