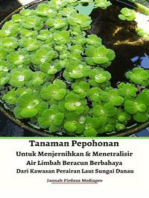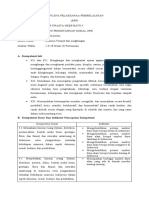Bahan Ajar Pengelolaan SDA
Bahan Ajar Pengelolaan SDA
Diunggah oleh
Lyra NindyahHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Bahan Ajar Pengelolaan SDA
Bahan Ajar Pengelolaan SDA
Diunggah oleh
Lyra NindyahHak Cipta:
Format Tersedia
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Satuan Pendidikan : SMA
Mata Pelajaran : Geografi
Kelas/Semester : XI/Ganjil
Materi Pokok : Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia
Kompetensi Inti
KI3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan
kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena
dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang
spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.
KI4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait
dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak
secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai kaidah
keilmuan.
Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi
3.3 Menganalisis Pertemuan 1
sebaran dan 3.3.1 Mengklasifikasikan sumber daya alam
pengelolaan sumber 3.3.2 Menggambarkan persebaran sumberdaya alam
daya kehutanan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata
pertambangan, di Indonesia
kelautan, dan 3.3.3 Menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan,
pariwisata sesuai pertambangan, kelautan, dan pariwisata di
prinsip-prinsip Indonesia.
pembangunan Pertemuan 2
berkelanjutan. 3.3.4 Menjelaskan konsep AMDAL dalam pembangunan
3.3.5 Menguraikan prosedur AMDAL dalam
pembangunan
Pertemuan 3
3.3.6 Menganalisis bentuk-bentuk pemanfaatan SDA
dengan prinsip pembangunan berkelanjutan
3.3.7 Mendeskripsikan tujuan pemanfaatan SDA dengan
prinsip pembangunan berkelnjutan
4.3 Membuat peta 4.3.1 Membuat peta persebaran sumber daya kehutanan,
persebaran pertambangan, kelautan, dan pariwisata Indonesia
sumber daya 4.3.2 Merangkum informasi potensi sebaran sumber daya
kehutanan, kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata
pertambangan, Indonesia
kelautan, dan
pariwisata di
Indonesia.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 1
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Tujuan Pembelajaran:
Setelah mempelajari materi pengelolaan sumber daya alam Indonesia, peserta didik kelas
XI SMA semester satu diharapkan mampu:
a. Mengklasifikasi sumber daya alam di Indonesia
b. Mengidentifikasi potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan,
pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia
c. Menjelaskan peran analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dalam
pembangunan
d. Memahami pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan.
Dengan rasa ingin tahu, tanggung jawab, diiplin selama proses pembelajaran, bersikap
jujur, santun, percaya diri, dan pantang menyerah, memiliki sikap responsif dan proaktif,
serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 2
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
MATERI AJAR
Pertemuan 1
Indikator:
3.3.1 Mengklasifikasikan sumber daya alam.
3.3.2 Menganalisis potensi sumber daya alam kehutanan, pertambangan,
kelautan, dan pariwisata di Indonesia.
3.3.3 Menggambarkan persebaran sumberdaya alam kehutanan,
pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia
A. Pengertian Sumber Daya
Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur
tertentu dalam kehidupan. Sumber daya bisa berupa fisik, bisa berupa non-fisik. Dalam
Undang-Undang republik Indonesia No 4 tahun 1982, disebutkan bahwa sumber daya
adalah unsur lingkungan hidup, yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam
hayati, sumber daya alam non-hayati, dan sumber daya buatan.
Sejak bumi dihuni, manusia dan bentuk kehidupan lainnya bergantung pada hal-
hal yang ada di alam untuk bertahan hidup. Makhluk hidup memanfaatkan air (air tawar
dan air laut), tanah, batu, pepohonan (hutan), hewan, bahan bokar fosil dan mineral.
Semua itu disebut dengan sumber daya alam yang merpakan dasar kehidupan di bumi.
Sumber daya alam adalah bahan baku bermanfaat yang dihasilkan dari bumi.
Sumber daya alam terbentuk secara alami, artinya, manusia tak dapat menciptakan
sumber daya alam. Manusia hanya bisa mengganti dan memodifikasi sumber daya alam.
B. Klasifikasi Sumber Daya
1. Sumber Daya Alam (SDA)
Sumber daya alam adalah bahan baku bermanfaat yang dihasilkan dari bumi.
Sumber daya alam terbentuk secara alami, artinya, manusia tak dapat menciptakan
sumber daya alam. Manusia hanya bisa mengganti dan memodifikasi sumber daya alam.
Beberapa sumber daya alam dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara. Pengklasifikasian
sumber daya alam dapat digolongkan berdasarkan beberapa hal, yaitu berdasarkan bagian
atau bentuk yang dimanfaatkan (potensi), berdasarkan pembentukannya atau sifat
kelestariannya, berdasarkan jenisnya, dan berdasarkan nilai kegunaannya.
a. Sumber Daya Alam berdasarkan Pemanfaatan
Berdasarkan potensinya, sumber daya alam dapat dikasifikasikan sebagai berikut:
1) Sumber Daya Alam Materi
Sumber daya alam materi yaitu sumber daya alam yang berbentuk materi, yang
dimanfaatkan oleh manusia adalah materi sumber daya alam itu sendiri. Contoh: mineral
magnetit, hematit, limonit, siderit, dan pasir kuarsa yang dapat dilebur menjadi besi/baja
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, di antaranya untuk kerangka beton,
kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 3
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
2) Sumber Daya Energi
Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang berguna untuk menghasilkan
energi. Contoh: bahan bakar fosil, Bahan bakar minyak (bensin, solar, minyak tanah),
batu bara, gas alam, dan kayu bakar merupakan sumber daya alam energi, karena manusia
menggunakan energinya untuk memasak, menggerakkan kendaraan, dan mesin industri.
3) Sumber Daya Ruang
Sumber daya alam ruang, yaitu tempat yang diperlukan manusia dalam hidupnya.
Makin besar kenaikan jumlah penduduk, maka sumber daya alam ruang makin sempit
dan sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk areal peternakan,
pertanian, perikanan, ruang tempat tinggal, ruang arena bermain anak-anak dan
sebagainya.
b. Sumber Daya Alam Berdasarkan Pembentukannya atau Sifat Kelestariannya
Berdasarkan pembentukannya, sumber daya alam dapat diklasifikasikan sebagai
berikut:
1) Sumber Daya Alam yang Dapat Dipebarui (Renewable Resources)
Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak akan
habis, karena bagian-bagian yang telah terpakai dapat diganti dengan yang baru. Sumber
daya alam yang dapat diperbarui jika digunakan secara terus-menerus maka dalam jangka
waktu tertentu akan kembali seperti sediakala dan dapat digunakan lagi untuk diambil
manfaatnya. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah udara, angin, tenaga
air terjun, tanah, sinar matahari, tumbuh-tumbuhan, dan hewan.
Gambar 1. Air, sumber daya alam yang dapat diperbaharui
Sumber : https://pixabay.com/id/iguaz%C3%BA-falls-air-terjun-water-wall-377990/
2) Sumber Daya Alam yang Tidak Dapat Diperbarui (Unrenewable Resources)
Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam jika
digunakan secara terus-menerus, maka lama kelamaan akan habis dan tidak dapat
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 4
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
dihasilkan sendiri oleh manusia. Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui
adalah berbagai barang tambang, mineral logam, mineral bukan logam dan mineral
penghasil energi, timah, besi, bauksit, batu bara, dan minyak bumi.
c. Sumber Daya Alam Berdasarkan Jenis
Sumber daya alam berdasarkan jenisnya dapat dikelompokkan atas sumber daya
alam nonhayati (abiotik) dan sumber daya alam hayati (biotik).
1) Sumber Daya Alam Nonhayati (Abiotik)
Sumber daya alam abiotik adalah sumber adya alam fisik berupa benda-benda mati
di lingkungan alam fisik. Contohnya tanah, air, udara, batuan, dan mineral. Sumber daya
alam nonhayati ada yang dapat diperbaharui dan ada juga yang dapat diperbaharui.
Contoh sumber daya alam abiotik yang dapat diperbaharui adalah air dan udara. Contoh
sumber daya alam nonhayati yang tidak dapat diperbaharui adalah mineral.
2) Sumber Daya Alam Hayati
Gambar 2. Sumber Daya Alam Hayati; Nabati dan Hewani
Sumber: Dok. Pribadi
Sumber daya hayati adalah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, yaitu
hewan dan tumbuhan. Sumber daya alam tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya nabati,
sedangkan sumber daya hewan disebut sumber daya hewani.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk
mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang
mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju
tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM adalah bagian integral dari sistem yang
membentuk suatu organisasi yang megelola Sumber Daya Alam.
3. Sumber Daya Buatan (SDB)
Sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan dayagunanya
untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kepentingan pertahanan negara. Pemanfaatan
sumber daya buatan akan mengurangi eksploitasi sumber daya alam sehingga tetap dapat
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 5
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
menjaga keseimbangan ekosistem suatu wilayah. Sumber daya buatan merupakan
pengembangan sumber daya alam untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan/atau
kemampuan daya dukungnya. Contohnya adalah hutan buatan, waduk, dan lain-lain.
C. Potensi dan Persebaran Sumber Daya Alam Indonesia
1. Sumber Daya Alam Kehutanan
Hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan
atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Potensi sumber
daya hutan di wilayah Indonesia sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3%
dari seluruh luas wilayah Indonesia (Kemenhut, 2011). Luas hutan yang besar tersebut
saat ini masih dapat dijumpai di Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumatra. Di Jawa,
luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian
dan permukiman penduduk. Sementara itu, di Sumatera dan Kalimantan banyak dijumpai
alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan.
Sumber Daya Kehutanan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa
hamparan lahan yang berisi SDA hayati yang didominasi pepohonan dalam dalam
persekutuan alam dan lingkungannya, yag satu dengan lalinnya tidak dapat dipisahkan.
Hutan sebagai suatu ekosistem tidak hanya menyimpan sumberdaya alam berupa kayu,
tetapi masih banyak potensi non kayu yang dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat
melalui budidaya tanaman pertanian pada lahan hutan.
Gambar 3. Hutan
Sumber: http://leuserconservation.org/wp-content/uploads/2017/03/hutan-sumatera.jpg
Kawasan hutan adalah wilayah hutan tertentu, yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Penetapanini
dilakukan untuk menjamin kepastian hukum mengenai status kawasan hutan, letak batas
dan luas suatu wilayah tertentu yang sudah ditunuk sebagai kawasan hutan menjadi
kawasan hutan tetap. Kawasan Hutan Indonesia ditetapkan oleh Mentri Kehutanan dalam
bentuk surat Keputusan Mentri Kehutanan tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 6
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Perairan Provinsi. Penunjukan kawasan hutan juga mencakup kawasn perairan yang
menjadi bagian dari Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).
Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan
dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi.
1) Hutan produksi, yang dikelola untuk menghasilkan kayu ataupun hasil hutan bukan
kayu. Hutan kayu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, bahan baku kertas, bahan
baku industri meubel dan lain-lain. Diantara jenis kayu yang bernilai ekonomis
tinggi adalah a) kayu jati yang tersebar di Pulau Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, b)
kayu meranti yang tersebar di hutan Kalimantandan Sumatera, c) kayu cendana,
tersebar di Nusa Tenggara dan hutan-hutan daerah Jawa, d) kayu akasia, tersebar di
hutan-hutan Jawa Barat. Hasil hutan non kayu berupa buah, madu, kareat, rempah-
rempah, rotan, dan sagu.
a. Hutan produksi tetap (HP). Berdasarkan statistik Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan tahun 2015, luas hutan produksi tetap sekitar
29.250.783,10 ha
b. Hutan produksi terbatas (HPT), merupakan hutan yang hanya dapat diekploitasi
dengan cara tebang pilih. Berdasarkan statistik Kementrian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tahun 2015, luas hutan produksi tetap sekitar 26.798.382,01 ha.
c. Hutan produksi yang dikonversi (HPK). Hutan produksi yang dapat dikonversi
adalah kawasan hutan produksi yang dapat diubah untuk kepentingan usaha
pekebunan dan tidak dipertahankan sebagai hutan tetap. Hutan jenis ini juga
dicadangkan sebagai pengembangan transmigrasi, pemukiman, pertanian, dan
perkebunan. Berdasarkan statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tahun 2015, luas hutan produksi tetap sekitar 12.942.295,24 ha.
2) Hutan lindung, dikelola untuk mengelola tanah dan air Hutan suaka alam, dikelola
untuk melindungi kekayaan keanekaragaman hayati atau keindahan alam.
Berdasarkan statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015,
luas hutan produksi tetap sekitar 29.673.382,37 ha.
3) Hutan konservasi, yakni kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki
fungsi perlindungan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
Berdasarkan statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015,
luas hutan produksi tetap sekitar 22.108.630,99 ha. Hutan konservasi terdiri dari:
a. Kawasan suaka alam berupa cagar Alam (CA) dan suaka Margasatwa (SM),
adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang
mempunyai funsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman
tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah
sistem penyangga kehidupan.
b. Kawasan pelestarian alam,berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan raya
(THR), dan Taman Wisata Alam (TWA). Adalah kawasan dengan ciri khas
tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok
perlindungan sistem penyangga kehidupan pengaweetan keanekaragaman jenis
tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati
dan ekosistemnya.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 7
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
c. Taman Buru (TB), adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata
berburu.
Ada berbagai jenis hutan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut:
a. Hutan hujan tropis, adalah hutan belantara dengan tumbuhan yang sangat bervariasi.
Tingkat kerapatan tumbuhannya cukup tinggi seingga sinar matahari tidak dapat
menembus permukaaan tanah. Hutan ini banyak terdapat di daerah dengan curah
hujan tahunan minimum antara 1.750 mm-2.000 mm, dan rata-rata temperatur
bulanan >18o C sepanjang tahun. Terdapat di Kalimantan, Sumatera, dan Papua.
b. Hutan musim, yaitu hutan campuran yng terdapat di daerah dengan cuah hujan
tahunan antara 1.500-4.000 mm, yang dikombinasikan degan bulan-bulan kering
selama 4-6 bulan. Pada saat musim kemarau, pohon-pohon menggugurkan daunna
agar dapat menyesuaikan diri dan berkembang. Pohon yang terdapat di hutan musim
adalah pohon jati, bungur, kesambi dan lain-lain. Hutan ini terdapat di Indonesia
bagian tengah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara.
c. Hutan hujan pegunungan, terdapat pohon-pohon yang selalu menghijau. Kerapatan
tumbuhannya cukup tinggi. Pohon-pohonnya diantara lain jemuju, pinus, rasamala,
dan damar. Hutan ini tersebar di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua.
d. Hutan sabana, adalah hutan yang banyak ditumbuhi kelompok semak belukar yang
diselingi padang rumput dengan jenis tanaman berduri. Tumbuhannya antara lain
kaktus, Saesalpinae, Leguminosae, dan Euphorbiaceae. Hutan sabana dapat ditemuii
di Flores, Sumba, dan Timor.
e. Hutan rawa, merupakan hutan yang tumbuh pada tanah aluvial yang selalu
tergenang air tawar. Tumbuhannya berupa pohon berakar lutut yang tunasnya
terendam air. Hutan ini banyak terdapat di sepanjang pantai timur Sumatera, dataran
rendah Kalimantan, dan Papua.
f. Hutan mangrove, disebut juga hutan pantai, hutan pasang surut, hutan payau, atau
hutan bakau. Hutan mangrove terdapat di dataran rendah pantai Sumatera,
Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua.
g. Hutan gambut, terdapat di daerah beriklim tipe A atau B menurut klasifikasi
Koppen. Hutan ini tumbuh di atas tumpukan bahan organik yang tergantung pada
turunnya hujan. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
Papua, dan Riau.
h. Hutan lumut. Lumut di hutan ini tidak hanya menutupi permukaan tanah, tetapi juga
batang-batang pohon. Hutan lumut terdapat pada ketinggian >.1000 mdpl di Papua,
Sumatera, Kalimantan, sulawesi, dan Jawa.
Luaas daratan kawasan Indonesia pada tahun 2015 sekitar 120.773.441,72 ha. Hutan ini
tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Hutan yang terluas terdapat di Pulau Papua.
Tabel 1. Sebaran kawasan hutan di Indonesia pada tahun 2015
Provinsi Jumlah Luas Daratan Kawasan Hutan (dalam ha)
Aceh 3.557.928
Sumatera Utara 3.055.794
Sumatera Barat 2.342.894
Riau 5.499.693
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 8
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Jambi 2.098.535
Sumatera Selatan 3.418.194
Bengkulu 924.631
Lampung 1.004,735
Kep. Bangka Belitung 654.562
Kep. Riau 382.131,73
DKI Jakarta 475,45
Jawa Barat 816.603
Jawa Tengah 647.133
DI Yogyakarta 16.819,52
Jawa Timur 1.357.640
Banten 202.787
Bali 127,271,01
NTB 1.035.838
NTT 1.528.269
Kalimantan Barat 8.198.656
Kalimantan Tengah 12.697.165
Kalimantan Selatan 1.779.982
Kal. Timur dan Utara 13.855.833
Selawesi Utara 694.939
Sulawesi Tengah 3.934.568
Sulawesi Selatan 2.118.992
Sulawesi Tenggara 2.326.419
Gorontalo 824.668
Sulawesi Barat 1.092.376
Maluku 3.910.409
Maluku Utara 2.515.220
Papua Barat 8.784.787
Papua 29.368.482
Total 120.773.441,71
Sumber: Statistik Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015
Salah satu hasil hutan Indonesia adalah kayu bulat, sebanyak 43,87 juta ton3 pda tahun
2015. Beberapa jenis kayu bulat yang tersebar produksinya adalah kayu akasia, meranti,
rimba campuran, sengon, eukaliptus, jati, karet, mahoni, dan merbau. Selain kayu bulat,
Indonesia juga menghasilkan kayu olahan. Jenia kayu olahan utama yang ada di setiap
pulau di Indenesia adalah sebagai berikut:
Tabel 2. Jenis kayu olahan utama di setiap pulau
No Pulau Jenis Kayu Olahan
1 Sumatera Cip dan partikel, bubur kayu, kayu gergajian, dan papan serat
2 Jawa Kayu gergajian, barecore, veener, dan kayu lapis
3 Basi dan Nusa Kayu gergajian
Tenggara
4 Kalimantan Cip dan partikel, kayu lapis, kayu gergajian, dan veneer
5 Sulawesi Kayu lapis, veneer, kayu gergajian, dan moulding/dowel
6 Maluku dan Kayu lapis, kayu gergajian, veneer, dan moulding/dowel
Papua
Sumber: Statistik Produksi Kehutanan tahun 2015
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 9
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Hutan Indonesia juga memiliki produksi hasil non kayu, seperti bambu, rotan, madu, nira,
getah pinus, getah karet, sagu, kemiri, daun kayu putih, jamur, dan asam.
Tabel 3. Sebaran produksi hasil hutan non kayu tahun 2015
No Pulau Jenis Hasil Hutan Non Kayu
1 Sumatera Rotan, nira, bambu, getah karet, dan sagu
2 Jawa Bambu, madu, getah pinus, daun kayu putih
3 Basi dan Nusa Bambu, kemiri, madu, asam, dan pinang
Tenggara
4 Kalimantan Gaharu, rotan, getah karet, sarang burung walet, dan madu
5 Sulawesi Bambu, nira, rotan, madu, dan getah pinus
6 Maluku dan Gambir, gaharu, kulit masohi, damar, dna daun kayu putih
Papua
Sumber: Statistik Produksi Kehutanan tahun 2015
2. Sumber Daya Alam Pertambangan
Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian,
penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian.
Menurut Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 pengelompokan secara rinci bahan
galian adalah sebagai berikut, yaitu:
a) Bahan galian golongan A atau bahan galian strategis, terdiri dari:
1) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
2) Bitumen padat, aspal;
3) Antrasit, batu bara, batu bara muda;
4) Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
5) Nikel, kobalt;
6) Timah.
b) Bahan galian golongan B atau bahan galian vital, terdiri dari:
1) Besi, mangan, molibdenum, khrom, walfran, vanadium, titanium;
2) Bauksit, tembaga, timbal, seng;
3) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
4) Arsen, antimon, bismut;
5) Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
6) Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
7) Kriolit, flouspar, barit;
8) Yodium, brom, khlor, belerang.
c) Bahan galian golongan C atau bahan galian industri, terdiri dari:
1) Nitrat, phosphate, garam batu;
2) Asbes, talk, mike, grafit, magnesit;
3) Yarosit, leusit, tawas (alam), oker;
4) Batu permata, batu setengah permata;
5) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonite;
6) Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanah diatome;
7) Marmer, batu tulis;
8) Batu kapor, dolomit, kalsit;
9) Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 10
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Persebaran barang tambang di Indonesia adalah sebagai berikut:
a) Minyak Bumi dan Gas
Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak
dipakai untuk keperluan industri, tranportasi, dan rumah tangga.Saat ini telah
dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis
tumbuhan dan sumber energi lainnya, seperti energi matahari, angin, dan gelombang.
Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya.
Gambar 4. Peta sebaran minyak bumi di Indonesia
Sebaran penghasil minyak pada sejumlah pulau di Indonesia sebagai potensi
sumber daya tambang di Indonesia dapat dilihat pada data berikut ini.
1) Sumatra: Pereula dan Lhokseumawe (Aceh Darussalam), Sungai Pakning dan
Dumai (Riau), Plaju, Sungai Gerong dan Muara Enim (Sumatra Selatan)
2) Jawa: Jati Barang Majalengka (Jawa Barat), Wonokromo, Delta (Jawa Timur),
Cepu, Cilacap (Jawa Tengah).
3) Kalimantan: Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu dan Sungai Mahakam
(Kalimantan Timur), Rantau, Tanjung, dan Amuntai (Kalimantan Selatan).
4) Maluku : Pulau Seram dan Tenggara
5) Papua : Klamono, Sorong, dan Babo
b) Batu Bara
Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah
mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya
terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen.Batu bara digunakan sebagai sumber
energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan
untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga (memasak), pembakaran
pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kapur, bijih besi dan baja, industri
kimia, dan lain-lain. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan
dan Sumatra.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 11
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Gambar 5. Tiga daerah cadangan batu bara tersebesar di Indonesia; Sumatera
Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur
Sumber: Indonesiainvestment.com
Potensi batu bara sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia di kedua
pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di
Kalimantan Timur (Lembah Sungai Berau dan Samarinda), Sumatra Barat (Ombilin
dan Sawahlunto), Sumatra Selatan (Bukit Asam dan Tanjung Enim).
c) Bauksit
Bauksit merupakan bahan yang heterogen, yang mempunyai mineral dengan
susunan terutama dari oksida aluminium. Bauksit merupakan kelompok mineral
aluminium hidroksida yang dalam keadaan murni berwarna putih atau kekuningan.
Aluminium ini tahan panas, kuat namun lentur dan mudah dibentuk. Untuk onderdil
otomotif, perkapalan dan industri pesawat terbang, menggunakan bauksit secara
massif. Potensi dan cadangan endapan bauksit terdapat di Pulau Bintan, Kepulauan
Riau, Pulau Bangka, dan Pulau Kalimantan.
d) Biji Besi
Biji besi merupakan salah satu unsur yang paling sering dimanfaatkan dalam
kehidupan sehari – hari. Bijih besi dilebur dan dicampur dengan unsur lain lalu
kemudian menjadi banyak jenis – jenis besi. Biji besi dimanfaatkan untuk bahan
baku pemebuatan besi baja dan kawat baja, bahan dasar pembuatan tiang rambu lalu
lintas dan lampu penerangan jalan, bahan pembuatan besi tuang, besi tempa,
pembuatan baja lunak, dan baja sedang yang kemudian akan diolah menjadi produk
yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.
Aktivitas penambangan biji besi sebagai potensi sumber daya tambang di
Indonesia dapat ditemukan di Cilacap (Jawa Tengah), Sumatra, Lombok,
Yogyakarta, Gunung Tegak (Lampung), Pegunungan Verbeek (Sulawesi Selatan),
dan Pulau Sebuku (Kalimantan Selatan).
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 12
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
e) Timah Putih
Timah merupakan logam dasar terkecil yang diproduksi, yaitu kurang dari
300.000 ton per tahun, apabila dibandingkan dengan produksi aluminium sebesar 20
juta ton per tahun. Timah putih merupakan unsur langka, sebagian besar (80%)
timah putih dunia dihasilkan dari cebakan letakan (aluvial), sekitar setengah
produksi dunia berasal dari Asia Tenggara. Mineral ekonomis penghasil timah putih
adalah kasiterit (SnO2), meskipun sebagian kecil dihasilkan juga dari sulfida seperti
stanit, silindrit, frankeit, kanfieldit dan tealit. Timah di Indonesia adalah di daerah
jalur timah yang membentang dari Pulau Kundur sampai Pulau Belitung dan
sekitarnya. Potensi timah putih di Indonesia tersebar sepanjang kepulauan Riau
sampai Bangka Belitung, serta terdapat di daratan Riau yaitu di Kabupaten Kampar
dan Rokan Ulu. Sumber daya timah putih yang telah diusahakan merupakan cebakan
sekunder, baik terdapat sebagai tanah residu dari cebakan primer, maupun letakan
sebagai aluvial darat dan lepas pantai.
f) Nikel
Nikel ditemukan oleh A. F. Cronstedtpada tahun 1751, merupakan logam
berwarna putih keperak-perakan yang berkilat, keras dan mulur, tergolong dalam
logam peralihan, sifat tidak berubah bila terkena udara, tahan terhadapoksidasi dan
kemampuan mempertahankan sifat aslinya di bawah suhu yang ekstrim (Cotton dan
Wilkinson, 1989). Nikel digunakan dalam berbagai aplikasi komersial dan industri,
seperti :pelindung baja (stainless steel), pelindung tembaga, industri baterai,
elektronik, aplikasi industri pesawat terbang, industri tekstil, turbin pembangkit
listrik bertenaga gas, pembuat magnet kuat,pembuatan alat-alat laboratorium
(nikrom), kawat lampu listrik, katalisator lemak, pupuk pertanian, dan berbagai
fungsi lain (Gerberding J.L., 2005).
Tambang Nikel di Indonesia terdapat di Kalimantan Barat, Maluku, Papua,
Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
g) Mangan
Mangan banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai
kering, keramik, gelas, dan sebagainya. Mangan sebagai potensi sumber daya
tambang di Indonesia ditambang di daerah Tasikmalaya (Jawa Barat), Kiripan
(Yogyakarta), dan Martapura (Kalimantan Selatan).
Selain barang tambang yang telah disebutkan diatas, masih banyak lagi sumber daya
mineral yang ditemukan di Indonesia. Sebaran mineral strategis di Indonesia dapat dilihat
pada peta berikut:
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 13
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Gambar 6. Peta sebaran mineral strategis di Indonesia
Sumber: http://webmap.psdg.bgl.esdm.go.id/
Sumber daya alam tambang termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang tidak
bisa diperbarui.Sehingga jika kelak sumber daya alam ini habis, maka kita tidak bisa
memanfaatkannya lagi.Oleh karena itu, tindakan yang tepat dalam pemanfaatan dan
pengelolaan sumber daya alam tambang sangatlah penting.
Kegiatan pertambangan meliputi beberapa kegiatan yakni observasi, eksplorasi dan
eksploitasi di daerah litosfer maupun di permukaan bumi.
a) Observasi merupakan kegiatan pengamatan ke daerah yang diperkirakan secara
teoritis mempunyai sumber tambang.
b) Ekplorasi merupakan kegiatan penyelidikan tentang keadaan mineral tambang
beserta kemungkinannya untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Kegiatan eksplorasi
terdiri dari 2 macam yakni: 1) penyelidikan tentang banyaknya mineral,
persebarannya serta keuntungan ekonomisnya bila dilakukan pengelolaan, 2)
Menentukan syarat teknis bilamana akan dilakukan ekploitasi.
c) Eksploitasi merupakan kegiatan pengambilan barang tambang. Eksploitasi bisa kita
sebut juga sebagai penambangan. Dalam melakukan eksploitasi harus
memperhatikan betul-betul tentang teknis dan ketentuan lain yang berlaku.
3. Sumber Daya Alam Kelautan
Indonesia memiliki laut dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya.
Sumber daya laut adalah unsur hayati dan nonhayati yang terdapat di wilayah laut.
Potensi sumberdaya laut Indonesi atidak hanya berupa ikan, tetapi juag bahan
tambag seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, dan lain-lain yang berada di
bawah permukaan laut.
a) Perikanan
Indonesia memiliki potensi sumber daya perikana yang sangat baik dari segi
jumlah dan keanekaragamannya. Potensi lestari (penangkapan ikan tangkap yang
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 14
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
memungkinkan untuk regenerasi sehingga populasi ikan tidak berkurang) sumber
daya perikanan Indoenesia sekitar 6,4 juta ton per tahun. Menurut Departemen
Kelautan dan Perikanan, potesi perikanan laut Indonesia terdiri atas perikanan
pelagis yang tersebar hampir di semua bagian laut Indoensia. Di Indonesia bagian
barat, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Di Indonesia
bagian timur, bayak ditemukan ikan pelagis besar, cakalang, dan tuna. Selain ikan
yang tersedia di lautan, penduduk Indonesia juga banyak membudidayakan ikan,
terutama di daerah pesisir dengan jenis ikan bandeng dan udang.
b) Hutan Mangrove
Adalah hutan khas yang hidup di sepanjang pantai di daerah tropis yang
dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Banyak terdapat di pesisir timur Sumatera,
pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua.Ada dua fungsi hutan mangrove
sebagai potensi sumber daya laut di indonesia yaitu fungsi ekologis dan ekonomis.
Gambar 7. Hutan mangrove di Pulau Siberut, Mentawai, Sumatera Barat
Sumber: wordpress.com
Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat (tempat hidup) binatang
laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang
lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Fungsi
ekonomis hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu pepohonan dan makhluk
hidup yang ada di dalamnya.Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan
kayu bakar atau bahan pembuat arang. Kayu bakau juga dapat dijadikan bahan
pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 15
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang
biak dengan baik di wilayah ini.
c) Terumbu Karang
Adalah terumbu (batuan sedimen kapur di laut) yang terbentuk dari kapur yang
sebagian besar dihasilkan dari koral (binatang yang menghasilkan kapur untuk
kerangka tubuhnya). Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan
membentuk karang.
Gambar 8. Terumbu karang
Sumber: goodnewsfromindonesia.id
Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu
karang terluas di dunia. Kekayaan terumbu karang Indonesia tidak hanya dari
luasnya, akan tetapi juga keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya.
Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di
indonesia juga yang tertinggi di dunia. Di dalamnya terdapat 2.500 jenis ikan, 2.500
jenis moluska, 1.500 jenis udang-udangan, dan 590 jenis karang.
Manfaat terumbu karang tersebut adalah manfaat ekonomi, manfaat ekologis, dan
manfaat sosialekonomi. Manfaat ekonomi adalah sebagai sumber makanan, obat-
obatan, dan objek wisata bahari. Manfaat ekologis diantaranya mengurangi
hempasan gelombang pantai yang dapat berakibat terjadinya abrasi. Manfaat sosial
ekonomi sebagai sumber perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan para
nelayan. Terumbu karang juga dapat menjadi daya tarik objek wisata yang dapat
meningkatkan pendapatan penduduk sekitar dari kegiatan pariswisata
Sebaran terumbu karang banyak ditemukan di bagian tengah wilayah Indonesia
seperti di Sulawesi, Bali, Lombok, dan Papua.Konsentrasi terumbu karang juga
ditemukan di Kepulauan Riau, pantai barat dan ujung barat Sumatra.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 16
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
d) Lamun
Adalah tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup
terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur di daerah terbuka pasang surut dan
perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang
mati, dengan kedalaman sampai empat meter. Lamun dapat membentuk suatu
padang lamun. Padang lamun tersebar di laut perairan Indonesia. Manfaat lamun di
lingkungan perairan dangkal adalah sebagi produsen primer, habitat biota,
penangkap sedimen, dan pendaur zat hara.
Gambar 9. Lamun
Sumber: m.viva.co.id
4. Sumber Daya Alam Pariwisata
Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan,
pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas
serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan
pemerintah daerah. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh
seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan
rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang
dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
Dalam lingkup ASEAN, wisata Indonesia berada diperingkat empat setelah
Singapura, Malaysia, dan Thailand. Potensi pariwisata Indonesia adalah sebagai
berikut:
a. Wisata alam, adalah bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang
memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik alami maupun setelah adanya
usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan
lingkungan alam, baik di wilayah perairan laut (seperti bentang pesisir pantai,
bentang laut, kolam air, dan dasar laut), maupun di wilayah daratan
(pegunungan, hutan alam/taman nasional/taman wisata alam/taman hutan raya,
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 17
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
perairan sungai dan danau, perkebunan, pertanian, serta bentang alam kgusus
seperti gua, karst, dan padang pasir.
b. Wisata budaya adalah perjalanan yang dilakukan untuk memperlus pandangan
hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negri untuk
mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup,
serta kebudayaan dan seni. Contoh objek wisata budaya adala situs purbakala
dan budaya(candi, bangunan sejarah, keraton dan kota tua), museum, dan
perkampungan tradisional (dengan adat dan tradisi budaya masyarakat yang
khas)
c. Wisata buatan, adalah kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan
objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata
buatan mencakup wisata MICE (pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran),
wisata olahraga, dan wisata terintegrasi. Contoh objek wisata buatan antara lain
fasilitas rekreasi dan hiburan/taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu,
serta fasilitas rekreasi dan olahraga.
Gambar 10. Lembah Harau, Payakumbuh. Salah satu tujuan wisata alam Sumatera
Barat
Sumber: http://www.lihat.co.id/wisata/lembah-harau-payakumbuh-sumbar.html
Wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan tidak berdiri sendiri. Ketiga tipe
objek wisata ini tersebar di seluruh Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2010-
2025, perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata nasional mencakup:
a. Lima puluh destinasi pariwisata nasional (DPN) yang tersebar di 33 provinsi.
Destinasi tersebut berskala nasional.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 18
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
b. Delapan puluh delapan kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) yang
tersebar di lima puluh DPN. Kawasan strategis pariwisata nasioanl adalah
kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi
pengembangan pariwisata nasional yag memiliki pengaruh penting dalam
berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, pemberdayaan sumber daya alam,
daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan
Gambar 11. Peta sebaran 50 destinasi pariwisata nasional, 88 kawasan strategis
perkembangan pariwisata nasional, dan 222 kawasan pengembangan
pariwisata nasional
Sumber: wordpress.com
Persebaran beberapa objek wisata yang ada di Indonesia antara lain:
a) Pulau Sumatera
Taman Nasional Gunung Leuser, Danau Laut Tawar, Rantau Prapat, Danau
Toba, Brastagi, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Benteng Fort de Kock,
Lembah Anai, Danau Ranau, Suaka Alam Way Kambas, dan Benteng
Marlborough.
b) Pulau jawa
Gunung Tangkuban Perahu, Maribaya, Pangandaran, Pelabuhan Ratu, Museum
Geologi, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Museum Satria Mandala,
Museum Gajah, Monumen Nasional, Kebun Binatang Ragunan, Planetarium,
Dataran Tinggi Dieng, Batu Raden, Gua Jatijajar, Candi Borobudur,
Prambanan, Keraton Jogja, Kota Gede, Pantai Parangtritis, Kaliurang, Makam
Imogiri, Gunung Bromo-Tengger, Taman Nasional Baluran, dan Pemandian
Tretes.
c) Bali
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 19
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Pantai Kuta, Legian, Tanah Lot, Danau Batur, Klungkung, Pura Besakih,
Daerah Trunyan, dan berbagai macam kesenian.
d) Kalimantan
Pantai Pasir Panjang, Danau Riam Kanan, Museum Lambung Mangkurat,
Istana Kesultanan Sambas, Taman Nasional Tanjung Puting, dan masyarakat
Dayak.
e) Nusa Tenggara
Gunung Tambora, Taman laut Gili Air, Taman Nasional Komodo, dan Danau
Kelimutu.
f) Sulawesi
Taman Laut Bunaken, Danau Tondano, Tana Toraja, Suaka marga satwa Anoa
dan burung Maleo, Mesjid tua Palopo, Taman wisata Renboken, dan Pantai
Losari.
g) Papua
Danau Sentani, Gugusan pulau Raja Ampat, Pantai Koren, Hutan wisata Supiori
Tanjung Kasuari, Tugu Pepera, Tugu peninggalan gugurnya Yos Sudarso, dan
lokasi bekas markas Jendral Doglas Mc. Arthu
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 20
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Pertemuan 2
Indikator:
3.3.4 Menjelaskan konsep AMDAL dalam pembangunan
3.3.5 Menguraikan prosedur AMDAL dalam pembangunan
A. Konsep Amdal
Amdal merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan
tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan perhubahan
terhadap lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah keseluruan unsur atau komponen
yang berada di sekitar individu yang memengaruhi kehidupan dan perkembangan
individu tersebut. Komponen lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi komponen
makhluk hidup (biotik) dan komponen benda mati (abiotik).
1) Lingkungan biotik, adalah semua makhluk hidup yang menempati bumi, terdiri atas
tumbuhan, hewan, dan manusia. Menurut fungsinya, lingkungan biotik dibedakan
menjadi:
a. Produsen, organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri, disebut
organisme autotrofik
b. Konsumen, adalah organisme yang hanya memanfaatkan hasil yang disediakan
oleh organisme lain. Konsumen disebut juga organisme heterotofik.
c. Pengurai, adalah organisme yang berperan menguraikan sisa-sisa makhluk
hidup yang telah mati. Contohnya adalah bakteri dan jamur.
2) Lingkungan abiotik, adalah berbagai benda mati dan unsur alam yang mempengaruhi
kehidupan makhluk hidup, antara lain udara, tanah, air, sinar matahari. Komponen-
komponen lingkungan yang ada disekitar kita merupakan suatu kesatuan yang saling
mempengaruhi antara komponen yang satu dan komponen lain, yang disebut
ekosistem.
3) Lingkungan sosial budaya, adalah lingkungan sosial dan budaya yang dibuat oleh
manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan dan juga keyakinan dalam perilaku
sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai sebuah keteraturan
berkat adanya sistem nilai dan juga sistem norma yang diakui dan ditaati oleh
segenap masyarakat.
Peraturan tentang kewajiban membuat Amdal diatur dalam peraturan peraturan
berikut:
a. UU No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994
tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 21
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang
Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak
Lingkungan Daerah.
Amdal berfungsi untuk:
a. Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
b. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari
rencana usaha dan atau kegiatan
c. Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan atau
kegiatan
d. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelola dan pemantauan lingkungan
hidup
e. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak ditimbulkan dari suatu rencana
usaha dann atau kegiatan
f. Awal dari rekomendasi tentang izin usaha
g. Sebagai Scientific Document dan Legal Document
h. Izin Kelayakan Lingkungan
i. Menunjukkan tempat pembangunan yang layak pada suatu wilayah beserta
pengaruhnya
j. Sebagai masukan dengan pertimbangan yang lebih luas bagi perencanaan dan
pengambilan keputusan sejak awal dan arahan atau pedoman bagi pelaksanaan
Manfaat Amdal adalah sebagai berikut:
a. Bagi Pemerintahan
1) Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran air,
pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak
mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.
2) Menghindari pertentangan yang mungkin timbul, khususnya dengan masyarakat
dan proyek - proyek lain.
3) Mencegah agar potensi dumber daya yang dikelola tidak rusak.
4) Mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada diluar lokasi proyek,
baik yang diolah proyek lain, masyarakat, ataupun yang belum diolah.
b. Bagi pemilik modal
4) Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengn misinya.
5) Melakukan pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal.
6) Menghindari duplikasi dari proyek lain yang tidak perlu.
7) Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar kembali
oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang.
Jenis usaha yang wajib dilengkapi dengan amdal diatur dalam Peraturan Lingkungan
Hidup No. 5 tahun 2002;
d. Bidang multisektoral, jenis kegiatan yang bersifat lintas sektor. Contohnya reklamasi
wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dengan luas area reklamasi ≥25 ha, dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 22
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
volume material timbunan ≥500.000 m3 atau panjang reklamasi ≥50 m (tegak lurus
ke arah laut dari garis pantai)
e. Bidang pertahanan dan keamanan. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas militer
skala tertentu berpotensi menimbulkan dampak penting, seperti potensi terjadinya
ledakan serta keresahan sosial akibat kegiatan operasional dan penggunaan lahan
yang cukup luas. Jenis kegiatan bidang pertahanan dan keamanan seperti
pembangunan pangkalan TNI AL, AU, dan pembangunan pusat latihan tempur,
f. Bidang pertanian. Pada umumnya, dampak yang ditimbulkan usaha budidaya
tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan berupa erosi tanah, perubahan
ketersediaan dan kualitas air akibat kegiatan pembukaan lahan, persebaran hama,
penyakit dan gulma pada saat beroperasi, serta perubahan kesuburan tanah akibat
penggunaan pestisida. Jenis kegiatan pertanian yang dimaksud seperti budidaya
tanaman pangan dengan atau tanpa unit pengolahannya, budidaya tanaman
hortikultura dengan atau tanpa unit pengolahannya, dan lain-lain.
g. Bidang perikanan dan kelautan. Dampak penting yang dihasilkan usaha budi daya
tambak udang dan ikan adalah perubahan ekosistem perairan dan pantai, hidrologi
dan bentang alam. Pembukaan hutan mangrove akan berdampak terhadap habitat,
jenis, dan kelimpahan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan yang berada di kawasan
tersebut. Adapun jenis kegiatannya seperti usaha budidaya perikanan.
h. Bidang kehutanan, pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah
gangguan terhadap hutan, hidrologi, keanekaragaman hayati, hama penyakit,
bencana alam, dan potensi konflik sosial.
i. Bidang perhubungan, misalnya pembangunan kereta api berpotensi menimbulkan
dampak berupa emisi gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan
pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasarana sosial, serta
dampak perubahan kestabilan lahan dan air tanah.
j. Bidang teknologi satelit, misalnya pembangunan fasilitas pembuatan propelan roket.
Kegiatan ii termasuk kegiatan berbahaya.
k. Bidang perindustrian, seperti industri semendengan proses klinker, adalah industri
semen yang kegiatanya menyatu dengan kegiatan penambangan. Kegiatan ini dapat
menyebabkan keluarnya debu dari cerobong, penggunaan lahan yang luas,
kebutuhan air cukup besar. selain itu, kegiatan ini berpotensi besar menghailkan
limbah.
l. Bidang pekerjaan umum, beberapa kegiatan pada bidang pekerjaan umum
mempertimbangkan skala/besaran kawasan perkotaan.
m. Bidang perumahan dan kawasan pemukiman, dampak pentingnya antara lain efek
pembangunan terhadap lingkungan sekitar (mobilisasi material, manusia, dan lalu
lintas)
n. Bidang energi dan sumber daya mineral terkait dengan proses produksi yang
memberi dampak penting seperti pada perubahan struktur dan stabilitas tanah
o. Bidang pariwisata, pada umumnya dampak penting yang ditimbulkan adalah
gangguan terhadap ekosistem, hidrologi, bentang alam, dan potensi konflik sosial.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 23
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
p. Bidang ketenaganukliran, secara umu, kegiatan yang berkaitan dengan
pengembangan dan penggunaan tenaga nuklir selalu memiliki potensi dampak dan
resiko radiasi.
q. Bidang pengolahan limbah beracun dan berbahaya (B3). Kegiatan yang
menghasilkan limbah B3 berpotensi menimbulkan dampak terhadapn lingkungan
dan kesehatan manusia, terutama kegiatan yang dipastikan akan mengonsentrasikan
limbah B3 dalam jumlah besar tertentu.
Rencana usaa dan/atau kegiatan yang dilakukan di dalam kawasan lindung; dan/atau
berbatasan langsung dengan kawasan lindung juga wajib memilki amdal. Kawasan
tersebut adalah:
a. Kawasan hutan lindung
b. Kawasan bergambut
c. Kawasan resapan air
d. Sempadan pantai
e. Sempadan sungai
f. Kawasan sekitar danau atau waduk
g. Suaka margasatwa dan suakamargasatwa laut
h. Cagar alam dan cagar alam laut
i. Kawasan pantai berhutan bakau
j. Taman nasional dan taman nasional laut
k. Taman hutan raya
l. Taman wisata alam dan taman wisata alam laut
m. Kawasan cagar budaya dan ilmu pegetahuan
n. Kawasan cagar alam geologi
o. Kawasan imbuan air tanah
p. Sempadan mata air
q. Kawasan perlindungan plasma nutfah
r. Kawasan pengungsian satwaa
s. Terumbu karang
t. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi
Dokumen amdal menjadi dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.
Dokumen amdal memuat hal-hal berikut:
a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha atau kegiatan
b. Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi rencana usaha dan kegiatan
c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan kegiatan
d. Prakiraan terhadap bersaran dampak serta sifat penting dampak yang tejadi jika
rencana usaha atau kegiatan tersebut dilaksanakan.
e. Evaluasi secara holistik terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan
atau ketidaklayakan lingkungan hidup
f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
Semua jenis usaha dan/atau kegiatan ini wajib memiliki analisis mengenai dampak
lingkungan hidup. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 24
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Dokumen amdal disusun oleh pemrakarsa yang
memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dengan melibatkan masyarakat tertentu
seperti pihak yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan pihak yang
berpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal. Dokumen ini dinilai oleh
Komisi Penilai amdal yag dibentuk oleh mentri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 25
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Pertemuan 3
Indikator:
3.3.6. Menjelaskan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
3.3.7. Menganalisis bentuk-bentuk pemanfaatan SDA dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan
A. Pembangunan Berkelanjutan
1) Konsep Pembangunan Berkelanjutan
Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis,
masyarakat, dsb) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan
pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan artinya
memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup untuk
memperbaiki kerusakan lingkungan hidup.
Pembangunan berkelanjutan dilatar belakangi dengan adanya keinginan dari
PBB untuk menanggulangi dan memperbaiki masalah kerusakan lingkungan yang
terjadi. Pada tanggal 1 Juni 1970, Sidang Umum PBB No 2657 (XXV) Tahun 1970
menugaskan pada Penitian Persiapan untuk menyesuaikan kebijakan nasional di
bidang lingkungan hidup dengan rencana Pembangunan Nasional untuk usaha
“melindungidan mengembangkan kepentingan-kepentingan negara yang sedang
berkemban”. Hal inilah yang selanjutnya dikembangkan dan menjadi hasil dari
Konferensi Stocholm yang dianggap sebagai dasar-dasar atau cikal bakal konsep
“Pembangunan Berkelanjutan”.
Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan atau suistainable
development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat dari
sumber daya alam dan sumber daya manusia, degan menyerasikan sumber alam
dengan manusia dalam pembangunan.
Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang
dihasilkan oleh KTT Bumi Rio de Jeneiro pada tahun 1992. Di dalamnya terkandung
dua gagasan penting, yaitu :
a. Gagasan kebutuhan, khususnya kebutuhan pokok manusia untuk menopang hidup,
di sini yang diprioritaskan adalah kebutuhan kaum miskin.
b. Gagasan keterbatasan, yakni keterbatasan kemampuan lingkungan untuk
memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang
Pembangunan berkelanjutan memerlukan faktor lingkungan untuk
mendukungnya (Otto Soemarwoto, 1977), yaitu:
a. Faktor tersedianya sumber daya yang cukup
b. Faktor terpeliharanya proses ekologi yang baik
c. Faktor lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai.
Faktor- faktor tersebut mengalami dampak dari pembangunan dan mempunyai
dampak pula terhadap pembangunan. Untuk hal tersebut pengelolaan lingkungan
untuk pembangunan harus didasarkan pada konsep yang lebih luas, mencakup:
a. Dampak lingkungan terhadap proyek
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 26
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
b. Pengelolaan lingkungan proyek yang sudah operasional
c. Perencanaan dini pengelolaan lingkungan untuk daerah yang belum mempunyai
rencana pembangunan.
2) Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Nasional
Pembangunan dikatakan berhasil jikadapat mensejahterakan kehidupan
masyarakat, memiliki fungsi dan peruntukan yang tepat, serta memiliki dampak
terhadap dampak kerusakan lingkungan terendah. Setiap pembangunan
menimbulkan dampak terhadap keseimbangan lingkungan hidup, namun dampak
tesebut harus diminimalisasi. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan
analisis mengenai dampak lingkungan, agar generasi mendatang dapat menikmati
kualotas dan kuantitas sumber daya alam sebagaimana yang tengah dinikmati
generasi sekarang. Atinya, kerusakan dan pencemaran lingkungan tidak diwarsikan
kepada generasi mendatang.
Menjaga kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan merupakan
usaha untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang mencakup jangka waktu
antar generasi atau pembangunan yang terlanjutkan. Agar pembangunan dapat
terlanjutkan, pembangunan haruslah berwawasan lingkungan dengan menggunakan
sumber daya secara bijaksana. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan tersebut
sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.
3) Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Istilah pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan digunakan
dalam UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pembangunan berwawasan lingkungan adalah bentuk pembangunan yang tetap
memperatikan daya dukung lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.
Pembangunan yang berwawasan lingkungan akan menghasilkan suatu pembangunan
yang berkelanjutan dan seimbang.
Menurut Emil Salim, pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan atau
suistainable development adalah suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan
manfaat dari sumber daya alam dan sumber daya manusia, degan menyerasikan
sumber alam dengan manusia dalam pembangunan.
Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan memiliki ciri-ciri berikut:
a. Dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan
memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta
yang akan timbul dikemudian hari
b. Memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung
kesinambungan pembangunan
c. Meminimalisasi dampak pencemaran lingkungan
d. Melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di
sekitar lokasi pembangunan.
4) Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan
Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang diterapkan dalam
implementasi pembangunan berkelanjutan antara lain :
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 27
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
a) Equity (Pemerataan)
Pemerataan dalam pembangunan berkelanjutan menjadi tujuan utama.
Pemerataan dianggap mampu meminimalisasi disparitas baik ekonomi dan
sosial serta kesempatan yang seimbang bagi masyarakat.
b) Engagement (Peran Serta)
Bentuk pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan melalui peningkatan dan
optimalisasi peran serta masyarakat dalam proses pembangunan lingkungan.
Dalam hal ini, pemerintah berperan sebagai fasilitator pemberdayaan
masyarakat dan mampu menampung aspirasi atau masukan dari masyarakat.
Sedangkan menurut UNCED dalam KTT Pembangunan Berkelanjutan tahun
2002 di Johannesburg Afrika Selatan, prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan
antara lain:
a) Keadilan Antar Generasi
Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap generasi manusia di dunia memiliki
hak untuk menerima dan menempati bumi bukan dalam kondisi yang buruk
akibat perbuatan generasi sebelumnya.
b) Keadilan Dalam Satu Generasi
Prinsip ini merupakan prinsip yang berbicara tentang keadilan di dalam sebuah
generasi umat manusia dimana beban permasalahan lingkungan harus dipikul
bersama oleh masyarakat dalam satu generasi.
c) Prinsip Pencegahan Dini
Prinsip ini mengandung pengertian bahwa apabila terjadi ancaman yang berarti
yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan maka
ketiadaan temuan atau pembuktian ilmiah yang konklusif dan pasti tidak dapat
dijadikan alasan untuk menunda upaya - upaya untuk mencegah terjadinya
kerusakan lingkungan.
d) Perlindungan Keanekaragaman Hayati
Prinsip ini merupakan prasyarat dari keberhasilan implementasi prinsip keadilan
antar generasi.Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati juga berarti
mencegah kepunahan jenis keanekaragaman hayati.
e) Internalisasi Biaya Lingkungan
Kerusakan lingkungan dapat dilihat sebagai biaya eksternal dari suatu kegiatan
ekonomi dan harus ditanggung oleh pelaku kegiatan ekonomi. Oleh karena itu
biaya kerusakan lingkungan harus diintegrasikan dalam proses pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan penggunaan sumberdaya alam.
5) Ciri-Ciri Pembangunan Berkelanjutan
a) Pembangunan yang dilaksanakan tidak terjadi atau mampu meminimalkan
kerusakan dan pencemaran lingkungan
b) Pembangunan yang dilaksanakan memperhatikan antara lingkungan fisik dan
lingkungan sosial
c) Pembangunan yang dilaksanakan mampu mengendalikan pemanfaatan sumber
daya
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 28
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
d) Pembangunan yang dilakukan mendasar pada nilai-nilai kemanusiaan serta
memperhatikan moral atau nilai yang dianut dalam masyarakat
e) Pembangunan yang dilaksanakan harus memiliki sifat fundamental dan ideal
serta berjangka pendek dan panjang
f) Pembangunan yang dilakukan mampu memperluas kesempatan kerja
g) Pembangunan yang dilakukan harus mampu melakukan pemerataan atau
keseimbanngan kesejahteraan rakyat
h) Pembangunan berkelanjutan dilakukan harus mampu melakukan pemerataan
atau keseimbangan kesejahteraan hidup antar golongan dan antar daerah
i) Pembangunan yang dilakukan dalam tingkat laju pertumbuhan ekonomi
nasional yang tinggi
j) Pembangunan yang dilakukan harus berpedoman untuk selalu mempertahankan
stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan keamanan nasional.
B. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Prinsip-Prinsip Pembangunan
Berkelanjutan
Sumber daya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidunya. Dengan demikian,
sumber daya alam memiliki peranganda, yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi, dan
sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Pemanfaatan SDA berkelanjutan adalah
prinsip yang dilakukan untuk menjaga kelestarian SDA dalam jangka panjang.
Pemanfaatan SDA berkelanjutan dikembangkan dalam kegiatan pertanian, pertambangan,
industri, dan pariwisata. Keberhasilan pemanfaatan SDA tersebut juga dapat didudung
dengan prinsip ekoefisien.
Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan diatur dalam Undang-Undang No. 5
tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok Agraria, Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang
ketentuan pokok Kehutanan, kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang
No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang no. 11 Tahun 1967
tentangketentuan pokok Pertambangan yang direncanakan akan diganti dalam waktu
dekat, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan.
1. Kehutanan Berkelanjutan
Kehutanan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hutan
dan kelestarian lingkungan untuk kepentingan hidup manusia saat sekarang dan generasi
yang akan datang. Sumber daya hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat
keterkaitannya dengan lingkungan hidup, baik secara fisik maupun sosial budaya.
Kerusakan sumber daya hutan dapat berdampak pada kerusakan iklim, kerusakan sungai
dan kerusakan lingkungan hidup manusia. Oleh karena itu dalam pengelolaan sumber
daya hutan tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam secara komprehensif dan
berkelanjutan.
Gambar 12. Pemanfaatan hutan berkelanjutan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 29
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Sumber: wordpress.com
Pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan menganut prinsip memanfaatkan
sumber daya hutan secara rasional dan bijaksana;
a. Pertimbangan ekonomi dan ekologi harus selaras, karena prinsip pengelolaan harus
mengusahakan tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan mempertahankan
kelestarian sumber daya alam.
b. Pengelolaan sumber daya alam mencakup masalah ekploitasi dan pembinaan dengan
tujuan mengusahakan agar penurunan daya produksi sumber daya alam sebagai
akibat eksploitasi diimbangi dengan tindakan konservasi dan pembinaan, dengan
demikian manfaat maksimal sumber daya alam dapat diperoleh secara berkelanjutan.
c. Untuk mencegah benturan kepentingan antara sektor-sektor yang memanfaatkan
sumber daya alam perlu diupayakan pendekatan multidisiplin dalam bentuk integrasi
usaha pengelolaan, khususnya integrasi dalam masalah tataguna lahan dan
perencanaan wilayah.
d. Pengelolaan sumber daya alam yang diharapkan berkelanjutan tersebut mencakup
aktivitas inventarisasi, perencanaan, implementasi, dan pengawasan.
e. Mempertimbangkan sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan ekosistem
yang bersifat kompleks, maka diperlukan metode inventarisasi dan perencanaan
yang terpadu serta organisasi pelaksana (kelembagaan) dan pengawasan yang
terkoordinasi dengan baik.
2. Pertanian Berkelanjutan
Secara umum, pertanian barkelanjutan bertujuan untuk meningkatakan kualitas
kehidupan (equality of life). Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut Manguiat, ada
beberapa kegiatan yang diperlukan. Beberapa kegiatan itu antara lain adalah
meningkatkan pembangunan ekonomi, memprioritaskan kecukupan pangan,
meningkatkan pengembangan sumber daya manusia, dan menjaga stabilitas lingkungan.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 30
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Gambar 13. Pertanian berkelanjutan dan penggunaan pestisida berlebihan
Sumber: dewi2ekasyaida.blogspot.co.id
Indikator kegiatan pertanian berkelanjutan adalah budi daya berbagai jenis tanaman
secara alami, memelihara keanekaragaman genetik sistem pertanian, meningkatkan siklus
hidup biologis dalam ekonomi sistem pertanian, menghasilkan produksi pertanian yang
bermutu dalam jumlah memadai, memelihara dan meningkatkan kesuburan tanah dalam
jangka panjang, menghindarkan pencemaran yang disebabkan penerapan teknik
pertanian.
Manfaat pertanian berkelanjutan :
a) Mampu meningkatkan produksi pertanian dam menjamin ketahanan pangan di dalam
negeri
b) Menghasilkan pangan dkualitas tinggi serta meminimalisasi kandungan bahan
pencemar kimia ataupun bakteri yang membahayakan.
c) Tidak mengurangi dan merusak kesuburan tanah, tidak meningkatkan erosi.
d) Mendukung dan menopang kehidupan masyarakat pedesaan dengan meningkatkan
kesempatan kerja serta menyediakan penghidupan layak bagi petani.
e) Tidak membahayakan kesehatan masyarakat yang bekerja atau hidup di
lingkunganpertaniandan bagi yang mengonsumsi hasil pertanian.
f) Melestarikan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup dilahan pertanian dan
perdesaanserta melestarikam SDA dan keragaman hayati.
3. Pertambangan Berkelanjutan
Kegiatan usaha tambang berisiko tinggi dan menimbulkan dampak terhadap
lingkungan fisik dan sosial. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, kegiatan berkelanjutan merupakan
kegiatan yang diawali dengan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan kegiatan
pascatambang. Pengelolaan tambang yang berkelanjutan memerlukan adanya komitmen
perusahaan terhadap nilai-nilai keberlanjutan. Selain itu, struktur organisasi sistem
manajemen yang memadai juga diperlukan.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 31
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
Gambar 14. Pertambangan berkelanjutan dan pertambangan tidak menjanjikan
kesejahteraan berkelanjutan
Sumber: www.suarakutim.com
International Council on Mining and Metals (2003) menyusun sepuluh prinsip
pengelolaan pertambangan berkelanjutan sebagai berikut :
a) Melaksanakan dan memelihara praktik etika bisnis dan taat kepada kekentuan
hukum yang diatur pemerintah
b) Mempertimbangkan pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dalam proses
pembuatan keputusan perusahaan
c) Menegakkan hak asasi dasar serta menghormati budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai
yang dianut oleh pekerja yang terkait dengan kegiatan pertambangan
d) Melaksanakan strategi manajemen resiko berdasarkan data yang sah dan kaidah
keilmuan
e) Melaksanakan perbaikan berkelanjutan terhadap kesehatan dan kinerja keamanan
f) Melaksanakan perbaikan berkelanjutan terhadap kinerja lingkungan
g) Menyumbang perbaikan bio deversitas dan melakukan pendekatan terpadu terhadap
rencana tata guna lahan
h) Memfasilitasi dan mendorong desain produk, penggunaan, penggunaan kembali,
mengolah ulang, dan pembuangan produk yang dapat dipertanggung jawabkan
i) Menyumbang pembangunan di bidang social, ekonomi, dan kelembagaan kepada
masyarakat di sekitar kegiatan
j) Melaksanakan perjanjian secara efektif dan transparan, melakukan komunikasi
secara teratur, dan memeriksa pelaporan perusahaan.
Kegiatan penambangan berkelanjutan dapat dilakukan untuk memenuhi harapan
sosial terhadap lingkungan sekitar.Kegiatan pertambangan berkelanjutan dapat dilakukan
melalui penetapan ujian jangka pendek dan jangka panjang secara konsisten. Ada tiga
prioritas utama untuk memaksimalkan potensi pertambangan berkelanjutan.
a) Menganalisis dampak dan keuntungan sosial, ekonomi, kesehatan, serta lingkungan
selama siklus kegiatan pertambangan, keselamatan, dan kesehatan para pekerja.
b) Meningkatkan partisipasi para pemangku kepentingan termasuk masyarakat adat dan
lokal serta kaum perempuan.
c) Mengembangkan prakitik pertambangan berkelanjutan melalui penyediaan
dukungan teknis serta pembangunan fasilitas dan keuangan kepada negara
berkembang dan miskin.
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 32
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
4. Industri Berkelanjutan
Kegiatan industri berperan terhadap tiga hal secara signifikan, yaitu kepada faktor
ekonomi, faktor sosial, dan faktor lingkungan. Pengaruh industri terhadap ekonomi dan
sosial adalah pengaruh positif, dimana kegiatan industri menciptakan lapangan kerja dan
meningkatkan pendapatan negara. Sementara itu, pengaruh industri terhadap lingkungan,
yaitu berupa pencemaran lingkungan adalah pengaruh yang merugikan. Kombinasi yang
seimbang dari ketiga faktor terpengaruh tersebut akan mewujudkan industri yang
berkelanjutan.
Oleh karena itu, pelaksanaan aktivitas di sektor industri perlu memperhatikan prinsip-
prinsip berikut:
a) Menggunakan SDA secara berkelanjutan.
b) Menjamin kualitas hidup masyarakat disekitar lokal penambangan.
c) Menjaga kelangsungan hidup ekologi sistem alami (environmental system).
Akan tetapi, ada hambatan bagi negara berkembang dalam melaksanakan kegiatan
industri berkelanjutan. Hambatan dalam pelaksanaan kegiatan industri berkelanjutan
sebagai berikut:
a) Potensi sumber daya melimpah, tetapi pemanfaatannya belum optimal.
b) Dukungan pemerintah terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan masih kurang.
Kawasan industri dinegara berkembang belum terpadu secara sistematis dan hanya
kumpulanindustri yang berdiri sendiri.
5. Kelautan Berkelanjutan
Hasil perikanan laut tahun 2003 cenderung menunjukkan adanya penurunan jumlah.
Untuk memperoleh hasil yang sama dengan waktu sebelumnya, diperlukan waktu yang
cukup lama. Hal ini terjadi karena makin menurunnya populasi ikan yang disebabkan
tertangkapnya ikan-ikan yang masih kecil. Di samping itu, tidak ada kesempatan bagi
ikan dewasa untuk berkembang biak. Oleh karena itu, perlu adanya usaha pengelolaan
perikanan di Indonesia.
Pengelolaan perikanan ini ditempuh dengan jalan sebagai berikut.
a. Perlindungan anak ikan, yaitu larangan penangkapan ikan yang belum dewasa
dengan menggunakan alat penangkapan yang ukuran jaringnya ditentukan.
b. Sistem kuota, yaitu menentukan bagian perairan yang boleh diambil ikannya pada
musim tertentu. Penggunaan sistem ini harus disertai kontrol yang baik.
c. Penutupan musim penangkapan dengan tujuan agar jumlah induk ikan tidak
berkurang, kemudian pada waktu pemijahan serta pembesaran anak ikan tidak
terganggu. Pada musim tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan-ikan tertentu.
d. Penutupan daerah perikanan, yaitu larangan penangkapan ikan di daerah pemijahan
dan pembesaran ikan, terutama di daerah yang populasinya menurun.
6. Pariwisata Berkelanjutan
Pariwisata berkelanjutan berfokus pada keberlanjutan pariwisata sebagai aktifitas
ekonomi dan mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan
berkelanjutan yang lebih luas. Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 33
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari
penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan.
Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan,
dan pelaksanaan, sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan
buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-
standar internasional.
Pariwisata berkelanjutan mengacu pada aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial
budaya dari suatu objek wisata, baik saat ini maupun di masa mendatang, serta untuk
menjawab kebutuhan wisatawan, insdustri, lingkungan, dan populasi setempat. Manfaat
pengembangan kegiatan pariwisata berkelanjutan adalah sebagai berikut:
a) Menjamin keseimbangan lingkungan pada objek wisata yang menjamin kelestaria
lingkungan alam dan budaya setempat.
b) Meningkatkan rasa cinta atau peduli masyarakat terhadap lingkungan.
c) Meningkatkan devisa negara dari jumlah kunjungan wisatawan asing
d) Memperluas lapangan kerja yang berorientasi pada faktor pendukung pariwisata
sehingga dapat menyerap angkatan kerja
e) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerima pajak bagi pemerintah daerah
yangberpotensi meningkatan pendapatan asli daerah
f) Mendorong pembangunan daerah menunjang kegiatan wisata
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 34
Bahan Ajar Geografi Kelas XI SMA
Pendidikan Geografi
Universitas Negeri Padang
DAFTAR RUJUKAN
Abdurrahman. 2013. Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Sumber Daya
Alam Indonesia. [Makalah]. Disampaikan pada seminar pembangunan hukum
nasional VIII tema Penegakan Hukum dalam era Pembangunan Berkelanjutan.
Anonim. [online]. Natural Resource. Tersedia di http://www.eschooltoday.com/natural-
resources/conservation-of-natural-resources.html [diakses 18 Agustus 2017]
Anonim. [online]. Pengelolaan Sumber Daya Hutan. Tersedia di http://forester-
untad.blogspot.co.id/2015/02/pengelolaan-sumber-daya-hutan.html. [diakses
20 Oktober 2017]
Anonim. [online]. Type of Natural Resource. http://www.eschooltoday.com/natural-
resources/types-of-natural-resources.html [diakses 18 Agustus 2017]
Huda, Nurul. Sumantri, Diaz. Rohman, Deri Syaeful. Urfan, Faiz. 2014. Suplemen
Sumber Belajar Olimpiade Geografi. Jakarta: PT Bina Prestasi Insani.
Indonesia Investment. 2017. Batubara. Indonesiainvesment.com https://www.indonesia-
investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236? [online] diakses pada
25 Oktober 2017
Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2015. Statistik Kementrian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2014.
Sindhu P, Yasinto. Geografi Untuk SMA/MA Kelas XI. Jakarta: Erlangga
Subadra, Nengah. Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. Diposting 14 Maret
2011. Jejakwisata.com http://jejakwisata.com/tourism-studies/planning-and-
development/113-prinsip-pembangunan-pariwisata-berkelanjutan.html [diakses
18 Agustus 2017]
Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia | 35
Anda mungkin juga menyukai
- Tanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauDari EverandTanaman Pepohonan Untuk Menjernihkan & Menetralisir Air Limbah Beracun Berbahaya Dari Kawasan Perairan Laut Sungai DanauBelum ada peringkat
- Makalah Sumber Daya AlamDokumen22 halamanMakalah Sumber Daya Alamleni0% (2)
- 3 - Angin Dan Sirkulasi GlobalDokumen60 halaman3 - Angin Dan Sirkulasi Globalbambang aconkBelum ada peringkat
- Contoh Soal Hitungan GeografiDokumen10 halamanContoh Soal Hitungan Geografibambang aconk100% (2)
- Soal PAKET 3 KEBUMIANDokumen48 halamanSoal PAKET 3 KEBUMIANbambang aconk100% (1)
- 2 3.3 Bahan Ajar Pengelolaan SDADokumen28 halaman2 3.3 Bahan Ajar Pengelolaan SDAlilan patilimaBelum ada peringkat
- LKPD Klasifikasi SdaDokumen7 halamanLKPD Klasifikasi SdaJulFha A'liBelum ada peringkat
- Sumber Daya Alam-1Dokumen21 halamanSumber Daya Alam-1AnggiyonoBelum ada peringkat
- Materi GeografiDokumen3 halamanMateri GeografiDaren SantiagoBelum ada peringkat
- Bahan Ajar Potensi Sumber Daya AlamDokumen11 halamanBahan Ajar Potensi Sumber Daya AlamSuratmi suratmi.2022100% (1)
- Kelas XI - Geografi - KD 3.1Dokumen64 halamanKelas XI - Geografi - KD 3.1Muhamad Hasan WadiBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Ilmu Lingkungan Acara 3Dokumen13 halamanLaporan Praktikum Ilmu Lingkungan Acara 3Amin Khusnadiyah100% (1)
- Sebaran SdaDokumen10 halamanSebaran SdaShafiyah NurilBelum ada peringkat
- Bab 3Dokumen27 halamanBab 3Fanisa AssilahBelum ada peringkat
- Makalah Geografi Kelompok 01Dokumen13 halamanMakalah Geografi Kelompok 01Nooriko NarasakiBelum ada peringkat
- Sumber Daya AlamDokumen14 halamanSumber Daya AlamEriyanti Ahmar23Belum ada peringkat
- Revisi Modul 6 KB 1. Potensi Sda - 1 Juli 2022Dokumen46 halamanRevisi Modul 6 KB 1. Potensi Sda - 1 Juli 2022Hendri PuswadiBelum ada peringkat
- IAD Kel 3Dokumen9 halamanIAD Kel 3Mailani Muadzimah LijawahirinisaBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen20 halamanBab I Pendahuluandefrianti41Belum ada peringkat
- Makalah IAD Kel 9Dokumen16 halamanMakalah IAD Kel 9bungo0210Belum ada peringkat
- BA XI 3.3 Pengelolaan Sumberdaya Alam PDFDokumen72 halamanBA XI 3.3 Pengelolaan Sumberdaya Alam PDFcherish tracey100% (1)
- Pengelolaan Sumber Daya AlamDokumen24 halamanPengelolaan Sumber Daya AlamYuliza LizaBelum ada peringkat
- Makalah Pengantar Ekonomi JulDokumen13 halamanMakalah Pengantar Ekonomi JulririndamayantiBelum ada peringkat
- Makalah Sumber Daya AlamDokumen16 halamanMakalah Sumber Daya AlamDea NirmalaBelum ada peringkat
- Makalah Ilmu Alamiah DasarDokumen12 halamanMakalah Ilmu Alamiah DasarAngga SetiawanBelum ada peringkat
- Makalah IAD Kelompok 6Dokumen16 halamanMakalah IAD Kelompok 6Novita P SilalahiBelum ada peringkat
- Lingkungan YudhaDokumen12 halamanLingkungan YudhaFarhan FayadhBelum ada peringkat
- Makalah IkmalDokumen23 halamanMakalah IkmalHermin rahmawatiBelum ada peringkat
- CBRDokumen16 halamanCBRYenni TrianaBelum ada peringkat
- Rencana Pelaksanaan PembelajaranDokumen6 halamanRencana Pelaksanaan Pembelajaransiti holidahBelum ada peringkat
- Ursula Tugas Makalah SeminarDokumen11 halamanUrsula Tugas Makalah SeminarArlynd ArlindaBelum ada peringkat
- Klasifikasi Dan Manfaat Sumber Daya Alam Untuk ManusiaDokumen9 halamanKlasifikasi Dan Manfaat Sumber Daya Alam Untuk ManusiaInsan IhsanBelum ada peringkat
- Makalah Geografi (Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia)Dokumen7 halamanMakalah Geografi (Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia)Ririn AnfBelum ada peringkat
- Ukbm 5 SdaaaaaDokumen12 halamanUkbm 5 SdaaaaaCindy CencenBelum ada peringkat
- Jenis Dan Penggolongan Sumber Daya AlamDokumen10 halamanJenis Dan Penggolongan Sumber Daya AlamIEkanza salsabil auliaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen65 halamanBab IiCaca CasperBelum ada peringkat
- Unit 3 Sumber Daya AlamDokumen17 halamanUnit 3 Sumber Daya AlamDominicus GideonBelum ada peringkat
- Bab 3 - 1 (Geo)Dokumen13 halamanBab 3 - 1 (Geo)ibrizuna bin hakimBelum ada peringkat
- KimLing Makalah SDA Dan EnergiDokumen22 halamanKimLing Makalah SDA Dan EnergiYemima ThorchiBelum ada peringkat
- Bab 3 Potensi Dan Pemanfaatan Sumber Daya AlamDokumen76 halamanBab 3 Potensi Dan Pemanfaatan Sumber Daya AlamnainaBelum ada peringkat
- Revisi Modul 6 KB 1. Potensi Sda - 1 Juli 2022-1-45-3-45Dokumen43 halamanRevisi Modul 6 KB 1. Potensi Sda - 1 Juli 2022-1-45-3-45Tika LestaryBelum ada peringkat
- Modul AjarDokumen30 halamanModul AjarAhmad ArifBelum ada peringkat
- Makalah Konservasi Sda KL 1Dokumen30 halamanMakalah Konservasi Sda KL 1Ade WirandaBelum ada peringkat
- Makalah Sains Mi Pgmi 3Dokumen16 halamanMakalah Sains Mi Pgmi 3Tripuji UtamiBelum ada peringkat
- Pelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan HidupDokumen18 halamanPelestarian Sumber Daya Alam Dan Lingkungan HidupRyo AquinoBelum ada peringkat
- Sumber Daya Alam Makalah Buk SaudahDokumen20 halamanSumber Daya Alam Makalah Buk SaudahSuri RahmayaniBelum ada peringkat
- Geografi Modul6 SDA Dan SDMDokumen179 halamanGeografi Modul6 SDA Dan SDMAlwin GhiffariBelum ada peringkat
- IPS SMP Kelas VII - Bab 3 Potensi Ekonomi LingkunganDokumen55 halamanIPS SMP Kelas VII - Bab 3 Potensi Ekonomi Lingkungansyska widyawatiBelum ada peringkat
- Pengertian Sumber Daya Alam Dan Pembagian MacamDokumen10 halamanPengertian Sumber Daya Alam Dan Pembagian MacambatikwigatiBelum ada peringkat
- Makalah Ekonomi SDL Kel 2Dokumen15 halamanMakalah Ekonomi SDL Kel 2Naen HabibBelum ada peringkat
- 1.4 Makalah Kelompok 1 Iad (18 BB 04)Dokumen53 halaman1.4 Makalah Kelompok 1 Iad (18 BB 04)DebyoctaviaBelum ada peringkat
- Makalah Sofia Ummul HusniaDokumen21 halamanMakalah Sofia Ummul Husniayandiwandi854Belum ada peringkat
- Materi - Sumber Daya Alam Dan PengelolaannyaDokumen21 halamanMateri - Sumber Daya Alam Dan PengelolaannyaTika Putri MaulinaBelum ada peringkat
- Xi Geografi KD-3.3 FinalDokumen48 halamanXi Geografi KD-3.3 FinalRiyantoBelum ada peringkat
- Bahan Ajar Dan LKPD XI IPS 1Dokumen8 halamanBahan Ajar Dan LKPD XI IPS 1indah nurBelum ada peringkat
- Keanekaragaman BiogeofisikDokumen15 halamanKeanekaragaman BiogeofisikCindra Fauziah HasanBelum ada peringkat
- BAB 3 SDA Dan Pelestariannya FixDokumen16 halamanBAB 3 SDA Dan Pelestariannya Fix2111031532 I Ketut WidianaBelum ada peringkat
- Isyatir Rodliyyah-C30121075-SDA& LingkunganDokumen20 halamanIsyatir Rodliyyah-C30121075-SDA& LingkunganTiara HumairaBelum ada peringkat
- Nasrul Hadi - 18073068 - Sumber Daya Alam - T.Minggu 10 - Ilmu Kealaman Dasar PDFDokumen4 halamanNasrul Hadi - 18073068 - Sumber Daya Alam - T.Minggu 10 - Ilmu Kealaman Dasar PDFNasrul HadiBelum ada peringkat
- RPP (02) Potensi Sumber Daya Alam Dan Kemaritiman IndonesiaDokumen12 halamanRPP (02) Potensi Sumber Daya Alam Dan Kemaritiman IndonesiaLiaBelum ada peringkat
- BAB 3 SDA Dan Pelestariannya FixDokumen20 halamanBAB 3 SDA Dan Pelestariannya Fix2111031532 I Ketut WidianaBelum ada peringkat
- Tugas Tutorial 3 KomputerDokumen5 halamanTugas Tutorial 3 KomputerMiftah NajibBelum ada peringkat
- ALC 2015 Paket 2 KebumianDokumen6 halamanALC 2015 Paket 2 Kebumianbambang aconkBelum ada peringkat
- ALC 2015 Paket 4 KebumianDokumen5 halamanALC 2015 Paket 4 Kebumianbambang aconkBelum ada peringkat
- Berkas Administrasi Wali KelasDokumen20 halamanBerkas Administrasi Wali Kelasbambang aconkBelum ada peringkat
- ALC 2015 Paket 3 KebumianDokumen6 halamanALC 2015 Paket 3 Kebumianbambang aconkBelum ada peringkat
- ALC 2015 Paket 1 AstronomiDokumen19 halamanALC 2015 Paket 1 Astronomibambang aconkBelum ada peringkat
- Laporan: OlehDokumen8 halamanLaporan: Olehbambang aconkBelum ada peringkat
- SMA Geografi Paket 04 Fenomena Geosfer PKB2019 DIKMENDokumen358 halamanSMA Geografi Paket 04 Fenomena Geosfer PKB2019 DIKMENbambang aconkBelum ada peringkat
- 1 KARTOGRAFI - AsthinaDokumen198 halaman1 KARTOGRAFI - Asthinabambang aconk33% (3)
- 3.2 Bahan Ajar Flora Dan Fauna PDFDokumen33 halaman3.2 Bahan Ajar Flora Dan Fauna PDFbambang aconkBelum ada peringkat
- LKPD InteraksiDokumen5 halamanLKPD Interaksibambang aconkBelum ada peringkat
- 5.kelembaban UdaraDokumen13 halaman5.kelembaban Udarabambang aconkBelum ada peringkat
- 4.neraca EnergiDokumen9 halaman4.neraca Energibambang aconkBelum ada peringkat