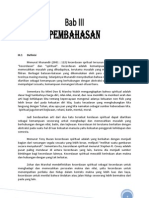Ahlul Asbab Dan Ahlut Tajrid. Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus. FPPsi
Diunggah oleh
Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
22 tayangan3 halamanTeks ini membahas dua pendekatan dalam melihat rezeki yaitu ahlul asbab dan ahlut tajrid. Ahlul asbab melihat bahwa manusia harus berusaha keras untuk mendapatkan rezeki dengan cara mencari sebab-sebabnya, seperti bekerja, belajar, lalu bertawakal kepada Tuhan. Sedangkan ahlut tajrid lebih bertawakal terlebih dahulu sebelum berusaha, dimana sebab-sebabnya datang dari
Deskripsi Asli:
Judul Asli
Ahlul Asbab dan Ahlut Tajrid. Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus. FPPsi
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniTeks ini membahas dua pendekatan dalam melihat rezeki yaitu ahlul asbab dan ahlut tajrid. Ahlul asbab melihat bahwa manusia harus berusaha keras untuk mendapatkan rezeki dengan cara mencari sebab-sebabnya, seperti bekerja, belajar, lalu bertawakal kepada Tuhan. Sedangkan ahlut tajrid lebih bertawakal terlebih dahulu sebelum berusaha, dimana sebab-sebabnya datang dari
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
22 tayangan3 halamanAhlul Asbab Dan Ahlut Tajrid. Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus. FPPsi
Diunggah oleh
Muhammad Iqbal Fakhrul FirdausTeks ini membahas dua pendekatan dalam melihat rezeki yaitu ahlul asbab dan ahlut tajrid. Ahlul asbab melihat bahwa manusia harus berusaha keras untuk mendapatkan rezeki dengan cara mencari sebab-sebabnya, seperti bekerja, belajar, lalu bertawakal kepada Tuhan. Sedangkan ahlut tajrid lebih bertawakal terlebih dahulu sebelum berusaha, dimana sebab-sebabnya datang dari
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 3
AHLUL ASBAB DAN AHLUT TAJRID: REFLEKSI KULTUR “HIJRAH”
Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus*
Kita terkadang membaca testimoni tentang kondisi para “sobat hijrah” yang mengalami
ketidakseimbangan dalam kehidupan duniawinya, terutama dalam bidang ekonomi. Mereka
meninggalkan pekerjaan yang menurut mereka adalah bagian dari “institusi riba”, namun
kemudian mereka enggan melunasi utang kepada bank dengan alasan riba, sampai terjebak utang
hingga menzalimi atau merepotkan diri sendiri, keluarga, tetangga, maupun sahabat, sehingga
menciptakan relasi sosial yang kurang baik dan silaturahmi terganggu. Tentu, tidak semua “sobat
hijrah” terpuruk, sebab faktanya, ada yang biasa-biasa saja, bahkan kondisi ekonominya jauh
membaik.
Bagi Penulis, setiap tafsir atau pendapat yang kita yakini benar selalu memiliki
konsekuensi. Konsekuensi itu sedikit banyak dipengaruhi oleh raison d’etre dari pilihan kita atas
tafsir yang kita yakini. Mereka yang hengkang begitu saja dari pekerjaannya hanya berbekal
keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memberi rezeki. Secara keilmuan, keyakinan tersebut tidak
salah, tetapi keyakinan bahwa Tuhan yang memberi rezeki sebenarnya merupakan azas
pengetahuan teologis atau berkaitan dengan tauhid. Ketika azas ini hendak diterapkan dalam
kehidupan duniawi, maka seseorang akan membutuhkan syariat dan jalan, yang dalam
pengertian umum disebut tarekat. Secara umum, kita mengetahui bahwa Tuhan tidak serta merta
menjatuhkan uang dari langit begitu saja, sebab kebanyakan dari kita masih berada dalam
maqam ahlul asbab. Menurut Penulis, ada sedikit kekeliruan pemahaman ketika menjalankan
kredo “memasrahkan rezeki kepada Tuhan”.
Syaikh Ibn ‘Athaillah as-Sakandari dalam kitabnya yang masyhur, al-Hikam, tepatnya
dalam hikmah kedua menyatakan bahwa manusia dibagi menjadi dua kondisi: ahlul asbab dan
ahlut tajrid. Sebagian besar dari kita adalah ahlul asbab, dalam arti kita berada dalam dimensi
kausalitas dan oleh Tuhan, kita “dipinjami” daya untuk menciptakan atau menempuh sebab
untuk mendapatkan rezeki dalam pengertian luas. Misalnya, untuk memperoleh rezeki ilmu dan
harta, seseorang harus menempuh sebab-sebab, seperti tekun belajar, bersekolah, mengikuti
ujian, dan melakukan penelitian atau tugas-tugas akademis lainnya. Melalui pengetahuan yang
didapat, kita berusaha menciptakan peluang untuk mendapat saluran rezeki yang telah disiapkan
Tuhan sampai apa yang diharapkan tercapai, tentu dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan yang
menentukan hasilnya. Artinya, kita berusaha keras, lalu bertawakal. Seperti dalam al-Quran,
“apabila kamu telah bertekad dan berusaha keras, maka bertawakallah kepada Allah,” (QS. Al
‘Imran: 159). Tawakal muncul setelah ikhtiar keras, dan perlu diingat juga bahwa secara kodrati,
ada syarat dan ketentuan yang berlaku dalam setiap ikhtiar manusia.
Berbeda halnya dengan ahlut tajrid. Ahlut tajrid dapat dikatakan sebagai kelompok yang
lebih sedikit, sebab berkaitan dengan rahasia keikhasan dalam menjalankan laku rohani yang
lebih “khusus”. Bagi ahlut tajrid, sumber rezeki mereka sebagian besar tetaplah sebab, namun
sebab itu didatangkan oleh Tuhan tak selalu melalui upaya keras mereka sendiri. Secara teoretis,
tingkat tawakal mereka adalah tingkatan para arifin, yakni orang-orang yang mengenal Tuhan
melalui Tuhan itu sendiri, serta berjalan bersama dan di dalam Tuhan. Berbeda dengan ahlul
asbab seperti kebanyakan kita yang harus berusaha menciptakan atau memikirkan sebab, ahlut
tajrid menindaklanjuti sebab dengan amal atau ikhtiar. Dengan kata lain, mereka bertawakal
lebih dahulu, kemudian berusaha sesuai syariat dan hakikat dari pelaksanaan usaha itu.
Namun, tawakal lebih dahulu ini bukan dalam pengertian umum. Kita bisa bertanya, di
manakah letak tawakal-lebih-dahulu itu? Apakah ia berada dalam akal pikiran, dalam sifat kita,
dalam hawa nafsu, dalam rasa kita, dalam ruh atau sirr kita, atau di mana?
Singkat kata, orang yang ditempatkan oleh Tuhan dalam kelompok ahlut tajrid adalah
mereka yang benar-benar sudah mengenal diri mereka sendiri, yang berarti telah mengenal
Tuhannya sesuai dengan yang Dia kehendaki dan perkenalkan dalam firman-Nya maupun dalam
ciptaan-Nya, bukan menurut pikiran atau pemahaman kognitif kita sendiri. Kalau diri telah
mengenal Sang Pencipta, maka diri akan menyaksikan af’al atau perbuatan Tuhan dalam seluruh
sisi kehidupan, dan oleh sebab itu, ketika dia melakukan sesuatu berdasarkan apa yang termaktub
dalam dirinya, dia akan tawakal sejak dini dengan mengatakan ”ya” dan “sami’na wa atha’na”
di awal. Kepatuhan jenis ini bukan pada sisi lahiriah, bukan pula pada sisi pikiran atau daya
kognitif dan mental, melainkan kepatuhan pada sisi rohaniah atau sirri (rahasia insani) yang
membutuhkan kejernihan hati, ketika hawa nafsu, egoisme, sifat insani, beserta daya inderawi
telah sepenuhnya mengenal dirinya sendiri dan tunduk pada kehendak zat ilahi.
Kalau kita masih berada di ranah kausalitas, tentu akan berantakan jika melompat ke laku
ahlut tajrid yang membutuhkan lebih banyak syarat dan ketentuan khusus, serta berkaitan
dengan laku rohani yang lebih intensif. Oleh karena itu, “hijrah” sebagaimana penafsiran yang
diyakini oleh “sobat hijrah” itu bukan suatu persoalan serta tidak menimbulkan dampak
psikologis dan sosiologis yang parah jika (dan hanya jika) kita tahu diri dan benar-benar paham
tentang kedudukan kita sebagai hamba dan manusia, yakni manusia yang masih butuh sebab,
pertimbangan rasional, intelektual, sosial, kultural, dan ikhtiar lahiriah lain yang penuh
kesungguhan, tentu dalam batas hukum yang kita yakini atau sepakati.
Maka, belum tibakah bagi kita untuk lebih ngopeni ati, agar kita mengenal diri untuk bisa
hidup dalam kedamaian dan kepasrahan yang berada dalam titik keseimbangan dunia-akhirat?
Bukankah sebaik-baik urusan adalah yang seimbang atau pertengahan?
* Mahasiswa S1 Psikologi, Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang. Dapat
dihubungi di nomor WhatsApp 085231975696.
Anda mungkin juga menyukai
- Bagaimana Manusia BertuhanDokumen9 halamanBagaimana Manusia BertuhanEga SafitriBelum ada peringkat
- Tugas Pendidikan Agama IslamDokumen10 halamanTugas Pendidikan Agama IslamDian Putri UtamiBelum ada peringkat
- Makalah Fitrah Manusia BertuhanDokumen19 halamanMakalah Fitrah Manusia BertuhanAsyrafullah Fikri100% (1)
- AGAMADokumen2 halamanAGAMASufiaf AfBelum ada peringkat
- Makalah MANUSIA BERTUHANDokumen10 halamanMakalah MANUSIA BERTUHANgaluh candraBelum ada peringkat
- Rangkuman Materi: Moh. Noridwan (1947240001)Dokumen20 halamanRangkuman Materi: Moh. Noridwan (1947240001)Toko TriNurBelum ada peringkat
- UAS AGAMA ISLAM - Nabila Aji Aulia Putri - 02019146560Dokumen4 halamanUAS AGAMA ISLAM - Nabila Aji Aulia Putri - 02019146560Nabila Aji Aulia PutriBelum ada peringkat
- SpiritualitasDokumen14 halamanSpiritualitasajirahmatBelum ada peringkat
- Watermark BAB 2Dokumen28 halamanWatermark BAB 2wahyu aidil fitraBelum ada peringkat
- Bagaimana Manusia BertuhanDokumen17 halamanBagaimana Manusia BertuhanSalsa FebrianiBelum ada peringkat
- Tugas AgamaDokumen9 halamanTugas AgamaPutri Kusuma WardhaniBelum ada peringkat
- Buat para Penganut AgnostikDokumen9 halamanBuat para Penganut AgnostikKang AryaBelum ada peringkat
- Makalah Pendidikan Agama IslamDokumen10 halamanMakalah Pendidikan Agama IslamAdi WahyuBelum ada peringkat
- Rangkuman 20 HLMNDokumen4 halamanRangkuman 20 HLMNToko TriNurBelum ada peringkat
- MPLS-Materi 1-Muhassabah FIXDokumen6 halamanMPLS-Materi 1-Muhassabah FIXhurasumsaBelum ada peringkat
- AgamaDokumen14 halamanAgamaRayhan MandalikaBelum ada peringkat
- Pembahasan MateriDokumen11 halamanPembahasan MateriElisa YinBelum ada peringkat
- Pertemuan Ke 3-1Dokumen12 halamanPertemuan Ke 3-1hutabarathutabarat09Belum ada peringkat
- Tazkirah RezekiDokumen2 halamanTazkirah Rezekianif fazziBelum ada peringkat
- Bagaimana Agama Menjamin KebahagiaanDokumen16 halamanBagaimana Agama Menjamin KebahagiaanWitri YaniiBelum ada peringkat
- BAGAIMANA MANUSIA BERTUHAN AgamaDokumen9 halamanBAGAIMANA MANUSIA BERTUHAN AgamaGREEN COFFEE DISTRIBUTORBelum ada peringkat
- Kelompok 1 Hakikat Manusia BertuhanDokumen21 halamanKelompok 1 Hakikat Manusia BertuhanTanak GadangBelum ada peringkat
- Tugas PaiDokumen14 halamanTugas PaiRayhan MandalikaBelum ada peringkat
- Kultum Baru Rizki Dan UmurDokumen2 halamanKultum Baru Rizki Dan UmurArip BudimanBelum ada peringkat
- Mencari Tuhan PDFDokumen150 halamanMencari Tuhan PDFAkmal IbrahimBelum ada peringkat
- Resum Materi Agama Islam IVDokumen30 halamanResum Materi Agama Islam IVKholifatur RizqiyahBelum ada peringkat
- Abuddin Nata-WPS OfficeDokumen9 halamanAbuddin Nata-WPS OfficefajrinBelum ada peringkat
- Defrino GionaldoDokumen20 halamanDefrino GionaldoDefrino GionaldoBelum ada peringkat
- Bab Ii Memahami Psikologi AgamaDokumen20 halamanBab Ii Memahami Psikologi Agamaahyar muchlisBelum ada peringkat
- Anugerah Demi Anugerah Dalam Spiritualitas KristenDokumen12 halamanAnugerah Demi Anugerah Dalam Spiritualitas KristenSalomo Galih NugrohoBelum ada peringkat
- Bagaimana Manusia BeragamaDokumen2 halamanBagaimana Manusia BeragamaHANIF SYAZALI100% (1)
- Membangun Kecerdasan SpiritualDokumen30 halamanMembangun Kecerdasan SpiritualNanda NandaBelum ada peringkat
- Ketuhanan Dalam IslamDokumen15 halamanKetuhanan Dalam IslamDiah AyuBelum ada peringkat
- Scribt Psikoterapi SholatDokumen7 halamanScribt Psikoterapi SholatNike Wahyuni, M.PsiBelum ada peringkat
- Makalah Akhlak TasawufDokumen11 halamanMakalah Akhlak TasawufNeni Ratu VilaBelum ada peringkat
- Bahan Ajar - 6-OkDokumen31 halamanBahan Ajar - 6-OkRachena FebrieryBelum ada peringkat
- Tugas ResumeDokumen8 halamanTugas ResumeRobytoh Nur Aulia DenhasBelum ada peringkat
- Konsep Agama Sebagai Jalan Menuju KebahagiaanDokumen16 halamanKonsep Agama Sebagai Jalan Menuju Kebahagiaan김일숙Belum ada peringkat
- Konsep Bahagia Dalam TasawufDokumen9 halamanKonsep Bahagia Dalam TasawufNurwach YudiBelum ada peringkat
- Pengertian AqidahDokumen15 halamanPengertian AqidahGis Gidamee100% (1)
- Bagaimana Manusia BertuhanDokumen9 halamanBagaimana Manusia BertuhanAldi NovandiBelum ada peringkat
- 7 Ciri SpiritualDokumen3 halaman7 Ciri SpiritualazharBelum ada peringkat
- Bab 2 Bagaimana Manusia BertuhanDokumen32 halamanBab 2 Bagaimana Manusia BertuhanTri YaniBelum ada peringkat
- Makalah Psikologi Agama Rinanda Dwi AgustinDokumen24 halamanMakalah Psikologi Agama Rinanda Dwi AgustinResy KusnadyBelum ada peringkat
- Makalah Agama IslamDokumen8 halamanMakalah Agama IslamAlma SiwiBelum ada peringkat
- 05-Bagaimana Manusia Ber-TuhanDokumen19 halaman05-Bagaimana Manusia Ber-TuhanEdward TionadiBelum ada peringkat
- MENCARI TUHAN (Kumpulan Artikel Gugun Ekalaya) 2019Dokumen44 halamanMENCARI TUHAN (Kumpulan Artikel Gugun Ekalaya) 2019Gugun AriefBelum ada peringkat
- Bab 2 KetuhananDokumen12 halamanBab 2 KetuhananWahyu SetiawanBelum ada peringkat
- Tugas PAI 1Dokumen42 halamanTugas PAI 1Rafli ansyahBelum ada peringkat
- Kecerdasan SpiritualDokumen12 halamanKecerdasan SpiritualmentariBelum ada peringkat
- Kebertuhanan ManusiaDokumen23 halamanKebertuhanan ManusiaRahma SariBelum ada peringkat
- Makrifatullah Tugas Tauhid MZDokumen6 halamanMakrifatullah Tugas Tauhid MZmarazonanstBelum ada peringkat
- Semester 5 Psikologi AgamaDokumen14 halamanSemester 5 Psikologi AgamaMayy AissidiqyahBelum ada peringkat
- Konsep Manusia BertuhanDokumen28 halamanKonsep Manusia BertuhanVeto NugrohoBelum ada peringkat
- BAB 2 Agama IslamDokumen10 halamanBAB 2 Agama Islamika100% (1)
- Bab II Bagaimana Manusia BertuhanDokumen11 halamanBab II Bagaimana Manusia Bertuhanyeni riskaBelum ada peringkat
- Word AgamaDokumen10 halamanWord Agamaanntsy0% (1)
- Kecerdasan SpiritualDokumen14 halamanKecerdasan SpiritualKhairil AnuarBelum ada peringkat
- Bagaimana Manusia Bertuhan Kelompok 5Dokumen16 halamanBagaimana Manusia Bertuhan Kelompok 5nurlitasilvipnBelum ada peringkat
- Laporan Modifikasi PerilakuDokumen12 halamanLaporan Modifikasi PerilakuMuhammad Iqbal Fakhrul FirdausBelum ada peringkat
- Opini. Matinya Kertas, Matinya Kepakaran. Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus. FPPsi UMDokumen3 halamanOpini. Matinya Kertas, Matinya Kepakaran. Muhammad Iqbal Fakhrul Firdaus. FPPsi UMMuhammad Iqbal Fakhrul FirdausBelum ada peringkat
- Bab I Dan IIDokumen8 halamanBab I Dan IIMuhammad Iqbal Fakhrul FirdausBelum ada peringkat
- Analisis Puisi UbaiDokumen4 halamanAnalisis Puisi UbaiMuhammad Iqbal Fakhrul FirdausBelum ada peringkat