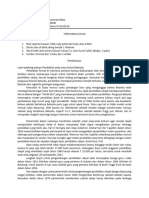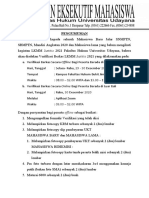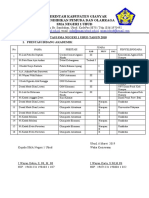Makalah Sej - Pend 01 Fix
Makalah Sej - Pend 01 Fix
Diunggah oleh
Dex Dauh0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
5 tayangan34 halamanJudul Asli
MAKALAH SEJ.PEND 01 FIX
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
5 tayangan34 halamanMakalah Sej - Pend 01 Fix
Makalah Sej - Pend 01 Fix
Diunggah oleh
Dex DauhHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 34
PENDIDIKAN ZAMAN PORTUGIS, SPANYOL DAN KOLONIAL
BELANDA
Disusun Oleh :
KELOMPOK 3
RIZA RIZKI SUKMARINI NIM. 1814021009
I WAYAN ARYA MAHENDRA NIM. 1814021024
I WAYAN SUARTIKA NIM. 1814021026
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN SEJARAH SOSIOLOGI DAN PERPUSTAKAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA
2019
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang mana
telah memberikan kami semua kekuatan serta kelancaran dalam menyelesaikan
makalah mata kuliah Sejarah Pendidikan yang berjudul “Pendidikan Zaman
Portugis, Spanyol, dan Kolonial Belanda” dapat selesai seperti waktu yang telah
direncanakan. Tersusunnya makalah ini tentunya tidak lepas dari berbagai pihak
yang telah memberikan bantuan secara materil dan moril, baik secara langsung
maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih
kepada :
1. Bapak Dr. Drs. I Made Pageh, M.Hum dan Wayan Putra Yasa, S.Pd.,
M.Pd selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Universitas
Pendidikan Ganesha.
2. Orang tua yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis
sehingga makalah ini dapat terselesaikan.
3. Teman-teman yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat
agar makalah ini dapat di selesaikan.
Selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis, makalah ini
disusun untuk memenuhi salah satu tugas Mata Kuliah Sejarah Pendidikan.
Makalah ini membahas tentang Pendidikan Zaman Portugis, Spanyol, dan
Kolonial Belanda.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik
dari bentuk penyusunan maupun materinya. Kritik konstruktif dari pembaca
sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan makalah-makalah selanjutnya.
Singaraja, 21 Maret 2019
Penulis
BAB I PENDAHULUAN
2.1. Latar Belakang
Pendidikan merupakan hal yang wajib serta sangat penting bagi setiap
negara.Pendidikan merupakan suatu hak serta kewajiban yang harus dimiliki bagi
setiap warga negara.Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang republik
indonesia yakni dalam pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “setiap warga negara berhak
mendapatkan pendidikan” hal tersebut sangat jelas bahwa pendidikan itu sangat
penting.
Selain itu pendidikan juga memiliki fungsi yakni untuk membangun serta
mempertahankan suatu negara agar negara tersebut tidak tertinggal dengan negara
lain.Dengan adanya pendidikan ini pola pikir masyarakat pun berubah,berbeda
dengan yang tidak mengenyam bangku pendidikan.Masyarakat memberi sepakat
untuk memperoleh pendidikan memiliki pemikiran yang lebih maju serta dewasa
berbanding terbalik dengan yang tidak berpendidikan.
Sejak zaman penjajahan pun pendidikan ini sangat diperhatikan salah satu
cara yang dilakukan agar pendidikan ini terlaksana yakni dengan cara bersekolah.
2.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas,maka didapatkan beberapa rumusan
masalah sebagai berikut :
1. Bagaimana ciri-ciri pendidikan zaman Portugis,Spanyol,dan Belanda di
Indonesia
2. Bagaimana sistem pendidikan zaman pemerintahan kolonial Belanda di
Indonesia?
2.3. Tujuan
1. Mengetahui bagaimana ciri-ciri pendidikan zaman Portugis,Spanyol,dan
Belanda di Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana sistem pendidikan zaman pemerintahan kolonial
Belanda di Indonesia.
BAB II PEMBAHASAN
2.4. Ciri-Ciri Pendidikan Zaman Portugis, Spanyol, dan Belanda di
Indonesia.
Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan
dengan penyebaran agama Katholik. Demi kepentingan tersebut, tahun 1536
mereka mendirikan sekolah (Seminarie) di Ternate, selain itu didirikan pula di
Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama Katolik, ditambah
pelajaran membaca, menulis dan berhitung. Pendidikan diberikan bagi anak-anak
masyarakat terkemuka. Pendidikan yang lebih tinggi diselenggarakan di Gowa,
pusat kekuasaan Portugis di Asia. Pemuda-pemuda yang berbakat dikirim ke sana
untuk dididik. Pada tahun 1546, di Ambon telah ada tujuh kampung yang
kedudukannya memeluk agama Nasrani Katolik.
2.5. Sistem Pendidikan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia.
Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di Indonesia
pada zaman ini, secara umum dapat dibedakan menjadi dua garis penyelenggaraan
pendidikan,yaitu : pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial
Belanda, kedua adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh rakyat dan Kaum
Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional) sebagai sarana perjuangan demi
merebut kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan
nasional. Berikut ini adalah pendidikan pada jaman kolonial belanda :
2.5.1. Pendidikan Zaman VOC
Pendidikan di zaman VOC menyelenggarakan sekolah dengan tujuan
untuk misi keagamaan (Protestan), bukan untuk misi intelektualitas, adapun
tujuan lainnya adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi rendahan di
pemerintahan dan gereja. Sekolah-sekolah utamanya didirikan di daerah-daerah
yang penduduknya memeluk Katholik yang telah disebarkan oleh bangsa
Portugis. Sekolah pertama didirikan VOC di Ambon pada tahun 1607. Sampai
dengan tahun 1627 di Ambon telah berdiri 16 sekolah, sedangkan di pulau-pulau
lainnya memiliki 18 sekolah. Kurikulum pendidikannya berisi tentang pelajaran
agama Protestan, membaca dan menulis. Kurikulum pendidikan belum bersifat
formal, (belum tertulis), dan lama pendidikannya pun tidak ditentukan dengan
pasti. Murid-muridnnya berasal dari anak-anak pegawai, sedangkan anak-anak
rakyat jelata tidak diberi kesempatan untuk sekolah. Pada awalnya yang menjadi
guru adalah orang Belanda, kemudian digantikan oleh penduduk pribumi ,yaitu
mereka yang sebelumnya sudah dididik di Belanda. Sampai tahun 1779 jumlah
murid pada sekolah VOC adalah sebagai berikut : Batavia 639 orang, pantai utara
Jawa 327 orang, Makasar 50 orang, Timor 593 orang, Sumatera barat 37 orang,
Cirebon 6 orang, Banten 5 orang, Maluku 1057 orang dan Ambon 3966 orang.
Kegiatan pendidikan yang dilakukan VOC terutama dipusatkan di bagian
timur Indonesia dimana agama Katholik telah berakar dan di Batavia sebagai
pusat administrasi kolonial. Tujuan utama rupanya untuk menggantikan agama
Katolik dengan menyebarkan agama Protestan, Calvinisme. Jumlah sekolah cepat
bertambah. Pada tahun 1645 telah meningkat menjadi 33 sekolah dengan 1.300
siswa.
Sementara di Jakarta, sekolah pertama didirikan tahun 1630 untuk
mendidik anak Belanda dan Jawa agar menjadi pekerja yang kompeten pada
VOC. Pada tahun 1636 jumlahnya bertambah menjadi 3 sekolah. Tahun 1706,
jumlah sekolah terus meningkat dengan jumlah guru 34 orang dan murid
sebanyak 4.873 siswa. Yang menarik, sekolah-sekolah itu terbuka bagi semua
anak tanpa perbedaan kebangsaan.
Kurikulum di sekolah-sekolah selama VOC bertalian erat dengan gereja.
Menurut instruksi “Heeren XVII” badan tertinggi VOC di negeri Belanda yang
terdiri atas 17 orang anggota, tahun 1617 gubernur di Indonesia harus
menyebarluaskan agama Kristen dan mendirikan sekolah untuk tujuan itu.
Menurut peraturan sekolah tahun 1643 tugas guru ialah: memupuk rasa takut
kepada Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kristen, mengajar anak berdoa,
bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi orang tua, penguasa dan guru-guru.
Walaupun tidak ada kurikulum yang ditentukan, biasanya sekolah
menyajikan pelajaran tentang katekismus, agama, membaca, menulis, dan
bernyanyi.
Pembagian kelas dalam tiga kelas untuk pertama kali dilakukan di tahun
1778. Di kelas 3, kelas terendah, anak-anak belajar abjad. Di kelas 2 belajar
membaca, menulis, dan bernyanyi. Sementara di kelas 1, sebagai kelas tertinggi:
membaca, menulis, katekismus, bernyanyi, dan berhitung.
Mengajar dilaksanakan berdasarkan individual. Murid-murid datang seorang
demi seorang ke meja guru dan menerima bantuan secara individual. Menyanyi
lagu gerejani dan resitasi teks buku injil dilakukan bersama oleh seluruh kelas.
Semua sekolah di suatu wilayah berada di bawah pengawasan pendeta. Guru-
guru diangkat oleh Gereja Reformasi di Amsterdam. Sebelum dikirim ke tanah
jajahan mereka mula-mula diuji tentang kemampuannya membaca dan
menyanyikan lagu-lagu gerejani. Di antara mereka terdapat orang-orang seperti
penjahat, tentara, pembuat peti mati, bahkan bekas pastor Katolik dan Rabbi
Yahudi.
Masalah yang rumit dalam pendidikan adalah soal bahasa pengantar di
sekolah. Guru pertama di sekolah pertama di Ambon yang ingin menjadikan tanah
jajahan sungguh-sungguh sebagai tanah koloni Belanda, menggunakan bahasa
Belanda sebagai bahasa yang dicita-citakan atasannya. Ternyata hal tersebut gagal
karena bahasa Portugis dan Melayu lebih populer.
Karena kondisi itu, sejak tahun 1758 tidak ada lagi kebijakan mengirimkan
guru dari negeri Belanda. Jauh ke belakang sebelum itu, sebenarnya sudah
diupayakan usaha untuk mempopulerkan bahasa Belanda. Pada tahun 1674,
Gubernur Jenderal J. Maetsuvker mengeluh tentang peranan dominan dan bahasa
Portugis, bahkan di kalangan orang-orang Belanda itu seniri. Pada tahun 1780
kembali ditandaskan agar hanya bahasa Belanda yang digunakan di sekolah.
Tahun 1786, peraturan satu-satunya bahasa Belanda yang digunakan di
sekolah dicabut. Ini dilakukan dengan alasan bahwa orang tua dan anak-anak
tidak memahami bahasa Belanda. Bahasa Belanda bahkan kehilangan fungsinya
setelah kitab injil diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu pada tahun 1733. Akan
tetapi, nilai bahasa Belanda melonjak setelah diadakan Klein Abternaarsexamen
atau ujian pegawai rendah pada tahun 1864 yang menjadi syarat bagi
pengangkatan pegawai pemerintah. Bahasa Belanda menduduki tempat yang
dominan setelah merupakan jalan satu-satunya ke pendidikan menengah dan
tinggi.
Perkembangan pendidikan mulai merosot pada pertengahan abad ke-18.
Jakarta yang berpenduduk 16.000 jiwa hanya mempunyai 270 murid, Surabaya
hanya 24, dan di seluruh pulau Jawa hanya 350 murid. Pada tahun 1800, sejumlah
uang disumbangkan kepada sekolah di Jakarta namun tak diketahui apa yang
harus diperbuat dengan uang itu karena pada saat itu tak ada seorang pun guru
Belanda di sana. Pada saat yang kurang lebih bergeser dan waktu itu, VOC pun
dibubarkan.
2.5.2. Pendidikan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda
Sebagai kelanjutan dari zaman VOC, pendidikan pada zaman pemerintahan
kolonial Belanda pun mengecewakan bangsa Indonesia. Kebijakan dan praktek
pendidikan pada zaman ini antara lain :
a. Tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendels memerintahkan agar para bupati di
Pulau Jawa menyebarkan pendidikan bagi kalangan rakyat, tetapi kebijakan
ini tidak terwujud.
b. Tahun 1811-1816 ketika pemerintahan di bawah kekuasaan Raffles
pendidikan bagi rakyat juga diabaikan.
c. Tahun 1816 Komisaris Jenderal C.G.C Reindwardt menghasilkan Undang-
Undang Pengajaran yang dianggap sebagai dasar pendirian sekolah, tetapi
Peraturan Pemerintah yang menyertainya yang dikeluarkan tahun 1818 tidak
sedikit pun menyangkut perluasan pendidikan bagi rakyat Indonesia,
melainkan hanya berkenaan dengan pendidikan bagi orang-orang Belanda
dan golongan Pribumi penganut Protestan.
d. Di bawah Gubernur Jenderal Van den Bosch dikeluarkan kebijakan
Culturstelsel (Tanam Paksa) demi memperoleh keuntungan sebanyak-
banyaknya bagi Belanda. Karena untuk hal ini dibutuhkan tenaga kerja murah
atau pegawai rendahan yang banyak, maka tahun 1848 Gubernur Jenderal
diberi kuasa untuk menggunakan dana anggaran belanja negara sebesar
f25.000 tiap tahunnya untuk mendirikan sekolah-sekolah di pulau Jawa
dengan tujuan menghasilkan tenaga kerja murah atau pegawai rendahan. Pada
tahun 1849-1852 didirikan 20 sekolah (di tiap keresidenan). Namun sekolah
ini hanya diperuntukan bagi anak-anak Pribumi golongan priyayi/bangsawan,
sedangkan anak-anak rakyat jelata tidak diperkenankan. Penyelenggaraan
pendidikan bagi kalangan bumi putra yang dicanangkan sejak 1848
mengalami hambatan karena kekurangan guru dan mengenai bahasa
pengantarnya. Maka pada tahun 1852 didirikanlah Kweekschool (sekolah
guru) pertama di Surakarta, dan menyusul di kota-kota lainnya. Sekolah ini
pun hanyalah untuk anak-anak golongan priyayi.
e. Pada tahun 1863 dan 1864 keluar kebijakan bahwa penduduk pribumi pun
boleh diterima bekerja untuk pegawai rendahan dan pegawai menengah di
kantor-kantor dengan syarat dapat lulusan ujian. Syarat-syarat ini ditetapkan
oleh putusan Raja pada tanggal 10 September 1864. Demi kepentingan itu di
Batavia didirikanlah semacam sekolah menengah yang disempurnakan
menjadi HBS (Hogere Burger School).
f. Tahun 1867 didirikan Departemen Pengajaran Ibadat dan Kerajinan
g. Tahun 1870 UU Agraris dari De Waal yang memberikan kesempatan kepada
pihak partikelir untuk melaksanakan usaha dibidang pertanian mengakibatkan
meningkatnya kebutuhan akan pegawai. Hal ini berimplikasi pada perluasan
sekolah.
h. Tahun 1893 keluar kebijakan diferensiasi sekolah untuk Bumi Putera, yaitu
Sekolah Kelas I untuk golongan priyayi, sedangkan Sekolah Kelas II untuk
golongan rakyat jelata.
1) Setelah dilaksanakannya Politik Etis, pada tahun 1907 Gubernur Jenderal
Van Heutsz mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan Bumi Putera:
pertama, mendirikan Sekolah Desa yang diselenggarakan oleh Desa,
bukan oleh Gubernemen. Biaya dan sebagainya, menjadi tanggung jawab
pemerintah desa; kedua, memberi corak sifat ke-Belanda-an pada
Sekolah Kelas I. Maka pada tahun 1914 Sekolah Kelas I diubah menjadi
HIS (Holands Inlandse School) 6 tahun dengan bahasa pengantar bahasa
Belanda. Sedangkan Sekolah Kelas II tetap bernama demikian atau
disebut Vervoleg School (sekolah sambungan) dan merupakan lanjutan
dari Sekolah Desa yang didirikan mulai tahun 1907. Akibat dari hal ini,
maka anak-anak pribumi mengalami perpecahan, golongan yang satu
merasa lebih tinggi dari yang lainnya.
2) Pada tahun 1930-an usaha perluasan pendidikan bagi Bumi Putera
mengalami hambatan. Surat Menteri Kolonial Belanda Colijn kepada
Gubernur Jenderal de Jonge pada 10 Oktober 1930 menyatakan bahwa
perluasan sekolah negeri jajahan terutama untuk kaum Bumi Putera akan
sulit karena kekurangan dana. Dalam periode pemerintahan kolonial
Belanda, betapa kecilnya usaha-usaha pendidikan bagi kalangan Bumi
Putera. Sampai akhir tahun 1940 jumlah penduduk bangsa Indonesia
68.632.000, sedangkan yang bersekolah hanya 3,32%.
2.5.3. Pendidikan bagi Warga Belanda
Sekolah pertama bagi anak Belanda dibuka di Jakarta pada tahun 1817 yang
segera diikuti oleh pembukaan sekolah di kota-kota lain di Jawa. Dan tahun ke
tahun jumlahnya meningkat. Dan 7 sekolah di tahun 1820 menjadi 19 di tahun
1835. Lalu, meningkat lagi di tahun 1845 yang menjadi 25 sekolah, dan menjadi
57 di tahun 1857. Prinsip yang dijadikan pegangan tercantum di Statuta 1818
bahwa sekolah-sekolah harus dibuka di tiap tempat bila diperlukan oleh penduduk
Belanda dan diizinkan oleh keadaan, atau secara lebih khusus, apabila jumlah
murid mencapai 20 siswa untuk Jawa atau 15 siswa untuk di luar Jawa. Seorang
inspektur pendidikan diangkat dan pada tahun 1830 telah terdapat sekolah di
kebanyakan kota. Pada akhir abad ke-19 hampir tercapai taraf pendidikan universal
bagi anak-anak Belanda di seluruh Indonesia.
a. Europese Lagere School (ELS)
Sekolah Belanda atau Europese Lagere School (ELS) sejak mula
dimaksud agar sama dengan yang di Nederland. Tujuan utamanya ialah
mengembangkan dan memperkuat kesadaran nasional di kalangan keturunan
Belanda, yang kebanyakan indo Belanda, termasuk anak-anak yang lahir dan
hubungan yang tak legal. ELS yang didirikan pada tahun 1817 di Batavia
(Jakarta). Sekolah serupa ini boleh didirikan di tiap tempat asalkan jumlah
muridnya mencapai 20 siswa untuk di Jawa dan 15 jiwa untuk luar Jawa. Pada
tahun 1920, jumlah ELS telah meningkat menjadi 196 sekolah.
Tujuan ELS bukan lagi mendidik orang untuk taat beragama, melainkan
menjadi warga negara yang baik. Kurikulumnya terdiri atas mata pelajaran
membaca, menulis, berhitung, bahasa Belanda, sejarah, ilmu bumi dan mata
pelajaran lain. Mata pelajaran lain ini diisi dengan bahasa Perancis yang menjadi
dasar bagi siswa ELS agar dapat melanjutkan ke HBS.
ELS dapat dipandang sebagai alat politik yang sepenuhnya dikuasai dan
diawasi oleh pemerintah, karenanya pengajaran bahasa Belanda memegang
peranan utama dan meresapi semua mata pelajaran lain. Penguasaan bahasa
Belanda menjadi kunci menjadi pegawai. Kemampuan berbahasa Belanda
menjadi seorang digolongkan terdidik. Intelek dan menduduki tempat terhormat di
masyarakat. Ujian khusus, yakni Klein Ambtenaars examen yang mengutamakan
penguasaan Bahasa Belanda harus ditempuh agar memperoleh pekerjaan dalam
pemerintahan.
b. Hogere Burgerschool (HBS)
Murid-murid Europese Lagere School (ELS) dapat menempuh dua macam
ujian, yakni ujian pegawai rendah (Klein Ambtenaars examen) setelah kelas 6 dan
ujian masuk HBS (Hogere Burgerschool, sekolah menengah, setaraf dengan SMP
dan SMA sekarang), setelah kelas 7. Biasanya anak-anak ELS sekitar 80% lulus
untuk kedua macam ujian itu. Bagi anak lulusan ELS, memiliki ijazah Klein
Ambtenaars (pegawai rendah) belum menjamin pekerjaan.
HBS merupakan jalan satu-satunya ke universitas-universitas di negeri
Belanda. Mereka orang-orang Indonesia yang tidak meneruskan pelajarannya
dapat mengharapkan pekerjaan yang baik apabila memiliki ijazah HBS. Dalam hal
ini orang-orang Belanda berpolitik. Dengan membatasi jumlah anak Indonesia ke
ELS, maka orang-orang Belanda lah yang memonopoli pekerjaan-pekerjaan yang
tinggi dalam pemerintahan.
ELS merupakan sekolah rendah yang menjadi bagian yang integral dari
suatu sistem pendidikan bagi warga Belanda, maka sering dipikirkan usaha untuk
memperlancar peralihan antara ELS ke HBS. Periode 1900-1905, sekitar sepertiga
lulusan ELS yang melanjutkan pelajarannya ke sekolah kejuruan atau HBS.
Periode 1905-1909 lebih dari setengahnya; dan antara 1915-1919, jumlah ini
menjadi 80% atau empat dari lima anak.
c. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)
Tahun 1903 adalah tahun pendirian kursus MULO yang disambut baik
oleh kaum lndo-Belanda dan mereka yang tidak sanggup menyekolahkan anaknya
ke HBS yang dianggap mahal. MULO juga dianggap dapat memungkinkan
lulusannya bekerja di kantor pemerintah. Pada tahun 1914, kursus MULO diubah
menjadi sekolah MULO. Sekolah ini merupakan sekolah pertama yang tidak
mengikuti pola pendidikan Belanda, namun tetap merupakan pendidikan yang
berorientasi Barat dan tidak mencari penyesuaian dengan Indonesia. Kalangan
tertentu menginginkan MULO dikhususkan bagi anak-anak Belanda, akan tetapi
diputuskan agar MULO meniadi lembaga pendidikan untuk semua.
2.5.4. Pendidikan bagi Warga Bumi Putera
Ide liberal yang berdampak pada penyediaan fasilitas yang sebaik-baiknya
bagi anak-anak yang belajar, ternyata tidak berdampak bagi kalangan bumi putera.
Padahal, adanya Statuta 1818 yang menyatakan, ”pemerintah hendaknya membuat
peraturan yang diperlukan mengenai sekolah-sekolah bagi anak bumi putera.
Pemerintah memberi kesempatan pada anak bumi putera untuk mendapat
pendidikan di sekolah Belanda,” seolah menjadi harapan. Namun, ternyata
pemerintah hanya membuat peraturan tanpa menyediakan fasilitas untuk anak
Indonesia. Dengan demikian jumlah anak Indonesia yang bersekolah dengan
jumlah yang sangat minimal. Hal ini disebabkan karena Gubernur Jenderal
mengemukakan kebijaksanaan, sesuai dengan advis Dewan Hindia Belanda agar
jangan menerima anak China dan Bumi Putera tanpa rundingan dengan
pemerintah.
Selama setengah abad, pemerintah Belanda tak menyediakan satu sekolah pun
bagi anak-anak Indonesia dengan alasan menghormati bumi putera serta lembaga-
lembaga mereka dengan membiarkan penduduk di bawah bimbingan pemimpin
mereka. Alasan lain adalah kesulitan finansial yang berat dihadapi oleh Belanda
akibat Perang Diponegoro (1825-1830) yang mahal dan menelan banyak korban,
serta perang Belanda-Belgia (1830-1839).
sekolah bagi anak bumi putera.
Kondisi yang mendukung terlaksananya pendidikan pada anak bumi
putera pun berlanjut. Setelah tahun 1848, dikeluarkan peraturan-peraturan yang
menunjukkan bahwa pemerintah lambat laun menerima tanggung jawab yang
lebih besar atas pendidikan anak-anak lndonesia sebagai hasil perdebatan di
parlemen Belanda. Peraturan pemerintah pada tahun 1854 mengintruksikan pada
Gubernur Jenderal untuk mendirikan sekolah di setiap kabupaten bagi pendidikan
anak pribumi.
Bahkan, pada tahun 1863 mewajibkan Gubernur Jenderal untuk
mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk bumi putera
pada umumnya untuk menikmati pendidikan. Pada tahun itu pula Fransen van de
Putte Menteri Tanah Jajahan yang beraliran liberal berhasil mempercepat
pembangunan sekolah dengan meningkatkan biaya dari f25.000, menjadi
f400.000, maka tidak mengherankan jumlah murid Indonesia menjadi makin
bertambah dari 16.805 pada tahun 1866 menjadi 40.992 pada tahun 1882.
Seiring dengan pertumbuhan sekolah, lembaga yang mendidik para guru
seperti Sekolah Pendidikan Guru dibuka secara beruntun. Dalam rentang tahun
1852-1879 telah ada sepuluh lembaga serupa. Keadaan ekonomi yang
menguntungkan memungkinkan de Putte mewujudkan progam pendidikannya.
Didirikanlah Departemen Pendidikan, Agama dan Industri untuk
menyelenggarakan sekolah-sekolah. Sayang, tahun 1870 ekonomi kembali
memburuk. Peperangan pemerintah dengan raja-raja lndonesia menghabiskan
banyak biaya. Perang Aceh yang berlangsung 39 tahun menelan jutaan gulden dan
memengaruhi situasi ekonomi. Krisis ekonomi terberat terjadi di tahun 1884-1893
ketika harga gula sebagai komoditi ekspor utama jatuh diikuti oleh penyakit tebu
dan diadakan penghematan ketat.
Keadaan itu membuat pemerintah Belanda kembali menghitung dana
pendidikan. Karena dianggap lebih murah memberi subsidi sekolah swasta dari
pada memelihara sekolah pemerintah, maka sejak 1890 sekolah-sekolah dari
berbagai agama termasuk sekolah Islam yang memenuhi syarat dapat mengajukan
subsidi ke pemerintah.
2.5.5. Sekolah-sekolah untuk Bumi Putera
Sejak pemahaman pentingnya pendirian sekolah bagi bumi putera, mulai
tumbuh beberapa sekolah. Apabila dirinci, sekolah-sekolah tersebut adalah:
a. Sekolah Kelas Satu
Sekolah ini merupakan akibat dari krisis ekonomi yang dialami
pemerintah W.P. Groenevelt, seorang Direktur Pengajaran, agama dan industri
mengajukan usul yang akhirnya disetujui oleh Gunernur Jenderal Dewan Hindia
untuk mendirikan sebuah Sekolah Kelas Satu untuk aristokrasi dan orang berada
di kalangan bumi putera.
Kurikulum sekolah ditentukan sebagaimana peraturan tahun 1893 terdiri
atas mata pelajaran membaca, dan menulis dalam bahasa daerah dalam huruf
daerah dan latin; membaca dan menulis dalam bahasa melayu; berhitung ilmu
bumi Indonesia; ilmu alam; sejarah pulau tempat tinggal; menggambar dan
mengukur tanah.
Sekolah kelas satu tidak popular di kalangan priyayi karena tidak
memberikan pelajaran bahasa Belanda dan tidak membuka kesempatan untuk
memperoleh pendidikan lanjutan maupun kedudukan yang baik. ELS masih
merupakan satu-satunya lembaga bagi mereka yang menginginkan pendidikan
lanjutan. Sudah sewajarnya, orang tua anak Indonesia yang cukup berada
senantiasa mengajukan permohonan memasukkan anaknya ke ELS.
Mendapat berbagai desakan dan beratnya tanggungan ELS, maka pada
tahun 1907 bahasa Belanda dimasukkan ke dalam progam Sekolah Kelas Satu.
Meskipun demikian, pengajaran bahasa Belanda sangat lambat berangsurnya
karena kurangnya guru yang bersedia mengajar bahasa Belanda yang dipimpin
oleh kepala sekolah yang berbangsa lndonesia.
b. Sekolah Kelas Dua
Sekolah Kelas Dua merupakan pilah layanan pendidikan yang lain bagi
masyarakat bumi putera. Sekolah Kelas Dua dimaksudkan sebagai sekolah rakyat
yang memberi pendidikan yang sederhana bagi seluruh rakyat. Pada awalnya,
Sekolah Kelas Dua berlangsung hanya 3 tahun. Kemudian dalam perkembangan
berikutnya sekolah ini memiliki kesamaan waktu layanan dengan Sekolah Kelas
Satu, yakni selama 7 tahun.
Masalah pendidikan untuk warga pribumi tidak penah selasai. Selain
masalah keuangan, masalah lain akibat muncul Sekolah Kelas Dua adalah
sejumlah besar warga menjauhi kehidupan desa dan pekerjaan kasar dengan
mengharapkan pekerjaan-pekerjaan kantor. Menyadari hal itu, maka pemerintah
Belanda memecah minat masyarakat pribumi dengan mendirikan Sekolah Desa
yang mampu memberikan pengajaran sebesar-besarnya dengan biaya yang
serendah-rendahnya.
c. Sekolah Desa
Sekolah Desa dibandingkan dengan Sekolah Kelas Dua sangat jauh
berbeda. Anak-anak duduk di lantai seperti duduk di rumah sendiri. Kaleng-
kaleng kosong yang didapatkan cuma-cuma dari warung China dijadikan meja
tulis. Sebidang tanah yang dipagari dijadikan tempat penitipan kerbau karena
anak-anak yang belajar sambil menggembalakan kerbaunya. Selama belajar,
mereka hanya di awasi oleh seorang yang dewasa yang kemudian dijadikan guru.
Sekolah dibuka jam O9.00-12.00 dan 13.00-15.00 dengan kurikulum yang sangat
sederhana. Di bawah ini contoh kurikulum sekolah Desa di Aceh:
1) Kelas 1: Materi di kelas ini adalah membaca dan menulis bahasa Melayu
dan huruf Latin. Selain itu, terdapat pula latihan bercakap-cakap dan juga
berhitung dari angka 1 sampai dengan angka 20.
2) Kelas II: Materi yang disampaikan di kelas ini adalah materi lanjutan
membaca dan menulis dengan huruf Latin dan juga Arab. Di kelas II ini,
mulai diperkenalkan materi dikte dalam dua macam tulisan itu.
3) Kelas III: Mulai mengenal ulangan atau tes materi pelajaran yang telah
dipelajari. Demikian pula dengan berhitung sudah di atas 100. Di kelas ini
pun telah dikenalkan pecahan sederhana.
Akan tetapi, seperti haknya dengan Sekolah Kelas Dua, Sekolah Desa pun
segera dirasakan tidak memenuhi keinginan siswa untuk melanjutkan sekolah.
Dalam masa kemajuan komunikasi dan transportasi menjadi tidak mungkin lagi
mengisolasi desa dari pengaruh kota. Sejumlah anak yang belajar di Sekolah Desa
ingin dipindahkan ke Sekolah Kelas Dua.
Dorongan itu bertambah kuat karena terdapat anak-anak yang lulusan
Sekolah Desa yang diterima di kelas 3 Sekolah Kelas Dua. Kalau dihitung-hitung,
berarti mereka yang belajar di Sekolah Desa merugi satu tahun. Menyadari
banyaknya permintaan tersebut, akhirnya pemerintah Belanda mengakui resmi
peralihan itu dengan mendirikan Vervolgschool (sekolah sambungan), yang terdiri
atas kelas 4 dan kelas 5. Lambat laun, sekolah sambungan menjadi bagian dari
sistem sekolah Desa (Volksschool-Vervolgschool).
Kesulitan keuangan pemerintah (1922-1923) mempercepat perpaduan itu
dengan menjadikan Sekolah Desa (Volksschool) sebagai substruktur Sekolah
Sambungan (Vervolgschool) dengan mengadakan perbaikan kurikulum Sekolah
Desa. Akhirnya Sekolah Desa menjadi bagian dari Sekolah Kelas Dua, suatu hal
yang semula tidak diinginkan oleh pemerintah Belanda.
d. Holland Inlandse School (HIS)
Alasan prinsip dari pendirian HIS adalah keinginan yang kian menguat di
kalangan orang Indonesia untuk memperoleh pendidikan, khususnya pendidikan
Barat. Keinginan itu adalah konsekuensi yang wajar dari perubahan sosial politik
di Timur Jauh. Budi Utomo antara lain meminta dipermudahnya peraturan masuk
ELS karena hanya sekolah ini yang memberikan pendidikan yang sesuai untuk
menempuh ujian pegawai rendah dan OSVIA, STOVIA, dan NIAS.
Kurikulum HIS seperti tercantum dalam Statuta 1914 No. 764 meliputi
semua mata pelajaran ELS, bahkan lebih kaya dengan adanya mata pelajaran
menulis bahasa Melayu dan Arab, secara fleksibel. Artinya, bagi siswa China
mata pelajaran tersebut dapat saja dihilangkan.
Kurikulum HIS seperti halnya ELS tidak banyak mengalami perubahan.
Kurikulum ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan anak dan masyarakat
Indonesia akan tetapi, senantiasa berorientasi pada Nederland. Buku-buku yang
ditulis oleh pengarang Belanda memandang Indonesia dari sudut pandangnya
sendiri. Oleh karena itu, tak heran jiwa ke-Belanda-an meresapi sebagian besar
jiwa siswa HIS.
Lulusan HIS relatif banyak yang lulus dalam ujian pegawai rendah (Klein
Ambtenaar Examen). Sungguh suatu bukti akan keberhasilan sekolah ini.
Selanjutnya, para lulusan dapat diterima di STOVIA (School tot Opleiding voor
Indische Artseen, atau Sekolah Dokter Jawa) dan MULO. Selain itu, mereka dapat
memasuki Sekolah Guru, Sekolah Normal, Sekolah Teknik, Sekolah Tukang,
Sekolah Pertanian, Sekolah Menteri Ukur, dan lainnya dengan kemungkinan tidak
perlu ujian masuk.
e. Agemene Middelbare School (AMS)
Pendirian MULO sebagai lanjutan segala macam sekolah rendah yang
berorentasi Barat, khususnya HIS merupakan langkah yang sangat penting dalam
perkembangan suatu system pendidikan yang lengkap di Indonesia. Langkah
berikutnya adalah dibukanya AMS.
Sekolah ini merupakan super-struktur MULO yang terbagi atas bagian A
yang mengutamakan Sastra dan Sejarah dan bagian B yang mengutamakan
Matematika dan Fisika. Bagian A dibagi lagi menjadi A1 untuk studi Klasik
Timur dan bagian A2 untuk studi Klasik Barat. AMS bagian B pertama yang
mengutamakan Matematika dan Fisika secara resmi dibuka di Jakarta (1919) dan
AMS A2 Klasik Barat di Bandung (1920), dan AMS A1 Klasik Timur di Solo
(1926). Ijazah AMS disamakan dengan HBS untuk memasuki perguruan tinggi
atau menduduki jabatan tertentu. Dengan demikian, terbuka jalan bagi anak-anak
Indonesia untuk mengecap pendidikan di Universitas.
f. Pendidikan bagi Warga China
Jika memang harus disebutkan layanan pendidikan khusus untuk orang-
orang China bisa dikatakan hanyalah satu sekolah, yakni; Hollands Chinese
School (HCS). Ini pun apabila ditelusuri sejarahnya dengan sungguh-sungguh,
bukan karena inisiatif pemerintah tetapi karena desakan dari warga China yang
menginginkan pendidikan yang merata dan lebih baik.
Sampai tahun 1908, tiga abad setelah orang Belanda datang ke Indonesia,
Belanda tidak bersedia memberi bantuan finansial kepada warga China padahal
mereka adalah pembayar pajak yang baik. Di sisi lain, sebagaimana warga bumi
putera, warga China pun kesulitan memasuki ELS. Mereka mencoba dengan
berbagai cara, seperti bersedia membayar guru Belanda dengan biaya tinggi.
Namun, permintaan itu pun ditolak. Karena kesulitan itu, mereka meminta
bantuan langsung dari China dan mengganti guru Belanda dengan guru Inggris.
Mereka berkeyakinan bahwa di luar Indonesia, yakni Semenanjung Malaya,
Filipina, Hongkong, India, bahkan Jepang hanya terbuka bagi mereka yang
menguasai bahasa Inggris.
Di samping kondisi di atas, Kaisar China menunjukkan banyak perhatian
kepada perkembangan pendidikan di daerah jajahan Belanda. Disadarinya bahwa
melalui pendidikan dapat dicapai hubungan yang lebih erat antara China
perantauan dengan tanah leluhurnya. Dengan dasar itu, maka Kementerian
Pendidikan di Peking memperoleh cap resmi untuk mempergunakan semua
korespondensi. Pemuda-pemuda China diajak menjalani latihan militer di
Tiongkok. Bahkan, Peking merencanakan sebuah Universitas untuk pelajar-
pelajar dari Indonesia.
Sebagai konsekuensi kebangkitan nasional itu bahasa China menjadi pusat
pendidikan. Pendidikan nasionalistis di Tiong Hoa Hwee Kuan (THHK) yang
mengajar bahasa China dan Inggris dengan mengesampingkan bahasa Belanda
menjadi ancaman terhadap supermasi kultural dan mungkin politik Belanda.
Orang China memandang rendah terhadap bahasa dan kebudayaan Belanda,
bahkan dirasakan suasana anti-Belanda.
Keadaan ini menyadarkan pemerintah Belanda dan memutuskan untuk
membuka Hollands Chinese School (HCS) pada tahun 1908. Tujuannya jelas,
agar dengan pengantar bahasa Belanda akan terkalahkan keinginan untuk
mempelajari bahasa dan kebudayaan China. Maka, disusunlah kurikulum HCS
yang sama dengan ELS agar memberikan pendidikan Belanda yang murni kepada
anak-anak China.
Dalam penerapan di lapangan, HCS dapat lebih lengkap daripada ELS.
Ada pengajaran bahasa Inggris dan Prancis pada sore hari yang didapatkan anak-
anak HCS. Selain itu, ada kelas persiapan bagi siswa berusia 5 tahun agar lebih
mudah mendapatkan pelajaran di kelas satu.
Sementara itu pengajaran bahasa China yang tadinya sebagai bahasa
pengantar dan pusat pendidikan menjadi terbengkalai. Walaupun ada keinginan
untuk kembali mendapatkan pengajaran bahasa China, pemerintah Belanda tidak
bersedia membiayai tujuan-tujuan nasionalistis. Sejajar dengan itu, bahasa Melayu
pun sulit pula diterima oleh orang China. Mereka mengangap bahasa itu sebagai
bahasa pasar dan hanya digunakan oleh pembantu. Orang China secara lambat
tapi pasti telah berupaya menggunakan bahasa Belanda di rumah tangga mereka
dan sebagai bahasa dan sebagai bahasa pergaulan sehari-hari.
2.5.6. Pendidikan yang Diselenggarakan Kaum Pergerakan Kebangsaan
(Pergerakan Nasional) dan Pendidikan Zaman Pendudukan Militerisme Jepang
Kegiatan belajar ini menyajikan sejarah pendidikan Indonesia pada zaman
Pemerintahan Kolonial Belanda yang diselenggarakan Kaum Pergerakan, dan
pendidikan pada zaman Pendudukan Militerisme Jepang. Kajian sejarah
pendidikan tersebut meliputi latar belakang sosial budayanya dan implikasinya
terhadap pendidikan. Dengan demikian, setelah mempelajari kegiatan belajar ini
Anda akan dapat menjelaskan pendidikan yang diselenggarakan Kaum Pergerakan
sebagai upaya perjuangan kemerdekaan dan rintisan pendidikan nasional, serta
dapat menjelaskan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Pendudukan
Militerisme Jepang.
2.5.7. Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan Nasional)
sebagai Sarana Perjuangan Kemerdekaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Nasional
Djumhur dan H. Danasuparta (1976) mengemukakan bahwa setelah tahun
1900 usaha-usaha partikelir di bidang pendidikan berlangsung dengan sangat
giatnya. Untuk mengubah keadaan akibat penjajahan, kaum pergerakan
memasukan pendidikan ke dalam program perjuanganya. Dewasa ini lahirlah
sekolah-sekolah partikelir (perguruan nasional) yang diselenggarakan para perintis
kemerdekaan. Sekolah-sekolah itu mula-mula bercorak dua:
1. Sekolah-sekolah yang sesuai haluan politik, seperti yang diselenggarakan
oleh: Ki Hadjar Dewantara (Taman Siswa), Dr. Douwes Dekker atau Dr.
Setyabudhi (Ksatrian Institut), Moch. Sjafei (INS Kayutanam) dan
sebagainya.
2. Sekolah-sekolah yang sesuai tuntutan agama (Islam), seperti yang
diselenggarakan oleh: Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib
di Padang panjang, dan lain-Iain. Selain itu, sebelumnya telah
diselenggarakan pula pendidikan oleh tokoh-tokoh wanita seperti R.A Kartini
(di Jepara), Rd. Dewi Sartika (di Bandung), dan Rohana Kuddus (di
Sumatera). Kebijakan dan praktek pendidikan yang diselenggarakan rakyat
dan kaum pergerakan antara lain sebagaimana diuraikan berikut ini:
a. R.A. Kartini, Rd. Dewi Sartika, dan Rohana Kuddus
Sekalipun tinggal di daerah yang berjauhan, R.A. Kartini, Rd. Dewi
Sartika, dan Rohana Kuddus menghadapi masalah yang relatif sama. Mereka
melihat kepincangan dalam masyarakat dan ketidakadilan terhadap wanita,
sehingga menghambat kemajuan kaum wanita karena adat kebiasaan yang
berlaku pada saat itu. Sebab itu, baik R.A. Kartini, Dewi Sartika, maupun
Rohana Kudus memiliki cita-cita yang relatif sama pula, yaitu keinginan
untuk bebas, berdiri sendiri, serta membebaskan kaum wanita (gadis-gadis)
Indonesia lainnya dari ketertinggalan dan ikatan adat kebiasaan. Mereka
masing-masing berupaya memperjuangkan emansipasi kaum wanita demi
perbaikan kedudukan dan derajat kaum wanita untuk mengejar kemajuan
melalui upaya pendidikan. Upaya-upaya pendidikan yang dilakukan mereka
adalah:
R.A. Kartini (1879-1904): Pada tahun 1903 Ia membuka ”Sekolah Gadis”
di Jepara, dan setelah menikah ia membukanya lagi di Rembang. Karena
usianya yang relatif pendek usaha Kartini di bidang pendidikan tidak
terlalu banyak, namun ia telah memberikan petunjuk jalan, melakukan
rintisan pendidikan bagi kaum wanita. Cita-citanya memberikan gambaran
perjuangan dan cita-cita kaum wanita Indonesia.
Rd. Dewi Sartika (1884-1947): Pada tahun 1904 Ia mendirikan ”Sakola
Isteri” (Sekolah Isteri). Murid pertamanya berjumlah 20 orang, makin
lama muridnya bertambah. Pada tahun 1909 sekolah ini melepas
lulusannya yang pertama dengan mendapat ijazah. Pada tahun 1912 di 9
kabupaten seluruh Pasundan telah dijumpai sekolah semacam Sekolah
Isteri Dewi Sartika. Pada tahun 1914 Sekolah Isteri diganti namanya
menjadi ”Sakola Kautamaan Isteri” (Sekolah Keutamaan Isteri), dan pada
tahun 1920 tiap-tiap kabupaten di seluruh Pasundan mempunyai Sakola
Kautamaan Isteri. Adapun untuk melestarikan sekolah-sekolahnya itu
dibentuk ”Yayasan Dewi Sartika”.
Rohana Kuddus (1884-1969): Rohana Kuddus dikenal sebagai wanita
Islam yang taat pada agamanya dan sebagaimana kedua tokoh di atas ia
giat sekali mempelopori emansipasi wanita. Selain sebagai pendidik, ia
pun adalah wartawan wanita pertama Indonesia. Sebagaimana
dikemukakan I. Djumhur dan H. Danasuparta (1976), pada tahun 1896
(pada usia 12 tahun) Rohana telah mengajarkan membaca dan menulis
(huruf Arab dan Latin) kepada teman-teman gadis sekampungnya. Pada
tahun 1905 ia mendirikan Sekolah Gadis di Kota Gedang. Pada tanggal 11
Februari 1911 ia memimpin Perkumpulan Wanita Minagkabau yang diberi
nama ”Kerajinan Amai Setia” yang kemudian dijadikan nama sekolahnya.
Rohana juga berjuang menerbitkan surat kabar khusus untuk wanita. Pada
tanggal 10 Juli 1912 Rohana menjadi pemimpin redaksi surat kabar wanita
di kota Padang yang diberi nama ”Soenting Melajoe”. Kurikulum
pendidikan mereka memiliki kesamaan pula, yaitu berkenaan dengan
membaca, menulis, berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan
kewanitaan agar mereka dapat berkarya.
b. Budi Utomo
Pada tahun 1908 Budi Utomo dalam kongresnya yang pertama (3-4
Oktober 1908) menegaskan bahwa tujuan perkumpulan itu adalah untuk
kemajuan yang selaras buat negeri dan bangsa Indonesia, terutama dengan
memajukan pengajaran, pertanian, peternakan, dagang, teknik industri, dan
kebudayaan.
c. Muhammadiyah
Pada tanggal 18 November 1912 K. H. Ahmad Dahlan mendirikan
organisasi perkumpulan Muhammadiyah di Yogyakarta. Muhammadiyah
dengan berbagai sekolahnya, didirikan dalam rangka memberikan pendidikan
bagi bangsa Indonesia sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia sendiri,
untuk mengatasi kristenisasi, dan untuk mewujudkan masyarakat Islam yang
melaksanakan ajaran al-Qur'an dan Hadits sesuai yang diajarkan Rosululloh
(Nabi Muhammad S.A.W).
Dasar/Asas dan Tujuan Pendidikan
Pendidikan Muhammadiyah berasaskan Islam dan berpedoman
kepada Al-Qur'an dan Hadits. Tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah
membentuk manusia muslim berakhlak mulia, cakap, percaya diri dan
berguna bagi masyarakat. Sebagai orang muslim harus mempunyai ciri-ciri
sebagai berikut: berjiwa tauhid yang murni; beribadah kepada Allah; berbakti
kepada orang tua dan baik kepada kerabatnya; memiliki akhlak yang mulia
dan halus perasaannya; berilmu pengetahuan dan mempunyai kecakapan; dan
cakap memimpin keluarga dan masyarakat (Abu Ahmadi, 1975).
d. Perkumpulan Putri Mardika
Perkumpulan Putri Mardika didirikan tahun 1912. Bertujuan
memajukan pengajaran anak-anak perempuan (Odang Muchtar, 1976).
e. Trikoro Dharmo
Pada tahun 1915 didirikan Trikoro Dharmo, dan selanjutnya berdiri
berbagai perkumpulan pemuda dan pelajar di berbagai tempat di tanah air
hingga terwujudnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Berbagai organisasi
pemuda dan pelajar ini bersama-sama gerakan lainnya menyumbangkan jasa-
jasa yang besar demi pendidikan nasional dan kemerdekaan Indonesia.
"Mereka bersepakat untuk memperbanyak kesempatan memperoleh
pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah sehingga dapat menampung
semakin banyak anak Indonesia, mempermudah untuk dapat mengikuti
pelajaran bagi semua lapisan masyarakat, dan agar para anak didik
mempunyai perasaan peka sebagai putra Indonesia” (H.A.R. Tilaar, 1995).
f. Perguruan Taman Siswa
Pada mulanya Ki Hadjar Dewantara (1889-1959) bersama rekan-
rekannya berjuang di jalur politik praktis, selanjutnya mulai tahun 1921
perjuangannya difokuskan di jalur pendidikan. Hal ini Beliau lakukan
mengingat Departemen Pengajaran Pemerintah Belanda bersikap
diskriminatif mengenai hak dan penyelenggaraan pendidikan bagi bangsa
kita. Pendidikan Kolonial tidak berdasarkan kebutuhan bangsa kita,
melainkan hanya untuk memenuhi kepentingan kolonial. Isi pendidikannya
tidak sesuai dengan kemajuan jiwaraga bangsa. Pendidikan kolonial tidak
dapat mengadakan perikehidupan bersama, sehingga kita selalu bergantung
kepada kaum penjajah. Pendidikan kolonial tidak dapat menjadikan kita
menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hadjar Dewantara keadaan ini
(penjajahan) tidak akan lenyap jika hanya dilawan dengan pergerakan politik
saja. Melainkan harus dipentingkan penyebaran benih hidup merdeka di
kalangan rakyat dengan jalan pengajaran yang disertai pendidikan nasional (I.
Djumhur dan H. Danasuparta, 1976). Sehubungan dengan hal di atas pada
tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta Ki Hadjar Dewantara mendirikan "National
Onderwijs Institut Taman Siswa" yang kemudian menjadi "Perguruan
Nasional Taman Siswa".
Dasar atau Azas Pendidikan
Pada pembukaan lembaga pengajaran Taman Siswa (3 Juli 1922), Ki
Hadjar Dewantara mengemukakan tujuh azas pendidikannya yang kemudian
dikenal dengan Azas Taman Siswa 1922. Ketujuh Azas tersebut adalah:
1. Hak seseorang akan mengatur dirinya sendiri dengan wajib mengingat
tertibnya kehidupan umum. Hendaknya tiap anak dapat berkembang
menurut kodrat atau bakatnya. Dalam mendidik, perintah dan hukuman
yang kita anggap memperkosa hidup kebatinan anak hendaknya
ditiadakan. Mereka hendaknya dididik melalui ”Among-methode”.
2. Pengajaran berarti mendidik untuk menjadi manusia yang merdeka
batinnya, merdeka fikirannya, dan merdeka tenaganya. Guru jangan
hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, melainkan harus
juga mendidik murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan
mengamalkannya demi kepentingan umum. Pengetahuan yang baik dan
perlu yaitu yang bermanfaat bagi kepentingan lahir dan batin dalam
hidup bersama.
3. Pendidikan hendaknya berasaskan kebudayaan kita sendiri sebagai
penunjuk jalan, untuk mencari penghidupan baru, yang selaras dengan
kodrat kita dan akan memberi kedamaian dalam hidup kita. Dengan
keadaan bangsa kita sendiri kita lalu pantas berhubungan bersama-sama
dengan bangsa asing.
4. Pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat umum daripada
mempertinggi pengajaran kalau usaha mempertinggi ini mengurangi
tersebarnya pengajaran.
5. Agar bebas, merdeka lahir batin, maka kita harus bekerja menurut
kekuatan sendiri.
6. Agar hidup tetap dengan berdiri sendiri, maka segala belanja mengenai
usaha kita harus dipikul sendiri dengan uang pendapatan sendiri.
7. Dengan tidak terikat lahir batin, serta kesucian hati, berminat kita
berdekatan dengan Sang Anak. Kita tidak meminta sesuatu hak, akan
tetapi menyerahkan diri untuk berhamba kepada Sang Anak. Sesudah
proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Asas Taman Siswa 1922,
Maksudnya pendidikan yaitu: menuntun segala kekuatan kodrat yang ada
pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-
tingginya. Tujuan pendidikan itu ialah kesempurnaan hidup lahir batin sebagai
satu-satunya untuk mencapai hidup selamat dan bahagia manusia, baik sebagai
satu-satunya orang (individual), maupun sebagai anggota masyarakat (social)”.
(Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977).
Penyelenggaraan Pendidikan
Berdirinya Perguruan Nasional Taman Siswa (1922) dimulai dengan
dibukanya sekolah untuk anak-anak di bawah umur 7 tahun yang diberi nama
Taman Lare atau Taman Anak kadang diberi nama penjelasan “Sekolab Froebel
Nasional atau Kindertuin”. Sebutan Taman Lare atau Taman Anak untuk anak di
bawah umur 7 tahun kemudian diganti namanya menjadi Taman Indria.
Alasannya karena anak-anak di bawah umur 7 tahun itu semata-mata berada pada
periode perkembangan pancainderanya.
Pada tahun-tahun berikutnya dibuka Taman Anak untuk anak-anak umur
7-9 tahun (kelas I-III); Taman Muda untuk anak-anak umur 10-13 tahun (kelas
IV-VI), dan kelas VII sebagai kelas masyarakat; Taman Dewasa (setingkat SMP);
Taman Madya (setingkat SMA); Taman Guru; dan Taman llmu (setingkat
Sekolah Tinggi). Taman Guru meliputi: Taman Guru BI, yaitu sekolah guru untuk
calon guru Taman Anak dan Taman Muda (satu tahun setelah Taman Dewasa);
Taman Guru BII (satu tahun setelah Taman Guru BI); Taman Guru BIII (satu
tahun setelah Taman Guru BII) yang menyiapkan calon guru Taman Dewasa.
Taman Guru BIII terdiri atas dua bagian: Bagian A (Alam/Pasti), yaitu bagi para
calon guru mata pelajaran alam/pasti; dan Bagian B (Budaya), yaitu bagi para
calon guru mata pelajaran Bahasa, Sejarah, dsb. Pada Taman Guru, selain
diselenggarakan Taman Gurtu BI s.d. BIII, juga diselenggarakan Taman Guru
lndriya, yaitu sekolah gurtu yang menyiapkan para calon guru untuk Taman
lndriya.
Ki Hajar Dewantara mendirikan pendidikan Kebangsaan yang terkenal
dengan nama Taman Siswa (3-7-1922). Sifat, Sistem, dan metode pendidikan
Taman Siswa diringkas kedalam empat kemasan yaitu Asas Taman Siswa, Panca
Dharma, Adat Istiadat dan semboyan atau perlambang serba sedikit tentang taman
siswa, secara obyektif Penerbitan Pemerintah Hindia Belanda menguraikan
sebagaimana dikutip Abdurrachman Surjomiharjo (1986:90).
Semula didirikan pada tahun 1922 di Jogyakarta, sekarang ini perguruan
Taman Siswa meliputi 40 Cabang, tiga diantaranya di Sumatra Timur dan empat
keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur dengan jumlah murid 5.140 orang.
Ibu Pawiyatan di Jogyakarta terdiri dari sebuah MULO dengan 238 murid,
sekolah rendah dengan 362 murid dan Schakelscool dengan 97 orang. Sejak tahun
1925, pada waktu sekolah rendah untuk pertama kali meluluskan muridnya, rata-
rata 70% dari mereka telah lulus ujian pegawai negeri rendah dan ujian masuk
MULO Kweekscool, yang didirikan pada tahun 1924.
Dari lulusan MULO pada tahun 1928, lima di antaranya Sembilan, dan
pada tahun 1929, enam diantara 14 telah lulus ujian masuk AMS atau berarti rata-
rata 45%, sedangkan 24 lulus Taman Guru (= MULO ditambah satu tahun Teori
dan ditambah lagi 1 tahun pendidikan Praktik) sekarang semua bekerja sebagai
guru pada Taman Siswa atau lembaga pendidikan Partikelir lainya. Pada tahun
1929 yang mencatat diri sebagai murid MULO begitu besar sehingga banyak yang
ditolak. Tentang Taman Siswa di Yogyakarta para ahli telah memberikan
penilaiannya dengan baik.
Di Batavia terdapat Taman Kanak-kanak dengan 60 murid di Kemayoran
dan sekolah Rendah (tipe HIS) dengan 200 murid di Jati Baru. Mulai tanggal 1
Juli sekolah rendah yang kedua didirikan di Kebon Jeruk. Sebuah asrama baru di
Jati Baru. Sekolah di Tegal mampu menyiapkan beberapa murid untuk ujian
masuk HBS, sedang sekolah Malang, yang menghasilkan calon-calon untuk
MULO pemerintah, pada tahun 1929 makin berkembang dengan mendirikan
sekolah pertemuan. Selain itu ada sebuah Schakelschool, dan pada tahun 1930
dilaksanakan sistem pondok di situ.
Mr. A. Jonkman, yang telah mengunjungi sekolah menengah Taman Siswa
di Bandung menulis bahwa pada waktu itu (1927) sekolah dipimpin oleh Sosro
Kartono, kakak R.A. Kartini, dan sebagai gurunya terdapat Ir. Soekarno dan Mr.
Sunario, sekolah itu kelihatannya bercorak nasional Indonesia dalam arti, bahwa
ia merupakan hasil kerja sendiri. Selanjutnya tampak sekolah itu mengikuti
MULO pemerintah.
Bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar. Diduga Mr. Sunario, yang
memberikan pelajaran dalam ilmu tata negara dan Sejarah, akan menitik beratkan
kepada corak lndonesia. Direktur Sosro Kartono lebih menyukai sekolah AMS
dengan bahasa timur Klasik dan memikirkan sebagai kelanjutan sebuah fakultas
sastra timur.
Sebagai hasil pemikiran Ki Hajar Dewantara, di bawah ini merupakan hal
yang harus dihargai dalam penerapan pendidikan dengan memperhatikan asas dan
tujuan taman siswa yakni bahwa:
a. Setiap orang mempunyai hak mengatur dirinya sendiri dengan terbitnya
persatuan dalam peri kehidupan umum.
b. Pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah yang dalam arti
lahir batin dapat memerdekakan diri.
c. Pengajaran harus berdasarkan pada kebudayaan dan kebangsaan sendiri.
d. Pengajaran harus tersebar luas sampai dapat menjangkau seluruh rakyat.
e. Sebagai konsekuensi hidup dengan kekuatan sendiri, maka harus mutlak
mempelajari diri sendiri segala usaha yang dilakukan.
f. Dalam mendidik anak-anak perlu adanya keiklasan lahir dan batin untuk
mengorbankan segala kepentingan pribadi demi keselamatan dan
kebahagiaan anak anak.
g. Kemudian ditambahkan dengan asas kemerdekaan, asas kodrat alam, asas
kebudayaan, asas kebangsaan dan asas kemanusiaan.
Banyak yang belum memahami betapa besar jasa Ki Hajar Dewantara.
Kekurangpahaman itu mungkin dapat dikikis dengan memulai mengenal tujuan
taman siswa, yakni:
a. Sebagai badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat tertib
dan damai.
b. Membangun anak didik menjadi manusia yang merdeka lahir batin, luhur
akal budinya, serta sehat jasmaninya untuk menjadi anggota masyarakat
yang berguna dan bertanggung jawab atas keserasian bangsa, tanah air, serta
manusia pada umumnya.
Demikianlah Ki Hajar Dewantara yang lekat dengan Taman Siswa. Jasa-
jasanya bagi peletakan dasar layanan pendidikan di Indonesia patut mendapatkan
penghargaan dengan mengenal dan mengambil manfaat dari apa yang telah
dilakukannya jauh sebelum kemerdekaan negara Indonesia.
g. Ksatrian Institut
Ksatrian Institut didirikan di Bandung oleh Ernest Francoist Eugene
Douwes Dekker (Multatuli atau Setyabudhi). Ia memimpin lembaga ini sejak
1922-1940. Dasar pendidikannya adalah kebangsaan Indonesia, terutama melalui
sejarah kebangsaan. Tujuan pendidikannya yakni menghasilkan ksatria
(ridderschap) bagi Indonesia Merdeka di masa datang. Sekolah kejuruan
merupakan organisasi dalam sistem pendidikan Ksatreian Institut, yang
diharapkan agar lulusannya menjadi nasionalis yang berguna dan dapat berdiri
sendiri serta mencari lapangan kerja yang praktis. Lulusan umumnya mendapat
tempat di perusahaan-perusahaan swasta atau berdiri sendiri. Sampai dengan
tahun 1937 perkembangan sekolahnya telah mencapai 9 sekolah yang tersebar di
Bandung, Ciwidey, dan Ciajur (Odang Muchtar, 1976).
h. Nahdlatul Ulama (NU)
Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926.
Salah seorang ulama yang membangun perkumpulan NU adalah K.H. Hasyim
Asy'ari, yang pernah menjadi Raisul Akbar perkumpulan ini. Sejak 1899 Beliau
telah membuka pesantren Tebuireng di Jombang. Sebelum menjadi partai politik
NU bertujuan: memegang teguh salah satu mazhab dari mazhab Imam yang
berempat, yaitu: 1. Syafi'I, 2. Maliki, 3. Hanafi, 4. Hambali dan mengerjakan apa-
apa yang menjadikan kemaslahatan untuk agama Islam. Untuk mencapai tujuan
tersebut, diselenggarakan berbagai usaha seperti: memajukan dan memperbanyak
pesantren dan madrasah serta mengadakan tabligh-tabligh dan pengajian-
pengajian, di samping usaha lainnya. Pada akhir tahun 1938 Komisi Perguruan
NU telah menetapkan susunan madrasah-madrasahnya sebagai berikut: Madrasah
Awaliyah (2 tahun); Madrasah Ibtidaiyah (3 tahun); Madrasah Tsanawiyah (3
tahun); Madrasah Mu'alimin Wusytha (2 tahun); dan Madrasah Mu'alimin Ulya (3
tahun). Selanjutnya setelah menjadi partai politik (Mei 1952) hingga sekarang NU
terus berjuang melakukan inovasi dan menyelenggarakan pendidikan (I. Djumhur
dan H. Danasuparta, 1976).
i. INS Kayutanam
Pendidikan untuk dan dari rakyat, merupakan rumusan yang dikemukakan
oleh Abraham Lincoln yang sangat dikenal itu, juga secara harfiah dipakai dalam
usaha pendidikan yang ingin membedakan rencana pelajarannya dari rencana
pelajaran pemerintah kolonial. Inti dari rencana itu adalah melaksanakan praktek,
yang berasal dari dan untuk rakyat banyak. Dicita-citakan untuk menanamkan
cara kesadaran berpikir barat, di dalam pengajaran, namun anak didik tidak
diarahkan cendekiawan setengah matang yang angkuh, tetapi akan menjadi
pekerja cekatan yang rendah hati. Murid yang ideal adalah yang memiliki cinta
kebenaran dalam hatinya, pengetahuan dalam otak. Antara keduanya memiliki
hubungan timbal balik, kegembiraan kerja dalam suasana kesehatan jasmani dan
rohani, mencintai tanah airnya tetapi sadar selalu sebagai bagian dunia seperti
yang dikemukakan oleh Muhammad Sjafei.
Tiga unsur pendidikan yang ingin dikembangkan dalam mencapai tujuan
tersebut, yaitu pembentukan watak, kebiasaan kerja sistematis, intensitas dan rasa
setia kawan antara para muridnya. Seperti juga pendapat Taman Siswa, sekolah
Kayu tanam menganggap pengajaran pemerintah Hindia Belanda bercorak berat
sebelah, yang hanya mementingkan kecerdasan saja. Praktek pengajaran dan
pendidikan pada waktu itu sama sekali kurang memperhatikan perkembangan
perasaan, kecakapan dan ketangkasan.
Indonesisch Nederland School (INS) didirikan oleh Mohammad Sjafei
(1895-1969) pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayutanam, Sumatera Barat. Pada
tahun 1950 kepanjangan INS diubah menjadi Indonesian Nasional School, dan
selanjutnya menjadi Institut Nasional Sjafei. Perjuangan INS juga diarahkan demi
kemerdekaan melalui pendidikan yang menekankan lulusannya agar dapat berdiri
sendiri tidak tergantung pada orang lain atau jabatan yang diberikan oleh kaum
penjajah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ag. Soejono (1979) pada awal
didirikannya INS mempunyai dasar pendidikan sebagai berikut:
1. Berfikir secara logis atau rasional. INS mementingkan berfikir logis sebab
menurut kenyataan, dalam masyarakat Indonesia saat itu masih banyak
orang yang berfikir secara mistik.
2. Keaktifan atau kegiatan. INS menggunakan banyak keaktifan anak dalam
pengajaran, latihan skill dan pendidikan agar anak bekerja beraturan dan
intensif. Lagi pula Moh. Sjafei menyadari, bahwa besar sekali pengaruh
keaktifan bagi pengalaman, fikir dan watak. Pendidikan kemasyarakatan.
Sesuai dengan sifat Indonesia, maka di INS diberikan banyak kesempatan
bekerja sama. Contoh: Majalah Rantai Mas dikerjakan bersama dan
merupakan tempat untuk mengadakan ekspresi dengan bahasa; bersama
menjalankan pertunjukan dan koperasi. Perkumpulan koperasi bukan saja
untuk memenuhi keperluan murid sehari-hari, melainkan juga sebagai
latihan bekerja bersama dalam lapangan ekonomi, yang menanti mereka,
apabila mereka kelak terjun ke dalam masyarakat. Bergotong royong adalah
ciri khas lndonesia.
3. Memperhatikan bakat anak. Anak yang ternyata pandai dan mempunyai
banyak kesanggupan dalam sesuatu mata pengajaran, setelah mengikuti
semua mata pengajaran, mendapat pendidikan lebih lanjut dan mendalam
untuk menyempurnakan bakat, hingga ia dapat menjadi ahli dalam vak itu.
4. Menentang intelektualisme. Hal tersebut di atas adalah beberapa usaha
untuk menjauhkan intelektualisme dari INS. Sejalan dengan hal di atas,
usaha-usaha yang lainnya adalah:
a) Pendidikan keindahan diperhatikan sungguh-sungguh. Ini terbukti
dengan dipentingkannya vak ekspresi; kerap diadakan pertunjukan;
bersama-sama murid mengatur gedung dan halamannya, dsb.
b) Rasa tanggung jawab dikembangkan melalui berbagai keaktifan, agar
anak didik berani berdiri sendiri. Penyelenggaraan dan perkembangan
INS sendiri memberi contoh dalam hal ini. Atas usaha sendiri Moh.
Sjafei menyelenggarakan INS yang megah itu. Tidak diterimanya
bantuan dari pihak mana pun seperti dari pemerintah Belanda yang
dapat mengikat hidup INS.
c) Perasaan keagamaan diberi kesempatan berkembang luas dan bersih
jauh dari kepicikan dan kekolotan.
Tujuan Pendidikan INS
Tujuan pendidikan INS Kayutanam sebagaimana dikemukakan Umar
Tirtarahardja dan La Sulo (1995) adalah sebagai berikut:
1) Mendidik rakyat ke arah kemerdekaan.
2) Memberi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3) Mendidik para pemuda agar berguna untuk masyarakat.
4) Menanamkan kepercayaan terhadap diri sendiri dan berani bertanggung
jawab.
5) Mengusahakan mandiri dalam pembiayaan.
Beberapa usaha yang dilakukan Ruang Pendidik INS Kayu Tanam yang
dalam bidang pendidikan antara lain menyelenggarakan berbagai jenjang
pendidikan, seperti Ruang Rendah (7 tahun, setara sekolah dasar), Ruang Dewasa
(4 tahun sesudah Ruang Rendah, setara sekolah menengah), dan sebagainya. Di
samping itu, INS Kayu Tanam juga menyelenggarakan usaha lain sebagai bagian
mencerdaskan kehidupan bangsa, yakni penerbitan Sendi (majalah anak-anak),
buku bacaan dalam rangka pemberantasan buta huruf/aksara dan angka dengan
judul Kunci 13, mencetak buku-buku pelajaran, dan lain-lain (Soejono, 1958:46).
Seperti diketahui, upaya-upaya dari Ruang Pendidik Pada bulan Juli Tahun 1927
dalam pidato pembelaannya Bung Hatta di pengadilan Den Haag mengusulkan
supaya ada perbaikan dalam berbagai bidang sosial, antara lain adalah bidang
pembinaan pendidikan nasional.
j. Kongres Pasundan pada tahun 1930 juga menempatkan pendidikan dan
pengajaran sebagai salah satu sarana utama perjuangannya.
k. Pada bulan November 1937 dalam kongres ke-26 Persatuan Guru
Indonesia (PGI) di Bandung dirumuskan supaya diadakan wajib belajar. Pada
Kongresnya tahun 1938 di Malang PGI menuntut agar pendidikan dan
pengajaran diserahkan ke daerah tetapi didahului dengan perbaikan keuangan
daerah. Tentu saja masih banyak lagi usaha-usaha rakyat, partai dan
organisasi yang berjuang dalam bidang pendidikan, seperti: Syarikat Islam
(SI), perjuangan PNI, berbagai pesantren, dsb. Muhammad Syafei adalah
seorang berdarah minang yang dilahirkan di Kalimantan Barat. Ia dilahirkan
tepatnya didaerah Natan tahun 1895. Ayahnya bernama Mara Sutan dan
ibunya Khadijah. Syafei berhasil menamatkan pendidikan dasarnya di sekolah
rakyat pada tahun 1908. Kemudian ia pun meneruskan pendidikannya ke
sekolah Raja(Sekolah Guru) dan lulus pada tahun 1914. Perjalanan hidup
mengharuskan dirinya hijrah ke Jakarta dan menjadi guru pada Sekolah
Kartini selama 6 tahun. Di sela-sela kesibukannya, ia menyempatkan diri
untuk Belajar menggambar. la aktif dalam Pergerakan Budi Utomo serta
membantu pergerakan wanita putri merdeka.
Pada tanggal 31 mei 1922 Muhammad Syafei berangkat ke negeri Belanda
untuk menempuh pendidikan atas biayanya sendiri. Beliau belajar selama 3 tahun
dan memperdalam ilmu musik, menggambar, pekerjaan tangan, sandiwara,
termasuk memperdalam pendidikan dan keguruan. Pada tahun 1925, beliau
kembali ke Indonesia untuk mengabdikan ilmu pengetahuannya.
Sekembalinya dari Belanda, Syafei menerapkan ilmunya dengan
mengelola sebuah sekolah yang kemudian dikenal sekolah INS Kayutaman, sebab
sekolah ini didirikan di Kayutaman. Kayutaman adalah sebuah nama desa kecil di
Sumatra barat, sedangkan INS sebuah lembaga pendidikan yang merupakan
akronim dari Nederlandsche School. Cikal bakal sekolah ini adalah milik jawatan
kereta api yang dipimpin oleh ayahnya yang pada tanggal 31 Oktober 1926
diserahkan kepada M. Syafei untuk dikelola. Akibat kemampuan Syafei
mengelola sekolah ini kemudian sekolah ini tersohor dengan nama ruang
pendidikan Indonesische Nederlandsche school (RP INS) Kayutaman.
Tujuan utama Syafei mendirikan INS adalah untuk mendidik anak-anak
agar dapat berdiri sendiri atas usaha sendiri dengan jiwa yang merdeka. Dengan
berdirinya sekolah ini, berarti ia menentang sekolah-sekolah Hindia-Belanda yang
hanya menyiapkan anak-anak untuk menjadi pegawai-pegawai mereka saja. RP
INS Kayutaman tahun 1926 memiliki 75 siswa terdiri dari 2 kelas (1A dan 18)
dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia.
Biaya operasional INS diperoleh dari berbagai kerajinan tangan siswa dan
kreatifitas lainnya, seperti dengan menggelar pertunjukan dengan tiket terjangkau,
tidak menerima subsidi dari pihak manapun termasuk dari pemerintah Belanda.
Dengan pecahnya perang dunia II 1941, INS diduduki secara paksa oleh
Belanda dan proses pembelajaran terhenti. Setelah Jepang menang tahun 1942 RP
INS berubah terjemahannya menjadi lndinesische Nippon School. Di zaman ini
pembelajaran merosot tajam yang disebabkan oleh sulitnya memperoleh alat-alat
pelajaran dan digunakan untuk bekerja serta berlatih demi kepentingan perang
Jepang.
2.5.8. Politik Pengajaran Hindia Belanda terhadap Sekolah Partikelir
Perkembangan sekolah-sekolah partikelir Indonesia seperti terurai di atas
mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Departemen Pengajaran dan
Ibadat. Pada tahun 1922 Direktur Pengajaran berpendapat bahwa telah tiba
waktunya bagi pemerintah untuk mengadakan pengawasan terhadap sekolah-
sekolah partikelir Indonesia dan China yang tidak bersubsidi. Hal itu dirasakan
perlu karena adanya pengaruh politik pergerakan kebangsaan berakibat merusak
pada sekolah-sekolah China karena makin berkembangnya suasana anti Belanda
berhubung dengan melonjaknya nasionalisme China.
Menurut rencana guru-guru pada sekolah-sekolah yang tidak bersubsidi
diharuskan mendaftarkan diri pada penguasa setempat dan akan diawasi dalam
menjalankan tugasnya. Untuk keperluan itu, maka pada tahun 1923 dibuatlah
ordonansi yang berisi ketentuan-ketentuan pengawasan terhadap sekolah-sekolah
partikelir yang tidak bersubsidi, di samping usaha-usaha untuk menciptakan iklim
agar suatu pengajaran yang baik dapat ditentukan pada sekolah-sekolah, yang
disebut sebagai sekolah liar (wilde scholen).
Pada tahun 1925 masalah pengawasan terhadap sekolah-sekolah partikelir
tidak bersubsidi dibicarakan lagi dalam nota Direktur Pengajaran waktu itu, maka
disarankan adanya pembentukan panitia yang akan menyelidiki soal-soal
organisasi dan kedudukannya di dalam struktur universitas yang telah ada.
Gubernur Jenderal setuju dengan gagasan itu, tetapi Raad van Indie (Dewan
Hindia) berpendapat bahwa waktu belum matang untuk mendidirikan fakultas
sastra
Dengan pendidikan yang bercorak lndonesia Centrisch itu dapat
diharapkan tercapai masyarakat yang harmonis. Dalam jangka panjang,
keberadaan sistem pendidikan yang demikian merupakan tanggul yang dapat
menahan arus revolusioner dalam masyarakat Indonesia. Untuk mempelajari
masalah itu dan guna kepentingan pembaharuan-pembaharuan yang diusulkan
perlu dibentuk komisi HIS yang kedua, disamping komisi yang telah ada.
Direktur pengajaran menolak usul-usul Van der Pias itu, tetapi Gubernur
Jenderal kurang setuju dengan garis pemikiran Direktur Pengajaran (yang
dikemukakan oleh wakil direkturnya, W.J.A.C. Bins). Ia juga tidak setuju dengan
pembentukan komisi HIS yang kedua. Masalah pengaruh denasionalisasi dari
pengaruh HISD akan tetap merupakan persoalan di masa yang akan datang.
Pada tahun 1929 Direktur Pengajaran dan Ibadat menjelaskan sikapnya
untuk menetapkan persyaratan bagi guru-guru di sekolah tidak bersubsidi agar
memiliki kualifikasi-kualifikasi tertentu. Tetapi demi kepentingan praktis, dan
kepentingan politik, maka ia menyarankan lebih jauh agar ditunda pelaksanaannya
pada waktu itu. Lebih baik pemerintah mengambil sikap tunggu dan lihat sambil
mengamati perkembangan.
Sebaliknya Dewan Hindia (Raad van Indie) berpendapat tindakan-
tindakan pembatasan bagi guru-guru mutlak diperlukan untuk melindungi
perorangan dan masyarakat dari pengajaran yang tidak bermutu. Pada waktu
bersamaan timbul masalah penggunaan bahasa Indonesia di sekolah-sekolah HIS.
Pejabat Direktur Pengajaran (B.J.O Schreke) mengemukakan berdasarkan
nasehat-nasehat yang diterimanya dari bupati-bupati di Jawa, Kepala Distrik di
Sulawesi dan Tapanuli, beberapa ahli soal-soal bumiputra dan ahli pendidikan,
maka bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib supaya dikeluarkan dari
mata pelajaran HIS di Jawa dan Madura, tetapi tetap di ajarkan di pulau-pulau
lainnya.
Dengan suratnya tanggal 13 Juni 1932. Direktur Pengajaran (B.J.O
Schreke) mengusulkan guru-guru pada sekolah-sekolah liar diharuskan memiliki
izin mengajar. Rencana ordonansi yang telah diajukan kepada Dewan rakyat
(Volksraad) ternyata telah mendapat usul-usul perubahan. Ordonansi tersebut
menimbulkan perlawanan-perlawanan di kalangan bangsa Indonesia, yang
dipimpin oleh Ki Hadjar Dewantara, pemimpin persatuan Perguruan taman Siswa.
Untuk menjajagi kemungkinan-kemungkinan yang lebih lunak dalam
melaksanakan aksi-aksi perlawanan itu, Gubernur Jenderal memerintahkan
Kiewiet de Jonge, kuasa pemerintah untuk soal-soal umum
(Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken) untuk mengadakan pembicaraan
dengan Ki Hadjar Dewantara di Yogyakarta. Laporannya sangat panjang dan
kecuali berisi soal-soal yang menyangkut ordonansi yang memuat pokok-pokok
pikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Perguruan taman Siswa, asas-asasnya
maupun kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam perguruan tersebut.
BAB III PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Pengaruh bangsa Portugis dalam bidang pendidikan utamanya berkenaan
dengan penyebaran agama Katholik.Demi kepentingan tersebut,tahun 1536
mereka mendirikan sekolah (Seminarie) di Ternate,selain itu didirikan pula di
Solor. Kurikulum pendidikannya berisi pendidikan agama katholik,ditambah
pelajaran membaca,menulis,dan berhitung.
Implikasi dari kondisi politik, ekonomi, dan sosial budaya di indonesia
pada zaman ini, secara umum dapat dibedakan menjadi dua aris
penyelenggaraan pendidikan,yaitu : pendidikan yang diselenggarakan oleh
pemerintah kolonial belanda ,kedua adaah pendidikan yang dilaksanakan oleh
rakyat dan kaum pergerakan nasional sebagai sarana perjuangan demi merebut
kembali kemerdekaan dan sebagai upaya rintisan ke arah pendidikan nasional.
Berikut ini adaah pendidikan pada jaman pemerintahan kolonial belanda :
1. Pendidikan Zaman VOC
2. Pendidkan Zaman Pemerintahan Kolonial Belanda
3. Pendidikan Bagi Warga Negara
4. Pendidkan Bagi Warga Bumi Putera
5. Sekolah-sekolah untuk Bumi Putera
6. Pendidkan yang Diselenggarakan Kaum Pergerakan Kebangsaan
(Pergerakan Nasional dan Pendidikan Zaman Pendudkan
Militerisme Jepang)
7. Pendidikan oleh Kaum Pergerakan Kebangsaan (Pergerakan
Nasional) Sebagai sarana Perjuangan Kemerdekaan dan
Penyelenggaran Pendidikan Nasional.
8. Politik Pengajaran Hindia Belanda terhadap Sekolah Partikelir.
3.2. Saran
Karena keterbatasan waktu dan kemampuan penulis, diharapkan kepada
pembaca agar memberikan masukan yang bersifat membangun demi
kesempurnaan makalah ini.
Anda mungkin juga menyukai
- Kurikulum Pendidikan Di ThailandDokumen26 halamanKurikulum Pendidikan Di ThailandNur Irma Oktaviana100% (2)
- Akta Pendirian PT Cahaya Satya AtmajaDokumen31 halamanAkta Pendirian PT Cahaya Satya AtmajaDex DauhBelum ada peringkat
- Dinamika Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda-1Dokumen20 halamanDinamika Pendidikan Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda-1KhanifaBelum ada peringkat
- Amalia Amanda Nasution Sejarah Tokoh Pendidikan Di Indonesia 2Dokumen17 halamanAmalia Amanda Nasution Sejarah Tokoh Pendidikan Di Indonesia 2Nuriana sari DalimunteBelum ada peringkat
- MAKALAH Sejarah - Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Sejak Kedatangan Bangsa Barat Sampai Menjelang Kemerdekaan Dari Tahun 1848Dokumen9 halamanMAKALAH Sejarah - Perkembangan Pendidikan Di Indonesia Sejak Kedatangan Bangsa Barat Sampai Menjelang Kemerdekaan Dari Tahun 1848Audrey SinyomanBelum ada peringkat
- C10 - Ginanjar Bima SaktiDokumen5 halamanC10 - Ginanjar Bima SaktiGinanjar Bima SaktiBelum ada peringkat
- Soal UtsDokumen4 halamanSoal UtsstrawartBelum ada peringkat
- Kurikulum Sebelum Kemerdekaan IndonesiaDokumen14 halamanKurikulum Sebelum Kemerdekaan IndonesiaKusuma VariioBelum ada peringkat
- PENDIDIKAN MASA PORTUGIS DAN VOC-Kelompok 3Dokumen11 halamanPENDIDIKAN MASA PORTUGIS DAN VOC-Kelompok 3Tika AnggraeniBelum ada peringkat
- Pendidikan Pada Masa PortugisDokumen7 halamanPendidikan Pada Masa PortugisRetno Eka WulansariBelum ada peringkat
- Tugas 2 Perjalanan Pendidikan Dari Masa Ke MasaDokumen4 halamanTugas 2 Perjalanan Pendidikan Dari Masa Ke MasaInayah Qarimah D'kaengBelum ada peringkat
- Pendidikan Sebelum Kemerdekaan Di IndonesiaDokumen11 halamanPendidikan Sebelum Kemerdekaan Di IndonesiaAnnisaBelum ada peringkat
- Resume Buku Landasan PendidikanDokumen17 halamanResume Buku Landasan PendidikanriduantoBelum ada peringkat
- Kondisi Pendidikan Di IndonesiaDokumen14 halamanKondisi Pendidikan Di IndonesiaRahmat HidayatBelum ada peringkat
- Filsafat Pendidikan Kolonial Kelompok 1Dokumen7 halamanFilsafat Pendidikan Kolonial Kelompok 1Tibbyyy lvvBelum ada peringkat
- Cetak Biru Pendidikan Indonesia KedepanDokumen6 halamanCetak Biru Pendidikan Indonesia KedepanDivani Rahma FitriBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 10.Dokumen13 halamanMakalah Kelompok 10.Wahyu Pratama HasibuanBelum ada peringkat
- Sejarah Dan Perkembangan PendidikanDokumen19 halamanSejarah Dan Perkembangan PendidikanRizky Mutiara AyuBelum ada peringkat
- Muhammar Pulungan - UTS Pilosofi Pendidikan IndonesiaDokumen4 halamanMuhammar Pulungan - UTS Pilosofi Pendidikan Indonesiappg.muhammarpulungan26Belum ada peringkat
- uAS PedagogikDokumen20 halamanuAS Pedagogikira100% (1)
- Kebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia BelandaDokumen28 halamanKebijakan Pendidikan Pemerintah Hindia BelandaLelin MusliadiBelum ada peringkat
- Kelompok 3 Sejarah Pendidikan Kolonial Belanda (1) - 1Dokumen30 halamanKelompok 3 Sejarah Pendidikan Kolonial Belanda (1) - 1DinaAnggrainiBelum ada peringkat
- Sejarah Pgri Sebelum KemerdekaanDokumen12 halamanSejarah Pgri Sebelum Kemerdekaanaf raffi06Belum ada peringkat
- Reading Report P4 - Mohammad Akbar - 22046040Dokumen5 halamanReading Report P4 - Mohammad Akbar - 22046040akbartais86Belum ada peringkat
- Perkembangan Pendidikan Antar Generasi Di IndonesiaDokumen4 halamanPerkembangan Pendidikan Antar Generasi Di IndonesiaFIEBIE ELCHINOBelum ada peringkat
- Materi 1Dokumen12 halamanMateri 1DevitaOktaviaKhatulistiwaBelum ada peringkat
- Pengembangan Kurikulum Pai Di Sekolah Umum Yuyun YunitaDokumen17 halamanPengembangan Kurikulum Pai Di Sekolah Umum Yuyun YunitaSalsabilaBelum ada peringkat
- LANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN KEL. 10. RevDokumen23 halamanLANDASAN HISTORIS PENDIDIKAN KEL. 10. Revazril nurjamanBelum ada peringkat
- CBR IlpenDokumen21 halamanCBR IlpenFram RitongaBelum ada peringkat
- SEJINDokumen6 halamanSEJINMuhammad MuhyiddinBelum ada peringkat
- Sejarah Pendidikan, by Kelompok 2Dokumen14 halamanSejarah Pendidikan, by Kelompok 2Putri S. DadungBelum ada peringkat
- Makalah Personal Calon Anggota Dewan PenDokumen22 halamanMakalah Personal Calon Anggota Dewan PenNano SuyatnoBelum ada peringkat
- t1 Filosofi Pendidikan Koneksi Antar MateriDokumen3 halamant1 Filosofi Pendidikan Koneksi Antar MateriAgung Adhi NugrohoBelum ada peringkat
- BJT 2 MKDK 4001 Paulina JulanDokumen11 halamanBJT 2 MKDK 4001 Paulina JulanSatrian RipianBelum ada peringkat
- Makalah Analisis Kurikulum - Rani RamadaniDokumen21 halamanMakalah Analisis Kurikulum - Rani RamadaniAnonymous 7h116owU0iBelum ada peringkat
- Pendidikan Merupakan Salah Satu Kebutuhan Manusia Untuk Bisa Berproses Dan Berinteraksi Di Dunia Luar Dengan Semua Masyarakat SekitarnyaDokumen8 halamanPendidikan Merupakan Salah Satu Kebutuhan Manusia Untuk Bisa Berproses Dan Berinteraksi Di Dunia Luar Dengan Semua Masyarakat SekitarnyaRohani songsBelum ada peringkat
- Revika - 856977924 - PDGK4104 - TT 1Dokumen10 halamanRevika - 856977924 - PDGK4104 - TT 1Revi Niskajepina IIBelum ada peringkat
- Sejarah Pendidikan IndonesiaDokumen4 halamanSejarah Pendidikan Indonesiaagues16Belum ada peringkat
- Diskusi 1 Perspektif Pendidikan SD - Honnil MazarniDokumen3 halamanDiskusi 1 Perspektif Pendidikan SD - Honnil MazarniRiki RenaldoBelum ada peringkat
- Jawaban Tutorial 2 Pengantar PendidikanDokumen8 halamanJawaban Tutorial 2 Pengantar PendidikanJust ZeTRiBelum ada peringkat
- Kelompok 1 PGRI 1 SalinanDokumen15 halamanKelompok 1 PGRI 1 SalinanFadil PrasetyaBelum ada peringkat
- Perkembangan Kurikulum Di Indonesia Dimulai Dari Zaman Sebelum Kemerdekaan Hingga SekarangDokumen7 halamanPerkembangan Kurikulum Di Indonesia Dimulai Dari Zaman Sebelum Kemerdekaan Hingga SekarangRIDWAN HBelum ada peringkat
- Article UasDokumen5 halamanArticle UasMoh. Badrul AnwarBelum ada peringkat
- Sejarah Pendidikan IndonesiaDokumen3 halamanSejarah Pendidikan Indonesiamuhammadhanroy5758Belum ada peringkat
- Kontekstualisasi Perjalanan Pendidikan NasionalDokumen2 halamanKontekstualisasi Perjalanan Pendidikan NasionalKumala SariBelum ada peringkat
- Sejarah Pendidikan IndonesiaDokumen11 halamanSejarah Pendidikan IndonesiasitisolikhahBelum ada peringkat
- Buku Sejarah Pendidikan Indonesia Yang DDokumen5 halamanBuku Sejarah Pendidikan Indonesia Yang Dpen adiBelum ada peringkat
- Pendidikan Di Indonesia Pra KemerdekaanDokumen28 halamanPendidikan Di Indonesia Pra KemerdekaanGusti Syarifudin Mi'rojBelum ada peringkat
- Sejarah Pendidikan Indonesia (LP)Dokumen14 halamanSejarah Pendidikan Indonesia (LP)sigit kurniawanBelum ada peringkat
- Resume Modul 5 Pengantar PendidikanDokumen3 halamanResume Modul 5 Pengantar PendidikanPutri Apriyani Pratiwi67% (6)
- Telaah KurikulumDokumen21 halamanTelaah KurikulumTali LusianBelum ada peringkat
- Proposal Penelitian Sejarah 1Dokumen12 halamanProposal Penelitian Sejarah 1NaufalhazamiBelum ada peringkat
- Pendidikan Pada Era PenjajahanDokumen8 halamanPendidikan Pada Era PenjajahanSilvi JelliantiBelum ada peringkat
- SEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA Kelompok 1Dokumen9 halamanSEJARAH KURIKULUM DI INDONESIA Kelompok 1muanigushaviraBelum ada peringkat
- Ringkasan 13407144007 PDFDokumen28 halamanRingkasan 13407144007 PDFadi jhonBelum ada peringkat
- Pendidikan Zaman Penjajahan BelandaDokumen34 halamanPendidikan Zaman Penjajahan BelandaGhaidanurulfauziyyahBelum ada peringkat
- Uas Artikel Sospen - Silvi Jellianti - 0035Dokumen9 halamanUas Artikel Sospen - Silvi Jellianti - 00350035 silvijelliantiBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Kurikulum 1Dokumen12 halamanSejarah Perkembangan Kurikulum 1Imam NirlekaBelum ada peringkat
- Kelompok 6 - Filsafat Pendidikan Kolonial - Pipa 1aDokumen12 halamanKelompok 6 - Filsafat Pendidikan Kolonial - Pipa 1aade arianti67% (3)
- Artikel SPI (INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM PADA PENDIDIKAN UMUM) Ahmad Rafi Indrawan - 2011060346Dokumen12 halamanArtikel SPI (INTEGRASI PENDIDIKAN ISLAM PADA PENDIDIKAN UMUM) Ahmad Rafi Indrawan - 2011060346Rafi IndrawanBelum ada peringkat
- Hermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganDari EverandHermeneutika Sunda: Simbol-Simbol Babad Pakuan/Guru GantanganPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (10)
- Kelompok 9 - Makalah Hukum DagangDokumen10 halamanKelompok 9 - Makalah Hukum DagangDex DauhBelum ada peringkat
- Kalimat EfektifDokumen8 halamanKalimat EfektifDex DauhBelum ada peringkat
- Contoh Norma Berpasangan Ada Pada Pasal 362 KUHPDokumen1 halamanContoh Norma Berpasangan Ada Pada Pasal 362 KUHPDex DauhBelum ada peringkat
- Pengeluaran Sie Humas Dan DokumentasiDokumen1 halamanPengeluaran Sie Humas Dan DokumentasiDex DauhBelum ada peringkat
- Berita Acara Hasil PelelanganDokumen4 halamanBerita Acara Hasil PelelanganDex DauhBelum ada peringkat
- Soal Kalimat PaduDokumen1 halamanSoal Kalimat PaduDex DauhBelum ada peringkat
- Form Verifikasi BerkasDokumen10 halamanForm Verifikasi BerkasDex DauhBelum ada peringkat
- Beriita Acara Ahli Digital ForensikDokumen8 halamanBeriita Acara Ahli Digital ForensikDex DauhBelum ada peringkat
- Tugas Hukum PidanaDokumen3 halamanTugas Hukum PidanaDex DauhBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa Inggris HukumDokumen2 halamanTugas Bahasa Inggris HukumDex Dauh0% (1)
- BAB V Tugas Bahasa Inggris HukumDokumen2 halamanBAB V Tugas Bahasa Inggris HukumDex DauhBelum ada peringkat
- Makalah AgamaDokumen13 halamanMakalah AgamaDex DauhBelum ada peringkat
- Resume Sejarah Perkembangan Administrasi Negara Di IndonesiaDokumen3 halamanResume Sejarah Perkembangan Administrasi Negara Di IndonesiaDex DauhBelum ada peringkat
- GENTODDokumen10 halamanGENTODDex DauhBelum ada peringkat
- Prestasi 2k18 AkademikDokumen1 halamanPrestasi 2k18 AkademikDex DauhBelum ada peringkat
- Surat Pernyataan OSIS 38Dokumen2 halamanSurat Pernyataan OSIS 38Dex DauhBelum ada peringkat