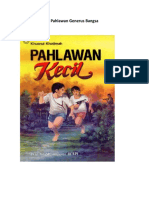Cerpen 95
Diunggah oleh
Geger GendroyonoDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Cerpen 95
Diunggah oleh
Geger GendroyonoHak Cipta:
Format Tersedia
Imam Ghazali
Imam Ghazali. Nama itu ia sandang sejak lahir, diberikan oleh bapaknya setelah meminta petunjuk
Mbah Jogo Mursid, orang paling tua dan dituakan di kampung Randuklampis dan sekitarnya. Bapaknya
sendiri bernama Nyamad; sedangkan emaknya, Bayem. Bertahun-tahun kemudian nama itu seolah
menjadi kutukan, membuatnya merasa tidak akan terlalu sengsara jika saja dulu bapaknya memberinya
nama Rawat, Seno, Lempung, atau apa saja asal bukan Imam Ghazali.
Kawan main dan orang-orang sekampung memanggilnya JALI, dengan tambahan n tidak penuh pada
pengucapan huruf awalnya. Sama sekali bukan masalah baginya. Semula, meskipun belum dan mungkin
tidak akan pernah membaca naskah drama Romeo dan Juliet gubahan Shakespeare yang terkenal itu, ia
tidak pernah menganggap penting sebuah nama, kecuali sebagai sekedar bunyi panggilan yang
membedakannya dari orang lain. Namun pandangannya tentang hal itu berubah drastis begitu ia masuk
pesantren.
Di dalam kelas, ketika Pak Ustadz memanggil namanya –biasanya untuk membaca materi sebelumnya
atau menghafal nadzoman di depan –suasana akan segera menjadi riuh rendah oleh gumam dan tawa-
tiwi tertahan. Bahkan, ketika kelas diisi oleh ustadz-ustadz muda yang masih kurang pamor dan wibawa,
bisa sampai ada yang melontarkan celetuk kasar dan candaan garing, yang anehnya selalu langsung
disambar tawa oleh seisi kelas.
Hampir seperti kepastian hasil yang akan kita peroleh dari soal penjumlahan dua ditambah dua, ia akan
bangkit dari bangkunya, lalu, dengan pandangan gugup, melangkah ke depan, dan berdiri di sana sampai
pelajaran berakhir. Begitulah yang selalu terjadi, hampir setiap hari, sepanjang tahun pelajaran, pada
setiap tingkatan. Ia selalu naik kelas, meskipun dengan nilai rata-rata di bawah empat untuk semua mata
pelajaran. Sopan santun dan penghormatan yang tinggi terhadap kiai dan guru adalah satu-satunya hal
yang memberinya syafaat di hari sidang kenaikan kelas.
Jangan salah. Jali bukan santri pemalas yang senang bermain-main dan mengabaikan belajar. Di
asramahnya, dari semua santri yang memanfaatkan waktu malamnya untuk belajar, bisa dikatakan ia
yang tidur paling akhir dan bangun paling awal. Bahkan, di dalam kelas, ia satu-satunya yang tetap
terjaga dan berupaya fokus mendengarkan penjelasan Pak Syamsudin, yang hanya sedikit kalah panjang
oleh jalur rel kereta api Surabaya-Jakarta, dan dengan intonasi serta nada yang terdengar seperti bunyi
detak jarum jam di malam hari.
Masalahnya, meskipun bisa membaca huruf-huruf dan tidak pernah lepas dari kitab-kitab, ia tidak
pernah dapat melekatkan apapun yang ia baca di pikirannya. Begitupula, setiap keterangan hanya
sampai di organ pendengaran dan kemudian menguap begitu saja. Tanpa bekas. Biarpun, misalnya, ia
telah membaca atau mendengarkan keterangan seribu kali hasilnya sama saja: gelap gulita.
Salah seorang kawannya, dengan nada simpati, pernah bertanya: “Apakah kepalamu terasa berat dan
pusing saat belajar?”
“Tidak. Biasa saja,” jawabnya.
“Lalu, apa yang kau rasakan?”
“Hanya sering kesemutan dan linu.”
“Hmm, menjadi jelas sekarang,” kata kawan yang baik budi itu, tetap dengan nada serius penuh simpati.
“Bisa jadi dulu malaikat salah meletakkan otakmu. Bukan di kepala. Mulai sekarang kau harus mengubah
gaya belajarmu.”
Selama berhari-hari ia merenungkan nasehat itu, lalu mencoba berbagaimacam gaya dan posisi belajar
yang anti-mainstream, tanpa sedikitpun menaruh curiga dan syak wasangka bahwa kawan yang baik
budi itu ternyata tertawa pingkal-pingkal di belakangnya.
Meskipun sedih, dan tentunya malu, ia tetap bertahan di pondok sampai tingkat lima. Bukan karena
tidak kerasan, tapi ada hal lain, yang tidak dapat ia jelaskan kepada siapapun, yang membuatnya harus
segera boyong dari pondok. Orang-orang hanya tahu bahwa menjelang ujian kenaikan tingkat, ia
ditimbali oleh Romo Yai dan beberapa waktu kemudian tidak pernah lagi terlihat ujung pecinya di
pondok.
Lagi pula, tidak ada hal yang membuatnya tidak betah tinggal di pondok. Berdiri di depan kelas setiap
mata pelajaran bukan persoalan besar baginya. Bukan persoalan pula ketika para ustadz tetap
memanggilnya ke depan, meskipun mereka tahu ia tidak akan pernah sanggup menuntaskan hapalan
atau memberi makna kitab gundul. Ia menganggap panggilan-panggilan itu sebagai bentuk kasih sayang
mereka terhadapnya.
Sedikit persoalan, yang justru paling membuatnya sengsara, adalah ketika kawan-kawannya menjadikan
namanya sebagai bahan candaan. Entah bagaimana hal itu membuat rasa malunya naik sampai ke
puncak langit. Membuat kulit wajahnya terasa tebal dan kebas. Ketika orang lain merasa bangga pada
nama terbaik yang diberikan orang tuanya, ia justru merasa sebaliknya. Ia merasa nama Imam Ghazali
itu terlalu besar dan berat untuk ia sandang. Jika Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad
al-Ghazali sanggup menegakkan dan menghidupkan syiar Islam dengan ilmu dan pengetahuannya, maka
yang paling mungkin dapat ia lakukan hanyalah menegakkan kedua kakinya di depan kelas dan
menghidupkan gelak tawa kawan-kawannya.
Salah satu kelakar terbaik, yang kerap ia dengar dari kawannya ialah: kelak ketika masing-masing orang
akan diabsen dengan nama panggilanya di hari pembalasan, Hujatul Islam Imam al-Ghazali akan pura-
pura tidak mendengar panggilan malaikat, semata-mata karena malu memiliki panggilan yang sama
dengannya.
Kelakar itu sudah begitu masyhur di pondok, didengar oleh semua guru dan bahkan sampai juga kepada
Romo Yai. Dan barangkali karena kelakar itu pula, pada suatu malam, ia dipanggil menghadap ke
ndalem, bersamaan waktunya dengan diriku.
“Kamu kerasan tinggal di pondok?” tanya Romo Yai.
Ia mengangguk pelan. Lalu menunduk lagi. Seolah tidak tahan bersitatap, barang satu kejap saja, dengan
Romo Yai.
“Biarpun kerasan, kamu tidak bisa tinggal selamanya di sini. Pada saatnya kamu tetap harus boyong.
Meninggalkan pondok. Dan rasa-rasanya saat itu sudah hampir tiba untukmu.”
Ia mengangkat wajahnya sekejap, lalu beralih menatapku, seolah meminta penjelasan kepadaku, yang
juga sama tidak mengerti seperti dirinya. Tetap tidak ada suara keluar dari mulutnya.
Lalu Romo Yai mengenalkan diriku kepadanya, yang tentunya sudah ia kenal betul karena sepanjang
tingkat lima telah mengisi kelasnya untuk pelajaran Nahwu Shorof.
“Beliau ini akan pindah dan membabat alas di daerah sekitar Lereng Awu-awu,” kata Romo Yai. “Di sana
masih suwung dan mungkin banyak sekali tantangannya. Jadi Beliau ini akan sangat membutuhkan
bantuanmu.”
Ia menatapku sekali lagi.
“Jangan kecil hati,” pesan Romo Yai. “Tidak ada yang diciptkan sia-sia di dunia ini. Dan jangan ragukan
kuasa Gusti Allah yang telah mengatur segalanya. Barangkali memang kelak dunia akan membutuhkan
seorang Imam Ghazali lain, yang akan menegakkan agama-Nya, meskipun bukan dengan bacaan
kitabnya, atau hafalan alfiyahnya. Ngerti?”
“Inggih, Yai…” jawabnya.
Sekitar lima hari kemudian kami berangkat ke Lereng Awu-awu. Mendirikan sebuah surau kecil, yang
menjadi cikal bakal sebuah pesantren besar, tempat bertemunya para santri dari seluruh dunia.
Anda mungkin juga menyukai
- Arifureta Jilid 01 (Premium) Upload by Http://isekaipantsu - Blogspot.co - IdDokumen297 halamanArifureta Jilid 01 (Premium) Upload by Http://isekaipantsu - Blogspot.co - IdisekaipantsuBelum ada peringkat
- AutobioDokumen4 halamanAutobiorayalbani2007Belum ada peringkat
- Karangan Gressya XI MIA1 Penderita Menjadikan Kita SahabatDokumen3 halamanKarangan Gressya XI MIA1 Penderita Menjadikan Kita SahabatGressya Damaris VioletaBelum ada peringkat
- Inbound 6714411793041342121Dokumen3 halamanInbound 6714411793041342121bilaBelum ada peringkat
- Upload TugasDokumen2 halamanUpload Tugasgampang lupaBelum ada peringkat
- Naskah Novel Kala ItuDokumen93 halamanNaskah Novel Kala ItuJaeBelum ada peringkat
- SINOPSISDokumen5 halamanSINOPSISUlfa Irma KasHanBelum ada peringkat
- Bukan Kaleng-Kaleng FixDokumen6 halamanBukan Kaleng-Kaleng FixMiftahul HaeraBelum ada peringkat
- SinopsisDokumen2 halamanSinopsisaisyah three asyaBelum ada peringkat
- Novel Ipi TamatDokumen32 halamanNovel Ipi Tamattia0% (1)
- Bab 1 - Diodara - Sosok DaraDokumen6 halamanBab 1 - Diodara - Sosok DaraWulandari SetyaniBelum ada peringkat
- PrologDokumen2 halamanPrologMeylita ViviyaniBelum ada peringkat
- Penggalan NovelDokumen6 halamanPenggalan Novelfaisalohm0% (2)
- Cerpen TalitaDokumen1 halamanCerpen Talitagata habBelum ada peringkat
- I Have Loved You, Oh So Many YearsDokumen12 halamanI Have Loved You, Oh So Many YearsInii CobaBelum ada peringkat
- Bab 8Dokumen7 halamanBab 8rafiqaBelum ada peringkat
- Teks Ulasan Hello Salma B. IndonesiaDokumen38 halamanTeks Ulasan Hello Salma B. IndonesiaKennethBelum ada peringkat
- Resensi NovelDokumen5 halamanResensi Novelherry candraBelum ada peringkat
- Tugas Indo Cerpen 2018Dokumen8 halamanTugas Indo Cerpen 2018Senja Jay YugureBelum ada peringkat
- KITA Rasa Diwaktu SalahDokumen234 halamanKITA Rasa Diwaktu SalahFrederic ChopinBelum ada peringkat
- Kenangan TerindahDokumen3 halamanKenangan Terindahsarif hidayatBelum ada peringkat
- UAS Kritik SastraDokumen5 halamanUAS Kritik SastraAsri Dwi RahmayantiBelum ada peringkat
- I Love Rosululloh SaidahDokumen6 halamanI Love Rosululloh Saidahsmk marsBelum ada peringkat
- Sriyanti - Cerpen - Aku Yang Tak DiperdulikanlDokumen4 halamanSriyanti - Cerpen - Aku Yang Tak DiperdulikanlSriyanti IbrohimBelum ada peringkat
- Resensi Film Negeri 5 MenaraDokumen3 halamanResensi Film Negeri 5 MenaraIde Indonesia LearningBelum ada peringkat
- Contoh Resensi Novel Negeri 5 MenaraDokumen3 halamanContoh Resensi Novel Negeri 5 MenaraMinmiee Merry Yelloicy CathabellBelum ada peringkat
- Tugas Teks Ulasan Negeri 5 Menara Berserta Struktur Dan Kaidah KebahasaanDokumen4 halamanTugas Teks Ulasan Negeri 5 Menara Berserta Struktur Dan Kaidah KebahasaanAnthon KurniawanBelum ada peringkat
- CerpenDokumen30 halamanCerpenIqbal Zea UntitleBelum ada peringkat
- Surat Terakhir Buat KakakDokumen4 halamanSurat Terakhir Buat KakakSiti Hawalia PontohBelum ada peringkat
- Bersyukur Bisa Berada Di Kelas IniDokumen2 halamanBersyukur Bisa Berada Di Kelas IniVolcanicOceanBelum ada peringkat
- Pelangi SenjakuDokumen12 halamanPelangi SenjakuAlvin NFBelum ada peringkat
- Resensi Novel OziiiDokumen6 halamanResensi Novel Oziiifauzanfadilah019Belum ada peringkat
- Sriyanti - Cerpen - Aku Yang Tak DipedulikanlDokumen4 halamanSriyanti - Cerpen - Aku Yang Tak DipedulikanlSriyanti IbrohimBelum ada peringkat
- Senna Puspita Rani - Resensi Novel Senyum Sahabat XI MIPA CDokumen4 halamanSenna Puspita Rani - Resensi Novel Senyum Sahabat XI MIPA CSennaa100% (1)
- Seloka 4PDDokumen1 halamanSeloka 4PDKhairul AfzalBelum ada peringkat
- Resensi BukuDokumen2 halamanResensi BukuSilvana SabillaBelum ada peringkat
- Resensi NovelDokumen13 halamanResensi NovelshaquaBelum ada peringkat
- Guruku PahlawankuDokumen5 halamanGuruku PahlawankuhazbiBelum ada peringkat
- Cerita TemanDokumen51 halamanCerita TemanRossa IndahBelum ada peringkat
- Resensi BukuDokumen1 halamanResensi BukuTata TarmaBelum ada peringkat
- Negeri 5 Menara,,,,,tugas BahasaDokumen4 halamanNegeri 5 Menara,,,,,tugas BahasaPahlevialiefBelum ada peringkat
- CERPENDokumen2 halamanCERPENKara MillerBelum ada peringkat
- Perusak PersahabatanDokumen1 halamanPerusak PersahabatanGilang RizkiBelum ada peringkat
- Resensi Novel "Ayahku (Bukan) Pembohong"Dokumen3 halamanResensi Novel "Ayahku (Bukan) Pembohong"YOGIE XG100% (1)
- CeritaDokumen5 halamanCeritaAlawiyah NurBelum ada peringkat
- Tugas Bahasa Indonesia - RaffaDokumen4 halamanTugas Bahasa Indonesia - RaffaRaffasya AbimataBelum ada peringkat
- Resensi Novel Ketika Cinta BertasbihDokumen2 halamanResensi Novel Ketika Cinta BertasbihMadesu WantonaBelum ada peringkat
- Novel JasmineDokumen4 halamanNovel JasmineNurul KhamidahBelum ada peringkat
- Cerpen - Keisha Azzahra TetadrianDokumen2 halamanCerpen - Keisha Azzahra TetadrianKeisha AzzahraBelum ada peringkat
- Novel - Haifatuzahro - Friends, Love, and VolleyballDokumen82 halamanNovel - Haifatuzahro - Friends, Love, and VolleyballHaifatuzahro0% (1)
- Isi CerpenDokumen58 halamanIsi CerpenHasnita NitaBelum ada peringkat
- Kritik B.indoDokumen2 halamanKritik B.indoDimas PrasetyoBelum ada peringkat
- Laporan Buku FiksiDokumen4 halamanLaporan Buku FiksiShafiyah PutriBelum ada peringkat
- Dokumen Tanpa JudulDokumen5 halamanDokumen Tanpa JudulElita HutaurukBelum ada peringkat
- Nona MawarDokumen17 halamanNona Mawarputrisondang27Belum ada peringkat
- Tentang KenanganDokumen2 halamanTentang KenanganahmadthursinaBelum ada peringkat
- Cerpen BERKAH DIBALIK PINTU PESANTRENDokumen5 halamanCerpen BERKAH DIBALIK PINTU PESANTRENguru mamidaBelum ada peringkat
- Pahlawan KecilDokumen6 halamanPahlawan Kecilحديد عبد الرحمنBelum ada peringkat