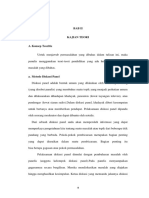Modul Toleransi Dalam Keberagaman (Instruktur) Ok
Modul Toleransi Dalam Keberagaman (Instruktur) Ok
Diunggah oleh
19 Muchammad Chafidz HidayatullohHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Modul Toleransi Dalam Keberagaman (Instruktur) Ok
Modul Toleransi Dalam Keberagaman (Instruktur) Ok
Diunggah oleh
19 Muchammad Chafidz HidayatullohHak Cipta:
Format Tersedia
PERKENALAN
Waktu: 2 Jam Pembelajaran /JPL (120 Menit) Efektif
S esi perkenalan tidak hanya berisi perkenalan dari seluruh peserta, panitia,
fasilitator dan narasumber, tetapi juga sekaligus dijadikan sarana untuk
membangun suasana keakraban, keterbukaan, kesetaraan (musawah) dan
kebersamaan. Acara perkenalan seperti ini penting dilakukan karena diantara para
peserta, panitia, fasilitator, dan narasumber belum kenal, sehingga masih ada
sekat-sekat diantara mereka. Disamping itu, satu sama lain belum bisa bersikap
terbuka dan saling percaya serta masih dibebani oleh kecurigaan dan perasaan
superior dan inferior akibat adanya hirarkhi sosial yang dibawa dari tempat
masing-masing. Acara perkenalan ini juga dapat difungsikan sebagai proses awal
untuk masuk ke materi pelatihan secara umum.
Tujuan
Di akhir sesi perkenalan ini peserta diharapkan :
1. Terbangun suasana akrab, cair, terbuka dan saling percaya satu sama lain
sehingga memudahkan dalam proses-proses selanjutnya;
2. Peserta, panitia, fasilitator, dan narasumber bisa saling mengenal satu sama
lain, baik persamaan maupun perbedaan-perbedaannya;
3. Tumbuh rasa setara diantara mereka, tidak ada yang lebih superior maupun
inferior;
4. Tumbuh suasana dinamis, aktif dan partisipatif dalam mengemukakan
pendapat, bertanya, maupun berargumentasi; dan
5. Seluruh peserta sudah memiliki kesiapan mental untuk memasuki pelatihan.
Pokok Bahasan
1. Persiapan menuju materi pelatihan;
2. Perkenalan seluruh peserta, panitia, fasilitator dan nara sumber;
3. Identifikasi masalah yang terkait dengan materi pelatihan.
Toleransi dalam Keberagaman
Metode
Metode yang dipakai dalam perkenalan dan kontak adalah penuturan lisan dan
brainstorming.
Bahan/ Alat
Kertas HVS, kertas plano, spidol sejumlah peserta, dan lakban.
Waktu
2 jam (120 menit) efektif
Langkah-langkah
1. Bukalah sesi dan jelaskan pentingnya perkenalan sebagai awal dari proses
pelatihan;
2. Tanyakan kepada peserta mengenai apa saja yang perlu diperkenalkan dan
bagaimana bentuk perkenalannya;
3. Usulkan kepada peserta suatu jenis perkenalan yang lebih akrab dan bisa
mengenal paling banyak karakter peserta. Yaitu, masing-masing kelompok
diminta untuk berhadapan (satu kelompok dua orang). Jika pesertanya ganjil,
ada satu kelompok yang berisi 3 orang. Masing-masing kelompok diminta
memperkenalkan minimal 5 identitas yang sama dan 5 identitas yang berbeda;
4. Beri waktu 5 menit untuk berkenalan satu-sama lain;
5. Masing-masing kelompok memperkenalkan diri;
6. Fasilitator memberi catatan terhadap perkenalan dan menyimpulkan apa hasil
perkenalan tadi;
7. Fasilitator berdialog dengan peserta mengenai problem intoleransi yang terjadi
di daerah masing-masing. Apa saja masalahnya, bagaimana kejadiannya, siapa
pelaku dan korbannya, serta apa saja yang telah dilakukan untuk mengatasi
masalah tersebut; dan
8. Fasilitator menyimpulkan hasil identifikasi masalah, lalu menutup sesi sambil
menjelaskan apa materi sesi berikutnya.
Toleransi dalam Keberagaman
Catatan untuk Fasilitator
Jika bentuk perkenalan di atas tidak memungkinkan, fasilitator bisa
memilih bentuk perkenalan lain yang lebih sesuai dengan kondisi dan situasi.
Yang penting, substansi perkenalan sebagai ajang membangun keakraban,
keterbukaan dan kesetaraan dapat diwujudkan.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam sesi ini adalah masalah waktu.
Terutama di saat beserta dimintai untuk menyampaikan pengalaman toleransinya
masing-masing. Waktu yang harus diawasi secara ketat, sehingga bisa
memberikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang sejarah toleransi dalam Islam.
Toleransi dalam Keberagaman
HARAPAN, KEKHAWATIRAN DAN KONTRAK PELATIHAN
Waktu: 1 jam pelajaran / JPL (60 menit efektif)
K ontrak Belajar adalah upaya membangun kesepakatan mengenai proses
pelatihan yang akan dilaksanakan. Kesepakatan ini terutama menyangkut
aturan main dan tata tertib agar pelatihan sesuai dengan harapan dan dapat
meminimalisasir kekhawatiran yang tidak diharapkan selama pelatihan.
Kesepakatan ini penting agar proses pelatihan berjalan dengan tertib dan lancar.
Tujuan
Kontrak belajar ini bertujuan untuk:
1. Membangun komitmen bersama mengenai aturan dan tata tertib pelatihan;
2. Menyepakati mengenai apa yang diharapkan dari pelatihan dan apa kontribusi
masing-maisng peserta agar harapan tersebut dapat diwujudkan; dan
3. Menjadikan kesepakatan, komitmen dan harapan di atas sebagai bahan
evaluasi di akhir pelatihan.
Pokok Bahasan
1. Pemetaan harapan peserta mengenai pelatihan dan bagaimana mewujudkan
harapan tersebut;
2. Pemetaan mengenai kekhawatiran peserta terhadap pelatihan dan bagaimana
menghindarinya; dan
3. Penyusunan kesepakatan mengenai materi, waktu, jadwal, dan tata tertib
pelatihan.
Metode
Metode yang dipakai dalam perkenalan dan kontrak belajar adalah diskusi
kelompok dan brainstorming
Bahan /Alat
Kertas Plano, kertas kecil (HVS), Spidol, White board
Toleransi dalam Keberagaman
Waktu
60 menit waktu efektif
Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan pentingnya kontrak pelatihan;
2. Fasilitator membagi peserta menjadi tiga kelompok. Masing-masing
mendiskusikan tentang: (a) harapan terhadap pelatihan ini, meliputi proses:
materi, metode, fasilitatoir, narasumber, bahan-bahan bacaan, pengelolaan
waktu, dan lain-lain; (b) kekhawatiran terhadap pelatihan; dan (c) kontribusi
yang dapat diberikan peserta agar proses pelatihan berjalan lancar;
3. Fasilitator memberi waktu kepada peserta untuk mendiskusikan materi
masing-masing;
4. Presentasi hasil diskusi kelompok;
5. Fasilitator memandu peserta untuk menjadikan hasil diskusi kelompok sebagai
tata tertib pelatihan;
6. Fasilitator menyandingkan mengenai kesepakatan di atas dengan alur materi
pelatihan, dalam rangka untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan antara
harapan peserta dengan alur yang sudah disiapkan; dan
7. Fasilitator menutup sesi sambil menjelaskan materi berikutnya.
Catatan untuk Fasilitator
Kontrak pelatihan adalah upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan
kekhawatiran terhadap pelatihan. Agar identifikasi tersebut dalam melebar, maka
fasilitator diharapkan memfokuskan diri pada upaya menciptakan kesepakatan
agar kebutuhan dan harapan peserta terhadap pelatihan ini bisa diwujudkan,
sekaligus kekhawatiran terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan bisa
diminimalisir. Karena itu, fasilitator diharapkan bersikap luwes, akomodatif,
mampu merangsang partisipasi peserta, tapi sekaligus tegas dalam memandu agar
pembahasan ini tidak melebar.
Toleransi dalam Keberagaman
Toleransi dalam Keberagaman
Materi untuk jenjang MI
PENGALAMAN TOLERANSI DALAM SEJARAH ISLAM
Waktu: 2 jam pembelajaran / JPL (120 menit) Efektif
M
ateri ini berisi tentang sejarah toleransi dalam Islam, yaitu masa
awal Islam hingga masa modern. Pemahaman terhadap sejarah
yang bernuansa toleransi tersebut diharapkan dapat memberi
keyakinan baru tentang toleransi sebagai warisan masa lalu yang mesti dijadikan
teladan. Dalam sesi ini, arus-arus toleransi dalam Islam akan dihadirkan secara
lebih mendalam, sehingga peserta dapat menjadikannya sebagai keniscayaan
dalam kehidupan kontemporer. Di sini, arti penting memelihara tradisi lama yang
baik menjadi kata kunci yang ditekankan kepada para peserta.
Tujuan
1. Menjelaskan tentang pentingnya toleransi dalam masyarakat yang majemuk,
baik dari segi agama, suku, ras, maupun bahasa;
2. Memberikan gambaran praktik-praktik toleransi dalam sejarah Islam di masa
lalu hingga masa kini. Karena itu, eksplorasi sejarah Islam harus disampaikan
secara sederhana, mudah dan mendalam; dan
3. Meyakinkan peserta, bahwa toleransi baik dari segi ajaran maupun sejarahnya,
bukanlah hal baru bagi Islam. Sejarah Islam sangat akrab dengan yang
namanya toleransi. Dan ajaran Islam juga tidak asing dengan toleransi. Bahkan
dalam beberapa hal tertentu, ajaran Islam adalah toleransi itu sendiri.
Pokok Bahasan
1. Toleransi pra Islam. Sebelum Nabi Muhammad saw. diangkat sebagai Rasul,
contohnya, orang-orang Arab Mekah sudah berkenalan dengan banyak
penganut agama dan keyakinan. Setiap tahun orang-orang dari luar Mekah
berdatangan ke kota itu untuk mengunjungi "Pasar Nusiman Ukhaz", sebuah
forum bagi para penyair Arab untuk memperlombakan syair mereka dan bagi
para pedagang untuk menawarkan barang dagangan mereka. Di antara
Toleransi dalam Keberagaman
pengunjung itu terdapat para pedagang dari suku-suku Arab yang sudah
memeluk Kristen;
2. Toleransi pada zaman Nabi Muhammad Saw. Seperti pengalaman Nabi
Muhammad saw. dengan seorang pembantu Kristen bernama Addas.
Sebagaimana tertulis dalam sejarah Islam Nabi Muhammad pernah berdakwah
di kawasan yang bernama Thaif. Namun masyarakat kota itu menolak dan
menzalimi Nabi Muhammad Saw. Hingga kemudian Addas di atas menolong
Nabi dan memberinya anggur;
3. Toleransi pada zaman sahabat. Sahabat Nabi yang terkenal alim dan cerdas,
yaitu Abu Musa Al Asy'ari, contohnya, banyak mempunyai pekerja beragama
Yahudi. Di masa Nabi Muhammad saw., sahabat ini pernah menawarkan jasa
untuk melibatkan para pekerjanya tersebut dalam peperangan yang dipimpin
Nabi Muhammad saw. Bahkan ketika Umar mencoba gubernurnya, Imam Al-
Asy'ari berargumen, bahwa untuk mereka agamanya. Tapi untukku pekerjaan
mereka.
4. Toleransi pada zaman kekhilafahan. Peradaban Baghdad yang tercatat sangat
gemilang dalam sejarah Islam, contohnya, terbentuk karena tradisi toleransi
yang mapan dalam kehidupan masyarakat. Di masa kekhalifahan ar-Rasyid,
contohnya, disebutkan bahwa non-Islam seperti Kristen juga mempunyai
semangat yang sama untuk memajukan Baghdad. Bahkan salah satu orang
yang sangat berjasa di bidang penerjemahan buku-buku Yunani kuno adalah
Jumain, seorang penganut agama Kristen. Dikisahkan, bahwa bunda ini pernah
mendapat penghargaan emas dari ar-Rasyid seberat buku-bukunya yang
diterjemahkan.
5. Toleransi pada zaman kontemporer. Mungkin, untuk sebagian, atau di
kawasan Islam tertentu, toleransi meredup, atau bahkan "padam". Namun
demikian, tak dapat dipungkiri, bahwa terdapat sekian banyak ulama yang
concern dengan pembahasan toleransi. Gagasan mereka sudah seharusnya
mendapatkan "panggung intelektual" yang lebih luas. Hingga gagasan-gagasan
mereka menyinari dunia Islam secara umum.
Toleransi dalam Keberagaman
Bahan / Alat
Spidol, kertas, LCD makalah, dan rangkuman materi (dalam bentuk power point)
Metode
Sesi ini akan menggunakan metode ceramah-dialog dan diskusi kelompok
Waktu
2 jam pembelajaran / JPL (120 menit) Efektif
Langkah-Langkah
1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan dan pokok-pokok bahasan;
2. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan pengalaman masing-masing
tentang toleransi dalam komunitas masing-masing. Fasilitator menanyakan
kepada peserta:
Apakah Anda mempunyai pengalaman toleransi dalam komunitas Anda
khususnya komunitas masyarakat, masjid, atau mushola?
3. Fasilitator merangkum pengalaman peserta dalam praktek toleransi;
4. Fasilitator mempersilahkan kepada narasumber untuk menjelaskan sejarah
toleransi dalam tradisi Islam. Penjelasan ini dalam rangka membuktikan
kepada peserta bahwa toleransi merupakan praktik keberagamaan yang
dipraktikkan oleh Nabi Muhammad saw.;
5. Fasilitator membuka sesi dialog dan tanya jawab dengan peserta tentang
khazanah toleransi dalam Islam. Pada sesi ini dibuka untuk 4 orang penanya;
6. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab pertanyaan,
komentar, dan tanggapan dari peserta;
7. Fasilitator membuka kembali sesi dialog dan tanya jawab untuk sesi kedua
untuk 4 orang penanya;
8. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab pertanyaan, komentar
dan tanggapan peserta; dan
9. Fasilitator merangkum dan membuat kesimpulan umum dari sesi ini.
Toleransi dalam Keberagaman
Catatan untuk Fasilitator
Upayakan ada ulasan lebih mendalam tentang beberapa pengalaman
toleransi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan peserta. Baik pengalaman
toleransi tersebut dari para fasilitator atau dari peserta. Hal ini penting, karena
memahamkan sesuatu yang sudah dirasakan jauh lebih gampang ketimbang yang
bersifat wacana.
Pada sesi ini biasanya selalu terdapat sebagian peserta yang mencoba
membantah fakta-fakta toleransi sebagaimana disampaikan oleh fasilitator. Para
fasilitator diharapkan mampu mengatasi masalah ini dengan baik. Karena ibarat
menanam pepohonan, sesi ini adalah "sawah" yang harus dikelola secara baik
sehingga tidak "gersang". Fasilitator sebagai pengelola sawah ini harus menjaga,
merawat, dan mengamankan sawah dari gangguan hama apapun.
Hal lain yang harus diperhatikan dalam sesi ini adalah masalah waktu.
Terutama pada saat peserta diminta untuk menyampaikan pengalaman
toleransinya masing-masing. Waktu yang harus diawasi secara ketat, sehingga
bisa memberikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang sejarah toleransi dalam
Islam.
Toleransi dalam Keberagaman
Materi jenjang MTs
PANDANGAN AL-QUR’AN, HADITS, DAN ULAMA
TENTANG TOLERANSI
Waktu: 2 jam (120 menit efektif)
S esi ini dimaksudkan untuk memperkenalkan dan menghadirkan konsep
umum Islam tentang toleransi (tasammuh), ditinjau dari sudut pandang
sumber-sumber ke-Islam-an yang otoritatif, yaitu Al-Qur’an, Hadits, dan
pandangan para ulama yang menjadi suatu keniscayaan. Karena keseluruhan
pemahaman ke-Islam-an meniscayakan adanya pandangan yang kuat dari teks-
teks suci dan tafsir ulama klasik. Selain itu, juga memberi pandangan tentang
toleransi dalam perspektif agama-agama dunia.
Tujuan
Setelah mengikuti sesi ini, peserta diharapkan dapat:
1. Memiliki pemahaman yang baik, cukup, dan mendalam tentang toleransi
dalam perspektif agama-agama;
2. Memiliki pemahaman yang baik, cukup, dan mendalam soal pandangan Al-
Qur’an tentang toleransi, sehingga peserta semakin terdorong untuk
memahami toleransi dan keberagaman;
3. Memahami hakikat pandangan hadits Nabi Muhammad saw. tentang toleransi,
sehingga dapat menampilkan pandangan yang cocok dalam khazanah hadits;
dan
4. Memahami pandangan para ulama terdahulu tentang toleransi, sehingga
peserta dapat memahami komitmen para ulama dalam membangun masyarakat
yang toleran.
Pokok Bahasan
Toleransi dalam Keberagaman
1. Memahami sejauhmana nilai-nilai toleransi dan keberagaman yang menjadi
nilai dasar dalam setiap agama-agama dan harus dijunjung tinggi bagi
pemeluknya dalam kehidupan bermasyarakat;
2. Memahami sejauhmana perhatian Al-Qur’an terhadap toleransi, terutama bila
dikaitkan dengan ajaran-ajaran lain yang sekilas bertentangan dengan toleransi
seperti ayat-ayat yang terkait dengan peperangan (qital), pemaksaan (ikrah),
pengkafiran (takfiri), pemurtadan (irtidad) dan sebagainya;
3. Memahami konteks ayat Al-Qur’an yang terkait dengan toleransi dan
intoleransi, serta menghindari menghakimi dengan menggunakan satu ayat
terhadap ayat lain, seperti penghakiman terhadap ayat-ayat toleransi dengan
menggunakan ayat yang sekilas tampak intoleran. Hingga bisa dipahami
bahwa ajaran Al-Qur’an tidak bertentangan antara yang satu dengan yang lain;
4. Memahami toleransi dalam prilaku Nabi, baik yang terkait dengan perkataan
(aqwal), perbuataan (af’al) atau pengakuan (taqrir);
5. Menelusuri toleransi sebagaimana dipraktikkan Nabi Muhammad saw. secara
lebih mendalam, baik toleransi di internal umat Islam, atau toleransi Nabi
Muhammad saw. terkait dengan umat lain seperti kaum Yahudi, Nasrani,
orang-orang Quraisy dan sebagainya;
6. Menghadirkan toleransi sebagaimana dianjurkan dan dipraktikkan oleh para
ulama Islam sebagaimana tertera dalam banyak karya-karyanya, terutama
dalam kitab-kitab Fikih;
7. Memahamkan bahwa perbedaan sebagai fakta yang meniscayakan adanya
toleransi merupakan hal yang bisa dalam kehidupan para ulama terdahulu,
terutama dalam ranah fikih;
8. Mengeksplorasi pandangan ulama tentang perbedaan pendapat secara lebih
mendalam. Seperti sikap empat Imam Madzab Fikih (Abu Hanifah, Imam
Malik, Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad bin Hanbal) dalam
menghadapi perbedaan pendapat di antara para imam tersebut; dan
9. Membedah sebab-sebab munculnya tindakan ekstremisme di antara kalangan
umat Muslim dan atau dengan umat lainnya pada era kontemporer.
Metode
Toleransi dalam Keberagaman
Ceramah, diskusi kelompok (tanya jawab), dan brainstorming
Bahan/Alat
Spidol, kertas plano, LCD, Al-Qur’an, hadits, dan kitab-kitab kuning
Waktu
120 menit waktu efektif
Langkah-langkah
1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan dan pokok bahasan;
2. Fasilitator membagi peserta dalam 3 kelompok dan menjelaskan hal-hal yang
didiskusikan dalam kelompok masing-masing;
3. Fasilitator memberikan tugas kepada setiap kelompok untuk mencari dan
mendiskusikan ayat-ayat, hadits, pendapat ulama, pandangan agama-agama
tentang toleransi. Adapun pembagian tugas kelompok sebagai berikut:
a. Kelompok 1 : mencari ayat-ayat tentang toleransi
b. Kelompok 2 : mencari hadits-hadits tentang toleransi
c. Kelompok 3 : mencari pendapat ulama dan pandangan agama-
agama tentang toleransi
4. Fasilitator mempersilahkan setiap kelompok untuk menyampaikan hasil
diskusinya dengan durasi waktu 10 menit;
5. Fasilitator merangkum secara umum hasil diskusi kelompok;
6. Fasilitator mempersilahkan kepada narasumber untuk menjelaskan secara
lebih luas tentang toleransi dalam Islam, khususnya dalam pandangan al-
Qur’an, hadits, ulama, dan pandangan agama-agama tentang toleransi;
7. Fasilitator membuka sesi tanya jawab kepada para peserta untuk tiga orang
penanya;
8. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab pertanyaan dari
peserta; dan
9. Fasilitator menutup sesi.
Toleransi dalam Keberagaman
Catatan untuk Fasilitator
Dalam setiap pembahasan seharusnya menyertakan landasan tekstualnya,
baik al-Qur’an, hadits, maupun pernyataan ulama. Hal ini dimaksudkan untuk
menutup rapat tentang keraguan dan menghapus kebingungan peserta menyangkut
pandangan Islam tentang toleransi.
Fasilitator diharapkan mempunyai persediaan jawaban dan argumen yang
memadai. Hal ini sangat penting, mengingat adanya beberapa ajaran dalam Islam
dan agama lainnya yang selama ini disalahpahami oleh sebagian umat Islam dan
agama lain. Biasanya kesalahpahaman ini berpangkal pada pengutipan beberapa
ajaran dalam Islam dan agama lainnya secara parsial (tidak utuh).
Toleransi dalam Keberagaman
AL-QURAN TENTANG TOLERANSI
Kategori Ayat / terjemahan
اَك َن النَّ ُاس ُا َّم ًة َّوا ِحدَ ًة ۗ فَ َب َع َث اهّٰلل ُ النَّ ِبنّٖي َ ُمبَرِّش ِ ْي َن َو ُمنْ ِذ ِر ْي َن ۖ َو َا ْن َز َل َم َعهُ ُم
ْال ِك ٰت َب اِب لْ َح ّ ِق ِل َي ْحمُك َ بَنْي َ النَّ ِاس ِف ْي َم ا ا ْختَلَ ُف ْوا ِف ْي ِه ۗ َو َم ا ا ْختَلَ َف ِف ْي ِه ِااَّل
اذَّل ِ ْي َن ُا ْوت ُْو ُه ِم ْۢن ب َ ْع ِد َما َج ۤا َءهْت ُ ُم الْ َب ِ ّينٰ ُت ب َ ْغ ًي ا ۢ بَيْهَن ُ ْم ۚ فَهَ دَ ى اهّٰلل ُ اذَّل ِ ْي َن ٰا َمنُ ْوا
ٍ ِل َما ا ْختَلَ ُف ْوا ِف ْي ِه ِم َن الْ َح ّ ِق اِب ِ ْذ ِن ٖه ۗ َواهّٰلل ُ هَي ْ ِد ْي َم ْن يَّشَ ۤا ُء ِاىٰل رِص َ ٍاط ُّم ْس َت ِقمْي
Manusia itu (dahulunya) satu umat. Lalu Allah mengutus para
Satu umat dan nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan.
beraga, Nabi sebagai Dan diturunkan-Nya bersama mereka Kitab yang mengandung
landasan toleransi kebenaran, untuk memberi keputusan di antara manusia
tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang
berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi (Kitab),
setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena
kedengkian di antara mereka sendiri. Maka dengan kehendak-
Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman
tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi
petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus
(Q.S. Al-Baqarah:213)
ِانَّٓا َا ْن َزلْنَ ا التَّ ْو ٰرى َة ِفهْي َ ا ُه دً ى َّون ُ ْو ٌۚر حَي ْ مُك ُ هِب َ ا النَّ ِبيُّ ْو َن اذَّل ِ ْي َن َا ْس لَ ُم ْوا ِلذَّل ِ ْي َن
َه اد ُْوا َو َّالراَّب ِن ُّي ْو َن َوااْل َ ْح َب ُار ِب َم ا ْاس ُت ْح ِف ُظ ْوا ِم ْن ِك ٰت ِب اهّٰلل ِ َواَك ن ُْوا عَلَ ْي ِه
ُشهَدَ ۤا َۚء فَاَل خَت ْ َش ُوا النَّ َاس َوا ْخ َش ْو ِن َواَل ت َ ْش رَت ُ ْوا اِب ٰ يٰيِت ْ ثَ َمنً ا قَ ِل ْياًل َۗو َم ْن ل َّ ْم
حَي ْ مُك ْ ِب َمٓا َا ْن َز َل اهّٰلل ُ فَ ُاو ٰلۤى َك مُه ُ ْال ٰك ِف ُر ْو َن
Sungguh, Kami yang menurunkan Kitab Taurat; di dalamnya
ِٕ
Taurat sebagai (ada) petunjuk dan cahaya. Yang dengan Kitab itu para nabi
petunjuk dan cahaya yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara
orang Yahudi, demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta
mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab
Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu
janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah
kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan
harga murah. Barangsiapa tidak memutuskan dengan apa yang
diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir (Q.S.
Al-Maidah: 44)
Keragaman َو ِم ْن ٰايٰ ِت ٖ ٓه َا ْن َخلَ َقمُك ْ ِّم ْن تُ َر ٍاب مُث َّ ِاذَٓا َانْمُت ْ بَرَش ٌ تَ ْنتَرِش ُ ْو َن
merupakan salah
Toleransi dalam Keberagaman
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia
satu ayat Tuhan
menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu
yang paling otentik
(menjadi) manusia yang berkembang biak (Q.S. Ar-Rum: 20).
آٰي َهُّي َا النَّ ُاس ِااَّن َخلَ ْق ٰنمُك ْ ِ ّم ْن َذ َك ٍر َّو ُانْىٰث َو َج َعلْ ٰنمُك ْ ُش ُع ْواًب َّوقَ َب ۤاى َل ِل َت َع َارفُ ْوا ۚ ِا َّن
ِٕ
Membangun ٌ اَ ْك َر َممُك ْ ِع ْندَ اهّٰلل ِ َاتْ ٰقىمُك ْ ۗ ِا َّن اهّٰلل َ عَ ِلمْي ٌ َخ ِبرْي
toleransi di tengah
kemajemukan Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari
merupakan salah seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami
satu bentuk takwa jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu
kepada Tuhan saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh,
Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. Al-Hujurat: 13)
الصاب ُِٔـ ْو َن َوالنَّرٰص ٰ ى َم ْن ٰا َم َن اِب هّٰلل ِ َوالْ َي ْو ِم َّ ِا َّن اذَّل ِ ْي َن ٰا َمنُ ْوا َواذَّل ِ ْي َن َه اد ُْوا َو
Jaminan surga bagi ااْل ٰ ِخ ِر َومَع ِ َل َصا ِل ًحا فَاَل خ َْو ٌف عَلَهْي ِ ْم َواَل مُه ْ حَي ْ َزن ُْو َن
orang-orang
Muslim, Yahudi, Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang
Nasrani dan Yahudi, shabiin dan orang-orang Nasrani, barangsiapa
penganut Sabian beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat
kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya dan mereka
tidak bersedih hati (Q.S. Al-Maidah: 69)
َو َما ا ْختَلَ ْفمُت ْ ِف ْي ِه ِم ْن يَش ْ ٍء فَ ُحمْك ُ ٗ ٓه ِاىَل اهّٰلل ِ ۗ ٰذ ِلمُك ُ اهّٰلل ُ َريِّب ْ عَلَ ْي ِه ت ََولَّك ْ ُ ۖت َو ِال َ ْي ِه
Tuhan sebagai ُا ِنيْ ُب
hakim tunggal atas
perbedaan Dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang
sesuatu, keputusannya (terserah) kepada Allah. (Yang memiliki
sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku. Kepada-Nya aku
bertawakal dan kepada-Nya aku kembali (Q.S. As-Syura: 10)
Menghargai agama لَمُك ْ ِديْ ُنمُك ْ َويِل َ ِد ْي ِن
orang lain sebagai
salah satu bentuk Untukmu agamamu, dan untukku agamaku (QS. Al-Kafirun: 6)
toleransi
Larangan ِم ْن َا ْج ِل ٰذكِل َ ۛ َك َت ْبنَ ا عَىٰل بَيِن ْٓ ِارْس َ ۤا ِءيْ َل َان َّ ٗه َم ْن قَتَ َل ن َ ْف ًس ۢا ِب َغرْي ِ ن َ ْف ٍس َا ْو
menebarkan
kekerasan dan فَ َسا ٍد ىِف ااْل َ ْر ِض فَاَك َن َّ َما قَتَ َل النَّ َاس مَج ِ ْي ًع ا ۗ َو َم ْن َا ْح َيا َه ا فَاَك َن َّ َم ٓا َا ْح َي ا النَّ َاس
pembunahan
مَج ِ ْي ًع ا َۗولَ َق دْ َج ۤا َءهْت ُ ْم ُر ُس لُنَا اِب لْ َب ِ ّينٰ ِت مُث َّ ِا َّن َك ِثرْي ً ا ِّمهْن ُ ْم ب َ ْع دَ ٰذكِل َ ىِف ااْل َ ْر ِض
لَ ُمرْس ِ فُ ْو َن
Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil,
bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang
itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat
kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh
semua manusia. Barangsiapa memelihara kehidupan seorang
manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan
semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang
Toleransi dalam Keberagaman
kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan
yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah
itu melampaui batas di bumi (Q.S. Al-Maidah: 32)
Anjuran agar ُ الس ِم ْي ُع الْ َع ِلمْي
َّ َوا ِْن َجنَ ُح ْوا ِل َّلسمْل ِ فَ ْاجنَ ْح لَهَا َوت ََولَّك ْ عَىَل اهّٰلل ِ ۗ ِان َّ ٗه ه َُو
mengutamakan Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka
perdamaian terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha
Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Anfal: 61)
َّ َو ِا ْذ َاخ َْذاَن ِم ْيثَاقَمُك ْ اَل ت َ ْس ِف ُك ْو َن ِد َم ۤا َءمُك ْ َواَل خُت ْ ِر ُج ْو َن َانْ ُف َس مُك ْ ِ ّم ْن ِداَي ِرمُك ْ ۖ مُث
َا ْق َر ْرمُت ْ َو َانْمُت ْ ت َ ْشهَدُ ْو َن
Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji kamu, “Janganlah
kamu menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan
mengusir dirimu (saudara sebangsamu) dari kampung
halamanmu.” Kemudian kamu berikrar dan bersaksi (Q.S. Al
Baqarah: 84)
مُث َّ َانْمُت ْ ٰهُٓؤ اَل ۤ ِء تَ ْق ُتلُ ْو َن َانْ ُف َس مُك ْ َوخُت ْ ِر ُج ْو َن فَ ِريْقً ا ِ ّمنْمُك ْ ِ ّم ْن ِداَي ِرمِه ْۖ ت َٰظهَ ُر ْو َن
عَلَهْي ِ ْم اِب اْل ِمْث ِ َوالْ ُعدْ َو ِ ۗان َوا ِْن يَّْأت ُْومُك ْ ُارٰس ٰ ى تُ ٰفدُ ْومُه ْ َوه َُو ُم َح َّر ٌم عَلَ ْيمُك ْ ِاخ َْراهُج ُ ْم
Perdamaian adalah ْ ۗ َافَتُْؤ ِمنُ ْو َن ِب َب ْع ِض ْال ِك ٰت ِب َوتَ ْك ُف ُر ْو َن ِب َب ْع ٍۚض فَ َم ا َج َز ۤا ُء َم ْن ي َّ ْف َع ُل ٰذكِل َ ِمنْمُك
ۗ ِ ِااَّل ِخ ْز ٌي ىِف الْ َح ٰيو ِة ادلُّ نْ َيا َۚوي َ ْو َم الْ ِق ٰي َم ِة يُ َرد ُّْو َن ِاىٰٓل َا َش ِّد الْ َع َذ
kontrak pertama
manusia dengan ُ اب َو َم ا اهّٰلل
Tuhan ِبغَا ِف ٍل مَع َّا تَ ْع َملُ ْو َن
Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (sesamamu),
dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung
halamannya. Kamu saling membantu (menghadapi) mereka
dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang
kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu
dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada
sebagian Kitab (Taurat) dan ingkar kepada sebagian (yang
lain)? Maka tidak ada balasan (yang pantas) bagi orang yang
berbuat demikian di antara kamu selain kenistaan dalam
kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan
kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah
terhadap apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al Baqarah: 85)
Iman kepada para قُ ْولُ ْوٓا ٰا َمنَّا اِب هّٰلل ِ َو َم ٓا ُا ْن ِز َل ِالَ ْينَ ا َو َم ٓا ُا ْن ِز َل ِاىٰٓل ِا ْب ٰرمٖه َ َو ِامْس ٰ ِع ْي َل َو ِاحْس ٰ َق
Nabi sebagai salah
satu bentuk toleransi َوي َ ْع ُق ْو َب َوااْل َ ْس َب ِاط َو َمٓا ُا ْويِت َ ُم ْوىٰس َو ِعيْىٰس َو َمٓا ُا ْويِت َ النَّ ِبيُّ ْو َن ِم ْن َّرهِّب ِ ْ ۚم اَل
ن ُ َف ّ ِر ُق بَنْي َ َا َح ٍد ِ ّمهْن ُ ْ ۖم َوحَن ْ ُن هَل ٗ ُم ْس ِل ُم ْو َن
Katakanlah, “Kami beriman kepada Allah dan kepada apa
yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan
kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan
Toleransi dalam Keberagaman
kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada
apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami
tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan
kami berserah diri kepada-Nya (Q.S. Al-Baqarah: 136)
َو ِللُك ٍّ ِّوهْج َ ٌة ه َُو ُم َو ِل ّهْي َا فَ ْاست َ ِب ُقوا الْ َخرْي ٰ ِ ۗت َا ْي َن َما تَ ُك ْون ُْوا يَْأ ِت ِبمُك ُ اهّٰلل ُ مَج ِ ْي ًع ا
Berlomba-lomba ۗ ِا َّن اهّٰلل َ عَىٰل لُك ِ ّ يَش ْ ٍء قَ ِد ْي ٌر
dalam kebaikan Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap
adalah tujuan akhir kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan.
toleransi Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan
kamu semuanya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala
sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah: 148)
ٓاَل ِا ْك َرا َه ىِف ّ ِادل ْي ِ ۗن قَدْ ت َّ َبنَّي َ ُّالر ْش دُ ِم َن الْغ ّ َِي ۚ فَ َم ْن ي َّ ْك ُف ْر اِب َّلطاغُ ْو ِت َويُ ْؤ ِم ْۢن
ٌ اِب هّٰلل ِ فَ َق ِد ا ْس َت ْم َس َك اِب لْ ُع ْر َو ِة الْ ُوثْ ٰقى اَل انْ ِف َصا َم لَهَا َۗواهّٰلل ُ مَس ِ ْي ٌع عَ ِلمْي
Toleransi dan Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam),
kebebasan beragama sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar
dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut
dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang
(teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah
Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 256)
َوقُ ِل الْ َح ُّق ِم ْن َّر ِبّمُك ْ ۗ فَ َم ْن َش ۤا َء فَلْ ُي ْؤ ِم ْن َّو َم ْن َش ۤا َء فَلْ َي ْك ُف ْ ۚر ِانَّٓا َا ْع َت دْ اَن
ِل ٰ ّلظ ِل ِمنْي َ اَن ًر ۙا َا َح َاط هِب ِ ْم رُس َ ا ِدقُهَاۗ َوا ِْن ي َّْس َت ِغ ْيث ُْوا يُغَاثُ ْوا ِب َم ۤا ٍء اَك لْ ُمهْ ِل ي َْش ِوى
اب َو َس ۤا َء ْت ُم ْرتَ َفقًاۗ ُ َ الْ ُو ُج ْو َهۗ ِبْئ َس الرَّش
Dan katakanlah (Muhammad), “Kebenaran itu datangnya dari
Kebebasan memilih
Tuhanmu; barangsiapa menghendaki (beriman) hendaklah dia
jalan iman dan jalan
beriman, dan barangsiapa menghendaki (kafir) biarlah dia
kufur
kafir.” Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi
orang zalim, yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka
meminta pertolongan (minum), mereka akan diberi air seperti
besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah)
minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling
jelek (Q.S. Al-Kahfi: 29)
Toleransi praksis الط ِ ّي ٰب ُ ۗت َو َط َعا ُم اذَّل ِ ْي َن ُا ْوتُوا ْال ِك ٰت َب ِح ٌّل لَّمُك ْ َۖو َط َع ا ُممُك ْ ِح ٌّل
َّ ُ َالْ َي ْو َم ُا ِح َّل لَمُك
لَّه ُْم َۖوالْ ُم ْح َص نٰ ُت ِم َن الْ ُم ْؤ ِم ٰن ِت َوالْ ُم ْح َص نٰ ُت ِم َن اذَّل ِ ْي َن ُا ْوتُ وا ْال ِك ٰت َب ِم ْن
Islam terhadap
agama lain
قَ ْبلِمُك ْ ِاذَٓا ٰاتَيْ ُت ُم ْوه َُّن ُا ُج ْو َره َُّن ُم ْح ِص ِننْي َ غَرْي َ ُم َس ا ِف ِحنْي َ َواَل ُمتَّ ِخ ِذ ْ ٓي َا ْخ دَ ٍ ۗان
َو َم ْن ي َّ ْك ُف ْر اِب اْل ِيْ َم ِان فَ َقدْ َح ِبطَ مَع َ هُل ٗ َۖوه َُو ىِف ااْل ٰ ِخ َر ِة ِم َن الْخٰ رِس ِ ْي َن
Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik.
Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan
makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu
Toleransi dalam Keberagaman
menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di
antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-
perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang
yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar
maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud
berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan.
Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal
mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi
(Q.S. Al-Maidah: 5)
َ َواَل ت َ ُس ُّبوا اذَّل ِ ْي َن يَدْ ع ُْو َن ِم ْن د ُْو ِن اهّٰلل ِ فَيَ ُس ُّبوا اهّٰلل َ عَ دْ ًو ۢا ِب َغرْي ِ ِعمْل ٍۗ َك ٰذكِل
َزيَّنَّا ِللُك ِّ ُا َّم ٍة مَع َ لَه ْ ُۖم مُث َّ ِاىٰل َرهِّب ِ ْم َّم ْر ِج ُعه ُْم فَ ُينَ ِب ّهُئ ُ ْم ِب َما اَك ن ُْوا ي َ ْع َملُ ْو َن
Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah
Larangan memaki selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan
umat lain melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami
jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka.
Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan
memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka
kerjakan (Q.S. Al-An’am: 108).
ُا ْد ُع ِاىٰل َس ِب ْي ِل َرب ّ َِك اِب لْ ِحمْك َ ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِة الْ َح َسنَ ِة َو َجا ِدلْه ُْم اِب لَّيِت ْ يِه َ َا ْح َس ُ ۗن
ِا َّن َرب َّ َك ه َُو َا ْعمَل ُ ِب َم ْن ضَ َّل َع ْن َس ِب ْيهِل ٖ َوه َُو َا ْعمَل ُ اِب لْ ُمهْ َت ِد ْي َن
Berdakwah secara Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan
arif, toleran dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan
dialogis cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih
mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang
lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk (Q.S. An-Nahl:
125)
Islam sebagai agama َ َو َمٓا َا ْر َسلْ ٰن َك ِااَّل َرمْح َ ًة ِل ّلْ ٰعلَ ِمنْي
yang membawa visi Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan
dan misi kerahmatan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam (Q.S. Al-Anbiya:
global 107)
Toleransi dalam Keberagaman
HADITS-HADITS TOLERANSI
Kategori Hadits/Terjemahan
Agama-agama ibarat َّ ال،ُ َّن َمثَيِل َو َمث َ َل اَألنْ ِب َيا ِء ِم ْن قَ ْبيِل مَك َث َِل َر ُج ٍل بَىَن بَيْتً ا فَ َْأح َس نَ ُه َوَأمْج َ هَل
sebuah rumah, Islam ِإ ِإ
datang untuk ونَ ُ َوي َ ُقول،ُ ون هَل َ ون ِب ِه َوي َ ْع َج ُب َ ُ فَ َج َع َل النَّ ُاس ي َ ُطوف،َم ْو ِض َع ل َ ِبنَ ٍة ِم ْن َزا ِوي َ ٍة
menyempurnakan
َوَأاَن خَامِت ُ النَّ ِب ِي ّ َني،َه َّال ُو ِض َع ْت َه ِذ ِه الل َّ ِبنَ ُة قَا َل فََأاَن الل َّ ِبنَ ُة
Rasulullah Saw. bersabda: “Perumpamaanku dan nabi-nabi
yang lain seperti seorang yang membangun sebuah rumah, lalu
ia memperindah, kecuali hanya satu tempat batu-bata, sehingga
orang-orang yang mengelilingi tempat tesebut sembari
terheran-heran dengan batu itu”. Lalu mereka bertanya,
“Tidakkah batu tersebut diletakkan”. Nabi menjawab, “Saya
adalah batu tersebut dan saya penutup para nabi” (HR.
Bukhari).
Tuhan Sebagai Maha َّن اهَّلل َ َر ِفيقٌ حُي ِ ُّب ّ ِالرفْ َق َوي ُ ْع ِطي عَىَل ّ ِالرفْ ِق َما اَل يُ ْع ِطي عَىَل الْ ُع ْن ِف
Penebar kasih, bukan ِإ
penebar kekerasan
Dari Abdullah bin Mughaffal, beliau berkata: Rasulullah
bersabda, “Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, mencintai
sifat welas asih, dan memberikan (banyak keistimewaan) yang
tidak diberikan kepada sifat kejam atau kekerasan” (HR. Abu
Daud).
Kelenturan dan ول اهَّلل ِ َصىَّل اهَّلل ُ عَلَ ْي ِه َو َسمَّل َ بَنْي َ َأ ْم َر ْي ِن قَ طُّ اَّل َأ َخ َذ َأيْرَس َ مُه َا ُ َما ُخرِّي َ َر ُس
Kemudahan Ajaran
ِ ول اهَّلل ِإ
ُ َم ا لَ ْم يَ ُك ْن ثْ ًم ا فَ ْن اَك َن ثْ ًم ا اَك َن َأبْ َع دَ النَّ ِاس ِمنْ ُه َو َم ا انْ َت َق َم َر ُس
Islam
ِإ ِإ
َصىَّل اهَّلل ُ عَلَ ْي ِه َو َِإسمَّل َ ِلنَ ْف ِس ِه يِف يَش ْ ٍء قَ طُّ اَّل َأ ْن تُنْهَت َ َك ُح ْر َم ُة اهَّلل ِ فَيَ ْن َت ِق َم
ِإ ِ هِب َا هَّلِل
Dari Aisyah, beliau berkata: “Rasulullah tak akan memilih dari
dari dua hal kecuali yang termudah di antara keduanya (selama
itu bukan termasuk perbuatan dosa). Jika iya, maka beliau
adalah orang pertama yang akan menjauhinya. Dan beliau tak
akan pernah mempermasalahkan hal tersebut kecuali ketika
larangan Allah dilanggar. Jika dilanggar, beliau akan
menindaknya dengan tegas” (HR. Abu Daud).
Perlu saling ِ ُأ ِم َر ن ُّيب:خ ذ العف و ق ال
هللا ص ىل هللا علي ه وس مل أن يأخ َذ العف َو من
memaafkan untuk
Toleransi dalam Keberagaman
membangun ِ خالق
الناس ِ أ
masyarakat toleran
Dari Abdullah bin Zubair, beliau berkata: Tafsir firman Allah
“Berilah maaf adalah bahwa Rasulullah diperintahkan untuk
menyikapi tingkah laku atau perbuatan manusia dengan ringan
atau mudah (HR. Abu Daud).
Larangan اَل تَ َباغَ ُض وا َواَل حَت َ َاس دُ وا َواَل تَ دَ ابَ ُروا َو ُكون ُ وا ِع َب ا َد اهَّلل ِ خ َْوااًن َواَل حَي ِ ُّل
menebarkan ِإ
kebencian di antara ِل ُم ْسمِل ٍ َأ ْن هَي ْ ُج َر َأخَا ُه فَ ْو َق ثَاَل ٍث
sesama manusia
Dari Anas bin Malik, beliau berkata: Rasulullah bersabda
“Janganlah kalian saling membenci, menghasut, atau
memusuhi. Jadilah hamba-hamba Allah dalam ikatan
persaudaraan. Dan seorang Muslim dilarang diam dengan
saudaranya lebih dari tiga malam” (HR. Abu Daud).
Himbauan untuk إايمك والغلو يف ادلين
menjauhi sikap
ekstrim
Rasulullah bersabda: “Hindarilah sikap ekstremisme (al
ghulauw) dalam beragama” (HR. Bukhari, Ibnu Majah, Ahmad
bin Hanbal, Nasai, dll)
Larangan menyakiti من آذى ذميا فقد آذاين ومن آذاين فقد آذى هللا
umat Kristiani dan
Yahudi yang berada
di bawah otoritas Rasulullah bersabda: “Barangsiapa menyakiti al-dzimmah,
umat Muslim (al- sesungguhnya ia telah menyakiti saya. Barangsiapa menyakiti
dzimmah) saya, maka berarti ia menyakiti Allah”. (HR. Thabrani).
Para Nabi adalah إخو ٌة ل َعاَّل ت اهمات متعددات
َ ِديهُن م وا ِح ٌد وُأ َّمهاهُت م َشىَّت األنبيا ُء
satu agama, tetapi
mereka berbeda
dalam syariat Rasulullah bersabda: “Agama para Nabi satu, dan ibu mereka
banyak. Para Nabi hanya sebagai saudara bagi ibu-ibu mereka”.
(HR. Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad).
Islam adalah agama
yang lurus dan
َّ َأ َح ُّب ِّادل ِين ِإ ىَل اهَّلل ِ الْ َح ِني ِفيَّ ُة
الس ْم َح ُة
toleran
Rasulullah bersabda: “Agama yang paling dicintai Tuhan
adalah agama hanif yang toleran”. (HR. Ibnu Syaybah dan
Muslim)
Larangan َّن ِد َم َاءمُك ْ َوَأ ْم َوالَمُك ْ َوَأع َْراضَ مُك ْ عَلَ ْيمُك ْ َح َرا ٌم
menebarkan ِإ
kekerasan
Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya darah, harta, dan jiwa
kalian haram dirampas oleh siapapun”. (HR. Bukhari dan
Muslim)
Toleransi dalam Keberagaman
Larangan ال رضر وال رضار يف اإلسالم
menebarkan
kemadharatan yang
dapat merugikan Rasulullah bersabda: “Dalam Islam, membahayakan diri sendiri
orang lain dan orang lain dilarang keras”. (HR. Ibnu Majad, Al-
Daruquthni dan Malik)
Islam adalah agama اي أهيا الن اس أال إن ربمك واح د وإ ن أابمك واح د أال ال فض ل لع ريب عىل
yang menjunjung
tinggi kesetaraan أجعمي وال لعجمي عىل عريب وال ألمحر عىل أسود وال أسود عىل أمحر إال
ابلتقوى
Rasulullah bersabda: “Wahai manusia, bukankah Tuhan kalian
satu, nenek moyang kalian satu. Bukankah tidak ada
keistimewaan antara orang-orang Arab dengan orang-orang
asing, dan antara orang-orang asing dengan orang Arab, tidak
pula untuk orang yang berkulit merah atas orang berkulit putih,
dan tidak pula orang berkulit putih atas yang berkulit merah,
kecuali takwa kepada Allah Swt”. (HR. Imam Ahmad).
Ajaran persatuan َمث َُل الْ ُمْؤ ِم ِن َني يِف ت ََوا ِ ّدمِه ْ َوتَ َرامُح ِ ه ِْم َوتَ َع ُاط ِفه ِْم َمث َُل الْ َج َس ِد َذا ْاش َتىَك ِمنْ ُه
dalam Islam ِإ
ُعضْ ٌو تَدَ ا َعى هَل ُ َساِئ ُر الْ َج َس ِد
Rasulullah bersabda: “Dalam kebercintaan dan kasih
sayangnya, orang-orang mukmin bagaikan satu tubuh. Jika
salah satu anggota tubuh merasa sakit, seluruh anggota tubuh
yang lain juga akan merasakan sakit”. (HR. Bukhari).
Toleransi dalam Keberagaman
PANDANGAN ULAMA TENTANG TOLERANSI
Kategori Pandangan Toleransi
Pandangan Imam Ali التكونن عىل الناس سبعا ض اراي تغتمت ألكهم ف اهنم ص نفان إم ا اخ كل يف
bin Abi Thalib
tentang pentingnya ادلين او نظري كل يف اخللق
persaudaraan Imam Ali karramallahu wajhah berkata: “Janganlah kamu
berbuat jahat kepada manusia atau berupaya menerkamnya,
karena manusia itu terbagi dalam dua kelompok, yaitu
saudaramu dalam agama dan saudaramu dalam kapasitasnya
sebagai ciptaan Tuhan” (Nahjul Balaghah: 428)
Pandangan Imam Ali احلمكة ضاةل املؤمن ايامن وجدها فهو احق هبا
bin Abi Thalib
tentang kebenaran
Imam Ali karramallahu wajhah berkata: “Hikmah adalah harta
karun umat Muslim yang hilang. Di mana pun menemukannya,
maka berhak mendapatkannya”.
Pandangan Imam Al- فيجب أن ترعوا من تكفري الفرق وتطويل اللسان يف اهل الاسالم وان
Ghazali tentang
bahaya pengkafiran اختلفت طرقهم م اداموا ممتس كني بق ول ال اهل الا هللا محمدا رس ول هللا
صادقني هبا (فيصل التفرقة بني الاسالم والزندقة
Imam Al-Ghazali berkata: “Saya ingin memberimu nasehat
yang baik agar kamu berhat-hati dalam mengkafirkan seseorang
atau menghina orang Muslim selama ia berpegang teguh
kepada dua kalimat syahadat Tiada Tuhan selain Allah dan
Muhammad sebagai utusan Allah.”
Pandangan Ibnu مفا اكن مهنا موافقا للح ق قبلن اه مهنم ورسران ب ه وش كرانمه علي ه م ا اكن
Rusyd tentang
kebenaran مهنا غري موافق للحق نهبنا عليه وحذران منه وعذرانمه
Ibnu Rusyd berkata: “Kebenaran yang datang dari mereka yang
berbeda agama dan ajaran kami menerimanya, dan bila terdapat
kekeliruan dan kesalahan, kita harus memperbaikinya.” (Fash
al-Maqal fima baina al-Hikmah wa al-Syariah min al-Ittishal)
Pandangan Imam ومجموع الرضورايت مخس ة ويه حف ظ ادلين والنفس والنس ل واملال
Asy-Syatibiy tentang
lima nilai universal والعقل وقد قالوا اهنا مراعاة يف لك مةل
Toleransi dalam Keberagaman
Imam Asy-Syatibiy berkata: “Islam dan agama-agama pada
umumnya mengajarkan kepada kita tentang pentingnya
memelihara agama, jiwa, harta, keturunan, dan akal” (Al-
Muwafaqat fi Ushul al-Syariat: Jilid I/8)
Pandangan Imam اذا صدر ق ول من قائ ل حيمتل الكف ر مئ ة وج ه وحيمتل الاميان من وج ه
Muh. Abduh tentang
Keimanan واحد محل عىل الاميان وال جيوز محهل عىل الكفر
Imam Muh. Abduh berkata: “Seorang yang di dalam dirinya
terdapat 99% kekufuran dan 1% keimanan, maka ia disebut
Muslim” (al-A’mal al-Kamilah: 302)
Pandangan KH. الاخ وة له ا ثالث أن واع يه األخ وة الاس المية و األخ وة الوطني ة و
Achmad Siddiq
tentang persaudaraan األخوة اإلنسانية
KH. Achmad Siddiq berkata: “Ada tiga macam persaudaraan,
yaitu persaudaraan keislaman (Ukhuwah Islamiyah),
persaudaraan kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), dan
persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah basyariyah)”.
Toleransi dalam Keberagaman
Materi Jenjang MA
MODEL-MODEL PRAKSIS TOLERANSI
Waktu: 2 Jam Pembelajaran /JPL (120 Menit) Efektif
S
esi ini mengelaborasi model-model praksis toleransi yang pernah terjadi
di beberapa negara, baik dalam konteks hubungan intern agama maupun
antar umat beragama. Model praksis toleransi yang berkembang pun
sangat beragam: ada model dialog; model kerjasama; model pemberdayaan; model
advokasi; model solidaritas; dan model komunitas (perkampungan pesantren).
Model-model seperti ini bisa dijadikan sebagai pelajaran, bahkan bisa dijadikan
contoh untuk diterapkan di Indonesia.
Tujuan
1. Menunjukkan pada peserta bahwa praksis-praksis toleransi bukan sesuatu
yang sama sekali asing di Indonesia;
2. Merangsang peserta untuk mengambil inspirasi dalam melakukan praksis
toleransi;
3. Mencari model praksis toleransi yang bisa diterapkan di masyarakat; dan
4. Mengembangkan budaya toleran di masyarakat.
Pokok Bahasan
1. Model Toleransi Berbasis Dialog
2. Model Toleransi Berbasis Kerjasama.
3. Model Toleransi Berbasis Pemberdayaan (Advokasi).
4. Model Toleransi Berbasis Solidaritas Kemanusiaan.
5. Model Toleransi Berbasis Komunitas (Lingkungan).
6. Model Toleransi Berbasis Pesantren
Metode
Toleransi dalam Keberagaman
Fenemenologis, dialog (tanya-jawab), brainstorming
Langkah-Langkah
1. Fasilitator membuka dan menjelaskan tujuan dan pokok-pokok bahasan
model-model praksis toleransi. Sesi ini menekankan pentingnya perilaku
toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan cara belajar dari pengalaman
orang lain, atau belajar dari model-model praksis toleransi yang pernah terjadi
di negara lain.
2. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menceritakan seputar
pengalaman praksis toleransi berbasis Kyai dan pesantren. Adapun poin-poin
yang akan ditanyakan kepada narasumber :
a. Bagaimana pengalaman Anda dalam membangun praktik toleransi di
kalangan pesantren?
b. Seperti apa bentuk gerakan toleransi yang Anda bangun?
c. Kenapa Kiai dan pesantren sebagai basis gerakan toleransi?
d. Kelompok mana saja yang terlibat dalam kegiatan Anda?
e. Bagaimana respon masyarakat dan pemerintah setempat?
f. Sejauh mana efek dari toleransi yang Anda bangun terhadap hubungan
antar agama?
3. Fasilitator mempersilahkan peserta untuk berdialog dengan narasumber dalam
rangka pendalaman materi /pengalaman toleransi. Fasilitator mengarahkan dan
memfokuskan dialog peserta dengan narasumber seputar tahapan dan strategi
membangun toleransi berbasis Kyai dan pesantren.
4. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menjawab pertanyaan dan
komentar peserta. Jawaban narasumber diarahkan pada kesimpulan materi
pembahasan, agar adanya suatu pemahaman yang mendalam di kalangan
peserta.
5. Fasilitator melakukan brainstorming terhadap peserta untuk menggali model-
model praksis toleransi berdasarkan pengalamannya masing-masing. Peserta
diarahkan untuk menceritakan pengalamannya untuk bisa dijadikan salah satu
Toleransi dalam Keberagaman
model alternatif dalam praksis toleransi, khususnya berbasis Kyai dan
pesantren.
6. Fasilitator menjelaskan model-model praksis toleransi dari pelbagai agama,
negara, dan kelompok sipil lainnya untuk dijadikan inspirasi dan model dalam
melakukan gerakan toleransi di kalangan pesantren.
7. Fasilitator menutup sesi model-model praksis toleransi.
Catatan untuk Fasilitator:
Fasilitator harus mampu mengaitkan antara pengalaman yang pernah dialami
sendiri oleh peserta dengan pengalaman narasumber, serta sebagai
penyempurnaan diharapkan dapat menjelaskan model-model toleransi secara luas,
sebagaimana tertera dalam model-model praktik toleransi.
Toleransi dalam Keberagaman
MATERI
Model Toleransi Berbasis Dialog
DIALOG DAN TOLERANSI
(Sebuah Alternatif Dakwah Di Tengah Pluralisme Agama)
Farichatul Maftuchah
Pendahuluan
Beberapa tahun terakhir ini masyarakat Indonesia disuguhi berbagai
peristiwa dan serentetan konflik di tanah air yang mengejawantah pada
radikalisme dan militansi perilaku dengan berbagai simbol keagamaan yang
kental dan atraktif, semisal tragedi Banjarmasin 1998, Poso 1998-2000,
Ambon 1999-2000, dan Sampit. Demikian juga serangkaian aksi terorisme
yang meng- atanamakan agama. Meskipun agama bukan merupakan satu-
satunya faktor, namun jelas sekali bahwa pertimbangan keagamaan dalam
konflik-konflik tersebut dalam eskalasinya banyak memainkan peran.
Secara apologis, dengan mudah kita mengatakan bahwa ajaran agama pada
dasarnya anti kekerasan (non violent), dan pemeluknya baik secara individu
maupun kelompok yang mereduksi maknanya. Realitas yang ada akar keke-
rasan bisa dilacak ulang dalam kekerasan yang mengatasnamakan agama, dan
itulah sebabnya agama bisa dengan mudah menjadi kendaraan bagi
kecenderungan kekerasan.
Pluralitas agama merupakan satu keniscayaan yang tidak dapat dibantah,
untuk itulah merupakan satu tugas penting dakwah di era kemajemukan.
Bagaimana cara bersikap dan berperan aktif dalam mewujudkan tatanan yang
harmoni, agar konflik kekerasan tidak perlu terjadi lagi.
Agama dan Kekerasan
Agama baru menjadi konkrit sejauh dihayati oleh pemeluknya, satu sisi
Toleransi dalam Keberagaman
agama menganjurkan pemeluknya untuk menghormati dan menghargai,
merupakan wahana untuk menemukan kedamaian, harapan hidup dan
kebahagiaan abadi. Klaim bahwa agama selalu mengajarkan yang baik
memang benar, tetapi realitas sering berbicara lain, di sisi lain banyak orang
yang menimba kekuatan dan mendapatkan topangan berhadapan dengan
penderitaan, penindasan dan benih-benih konflik. Di sinilah kemudian
agama sering dikaitkan dengan fenomena kekerasan. Fenomena kekerasan
yang melanda tanah air kita memang tidak bisa dilepaskan dari pluralitas
agama-agama yang hidup di Indonesia.
Pluralitas agama berpotensi melahirkan benturan, konflik, kekerasan dan
sikap anarkis terhadap pemeluk agama lain. Hal ini dikarenakan setiap ajaran
agama mempunyai aspek eksklusif berupa truth claim yaitu satu pengakuan
bahwa agama yang dianutnya adalah yang paling benar, konsekuensinya adalah
agama yang dipeluk oleh orang yang berbeda adalah salah.
Klaim benar dan salah atau perbedaan yang baik dan yang buruk
merupakan sumber lain dari kekerasan yang terkait erat dengan agama. Pada
dasarnya perbedaan ini ada dalam kitab suci. Identifikasi dengan yang baik
menjustifikasi banyak kekerasan dalam sejarah semua agama, dari perang
sampai penjajahan, melalui penindasan intern terhadap perilaku bid‘ah dan
penyiksaan, demikian juga penyiaran agama berkaitan dengan penggunaan
kekerasan.
Jika kita melacak sejarah agama-agama besar, kita akan menemukan jejak
yang sama, teks-teks dasar mencerminkan upacara pengorbanan, penggunaan
kekerasan untuk tujuan yang lebih tinggi dan perlunya kekerasan dalam
mempertahankan agama, bersamaan dengan regulasi etis akan kekerasan yang
tidak legitimate, semuanya ditujukan untuk mencapai perdamaian tertinggi.
Mengikuti pola pikir Wim Beuken, setidaknya terdapat tiga mekanisme
yang berperan dalam hubungan antara agama dan kekerasan dalam fungsi sosial
yakni pembacaan agama mengenai hubungan sosial, agama sebagai faktor
identitas dan agama sebagai legitimasi etis dari hubungan sosial tertentu.
Pertama, ketika agama menyediakan dasar dan pembacaan hubungan
Toleransi dalam Keberagaman
sosial dan legitimasi, maka ini merupakan fungsi ideologis agama, wajah agama
yang hadir dalam tatanan sosial. Tatanan sosial dikehendaki oleh Tuhan, dan
hubungan yang ada antara berbagai golongan yang membentuk masyarakat
adalah hasil dari kehendak adi duniawi yang kemudian menjadi naturalisasi
tatanan sosial, alam dan hukumnya menjadi hasil ciptaan Tuhan, tidak ada
orang yang berani mengusiknya.
Kedua, agama sebagai faktor identitas budaya, identitas dapat
dimaknai sebagai rasa memiliki pada etnis, kelompok nasional atau sosial
tertentu yang pada saatnya memberikan stabilitas sosial, status, pandangan
dunia (world view) pola berpikir serta peradaban. Di sini agama dapat
menjadi salah satu entitas yang menentukan identitas kelompok. Identitas
kelompok bisa menjadi hasil dari kepemilikan etnis yang berbeda satu sama
lain khususnya karena adanya agama yang dipeluk berbeda.
Ketiga, agama menjadi legitimasi etis relasi sosial, peran agama dalam
ranah ketiga ini bahwa suatu tatanan sosial mendapat dukungan dari agama.
Identifikasi sistem sosial, politik atau ekonomi tertentu dengan nilai-nilai
agama tertentu akan melahirkan satu penolakan oleh agama lain.
Penghayatan agama seperti ini cenderung menekankan simbol-simbol,
maka legitimasi etis hubungan sosial akan mudah menimbulkan konflik.
Kesuksesan atau kegagalan sistem sosial tertentu akan diidentikkan dengan
kelompok agama tertentu.
Pluralisme Agama: Sebuah Panorama
Ide pluralisme agama pada awalnya adalah ide yang digagas sebagai
respon teologis atas perkembangan yang berlaku di masyarakat Barat. Ketika
konflik agama terjadi di mana-mana sehingga merenggut banyak korban
jiwa. Atas nama agama, masing-masing pemeluk agama menghantam pemeluk
agama lain yang berseberangan.
Secara historis term pluralisme diidentifikasi dengan sebuah aliran filsafat
yang menentang konsep negara yang absolut. Pluralisme kembali kepada
problematika masyarakat plural yang penduduknya tidak homogen tetapi
Toleransi dalam Keberagaman
terbagi dalam berbagai suku, etnis, agama, di mana keheterogenan ini kadang
menyatu tetapi juga cenderung menyebabkan konflik. Fenomena pluralisme
dapat kita temukan dalam setiap kehidupan keseharian manusia, dalam konteks
demikian sangat sulit untuk mempertahankan “paradigma tunggal” dalam
wacana apapun.
Dalam konteks agama, Harold Coward menyatakan bahwa dunia selalu
memilik pluralitas agama. Segala fenomena yang ada di hadapan kita, budaya,
etnis, pendidikan, militer, politik dan juga agama semuanya menampakkan
wajahnya yang pluralistik. Dalam hubungannya dengan agama, maka dalam
masyarakat intern umat beragama menjadi fenomena pluralisme tersebut,
setidaknya dalam nuansa aspirasi, kepentingan, dan cara berpikir atau pema-
haman terhadap agama yang dipeluknya.
Berangkat dari asumsi di atas, kita dapat merujuk pada al-Qur'an yang
mengajarkan paham keanekaragaman (religious plurality). Ajaran ini tidak
perlu diartikan sebagai secara langsung pengakuan akan kebenaran semua
agama dalam tampilan nyata sehari-hari, tetapi ajaran pluralisme agama me-
nandaskan pengertian dasar bahwa semua agama diberi ruang untuk hidup,
sikap ini dapat dimaknai sebagai suatu harapan kepada semua agama yang ada,
yaitu pada mulanya semua agama itu menganut prinsip yang sama yaitu ke-
harusan tunduk dan berserah kepada Tuhan yang Kuasa. Oleh karenanya,
agama-agama itu, baik karena dinamika internalnya sendiri atau karena
persinggungannya dengan yang lain akan berangsur-angsur menemukan
kebenarannya sendiri. Semuanya akan bertemu dalam satu titik temu “common
platform” sebagaimana rekaman al-Qur'an.
Pluralitas agama hendaknya dipandang sebagai bagian dari kehidupan
umat manusia yang tidak dapat dihindari, tetapi harus disikapi, isu pluralitas
bukan hal baru dan akan selalu ada. Membincang pluralitas ibarat memasukkan
minuman anggur ke dalam botol yang lama, pluralisme merupakan realitas
aksiomatis (tidak dapat dipungkiri) dan merupakan keniscayaan sejarah
(historical necessary) yang universal dan akan selalu ada.
Toleransi dalam Keberagaman
Pluralisme adalah pandangan yang menghargai keanekaragaman serta
penghormatan terhadap yang lain yang berbeda (the others), membuka diri
terhadap warna-warni keyakinan, kerelaan untuk berbagi, keterbukaan untuk
saling belajar (inklusivisme) serta keterlibatan diri secara aktif dalam dialog
untuk menemukan persaman-persamaan (common belief) dan menyelesaikan
konflik. Tanpa partisipasi aktif dalam pengembangan sikap dialogis ini, tidak
akan ada pluralisme.
Dalam konteks pluralisme, dan menilik pandangan keagamaan sesorang,
Komarudin Hidayat sebagaimana dikutip Sumiarti, memetakan lima tipologi
sikap keagamaan yaitu: Pertama, eksklusivisme adalah sikap keagamaan
yang meyakini bahwa ajaran agama yang paling benar adalah agama yang
dipeluknya, yang lainnya salah.
Kedua, inklusivisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan
bahwa selain agama yang dipeluknya juga terdapat kebenaran, meskipun tidak
seutuh dan sempurna seperti agama yang dipeluknya.
Ketiga, pluralisme adalah sikap keagamaan yang berpandangan bahwa
secara teologis, kemajemukan agama dipandang sebagai suatu keniscayaan
realitas yang masing-masing berdiri sejajar sehingga spirit misionaris dan
dakwah dipandang “tidak relevan”.
Keempat, eklektivisme, yaitu sikap keagamaan yang berusaha memilah
dan mempersandingkan berbagai ajaran agama yang dipandang baik dan sesuai
untuk dirinya sehingga bentuk finish dari sebuah agama menjadi sebentuk
mozaik eklektik.
Kelima, universalisme, adalah sikap keagamaan yang berpandangan
bahwa pada prinsipnya semua agama adalah satu dan sama, yang membedakan
hanyalah faktor historis, sehingga agama muncul dalam berbagai ragam
tampilan.
Menerima Pluralitas: Membangun Dialog dan Toleransi
Kemajemukan (pluralitas) sesungguhnya merupakan keniscayaan
sejarah yang tak terbantahkan, baik pluralitas etnis, warna kulit, budaya,
Toleransi dalam Keberagaman
bangsa serta agama. Dengan realitas ini sesungguhnya sangat sulit untuk
mempertahankan paradigma tunggal dalam wacana apapun, semuanya serba
majemuk sehingga pendekatannya harus dengan multidimensional
approaches.
Untuk membangun dialog dan toleransi, menarik disimak tawaran
yang disampaikan oleh Haryatmoko bahwa untuk membangun dialog dan
toleransi dapat dilakukan dengan, Pertama, tiap pemeluk/umat beragama
hendaknya mempunyai kesadaran bahwa agama bukanlah suatu entitas suci
yang tidak tersentuh, tetapi menjadi kongkret dalam penghayatan umat
beragama dengan institusi, ritus, sistem ajaran, norma moral dan tokoh-
tokohnya. Oleh karenanya sebagai institusi sosial historis, agama tidak terlepas
dari kepentingan dan tentu saja bisa berbeda, apalagi jika penafsiran sebuah
agama sudah diwarnai oleh kepentingan dan kekuasaan.
Kedua, dalam proses menafsirkan kitab suci suatu agama diukur
dari buahnya artinya penafsiran tersebut harus membawa pemeluknya
kepada pemahaman yang lebih baik. Pemahaman diri yang lebih baik akan
terjadi bila ada proses apropiasi teks (menjadi milik pribadi penafsir), yang
menuntut adanya pengambilan jarak (kritik ideologi, pembongkaran). Agama
akan dapat menciptakan perdamaian dan menyumbang kemanusiaan bila
pemeluk agama mampu melakukan pengambilan jarak dan menerapkan
mekanisme otokritik. Dengan demikian, cara melihat kesalehan yang
dikaitkan dengan praktek formal dan penekanan pada simbol-simbol akan
cenderung terbuka terhadap kebenaran agama lain (pluralisme).
Ketiga, penerimaan pluralitas tidak hanya atas dasar tuntutan realitas,
demi penegakan hak asasi manusia, keselarasan hidup bersama, tetapi
penerimaan pluralitas didasarkan atas pemahaman teologis bahwa “Tuhan
menjadi lebih kaya terungkap oleh keanekaragaman agama daripada oleh
satu tradisi saja.” Dengan demikian semua bentuk monopoli kebenaran
dipertanyakan, eksklu- sivsme tidak mendapat tempat. Dogmatisme
yang pada dasarnya adalah argumen yang cenderung mendasarkan pada
otoritas harus didialogkan secara kritis.
Toleransi dalam Keberagaman
Dengan demikian diharapkan agama tidak menjadi sumber konflik,
meskipun konflik adalah resiko kehidupan yang harus dihadapi. Seseorang
menjadi berharga dan berhak menyandang kemanusiaan karena mempunyai
kesempatan hidup dengan konflik. Realitas sejarah manusia senantiasa berisi
tantangan terhadap pluralitas dalam segala bidang kehidupan. Apa yang men-
jadi tantangan masa depan manusia pun tidak luput dari tantangan terhadap
perbedaan (pluralitas) dalam segala bidang kehidupan. Dari titik inilah kemu-
dian menjadi penting untuk mengembangkan dialog sebagai salah satu cara
me- manage benih konflik.
Dialog adalah cara untuk saling memahami, dan saling mengerti serta
saling menghargai satu sama lain, mengenal dan menghormati
pengakuan keabsahan keyakinan pemeluk lain, serta mampu melakukan kritik
terhadap diri sendiri untuk mengetahui perbedaan antara apa yang teks suci
katakan dan inti agama, sehingga di sini seseorang bisa menentukan secara
jelas posisinya.
Dialog bukan sekadar bermakna diplomasi, saling
menyembunyikan kepentingan dan menguasai untuk mencari titik
kelemahan orang lain. Umat beragama era global harus membangun
pemahaman bahwa berbeda bukan semata-mata merupakan identitas yang
pasif, melainkan sebagai sarana untuk saling melengkapi. Agenda utama
yang harus segera diwujudkan adalah membangun parsisipasi aktif untuk
saling memahami.
Seseorang dapat menjadi pluralis atau inklusif tanpa harus kehilangan
apapun dari pribadinya, mungkin seseorang tidak perlu menawarkan
keselamatan (salvation) bagi orang lain yang tidak seagama, karena
keselamatan dan segala yang berkaitan dengan kehidupan kemudian adalah
di luar otoritas manusia. Cukuplah bagi kita untuk saling memahami,
mengasihi satu sama lain dan senantiasa menabur keadilan di muka bumi.
Oleh karena itu baik agama, paham atau kebijaksanaan besar tidak
menyediakan tempat bagi ketidakadilan apaun bentuknya.
Untuk mewujudkan dialog ini, toleransi bisa dijadikan sebagai kunci
Toleransi dalam Keberagaman
pem- buka terciptanya kedamaian. Ada dua makna toleransi yang bisa
dikemukakan: pertama, the negative interpretation of tolerance yaitu
pemaknaan toleransi yang hanya mensyaratkan cukup membiarkan dan
tidak mennyakiti serta mengganggu kelompok lain. Kedua, the positive
interpretation of tolerance yaitu pemaknaan toleransi yang membutuhkan
lebih daripada itu, toleransi memerlukan dorongan, bantuan serta dukungan
dan pengembangan kelompok lain.
Dalam menyikapi pluralitas agama, lahirlah pandangan mengenai
sikap keagamaan sebut saja Hans Kung yang memperkenalkan ide tentang
global Ethic, John Hick dengan global theology yang dilebur dengan gagasan
teologi inklusif.
Upaya membangun common platform (kaalimatun sawaa’) dengan
perjumpaan dan dialog yang konstruktif dan berkesinambungan dengan
agama lain merupakan tugas manusia yang perennial, abadi, jika ini dapat
berlangsung dengan baik, maka agama dapat menjadi sumber bagi
penciptaan kedamaian, tetapi jika hal ini gagal, maka akan terjadi klaim
bahwa agama dapat dianggap sebagai sumber konflik dan kekerasan.
DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Masykuri. Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Muslim
Indonesia Terhadap Demokrasi. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
Abdullah, M. Amin. Falsafah Kalam di Era Postmodernisme. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2004.
Beuken, Wim dan Karl-Josef Kuschel. Religion as a Source of Violence?. New
York: SCM Press Ltd, Maryknoll, 1997.
Coward, Harold. Pluralisme: Tantangan bagi Agama-agama. Yogyakarta:
Kanisius, 1992.
Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat keagamaan Puslitbang
kehidupan Beragama. Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia.
Jakarta: Bagian Proyek Peningkatan Pengkajian kerukunan Hidup Umat
Beragama, 2003.
Haryatmoko. Etika Politik dan Kekuasaan. Jakarta: Kompas, 2003.
Ramadan, Tariq. Western Muslims and The Future of Islam. Oxford: Oxford
University Press, 2004.
Sumiarti, “Pluralisme Agama: Studi tentang Kearifan Lokal”, dalam Jurnal
Toleransi dalam Keberagaman
Penelitian Agama vol. 9 Desember 2008, Purwokerto: P3M STAIN
Purwokerto, 2008.
MATERI
Model Toleransi Berbasis Pemberdayaan (Advokasi)
SEJARAH ADVOKASI PLURALISME AGAMA:
STUDI KASUS ADVOKASI AGAMA LELUHUR DI INDONESIA
Husni Mubarok
Pendahuluan
November 2017, dekade kedua reformasi di Indonesia, adalah bulan
bersejarah bagi penghayat agama leluhur. Mahkamah Konstitusi (MK)
mengabulkan uji materi para penghayat agama leluhur atas pasal 61 ayat 1 dan
pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk)
2013, revisi atas UU tahun 2006. Para penghayat agama leluhur menggugat pasal
tersebut karena kedua pasal tersebut menjadi rujukan bagi diskriminasi yang
mereka alami selama ini, yakni kehilangan akses layanan publik karena persoalan
pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP). MK menyatakan bahwa agama
pada kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD dan tidak berkekuatan
hukum sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Atas dasar keputusan tersebut,
kedua pasal tersebut gugur. Putusan MK tersebut berimplikasi bahwa pemerintah
Indonesia kini wajib menambahkan pilihan pada kolom agama pada KTP, yakni
“aliran kepercayaan” bagi penghayat kepercayaan.
Putusan MK di atas merupakan tonggak kepada para penghayat
kepercayaan, yang selama ini termarjinalkan. Pada level kebijakan berbagai pihak
telah melakukan beragam cara untuk mengubah kebijakan agar lebih ramah
terhadap kelompok rentan.1 Usaha tersebut, sayangnya, seringkali tidak memenuhi
harapan dan menghasilkan perubahan seperti direncanakan. Pada UU tahun 2003
tentang Pendidikan Nasional, misalnya, mengandung pasal yang berpotensi
Toleransi dalam Keberagaman
mengutamakan komunitas agama tertentu.2 UU pornografi,3 uji materi terhadap
UU penodaan agama,4 Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian rumah
ibadah,5 Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama, 6 adalah contoh-contoh di
mana regulasi tidak banyak berubah, khususnya dimensi diskriminasi terhadap
kelompok paling tak beruntung.
Situasi di level relasi sosial juga menghadapi kebuntuan serupa. Penganut
Syiah di desa Nangkernang, Sampang, misalnya, yang mengungsi di dalam negeri
atau biasa disebut internally displace person, setelah diusir 2012 silam, belum bisa
pulang ke kampung halaman.7 Serupa penting advokasi pluralisme agama di
Indonesia.
Sejak reformasi, gugatan para penghayat kepercayaan ini merupakan uji
materi pertama terkait pluralisme agama yang dikabulkan MK seluruhnya.
Sebelumnya, beberapa individu dan organisasi masyarakat sipil menggugat UU
Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang penodaan agama namun MK memutuskan
menolak gugatan tersebut dan merekomendasikan agar UU yang digugat direvisi
melalui parlemen tahun 2010. Dua tahun berselang, beberapa orang dan organisasi
masyarakat sipil kembali mengajukan permohonan uji materi ke MK pada 2012.
Mereka secara spesifik meminta bagaimana tafsir MK terhadap UU tersebut
sebagaimana tercantum pada putusan MK JR 2010 yang merekomendasikan untuk
merevisi konsep penodaan agama di parlemen. MK kembali menolak permohonan
tersebut. MK menyatakan bahwa revisi tidak termasuk wewenang MK.1 Selain
kali pertama, putusan MK atas UU Adminduk juga mendasari pelayanan setara
warga Syiah di Jawa Timur, anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia ( JAI) yang
harus mengungsi di Transito Majeluk, Mataram setelah diserang sekelompok
orang belum memperoleh kejelasan kapan akan kembali ke tanah milik mereka.8
Contoh lainnya adalah pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi dan GKI
Yasmin di Bogor yang hingg kini belum menemukan titik terang jalan keluarnya.9
Putusan MK tentang status kewarganegaraan penghayat agama leluhur
merupakan harapan di tengah oase advokasi pluralisme di Indonesia. Tulisan ini
akan menelusuri sejarah advokasi pluralisme agama dengan memfokuskan
perhatian pada advokasi kelompok penghayat agama leluhur di Indonesia. Tulisan
Toleransi dalam Keberagaman
ini berangkat dari pertanyaan, bagaimana rute dan jalan advokasi terhadap ragam
agama, dalam konteks ini penghayat agama leluhur dalam sejarahnya?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses
pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga cara: wawancara tatap muka,
pengamatan lapangan, dan mempelajari dokumen. Dokumen dirujuk dalam
penelitian ini adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan advokasi
Yasalti dan Donders sepanjang 2015-2018. Penelitian ini juga menggunakan data
hasil observasi dalam kunjungan ke komunitas Marapu dan kantor Yasalti dan
Donders pada 25 November – 02 Desember 2019. Selain dari dokumen dan
observasi, penelitian ini juga mewawancarai narasumber yang berasal dari
pimpinan Yasalti dan Donders, pendamping lapangan, tokoh pemerintah, pemuka
agama, penghayat Marapu, dan tokoh lainnya di Sumba Timur dan Sumba
Tengah. Sementara itu, penjelasan mengenai sejarah advokasi, penelitian ini
mengandalkan tulisan-tulisan yang berserakan dari sejumlah peneliti dan
wawancara kepada sejumlah tokoh yang dianggap memiliki peran khususnya
setelah rezim Orde Baru jatuh.
Tulisan ini mengajukan argumen bahwa penghayat kepercayaan sejak
kemerdekaan telah terbiasa mengadvokasi diri sendiri untuk memperjuangkan
nasib komunitasnya di hadapan berbagai rezim. Peran aktivis LSM dan akademisi
lebih sebagai sistem pendukung atas keputusan komunitas penghayat agama
leluhur dalam menghadapi perubahan struktur politik dan politik agama sejak
kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai sistem pendukung, hubungan LSM-
akademisi sebagai pendamping dan para penghayat yang didampingi cenderung
dinamis: kadang sejalan, kadang tidak.
Tulisan ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama akan memaparkan
advokasi penghayat kepercayaan di tengah politik agama yang begitu kuat sejak
kemerdekaan hingga rezim Orde Baru tumbang. Bagian kedua, advokasi
penghayat kepercayaan pasca reformasi yang didominasi wacana hak asasi
manusia. Bagian terakhir akan mendiskusikan perkembangan advokasi penghayat
kepercayaan terkini, yakni melalui Program Peduli, yang kemudian menjadi studi
kasus pada penelitian ini.
Toleransi dalam Keberagaman
Advokasi Penghayat Kepercayaan: Kemerdekaan hingga Orde Baru
Dalam sejarahnya, pengakuan negara terhadap eksistensi agama leluhur di
Indonesia saat ini merupakan hasil pergulatan politik penganut agama leluhur itu
sendiri dalam konteks politik agama. Samsul Maarif, dosen Center for Religius
and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, mendokumentasikan dinamika tersebut
dalam buku Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di
Indonesia (2018). Politik pengakuan agama leluhur di Indonesia, menurut Maarif,
bisa ditelusuri sejak polarisasi antara santri dan abangan pada era penjajahan
belanda dan Jepang. Sementara abangan lebih mengutamakan budaya lokal, santri
mengampanyekan purifikasi agama. Polarisasi abangan dan santri ini berlanjut
pada masa awal kemerdekaan khususnya dalam perdebatan di BPUPKI. Professor
Supomo, anggota BPUPKI yang juga pembela hukum adat, menentang Piagam
Jakarta yang berupaya memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi Indonesia.
Polarisasi santri dan abangan bertransformasi menjadi polarisasi baru antara
agama dan kepercayaan. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang kemerdekaan
menganut dan menjalankan keyakinan menyebut agama dan kepercayaan secara
terpisah. Penyebutan kepercayaan terpisah dari agama itu merupakan usulan dari
kelompok “abangan” yang merasa terancam oleh agenda kelompok santri. 10
Ancaman tersebut mencuat menyaksikan sejumlah aksi kelompok santri setelah
mereka kecewa karena Piagam Jakarta dicoret pada konstitusi. Mereka misalnya
mengusulkan pembentukan Departemen Agama (Depag) yang dibentuk pada
1946, yang pada masa awalnya hanya melayani umat Islam. sebagai lembaga
baru, Depag kemudian merumuskan definisi agama pada 1952 untuk memperjelas
posisinya. Mereka mengusulkan tiga kriteria agama: nabi, kitab suci, dan jaringan
internasional. Sekalipun pada awalnya ditolak sejumlah pihak, definisi tersebut
lambat laun menjadi pemahaman bersama yang kemudian menjadi alat ukur mana
agama dan mana yang bukan agama.11
Konteks sosial politik ini, menurut Maarif, mendorong komunitas
kepercayaan di Jawa berkumpul dan membentuk Badan Kongres Kebatinan
Indonesia (BPKI) pada kongres pertama di Semarang pada 1955. Kongres yang
Toleransi dalam Keberagaman
dihadiri 680 perwakilan dari sekitar 60an organisasi kebatinan ini memilih Mr.
Wongsonegoro sebagai ketua. Di bawah kepemimpinan Wongsonegoro, BPKI
menyelenggarakan kongres lima kali hingga tahun 1960 yang diikuti peserta lebih
dari dua juta peserta. Perkembangan pesat kelompok kebatinan ini menarik
perhatian Depag yang kemudian mengumumkan 61 aliran kebatinan yang bukan
pemeluk agama Islam, Protestan, dan Katolik. Merespons pengumuman tersebut,
BPKI mendeklarasikan diri sebagai aliran kebatinan dan tidak berencana menjadi
agama.12 Deklarasi ini dengan sendirinya memperlihatkan bahwa BPKI pada
akhirnya seakan menerima definisi agama yang dirumuskan Depag.
Polarisasi agama dan kepercayaan sejak saat itu semakin terlembagakan.
Pemerintah untuk pertama kalinya menyatakan pengakuan terhadap kelompok
kebatinan dalam regulasi negara. Pengakuan tersebut terekam pada TAP MPRS
No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional
Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Pasal 2 ayat 1 GBHN ini
merumuskan Mental, Agama, dan Kerohanian dengan menggunakan garis miring
sebagai pertanda kesetaraan ketiganya. Sementara itu, pada pasal 3, ketentuan
mengenai pendidikan, menyatakan bahwa setiap anak akan mendapatkan
pendidikan agama, betapapun tak mereka yakini. Meski begitu, pasal tersebut juga
menjamin kelompok kebatinan untuk tidak mengikuti pelajaran agama tersebut. 13
Dinamika hubungan agama dan kepercayaan berkembang dengan munculnya Biro
Pakem di Departemen Kejaksaan Pusat, yang salah satu kewenangannya
mengawasi perkembangan kelompok kebatinan. Pengawasan tersebut semakin
intensif setelah UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan
Agama disahkan. UU tersebut secara tegas melegitimasi agama dan
mendelegitimasi aliran kepercayaan, bahkan ada kemungkinan mengkriminalisasi
kelompok kepercayaan.
Peristiwa 30 September 1965 menandai babak baru hubungan agama dan
kepercayaan. Peristiwa ini mendorong tentara membersihkan Partai Komunis
Indonesia (PKI) dan unsur-unsurnya, yang mana aliran kepercayaan dihubungkan
dengan partai tersebut.14 Asosiasi antara penganut kepercayaan dengan PKI
mengakibatkan para penganut kepercayaan bermigrasi ke agama- agama yang
Toleransi dalam Keberagaman
diakui sebagai strategi untuk menghindari tak beragama dan karenanya komunis.
Tekanan dari kelompok Muslim agar penganut Islam memperlihatkan diri
keislamannya mengakibatkan sebagian besar penganut kepercayaan di Jawa
berpindah ke agama Kristen atau Katolik. World Council of Churches (WCC)
melaporkan jumlah penganut Kristen meningkat 2,5 juta sepanjang 1986-1968. 15
Aliran kepercayaan mendapat peluang baru pada rezim Orde Baru khususnya
setelah Partai Golongan Karya (Golkar) berdiri. Satu di antara komunitas yang
bergabung pada sekretariat bersama (Sekber) Golkar adalah organisasi aliran
kebatinan. Golkar membentuk BK5I (Badan Kongres Kepercayaan Kejiwaan
Kerohanian Kebatinan Indonesia). Pada 1971, BK5I bertransformasi
menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK), yang diketuai Wongsonegoro
serta R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, mantan Kapolri pertama, sebagai sekretaris
jenderal (Aryono, 2018:61).
Dukungan elit Golkar kepada aliran kebatinan ini memperlihatkan dua
kemungkinan. Kemungkinan pertama, aktor politik Orde Baru di level elit bisa
membedakan dengan tegas beda antara aliran kebatinan dan unsur-unsur
komunisme, yang mana sebelumnya diasosiasikan antara keduanya. Hal ini
dimungkinkan karena di antara anggota aliran kebatinan adalah elit di Parati,
seperti R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai sekretaris jenderal SKK
merupakan mantan Kapolri pertama. Sementara itu, masyarakat pada umumnya
menganggap aliran kebatinan dan komunisme berasosiasi satu sama lain.
Kemungkinan kedua, massa aliran kebatinan di pulau Jawa signifikan untuk
mendukung pengembangan Golkar sehingga satu cara mendapat suara mereka
adalah dengan memasukkan aliran kebatinan menjadi bagian dari Golkar.
Sesuai saran Golkar, BK5I mengganti kebatinan menjadi kepercayaan
sebagaimana dengan konstitusi pasal 29 ayat 2. Melalui Golkar, pemerintah
mengakui kembali aliran kepercayaan secara formal, yang pada gilirannya
mendapat dukungan finansial dari pemerintah. Hal ini menandai babak baru
pengakuan terhadap penganut agama leluhur di Indonesia. Pada kongres Subud,
salah satu aliran kepercayaan pada 1971, Presiden Soeharto menyatakan untuk
menerima organisasi kepercayaan secara wajar.16 Pemerintah menunjukkan
Toleransi dalam Keberagaman
semakin kuat untuk mengakui aliran kepercayaan setara dengan agama-agama
dilihat dari TAP MPR 1973 yang menyatakan akan memberikan sejumlah sarana
dan prasarana terhadap aliran kepercayaan.17
Kecenderungan pengakuan setara terjadi pada aspek kewargaan lainnya,
perkawinan. Hal ini tercermin pada UU perkawinan yang telah disusun pada 1952
dan direvisi pada 1974. Sementara UU perkawinan 1952 hanya berlaku bagi umat
Islam, pada UU 1974 mencakup seluruh warga negara, yang terkait dengan
perkembangan aliran kepercayaan. Pada UU 1974, pemerintah mengatur bahwa
perkawinan dilakukan oleh masing-masing pemuka agama. Pencatatan pernikahan
penganut agama Islam dilakukan oleh petugas khusus, sementara penganut agama
lainnya dan kepercayaan dicatat di kantor pencatatan sipil. Sampai sini, penganut
kepercayaan dijamin haknya setara dengan agama lain. Pengakuan terhadap aliran
kepercayaan surut kembali ketika pengakuan pada dokumen paling dasar, Kartu
Tanda Penduduk (KTP dan Kartu keluarga (KK). Pemerintah tidak mencatatkan
kolom agama di luar UU PNPS 1965. Sejak saat itu, penganut aliran kepercayaan
tidak punya pilihan kecuali mengikuti aturan tersebut dengan berpura-pura masuk
salah satu agama, atau sama sekali tidak memiliki dokumen legal sebagai warga
negara.
Advokasi Penghayat Kepercayaan: Paska Reformasi
Sementara komunitas penghayat mengadvokasi diri sendiri pada masa
kemerdekaan hingga Orde Baru, pada era reformasi beberapa lembaga non
pemerintah turut serta mendampingi klaim kelompok penghayat kepercayaan
menyatakan klaim hak kewarganegaraannya. Pendampingan masyarakat sipil itu
bisa ditelusuri pada perubahan struktur sosial politik paska reformasi, yakni
terbentuknya UU HAM 1999 dan amandemen UU konstitusi pada 2000-2002
yang memasukkan dimensi HAM di dalamnya.
Advokasi terhadap komunitas penghayat kepercayaan bisa ditelusuri dari
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang terbentuk pada kongres
pertama 1999. AMAN tidak spesifik mengadvokasi hak beragama, melainkan hak
atas tanah ulayah masyarakat adat yang saat itu banyak diambil alih perubahan-
Toleransi dalam Keberagaman
perusahaan besar atas nama pembangunan dan investasi. Pada kongres pertama,
misalnya, AMAN menyatakan “Kami tidak mengakui negara jika negara tidak
mengakui kami”.18 AMAN memandang negara telah abai terhadap hak sipil,
politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat. Fokus pada hak ekonomi
dan kebudayaan juga tampak dari penamaannya, masyarakat adat. Tidak semua
masyarakat adat menganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan, dan tidak
semua penghayat kepercayaan tinggal di lingkungan masyarakat adat. Tetapi,
penghayat kepercayaan yang berada di wilayah pedalaman yang memiliki tanah
ulayat adalah komunitas yang didampingi AMAN.
Pada perkembangannya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-5 pada
2017, penyelenggara mulai menyediakan ruang bagi diskusi dengan topik tentang
spiritualitas dan kebudayaan. Pada sarasehan tersebut, sejumlah tokoh khususnya
komunitas penghayat kepercayaan yang selama ini mengampanyekan kebebasan
beragama/ berkeyakinan menjadi pembicara. Gagasan tersebut sebetulnya sudah
ada pada kongres sebelumnya pada 2012 di Halmahera, yang pada dokumen
deklarasi menyatakan bahwa pemerintah agar tidak mengintervensi spiritualitas
dan kebudayaan masyarakat adat nusantara. Sementara pada kongres ke-5 kongres
mendiskusikan hak sipil politik, khususnya hak kewarganegaraan terkait
kebebasan beragama/ berkeyakinan. Pada diskusi tersebut, sebagian komunitas
masyarakat adat tidak ingin bertransformasi menjadi komunitas agama tertentu.
Kelompok lain menyatakan ingin pemerintah mengakui eksistensi komunitasnya
sebagai salah satu agama di Indonesia. Kelompok lainnya cenderung mengikuti
peraturan pemerintah yang berlaku, walaupun mereka memiliki dimensi
spiritualitas tertentu.19
Singkatnya, AMAN telah mengadvokasi kelompok agama leluhur dengan
fokus pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi belum membahas implikasi
perbedaan keyakinan spiritualitas para penghayat. Meski diskusi tentang hak
kewarganegaraan dari segi agama telah muncul, Resolusi Wanua Koha, hasil rapat
kerja nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-5 itu, tidak memasukkan isu
agama dan keyakinan sebagai agenda gerakan.
Toleransi dalam Keberagaman
Sementara itu, advokasi yang fokus penghayat kepercayaan dari sudut
pandang pluralisme agama sudah mulai didiskusikan pada acara-acara dialog antar
agama. LSM yang bergerak dalam bidang dialog antar keyakinan meletakkan
penghayat kepercayaan sebagai agama leluhur yang derajatnya setara dengan
agama-agama lain. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Djohan Effendi, misalnya,
melalui Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang didirikan pada
2000 menggugat klaim agama resmi yang meminggirkan sejumlah agama yang
ada di Indonesia, termasuk agama leluhur. Djohan Effendi, selama menjabat
sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (1998-
2000) mengusulkan dialog antar iman, alih-alih antar agama. “Saat itu, usulan
narasi dialog antar iman, bukan antar agama, adalah sebagai cara untuk memberi
ruang kepada komunitas agama leluhur untuk menyampaikan pandangan
keagamaannya.”20 Meski tidak ada pendampingan khusus kepada komunitas
penghayat, ICRP melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan, tidak saja menjadi
peserta tetapi juga sebagai panitia yang turut serta merumuskan substansi
kegiatan. “Saat itu, bersama aliansi lintas iman belum mendiskusikan agama
leluhur dalam kerangka kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB).”21
Wacana KBB menjadi kerangka analisis dalam advokasi setelah pemerintah
Indonesia meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil politik. Ratifikasi
itu kemudian tertuang dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil Politik). Wacana HAM pada mulanya muncul sebagai respons
terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan pada masa transisi dari rezim otoriter
menuju demokrasi. Belakangan wacana HAM berkembang menjadi landasan
untuk klaim atas hak asasi warga negara, termasuk beragama/ berkeyakinan. Pada
dua ketentuan internasional itu, setiap negara yang meratifikasi wajib memenuhi,
menghormati, dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Setelah UU
ratifikasi terbit, aliansi yang bekerja untuk dialog antar agama (seperti Dian
Interfidei, ICRP, Madia, dan lainnya) dan aktivis HAM (Lembaga Bantuan
Hukum (LHB), Elsam, ILRC, dan lainnya), yang sebelumnya bekerja di wilayah
masing-masing, bertemu di bawah kerangka kebebasan beragama/ berkeyakinan
Toleransi dalam Keberagaman
(KBB). Pada kerangka KBB inilah wacana mengenai hak beragama penganut
agama leluhur atau penghayat kepercayaan mulai mendapat perhatian khusus.
Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) adalah satu di antara LSM
yang mengadvokasi komunitas penghayat kepercayaan dari aspek hak sipil politik,
khususnya sebagai komunitas agama. Kongres pertama, yang kemudian menjadi
cikal bakal pembentukan ANBTI pada 2006, merekomendasikan agar penghayat
kepercayaan menjadi satu di antara komunitas yang didampingi dan diperkuat.
“Kami yang sejak saat itu lebih suka menggunakan istilah agama leluhur daripada
penghayat kepercayaan, menaruh perhatian khusus pada kelompok agama
leluhur,” tutur Nia Syarifuddin, direktur ANBTI. 22 Setahun berselang, ANBTI
menyelenggarakan Sarasehan Kebhinekaan, yang melibatkan 33 komunitas agama
leluhur di Indonesia seperti Sunda Wiwitan, Marapu, Kaharingan, dan lainnya.
ANBTI berperan sebagai penguat jaringan di antara berbagai elemen masyaraka,
khususnya mereka yang terdiskriminasi. ANBTI saat itu mengidentifikasi empat
aktor yang melanggengkan diskriminasi terhadap agama leluhur: pemerintah,
agama dunia, media, dan peneliti. Keempat aktor ini diyakini sebagai pihak yang
melanggengkan stigma terhadap penganut agama leluhur. Oleh sebab itu, ANBTI
kemudian menyelenggarakan sejumlah workshop pendokumentasian sebagai
alternatif bagi penganut agama leluhur membuat dokumentasi dan media sendiri
sebagai sarana menyuarakan kebenaran.
Bersama lembaga antar iman lainnya, ANBTI juga terlibat dalam sarasehan
nasional yang mendiskusikan hak keberagamaan penghayat kepercayaan pada
2005 sebagai respons atas rancangan UU tentang Adminduk. Saat itu, permintaan
LSM adalah menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang dinilai
sebagai titik masuk diskriminasi penganut agama dan kepercayaan di luar enam
agama, yang menjadi salah satu pasal dalam RUU tersebut. Menurut Anick HT,
direktur ICRP 2008-2010, “Kami waktu itu menolak RUU tersebut karena di
dalam UU tersebut ada penegasan mengenai agama resmi dan lainnya. Jika
sebelumnya tidak pernah ada pernyataan khusus mengenai agama resmi, RUU
Adminduk menegaskan hal itu dengan memisahkan mana agama dan mana
budaya.”23
Toleransi dalam Keberagaman
LSM dalam proses advokasi RUU tersebut berperan sebagai pendamping
bagi komunitas penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Badan Perjuangan
Kebebasan Beragama dan Berkayakinan (BPKBB). BPKBB diketuai Dr.
Wahyono Raharjo, penganut Kapribaden, satu di antara penghayat kepercayaan di
Indonesia. Pemerintah bersama DPR akhirnya mensyahkan UU Adminduk 2006
dengan catatan bahwa penganut kepercayaan boleh tidak mengisi kolom agama
atau menandai (-). Berbagai komunitas di BPKBB merespons keputusan tersebut
secara beragam. Di antara mereka, ada komunitas yang bersikukuh ingin agar
pemerintah mengakui mereka sebagai agama. komunitas lain tundak terhadap
keputusan tersebut, dan memilih mengosongkan kolom agama. Sementara itu,
banyak di antara penghayat kepercayaan yang akhirnya mengisi dengan satu di
antara enam agama, meski tidak meninggalkan tradisi dan ajaran kepercayaannya.
“Kami, karenanya, tidak hanya mengadvokasi agar pemerintah merekognisi dan
melayani penghayat, tetapi juga mengadvokasi komunitas di dalam penghayat itu
sendiri agar betapapun ada perbedaan internal, perjuangan tetap di bawah
kerangka hak asasi manusia,” tutur Anick.24
UU Adminduk 2006, saat itu, dinilai sebagai setengah kemenangan
kampanye KBB. Setengah kemenangannya adalah penghayat kepercayaan diberi
keleluasaan memilih untuk mengosongkan kolom agama yang sebelumnya
mereka terpaksa mengisi dengan satu dari enam agama yang diakui. Setengah
kekalahan lainnya, pengosongan kolom agama belum menyelesaikan status
kewarganegaraan penghayat. Menurut Anick “Mereka boleh mengosongkan
kolom agama, tetapi mereka tidak bisa memiliki Akta Pernikahan setara dengan
penganut agama lain. begitu juga dengan Akta Kelahiran anak-anak agama leluhur
yang tidak setara. Belum lagi pendidikan agama mereka di sekolah-sekolah yang
akan menjadi masalah atas dasar UU Adminduk 2006.”25
Di tengah euforia UU Adminduk, pemerintah Indonesia memasukkan RUU
anti-pornografi dan anti-pornoaksi dalam program legislasi nasional 2007. Satu di
antara pasal yang akan diatur adalah cara berpakaian. Jika UU tersebut disahkan
dengan pasal cara berpakaian yang dasarnya perspektif agama tertentu, maka
praktik berpakaian di berbagai wilayah termasuk kelompok adat dan komunitas
Toleransi dalam Keberagaman
penghayat kepercayaan akan menjadi korban. Lagi-lagi, aktivis KBB dan
masyarakat adat mengadvokasi RUU yang berpotensi mengebiri kebebasan
masyarakat adat dan komunitas penghayat (Taufiqurahman, 2006).
Di lingkungan akademik, program studi agama dan lintas budaya (Center for
Religions and Cross-cultural Studies – CRCS) UGM adalah program studi yang
untuk pertama kalinya menawarkan mata kuliah indigenous religion (agama
lokal). Indigenous religion terdiri dari tiga topik: “(1) mempersoalkan paradigma
agama dunia yang dominan digunakan dalam studi agama, dan karenanya telah
berkontribusi pada marginalisasi kajian agama lokal; (2) pendekatan yang
memungkinkan produktivitas kajian agama lokal, dan agar terhindar dari bayang-
bayang perspektif agama dunia; dan (3) pandangan dunia yang melaluinya dapat
ditunjukkan perbedaan antara paradigma agama dunia dan paradigma agama
lokal”.26
Sampai di sini, kita menyaksikan pendampingan penghayat kepercayaan
dilakukan di level nasional. Lebih dari itu, advokasi lebih banyak menyangkut
status penghayat pada kebijakan nasional. Sejauh ini, belum ada LSM yang
bekerja di tingkat lokal atau komunitas yang secara langsung mendampingi hak
kewarganegaraan. Mengisi kekosongan tersebut, sejumlah LSM di lima wilayah
melakukan advokasi penghayat kepercayaan menggunakan inklusi sosial sebagai
perspektif di bawah payung program Peduli.
Advokasi Penghayat Kepercayaan Terkini: Program Peduli
Program Peduli melanjutkan inisiatif pemerintah Indonesia di bawah payung
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang saat itu
meluncurkan program turunan yakni PNPM Peduli 2011-2012. Program ini sedari
awal memang diluncurkan untuk mendukung masyarakat sipil yang selama ini
mendampingi kelompok termarjinalkan di Indonesia. Kegiatan pada program ini
pada masa itu mengutamakan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan dan
peningkatan kapasitas mereka yang terpinggirkan, dengan pertama-tama
menumbuhkan kapasitas pendampingan yang memadai bagi organisasi
masyarakat sipil. PNPM Peduli didukung berbagai donor internasional yang
Toleransi dalam Keberagaman
dikelola World Bank. Tiga organisasi masyarakat sipil yang menerima hibah ini
adalah Kemitraan, Association for Community Empowerment – ACE, dan
Lakpesdam, sayap organisasi intelektual Nahdlatul Ulama (NU). Program ini
menjangkau 15.000 penerima manfaat melalui 29 mitra lokal dan 20 cabang
Lakpesdam di Indonesia.27
Pemerintah Indonesia melanjutkan inisiatif ini sejalan dengan “Nawa Cita”
pemerintahan Joko Widodo, yang menyatakan bahwa negara harus hadir
melindungi segenap warga negara; negara hadir dalam menciptakan tata kelola
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari
wilayah pinggiran; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; serta
memperteguh kebhinekaan dan restorasi Indonesia. Kementerian Koordinasi
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) membidangi
program Peduli atas dukungan pemerintah Australia melanjutkan program Peduli
dengan menggandeng The Asia Foundation sebagai mitra pengelola program ini.
Program Peduli jilid dua ini dilaksanakan sepanjang 2014-2018 dibagi ke dalam
dua fase. Program ini mengidentifikasi enam kelompok yang dinilai selama ini
terpinggirkan: Anak dan remaja rentan, (2) masyarakat adat dan lokal terpencil
yang tergantung pada sumber daya alam, (3) korban diskriminasi, intoleransi, dan
kekerasan berbasis agama, (4) orang dengan disabilitas, (5) hak asasi manusia dan
restorasi sosial, dan (6) waria.
Program yang melibatkan 72 organisasi masyarakat sipil dan tersebar di 84
kabupaten atau kota di Indonesia ini mengharapkan peningkatan inklusi sosial
bagi warga atau kelompok termarjinalkan. Tujuan ini dicapai melalui perubahan
dengan tiga indikator berikut: meningkatnya akses yang termarjinalkan pada
layanan publik dan penerimaan sosial, meningkatnya pemenuhan hak asasi
manusia, dan kebijakan publik tentang inklusi sosial. Berdasarkan tiga hal ini,
program Peduli merumuskan tiga hal: penerimaan, pelayanan, dan kebijakan
sebagai pendekatan. Ketiganya kemudian disebut sebagai trilogi inklusi sosial
sebab satu tergantung pada yang lain, atau satu memengaruhi yang lain.
Penerimaan sosial hanya bermakna jika pemerintah memberi akses seluas- luasnya
untuk pelayanan publik. Layanan publik sangat tergantung pada kebijakan yang
Toleransi dalam Keberagaman
tersedia sejauh mana memungkinkan akses tersebut terbuka bagi kelompok
termarjinalkan. Kebijakan publik dan layanan sosial tidak bisa jalan jika
penerimaan sosial kepada mereka masih bermasalah.
Di Indonesia, warga atau komunitas yang mengalami kekerasan, intoleransi,
dan diskriminasi adalah komunitas penganut agama leluhur atau lebih dikenal
dengan sebutan aliran kepercayaan. Pada periode tertentu, pemerintah Indonesia
mengakui aliran kepercayaan dengan memberi perlindungan dan akses pada
pelayanan dan fasilitas publik. Pada saat yang lain, pemerintah mengeluarkan
regulasi baru yang meminggirkan aliran kepercayaan sebagai akomodasi kepada
kelompok agama arus utama. Pada masa berikutnya lagi, pemerintah kembali
mengakui aliran kepercayaan dan menyediakan fasilitas meski tidak lagi
diletakkan serumah dengan agama arus utama, melainkan diletakkan sebagai
bagian dari kebudayaan.28
Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan
Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memperkirakan jumlah
penghayat di Indonesia sekitar 10-12 juta penduduk. Sementara itu, Badan Pusat
Statistik mencatat jumlah lebih kecil dari perkiraan Kementerian Pendudukan dan
Kebudayaan, 299.617 orang yang mengaku “Lainnya” diasosiasikan dengan aliran
kepercayaan. Kesimpangsiuran angka ini mencerminkan ketidakjelasan pendataan
terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Situasi ini lebih jauh
menandakan pemerintah tidak secara resmi memasukkan penganut aliran
kepercayaan pada kategori dalam sensus data kependudukan. Meski demikian,
Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencatat 187
organisasi aliran kepercayaan di Indonesia.29
Program Peduli menargetkan penghayat kepercayaan menjadi target grup
untuk advokasi. Melalui Satunama, LSM di Yogyakarta yang berperan sebagai
executive organizer (EO), menjalankan program ini pada pilar agama dan
menggandeng enam LSM lokal sebagai pelaksana advokasi: LKIS di Yogyakarta,
Aliansi Sumut Bersatu (ABS) di Sumatera Utara, eLSA, Jawa Tengah, Yasalti dan
Donders di Pulau Sumba. “Mayoritas penganut Marapu tinggal di Pulau Sumba.
Semua penganut Marapu pasti orang Sumba, sebaliknya tidak semua penduduk
Toleransi dalam Keberagaman
Sumba adalah penganut Marapu,” tutur Peter Mikhael (Wawancara berswama
Pater Mikhael, direktur Yayasan Donders, pada 25 November 2018). Meski diakui
keberadaannya di masyarakat, penganut Marapu di antara golongan yang
termarjinalkan dari sisi akses terhadap layanan publik sebagai warga negara.
Endnote:
1
Lihat Zainal A. Bagir. “Defamation of Religion Law in Post- Reformasi Indonesia: Is
Revision Possible?” Australian Journal of Asian Law, 13 (2), (2013); Jeremy Menchik.
“Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia.” Comparative Studies in Society and
History, 56 (3), (2014): 591-621.
2
M. Sirozi. “Secular–Religious Debates on the Indonesian National Education System:
Colonial Legacy and a Search for National Identity in Education.” Intercultural Education, 15
(2), (2004): 123-137.
3
Melissa Crouch. “Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New
Problems, Local Politics and Court Action.” Asian Studies Review, 34 (4), (2010): 403-419.
4
Lihat S. Butt & T. Lindsey, The Constitution of Indonesia: a Contextual Analysis
(Bloomsbury Publishing, 2012); Melissa Crouch. “Constitutionalism, Islam and the Practice of
Religious Deference: The Case of the Indonesian Constitutional Court.” Australian Journal of
Asian Law, 16 (2) (2016).
5
Ihsan Ali-Fauzi, S.R. Panggabean, N.G. Sumaktoyo, H.T., Anick, H. Mubarok & S.
Nurhayati, Kontroversi Gereja di Jakarta (Jakarta: Centre for the Study of Islam and Democracy,
2011); Melissa Crouch. “Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New
Problems, Local Politics and Court Action.” Asian Studies Review, 34(4), (2010): 403-419.
6
Lihat D. Candraningrum. “Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian
Shari‘ah Ordinances (Perda Syariah).” Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, 45 (2), (2007):
289-
320. A. Salim. “Muslim Politics in Indonesia’s Democratization: The Religious Majority and
the Rights of Minorities in the Post New Order Era.” Indonesia: Democrarcy and the Promise of
Good Governance, (2007): 115-137; M. Buehler. “The rise of shari’a by- laws in Indonesian
districts: An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption.”
South East Asia Research, 16 (2), (2008): 255-285; R. Bush. “10 Regional Sharia Regulations in
Indonesia: Anomaly or Symptom?” in G. Fealy& S. White, (Eds.), Expressing Islam: Religious
life and politics in Indonesia. (Institute of Southeast Asian Studies, 2008); Ihsan Ali-Fauzi & Saiful
Mujani, Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Ata Perda Syariah. (Jakarta:
Freedom Institute, 2009).
7
Lihat Muhammad Afdillah, Dari Masjid ke Panggung Politik; Studi Kasus Peran Pemuka
Agama dan Politisi dalam Konflik Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di
Sampang Jawa Timur (Master thesis, Universitas Gadjah Mada: 2013); N. Farabi. Hambatan
Pemulangan Pengungsi Internal Syiah Sampang dan Ahmadiyah Lombok (Yogyakarta: Doctoral
dissertation, Universitas Gadjah Mada: 2014).
8
C. Koerner & W. D. Putro. “The Socio-Legal Construction of Ahmadiyah as a Religious
Minority by Local and National Government Policy: Restrictions before the Law, a Challenge for
Religious Freedom in NTB, Indonesia.” International Journal of Indonesia Studies, issue 4
(2017).
9
S. R. Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi, Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia (Jakarta:
Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Paramadina: 2014).
10
Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia
(Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).
11
J. Moulder. “ The Defence Act and Conscientious Objection.” Philosophical Papers, 7
(1), (1978): 25-50.
Toleransi dalam Keberagaman
12
D. Dwiyanto, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah
Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Pararaton, 2010).
13
S. Suhadi. “Who are “Normal” and “Extreme” Muslims? Discursive Study of Christians’
Voice about Muslim’s Identity in Surakarta, Central Java.” PCD Journal, 5 (2), (2017): 241-265.
14
J. Moulder. “ The Defence Act and Conscientious Objection.” Philosophical Papers, 7
(1), (1978): 25-50, dikutip oleh
Maarif, 2017.
15
M. C. Ricklefs. “The Asian Immigration Controversies of 1984-85, 1988-89 and 1996-97:
A Historical Review.” The resurgence of racism: Howard, Hanson and the race debate, 39-
61 (1997): 124.
16
D. Dwiyanto, Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah
Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Pararaton, 2010),
17
Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di
Indonesia (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017): 45.
18
Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia.
Yogyakarta: CRCS UGM, 2017): 74; S. Moniaga “12 From Bumiputera to Masyarakat Adat.” In
J. Davidson & D. Henley, (Eds.), The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The
Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism (London: Routledge, 2007).
19
Wawancara bersama Samsul Maarif, dosen CRCS UGM, 25 Maret 2019.
20
Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.
21
Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.
22
Wawancara Nia Syarifuddin, Direktur ANBTI, 28 Maret 2019.
23
Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019
24
Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.
25
Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.
26
Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia
(Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).
27
Tentang PNMP Mandiri. http://www.pnpm-mandiri.org/ PNPMPeduli.html.
28
Samsul Maarif, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di
Indonesia (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).
29
Frendi Kurniawan. “Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepecayaan.” Tirto, 14
November 2017. https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-
cz2y (diunduh 2 April 2019).
DAFTAR PUSTAKA
Afdillah, Muhammad. Dari Masjid ke Panggung Politik; Studi Kasus Peran
Pemuka Agama dan Politisi dalam Konflik Kekerasan Agama antara
Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur. Master Thesis,
Universitas Gadjah Mada, 2013.
Ali-Fauzi, I., & Mujani, S. Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis
Ata Perda Syariah. Jakarta: Freedom Instiute, 2009.
Ali-Fauzi, I., Panggabean, S. R., Sumaktoyo, N. G., Anick, H. T., Mubarok, H., &
Nurhayati, S. Kontroversi Gereja di Jakarta. Jakarta: Centre for the Study of
Islam and Democracy, 2011.
Bagir, Zainal A. “Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is
Revision Possible?” Australian Journal of Asian Law, 13 (2), (2013).
Buehler, M. “The rise of shari’a by-laws in Indonesian districts: An indication for
changing patterns of power accumulation and political corruption.” South
East Asia Research, 16(2), (2008): 255-285.
Toleransi dalam Keberagaman
Bush, R. “10 Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?”
in Fealy, G., & White, S. (Eds.). (2008). Expressing Islam: Religious life
and politics in Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
Candraningrum, D. “Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian
Shari‘ah Ordinances (Perda Syariah).” Al-Jami’ah: Journal of Islamic
Studies, 45(2), (2007): 289-320.
Crouch, Melissa. “Constitutionalism, Islam and the Practice of Religious
Deference: The Case of the Indonesian Constitutional Court.” Australian
Journal of Asian Law, 16 (2) (2016).
Crouch, Melissa. “Implementing the Regulation on Places of Worship in
Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action.” Asian Studies
Review, 34 (4), (2010): 403-419.
Dwiyanto, D. Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah
Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Pararaton, 2010.
Farabi, N. Hambatan Pemulangan Pengungsi Internal Syiah Sampang dan
Ahmadiyah Lombok. Yogyakarta: Doctoral dissertation, Universitas Gadjah
Mada, 2014.
Koerner, C. & Putro, W. D. “The Socio-Legal Construction of Ahmadiyah as a
Religious Minority by Local and National Government Policy: Restrictions
before the Law, a Challenge for Religious Freedom in NTB, Indonesia.”
International Journal of Indonesia Studies, issue 4 (2017).
Kurniawan, Frendi. “Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepecayaan.” Tirto. 14
November 2017. https://tirto.id/seberapa- banyak-jumlah-penghayat-
kepercayaan-di- indonesia-cz2y (dunduh 2 April 2019).
Maarif, Samsul. Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di
Indonesia. Yogyaarta: CRCS UGM, 2017.
Menchik, Jeremy. “Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia.”
Comparative Studies in Society and History, 56 (3), (2014):
591-621.
Moniaga, S. “12 From Bumiputera to Masyarakat Adat.” In Davidson, J., &
Henley, D. (Eds.). (2007). The Revival of Tradition in Indonesian Politics:
The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism. London:
Routledge, 2007.
Moulder, J. “The Defence Act and Conscientious Objection.” Philosophical
Papers, 7 (1), (1978):25-50.
Panggabean, S. R. & Ali-Fauzi, I. Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia
Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Paramadina, 2014.
Ricklefs, M. C. “The Asian Immigration Controversies of 1984-85, 1988-89 and
1996- 97: A Historical Review.” The resurgence of racism: Howard,
Hanson and the race debate, 39-61 (1997): 124.
S., Butt, & Lindsey, T. The Constitution of Indonesia: a Contextual Analysis.
Bloomsbury Publishing, 2012.
Salim, A. “Muslim Politics in Indonesia’s Democratization: The Religious
Majority and the Rights of Minorities in the Post New Order Era.”
Indonesia: Democrarcy and the Promise of Good Governance, (2007): 115-
137.
Toleransi dalam Keberagaman
Sirozi, M. “Secular–Religious Debates on the Indonesian National Education
System: Colonial Legacy and a Search for National Identity in Education.”
Intercultural Education, 15 (2), (2004) 123-137.
Suhadi, S. “Who are “Normal” and “Extreme” Muslims? Discursive Study of
Christians’ Voice about Muslim’s Identity in Surakarta, Central Java.” PCD
Journal, 5 (2), (2017): 241-265.
MATERI
Model Toleransi Berbasis Solidaritas Sosial Melalui Pendidikan
MULTIKULTURALISME PENDIDIKAN ISLAM
DALAM PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MANUSIA UNTUK
MEWUJUDKAN SOLIDARITAS SOSIAL
Nur Hadi
Latar Belakang
Manusia adalah makhluk yang diciptakan berbeda-beda dan beragam
(majemuk-multkultur) yang merupakan sesuatu yang mutlak (sunnatullah) dari
Allah. Namun, acapkali ciptaan yang “mutlak” ini dalam faktanya sering dijadikan
sebagai konflik dan ketegangan antarsesama manusia. Walaupun, juga tidak
dipungkiri bahwa hakikat manusia cenderung menghendaki adanya perubahan
pada dirinya sebagai makhluk sosial, sehingga kehidupan manusia senantiasa
mengalami gerak dinamis yang berbeda dari waktu ke waktu baik yang mencakup
kepribadian, ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat dan lainnya. Tetapi yang
menjadi persoalan bahwa nilai kemajukan (multikultural) yang ada di dalam
manusia sering dilanggar bahkan diingkari (Siradj, 1999: 203).
Padahal, manusia dan masyarakat tidak dapat dipisahkan karena secara
bersama-sama menyusun kehidupan. Manusia menghimpun diri menjadi satuan
sosial-budaya, menjadi masyarakat. Masyarakat manusia melahirkan,
menciptakan, menumbuhkan, dan mengembangkan kebudayaan: “tidak ada
manusia tanpa kebudayaan, sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa manusia; tidak
ada masyarakat tanpa kebudayaan, tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat”.
Berangkat dari pengalamannya manusia dengan kesadarannya mendorong
menyusun rumusan, batasan, definisi, dan teori tentang kegiatan-kegiatan
Toleransi dalam Keberagaman
hidupnya yang bermula dari karunia akal, perasaan dan naluri kemanusiaannya
yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, kemudian “mengikatnya” dalam
kebudayaan sehingga menjalankan fungsi external suprabiological.
Fenomena ini berbalik lurus dengan apa yang dilakukan oleh Ar-Razi
dimana dalam berpendapat selalu mengedepankan multikulturalisme pemahaman
pemahaman para Imam, yaitu tidak hanya menjabarkan pendapat-pendapat
Asy’ariyah saja, tetapi juga mengemukakan pendapat-pendapat Mu’tazilah,
Jabariyah, Qadariyahdan lain-lain. Bahkan ketika menjelaskan ayat-ayat ahkām,
Ar-Razi tidak pernah lupa untuk mengungkapkan pendapat dari empat mazhab
fikih (Hidayat, 2015: 108). Hal ini patut diteladani pada pembelajaran saat ini,
sebab keadaan yang dihadapi oleh seorang pendidik pada era kontemporer peserta
didik yang dihadapi memiliki latar belakang yang berbeda-beda.
Berkiblat dari hal ini, maka pendidikan Islam memiliki peran penting
dalam memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mewujudkan
pembentukan kepribadian manusia yang memberikan ruang “kebebasan” untuk
menemukan akan esensi kemanusiaannya kepada Allah Swt tanpa dibatasi ruang
dan waktu dan menurut bakat-minat, kemampuan, karakteristik, serta keunikannya
sehingga mampu mewujudkan solidaritas sosial.
Multikulturalisme Pendidikan Islam
1. Pengertian Multikulturalisme
Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi artinya
banyak, kultur berarti budaya, dan isme berarti “aliran atau paham”. Secara hakiki,
dalam kata itu terkandung pengakuan akan mertabat manusia yang hidup dalam
komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan
demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab
untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap
kebutuhan untuk diakui (politics of recognition) yang merupakan akar dari segala
ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan (Mahfud, 2016: 75). Artinya, bahwa
multikulturalisme merupakan sebuah paham yang menekankan pada kesederajatan
Toleransi dalam Keberagaman
dan kesetaraan tanpa mengabaikan hak-hak eksistensi manusia dalam kehidupan
masyarakat.
2. Pengertian Pendidikan Islam
Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata
laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia
melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang
mendidik (Sunarto, 2017: 216).
Kata pendidikan diambil dari bahasa Arab, yatu tarbiyah berarti
pendidikan. Tarbiyah dalam leksikologi pendidikan Islam Al-Qur’an dan As-
Sunnah tidak ditemukan istilah al-tarbiyah, namun terdapat beberapa istilah yang
seakar dengannya, yaitu al-rabb, rabbayani, nurrabi, yurbi, dan rabbani.
Tarbiyah diambil dari fi‘il madhi-nya (rabbani) maka memiliki arti memproduksi,
mengasuh, menanggung, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan,
memelihara, membesarkan, dan menjinakkan. Pemahaman ini diambil dari 3 (tiga)
ayat dalam Al-Qur’an, yaitu: QS. Al-Isra’: 24; (kamma rabbayani shagira-
sebagaimana mendidikku sewaktu kecil), QS. Asy-Syu’ara: 18; (alam nurabbika
fina walida- bukankah kami telah mengasuhmu di antara atau keluarga kami); QS.
Al-Baqarah: 276 (yamhu Allah al-riba wa yurbi shadaqah- Allah menghapus
sistem riba dan mengembangkan sistem sedekah) (Nata, 2013: 334; Mujib &
Mudzakkir, 2010: 12).
Pendidikan menurut pandangan Islam adalah bagian dari tugas
kekhalifahan manusia yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.
Kemudian pertanggungjawaban itu baru bisa dituntut kalau ada aturan dan
pedoman pelaksanaan. Oleh karena itu, Islam tentunya memberikan garis-garis
besar tentang pelaksanaan pendidikan tersebut. Islam memberikan konsep-konsep
yang mendasar tentang pendidikan dan menjadi tanggung jawab manusia untuk
menjabarkan dengan mengaplikasikan konsepkonsep dasar tersebut dalam praktik
kependidikan (Zuhairi et.al., 1995: 148). Oleh karenanya, pendidikan Islam
merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran
multikulturalisme. Artinya, pendidikan Islam mampu berperan sebagai sarana bagi
terciptanya fundamen kehidupan multikultural secara ideal.
Toleransi dalam Keberagaman
Berangkat dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
multikulturalisme pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang menghargai,
menghormati dengan segala perbedaan yang ada baik dari etnis, budaya, sosial
yang dimiliki oleh setiap inividu dalam masyarakat secara ideal berdasarkan nilai-
nilai Islam.
Multikultiralisme Pendidikan Islam dalam Membentuk Kepribadian
Manusia untuk Mewujudkan Solidaritas Sosial
Pendidikan menyimpan kekuatan yang luar biasa untuk menciptakan
keseluruhan aspek lingkungan hidup dan dapat memberi informasi yang paling
berharga mengenai pegangan hidup masa depan di dunia, serta membantu peserta
didik dalam mempersiapkan kebutuhan esensial untuk menghadapi perubahan
(Zuharini, dkk., 2012: 160). Pendidikan Islam seperti pendidikan pada umumya
adalah membentuk kepribadian manusia melalui proses panjang dengan hasil yang
tidak dapat diketahui segera (Ramayulis, 2013: 208).
Pendidikan Islam harus mampu mencapai pertumbuhan kepribadian
manusia secara utuh dan seimbang dengan melalui latihan jiwa, intelektual, diri
manusia yang rasional, perasaan, dan indra. Oleh karena itu, pendidikan Islam
harus mencapai pertumbuhan manusia dalam aspeknya: spiritual, intelektual,
imajinatif, fisik, ilmiah, dan bahasa, baik secara individual maupun secara
kolektif. Selain itu, juga mendorong aspek ke arah kebaikan dan mencapai
kesempurnaan. Dimana tujuan akhir pendidikan Islam terletak dalam
ketertundukan yang sempurna kepada Allah (ultimate aims of education) (Azra,
2002: 57). Dan ini bersifat mutlak dan universal, tidak mengalami perubahan dan
berlaku umum, karena sesuai dengan konsep Ilahiyah dengan tujuan hidup
manusia dan peranannya sebagai makhluk ciptaan Allah: (1) menjadikan peserta
didik sebagai hamba yang paling bertakwa; (2) mengantarkan subjek peserta didik
menjadi khalifatullah fil ‘ard, yang mampu memakmurkan, membudayakan alam
sekitar dan mewujudkan rahmat bagi alam sekitarnya sesuai dengan tujuan
penciptanya; (3) memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia
sampai di akhirat baik individu maupun masyarakat.
Toleransi dalam Keberagaman
Hal ini selaras dengan yang diuraikan Abdurrahman An-Nahlawy (1965:
67) bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan beberapa hal: (1) pendidikan akal
dan persiapan pikiran; (2) menumbuhkan potensi-potensi dan bakat-bakat asal
pada peserta didik sesuai dengan fitrah manusia; (3) menaruh perhatian pada
kekuatan dan potensi peserta didik dan mendidiknya sebaik-baiknya; (4) berusaha
untuk menyumbangkan segala potensi-potensi dan bakat peserta didik sebagai
manusia.
Terdapat 3 (tiga) nilai yang perlu diberikan dikembangkan dalam
pendidikan Islam dalam membentuk keperibadian manusia (peserta didik), yaitu:
(1) belajar hidup dalam perbedaan; (2) kebebasan berpendapat atau terbuka dalam
berpikir; (3) saling menghargai dan menghormati. Apabila ketiga nilai
multikultural ini diaktualisasikan ke dalam pendekatan pembelajaran pendidikan
Islam, maka akan dihasilkan pembelajaran yang multikultural dengan ciri-ciri: (1)
peserta didik tidak lagi menerima informasi secara pasif, tetapi peserta didik bisa
bersifat aktif di dalam pembelajaran, karena peserta didik diberikan kebebasan
berpendapat sesuai dengan wawasan keilmuan yang dimilikinya, dan pendidik
berfungsi sebagai filter pengetahuan; (2) pembelajaran yang dilakukan tidak hanya
dilakukan secara abstrak dan teoritis, akan tetapi lebih kepada mengaitkan teori
kepada hal-hal yang ada di sekitar; (3) pembelajaran didasari pada pendekatan
memberi kebebasan dalam berpendapat atau terbuka dalam berpikir; (4)
pembelajaran harus didasari atas asas saling menghargai, akan menciptakan suatu
kondisi di mana seorang pendidik tidak mutlak menjadi “raja-intruktur” di dalam
kelas; dan (5) pembelajaran didasarkan pada kesadaran tanpa berpikir bahwa
perilaku tersebut akan mendapatkan penilaian ataupun tidak.
Dengan demikian, pendidikan Islam akan mampu menjadi institusi dalam
membentuk kepribadian manusia (peserta didik) dengan cara menanamkan nilai-
nilai keislaman di dalam kemajemukan sebagai landasan keyakinan yang mutlak
dengan menyeimbangkan pengetahuan agama dengan pengetahuan dari segala lini
dalam rangka membentuk peserta didik menjadi manusia paripurna, yaitu dengan
mempertahankan tradisi keislaman lama yang masih relevan dan mengambil
pemikiran barat yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam maupun esensi
Toleransi dalam Keberagaman
pendidikan Islam itu sendiri sehingga peserta didik akan mampu menemukan
esensi dirinya dengan berpedoman kepada falsafah Islam yang diaktualisasikan
dimana saja dan kapan saja tanpa dibatasi ruang dan waktu (Ramayulis, 2013:
187), sehingga akan terwujud solidaritas sosial yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan tanpa memandang perbedaan suku, ras, etnis, budaya, bahasa, dan
agama.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Razi, Abu Bakar. 1978. al-Thibb al-Ruhani, Tahkik ‘Abd Al-Lathif Al-Ghaid,
Kairo: Maktabat al-Nahdat al-Mishriyyat.
An-Nahlawy, Abdurrahman. 1965. Usus al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Thuruq
Tadrisiha, Damaskus: Dar al-Nahdhal al-Arabiyah.
Azra, Azyumardi. 2002. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernitas Menuju
Milenium Baru, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
Hidayat, Moh. Noor. 2015. Internalisasi Nilai-nilai Multikultural dalam Tafsîr Al-
Razi pada Pengembangan Pendekatan Pembelajaran Tafsir, jurnal Studi
Agama dan Masyarakat, Vol. 11, No. 1.
Mahfud, Choirul. 2016. Pendidikan Multikultural, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. 2010. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta:
Kencana Prenada Media.
Nata, Abudin. 2013. Metodologi Studi Islam, Jakarta: Rajawali Pers.
Ramayulis. 2013. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia.
Siradj, Said Aqil. 1999. Islam Kebangsaan: Fiqh Demokratik Kaum Santri,
Jakarta: Pustaka Cinganjur.
Sunarto. 2017. Sistem Pembelajaran PAI Berwawasan Multikultural. Jurnal Al-
Tadzkiyah. Vol. 8 No. 2.
Zuharini, dkk. 2012. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Bumi Aksara.
Toleransi dalam Keberagaman
MATERI
Model Toleransi Berbasis Komunitas (Lingkungan)
TOLERANSI DALAM ISLAM: (Antara Ideal dan Realita)
M. Maulana Mas’udi
Latar Belakang Masalah
Masyarakat Indonesia dikenal sebagai sosialistis-relegius. Kehidupan
agama di negeri ini mempunyai tempat tersendiri yang utama sebagai
konsekuensi logis dari pemenuhan kebutuhan atau keperluan dari kehidupan
masyarakat itu sendiri, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota
masyarakat secara bersama.
Terdapat berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia merupakan suatu
kenyataan. Indonesia negara yang berdasarkan pancasila mengetahui adanya 6
(enam) agama, yaitu : Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan yang terahir
adalah Kong Hu Cu. Diharapkan dengan kenyataan tersebut setiap orang dan
umat beriman dituntut untuk mengambil sikap. Sikap yang menegaskan bahwa
agama mempunyai makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu fungsi
agama ialah memupuk persaudaraan umat beragama yang bercerai-berai.1
Dengan adanya pluraritas agama ini, maka diperlukan adanya rasa saling
menghormati, serta saling bertoleransi antar umat beragama. Hal ini sangat
penting agar tidak terjadi ketegangan antara satu penganut agama dengan agama
lain. Terjadinya interaksi sosial sehingga tidak jarang terjadi konflik yang
merusak dan mengganggu perkembangan masyarakat.2 Untuk menghindari
terjadinya konflik dalam masyarakat maka diperlukan adanya toleransi yang
dapat memberikan suatu keselarasan dan kerukunan hidup bermasyarakat.
Toleransi merupakan sikap yang positif apalagi di Indonesia negara yang
berdasarkan Pancasila, yang memberi dan menjamin kebebasan bagi
Toleransi dalam Keberagaman
penduduknya untuk memeluk suatu agama dan kepercayaan yang disukainya
tanpa ada paksaan. Hal ini telah dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945
pasal 29 : 2, bahwa : Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agama masing- masing dan untuk beribadat menurut agama dan
kepercayaannya. 3
Negara juga tidak hanya melindungi dan memberi kebebasan, akan tetapi
juga mendukung dan memberikan bantuan kepada umat beragama
untuk memajukan kehidupan agamanya tanpa menimbulkan konflik dan
kerugian bagi umat agama lain.
Adanya toleransi antar umat beragama merupakan hal yang sangat penting,
sebab keberadaan toleransi dapat menciptakan kerukunan hidup antar umat
beragama. Toleransi merupakan awal adanya kerukunan, tanpa adanya toleransi
tidak mungkin ada sikap saling menghormati, mengasihi dan gotong-royong
antar umat beragama. Tetapi pada masa sekarang ini toleransi sering disalah
artikan dengan mengakui kebenaran semua agama.4 (Ahmad Azhar Basyir, 1993
: 240). Sehingga tidak jarang ada orang mengikuti perayaan keagamaan lain
tanpa diketahui, apakah itu acara biasa atau acara meriah dengan dalih toleransi.
Islam merupakan agama yang lengkap dan sempurna ajarannya meliputi
seluruh aspek kehidupan termasuk di dalamnya tentang hubungan antar manusia
yang dapat menciptakan kerukunan di antara mereka. Islam mengakui adanya
titik temu yang bersifat esensial dari berbagai agama, khususnya agama-agama
Samawi yakni kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan
untuk hidup Bersama 5.
Pengertian Agama dan Toleransi
1. Pengertian Agama
Menurut bahasa kata “agama” berasal dari bahasa sansekerta yakni dari
kata “a” berarti "tidak" dan gama berarti "kacau". Jadi agama bermakna "Tidak
Kacau" (beraturan)6. Adapun menurut istilah, agama berarti :
a. Sebagai pegangan atau pedoman hidup kekekalan
Toleransi dalam Keberagaman
b. Pelajaran yang menguraikan tata cara yang semuanya penuh misteri karena
tuhan dianggap bersifat rahasia
c. Mempunyai peraturan, memiliki tata tertib dari Tuhan yang mengatur hidup
dan kehidupan manusia lahir batin baik hubungan antara manusia dengan
manusia dan mahluk lain, maupun antara manusia terhadap Tuhan dengan
harapan agar selamat di dunia dan di akhirat 7.
Agama menurut F.O. Dea adalah "Pendayagunaan sarana-sarana supra-
empiris untuk maksud-maksud non empiris atau supra empiris"
8(Hendropuspito, 1991 : 34). Emile Durkhem memberikan definisi agama yaitu
"suatu kesatuan daripada kepercayaan-kepercayaan dan tingkah laku yang
berhubungan dengan hal-hal yang suci 9(Saparlan, 1990 : 8). Dari definisi yang
disampaikan oleh Emile Durkhem di atas dikembangkan lagi menjadi empat
unsur yang saling berkaitan, antara lain :
1. Unsur kepercayaan atau keyakinan manusia tentang bentuk dunia alam
ghaib, hidup, mati dan nyata
2. Unsur emosi atau getaran jiwa yang menggerakkan manusia mempunyai
masa cipta dan karya keagamaan.
3. Unsur rituis atau upacara keagamaan yang bertujuan mencari
4. hubungan dengan dunia ghaib berdasarkan sistem kepercayaan yang
diyakininya
5. Unsur kesatuan atau solidaritas kelompok keagamaan yang
melembaga dalam masyarakat 10.
Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui
bahwasanya meskipun dalam memberikan difinisi itu berbeda-beda, tetapi pada
dasarnya intinya adalah sama, yaitu agama merupakan pedoman hidup yeng
berasal dari Tuhan, yang mengatur hidup dan kehidupan manusia lahir dan batin
sehingga dapat menimbulkan ketenangan bagi para penganutnya.
Setelah mengetahui pengertian agama dari segi bahasa dan istilah, maka
untuk lebih jelasnya difinisi tentang agama ini, penulis membahas pengertian
Toleransi dalam Keberagaman
agama menurut para ahli sejarah agama.
Ahli sejarah agama berpendapat bahwa agama ada 2 macam, yaitu :
agama Samawi dan agama Ardhi. Agama Samawi (Revealed Religion) ialah
agama wahyu yang berasal dari langit, agama ini diwahyukan kepada para nabi
melalui MalaikatNya, sedangkan agama Ardhi ialah agama kebudayaan yang
diciptakan oleh akal manusia 11.
Agama Islam termasuk agama Samawi, yaitu agama yang bersumberkan
wahyu Allah yang disampaikan kepada nabi Muhammad saw. Islam secara
harfiah berarti patuh, taat dan taslim. Kata agama dan Islam apabila
digabungkan akan menjadi agama Islam yang berarti "Suatu ajaran yang
dibutuhkan manusia guna mengikat kebulatan dan ketulusan tekadnya"
menuju Allah SWT 12.
Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah membutuhkan agama dalam
kehidupannya yang digunakan sebagai pedoman hidup di dunia agar tidak
tersesat, hal ini disebabkan agama mempunyai fungsi-fungsi dan peranan. Fungsi
dan peranan agama atas diri pribadi setiap insan yang patut dan penting untuk
benar- benar dihayati, adalah:
a. Mendidik manusia jadi : tentram / damai, tabah dan Tawakal, ulet dan percaya
pada diri sendiri.
b. Membentuk manusia jadi : Berani berjuang menegakkan kebenaran dan
keadilan dengan kesiapan mengabdi dan berkorban.
c. Mencetak manusia jadi: (1) Berani berjuang menegakkan kebenaran dan
keadilan dengan kesiapan mengabdi dan berkorban; (2) Sadar, enggan dan
takut untuk melakukan pelanggaran yang menjurus kepada dosa.
d. Memberi Sugesti Manusia : Agar dalam jiwanya tumbuh sifat mulia,
terpuji, penyantun toleran dan manusiawi 13.
Dengan demikian tidak dapat dipungkiri lagi bahwa agama itu penting
dalam kehidupan manusia, sebab agama dapat membuat orang menjadi lebih baik
dan menganjurkan pada manusia untuk menghindari sikap permusuhan dengan
Toleransi dalam Keberagaman
menumbuhkan sikap toleran pada sesama manusia.
2. Pengertian Toleransi
Toleransi adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Inggris tolerance,
selanjutnya kata ini dipopulerkan dalam bahasa Indonesia menjadi toleransi yang
berarti sikap membiarkan lapang dada di dalam bahasa arabnya biasa
dikatakan ikhtimal tasaamukh yang artinya sikap membiarkan lapang dada 14.
Menurut istilah, toleransi berarti "Pemberian kebebasan kepada sesama
manusia / kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinannya
atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya masing-masing, selama di
dalam menjalankan dan menentukan sikap itu tidak melanggar dan tidak
bertentangan dengan syarat-syarat asas terciptanya ketertiban dan perdamaian
dalam masyarakat” 15.
Pendapat beberapa agama tentang toleransi :Toleransi menurut agama
Islam adalah pengakuan adanya kebebasan setiap warga negara untuk memeluk
suatu agama yang menjadi keyakinannya dan kebebasan untuk menjalankan
ibadahnya 16 (Departemen Agama, 1982-1983 :120).
Menurut Agama Kristen toleransi adalah menghormati, menghargai,
menjunjung tinggi semua manusia. Hai ini tercantum dalam kitab perjanjian baru
surat Matius 22 : 39, yang bunyinya : "Dan hukum yang kedua yang sama itu
ialah : Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri” 17.
Agama Hindu berpendapat bahwa toleransi adalah "memiliki sifat terbuka
bagi semua pihak, karena di dalam Kitab Suci Weda tertera Bhineka Tunggal Ika,
Tat Hana Dharma Mangrwa" yang berarti berbeda-beda mengucapkan, tapi
Tuhan tiada duanya tapi hanya satu, yaitu Syang Hyang Widhi Wasa / Tuhan
Yang Maha Esa 18.
Dari pengertian di atas dapat diambil pelajaran bahwasannya toleransi
menurut agama Hindu adalah semua agama itu sama, meskipun agamanya
Toleransi dalam Keberagaman
berbeda. Toleransi menurut agama Budha adalah saling kasih-mengasihi,
hormat- menghormati terhadap semua paham serta aliran agama yang ada.
Masalah toleransi agama Budha ini tercantum dalam piagam yang dibuat
oleh Raja Asoka. Piagam ini telah berusia lebih dari 22 abad. Isi piagam itu
adalah sebagai berikut : “Bila kita menghormati agama kita sendiri, janganlah
kita lalu mancemooh dan menghina agama lain. Seharusnya kita menghargai pula
agama-agama lainnya. Dengan demikian agama kita menjadi berkembang
disamping kita juga memberikan bantuan bagi agama-agama lainnya. Kalau
berbuat sebaliknya berarti kita telah menggali lubang bagi agama kita sendiri,
disamping kita telah membuat celaka bagi agama lainnya. Siapa yang
menghormati agamanya tetapi menghina agama lainnya dengan pikiran bahwa
dengan berbuat demikian ia merasa telah melakukan hal-hal yang baik bagi
agamanya sendiri, maka sebaliknya hal ini akan memberikan pukulan kepada
agama dirinya dengan hebat, maka karena itu toleransi dengan kerja sama sangat
diharapkan sekali dengan jalan suka juga mendengar ajaran agama-agama
lainnya, disamping mendengar ajaran-ajaran agama sendiri (Departemen
Agama,19.
Dari paragraf di atas dapat diketahui bahwa dalam agama Budha telah
mengajarkan kepada umatnya sejak dahulu tentang toleransi umat Budha tidak
diperbolehkan untuk mencemooh agama lain, mereka dianjurkan untuk
menghormati agamanya sendiri juga agama lain. Selain itu agama Budha tidak
melarang umatnya mendengarkan ajaran dari agama lain, tanpa melalaikan ajaran
agamanya sendiri.
Toleransi Antar Umat Beragama
Masalah toleransi di kalangan masyarakat merupakan masalah yang
sangat peka, bahkan merupakan masalah yang paling peka di antara berbagai
masalah sosial budaya lainnya. Sebab, terjadinya suatu masalah sosial akan
menjadi semakin ruwet jika masalah tersebut menyangkut pula masalah
agama dan kehidupan agama.
Toleransi dalam Keberagaman
Agama merupakan kesempurnaan eksistensi manusia, sumber vitalitas
yang mewujudkan perubahan dunia dan melestarikannya. Kualitas suatu
perubahan ditentukan oleh kualitas agama yang menjadi dasarnya. Seiring
dengan itu, agama juga diakui sebagai salah satu dan bahkan satu-satunya sumber
nilai, memiliki peranan dan sumbangan yang sangat besar dan paling tinggi bagi
sikap kehidupan manusia. Semua kebudayaan besar dan bersejarah telah diilhami
kelahiran dan perkembangannya oleh nilai-nilai dan semangat yang berurai
berakar dalam agama-agama besar. Sebagian besar pula peristiwa-peristiwa
univikasi dan konflik dunia dilatar belakangi oleh faktor agama. Agama
mempunyai kekuatan pengikat yang luar biasa ke dalam dan semangat keras
menyalahkan pertentangan ke luar (Power of Interhagnity and Eksternal
Conflict) 20.
Telah dijelaskan di muka bahwa negara Indonesia mengakui keberadaan
enam agama, dengan adanya enam macam agama ini tidak mudah untuk
mempersatukannya. Tetapi meskipun begitu hubungan antar berbagai agama di
Indonesia ini bervariasi, antara Hindu - Budha terjalin hubungan yang harmonis
begitu juga antar keduanya dengan Islam. Islam, Katholik, Prostestan dan Kong
Hu Cu mewarisi hubungan sejarah yang tidak menggembirakan sebelum
menginjakkan kaki masing-masing di bumi Indonesia, telah terlibat dalam
hubungan pertentangan dan konflik, eksklusivisme dan intoleran 21 . Hal ini
disebabkan setiap agama menganggap bahwa agamanya yang paling benar dan
menganggap bahwa agama lain salah. Di samping itu pertentangan iman,
kecemburuan sosial ekonomi, kecurigaan rasisme dan politik telah memicu
timbulnya konflik sampai ke tingkat bentrokkan fisik dalam wujud peperangan
yang menimbulkan korban harta dan jiwa pada kedua belah pihak di abad-abad
pertama perjumpaan di Indonesia.
Pada masa sekarang ini, hal seperti itu sedikit demi sedikit dapat
dihilangkan, meskipun tidak bisa secara keseluruhan karena memang adanya
perbedaan di antara umat beragama itu. Indonesia merupakan negara demokrasi
yang berdasarkan Pancasila, maka dari itu di Indonesia tidak ada paksaan dalam
Toleransi dalam Keberagaman
memilih agama atau kepercayaan, serta meakukan ibadah menurut agama dan
kepercayaannya masing-masing tanpa mengganggu kegiatan ibadah agama yang
lainnya. Untuk itu menciptakan itu semua maka diperlukan kesadaran dari setiap
individu untuk menghormati dan memberi kesempatan kepada orang yang
beragama lain dalam melakukan ibadah.
Sikap toleran antar umat beragama sangat diperlukan di sini sebab tanpa
umat beragama tidak akan tercipta hubungan yang harmonis dalam kehidupan
beragama. Toleransi yang diinginkan di sini bukan berarti mengakui kebenaran
semua agama tetapi memberikan kebebasan kepada pemeluk agama lain untuk
menjalankan ibadahnya menurut keyakinannya masing-masing. Seperti
yang ditegaskan oleh Suharto:
Toleransi antar umat beragama itu tidak berarti bahwa ajaran agama kita
masing-masing menjadi campur aduk. Toleransi hidup beragama itu
bukan suatu bentuk campur aduk melainkan terwujudnya ketenangan,
saling harga menghargai dan kebebasan yang sebebas-bebasnya bagi
setiap penduduk dalam menjalankan ibadah agama menurut keyakinannya
masing-masing bahkan sebenarnya lebih dari itu, antar semua pemeluk
agama harus dapat dibina kegotong royongan di dalam membangun
masyarakat kita sendiri, demi kebahagiaan bersama Sikap permusuhan
sikap prasangka harus kita buang jauh jauh, dan kita ganti dengan saling
hormat menghormati 22.
Dari penegasan Suharto di atas, dapat diambil pelajaran bahwa sikap
toleransi merupakan sikap yang positif, oleh karena itu perlu dikembangkan
dalam usaha untuk menciptakan keharmonisan dalam kehidupan antar umat
beragama. Tetapi seandainya tidak ada sikap toleransi maka akan mengakibatkan
hal-hal yang negatif yang dapat merugikan semua pihak. Sebab kalau tidak ada
toleransi maka akan terjadi :
a. Perpecahan, perpecahan antar umat beragama akan berakibat fatal sebab hal
ini akan mengundang campur tangan pihak lain untuk ikut-ikutan
meredahkannya. Hal ini telah terjadi pada masa lalu sehingga tanpa sadar
negara telah diadu domba oleh bangsa lain, hal itu dikarenakan bangsa belum
bisa bersatu.
b. Tertutup untuk tidak menerima kritik buah pikiran dan saran.
Toleransi dalam Keberagaman
Intoleran (tidak toleran) adalah manifestasi dari sikap takabur bersumber dari
perasaan bahwa dirinya paling sempurna, tidak ada yang melebihi atau
menandingi dalam segala-galanya23. Sikap atau perasaan paling sempurna ini
cenderung menutup adanya kritik dan saran, malahan lebih cenderung
melakukan kritik terhadap orang lain. HaI ini akan merugikan karena dapat
membawa kemunduran dan cenderung statis.
c. Bersikap isolatif dan radikal ekstrim
Sikap ini akan membawa kerugian baik bagi individu maupun
kelompok, sebab perasaan superioritas selalu memandang remeh kepada
setiap orang, baik keyakinan maupun kebangsaan sehingga tidak mau
menerima masukan dari orang lain dan bersikap menutup diri tanpa
menunjukkan sikap tenggang rasa.
Maka dari itu sikap intolerans harus dihilangkan kalau ingin mencapai
kehidupan yang sejahtera baik dalam masyarakat maupun dalam negara.
Sebab di samping sikap ini tidak menguntungkan, juga tidak ada gunanya
apabila hidup bermasyarakat, tetapi tidak rukun.
Untuk menciptakan sikap dan suasana toleransi di antara sesama
manusia atau di antara pemeluk agama yang berbeda, maka diperlukan segi-
segi antara lain:
a. Mengakui hak setiap orang
Suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam
mementingkan sikap, laku dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap
atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. Karena
kalau demikian kehidupan di dalam masyarakat akan kacau.
b. Menghormati keyakinan orang Lain
Landasan keyakinan di atas berdasarkan kepercayaan bahwa yang
tidak benar orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya
sendiri kepada orang atau golongan lain. Tidak ada orang atau golongan
yang memonopoli kebenaran dan landasan ini disertai catatan bahwa soal
keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing orang.
Toleransi dalam Keberagaman
c. Agree in disagreemant
"Agree in Disagreemant" (setuju dalam perbedaan) adalah prinsip
yang selalu didengungkan oleh Mukti Ali (Bapak Perbandingan Agama
Indonesia). Perbedaan tidak harus ada permusuhan karena perbedaan
selalu ada di dunia ini, dan perbedaan tidak harus menimbulkan
pertentangan.
d. Saling mengerti
Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama orang bila
mereka tidak saling mengerti, saling anti dan saling membenci, saling
berebut pengaruh adalah salah satu akibat dari tidak adanya saling
mengerti dan saling menghargai antara satu dengan yang lain.
e. Kesadaran dan Kejujuran
Toleransi menyangkut sikap jiwa dan kesadaran batin seseorang.
Kesadaran jiwa menimbulkan kejujuran dan kepolosan sikap laku.
f. Jiwa falsafah Pancasila
Falsafah Pancasila telah menjamin adanya ketertiban dan
kerukunan hidup bermasyarakat. Falsafat Pancasila merupakan suatu
landasan yang diterima oleh segenap manusia Indonesia merupakan tata
hidup dan dasar negara kita 24.
Enam segi-segi diatas mempunyai kedudukan yang sama yang
seharusnya bisa berjalan dan dihayati oleh setiap orang, agar dapat
menciptakan suasana toleransi di kalangan masyarakat dan umat beragama.
Dasar-dasar toleransi dalam islam
Islam dan umatnya selalu bersikap toleran dan selalu bekerja sama
berbuat seperti yang diperbuat oleh warga masyarakat lainnya, selagi hal
tersebut masalah kemasyarakatan. Sikap Islam terhadap umat lain tetap
hormat, mereka diperlakukan dengan penuh persaudaraan sebagai manusia
meskipun berbeda agama.
Hal ini bagi Islam bukanlah merupakan masalah baru, melainkan telah
Toleransi dalam Keberagaman
dipraktekkan Rasullullah saw. 15 abad yang lalu. Sungguh telah dilaksanakan
Rasul Allah dalam berbagai peristiwa sejarah dan kehidupan beliau sehari-
hari. Kemudian praktek Nabi itu diteruskan oleh Khalifah yang ada dan
pemimpin Islam lainnya hingga diikuti oleh umat Islam sampai saat ini.
Masalah toleransi antar umat beragama ini juga sudah dijelaskan
dalam aI- Qur’an dan hadits yang kedua-duanya merupakan pedoman hidup
bagi seluruh umat Islam yang didalamnya terdapat ajaran-ajaran yang jelas
tentang tata cara hidup bermasyarakat.
Ayat-ayat al-Qur'an tentang toleransi antar umat beragama, antara
lain: Q.S. Al-Baqarah ayat 256; Q.S. al-An'am ayat 108; Q.S. Yunus ayat 99
-100; Q.S. al- Kahfi ayat 29.
Dari keempat ayat tersebut dapat diambil suatu ketentuan bahwa tidak
dibenarkan dalam Islam memaki sembahan agama lain atau
memaksakan agamanya kepada orang lain. Persoalan kebebasan seseorang itu
tidak dibenarkan adanya unsur paksaan, karena masalah keimanan
merupakan urusan pribadi seseorang dengan Tuhannya. Hal ini menyangkut
petunjuk dan rahmat-Nya, tanpa itu mustahil seseorang beragama lain bisa
menjadi Muslim.
Hadits tentang toleransi antar umat beragama, antara lain
sebagaimana tersebut di bawah ini: Pertama, hadits yang diriwayatkan oleh
Abu Dawud, termasuk hadits hasan (Al-Bary, 1410 H: 215) yang berbunyi :
Artinya : “Barang siapa menzhalimi mu’ahad (orang kafir yang
mengikat perjanjian dengan kaum Muslimin), atau mengurangi hak-
hak orang tersebut atau memberikan beban padanya di luar batas
kemampuanya atau mengambil sesuatu darinya tanpa keridhaan
dalam hatinya, maka aku (Rasulullah) yang akan menjadi pembela
baginya di hari kiamat”29
Toleransi dalam Keberagaman
Hadits di atas menjelaskan bahwa non Muslim harus dijamin haknya,
keselamatan jiwa, harta dan kebebasan agama mereka di dunia. Nabi akan
memperkarakan orang yang menyakiti atau mengganggu hak-hak non
Muslim itu dalam pengadilan Allah di hari kiamat.
Kedua, hadits yang lainnya (Al-Mubarakfurry, 1412 H: 405)
menyatakan :
Artinya : “Nabi bersabda, "Wahai golongan Quraisy apakah yang
akan saya perbuat terhadap kamu sekalian menurut dugaanmu?"
Jawab mereka "Engkau akan berbuat baik sebab engkau adalah
seorang saudara yang menolong dan anak seorang saudara yang
mulia". Nabi bersabda "Pergilah (kemana kamu suka) sebab kamu
semuanya dibebaskan/dimaafkan".30
Hadits di atas menerangkan tentang peristiwa setelah jatuhnya kota
Mekkah ke tangan nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Orang-
orang Quraisy merasa sangat khawatir akan tindakan pembalasan dendam
dari nabi dan pasukan Islam kepada mereka, sebab mereka telah berbuat
kejam melampaui batas terhadap nabi dan orang-orang Islam yang
mengakibatkan nabi dan sahabatnya meninggalkan kampung halaman
mereka, Makkah, berhijrah ke kota Madinnah. Tetapi di luar dugaan mereka,
nabi Muhammad saw. justru memberikan pengampunan kepada mereka dan
Nabi melarang para sahabat-sahabatnya membalas dendam terhadap mereka.
Berpangkal pada dasar-dasar di atas, maka dapat diperoleh pelajaran
bahwa agama Islam itu adalah agama yang penuh dengan toleransi. Sejak
zaman nabi Muhammad saw. toleransi antar umat beragama ini sudah
dilaksanakan oleh kaum Muslimin terhadap atau dengan non Muslim.
Toleransi dalam Keberagaman
Dengan demikian secara normatif doktrinal, Islam menuntun dan
menuntut adanya sikap dan sifat toleansi setiap Muslim terhadap non Muslim
dengan batas- batas tertentu demi keselamatan kehidupan sosial masyarakat
antar umat beragama, dengan tidak mengorbankan aqidah dan syari’ah Islam.
Toleransi Pada Masa Rasulullah
Masa toleransi antar umat beragama dalam agama Islam, bukanlah
merupakan masalah yang asing atau baru dan bukan pula merupakan masalah
yang masih berupa teori atau slogan saja, melainkan telah dipraktekkan
oleh Nabi Muhammad saw. pada 15 abad yang lalu, pelaksanaan toleransi yang
dilaksanakan oleh Rasullullah SAW ini tidak berhenti sampai di situ saja, tetapi
kemudian diteruskan oleh para sahabat dan para penguasa pemerintahan Islam
selanjutnya (Dinasti Umayyah dan Abbasiyah) serta diikuti oleh segenap umat
Islam di mana pun mereka berada.
Hal itu adalah wajar, sebab di dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang kedua-
duanya merupakan Way of Life dari seluruh umat Islam, terdapat ajaran-ajaran
yang jelas tentang pentingnya toleransi antar umat beragama.
Islam merupakan agama yang penuh dengan toleransi, ini dapat dibuktikan
dari cara penyebaran agama Islam yang dilakukan dengan cara yang damai serta
tidak ada pemaksaan bagi orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Sebelum
Islam lahir dan menyebar di bumi ini tidak ada toleransi beragama. Di sana-sini
terjadi pemaksaan terhadap rakyat untuk memeluk salah satu agama atau sekte
agama tertentu dan apabila ada yang menentangnya maka akan disiksa, keadaan
seperti ini pernah terjadi di kerajaan Romawi (Masjfuk Zuhdi, 1989 : 847).
Tetapi setelah datangnya agama Islam yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits,
semua itu bisa diminimalisir, kalau pun hal itu terjadi lagi itu merupakan hasil
perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab.
Untuk menghindari adanya persengketaan antara pemeluk agama, Islam
telah menghilangkan prasangka kesukuan serta mengajarkan prinsip
persatuan bangsa dan persamaan umat manusia. Sebab manusia diciptakan oleh
Allah SWT dengan derajat yang sama dan hak-hak yang sama pula, yang
Toleransi dalam Keberagaman
membedakan di antara mereka dihadapan Allah adalah iman dan takwa mereka.
Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an:
Artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah
orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Mengenal" .
Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan
keadaan dan derajat yang sama, sedangkan yang membedakan di antara
mereka adalah takwa mereka kepada Allah SWT. Dengan demikian orang yang
paling bertakwalah yang mendapat tempat yang mulia di sisi Allah. Oleh sebab
itu sebagai mahluk ciptaan Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk
ciptaan Allah yang lain, manusia tidak seharusnya menunjukkan sikap fanatisme
golongan dan mengutamakan kepentingan pribadi tanpa melihat kepentingan
yang lebih besar, yaitu keutuhan dan kesatuan umat dan bangsa.
Fenomena-fenomena seperti inilah yang oleh Nabi Muhammad SAW
disebut sebagai sikap ashabiyah yang dianggap sebagai satu ciri kejahiliyahan .
Dengan ajaran tentang persatuan dan persamaan umat manusia, maka Rasullulah
juga amat mementingkan kerukunan dalam pergaulan dan kehidupan yaug
bersifat majemuk dalam masyarakat yang beranekaragam perbedaannya. Dalam
menciptakan kerukunan tersebut, Rasullulah mewujudkan dengan cara
mempersaudarakan kaum Muhajirin dari Mekkah dan kaum Anshor yang
merupakan penduduk asli dari Madinah. Sedangkan untuk menjalin kerukunan
dengan orang-orang non Muslim, Rasullulah membuat Piagam Madinah yang
tersohor itu, yang merupakan dasar dari hubungan dan kerjasama yang harmonis
antar umat Islam, ahli kitab dan suku-suku Arab yang belum memeluk Agama
Samawi. Piagam Madinah ini dibuat oleh nabi setelah nabi Hijrah dan tinggal di
Yastrib (Madinah), pada tahun 622 M. Menurut Hamidullah, piagam itu terdiri
dari Mukadimah, 10 Bab dan 47 pasal, yang mengandung 2 (dua) unsur yang
sangat penting, antara lain:
1. Mengatur hubungan antara sesama umat Islam, antara golongan
Toleransi dalam Keberagaman
Muhajirin yang datang dari Mekkah dan golongan Anshar yang menjadi
penduduk asli.
2. Mengatur perjanjin antara kaum Muslimin di satu pihak dengan kaum
Yahudi di pihak lain yang memuat pengakuan dan perlindungan terhadap
agama mereka.
Dengan Piagam Madinah ini tampak sebagai perjanjian segi tiga antar
Muhajirin dan Anshar serta golongan Yahudi. Dalam perjanjian ini menunjukkan
bahwa nabi Muhammad saw. berusaha untuk mendamaikan antar suku, yaitu
suku bangsa Arab di Madinah yakni antara umat Islam dengan umat yang
beragama dan berkepercayaan yang lain. Mereka (umat yang lain) diberikan
kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-
masing.
Dalam pelaksanaan toleransi antar umat beragama, Nabi Muhammad saw.
tidak hanya membuat perjanjian dengan golongan Yabudi saja, tetapi juga
dengan agama Kristen. Perjanjian Nabi Muhammad saw., dengan golongan
Kristen ini merupakan perjanjian yang pertama yang dibuat pada hari Senin akhir
tahun IV H ditandatangani oleh tiga puluh lima saksi. Adapun isi dari perjanjian
tersebut antara lain:
1. Bagi orang-orang Nasrani dan daerah sekitarnya diberikan keamanan
dari Tuhan dan janji RasulNya yang diluaskan kepada jiwa, agama dan harta
benda mereka, bagi sekalian yang hidup kini dan yang belum lahir di masa ini
dan orang-orang lainnya
2. Keyakinan agama dan menjalankan upacara.-upacara agama mereka tidak
akan dicampuri
3. Tidak akan ada perubahan di dalam hak-hak dan kesenangan mereka
4. Tidak seorang pun pendeta yang dicabut hak kependetaannya
5. Mereka semua akan tetap mendapat dan merasakan segala sesuatu, baik yang
besar maupun yang kecil seperti sedia kala
6. Tidak ada patung atau salib yang dihancurkan
7. Mereka tidak akan menindas dan ditindas
8. Mereka tidak lagi akan melakukan kebiasaan pembalasan darah secara
Toleransi dalam Keberagaman
jahiliyah
9. Pajak 10% tidak akan dipungut dari mereka, dan juga mereka tidak akan
diperintah menyediakan makanan untuk pasukan tentara.
Dilihat dari intisari perjanjian antara nabi Muhammad SAW dengan
"golongan Nasrani” ini, maka dapat diketahui bahwa perjanjian ini lebih
mengutamakan kepentingan golongan Nasrani dan kelihatan seperti berat
sebelah. Hak-hak golongan Nasrani lebih banyak daripada hak kaum muslimin,
tetapi meskipun begitu Rasul Allah SAW masih tetap menyetujuinya, demi
menjalin persatuan dan perdamaian.
Islam merupakan agama yang suka perdamaian, Islam melarang agresi,
sebab tujuan pokok dari Islam ialah menimbulkan dan memelihara perdamaian
dan ketertiban umum. Oleh karena itu Islam tetap mengasuh sikap tasamuh. Nabi
Muhammad dan para sahabat beliau, senantiasa memesankan kepada tentaranya
untuk tidak merusak rumah ibadah, seperti gereja dan sebagainya di negeri
yang mereka kuasai. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Nabi Muhammad
saw. selalu bersikap mengalah dalam menghadapi orang-orang yang tidak
menyukainya. Rasul Allah saw. tidak membalas kalau yang disakiti adalah
dirinya, tetapi beliau akan marah apabila ada orang yang menghina agamanya.
Sikap Nabi Muhammad saw. yang tenang ini telah dibuktikan pada waktu di
Mekkah, di saat beliau dan kaum Muslimin menjadi sasaran kekejaman musuh
dan hampir setiap hari secara terus-menerus selama 13 tahun. Namun beliau tidak
pernah melawan dan membalas agresi musuh itu. Oleh karena itu, untuk
mengakhirinya beliau beserta kaum Muslimin hijrah dari Mekkah ke Madinah.
Rasullulah tidak pernah ke Mekkah lagi dan baru ke Mekkah setelah mendapat
wahyu dari Allah untuk menjalankan Thawaf. Dalam menjalankan Thawaf ini
beliau dihalangi oleh kaum Kafir Mekkah, Nabi Muhammad saw. beserta
pengikutnya tidak boleh masuk ke Mekkah untuk menjalankan Thawaf. Tetapi
karena kaum Kafir Mekkah takut dimusuhi oleh kaum muslimin, maka kaum
Muslimin boleh melakukan Thawaf dan masuk ke Mekkah dengan melalui
perjanjian. Perjanjian ini dinamakan perjanjian Hudaibiyah. Isi perjanjian ini
Toleransi dalam Keberagaman
antara lain :
1. Kedua belah pihak tidak akan saling serang-menyerang selama 10 Tahun
Toleransi dalam Keberagaman
2. Tahun ini Muhammad beserta rombongan harus ke Madinah, tidak masuk
Mekkah, tahun belakang boleh datang ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan
umrah selama tiga hari, dan tidak boleh membawa senjata
3. Bila ada pihak ketiga, yakni dari kabilah-kabilah Arab yang ingin bergabung
dengan pihak Muhammad atau pihak Quraisy, dibebaskan untuk memilih
antara keduanya, dan bila terjadi peperangan antara kabilah-kabilah Arab,
pihak Muhammad dan pihak Quraisy tidak boleh membantu salah satunya,
hanya boleh melerai saja
4. Tidak ada orang Mekkah (dari pihak Quraisy) yang lari menggabungkan diri
ke Madinah (Muhammad), ia harus disuruh kembali ke Mekkah, dan
Muhammad bertanggung jawab atas itu. Tetapi sebaliknya bila ada pengikut
Muhammad yang lari ke Mekkah, kaum Quraisy tidak berkewajiban
mengembalikannya ke Madinah (Umar Hasyim, 1978 : 167-168).
Pada waktu perjanjian sedang berjalan, utusan kaum Quraisy bersikap
sangat congkak dan para sahabat susah payah untuk menahan diri agar tidak
terjadi keributan di antara mereka. Demikianlah bukti betapa besarnya jiwa
toleransi Nabi Muhammad saw., meskipun dimusuhi bagaimana pun tapi beliau
masih berusaha untuk tetap sabar. Kebesaran jiwa toleransi Nabi Muhammad
saw. terlihat juga pada sikapnya terhadap sejumlah orang (kurang lebih 12 orang)
terdiri dari 8 laki-laki dan 4 wanita yang telah dijatuhi hukuman mati dan
diperintahkan oleh nabi untuk dibunuh, karena kekejamannya atau sikap
permusuhannya yang melampaui batas kepada nabi. Tetapi akhirnya mereka
yang mau atau sempat menghadap nabi untuk memohon ampunan, Nabi
Muhammad saw. memaafkannya dengan penuh keikhlasan.
Praktik toleransi yang dilaksanakan oleh nabi yang sangat tinggi adalah
sikap beliau dan kaum muslimin terhadap tawanan perang, Rasul Allah saw.
memperlakukan mereka dengan penuh kemanusiaan, penuh kasih sayang, lemah-
lembut dan lapang dada. Nabi Muhammad saw. menawan musuh bukan untuk
dimusnahkan, tetapi tawanan justru untuk dibebaskan dengan persyaratan yang
cukup ringan bahkan ada di antara mereka yang dibebaskan tanpa syarat.
Sungguh suatu hal yang sangat terpuji betapa Nabi Muhammad saw. dan kaum
Toleransi dalam Keberagaman
muslimin memperlakukan para tawanan perang Badar dengan penuh kasih
sayang dan mereka dibebaskan dengan syarat yang cukup ringan bahkan sangat
ringan sampai ada yang dibebaskan tanpa syarat.
DAFTAR PUSTAKA
A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al Ikhlas, Surabaya, 1402 H.
Abdurrahman Wahid, Dialog Kritik dan Identitas Agama, Penerbit
Dian/lnterfidei, Cet I, Jakarta.
Ahmad Azhar Basyir, Refleksi atas Persoalan Ke-Islaman Seputar Filsafat
Hukum, Politik, Ekonomi, Penerbit Mizan, Cet I, Bandung, 1993.
Alamsyah Ratu Perwiranegara, Pembinaan Kerukunan Hidup Umat
Beragama, Departemen Agama RI., Jakarta, 1982.
Al-Khatib al-Baghdadi, Ahmad Ibn Ali, Tarikh Baghdad, Beirut Daar al-
Kutub al-‘Ilmiyah, 1417 H.
Al-Mubarakfurry, Shaffty al-Raman, Al-Rahiiq a-Makhtum, Riyadh, Maktabah
Daar al- Salam, 1412 H.
Badruddin Hsubky, KH, Bid’ah-Bid’ah di Indonesia, Gema Insani Pres, Cet II,
Jakarta, 1994.
Bey Arifin H., Hidup Sebelum Mati, CV Kinta, Cet III, Jakarta, 1992.
Burhanuddin Daya, Hubungan Antar Agama di Indonesia, Ulumul Qur’an, No.
4, Vol. IV, 1993.
BP-7, Undang-undang Dasar, Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila,
Garis- garis Besar Haluan Negara 1993.
Departemen Agama RI., Dinamika Kerukunan Hidup Baragama Di Daerah,
Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Depag RI, Jakarta,
1979/1980.
, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Mahkota, Surabaya, 1989.
, Hasil Musyawarah Antar Umat Beragama, Proyek Pembinaan
Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1982-1983.
, Hasil Musyawarah Antar Umat Beragama, Proyek Pembinaan
Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1982-1984.
, pekan Orientasi Antar Umat Beragama dengan Pemerintah,
Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, Jakarta, 1980-1981.
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Puataka, Cet II, Jakarta, 1989.
Hendropuspito, Sosiologi Agama, Kanisius, Cet VII, Yogyakarta, 1991.
Imam Munawir, Sikap Islam Terhadap Kekerasan Damai, Toleransi dan
Solidaritas, PT. Bina Ilmu, Cet I, Surabaya, 1984.
Jalalluddin Abdurrahman Abu Bakar As – Suyuti, Imam, Al Jami As-Shoghir,
juz II, Darul Fikri, Bairut, TT.
Jamin Roham, Abu, Tanya Jawab Populer Islam Kristen, Media Dakwah, Cet I,
Jakarta, 1993.
Toleransi dalam Keberagaman
Labib MZ. – Maftuh Ahnan, Toleransi Dalam Islam, CV. Bintang Pelajar, TT.
Lembaga Al Kitab Indonesia, Al Kitab, Lembaga Al Kitab Indonesia,
jakarta, 1992.
Masjfuk Zuhdi, Studi Islam, PT Raja Grafindo Persada, Jilid III, Cet II, Jakarta,
1993.
Munib – Hr. Sulistri, Memahami Kata dan Istilah Agama, Darussagaff,
Surabaya, 1985.
Nasrudin Rozak, Dinul Islam, PT. Al Ma’arif, Bandung, 1959.
Nazir Ph. P, Moh., Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
Quraish Shihab, M, Dr., Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Peranan Wahyu
Dalam Kehidupan Masyarakat), Mizan, Cet II, Bandung, 1992.
Rasjidi M. H., Mengapa Aku Tetap Memeluk Agama Islam, Bulan Bintang, Cet
IV, Jakarta, 1980.
Saparlan, Kerukunan Hidup Beragama dan Ketahanan Sosial (Seri Kewiraan),
Biro Penerbit dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN
Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 1990.
Sutrisno Hadi, Metodelogi Risearch, Penerbit Andi Offset, Jilid I, Cet. XXIV,
Yogyakarta, 1993.
Syamsudduha, Penyebaran dan Perkembangan Islam - Khatolik - Protestan
di Indonesia, Usaha Nasional, Cet II, Surabaya, 1987.
Umar Hasyim, Toleransi dan Kemerdekaan Beragama Dalam Islam Sebagai
Dasar Menuju Dialog dan Kerukunan Antar Agama, PT Bina Ilmu,
Surabaya, 1978.
W.J.S. Poerdwadarminta, Kamus umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka,
Cet VIII, Jakarta, 1985.
Toleransi dalam Keberagaman
MATERI
Model Toleransi Berbasis Pesantren
MODEL PENDIDIKAN TOLERANSI
DI PESANTREN MODERN DAN SALAF
Ali Maksum
Pendahuluan
Dalam konteks Indonesia, pendidikan toleransi, pendidikan yang dapat
mencetak peserta didik mempunyai kearifan lokal, atau menghasilkan peserta
didik yang berpandangan inklusif, penting untuk diwujudkan. Indonesia,
melebihi kebanyakan negara-negara lain, merupakan negara yang tidak saja
multisuku, etnik dan agama, tetapi juga multibudaya. Kemajemukan tersebut
pada satu sisi merupakan kekuatan sosial dan keragaman yang indah apabila satu
sama lain bersinergi dan saling bekerja sama untuk membangun bangsa. Namun,
pada sisi lain, kemajemukan tersebut apabila tidak dikelola dan dibina dengan
tepat dan baik akan menjadi pemicu dan penyulut konflik dan kekerasan yang
dapat menggoyahkan sendi- sendi kehidupan berbangsa. Peristiwa Ambon dan
Poso, misalnya, merupakan contoh kekerasan dan konflik horizontal yang telah
menguras energi dan merugikan tidak saja jiwa dan materi tetapi juga
mengorbankan keharmonisan antar sesama masyarakat Indonesia.
Semenjak reformasi digulirkan, diskursus pluralisme dan
multikulturalisme di negeri ini terus mengemuka dan berkembang pesat. Terkait
dengan masalah tersebut sikap hidup toleran menjadi penting. Toleransi
dipandang bisa menjadi perekat baru integrasi bangsa yang sekian lama tercabik-
cabik. Integrasi nasional yang selama ini dibangun berdasarkan politik
kebudayaan lebih cenderung seragam dianggap tidak lagi relevan dengan kondisi
dan semangat demokrasi global. Desentralisasi kekuasaan dalam bentuk otonomi
daerah semenjak 1999 adalah jawaban bagi tuntutan demokrasi tersebut. Namun,
desentralisasi sebagai keputusan politik nasional ternyata kemudian disadari tidak
begitu produktif apabila dilihat dari kacamata integrasi nasional suatu bangsa
besar yang isinya beraneka ragam suku bangsa, etnis, agama, dan status sosial.
Toleransi dalam Keberagaman
Berbicara tentang pendidikan Islam, pesantren merupakan jenis institusi
pendidikan Islam tertua dan telah lama berakar di dalam budaya masyarakat
Indonesia. Pesantren merupakan pusat pengkajian dan pendalaman khazanah
ilmu-ilmu keislaman dan sekaligus sebagai pusat gerakan dakwah penyebaran
agama Islam di masyarakat. Pesantren juga dikenal sebagai penjaga ortodoksi
Islam. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang unik, tidak saja
karena keberadaannya yang sudah sangat lama, tetapi juga karena kultur, metode,
dan jaringan yang diterapkan oleh lembaga agama tersebut. Selain itu pondok
pesantren juga sebagai sistem pendidikan yang asli (indegenious) di Indonesia.
Penelitian ini berhasil mengetahui dua hal pokok: (1) Sistem pendidikan
di Pesantren Modern Gontor Ponorogo dan Pesantren Salaf Tebuireng Jombang;
(2) Pelaksanaan pembelajaran toleransi di pesantren modern Gontor Ponorogo
dan pesantren salaf Tebuireng Jombang. Penelitian ini tidak hanya menghasilkan
pengetahuan deskriptif dan fenomenologis, tetapi memberikan kontribusi
akademis berupa peningkatan pengetahuan perilaku inklusif, demokratis, dan
toleran. Di samping itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi usaha-
usaha untuk melakukan pendidikan inklusif dan demokratis di lembaga
pendidikan pondok pesantren.
Tipologi Pesantren
Secara etimologis, “pesantren” berasal dari pe-santri-an yang berarti
tempat santri; asrama tempat santri belajar agama; atau pondok. Dikatakan pula,
pesantren berasal dari kata santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam,
dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul
untuk belajar agama Islam.
Sementara itu, secara terminologis, pondok pesantren merupakan institusi
sosial keagamaan yang menjadi wahana pendidikan bagi umat Islam yang ingin
mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Pondok pesantren dalam terminologi
keagamaan merupakan institusi pendidikan Islam, namun demikian pesantren
mempunyai icon sosial yang memiliki pranata sosial di masyarakat. Hal ini
Toleransi dalam Keberagaman
karena pondok pesantren memiliki modalitas sosial yang khas, yaitu: 1)
ketokohan kyai, 2) santri, 3) independent dan mandiri, dan 4) jaringan sosial yang
kuat antar alumni pondok pesantren.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam pesantren adalah pengajaran dan
pendidikan Islam. Hal ini menuntut kualitas seorang kyai tidak sekedar sebagai
seorang ahli tentang pengetahuan keislaman yang mumpuni, tetapi juga sebagai
seorang tokoh panutan untuk diteladani dan diikuti. Melalui kegiatan ajar-belajar,
seorang kyai mengajarkan pengetahuan keislaman tradisional kepada para
santrinya yang akan meneruskan proses penyebaran Islam tradidional.
Para ahli pendidikan, mengklasifikasi jenis pesantren kedalam dua
tipologi; yakni pesantren modern, yang sudah banyak mengadopsi sistem
pendidikan sekolah modern Barat dan pesantren salaf, yang berorientasi pada
pelestarian tradisi dengan sistem pendidikan tradisional.
Pertama, Pondok pesantren modern, merupakan pengembangan tipe
pesantren karena orientasi belajarnya cenderung mengadopsi seluruh sistem
belajar secara klasik dan meninggalkan sistem belajar tradisional. Penerapan
sistem belajar modern ini terutama nampak pada penggunaan kelas-kelas
belajar baik dalam bentuk madrasah maupun sekolah. Kurikulum yang dipakai
adalah kurikulum sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Santrinya
ada yang menetap ada yang tersebar di sekitar desa lokasi pesantren. Kedudukan
para kyai sebagai koordinator pelaksana proses belajar mengajar dan sebagai
pengajar langsung di kelas. Perbedaannya dengan sekolah dan madrasah
terletak pada porsi pendidikan agama dan bahasa Arab lebih menonjol sebagai
kurikulum lokal.
Kedua, pesantren Salaf. Menurut Zamakhsyari Dhofier, ada beberapa ciri
pesantren salaf atau tradisional, terutama dalam hal sistem pengajaran dan materi
yang diajarkan. Pengajaran kitab- kitab Islam klasik atau sering disebut
dengan kitab kuning karena kertasnya berwarna kuning, terutama karangan-
karangan ulama yang menganut faham Syafi‟iyah, merupakan pengajaran formal
yang diberikan dalam lingkungan pesantren tradisional. Keseluruhan kitab-kitab
klasik yang diajarkan di pesantren dapat digolongkan ke dalam delapan
Toleransi dalam Keberagaman
kelompok, yaitu nahwu (syntax) dan shorof (morfologi), fiqh, usul fiqh,
hadis, tafsir, tauhid, tasawuf dan etika, dan cabang-cabang lain seperti tarikh
dan balaghah.
Sistem Pendidikan Pesantren
Secara umum Pondok Pesantren didefinisikan sebagai lembaga pendidikan
yang memiliki lima elemen pokok; (1) Pondok/Asrama: adalah tempat tinggal
bagi para santri. Pondok inilah yang menjadi ciri khas dan tradisi pondok
pesantren dan membedakannya dengan sistem pendidikan lain yang
berkembang di Indonesia, (2) Masjid: Merupakan tempat untuk mendidik para
santri terutama dalam praktik seperti shalat, pengajian kitab klasik, pengkaderan
kyai, dan lain-lain, (3) Pengajaran kitab-kitab klasik: Merupakan tujuan
utama pendidikan di pondok pesantren, (4) Santri: Merupakan sebutan untuk
siswa/murid yang belajar di pondok pesantren, dan (5) Kyai: merupakan
pimpinan pondok pesantren. Kata kyai sendiri adalah gelar yang diberikan
masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang menjadi pimpinan pesantren
dan mengajarkan kitab-kitab klasik.
Kegiatan utama yang dilakukan dalam pesantren adalah pengajaran dan
pendidikan Islam. Hal ini menuntut kualitas seorang kyai tidak sekedar sebagai
seoarang ahli tentang pengetahuan keislaman yang mumpuni, tetapi juga sebagai
seorang tokoh panutan untuk diteladani dan diikuti. Melalui kegiatan ajar-belajar,
seorang kyai mengajarkan pengetahuan keislaman tradisional kepada para
santrinya yang akan meneruskan proses penyebaran Islam tradisional. Di dalam
pesantren proses pendidikan dan pengajaran bisa berlangsung dalam dua
bentuk: sistem klasikal dan berjenjang dan sistem tradisional, seperti sorogan,
wetonan, dan bandongan. Menurut Mustofa Bisri di samping ciri lahiriah
tersebut, masih ada cirri umum yang menandai karakteristik pesantren, yaitu
kemandirian dan ketaatan santri kepada kyai yang sering diinisiasi sebagai
pengkultusan. Meski mempunyai tipologi umum yang sama, pesantren juga
sangat ditentukan karakternya oleh kyai yang memimpinnya. Sebagai pendiri dan
“pemilik‟ pesantren (terutama pesantren salaf) dalam menentukan corak
Toleransi dalam Keberagaman
pesantrennya, pastilah tidak terlepas dari karakter dan kecenderungan pribadinya.
Islam dan Toleransi Beragama
Al-Qur’an menjelaskan bahwa pluralitas adalah salah satu kenyataan
objektif komunitas umat manusia, sejenis hukum Allah atau Sunnah Allah, dan
bahwa hanya Allah yang tahu dan dapat menjelaskan, di hari akhir nanti,
mengapa manusia berbeda satu dari yang lain, dan mengapa jalan manusia
berbeda-beda dalam beragama. Dalam al-Qur’an disebutkan, yang artinya:
“Untuk masing-masing dari kamu (umat manusia) telah kami tetapkan Hukum
(Syari’ah) dan jalan hidup (minhaj). Jika Tuhan menghendaki, maka tentulah
Dia jadikan kamu sekalian umat yang tunggal (monolitik). Namun Dia jadikan
kamu sekalian berkenaan dengan hal-hal yang telah dikaruniakan kepada kamu.
Maka berlombalah kamu sekalian untuk berbagai kebajikan. Kepada Allah-lah
tempat kalian semua kembali; maka Dia akan menjelaskan kepadamu sekalian
tentang perkara yang pernah kamu perselisihkan” (QS. 5: 48).
Dalam kaitan langsung dengan prinsip inilah Allah, di dalam Alquran,
menegur keras Nabi Muhammad saw. ketika dia menunjukkan keinginan dan
kesediaan yang menggebu untuk memaksa manusia menerima dan mengikuti
ajaran yang disampaikanya, sebagai berikut: “Jika Tuhanmu menghendaki, maka
tentunya manusia yang ada di muka bumi ini akan beriman. Maka apakah kamu
hendak memaksa manusia, di luar kesediaan mereka sendiri? (QS. 10: 99).
Demikianlah beberapa prinsip dasar al-Qur’an yang berkaitan
dengan masalah pluralisme dan toleransi. Paling tidak, dalan dataran
konseptual, al-Qur’an telah memberi resep atau arahan-arahan yang sangat
diperlukan bagi manusia Muslim untuk memecahkan masalah kemanusiaan
universal, yaitu realitas pluralitas keberagamaan manusia dan menuntut supaya
bersikap toleransi terhadap kenyataan tersebut demi tercapainya perdamaian di
muka bumi. Karena Islam menilai bahwa syarat untuk membuat keharmonisan
adalah pengakuan terhadap komponen-komponen yang secara alamiah berbeda.
Selain itu, era sekarang adalah era multikulturalisme dan pluralisme, yang
dimana seluruh masyarakat dengan segala unsurnya dituntut untuk saling
tergantung dan menanggung nasib secara bersama-sama demi terciptanya
Toleransi dalam Keberagaman
perdamaian abadi. Salah satu bagian penting dari konsekuensi tata kehidupan
global yang ditandai kemajemukan etnis, budaya, dan agama tersebut, adalah
membangun dan menumbuhkan kembali teologi pluralisme dalam masyarakat.
Demi tujuan itu, maka pendidikan sebenarnya masih dianggap sebagai
instrumen penting. Sebab, “pendidikan” sampai sekarang masih diyakini
mempunyai peran besar dalam membentuk karakter individu-individu yang
dididiknya, dan mampu menjadi “guiding light” bagi generasi muda penerus
bangsa. Dalam konteks inilah, pendidikan agama sebagai media penyadaran umat
perlu membangun teologi inklusif dan pluralis, demi harmonisasi agama-agama
(yang telah menjadi kebutuhan masyarakat agama sekarang).
Apalagi, kalau mencermati pernyataan yang telah disampaikan oleh Alex
R. Rodger (1982) bahwa “pendidikan agama merupakan bagian integral dari
pendidikan pada umumnya dan berfungsi untuk membantu perkembangan
pengertian yang dibutuhkan bagi orang-orang yang berbeda iman, sekaligus
juga untuk memperkuat ortodoksi keimanan bagi mereka”. Artinya pendidikan
agama adalah sebagai wahana untuk mengeksplorasi sifat dasar keyakinan agama
di dalam proses pendidikan dan secara khusus mempertanyakan adanya bagian
dari pendidikan keimanan dalam masyarakat. Pendidikan agama dengan begitu,
seharusnya mampu merefleksikan persoalan pluralisme, dengan mentransmisikan
nilai-nilai yang dapat menumbuhkan sikap toleran, terbuka dan kebebasan dalam
diri generasi muda.
Melalui pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam berbasis
kemajemukan dengan mempertimbangkan pengembangan komponen, bahan,
metode, peserta didik, media, lingkungan, dan sumber belajar. Maksud dan
tujuan pendidikan pluralisme-multikulturalisme, dengan begitu akan dapat
dijadikan sebagai jawaban atau solusi alternatif bagi keinginan untuk merespon
persoalan-persoalan di atas. Sebab dalam pendidikannya, pemahaman Islam
yang hendak dikembangkan oleh pendidikan berbasis pluralisme-
multikulturalisme adalah pemahaman dan pemikiran yang bersifat inklusif.
Toleransi dalam Keberagaman
Pendidikan dan Toleransi
Relasi harmonis antar-umat beragama seringkali menuai masalah tatkala
masing-masing pihak bersikukuh dengan kebenaran agama yang dianutnya,
dengan memaksakan agamanya kepada yang lain. Dalam konteks ini, Islam
melalui al-Qur’an dengan tegas menolak setiap orang beriman untuk
memaksakan agamanya kepada orang lain. Bahkan, al-Qur’an menjamin
kebebasan beragama kepada manusia. Sebagaimana diungkapkan dalam firman
Allah SWT: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu,
barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka
sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang
tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (Q.S. Al-
Baqarah: 256).
Orang beriman juga harus mampu menahan diri untuk tidak
melakukan kekerasan, misalnya, memaksakan iman kepada orang lain dengan
paksaan fisik, atau dengan paksaan lain, seperti tekanan sosial, bujukan harta
benda atau kedudukan, atau cara- cara lain yang bersifat politis dan tidak
berkeadilan/berkeadaban. Mereka harus berusaha dengan jalan ruhani, dan
biarlah Tuhan yang menentukan sesuai dengan kehendak-Nya (Abdullah Yusuf
Ali, Jilid I: 510). Untuk itu, sikap toleran dan tidak boleh ada paksaan dalam
beragama meniscayakan penyebaran agama secara santun dan sopan. Mengajak
orang untuk beragama, baik kepada orang yang seagama maupun kepada orang
yang berlainan agama, harus dilakukan dengan sebaik-baiknya ajakan dan penuh
hikmah (Q.S. Al-Nahl/16: 125).
Bahkan, al-Qur’an secara tegas melarang umat beragama berbantah-
bantahan mengenai Tuhan (Allah) dengan para penganut kitab suci lain karena,
para penganut kitab suci itu meski berbeda-beda tetapi sesungguhnya mereka
menyembah Allah yang Maha Esa. Allah SWT menegaskan itu dalam firman-
Nya: Artinya: “Apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah,
padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu; bagi kami amalan kami, bagi
Toleransi dalam Keberagaman
kamu amalan kamu dan hanya kepada-Nya kami mengikhlaskan hati” (Q.S. Al-
Baqarah: 139).
Shihab menafsirkan bahwa ayat ini menunjukkan tidak diperkenankannya
para pemeluk agama untuk mengklaim dirinya paling benar. Ayat ini tidak
memersalahkan siapa-siapa, dan tidak juga mengklaim kebenaran untuk siapa-
siapa. Oleh karena itu, cara berpikir umat-beragama yang biasanya hitam putih:
agama kitalah yang benar, yang absah, dan satu-satunya jalan keselamatan dari
Tuhan; agama lain adalah salah, palsu, menyesatkan, dan masuk neraka,
haruslah ditampik. Sebab, ketika perang klaim kebenaran (truth claim) dan
janji keselamatan dicuatkan, maka tidak saja meletupkan keberagamaan yang
eksklusif, tapi juga akan melahirkan suasana saling curiga -dalam sebagian kasus
menjadi konflik kekerasan-antar-umat beragama atas nama Tuhan.
Pendidikan formal mempunyai tugas untuk mempertahankan nilai-nilai
dan budaya nusantara dari derasnya perkembangan teknologi dari Negara-Negara
maju. Artinya, pendidikan kita harus tetap mempertahankan tradisi akademik
yang kokoh. Yang merupakan bukti eksistensinya terjaga dalam menjaga
keaslian iklim akademik. Pendidikan harus tetap menjaga dan melestarikan
lima aspek dalam membentuk peserta didik (Rusli, 1985: 129), yaitu, 1) dimensi
intelektual; 2) dimensi kultural; 3) dimensi nilai-nilai transendental; 4) dimensi
keterampilan fisik/jasmani; 5) dimensi pembinaan kepribadian manusia sendiri.
Kenyataannya, lembaga pendidikan sering mengabaikan kelima aspek
di atas, pada akhirnya menyebabkan hilangnya peran proses persemaian nilai-
nilai dan budaya kesantunan dan religiusitas yang inklusif. Upaya menciptakan
dinamika peradaban manusia yang berbasis ragam merupakan keniscayaan bagi
suatu negara berkembang. Arah pengembangannya tidak boleh kontra produktif
dengan nilai-nilai dasar keagamaan dan budaya Timur. Kehidupan masyarakat
mengutamakan gaya hidup bebas dan budaya pesta. Hal ini agar tidak terjadi
krisis intelektual dan moral manusia. Apalagi kehidupan global, langsung
maupun tidak langsung, berpengaruh terhadap nilai- nilai kehidupan masyarakat
maupun bangsa. Pendidikan merupakan cagar budaya dan sistem sosial
berpengaruh membentuk kepribadian dan interaksi sosialnya.
Toleransi dalam Keberagaman
Pendidikan toleransi, dalam perspektif Islam, tidak dapat dilepaskan
dengan konsep pluralitas, sehingga muncul istilah Pendidikan Islam Pluralis-
Multikultural. Konstruksi pendidikan semacam ini berorientasi pada proses
penyadaran yang berwawasan pluralitas secara agama, sekaligus berwawasan
multikultural. Dalam kerangka yang lebih jauh, konstruksi pendidikan Islam
pluralis-multikultural dapat diposisikan sebagai bagian dari upaya secara
komprehensif dan sistematis untuk mencegah dan menanggulangi konflik etnis
agama, radikalisme agama, separatisme, dan integrasi bangsa. Nilai dasar dari
konsep pendidikan ini adalah toleransi.
Islam inklusif adalah paham keberagamaan yang didasarkan pada
pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai yang
mengandung kebenaran dan dapat memberikan manfaat serta keselamatan bagi
penganutnya. Di samping itu, ia tidak semata-mata menunjukkan pada kenyataan
tentang adanya kemajemukan, melainkan keterlibatan aktif terhadap kenyataan
kemajemukan. Sebaliknya, eksklusif merupakan sikap yang memandang
bahwa keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip diri sendirilah yang paling
benar, sementara keyakinan, pandangan, pikiran, dan prinsip yang dianut
orang lain adalah salah, sesat, dan harus dijauhi.
Masyarakat Islam tradisional identik dengan masyarakat NU
(Nahdlatul Ulama) yang tentu saja tidak dapat dilepaskan dari pesantren ”salaf”
sebagai rujukan praktik beragama. Sikap golongan Islam tradisional yang
diwakili NU, pada dasarnya tidak terlepas dari akidah Ahlusunnah waljama'ah
(Aswaja) yang dapat disebut paham moderat.14 Pemikiran Aswaja sangat
toleransi terhadap pluralisme pemikiran. Berbagai pikiran yang tumbuh dalam
masyarakat muslim mendapatkan pengakuan yang apresiatif. Dalam hal ini
Aswaja sangat responsif terhadap hasil pemikiran berbagai madzhab, bukan saja
yang masih eksis di tengah-tengah masyarakat (Madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,
dan Hanbali), melainkan juga terhadap madzhab-madzhab yang pernah lahir,
seperti imam Daud al-Zhahiri, Imam Abdurrahman al-Auza’i, Imam Sufyan al-
Tsauri, dan lain-lain.
Toleransi dalam Keberagaman
Sistem Pendidikan di Pesantren Modern dan Salaf
Pesantren Gontor terkenal sebagai pesantren modern pertama di
Indonesia. Ciri khas pesantren modern berupaya memadukan tradisionalitas
dan modernitas pendidikan. Sistem pengajaran formal ala klasikal (pengajaran
di dalam kelas) dan kurikulum terpadu diadopsi dengan penyesuaian tertentu.
Dikotomi ilmu agama dan umum juga dieliminasi. Kedua bidang ilmu ini sama-
sama diajarkan, namun dengan proporsi pendidikan agama lebih mendominasi.
Sistem pendidikan yang digunakan di pondok modern dinamakan sistem
Mu’allimin. Dalam konteks ini di pesantren Gontor terkenal dengan nama
Kulliyatul-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI).
KMI membagi pendidikan formalnya dalam perjenjangan yang sudah
diterapkan sejak tahun 1936. KMI memiliki program reguler dan program
intensif.
a. Program reguler untuk lulusan Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah
(MI) dengan masa belajar hingga enam tahun. Kelas I-III setingkat dengan
pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah
(MTs) jika mengacu pada kurikulum nasional dan kelas IV-VI setara dengan
Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah (MA).
b. Program intensif KMI untuk lulusan SMP / MTs yang ditempuh dalam 4
tahun.
c. Untuk Perguruan Tinggi, pesantren Gontor pada tanggal 17 Nopember
1963 mendirikan PT dengan nama Perguruan Tinggi Darussalam (PTD).
Nama PTD ini kemudian berganti menjadi Institut Pendidikan Darussalam
(IPD) yang selanjutnya berganti menjadi Institut Studi Islam Darussalam
(ISID). Sejak tahun 1996 ISID telah memiliki kampus tersendiri di
Demangan, Siman, Ponorogo.
Selain jenjang program pendidikan di atas, pesantren modern
Gontor juga mempunyai sistem pendidikan yang excellent untuk menjaga
mutu pendidikannya, yaitu:
Toleransi dalam Keberagaman
a. Bahasa Arab dan bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa pergaulan dan
bahasa pengantar pendidikan, kecuali mata pelajaran tertentu yang harus
disampaikan dengan Bahasa Indonesia. Bahasa Arab dimaksudkan agar santri
memiliki dasar kuat untuk belajar agama mengingat dasar-dasar hukum Islam
ditulis dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris merupakan alat untuk mempelajari
ilmu pengetahuan / umum.
b. Pengasuhan santri adalah bidang yang menangani kegiatan
ekstrakurikuler dan kurikuler. Setiap siswa wajib untuk menjadi guru untuk
kegiatan pengasuhan pada saat kelas V dan VI jika ingin melanjutkan ke
jenjang perguruan tinggi di ISID, mereka tidak akan dipungut biaya, tetapi
wajib mengajar kelas I-VI di luar jam kuliah. Mengajar kuliah dan membantu
pondok itulah yang di lakukan sebagai bentuk pengabdian dan pengembangan
diri.
c. Pelatihan tambahan bagi guru dengan materi yang sesuai dengan standar
pendidikan nasional.
d. Keterampilan, kesenian, Kepramukaan dan olahraga tidak masuk kedalam
kurikulum tetapi menjadi aktivitas ekstrakurikuler.
e. Siswa diajarkan untuk bersosialisasi dengan membentuk masyarakat sendiri
di dalam pondok, melalui organ organisasi. Mulai dari ketua asrama, ketua
kelas, ketua kelompok, organisasi intra/ ekstra, hingga ketua regu
pramuka. Sedikitnya ada 1.500 jabatan ketua yang selalu berputar setiap
pertengahan tahun atau setiap tahun.
Sementara itu, pondok pesantren Tebuireng telah beberapa kali
melakukan perubahan kebijaksanaan yang berkaitan dengan pendidikan.
Sebagaimana umumnya pesantren, sistem pengajaran yang digunakan adalah
metode sorogan (santri membaca sendiri materi pelajaran kitab kuning di
hadapan guru), metode wetonan atau bandongan ataupun halaqah (kyai
membaca kitab dan santri memberi makna). Semua bentuk pengajaran tidak
dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan tingkat pendidikan dinyatakan
dengan bergantinya kitab yang khatam (selesai) dikaji dan diikuti santri.
Materi pelajarannya pun khusus berkisar tentang pengetahuan agama Islam, ilmu
Toleransi dalam Keberagaman
syari’at dan bahasa Arab. Inilah sesungguhnya misi utama berdirinya pondok
pesantren.
Perubahan sistem pendidikan di pesantren ini pertama kali diadakan Kyai
Hasyim Asy’ari pada tahun 1919 M. yakni dengan penerapan sistem madrasi
(klasikal) dengan mendirikan Madrasah Salafiyah Syafi’iyah. Sistem pengajaran
disajikan secara berjenjang dalam dua tingkat, yakni Shifir Awal dan Shifir
Tsani.
Hingga pada tahun 1929 M. kembali dirintis pembaharuan, yakni dengan
dimasukkannya pelajaran umum ke dalam struktur kurikulum pengajaran. Satu
bentuk yang belum pernah ditempuh oleh pesantren manapun pada waktu itu.
Dalam perjalanan penyelenggaraan madrasah ini berjalan lancar. Namun
demikian bukan tidak ada tantangan, karena sempat muncul reaksi dari para
wali santri –bahkan– para ulama’ dari pesantren lain. Hal demikian dapat
dimaklumi mengingat pelajaran umum saat itu dianggap sebagai kemunkaran,
budaya Belanda dan semacamnya. Hingga banyak wali santri yang
memindahkan putranya ke pondok lain. Namun madrasah ini berjalan terus,
karena disadari bahwa ini pada saatnya nanti ilmu umum akan sangat diperlukan
bagi para lulusan pesantren.
Kini, pondok Pesantren Tebuireng telah berumur lebih dari 1 abad.
Dinamika pun menyertainya seiring dengan perjalanan pesantren ini, dari
pergantian kepemimpinan (pengasuh), kebijakan, pembangunan sarana prasarana,
jumlah santri, dan sampai sistem pendidikan. Saat ini santri Tebuireng mencapai
kurang lebih 2000 orang yang berasal dari berbagai daerah, baik Jawa maupun
luar Jawa. Hanya saja, santri yang berasal dari Jawa lebih banyak dibanding luar
Jawa yang kira-kira hanya lima pesennya.
Pondok Pesantren Tebuireng yang pada awal berdirinya adalah
bertipe salaf, dalam dinamikanya dan untuk sekarang ini tidak lagi dapat disebut
dengan Pondok Pesantren Salaf sama sekali. Akan tetapi, pesantren ini di
samping masih mempertahankan sistem pendidikan salaf, dengan mengikuti
perkembangan zaman, menerapkan juga sistem pendidikan modern. Oleh karena
itu, untuk sekarang ini lebih tepat apabila menyebut Pondok Pesantren Tebuireng
Toleransi dalam Keberagaman
dengan sebutan Pondok Pesantren Campuran atau Pondok Pesantren Terpadu
(antara khalaf dan salaf).
Sistem campuran ini dapat dilihat, misalnya untuk yang salaf, model
pengajaran dengan sistem sorogan dan bandongan masih diterapkan, demikian
pula dengan masih adanya pengajaran terhadap kitab-kitab kuning (kitab salaf).
Sementara itu, sistem khalaf atau modern dapat dilihat bahwa Pondok Pesantren
Tebuireng telah menerapkan sistem klasikal (berkelas- kelas atau berjenjang) dan
bentuk pendidikan madrasah (sekolah modern). Sistem modern dapat dilihat
pula dari segi kurikulumnya (mengadopsi Depag dan Diknas) yang disediakan
atau metode pengajarannya.
Adapun jenjang-jenjang pendidikan umum yang ada di dalam pesantren
Tebuireng sebagai berikut: a). Madrasah Tsanawiyah Salafiyah Syafi’iyyah; b).
Madrasah Aliyah Salafiyah Syafi’iyyah; c). SMP A. Wahid Hasyim (Sekolah
Standar Nasional); d). SMA A. Wahid Hasyim; e). Madrasah Muallimin; dan f).
Ma’had ‘Aly.
Model Pendidikan Toleransi di Pesantren Modern dan Salaf
Dalam konteks pondok modern Gontor, pendidikan berwawasan toleransi
sesungguhnya telah menjadi pendidikan dasar yang tidak hanya diajarkan dalam
pengajar formal di kelas saja. Tapi juga dilakukan dalam kehidupan sehari-hari
santri. Pendidikan formal toleransi diwujudkan dalam bentuk pengajaran
materi keindonesiaan / kewarganegaraan yang telah dikurikulumkan. Sistem
pengajaran di pondok modern yang didominasi bahasa asing (Arab dan Inggris)
sebagai pengantar, tidak melunturkan semangat pendidikan toleransi anak didik
(santri). Karena materi ini ditempatkan sebagai materi primer dan harus
diajarkan dengan medium bahasa Indonesia pula.
Dalam bidang non formal, pesantren dengan kelebihan pendidikan
intens 24 jamnya, memiliki banyak waktu untuk menyisipkan aneka pendidikan.
Salah satunya wawasan toleransi. Pola umum yang nyaris diberlakukan di
berbagai pondok modern adalah sistem pendidikan toleransi dan multikultur yang
menyatu dalam aturan dan disiplin pondok. Salah satunya dalam urusan
Toleransi dalam Keberagaman
penempatan pemondokan (asrama) santri. Di pondok modern, tidak diberlakukan
penempatan permanen santri di sebuah asrama. Dalam arti, seluruh santri harus
mengalami perpindahan sistematis ke asrama lain, guna menumbuhkan jiwa
sosial mereka terhadap keragaman.
Dalam hal ini Amir Maliki, seorang alumni pesantren Gontor
mengatakan bahwa:
“ .... Untuk menumbuhkan sikap toleransi dan pemahaman terhadap
budaya lain, dalam satu kamar ditempatkan para santri yang berasal dari
berbagai daerah, baik Jawa, luar Jawa, dan bahkan santri dari luar negeri.
Penempatan santri dalam satu kamar ini tidak permanen. Pondok Modern
Gontor menetapkan regulasi agar setiap tahun santri diharuskan
mengalami perpindahan asrama. Setiap satu semester mereka juga akan
mengalami perpindahan antarkamar dalam asrama yang mereka huni. Hal
ini ditujukan untuk memberi variasi kehidupan bagi para santri, juga
menuntun mereka memperluas pergaulan dan membuka wawasan mereka
terhadap aneka tradisi dan budaya santri-santri lainnya. Penempatan santri
tidak didasarkan pada daerah asal atau suku. Bahkan, penempatan
telah diatur sedemikian rupa oleh pengasuh pondok, dan secara maksimal
diupayakan kecilnya kemungkinan santri-santri dari daerah tertentu
menempati sebuah kamar yang sama. Dengan demikian antara santri tidak
berpikir primordial dan hanya mengenal teman- temannya yang satu
daerah saja. Dengan sistem ini para santri mempunyai wawasan
multikultural dan toleransi melalui pengalaman nyata sehari-hari.”
Ketentuan yang diberlakukan, satu kamar maksimal tidak boleh dihuni
oleh tiga orang lebih santri asal satu daerah. Menurut Dr. KH Abdullah
Syukri Zarkasyi, upaya ini untuk melebur semangat kedaerahan mereka ke
dalam semangat yang lebih universal. Di samping itu, agar santri juga dapat
belajar kehidupan bermasyarakat yang lebih luas, berskala nasional, bahkan
internasional bersama para santri mancanegara. Namun, penerapan pola
pendidikan ini, menurut Syukri Zarkasyi, tidak berarti menafikan unsur daerah.
Karena unsur kedaerahan telah diakomodir dalam kegiatan daerah yang disebut
“konsulat”, yang ketentuan organisasi dan kegiatannya telah diatur, khususnya
untuk diarahkan menolaknya menjadi sumber fanatisme kedaerahan.
Pendidikan toleransi lainnya dalam intensitas pendidikan pondok modern
adalah diberlakukannya aturan mengikat yang melarang santri berbicara
menggunakan bahasa daerah. Selain bahasa utama Arab dan Inggris, ketika
Toleransi dalam Keberagaman
masuk lingkungan pondok santri hanya dibolehkan berbicara bahasa Indonesia
dalam beberapa kesempatan dan kepentingan. Pendisiplinan santri dalam
pendidikan multikulturalisme lewat bahasa ini sangat ketat. Bagi santri yang
melanggarnya akan diberi hukuman bervariasi yang edukatif. Pendidikan
toleransi atas perbedaan juga kental diajarkan dalam sistem pendidikan pondok
modern. Keberagaman pemikiran dan ijtihad diajarkan kepada santri tanpa
pemaksaan, atau mengajarkan mereka untuk memaksakan ide. Sikap toleransi
terhadap perbedaan pendapat sangat diunggulkan sistem pendidikan pondok
modern.
Dengan sistem Mu’allimin yang didukung intensitas pendidikan 24 jam,
beban pengejawantahan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), seperti
disyaratkan dalam pendidikan formal, dapat dilalui pondok modern. Pada
KBK, kendala utamanya adalah keterbatasan waktu ajar untuk memberi
pemahaman penuh sebuah materi kepada siswa. Dengan sistem Mu’allimin, masa
pendidikan luar kelas di pondok pesantren cenderung lebih banyak dibanding
waktu formal pembelajaran di dalam kelas.
Keterbatasan masa pengajaran di kelas ini pun dapat tertanggulangi
pondok pesantren dengan adanya banyak waktu luang yang dapat dimanfaatkan
para guru untuk melengkapi pengajaran kepada santri. Pola ini sangat
mengefisiensikan waktu dan membuat pengajaran menjadi efektif. Ditambah lagi
dengan arus utama sistem pendidikan di pondok modern yang tidak mengenal
dikotomi pendidikan ekstrakulikuler dan intrakulikuler.
Keutamaan pendidikan toleransi di pondok modern juga tercermin
dari muatan/isi kurikulum yang kentara mengajarkan wawasan santri akan
keragaman keyakinan. Dalam kelompok bidang studi Dirasah Islamiyah, sebagai
contoh, diajarkan materi khusus Muqaranat al-Adyan (Perbandingan Agama)
yang konten luasnya memaparkan sejarah, doktrin, isme, fenomena dan dinamika
keagamaan di dunia. Materi ini sangat substansial dalam pendidikan
multikulturalisme, karena santri diberi wawasan berbagai perbedaan
mendasar keyakinan agama mereka (Islam) dengan agama-agama lain di
dunia. Materi ini sangat potensial membangun kesadaran toleransi keragaman
Toleransi dalam Keberagaman
keyakinan yang akan para santri temui saat hidup bermasyarakat kelak.
Dalam pendidikan sikap multikulturalistik, pondok modern menerapkan
pemberian wawasan rutin melalui visualisasi aneka kultur dan budaya para
santrinya. Setiap tahun ajaran baru digelar seremoni besar Khutbatul ‘Arsy
dengan salah satu materi acara berupa pertunjukan aneka kreasi dan kreativitas
pelangi budaya semua elemen santri, berdasarkan kategori “konsulat”
(kedaerahan). Dalam acara ini dilombakan demontrasi keunikan khazanah dan
budaya tempat domisili asal santri. Semua santri diwajibkan terlibat dalam
kegiatan ini. Kegiatan pembuka tahun ajaran baru ini ditujukan untuk menjadi
pencerah awal dan wawasan kebhinekaan budaya dalam lingkungan yang akan
mereka huni.
Sementara itu, di pesantren Tebuireng, pendidikan toleransi di
sekolah formal yang ada di lingkungan Pondok Pesantren Tebuireng, santri
secara langsung memperoleh pendidikan multikultural setelah mereka belajar
PKN atau Moral Pancasila. Tentu saja, mata pelajaran ini akan membawa siswa
terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara dalam bingkai Indonesia. Mata
pelajaran ini akan mengantarkan siwa menjadi manusia Indonesia yang ramah,
toleran, moderat, dan dapat besikap adil. Intinya, bahwa mata pelajaran ini
menjadikan siswa dapat memahami nilai-nilai Pancasila dan mengamalkannya.
Demikian pula, secara langsung santri mendapat pendidikan
multikultural setelah mereka mengikuti pengajian kitab-kitab salaf (kuning)
yang diajarkan di Pesantren Tebuireng. Secara khusus, ada satu kitab yang dapat
membentuk karakter santri yang moderat atau mengantarkan santri berpaham
dalam Islam dengan paham yang tidak ekstrim, yaitu Kitab Risalah Ahlis Sunnah
Wal Jama'ah. Kitab ini tentu akan membekali santri berpaham Ahlussunnah Wal
Jama’ah. Sementara diketahui, bahwa paham keagamaan yang dikenal
Ahlussunnah Wal Jama’ah (Aswaja) memiliki ciri-ciri mengedepankan sikap
toleran, moderat, sikap adil.
Selanjutnya, pendidikan multikultural diperoleh santri Pondok
Toleransi dalam Keberagaman
Pesantren Tebuireng secara tidak langsung dari tradisi yang sekarang ini ada
dan dikembangkan di lingkungan Tebuireng. Misalnya, dari pengasuh yang
sekarang, yaitu K.H. Salahuddin Wahid, santri secara tidak langsung dapat
meneladani model, gaya, karakter, pemikiran, dan model ber-Islam beliau.
Dikatakan, bahwa pengasuh yang sekarang, K.H. Salahuddin Wahid tampak
dalam kepemimpinannya bersikap demokratis, menghormati pendapat santri, dan
bahkan dalam banyak hal pendapat para pengurus-lah yang dijadikan sebagai
pijakan kebijakan.
Akhmad Halim mengemukakan, “Kepemimpinan Gus Solah (panggilan
akrab K.H. Salahuddin Wahid) bersifat demokratis, efektif, dan rasional, karena
semua kebijakan merupakan hasil musyawarah. Kelebihan pada pemimpin-
pemimpin di Pesantren Tebuireng sebelumnya banyak diwariskan kepadanya,
meskipun basis pendidikannya bersifat umum, namun tidak mengurangi
kemampuannya untuk mengelola pesantren sebagai amanat berat yang
diembannya”.
Diyakini pula, apabila para santri dapat meneladani K.H. Salahuddin
Wahid dalam sikap dan pemikirannya, maka akan menjadi manusia yang
berpandangan luas, dapat membawa Islam sebagai ajaran rahmatun lil’lamiin,
berpaham Islam yang moderat, inklusif, dan intinya menjadi santri yang
telah memahami dan menjiwai nilai-nilai multikultural. Secara tidak langsung
santri Tebuireng juga telah belajar berpikir, berpandangan luas, dan berjiwa
demokratis ketika budaya diskusi dan dialog telah berjalan. Ada beberapa
forum diskusi sebagai pembelajaran santri yang telah berjalan di lingkungan
Pondok Pesantren Tebuireng, diantaranya Forum Bahtsul Masail, Fordislaf
(Forum Diskusi Santri Salaf), Forum Diskusi Mahasiswa S1 yang membahas
permasalahan sekitar tafsir dan penafsirannya dan juga pemikiran Islam, dan
Forum Diskusi Mahasiswa S2. Diskusi semacam ini tentu dapat menjadikan
pembelajaran bagi santri agar dapat berisikap demokratis dan menghargai
pendapat orang lain. Dapat dilihat, ketika diskusi berjalan tentu akan muncul
beragam pendapat dan pandangan, baik dari peserta diskusi sendiri maupun
referensi yang digunakan. Diketahui bahwa dalam paham Islam yang dipegang
Toleransi dalam Keberagaman
santri, yaitu Ahlussunnah Wal Jama’ah, dinyatakan mengakui eksistensi empat
mazhab dalam fiqih, sehingga bukan tidak mungkin muncul perbedaan dalam
menyikapi satu kasus dengan referensi dari berbagai mazhab.
DAFTAR PUSTAKA
Amir, Syafruddin, 2006, “Pesantren Pembangkit Moral Bangsa”.(Online)
(http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2006/072006/03/ 11wacana01.htm-
28k-diakses tanggal 5 April 2012).
Bisri, Mustofa, 2007, “Pesantren dan Pendidikan”, Tebuireng, Edisi
1/Tahun I/Juli-September.
Bruinessen, Martin Van, 2002, “Genealogies of Islamic Radicalism inpost-
Suharto Indonesia”, Southeast Asia Research, No. 2.
Bungin, Burhan. 2001, Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis
ke Arah Varian Kontemporer (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
Dhofier, Zamakhsyari, 1983, Tradisi Pesantren: Studi tentang
Pandangan Hidup Kyai (Jakarta: LP3ES).
Emzir, 2008, Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif
(Jakarta: Rajawali Pers).
Faisal, Sanapiah, 2001, Format-format Penelitian Sosial (Jakarta: Raja Grafindo
Persada).
http://qidal.wordpress.com/2012/03/28/pondok-pesantren-karakteristik-dan-
fungsinya/, diakses 12 Desember 2013.
Maksum, Ali, 2011, Pluralisme dan Multikulturalisme: Paradigma Baru
Pendidikan Agama Islam di Indonesia (Malang: Aditya Media).
Muhammad, Husein, 1999, “Memahami Sejarah Ahlussunnah
Waljamaah: Yang Toleran dan Anti Ekstrem”, dalam Imam Baehaqi
(ed.), Kontroversi Aswaja (Yogyakarta: LKiS).
Mun’im, A. Rafiq Zainul, 2009, “Peran Pesantren dalam Education For All di
Era Globalisasi”, (2009) dalam http://ejournal.sunan- ampel.ac.id/
index.php/JPI/ article/view/177/ 162, diakses 23 Nopember 2013.
Mustaqim, Abd., 2003, “Menggagas Pesantren Transformatif”, Aula, No. 09
Tahun XXV, September.
Naim, Ngainun dan Achmad Sauqi, 2008, Pendidikan Multikultural: Konsep dan
Aplikasi (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media).
Nazir, Mohammad, 2005, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia).
Qomar, Mujamil, 2002, NU Liberal; Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke
Universalisme Islam (Bandung: Mizan).
Rodger, Alex R., 1982, Educational and Faithin Open Society (Britain: The
Handel).
Wijdan SZ., Ade, Dkk., 2007, Pemikiran dan Peradaban Islam
(Yogyakarta: Safiria Insania Press).
Zarkasyi, KH. Abdullah Syukri, 2005, Manajemen Pesantren: Pengalaman
Pondok Modern Gontor (Ponorogo: Trimurti Press).
Jurnal Pendidikan Agama Islam Volume 03, Nomor 01, Mei 2015, hal 96-108
Toleransi dalam Keberagaman
Anda mungkin juga menyukai
- Buku Mentoring Tom 2019Dokumen57 halamanBuku Mentoring Tom 2019AyyirahmaBelum ada peringkat
- Makalah Bahasa IndonesiaDokumen8 halamanMakalah Bahasa IndonesiaDian Putri PangestuBelum ada peringkat
- Edit CeramahDokumen44 halamanEdit CeramahHendra wanBelum ada peringkat
- Macam-Macam Metode Dakwah, Metode Ceramah, Metode Tanya Jawab DeanDokumen13 halamanMacam-Macam Metode Dakwah, Metode Ceramah, Metode Tanya Jawab DeanRosa SeranBelum ada peringkat
- MAKALAH-CERAMAH-MIYAN-PRINT-doc (Finish2)Dokumen10 halamanMAKALAH-CERAMAH-MIYAN-PRINT-doc (Finish2)Nur HasanahBelum ada peringkat
- Rangkuman DDDGDokumen4 halamanRangkuman DDDGIffana LuthfiBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Bahasa Arab k3Dokumen15 halamanTugas Makalah Bahasa Arab k3Ahmad Zamzam (Leo)Belum ada peringkat
- Materi Teks CeramahDokumen15 halamanMateri Teks CeramahyogaBelum ada peringkat
- Struktur CeramahDokumen8 halamanStruktur CeramahRinaldiansyah Sp100% (1)
- Ceramah (Kelompok Mario, Ilham, Helmi)Dokumen26 halamanCeramah (Kelompok Mario, Ilham, Helmi)Heni RosalinaBelum ada peringkat
- Bahan Bacaan FasilitatorDokumen19 halamanBahan Bacaan Fasilitatoryusrul srBelum ada peringkat
- CER AMA: Pengertian Teks CeramahDokumen9 halamanCER AMA: Pengertian Teks CeramahBang'inBelum ada peringkat
- Materi Pidato Kelas 9 SMPDokumen3 halamanMateri Pidato Kelas 9 SMPGilang Chiakky Nugraha100% (2)
- Ceramah Dan KhotbahDokumen6 halamanCeramah Dan KhotbahMaulid YantiBelum ada peringkat
- Lembar Kerja Peserta DidikDokumen4 halamanLembar Kerja Peserta DidikBinti KhoiriyatiBelum ada peringkat
- Berbicara Untuk Keperluan Akademik Dan Penulisan IlmiahDokumen14 halamanBerbicara Untuk Keperluan Akademik Dan Penulisan IlmiahMutia AnggraeniBelum ada peringkat
- Juklak Makesta IPNU IPPNUDokumen10 halamanJuklak Makesta IPNU IPPNUAcihInginSetya100% (2)
- CERAMAHDokumen3 halamanCERAMAHAbrahamBelum ada peringkat
- Makalah PenelianDokumen19 halamanMakalah PenelianIshak RisaldiBelum ada peringkat
- TP 1. Elaborasi PemahamanDokumen3 halamanTP 1. Elaborasi PemahamanTri Yulia ArmaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen11 halamanBab IiYuston KarwayuBelum ada peringkat
- Tugas RingkasanDokumen9 halamanTugas Ringkasanmar haeniBelum ada peringkat
- CeramahDokumen23 halamanCeramahCuapaeng Kunedu KunduBelum ada peringkat
- RPP Aqidah Akhlak Adab Bertamu-Fadilla Putri Rahmanti 203111206Dokumen12 halamanRPP Aqidah Akhlak Adab Bertamu-Fadilla Putri Rahmanti 203111206EstiarrochmahBelum ada peringkat
- Penyajian Lisan 1Dokumen4 halamanPenyajian Lisan 1Putri GithaBelum ada peringkat
- Dakwah Mltikultural Kelompok 2Dokumen19 halamanDakwah Mltikultural Kelompok 2Juri AntoBelum ada peringkat
- B.arab Metode Istima' Kel 5Dokumen17 halamanB.arab Metode Istima' Kel 5hidayahsitinur438Belum ada peringkat
- Makalah Qur'an HaditsDokumen16 halamanMakalah Qur'an Haditsintan pariwaraBelum ada peringkat
- Isi Keterampilan MEMBIMBING DISKUSI KECILDokumen13 halamanIsi Keterampilan MEMBIMBING DISKUSI KECILLatifa RaBelum ada peringkat
- CERAMAHDokumen5 halamanCERAMAHLintang AyuBelum ada peringkat
- Materi Ceramah Kel. 6Dokumen4 halamanMateri Ceramah Kel. 6mufida alyBelum ada peringkat
- BMK - PidatoDokumen19 halamanBMK - PidatoTaufiq YusoffBelum ada peringkat
- Makalah Kelompok 2 SkiDokumen24 halamanMakalah Kelompok 2 SkiJoko DewoBelum ada peringkat
- TM 8 Desain Pendidikan GiziDokumen25 halamanTM 8 Desain Pendidikan GiziAdella AnggrainiBelum ada peringkat
- SMKN 2 MetroDokumen5 halamanSMKN 2 MetroSeptia Ummu ZamYasBelum ada peringkat
- CERAMAHDokumen27 halamanCERAMAHFatahiyah Mohd IshakBelum ada peringkat
- Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil Dan PeroranganDokumen2 halamanKeterampilan Mengajar Kelompok Kecil Dan PeroranganAdhit Satria100% (1)
- Makalah Metodologi Pembelajaran (1) - DikonversiDokumen13 halamanMakalah Metodologi Pembelajaran (1) - DikonversiTaat SantosoBelum ada peringkat
- Seminar Ke Sd-An FixDokumen22 halamanSeminar Ke Sd-An Fixkm5 SDN 48 CAKRANEGARABelum ada peringkat
- Makalah Case PresentationDokumen12 halamanMakalah Case PresentationNita SyafiraBelum ada peringkat
- Teknik Menstimulasi Konseling KelompokDokumen9 halamanTeknik Menstimulasi Konseling KelompokSuzyena Myme0% (1)
- MAKALAH B.Indo Kelompok 3Dokumen10 halamanMAKALAH B.Indo Kelompok 3VazenBelum ada peringkat
- Makalah Metode Dakwah 10Dokumen13 halamanMakalah Metode Dakwah 10hestikaihsaniilmi16Belum ada peringkat
- 3 - Konselor Sebagai FAsilitatorDokumen11 halaman3 - Konselor Sebagai FAsilitatorEnrike Felisia yemima EnrikepelisiaBelum ada peringkat
- Materi Ajar Teks CeramahDokumen8 halamanMateri Ajar Teks CeramahCesi Rahma NisaBelum ada peringkat
- MateriDokumen17 halamanMateriAbdul GhafurBelum ada peringkat
- Makalah B.Indonesia Kel 3 PDFDokumen14 halamanMakalah B.Indonesia Kel 3 PDFFauzi NasutionBelum ada peringkat
- (Fix) Modul Kel. 6 Penyuluhan Edukasi Konflik SARADokumen9 halaman(Fix) Modul Kel. 6 Penyuluhan Edukasi Konflik SARAmaximilien RobespierreBelum ada peringkat
- Teks CeramahDokumen20 halamanTeks CeramahOctavianiBelum ada peringkat
- Pidato, Presentasi, Resensi, RingkasanDokumen16 halamanPidato, Presentasi, Resensi, RingkasanebiBelum ada peringkat
- Makalah Tuan MudaDokumen13 halamanMakalah Tuan MudaMuda TuấnBelum ada peringkat
- Makalah Jenis2 Berbicara Dan Teknik ModeratorDokumen28 halamanMakalah Jenis2 Berbicara Dan Teknik ModeratorSiti Nur HasmaBelum ada peringkat
- Makalah Hadits TarbawiDokumen15 halamanMakalah Hadits TarbawitaufikBelum ada peringkat
- Makalah Strategi Pembelajaran 'Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil'Dokumen21 halamanMakalah Strategi Pembelajaran 'Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil'Silvi WahyuBelum ada peringkat
- 07 - XII - Bab.04 - Akidah Qada QadarDokumen22 halaman07 - XII - Bab.04 - Akidah Qada QadarSuliana 73Belum ada peringkat
- Makalah Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok KecilDokumen12 halamanMakalah Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok KecilAndika SetiawanBelum ada peringkat
- Makalah Ceramah (Miyan) PrintDokumen10 halamanMakalah Ceramah (Miyan) PrintChiie SaranghaeOnewryeowookimbum Sukanyahyunbinseohyun75% (4)
- POWERPOINT BERBICARA UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK (2) Universitas Mercu BuanaDokumen30 halamanPOWERPOINT BERBICARA UNTUK KEPERLUAN AKADEMIK (2) Universitas Mercu BuanaWiwid Wahyu PrasetyoBelum ada peringkat
- Langkah-Langkah menuju Pengetahuan (AH1-Indonesian Edition)Dari EverandLangkah-Langkah menuju Pengetahuan (AH1-Indonesian Edition)Belum ada peringkat
- Profilaksis: Antara Mumtaz & 49 MesyuaratDari EverandProfilaksis: Antara Mumtaz & 49 MesyuaratPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)