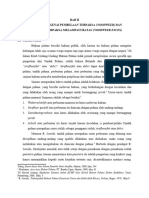Pengertian Dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana
Diunggah oleh
Nida Shilva Hadian0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2 tayangan19 halamanJudul Asli
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (3)
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
2 tayangan19 halamanPengertian Dan Ruang Lingkup Pertanggungjawaban Pidana
Diunggah oleh
Nida Shilva HadianHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPTX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 19
HUKUM PIDANA
Dr. H. Wahyu Wiriadinata, S.H., M.H.
Willman Supondho Akbar, S.H., M.H.
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (DADER)
Menurut Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. Sebelum
kesalahan normatif mengemuka (normatief
schuldbegrip), umumnya para ahli hukum pidana
memandang kesalahan semata – mata sebagai
masalah keadaan psikologis seseorang ketika
melakukan tindak pidana (psychologis schuldbegrip).
Kesalahan dipahami dalam beberapa pengertian, yang
selalu bertalian dengan psikologis pembuat tindak
pidana.
Pertama – tama, secara sempit kesalahan dipandang sama dengan
kealpaan. Dengan kata lain, istilah kesalahan digunakan sebagai sinonim
dari sifat tidak berhati – hati. Kemudian pengertian kesalahan juga
dikaitkan dengan alasan penghapus pidana di luar UU. Dalam hal ini
ketiadaan kesalahan sama sekali atau afwezigheid van alle schuld
(avas), dijadikan alasan penghapus pidana selain yang telah ditentukan
dalam UU. Istilah kesalahan juga digunakan sebagai nama pengumpul
‘kesengajaan’ dan ‘kealpaan’. Dikatakan ada kesalahan, jika pada diri
pembuat terdapat salah satu dari dua bentuk kesalahan, ketika
melakukan tindak pidana. Terakhir, dalam lapangan hukum acara pidana,
berkaitan dengan asas ‘praduga tidak bersalah’, kesalahan diartikan
sebagai ‘telah melakukan’ tindak pidana.
Semua pengertian tersebut umumnya merujuk pada
kenyataan bahwa kesalahan sebagai bagian inti tindak
pidana, yang isinya keadaan psikologis pembuat, ketika
melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan umumnya
dipandang sebagai unsur subyektif tindak pidana. Von Liszt
misalnya mengatakan, kesalahan dibentuk oleh keadaan
psikis tertentu dari pembuat. Fletcher menyebut teori
kesalahan psikologis sebagai teori deskriptif tentang
kesalahan, mengingat unsur mental terdeskripsi secara nyata
sebagai bagian tindak pidana.
Pendapat – pendapat yang senada juga dapat ditemui di negara –
negara common law. Kesalahan dalam common law system lazim
disebut dengan mens rea, selalu dipahami sebagai keadaan
psikologis pembuat ketika melakukan tindak pidana. Pada
mulanya mens rea merupakan konsep yang sama dengan
pemikiran yang salah. Dengan demikian, mens rea semata –
mata diartikan sebagai mental element dari tindak pidana. Mens
rea baik ‘intention’, ‘recklessness’ atau ‘negligence’, dipandang
sebagai unsur tindak pidana, yang berupa keadaan psikologis
pembuat ketika melakukan perbuatan tersebut.
Dalam tradisi common law system doktrin mens rea sempat diragukan. Menurut
Smith dan Hogan, pandangan yang berpendirian bahwa mens rea harus ada
pada tiap tindak pidana, hanya di ikuti sampai akhir abad kesembilan belas.
Setelah masa itu, doktrin mens rea dipandang tidak lagi berlaku mutlak.
Penyimpangan diawali ketika umumnya tindak pidana yang ditetapkan melalui
peraturan perundang – undangan (statutory offences atau regulatory offences),
dirumuskan tanpa unsur mental. Dengan demikian berbeda dengan common law
crime, yang umumnya memuat terdiri dari actus reus dan mens rea.
Penyimpangan atas doktrin mens rea semakin kentara ketika diterapkannya strict
liability terhadap statutory offences. Dengan demikian mens rea tidak lagi
dipandang unsur mutlak tindak pidana. Dalam hal ini, sejak kasus Prince 1875,
pengadilan di Inggris telah menerapkan strict liability terhadap statutory offences.
Dengan demikian, mens rea tidak lagi dipandang unsur mutlak tindak pidana.
Ironisnya, baik di negara – negara civil law maupun common law, kesalahan
atau mens rea itu, justru dipandang sebagai nilai etis dari penjatuhan pidana.
Apakah berdasar asas ‘geen straf zonder schuld’ atau menurut maksim latin
‘actus non est reus nisi mens sit rea’, kesalahan atau mens rea menjadi sangat
penting dalam penjatuhan pidana terhadap pembuat. Bahkan dikatakan berat
ringannya pidana yang dijatuhkan, harus setimpal dengan kesalahan pembuat.
Pada satu sisi pidana hanya mempunyai dasar susila jika dijatuhkan berdasar
kesalahan, tetapi pada sisi yang lain timbul kesulitan untuk mengaitkan
kesalahan dengan tindak pidana tertentu. Namun demikian, umumnya sikap
para ahli hukum pidana dalam menghadapi situasi sebagaimana tersebut di
atas, menerima pengecualian adanya kesalahan dalam pertanggungjawaban
pidana, atau mengakui berlakunya doktrin mens rea secara tidak mutlak.
Van Strien mengatakan, “dalam kaitan ini inti pengertian
kesalahan adalah suatu keadaan dimana dalam situasi
tertentu masih dimungkinkan bertindak secara lain dan dalam
situasi tersebut secara wajar dapat diharapkan bahwa
alternatif tidak tertentu masih mungkin untuk diambil.”
Dengan demikian, dapat dicelanya pembuat karena masih
terbuka kemungkinan untuk berbuat lain, selain tindak
pidana. Dengan kata lain, pembuat dapat dicela karena
sebenarnya hukum mengharapkan kepadanya untuk berbuat
lain, selain tindak pidana.
Menurut Sutorius, kesalahan terletak dalam melalaikan kesalahan itu.
Dikatakannya, kriteria kesalahan karenanya dapat ditentukan oleh beberapa
hal. Pertama, pada pembuat timbul kewajiban untuk mengenal risiko suatu
perbuatan tertentu untuk kepentingan yang dilindungi oleh norma yuridis dan
menilainya dengan baik. Dengan kata lain, pembuat juga memahami dampak
dari perilakunya. Kedua, pembuat harus mempunyai ketelitian lahir, guna
mencegah datangnya dampak tidak diinginkan dalam batas – batas
kemampuan. Termasuk di dalamnya; menjauhi perbuatan – perbuatan
berbahaya, meninggalkan perbuatan – perbuatan yang dituntut kemahiran
untuk melakukannya, bertindak hati – hati dalam situasi berbahaya, dan
mengadakan persiapan – persiapan yang sungguh – sungguh sebelum
bertindak dan berusaha mendapatkan informasi mengenai itu.
Dalam praktik peradilan, kesalahan diukur dari keadaan eksternal
dari pembuat tindak pidana dierapkan dalam kasus dr.
Setyaningrum, yang tidak diliputi culpa karena telah melakukan
upaya sewajarnya yang dapat dituntut daripadanya sebagai dokter
dengan pengalaman kerja selama 4 tahun dan sedang melakukan
tugasnya pada Puskesmas dengan sarana yang serba terbatas.
(Putusan MA RI No. 600/K/Pid/1973). Kesalahan tidak diukur dari
keadaan psikologis dr. Setyaningrum, tetapi penilaian atas keadaan
psikologis rata – rata dokter yang setara dengannya, yang boleh
jadi menurut ukuran – ukuran dokter yang lebih ahli padanya
teradapat ketidakhati-hatian yang nyata.
Dalam doktrin common law pembahasan mengenai mens rea juga
dihubungkan dengan ketercelaan (blameworthy) pembuat. Bahkan
tidak jarang mens rea disinonimkan dengan ‘tercela’ (blame).
Namun demikian, terdapat perbedaan konseptual, jika
dibandingkan dengan konsep ‘dapat dicelanya pembuat’
sebagaimana dikemukakan diatas. Dalam common law system,
masalah ketercelaan diwarnai oleh dua perseteruan antara dua
teori, yaitu capacity theory dan character theory. Sementara
pendapat lain melihat kedua teori tersebut justru sebagai two
models of responsibility.
Teori kesalahan normatif menyebabkan strict liability dapat diterima sebagai
bentuk pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan. Kesengajaan dan
kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan, sehingga
bukanlah kesalahan itu sendiri. Kesalahan ada jika kelakuan tidak sesuai
dengan norma yang harus diterapkan. Kesalahan tetap dapat dipandang
ada, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh mengenai kesengajaan atau
kealpaan pembuat tindak pidana. Sepanjang norma hukum menentukan
bahwa pembuatnya dapat di cela karena melakukan tindak pidana, maka
terdapat kesalahan pada diri pembuatnya. Apabila UU menetapkan suatu
tindak pidana dipertanggungjawabkan secara strict, maka pada
pembuatnya tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau
lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya.
Strict liability merupakan pertanggungjawaban terhadap
pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa harus
membuktikan kesalahannya. Kesalahannya tetap ada, tetapi
tidak harus dibuktikan. Terdakwa dinyatakan bersalah hanya
dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana.
Dengan demikian, fungsi utama strict liability adalah
berkenaan dengan hukum acara, dan bukan hukum pidana
materiil. Strict liability dalam pertanggungjawaban pidana lebih
merupakan persoalan pembuktian, yaitu kesalahan dipandang
ada sepanjang telah dipenuhinya unsur delik.
Menurut pendapat Schaffmeister yang menganggap
digunakannya strict liability sebagai penyimpangan atas
asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’. Selain itu, berbeda
pula dengan pendapat Barda N. Arief yang memandang
strict liability sebagai pengecualian berlakunya asas ‘tiada
pidana tanpa kesalahan’. Pada strict liability pembuatnya
tetap diliputi kesalahan. Kesalahan dalam pengertian
normatif.
Rancangan KUHP juga mengakui strict liability sebagai
pertanggungjawaban pidana berdasar kesalahan, sebagaimana
dirumuskan dalam Pasal 32 ayat (3) Rancangan KUHP. Ditentukan
bahwa: “untuk tindak pidana tertentu, UU dapat menentukan bahwa
seseorang dapat dipidananya semata – mata karena telah
dipenuhinya unsur – unsur tindak pidana tanpa memerhatikan
kesalahan”. Anak kalimat ‘tanpa memerhatikan kesalahan’ bukan
berarti dalam strict liability pertanggungjawaban pidana dilakukan
dengan mengabaikan kesalahan pembuat. Sebaliknya kesalahan
dipandang ada, sekalipun tidak tampak bentuknya.
Teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan tidak mutlak
harus dilihat sebagai ‘kondisi kejiwaan manusia’. Hal ini membuka
kesalahan selain perihal yang ditandai dengan kesengajaan atau
kealpaan (psikologis pembuat). Dengan demikian, memungkinkan
kesalahan terdapat bukan hanya pada subyek hukum manusia,
tetapi juga korporasi. Hampir tidak mungkin menentukan adanya
kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata – mata dilihat
sebagai masalah psikologis. Mereka yang menganut teori
psikologis, berpendapat kesalahan selalu ditujukan terhadap
subyke hukum manusia, sehingga perlu di cari dasar lain untuk
mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana.
Remmelink mengatakan, “percelaan atas kesalahan (schuldverwit)
selalu ditujukan pada manusia dan karena itu sifatnya sangat
personal”. Demikian pula dengan Van Bemmelen. Dikatakannya,
“kita tidak dapat lain selain menghubungkan pengertian personal
dengan individu manusiawi”. Jika akhirnya mereka berpendapat
bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum
pidana, itu pun dilakukan dengan ‘memanusiakannya’. Baik dengan
mengaitkan karakteristik atau sifat subyek hukum manusia yang
merupakan bagian dari korporasi pada korporasi itu sendiri (teori
organ) maupun dengan memandang korporasi sebagai ‘mahluk
super’ (gesamtperson) dengan sifat yang manusiawi.
Bersandar pada kesalahan normatif, pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan atas
dasar kesalahan. Hanya saja isi kesalahan tersebut berbeda dengan subyek hukum
manusia. Dasar dari penetapan dapat dipersalahkannya badan hukum ialah tidak
dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang di miliki badan hukum. Dilihat dari
segi kemasyarakatan ‘korporasi telah tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Indikator
keaslahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi
kemasyarakatan itu. Fungsi kemasyarakatan ini termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum mengharapkan kepada
korporasi untuk menjalankan fungsi kemasyarakatannya dengan baik sehingga sejauh
mungkin dapat menghindari terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, selagi terbuka
kemungkinan bagi korporasi untuk ‘dapat berbuat lain’ selain melakukan tindak pidana,
maka harapan tersebut harus sejauh mungkin tercermin dari kebijakan dan cara
pengoperasiannya. Terhadap korporasi penilaian adanya kesalahan ditentukan oleh
bagaimana korporasi memenuhi fungsi kemasyarakatannya, sehingga ‘dapat dicela’ ketika
suatu tindak pidana terjadi karenanya.
Memahami kesalahan tersebut, menempatkan hal itu dalam suatu sistem normatif.
Sistem inilah yang kemudian menentukan syarat dan isi kesalahan. Sistem normatif
ini menentukan apakah seseorang karenanya dapat dipertanggungjawabkan dalam
hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Dengan demikian, jika ‘kesalahan’ adalah
‘dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum’ maka setiap pertanggungjawaban
pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu melakukan tindak pidana terdapat
kesalahan pada diri pembuat. Baik pada subyek hukum manusia maupun pada
korporasi nilai patut tidaknya dijatuhi pidana terletak pada adanya kesalahan. Hal ini
berarti makna asas ‘tiada pidana tanpa kesalahan’ adalah ‘tiada
pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan’. Cara bagaimana asas kesalahan ini
dikonkretisasi dan tingkat kesalahannya yang dipersyaratkan tidaklah perlu sama
untuk tiap delik. Dengan demikian, syarat dan isi kesalahan tidak perlu sama,
terhadap pembuat tindak pidana dengan subyek hukum manusia atau korporasi.
Anda mungkin juga menyukai
- Kesehatan mental dan gangguan psikologis: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandKesehatan mental dan gangguan psikologis: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Bab2 - Bab4 - 2012144sc-pDokumen72 halamanBab2 - Bab4 - 2012144sc-praihandam2005Belum ada peringkat
- Konsep Pertanggung Jawaban PidanaDokumen17 halamanKonsep Pertanggung Jawaban Pidanalala istiqamahBelum ada peringkat
- Pertemuan Ke 11 Hukum PidanaDokumen29 halamanPertemuan Ke 11 Hukum PidanaHokky Putra UtamaroBelum ada peringkat
- Bab 2 - Navishya QintharDokumen24 halamanBab 2 - Navishya QintharnavishyaBelum ada peringkat
- Tugas Politik Hukum PidanaDokumen3 halamanTugas Politik Hukum PidanaBernadus FebriyantoBelum ada peringkat
- Bab Ii Tinjauan Pustaka: Responsibility, Atau Criminal Liability. Konsep Pertanggungjawaban PidanaDokumen22 halamanBab Ii Tinjauan Pustaka: Responsibility, Atau Criminal Liability. Konsep Pertanggungjawaban Pidanaampon muqtadir12Belum ada peringkat
- Uas - Ahmat Rudi Hasibuan - Pertanggungjawaban PidanaDokumen8 halamanUas - Ahmat Rudi Hasibuan - Pertanggungjawaban PidanaahmatrudihasibuanBelum ada peringkat
- KESALAHANDokumen17 halamanKESALAHANKadek Purnama Adi PutraBelum ada peringkat
- Siftiana Sariyatul Arzaqiyah - Kesalahan Dan Kemampuan BertanggungjawabDokumen7 halamanSiftiana Sariyatul Arzaqiyah - Kesalahan Dan Kemampuan BertanggungjawabArzaqBelum ada peringkat
- HUKUM PIDANA DAN PROFESIDokumen36 halamanHUKUM PIDANA DAN PROFESIYudha Febrian Al FaniBelum ada peringkat
- Kesalahan Dan Pertanggungajwaban Pidana Alasan PemaafDokumen27 halamanKesalahan Dan Pertanggungajwaban Pidana Alasan Pemaaftheman Jalan-jalanBelum ada peringkat
- HK PidanaDokumen9 halamanHK PidanaSoniaNiken KasumaBelum ada peringkat
- HHHHHDokumen38 halamanHHHHHAwan RidwanBelum ada peringkat
- Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Hukum PidanaDokumen4 halamanKesalahan Dan Pertanggungjawaban Hukum PidanagitaBelum ada peringkat
- Pertanggung Jawaban PidanaDokumen7 halamanPertanggung Jawaban PidanaSahimi As SawangiBelum ada peringkat
- Teori Pertanggungjawaban PidanaDokumen24 halamanTeori Pertanggungjawaban PidanaWilly Pratama JonidaBelum ada peringkat
- Batas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana AnakDokumen21 halamanBatas Usia dan Pertanggungjawaban Pidana AnakEunike SihombingBelum ada peringkat
- BAB II Elsi KristiDokumen7 halamanBAB II Elsi KristiVerytha SariBelum ada peringkat
- Kesalahan Dan Pertanggung Jawaban Pidana 4Dokumen6 halamanKesalahan Dan Pertanggung Jawaban Pidana 4Azzahra NingtyasBelum ada peringkat
- Geen Straf Zonder SchulDokumen11 halamanGeen Straf Zonder Schuloga yogananda100% (1)
- PERTANGGUNGJAWABANDokumen13 halamanPERTANGGUNGJAWABANFahmy AriefiantoBelum ada peringkat
- BAB 2 Skripsi HSADokumen26 halamanBAB 2 Skripsi HSAHelmy Syamsul AmryBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen23 halamanBab IiTerry RumabarBelum ada peringkat
- Asas KesalahanDokumen4 halamanAsas KesalahanSu Pros100% (1)
- Pertanggung Jawaban PidanaDokumen13 halamanPertanggung Jawaban PidanaSahimi As SawangiBelum ada peringkat
- Soal UTS Hukum Pidana VienskaDokumen5 halamanSoal UTS Hukum Pidana VienskaKristian TronikBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen10 halamanBab 2pooregskyBelum ada peringkat
- Asas Hukum PidanaDokumen6 halamanAsas Hukum PidanaDyah Ayu Retno FebrianaBelum ada peringkat
- Pertanggungjawaban Tindak Pidana KorporasiDokumen62 halamanPertanggungjawaban Tindak Pidana KorporasiBambangBelum ada peringkat
- Lexetsocietatis dk28,+3.+Grace+Yurico+Bawole 3Dokumen5 halamanLexetsocietatis dk28,+3.+Grace+Yurico+Bawole 3januarita.eki januarita.ekiBelum ada peringkat
- KELOMPOKDokumen10 halamanKELOMPOKAlif SurantoBelum ada peringkat
- Pertanggungjawaban PidanaDokumen20 halamanPertanggungjawaban PidanaTataBelum ada peringkat
- PERTANGGUNGJAWABAN PIDANADokumen15 halamanPERTANGGUNGJAWABAN PIDANAmoses ustadBelum ada peringkat
- HK - Pidana Kel.3Dokumen10 halamanHK - Pidana Kel.3Achmad Ridho IslamiBelum ada peringkat
- Full Materi Hukum PidanaDokumen143 halamanFull Materi Hukum Pidanaragil septianaBelum ada peringkat
- Penerapan Sanksi Pidana Terhadap UitlokkingDokumen8 halamanPenerapan Sanksi Pidana Terhadap UitlokkingTiya ErniyatiBelum ada peringkat
- Resume 1 Tindak Pidana Dan PemidanaanDokumen6 halamanResume 1 Tindak Pidana Dan PemidanaanTeguh AdiBelum ada peringkat
- Lindung L. SiahaanDokumen30 halamanLindung L. SiahaanziadBelum ada peringkat
- Teori Penanggungjawaban PidanaDokumen8 halamanTeori Penanggungjawaban PidanaAnindya A.KBelum ada peringkat
- TINDAK PIDANA UMUMDokumen38 halamanTINDAK PIDANA UMUMM. Fahrizal HidayatullahBelum ada peringkat
- Geubrina Mudhira (180510304)Dokumen7 halamanGeubrina Mudhira (180510304)Zoldyck jaya99Belum ada peringkat
- Pertanggungjawaban PidanaDokumen4 halamanPertanggungjawaban PidanaRyanSoetopoBelum ada peringkat
- Pembahasan PenggelapanDokumen43 halamanPembahasan PenggelapanPak ArifBelum ada peringkat
- LN Sesi 12 Pertanggungjawaban PidanaDokumen4 halamanLN Sesi 12 Pertanggungjawaban Pidanaanyelir sputriBelum ada peringkat
- Uts Hukum Pidana - Kartika SariDokumen5 halamanUts Hukum Pidana - Kartika SariNIKOTIN FLYBelum ada peringkat
- Uas Hukum PidanaDokumen2 halamanUas Hukum Pidanaadipta bagusBelum ada peringkat
- Hukum Pidana Abdul, Indra, TikaDokumen10 halamanHukum Pidana Abdul, Indra, TikaIndra DunggioBelum ada peringkat
- Hukum Pidana-Moh. Abdul Azis-2021395500171Dokumen9 halamanHukum Pidana-Moh. Abdul Azis-2021395500171Raudlatussalam GunungsariBelum ada peringkat
- Muhammad Dzikri Akbar Syafi'i - 231221018 - Kapita Selekta Hukum PidanaDokumen10 halamanMuhammad Dzikri Akbar Syafi'i - 231221018 - Kapita Selekta Hukum Pidanadzikri akbarBelum ada peringkat
- Materi Prof. GayusDokumen16 halamanMateri Prof. Gayuschika_syahrirBelum ada peringkat
- TEORI KORPORASIDokumen12 halamanTEORI KORPORASIHanif RenandaBelum ada peringkat
- KesalahanDokumen34 halamanKesalahanLaili AmeliaBelum ada peringkat
- Tugas Hukum Pidana.2003docDokumen9 halamanTugas Hukum Pidana.2003docsitha1990Belum ada peringkat
- Tugas Resume Tindak PidanaDokumen12 halamanTugas Resume Tindak PidanafckaryasejahteraBelum ada peringkat
- PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASIDokumen7 halamanPENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH KORPORASIKristina SimanungkalitBelum ada peringkat
- Diskusi Hukum Pidana Sesi 9 Rosyani AdaDokumen11 halamanDiskusi Hukum Pidana Sesi 9 Rosyani AdaYaniBelum ada peringkat
- Kevin Anugrah SesarDokumen13 halamanKevin Anugrah SesarheryBelum ada peringkat
- Materi PentingDokumen5 halamanMateri PentingkartiBelum ada peringkat
- Kesalahan Dan Pertanggungjawaban PidanaDokumen13 halamanKesalahan Dan Pertanggungjawaban PidanaMuhammad Aris SaputraBelum ada peringkat