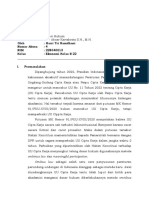Review Atas Putusan MK Terkait Pi
Review Atas Putusan MK Terkait Pi
Diunggah oleh
Fang Liie0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
8 tayangan27 halamanJudul Asli
5. Review Atas Putusan Mk Terkait Pi
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
PPT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
8 tayangan27 halamanReview Atas Putusan MK Terkait Pi
Review Atas Putusan MK Terkait Pi
Diunggah oleh
Fang LiieHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai PPT, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 27
Putusan MK No.
13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian
terhadap UU No.38 / 2008 tentang Pengesahan Charter of The
Association of South East Asian Nations
dan
PUTUSAN JUDICIAL REVIEW MK ATAS UU NO. 24
TAHUN 2000 TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL
Dr. Nanik Trihastuti,SH.,Mhum.
Hukum Perjanjian Internasional
Fakultas Hukum UNDIP
Pendapat MK
• lembaga ini berwenang untuk menguji Piagam ASEAN karena dokumen ini
tidak lain dan tidak bukan adalah bagian yang tak terpisahkan dari UU yang
merupakan objek yang sah untuk diuji oleh MK.
Argumentasi : Karena secara formal Piagam ini adalah UU maka tidak ada
alasan bagi MK untuk tidak dapat mengujinya
• Setelah memutuskan bahwa MK berwenang, selanjutnya para Hakim masuk
ke materi Piagam ASEAN
• MK menemukan bahwa Pasal 5 ayat (2) ASEAN Charter yang dipersoalkan
oleh Pemohon adalah kebijakan makro dan belum berlaku efektif.
• Secara nasional berlakunya kebijakan makro tersebut tergantung kepada
masing-masing negara anggota ASEAN untuk melaksanakan.
• Atas argument ini maka gugatan pemohon tidak beralasan menurut hukum.
• MK memberi pesan bahwa selama perjanjian internasional dibuat dalam
bentuk UU maka semua perjanjian internasional dapat diuji oleh MK. Artinya,
semua perjanjian internasional lainnya dapat diuji dan berpotensi untuk
dinyatakan bertentangan dengan UUD.
• Argumen ini sangat logis dan dapat dipahami.
• MK telah memilih aliran hukum yang menjadi kontroversi selama ini bahwa
UU yang meratifikasi Piagam ASEAN tidak berbeda dengan UU lainnya dan
tidak menemukan alasan yang meyakinkan mengapa UU ini harus dibedakan
dengan UU lainnya, sekalipun tersedia doktrin yang menyatakan sebaliknya.
PERSOALAN
• APAKAH PIAGAM ASEAN INI MERUPAKAN UU ?
• Dua Hakim Konstitusi melalui dissenting opinion keberatan dengan argumen
yang mengidentikkan UU No. 38/2008 dengan UU pada umumnya.
• Menurut kedua hakim ini: ‘memang benar, formil UU 38/2008 adalah
Undang-Undang, tetapi materilnya bukanlah Undang-Undang dan tidak
dapat dijadikan objek pengujian undang-undang yang menjadi wewenang
Mahkamah.
• Selanjutnya ditegaskan bahwa UU ini bukanlah suatu peraturan perundang-
undangan yang substansinya bersifat normatif, yang adressat normanya
dapat secara langsung ditujukan kapada setiap orang, tetapi merupakan
persetujuan dari DPR terhadap perjanjian internasional yang telah dibuat
oleh Pemerintah untuk memenuhi Pasal 11 UUD 1945, dan diberi ”baju”
dengan UU.
• Dalam pengujian Piagam ASEAN Tampaknya terdapat kesulitan juridis bagi
sebagian besar hakim konstitusi untuk keluar dari asas legalitas bahwa UU
yang meratifikasi suatu perjanjian tidak lain dan tidak bukan adalah UU.
• Kesulitan ini dapat terbaca karena di bagian lain MK mengatakan bahwa
pilihan bentuk hukum ratifikasi perjanjian internasional dalam bentuk formil
Undang-Undang perlu ditinjau kembali. (Kesimpulan ini dibangun dari premis
yang agak lain dan terkesan bahwa mengambil bentuk UU adalah sistem
yang keliru ).
• Dilain pihak argumentasi MK yang kelihatannya logis dari sisi hukum
tatanegara namun menjadi tidak logis dalam hukum internasional. Bagi MK,
pemuatan Piagam ASEAN kedalam UU 38/2008 dinilai sebagai pemindahan
format treaty kedalam format UU yang memiiki konsekuensi bahwa negara
pihak harus terikat pada UU ini. Padahal dalam konsepsi hukum publik
dikenal suatu model masuknya perjanjian internasional kedalam hukum
nasional melalui proses transformasi.
• Teori transformasi menjelaskan bahwa Piagam ASEAN dalam formatnya
sebagai Treaty mengikat semua negara pihak dalam tataran hukum
internasoinal, sedangkan UU 38/2008 jika hendak dianggap sebagai UU
transformasi maka hanya diartikan sebagai Piagam ASEAN yang
ditransformasikan kedalam hukum nasional dan bertujuan hanya untuk
mengikat subjek-sybjek dalam hukum nasional.
• Menurut teori ini, pemuatan Piagam ASEAN kedalam fromat UU 38/2008
adalah murni urusan hukum nasional dan tidak ada sangkut pautnya dengan
status Piagam sebagai treaty menurut hukum internasonal, yang tetap
tentunya mengikat negara pihak lainnya sebagai subjek hukum internasional.
• Dengan demikian, argumen MK yang menyatakan bahwa Negara lain harus
terikat pada UU 38 Tahun 2008 sangat tidak mendasar dan bukan
sebagaimana yang dimaksud oleh teori transformasi.
• Dapat tidaknya perjanjian internasional diuji oleh pengadilan nasional
hanya dapat dijawab setelah Indonesia menetapkan status perjanjian
internasional dalam hukum nasional
• Pasal 2, 9 (2) dan 11 (1) tidak semua perjanjian internasional harus mendapat
persetujuan DPR. Dengan demikian suatu kriteria dibutuhkan untuk
menentukan perjanjian yang mana yang harus ke DPR.
• Soal kriteria ini UU telah mengatur hanya 6 jenis perjanjian yang
mensyaratkan persetujuan DPR, dan kriteria inilah yang digugat pemohon.
Perjanjian yang harus ke DPR tidak bisa dibatasi hanya pada 6 jenis ini, bisa
saja diluar ke enam jenis ini terdapat perjanjian lain yang membutuhkan
persetujuan DPR, demikian dalil pemohon. MK kemudian mengabulkan
permohonan yang ini.
• Terhadap permohonan yang satu lagi yakni Pasal 10, MK menyatakan bahwa
pasal ini bertentangan dengan UUD jika dimaknai bahwa hanya jenis
perjanjian tertentu saja yang harus mendapatkan persetujuan DPR (yakni
hanya soal politik, perdamaian, hankam, batas wilayah, kedaulatan atau hak
berdaulat, HAM, LH, kaidah baru dan pinjaman LN).
Problem Kriteria
• kriteria perjanjian apa saja yang memerlukan persetujuan DPR?
• persoalan klasik yang ada dalam hampir semua sistem hukum nasional. Di era
globalisasi ini tidak mungkin semua perjanjian harus disetujui DPR, dan ini
telah dikonfirmasi oleh MK. Untuk itu hampir semua negera menetapkan
kriteria untuk menentukan mana yang memerlukan persetujuan DPR dan
mana yang tidak.
• Sistem hukum Indonesia sudah mengalami persoalan klasik ini sebelum tahun
1960, yang dibereskan dengan keluarnya Surat Presiden 2826/1960,
tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
Surat Presiden 2826/1960
• tertanggal 22 Agustus 1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat.
• Dalam surat tersebut Presiden Sukarno antara lain menafsirkan bahwa
perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR berdasarkan
Pasal 11 UUD 1945 tidak mencakup seluruh perjanjian internasional tetapi
hanya perjanjian-perjanjian yang bersifat penting saja, yakni yang materi
muatannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan politik yang lazimnya
dikehendaki berbentuk traktat (treaty).
• Untuk menjamin kelancaran hubungan antara Pemerintah dengan DPR
berdasarkan Pasal 11 UUD 1945, maka Pemerintah hanya akan
menyampaikan ”perjanjian-perjanjian yang bersifat penting saja, yakni yang
materi muatannya mengandung hal-hal yang berkaitan dengan politik yang
lazimnya dikehendaki berbentuk traktat (treaty)”.
• Untuk perjanjian-perjanjian lain (agreement) akan disampaikan kepada DPR
sebagai semacam pemberitahuan semata
• Menurut Surat Presiden tersebut, maka perjanjian yang harus mendapat
persetujuan DPR adalah yang mengandung materi, antara lain: (i) Hal-hal
politik atau hal-hal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri;
(ii) Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi
haluan politik negara; dan (iii) Hal-hal yang menurut UUD atau
berdasarkan sistem perundang-undangan harus diatur dengan UU.
• Surat Presiden ini selanjutnya diformalkan dalam UU No. 24/2000 dengan
beberapa modifikasi
• Menurut UU ini, perjanjian yang memerlukan persetujuan DPR adalah
perjanjian yang terkait dengan soal politik, perdamaian, hankam, batas
wilayah, kedaulatan atau hak berdaulat, HAM, LH, kaidah baru dan
pinjaman LN.
• Kriteria inilah yang dipersoalkan oleh pemohon dengan dalil bahwa
perjanjian diluar kriteria ini bisa saja menimbulkan akibat yang luas dan
mendasar, dan seharusnya memerlukan persetujuan DPR.
Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018 tentang Pengujian UU No. 24 / 2000 tentang
Perjanjian Internasional.
• MK menegaskan kembali bahwa tidak semua perjanjian internasional harus mendapat
persetujuan DPR (dibutuhkan kriteria untuk menentukan perjanjian yang mana yang harus
ke DPR)
• UU telah mengatur hanya 6 jenis perjanjian yang mensyaratkan persetujuan DPR, dan
kriteria inilah yang digugat pemohon.
Dalil Pemohon : Perjanjian yang harus ke DPR tidak bisa dibatasi hanya pada 6 jenis ini,
bisa saja diluar ke enam jenis ini terdapat perjanjian lain yang membutuhkan persetujuan
DPR
• MK setuju dan membongkar kriteria ini serta menggantikannya dengan yang baru
• MK selanjutnya menggunakan kriteria Pasal 11 (2) UUD, yaitu perjanjian harus mendapat
persetujuan DPR jika menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terkait
dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang.
• Dengan kriteria ini maka perjanjian tidak lagi terbatas pada 6 jenis perjanjian diatas, namun
bisa perjanjian apa saja sepanjang memenuhi kriteria ini.
• Namun dilain pihak, 6 jenis perjanjian yang biasanya ke DPR tidak lagi otomatis ke DPR
jika tidak memenuhi kriteria baru. Dalam hal ini MK telah memperluas kewenangan DPR
sekaligus mempersempitnya.
akibat
• kriteria ini sangat umum dan akan sulit menguji apakah suatu persetujuan
berakibat luas dan mendasar atau membutuhkan perubahan atau
pembentukan UU.
• MK mengakui kesulitan ini sehingga cenderung berpendapat bahwa kriteria
ini bersifat dinamis dan tidak dapat ditentukan secara limitatif melainkan
harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan perkembangan
kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional
• MK selanjutnya mendorong adanya mekanisme konsultasi antara DPR dan
Pemerintah guna menentukan apakah suatu perjanjian perlu atau tidak
untuk mendapatkan persetujuan DPR. Hasil konsultasi bersifat tidak
mengikat namun pada umumnya dihormati oleh Pemerintah
Penafsiran Baru thd Ps. 11 UUD 1945
• MK juga melakukan tafsir baru atas Pasal 11 UUD 1945 khususnya relasi
antara ayat (1) dan ayat (2).
• Pasal 11 ayat (1) menyatakan “Presiden dengan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan
perjanjian dengan negara lain”.
• Ayat ini adalah produk dari BPUPKI tahun 1945 dan pada umumnya dimaknai
sebagai perjanjian antar negara saja karena pada era ini tidak dikenal
perjanjian dengan selain negara.
• Tidak terdapat kriteria dalam ayat ini sehingga lahirlah Surat Presiden No.
2826 Tahun 1960 kepada DPR yang menetapkan kriteria bahwa perjanjian
yang penting saja (yang sering dinamai dengan “traktat”) yang perlu
mendapatkan persetujuan DPR
• Penandatangan Letter of Intent antara Indonesia dan IMF tahun 1998 telah
melahirkan kontroversi publik tentang perjanjian ini, yang dianggap
menimbulkan akibat luas dan mendasar yang terkait beban keuangan negara
• perjanjian ini bukan antara negara melainkan dengan organisasi internasional
maka Pasal 11 UUD tidak berlaku, sehingga perjanjian ini diberlakukan tanpa
memerlukan persetujuan DPR
• Kontroversi ini telah mendorong adanya amandemen pada pasal 11 sehingga
melahirkan ayat (2) yang menyatakan: “Presiden dalam membuat perjanjian
internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar
bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang
harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
• ayat (2) ini telah merumuskan kriteria perjanjian yang harus dengan
persetujuan DPR. Kriteria yang sama tidak ada pada ayat (1).
• Konstruksi kedua ayat ini telah melahirkan pertanyaan tentang apa
perbedaan antar perjanjian pada ayat (1) dan pada ayat (2)
• frasa “perjanjian internasional lainnya” pada ayat (2) ini sebagai perjanjian antar
Indonesia dengan subjek lain selain negara. Frasa ini dikonstruksikan secara logis
sebagai perjanjian selain ayat (1) yakni perjanjian selain dengan negara
• Pengertian perjanjian internasional “lainnya” adalah perjanjian selain yang
dimaksud Ayat (1) namun tetap dalam kerangka definisi Konvensi Wina 1969 dan
1986, yang berarti perjanjian antara Indonesia dengan subjek hukum internasional
lainnya selain negara
• terdapat anomali pada Pasal 11 ini karena kedua model perjanjian ini memiliki
kriteria yang berbeda dalam kaitannya dengan perlu tidaknya persetujuan DPR.
Ayat (1) tidak merumuskan kriteria dan menggunakan kriteria yang tercantum pada
Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 sebagai UU penjabarannya.
• ayat (2) merumuskan kriteria tersendiri yakni “yang menimbulkan akibat yang luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
• Di lain pihak, kriteria Pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000 berlaku baik untuk perjanjian
ayat (1) maupun perjanjian ayat (2) UUD
Respon MK
• MK menafsirkan secara sistematis Pasal 11 UUD 1945.
• Menurut MK frasa “perjanjian internasional lainnya” dalam ayat (2) berarti
menegaskan bahwa “perjanjian dengan negara lain” pada ayat (1) adalah juga
perjanjian internasional.
• Penegasan ini penting karena menurut MK ada dua Konvensi yang berbeda
mengatur perjanjian antara negara (Konvensi Wina 1969) dan perjanjian
antara negara dengan organisasi internasional (Konvensi Wina 1986).
• Selanjutnya MK menafsirkan bahwa tidak semua perjanjian internasional yang
dibuat oleh Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR melainkan
hanya perjanjian-perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan umum
yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945
Akibat
• Penafsiran baru MK terhadap Pasal 11 ini mengubah total relasi antara ayat
(1) dan ayat (2) yang selama ini dimaknai oleh publik.
• Kedua ayat ini tidak membedakan antara perjanjian antar negara dengan
perjanjian dengan subjek bukan negara, melainkan harus dibaca sebagai satu
kesatuan, yang maknanya menjadi:
1. Bahwa ‘perjanjian dengan negara lain’ adalah perjanjian internasional.
2. tidak semua perjanjian harus ke DPR melainkan yang memenuhi kriteria
seperti tertera pada ayat (2).
• Dengan penafsiran ini maka lahirlah kriteria yang sama, baik untuk perjanjian
antar negara maupun untuk perjanjian antara Indonesia dengan subjek
bukan negara. Relasi ayat (1) dan (2) UUD yang terkesan tidak kohesif selama
ini menjadi lebih terintegrasi.
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN DPR
Dalil pemohon : istilah “pengesahan” telah menggantikan istilah “persetujuan DPR”,
MK akhirnya menyentuh perdebatan tentang makna “pengesahan
Persoalan : apakah “persetujuan DPR” dan “pengesahan (UU pengesahan)” adalah
satu kesatuan proses atau dua proses yang berbeda?
• Pemahaman Pemerintah : selama ini selalu memaknai UU Pengesahan
sebagai bentuk persetujuan DPR sehingga istilah ‘persetujuan DPR”
mengambil format UU. (berdasarkan UU No. 24 Tahun 2000 mengartikan
kedua istilah itu sebagai satu kesatuan proses, yakni bahwa “persetujuan
DPR” diekpresikan melalui UU pengesahan)
• Dipilihnya format UU untuk menjubahi “persetujuan DPR” karena saat itu
produk persetujuan DPR hanya dalam bentuk UU
• Konstruksi ini mengakibatkan “persetujuan DPR” menurut Pasal 11 UUD
1945 adalah dalam rangka syarat terbitnya UU pengesahan seperti yang
dimaksud oleh Pasal 20 UUD 1945. Artinya, “persetujuan DPR” seperti yang
dimaksud dalam Pasal 11 adalah identik dengan “persetujuan DPR” menurut
Pasal 20 UUD 1945
Pandangan Pakar
• mendukung penafsiran Pemerintah selama ini
a.Prof. Natabaya : menegaskan bahwa “persetujuan DPR” akan selalu
melahirkan “Undang-Undang
b.Hamid Attamimi : bahwa “persetujuan DPR” sendiri tidak identik dengan
Undang-Undang namun jika “persetujuan DPR” tersebut dituangkan dalam
bentuk Undang-Undang tidak pula menyalahi UUD 1945 karena praktik
Indonesia yang dilakukan sejak dahulu telah melahirkan konvensi
ketatanegaraan.
• Penjubahan “persetujuan DPR’ dalam bentuk UU merupakan tradisi hukum
Belanda yang diwarisi oleh Indonesia.
Pendapat MK
• MK memiliki pendapat berbeda dan memaknai kedua istilah ini sebagai dua
proses yang berbeda.
• MK menegaskan perlunya dibedakan:
1.antara “persetujuan DPR” dengan “persetujuan untuk terikat pada suatu
perjanjian (consent to be bound)”.
2.perlu juga dibedakan antara “pengesahan perjanjian menurut hukum
internasional” dengan “pengesahan menurut hukum nasional”.
PEMBEDAAN PERTAMA
•MK melalui pembedaan pertama dengan argumentasinya berhasil
mengklarifikasi distorsi publik selama ini.
•Persetujuan DPR yang hasilnya adalah UU selalu dimaknai sebagai
persetujuan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian. Padahal keduanya
adalah proses yang berbeda.
•Persetujuan DPR (proses internal) diberikan terhadap rencana Pemerintah
untuk “menyatakan terikat” pada perjanjian (proses eksternal) yang
direfleksikan melalui penyampaikan “instrument of ratification” kepada
depository perjanjian itu. Artinya, persetujuan DPR bukan dimaksudkan untuk
“consent to be bound” terhadap perjanjian itu sendiri.
•Kerancuan ini muncul karena UU No. 24 Tahun 2000 mendefinisikan istilah
‘pengesahan” sebagai “consent to be bound” (proses eksternal) namun pada
bagian lain menggunakan istilah “pengesahan dengan UU (atau Perpres)”.
Konstruksi UU ini telah memberikan makna ganda pada istilah “pengesahan”.
PEMBEDAAN KEDUA
•MK mencoba membedakan antara “pengesahan perjanjian menurut hukum
internasional” dengan “pengesahan menurut hukum nasional”. Dari argumen ini lahir
istilah baru yakni “pengesahan menurut hukum nasional”. Istilah ini oleh MK merujuk
pada produk legislasi yakni UU atau Perpres
•MK memberi makna baru bahwa pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap
suatu perjanjian internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan
suatu perjanjian internasional sebagai bagian dari hukum nasional.
•MK cenderung membedakan antara “persetujuan DPR” seperti yang dimaksud oleh
Pasal 11 UUD 1945 dengan “pengesahan menurut hukum nasional”.
•“pengesahan menurut hukum nasional” yang dimaknai sebagai “pengesahan
UU/Perpres yang sekaligus memberlakuan perjanjian kedalam hukum nasional.
•Proses ini berdiri sendiri dan terlepas dari istilah “persetujuan DPR” seperti yang
dimaksud oleh Pasal 11 UUD 1945.
•Dalam hal ini, persetujuan DPR bisa saja diberikan tanpa harus melakukan
pengesahan menurut hukum nasional.
AKIBAT
• Penafsiran ini akan melahirkan dua kali persetujuan DPR, yakni persetujuan
seperti yang dimaksud oleh Pasal 11 UUD 1945 dan persetujuan untuk
mengesahkan UU sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 UUD 1945.
• Hal ini tentunya menyisakan pertanyaan juridis yaitu :
a. Dapatkah DPR menolak mengesahkan UU pengesahan sekalipun sudah
memberika persetujuan dalam rangka Pasal 11 UUD 1945?
b. Sebaliknya, Dapatkah DPR mengesahkan UU tsb sekalipun belum ada
persetujuan?
• Problem juridis ini tentunya harus diselesaikan dalam revisi UU No. 24 Tahun
2000.
Pemberlakuan Perjanjian kedalam Hukum Nasional
Putusan MK No. 13/PUU-XVI/2018, hlm. 262.:
Tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) juga merupakan konsekuensi dari
suatu perjanjian internasional yang mempersyaratkan adanya pengesahan
(ratifikasi) sebagai pernyataan untuk terikat (consent to bound) pihak-pihak yang
menjadi peserta dalam perjanjian internasional yang bersangkutan. Dengan
demikian, tahapan pengesahan (menurut hukum nasional) terhadap suatu perjanjian
internasional adalah sekaligus sebagai instrumen yang menjadikan suatu perjanjian
internasional sebagai bagian dari hukum nasional.
•Selama ini UU pengesahan hanya dimaknai sebagai bentuk persetujuan DPR
(tindakan internal) kepada Pemerintah untuk menyatakan terikat pada suatu
perjanjian (tindakan ekternal).
•Jika perjanjian tsb telah mengikat Indonesia, maka harus dimaknai bahwa perjanjian
itu sudah menjadi bagian dari hukum nasional tanpa perlu suatu instrumen yang
memberlakukannya.
•Dalam hal ini tanggal pemberlakuan perjanjian terhadap Indonesia adalah identik
dengan tanggal pemberlakuannya kedalam hukum nasional, dan tidak pernah identik
dengan tanggal pemberlakuan UU pengesahannya.
Akibat dalam Praktik
• Pemberlakuan UU pengesahan adalah tersendiri yakni ‘pada saat
diundangkan, sedangkan pemberlakuan perjanjian itu sendiri, dan
pemberlakuannya terhadap Indonesia (dalam hal perjanjian multilateral)
selalu berbeda dengan tanggal berlakunya UU pengesahan.
• Sebagai contoh, UNCLOS 1982 disahkan melalui UU No. 17 Tahun 1985 dan
UU ini mulai berlaku tanggal 31 Desember 1985. Sedangkan UNLCOS 1982 itu
sendiri mulai berlaku, termasuk terhadap Indonesia, tanggal 16 November
1994.
• Dengan praktik ini maka tidaklah mungkin pembuat UU bermaksud memaknai
UU pengesahan sebagai memberlakukan perjanjian kedalam hukum nasional
karena akibatnya UNCLOS 1982 akan berlaku dalam hukum Indonesia
sebelum Konvensi ini sendiri lahir.
• Dalil baru MK ini telah menambah kontroversi tentang bentuk hukum UU, yang
mulai dimaknai berbeda dalam Putusan MK 2013 pada Judicial Review Piagam
ASEAN
• Pemaknaan baru atas UU pengesahan sebagai pengesahan hukum nasional dalam
perkara UU Perjanjian Internasional tampaknya mengkoreksi pandangan MK
terdahulu pada perkara Piagam ASEAN ini.
• Dalam perkara Piagam ASEAN, MK berpendapat bahwa UU pengesahan adalah
memuat suatu perjanjian kedalam format UU.
• Piagam ASEAN telah dimuat kedalam UU 38/2008 yang mengesahkannya.
• Dalam hal ini MK tidak membedakan pengesahan Piagam ASEAN dalam level
hukum internasional dan level hukum nasional, sehingga pemindahan format
treaty kedalam format UU memiliki konsekuensi bahwa negara pihak harus terikat
pada UU ini.
• Dengan demikian, MK ingin menyatakan bahwa Negara lain harus terikat pada UU
38 Tahun 2008.
• Karena tidak logis, maka MK menyarankan agar pilihan bentuk UU untuk
Perjanjian Internasional ditinjau kembali
• Kerancuan pada pandangan MK ini diakibatkan tidak dibedakannya
mekanisme pemberlakuan kedalam hukum nasional dan pemberlakuannya
dalam hukum internasional, sehingga dengan serta merta pemuatannya
dalam UU No. 38 Tahun 2008 dianggap sebagai pemberlakuan Piagam
ASEAN itu sendiri baik dalam hukum nasional maupun internasional.
• tafsir MK ini telah menuntaskan perdebatan klasik tentang makna UU
pengesahan ini, dan dengan demikian UU ini akan memiliki dua fungsi
yakni:
a.memberikan otorisasi kepada Pemerintah untuk melakukan tindakan
eksternal mengikatkan diri pada suatu perjanjian (consent to be bound)
b. sebagai instrumen untuk memberlakukan perjanjian itu kedalam hukum
nasional.
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah HUKUM PERIKATANDokumen16 halamanMakalah HUKUM PERIKATANMorales Simatupang100% (3)
- Konvensi KetatanegaraanDokumen11 halamanKonvensi KetatanegaraanDani Sayuti100% (1)
- SITI IZZATUL BARIYAH PihDokumen3 halamanSITI IZZATUL BARIYAH PihZefinanda Dwi ABelum ada peringkat
- Melisafd, 09-Erlina DKKDokumen25 halamanMelisafd, 09-Erlina DKKAlia EliyantiBelum ada peringkat
- Syifa Anindya - 203300416045 - UTSDokumen4 halamanSyifa Anindya - 203300416045 - UTSSyifa AnindyaBelum ada peringkat
- ReinhartStephanusSihite ResumePerjInDokumen6 halamanReinhartStephanusSihite ResumePerjInreinhart stephanusBelum ada peringkat
- Proses RatifikasiDokumen7 halamanProses RatifikasiMade Agus RisaldiBelum ada peringkat
- Filsafat - A - Imania Octiana H. - 2019-458Dokumen8 halamanFilsafat - A - Imania Octiana H. - 2019-458KikishwlBelum ada peringkat
- Uas-Pih-Lailatul Rohmah-05010221010Dokumen2 halamanUas-Pih-Lailatul Rohmah-05010221010Zefinanda Dwi ABelum ada peringkat
- Perjanjian Internasional Dan Amandemen UUD '45Dokumen11 halamanPerjanjian Internasional Dan Amandemen UUD '45Faeza Rezi S RajoBujangBelum ada peringkat
- 3746 - Konvensi KetatanegaraanDokumen29 halaman3746 - Konvensi KetatanegaraanGonaricha ApBelum ada peringkat
- Ranti Amya Qalbia - 10040018189 - KKH 1 Tugas KKH Hi 1 - F - 2020Dokumen5 halamanRanti Amya Qalbia - 10040018189 - KKH 1 Tugas KKH Hi 1 - F - 2020Ranti A QalbiaaBelum ada peringkat
- UAS-PIH-02-Annisa Ayu PermatasariDokumen2 halamanUAS-PIH-02-Annisa Ayu PermatasariZefinanda Dwi ABelum ada peringkat
- Uts Hukum Perjanjian Internasional (Ivanka C Belnard)Dokumen5 halamanUts Hukum Perjanjian Internasional (Ivanka C Belnard)Gege LimbersBelum ada peringkat
- Tugas Legal Drafting - Amelya Matasik - 22C20017.Dokumen10 halamanTugas Legal Drafting - Amelya Matasik - 22C20017.Eko SaputraBelum ada peringkat
- Press Relese Webinar Putusan MK-UUCKDokumen5 halamanPress Relese Webinar Putusan MK-UUCKhantu pocongBelum ada peringkat
- Tekni Pembuatan Akta IIDokumen80 halamanTekni Pembuatan Akta IIMuhammad RaizBelum ada peringkat
- Makalah Kontrak InternasionalDokumen17 halamanMakalah Kontrak InternasionalSirlia Ahlina57Belum ada peringkat
- Materi HiDokumen5 halamanMateri HiZulfa RizqiyahBelum ada peringkat
- Rahmawaty Tugas 5 HIDokumen3 halamanRahmawaty Tugas 5 HIFaizal SamanBelum ada peringkat
- Uts Kelvin Setyawan Harianja Pppu e 180200487Dokumen4 halamanUts Kelvin Setyawan Harianja Pppu e 180200487KELVIN HARIANJABelum ada peringkat
- Persetujuan DPR Atas Perjanjian InternasionalDokumen22 halamanPersetujuan DPR Atas Perjanjian InternasionalhotmailrozaqBelum ada peringkat
- 13Dokumen7 halaman13afinaluthfiazmiBelum ada peringkat
- ABSTRAKDokumen1 halamanABSTRAKtolo leeBelum ada peringkat
- Uu Perjanjian InternasionalDokumen91 halamanUu Perjanjian Internasionalarya100% (1)
- Legal Opinion 5Dokumen6 halamanLegal Opinion 5JeniBelum ada peringkat
- Laporan Individu Fix Hukum InternasionalDokumen10 halamanLaporan Individu Fix Hukum InternasionalNathania Astria CahyaningtyasBelum ada peringkat
- 4 Hal Yang Harus DiperhatikanDokumen6 halaman4 Hal Yang Harus DiperhatikanJoni JontorBelum ada peringkat
- Makalah Pilihan Hukum Kontrak Internasional Semester VII C HUKUM BISNISDokumen5 halamanMakalah Pilihan Hukum Kontrak Internasional Semester VII C HUKUM BISNISedi bhorus100% (3)
- Dalam Laporan Ini Bahasa IndonesiaDokumen4 halamanDalam Laporan Ini Bahasa IndonesiaFardi sofariBelum ada peringkat
- Kedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang SahamDokumen25 halamanKedudukan Dan Akibat Hukum Dari Perjanjian Antar Pemegang SahamYohannes AzaryaBelum ada peringkat
- Hukum Perjanjian InternasionalDokumen53 halamanHukum Perjanjian InternasionalAgung Nugraha Nova SyauqiBelum ada peringkat
- Tutorial MemasakDokumen135 halamanTutorial MemasakRosyidatul FauziyahBelum ada peringkat
- Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ArbitraseDokumen11 halamanPenyelesaian Sengketa Bisnis Melalui ArbitraseIrfan Rakhman HidayatBelum ada peringkat
- Bab5 - Daftar Pustaka - 2016142sc-pDokumen8 halamanBab5 - Daftar Pustaka - 2016142sc-pKusna EniBelum ada peringkat
- Mengupas Omnibus Law Bikin GakLaw 8Dokumen24 halamanMengupas Omnibus Law Bikin GakLaw 8Haliza Nur RifdahBelum ada peringkat
- hUKUM INTERNASIONAL TERBARUDokumen26 halamanhUKUM INTERNASIONAL TERBARUJan morado SiraitBelum ada peringkat
- Cara Penyelesaian Sengketa HpiDokumen12 halamanCara Penyelesaian Sengketa HpiArdi R MBelum ada peringkat
- Studi Kasus SHADokumen23 halamanStudi Kasus SHAVitalokaBelum ada peringkat
- Hukum Yang Berlaku Dalam KontrakDokumen4 halamanHukum Yang Berlaku Dalam KontrakDavid KamBelum ada peringkat
- Benar Bahwa Isi Pasal 22D UUDDokumen3 halamanBenar Bahwa Isi Pasal 22D UUDsiti aisyahBelum ada peringkat
- Legal Opinian TerbaruDokumen11 halamanLegal Opinian TerbaruRAMLIBelum ada peringkat
- Sistem Hukum IndonesiaDokumen8 halamanSistem Hukum IndonesiaCitraBelum ada peringkat
- Keabsahan Perjanjian Baku (HK Kontrak Bisnis)Dokumen15 halamanKeabsahan Perjanjian Baku (HK Kontrak Bisnis)Adi DoanksBelum ada peringkat
- Supremacy of The Constitution-constitutionalismKETERTINGGIAN PERLEMBAGAANDokumen20 halamanSupremacy of The Constitution-constitutionalismKETERTINGGIAN PERLEMBAGAANanaqi99Belum ada peringkat
- Latar Belakang Hukum InternasionalDokumen9 halamanLatar Belakang Hukum InternasionalezmixxyBelum ada peringkat
- Sengketa Perdata Internasional KBC - Pertamina - PLNDokumen30 halamanSengketa Perdata Internasional KBC - Pertamina - PLNChikichikoman100% (3)
- Mediasi Perkara Di PengadilanDokumen25 halamanMediasi Perkara Di PengadilanLydia HabaBelum ada peringkat
- Tugas HpiDokumen5 halamanTugas HpiDavid PanjaitanBelum ada peringkat
- Ilneg TalitaDokumen5 halamanIlneg TalitaDamarani BangwolBelum ada peringkat
- PKN Xi Bab 5Dokumen40 halamanPKN Xi Bab 5Harry Andrian Syah100% (1)
- Analisis Putusan MK Tentang OmnibuslawDokumen6 halamanAnalisis Putusan MK Tentang Omnibuslawencep iik muzakirBelum ada peringkat
- Makalah Hukum Pajak IchaDokumen9 halamanMakalah Hukum Pajak IchaIcha ChoerunnisaBelum ada peringkat
- Damos Dumoli AgusmanDokumen11 halamanDamos Dumoli AgusmanRosita NovandaBelum ada peringkat
- Hukum Kontrak InternasionalDokumen12 halamanHukum Kontrak Internasionalnurul ayu tri ulfiahBelum ada peringkat
- Bahan Kuliah ASKUM Baru 2019Dokumen115 halamanBahan Kuliah ASKUM Baru 2019Hizkia RialBelum ada peringkat
- Konklusi Teori HukumDokumen6 halamanKonklusi Teori HukumharriBelum ada peringkat
- Bab 10Dokumen4 halamanBab 10Nindi RizkiBelum ada peringkat
- Proses Ratifikasi Hukum Internasional Menurut UU No 5 Tahun 2000Dokumen3 halamanProses Ratifikasi Hukum Internasional Menurut UU No 5 Tahun 2000Krisna HidayatullahBelum ada peringkat
- Naskah Akademik Pendirian Badan Pengatur Jalan TolDari EverandNaskah Akademik Pendirian Badan Pengatur Jalan TolPenilaian: 3.5 dari 5 bintang3.5/5 (8)