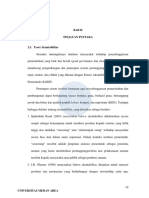Otonomi Daerah Dan
Diunggah oleh
Heepy Hariyadi0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
143 tayangan57 halamanbahan
Hak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen Inibahan
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
143 tayangan57 halamanOtonomi Daerah Dan
Diunggah oleh
Heepy Hariyadibahan
Hak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOCX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 57
OTONOMI DAERAH DAN
EKSISTENSI DESA PAKRAMAN
DI BALI
Oleh: Wayan Gede Suacana
Democracy, at least at present, is the best form of governance, but by no means a perfect one. In
democracy, one has the freedom. When democracy is misunderstood, however, and a freedom
misinterpreted, the result is anarchy.
(Mahathir Mohamad, Achieving True Globalization, 2004).
Pendahuluan
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam rangka pengakuan dan
penguatan integrasi nasional, disamping perkembangan paradigma pemerintahan saat sekarang yang mulai
menuju pada prinsip Clean Government dan Good Governance. Prinsip pertama menginginkan agar struktur
pemerintahan menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang berasal dari rakyat, serta menghindari terjadinya
penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan (abuse of power and authority). Sedangkan prinsip kedua,
menghendaki adanya satu mekanisme kerja, dimana aktivitas pemerintahan berorientasi pada terwujudnya
keadilan sosial. Disamping itu, pemerintah diharapkan mampu secara maksimal melaksanakan tiga fungsi dasar:
service, regulation dan empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan masyarakat secepat, sedekat
dan setepat mungkin serta melaksanakan demokrasi di/ dari bawah (grassroot democracy).
Kedua prinsip tersebut hendak meletakkan pemerintah tidak lagi sebagai inisiator aktivitas pada tataran
masyarakat, namun sebagai organisator aktivitas yang muncul dari masyarakat. Beberapa butir pengembangan
secara implisit tampak dalam penekanan implementasi otonomi daerah yang dianut dalam UU 32/ 2004, seperti:
demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keragaman daerah.
Otonomi Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32/ 2004 sangat diharapkan dapat memberikan
manfaat yang besar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini selain karena tujuan
utamanya adalah untuk mengembangkan kehidupan yang demokratis, tetapi juga ikut mendorong upaya
pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, memperkuat kedudukan dan kemampuan pemerintah daerah,
meningkatkan pelayanan umum serta meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah yang
berkelanjutan.
Dalam mewujudkan amanat tersebut diatas berbagai persoalan dan kendala masih banyak dijumpai.
Diantaranya, adalah masih banyak aparat pemerintah daerah sebagai implementator kebijakan tersebut, maupun
masyarakat umum yang belum memahami makna otonomi daerah yang diperluas ini. Sebagai akibatnya, masih
terjadinya kebingung aparat di daerah dalam mengatur wilayah dan sumber-sumber pendapatannya, munculnya
konflik-konflik kepentingan antar daerah, ketiadaan melakukan diskresi, karena harus menunggu petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat, dan sebagainya. Segala persoalan dan kendala tersebut
praktis akan menghambat pelaksanaan otonomi daerah di tingkat bawah.
Dalam pada itu, semangat UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga hasil amandemen UUD
1945 pasal 18 b ayat (2) dengan tegas telah memberikan peluang untuk membangkitkan atau menghidupkan
kembali otonomi asli dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa. Dengan begitu, sangat
memungkinkan bagi Balitentu, setelah melalui kajian mendalam, untuk menonjolkan atau mengangkat
keberadaan desa pakraman menjadi desa seperti yang dimaksudkan oleh UU no. 32 tahun 2004. Hal ini
didukung oleh sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa saat sekarang, yang ternyata sangat
menekankan aspek politis terbukti dengan pembentukan Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam rangka menjamin
pelaksanaan demokrasi di/ dari bawah (grassroot democracy). Tetapi, apakah tataran konseptual ini sudah
didukung oleh kondisi riil dalam tataran praksis ?
Kondisi Riil Otonomi Daerah Pasca UU 32/2004
Implementasi otonomi daerah sebagai konsekuensi pemberlakukan UU 32/ 2004 tidak terlepas dari azas
desentralisasi yang menjadi landasan bagi pembentukan pemerintah daerah. Sejak awal 1980-an beberapa
pakar desentralisasi dan administrasi pembangunan, seperti Diana Conyers, Dennis Rondinelli dan G. Shabbir
Cheema, telah memelopori pembahasan desentralisasi di negara-negara berkembang. Bank Dunia juga sangat
mendorong negara-negara penerima donor untuk melaksanakan desentralisasi. Konsekuensinya, hampir semua
negara sedang berkembang menyatakan diri melaksanakan paham desentralisasi, walaupun dalam prakteknya
tidak atau belum bisa dikategorisasikan sebagai desentralisasi.
Desentralisasi sering dimaknai sebagai prinsip pembelahan wilayah negara menjadi wilayah-wilayah yang lebih
kecil, dan wilayah-wilayah itu dibentuk institusi administrasi untuk melayani kebutuhan orang atau masyarakat
disatu tempat. Hal ini penting dilakukan sebab pada dasarnya pemerintah melaksanakan tiga fungsi dasar:
service, regulation dan empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan masyarakat secepat, sedekat
dan setepat mungkin. Untuk dapat mewujudkan desentralisasi, setidaknya diperlukan: resources, structures,
technology, support dan leadership, serta tiga kondisi berikut:
1. Pengakuan terhadap pluralisme masyarakat, yang tercermin dari kerelaan atau keikhlasan pemerintah
nasional menyerahkan wewenang pemerintahan;
2. Membuka kesempatan masyarakat di daerah untuk mengatur diri sendiri melalui local self-government,
sebab fokus aktivitas pemerintahan adalah untuk mensejahterakan rakyat;
3. Pengetrapan model pembangunan sesuai dengan kekhasan daerah.
Pulau Bali sebagai salah satu daerah pengemban amanat otonomi daerah tentu saja secara relatif juga
membutuhkan ketiga kondisi seperti tersebut diatas agar implementasi otonomi daerah dapat terlaksana dengan
baik. Pasca dua kali peledakan bom di Kuta dan Jimbaran beberapa tahun lalu hendaknya tidak menjadikan
semangat pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerahnya juga sirna. Sebaliknya, segenap
komponen pemerintah dan masyarakat Bali harus segera bangkit, atau setidaknya mampu menumbuhkan
kesadaran bersama (collective conciousness) bahwa otonomi mestinya segera dilaksanakan secara proaktif dan
penuh inisiatif untuk bisa segera membangun Bali kembali dengan ketersediaan sumber daya alam, manusia
dan dana yang dimiliki.
Dari berbagai bentuk persoalan otonomi yang dihadapi Bali, salah satu isu strategis yang perlu mendapatkan
perhatian secara serius adalah berkaitan dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena telah menimbulkan diskursus yang hangat dan kontreversial,
namun sampai saat ini belum juga ada kesepahaman pendapat sebagai kristalalisasi pilihan yang dapat
disepakati dan diterima oleh berbagai pihak.
Apabila alur perkembangan pemikiran tentang sistem penyelenggaraan desa di Bali ini diikuti secara cermat,
maka setidaknya ada empat ranah/ aliran pemikiran yang pernah mengemuka dan muncul ke permukaan, yaitu:
Pertama, Kelompok pemikiran yang menghendaki sistem pemerintahan dan kehidupan desa di Bali dibiarkan
seperti apa adanya sekarang ini . Desa Dinas dan Kelurahan bertugas mengurus hal-hal yang berhubungan
dengan masalah-masalah administrasi pemerintahan dan pembangunan, sedangkan Desa Pakraman
menangani hal-hal yang berhubungan dengan adat Bali dan Agama Hindu. Kedua, Kelompok pemikiran yang
merupakan reaksi dari kelompok pemikiran pertama, yang bernada emosional dan menghendaki penghapusan
desa dinas dan kelurahan serta menyerahkan segala urusan desa kepada desa pakraman. Ketiga, merupakan
bentuk kompromi dengan kelompok pemikiran yang pertama. Kelompok pemikiran ini menghendaki agar kedua
desa tetap dipertahankan dan hidup berdampingan sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Namun,
dituntut adanya ketegasan batas wilayah kewenangan dan anggaran yang disediakan bagi masing-masing desa
sehingga tidak muncul kesan bahwa desa dinas dianakemaskan dan desa pakraman dianaktirikan. Keempat,
boleh dikatakan sebagai bentuk kompromi dengan kelompok pemikiran kedua. Dalam hal ini dikemukakan
bahwa di Bali hanya ada satu desa, yaitu desa adat/ pakraman. Desa ini dikendalikan oleh perangkat prajuru,
dengan pucuk pimpinan yang disebut bendasa adat. Perangkat desa adat/ pakraman terdiri atas dua bidang,
yaitu: (1) Bidang Agama Hindu dan Adat Bali (AHA), (2) Bidang Administrasi Pemerintahan (AP). Bila pendapat
ini yang dipilih berarti dualisme desa hilang. Di Bali hanya akan ada satu desa yaitu desa adat/ pakraman.
Tugas-tugas yang selama ini dijalankan oleh desa dinas/ kelurahan, selanjutnya akan menjadi urusan Bidang
Administrasi Pemerintahan (AP) dalam satu desa pakraman.
Setiap ranah/ aliran pemikiran tersebut, mempunyai kelompok pendukung dengan dasar pembenar dan
argumentasinya masing-masing. Prinsip-prinsip demokrasi yang dianut sekarang ini, jelas memberikan peluang
yang sangat besar bagi variasi dan perbedaan pendapat dalam masyarakat. Tetapi, prinsip-prinsip tersebut
masih memungkinkan untuk bersifat akomodatif yang bermuara pada sebuah kesepahaman dan kesepakatan,
karena jelas semua kebenaran yang diperdebatkan relatif sifatnya. Perubahan situasi dan kondisi merupakan
faktor determinan yang bisa mengalihkan kebenaran ranah/ aliran pemikiran yang satu ke ranah/ aliran lainnya.
Dengan begitu, upaya dialog, kajian dan penelitian secara lebih intensif dan mendalam atas berbagai ranah/
aliran pemikiran tersebut masih dibutuhkan dengan melibatkan lebih banyak pemerhati, dan praktisi desa
pakraman.
Beberapa ranah/ aliran pemikiran tersebut, sedikit banyak masih mengandung muatan dan nuansa romantisme
yang menyelimuti alam pemikiran pikiran penggagasnya, karena pada dasarnya mereka berobsesi
memberdayakan dan melestarikan desa pakraman dengan mengangkat eksistensi ke tingkat republik desa
lengkap dengan sistem yang berlaku didalamnya seperti sistem kolegial konsensus. Bagi ranah/ aliran
pemikiran yang menginginkan pemunculan kembali nilai-nilai lokal sebagai dasar pijak penyelenggaraaan
pemerintahan desa, semestinya juga menyadari dan bertindak selektif bahwa beberapa dari nilai-nilai lokal
tersebut sesungguhnya sudah banyak yang terdistorsi secara mendasar di masa kolonialisme dulu dan banyak
dimanfaatkan untuk kepentingan status quo pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Bahkan apa yang
dianggap sebagai nilai tradisional adalah justru produk intervensi kolonial.
Satu hal yang juga patut mendapatkan perhatian semua pihak adalah munculnya kekhawatiran bahwa
kebangkitan nilai-nilai lokal akan mengarah kepada gejala primordialisme yang bermuatan kekerasan serta
kembalinya kultur feodalisme yang tidak demokratis. Rasa khawatir seperti ini memang perlu diperhatikandan
cukup beralasan, sehingga perlu direspon dengan melakukan berbagai upaya pengkajian yang lebih seksama
agar tugas mulia untuk memberdayakan desa pakraman, tidak justru membawa desa pakraman ke arah
penyelenggaran pemerintahan dengan semangat primordialisme sempit yang merupakan pengingkaran terhadap
nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.
Sesungguhnya tidaklah cukup kalau ranah/ aliran pemikiran yang dipilih nantinya sekadar memberikan harapan
dan sanjungan yang terlalu besar pada keberadaan desa pakraman, tanpa disertai oleh kajian obyektif tentang
keberadaannya. Dalam kenyataannya, sebagian besar desa pakraman memang sudah bisa dikategorikan
sebagai lembaga tradisional yang kuat dan tangguh dalam menghadapi berbagai hempasan perubahan sosial,
tetapi kondisi yang juga harus diakui adalah masih banyak diantara desa-desa pakraman yang ada pada saat ini
masih dalam keadaan kurang berdaya (empowerlesness) dalam menghadapi perkembangan jaman. Bahkan
upaya dari pemerintah Provinsi Bali untuk mengayomi desa pakraman dengan memberlakukan Perda Nomor 3
tahun 2001 tentang Desa Pakraman, sebagai pengganti Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1986 tentang
Kedudukan, Fungsi dan peranan Desa Adat sebagai kesatuan Masyarakat Hukum Adat, yang sudah dianggap
tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, belumlah dapat dikatakan memberikan jaminan bahwa desa
pakraman pasti akan menjadi lebih berdaya. Bahkan dapat dikatakan untuk sementara ini, justru Perda Nomor 3
tahun 2001 tentang Desa Pakraman telah menimbulkan rasa kebingunan-kebingunan baru bagi prajuru desa
pakraman. Hal ini antara lain disebabkan oleh proses pembuatan Perda yang terkesan tergesa-gesa, serta
kurangnya penyerapan aspirasi dari desa-desa pakraman pada proses pembuatan perda tersebut. Di samping
itu, masih adanya kecenderungan untuk mengatur keberadaan desa pakraman, yang karena keunikan tata
kehidupannya, semestinya Perda semacam ini cukup hanya memberikan pengakuan saja atas segala keunikan
yang dimiliki tersebut.
Berbagai Kendala di Tingkat Desa
Beberapa kendala untuk menjadikan desa pakraman sebagai penyelenggara tunggal pemerintahan dan
menurunkan konsep otonomi di tingkat desa pakraman antara lain:
1. Landasan filosofis religius Desa Pakraman, berkaitan dan mencerminkan keberadaan lembaga yang
bernafaskan agama Hindu, sehingga akan menyulitkan peluang bagi warga non-Hindu menjadi anggota atau
warga desa pakraman.
2. Dalam hal teritorial, disamping adanya ketidakseimbangan luas wilayah, juga terdapat beberapa wilayah di
Bali yang berada di luar kekuasaan desa pakraman.
3. Organisasi Desa Pakraman bersifat tradisional, lokal, hanya sampai di tingkat desa, tidak ada
hubungannya dengan desa lainnya. Kesannya memang mandiri/ otonom, tetapi di balik semua itu desa
pakraman kerdil bagaikan bonzai, terisolir dan rawan konflik.
4. Sebagai warisan masa lalu, struktur kepengurusan Desa Pakraman masih sangat sederhana, fungsi-fungsi
atau jabatan-jabatan yang ada misalnya kesinoman, petajuh, prajuru dan lain-lainnya hanya mampu
melaksanakan tugas/ peran sederhana kurang lebih sebatas tugas upacara yadnya. Begitupun manajemennya
masih sangat lemah, sederhana/ tradisonal, masih jauh tertinggal dari manajemen modern dengan teknologinya
yang canggih. Disamping itu, cara pemilihannya, cara kerjanya dan olih-olihannya, hampir semua berjalan
dengan kuna dresta serta adanya kecenderungan menghindar menjadi pengurus (prajuru) makin melemahkan
kepemimpinan desa pakraman.
5. Sumber daya manusia yang ada di desa pakraman, bukan sekedar diragukan kualitasnya, namun jumlah
mereka juga semakin menurun. Hal ini merupakan akibat logis dari mobilitas sosial yang merupakan produk
modernisasi. Warga desa yang terdidik, profesional dan terampil karena berbagai macam alasan, jarang
menetap di desa karena kurangnya lapangan kerja. Kondisi seperti ini jelas akan sangat menyulitkan bagi desa
pakraman untuk berotonomi.
6. Keterbatasan awig-awig, karena pada dasarnya hanya mengatur warganya (Hindu) dan yang unik dalam
batas-batas teritorialnya
7. Ketiadaan jaringan desa pakraman dan adanya fanatisme desa pakraman yang berlebihan, menyebabkan
kesulitan dalam melakukan hubungan koordinasi antar desa pakraman, sehingga mudah memicu selisih paham
dan konflik antara desa pakraman satu dengan lainnya.
8. Kelambatan dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi persoalan yang semakin kompleks karena
keadaan sistem sosial yang rumit.
9. Demokrasi dijalankan secara parsial, karena tidak melibatkan krama perempuan.
10. Belum terbiasa membicarakan potensi konflik secara terbuka. Membahas potensi dan manajemen konflik
masih dianggap tabu.
11. Bagaimana menempatkan dan mengharmoniskan hubungan desa pakraman yang masih bersifat tradisional
di satu pihak, dengan negara modern yang bersifat demokratis di pihak lain (terjadi perbenturan antara nilai
kebersamaan versus nilai perbedaan)
12. Akibat dari semua itu kondisi desa pakraman menjadi marginal, tidak mampu berbuat banyak bagi
warganya, tidak mampu membangun dan mengembangkan dirinya secara konseptual dan strategis, sebaliknya
justru menjadi obyek pembangunan.
Berbagai kendala tersebut juga diperkuat oleh tingginya tingkat diferensiasi sosial masyarakat Bali yang juga
sangat rentan terhadap berbagai potensi konflik. Beberapa potensi konflik, bukan saja yang bersifat laten,
melainkan yang sudah termanifestasi secara empirik dalam kehidupan sosial masyarakat di Bali antara lain:
1. Konflik antar etnis khususnya etnis Bali dengan non-Bali yang menguat pasca bom Bali I dan II. Potensi ini
semakin membesar dengan munculnya kristalisasi etnis di antara manusia Bali yang semakin membuat tembok
pembatas antara kekitaan dengan kemerekaan (we-ness dengan other-ness) seiring dengan implementasi
kebijakan penertiban penduduk pendatang oleh pecalang akhir-akhir ini. Beberapa wacana sosial juga sudah
menjadi indikator jelas mengenai hal ini. Kenyataan ini berasosiasi dengan proses indigenisasi masyarakat Bali
serta meningkatnya in-migrasi dari luar pulau.
2. Konflik antar-kelas, yang berlatar belakang ekonomi. Masyarakat kelas ekonomi bawah yang merasa
termaginalisasi sudah mulai memposisikan diri secara frontal dengan kaum kaya, khususnya pengusaha
(investor). Tindakan anarkhi pun sempat menggejala. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pemogokan kaum buruh/
karyawan di berbagai industri pariwisata, serta pawai ogoh-ogoh yang sempat dipaksakan masuk ke hotel
karena warga merasa masih kurangnya uang kompensasi hotel yang diberikan bagi keperluan desa pakraman.
3. Konflik antar kelompok homo-aequalis dan homo-hierarchicus. Kelompok homo-aequalis dengan ideologi
egalitarianisme ingin melihat masyarakat Bali yang demokratis, tanpa adanya diskriminasi atas dasar kelahiran
(keturunan). Di pihak lain, kelompok homo-hierarchicus dengan segala upaya mempertahankan status quo
hirarki tradisionalnya. Konflik yang sudah berlangsung sejak tahun 1920-an ini secara awam dikenal sebagai
konflik kasta (walaupun secara akademis istilah ini kurang tepat).
4. Konflik antara Hindu tradisional-ritualistik dengan Hindu modern-humanistik. Meskipun tidak terlalu
menonjol, sudah ada gejala-gejala pertentang antara penganut Hindu tradisi, yang menekankan pada ritus-ritus
besar dengan penekanan Bali, dengan Hindu modern yang menekankan pengamalan Hindu dengan konsep
back to Veda , yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai aliran baru. Kristalisasi indikator kontemporer
masalah ini ditambah dengan butir poin ketiga di atas sangat jelas tampak dengan adanya dualisme Parisadha
Bali yakni Parisadha versi Campuhan dan Besakih yang belum juga bisa disatukan hingga kini.
5. Konflik internal desa pakraman yang seringkali dipicu oleh persoalan-pesoalan pribadi menyangkut
pelaksanaan hak dan kewajiban seorang warga di desa pakraman. Konflik ini tidak jarang berujung pada
tindakan pengusiran (kasepekang) dari desa pakraman terhadap warga yang dianggap melanggar ketentuan
awig-awig atau tidak aktif dalam aktivitas adat.
Berkaitan dengan berbagai potensi konflik tersebut, makin menyadarkan kita bahwa kehidupan sosial
masyarakat Bali tidak selamanya kondusif bagi tumbuhnya toleransi dan demokrasi, apalagi dalam masyarakat
Bali yang pemilahan, fragmentasi serta polarisasi sosialnya cukup tinggi. Mengikuti teori integrasi sosial Furnivall
sejumlah properti hubungan-hubungan sosial yang biasa kita temukan sebagai konsekuensi dari struktur
masyarakat yang multikultur adalah: 1) kecenderungan berkembangnya perilaku konflik di dalam hubungan-
hubungan antar berbagai komunitas atau kelompok; 2) berkembangnya kecenderungan para pelaku konflik
melihat konflik bukan sebagai suatu game melainkan sebagai suatu total war; dan 3) berkembangnya proses
integrasi sosial berdasarkan dominasi oleh suatu komunitas atau kelompok di atas komunitas atau kelompok
lain.
Dalam sistem sosial yang tingkat pemilahannya tidak lagi bersifat membaur (cross cuting) akan tetapi bahkan
bersifat kumulatif, maka toleransi dan demokrasi akan sulit untuk dipelihara, sebab biasanya konflik yang
ditimbulkannya tidak lagi bersifat memusat (centripetal) akan tetapi bersifat memencar (centrifugal). Dalam
situasi konflik yang sifatnya memusat maka konflik akan menjadi sangat sulit diselesaikan.
Kondisi diferensiasi sosial yang demikian serta berbagai ancaman potensi konflik yang menyertainya makin
menyadarkan kita bahwa upaya untuk lebih mengaktualisasikan dan mengimplementasikan nilai-nilai
kebersamaan dalam masing-masing masyarakat desa pakraman di Bali adalah merupakan sebuah keniscayaan.
Beberapa Alternatif Pemikiran
Berhubung dengan berbagai kendala dan persoalan tersebut, ada beberapa alternatif pemikiran untuk lebih
memberdayakan peranan Desa Pakraman, antara lain:
1. Restrukturisasi desa pakraman dilakukan dengan cara melepaskan dari belenggu isolasi yang selama ini
dialami, membuka jalur informasi dan komunikasi baik vertikal maupun horisontal, sehingga tidak lagi bersifat
tertutup dan lokal, melainkan harus bersifat terbuka dan regional meliputi seluruh daerah Bali.
2. Pemberdayaan desa pakraman dalam rangka bottom up strategy dan peningkatan partisipasi krama desa.
Dalam upaya ini, kekhasan ragam/ diversifikasi budaya dari masing-masing wilayah desa pakraman agar tetap
dipertahankan dan dijaga keberadaannya agar berkelanjutan menurut konsep desa, kala dan patra. Disamping
itu, jabatan prajuru tidak lagi sekadar ngayah untuk kepentingan adat dan agama, tetapi juga sebuah jabatan
profesional (mendapat penghasilan dan fasilitas).
3. Desa Pakraman harus tetap memiliki kemampuan sebagai wahana integrasi sosial, yang memupuk serta
mengembangkan solidaritas/ kolektivisme krama adat, dan tidak justru sebagai wahana bagi terpeliharanya
potensi konlik laten. Dalam rangka mamanajemeni potensi konflik, beberapa konsep, seperti: sagilik-saguluk
salunglung sabayantaka, paras-paros sarpanaya perlu direvitalisasi. Konsep perbedaan tetap dikembangkan
tetapi bermuara pada kebenaran dan tujuan bersama.
4. Perlu dibentuk forum komunikasi antar Desa Pakraman sebagai sarana untuk memperlancar interaksi antar
Desa Pakraman yang sampai sekarang memang sangat minim, serta untuk mengatasi berbagai kendala,
kelemahan dan tantangan yang dihadapi Desa Pakraman ke depan. Di samping itu peran dan kinerja Majelis
Desa Pakraman (MDP) Provinsi Bali dan Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) di masing-masing kabupaten
bisa lebih dioptimalkan.
5. Perlu peningkatan kualitas pemimpin/ prajuru Desa Pakaraman pada masa mendatang, yang tidak semata-
mata bermodalkan kejujuran dan pengetahuan adat/ Agama Hindu semata, tetapi juga memiliki kualitas
pendidikan, wawasan politik, ekonomi keluarga dan pengetahuan umum yang memadai.
6. Peningkatan peranan Desa Pakraman dalam bidang ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pariwisata,
hukum, keagamaan dan lain-lain. Bila di sektor moneter peranan Desa Pakraman, melalui Lembaga Perkreditan
Desa (LPD), sudah mulai menampakkan hasil, maka pemberdayaan ekonomi Desa Pakraman di sektor riil perlu
ditingkatkan melalui Badan Usaha Milik Desa Pakraman (BUMDP), seperti: Koperasi Desa Pakraman, Pasar
Desa Pakraman hingga akhirnya dapat membantu usaha-usaha kecil lainnya, sehingga ekonomi rakyat dapat
lebih diberdayakan. Demikian juga misalnya lembaga keamanan, menurut catatan tahun 2003 jumlah Desa
Pakraman di Bali seluruhnya 1404. Kalau tiap Desa Pakraman memiliki 1 peleton pecalang, maka jumlah
seluruhnya menjadi 1404 peleton pecalang, cukup untuk mengamankan Bali. Masalahnya sekarang adalah
bagaimana menggali potensi itu dan me-manage dengan baik agar efektif dan efisien dalam tugas pengamanan.
7. Hubungan krama Desa Pakraman dengan LSM/ NGO yang peduli/ bernafaskan adat, budaya dan agama,
perlu dijaga agar masing-masing tetap berdiri sendiri, saling menghormati. Biarkan LSM/ NGO itu tumbuh dan
berkembang di luar organisasi krama adat. Para anggotanya adalah pemikir kritis dan kreatif yang sangat peduli
pada pembangunan Bali, karena itu wajib didukung eksistensinya. Desa Pakraman mengharapkan pengabdian
yang tulus dari LSM/ NGO, bebas dari kepentingan pribadi, kelompok dan aliran politik.
8. Mempererat hubungan antara Desa Pakraman dengan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) yang
memang sedari dulu bersifat sangat substansial, karena totalitas kehidupan masyarakat adat didasarkan, dijiwai
oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip Agama Hindu disamping seluruh Krama Adat adalah umat Hindu. Hubungan
yang sangat hakiki ini menjadikan Desa Pakraman dan PHDI seakan-akan menyatu, saling membutuhkan dan
saling mengisi.
Penutup
Dalam era demokrasi dan otonomi yang sangat luas sekarang ini, diharapkan peran aktif semua pihak yang
berkompeten, dalam rangka menemukan format pemerintahan desa yang paling tepat dan sesuai dengan
kondisi riil kemasyarakatan di Bali. Hal ini, demi untuk peningkatan keberdayaan desa pakraman, yang sampai
saat sekarang masih tetap diharapkan tetap sebagai benteng terakhir bagi kelangsungan budaya, adat Bali
serta Agama Hindu. Jangan sampai kebebasan berdemokrasi dan berotonomi itu lalu kebablasan menjadi
tindakan anarki yang merusak eksistensi desa pakraman sebagaimana diingatkan oleh Mahathir Mohamad
mantan Perdana Menteri Malaysia pada bagian awal tulisan ini.
J U M A T , 0 2 J U L I 2 0 1 0
Prospek Kebijakan Otonomi Daerah Bagi Daerah Istimewa dan Desa
Menurut UU No 22/1999
Abstract:
Lahirnya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya telah memberi
keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara otonom. bahkan,
desa yang menurut UU Nomor 5 tahun 1974 lebih merupakan wilayah administrasi, akan
dikembalikan kepada otonomi aslinya. Demikian pula dengan keberadaan suatu daerah istimewa
(cq. Yogyakarta). Dengan adanya perubahan kebijakan ini, tentu akan membawa implikasi-
implikasi tertentu baik pada desa maupun pada daerah istimewa. Secara prediktif dapat
disimpulkan bahwa prospek pengembangan daerah istimewa dan desa menurut UU Nomor 22 tahun
1999 sangat baik, karena secara historis memiliki hak asal-usul yang melekat padanya sejak
sebelum terbentuknya Negara Indonesia. Dan kenyataan inilah yang sedang berkembang dalam
wacana publik dewasa ini.
Pendahuluan
Akhir-akhir ini, tuntutan daerah untuk diberi (baca: memiliki) otonomi yang seluas-luasnya
makin menonjol. Bahkan, beberapa daerah memilih untuk memisahkan diri dari
Negara Kesatuan RIdan mendirikan negara baru, misalnya Sulawesi Selatan dan Aceh.
Kondisi seperti ini oleh sebagian orang dinilai sebagai benih-benih terjadinya disintegrasi
bangsa. Sebaliknya, oleh sebagian orang lainnya dinilai bahwa pemberian otonomi yang
seluas-luasnya ini merupakan satu-satunya jalan keluar untuk mempertahankan integrasi
nasional.
Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, fenomena tentang daerah yang memiliki otonomi
seluas-luasnya tadi sesungguhnya bukan hal yang baru bahkan terlebih lagi bukan sesuatu
yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. Demikian pula, keberadaan desa-desa
adat yang memiliki susunan asli ternyata tidak menimbulkan gagasan-gagasan pemisahan
diri dari unit pemerintahan yang lebih luas. Oleh karena itu, otonomi luas sesungguhnya
bukan paradoksi bagi integrasi bangsa dan sebaliknya. Artinya, cita-cita memberdayakan
daerah melalui kebijakan otonomi luas tidak perlu disertai dengan sikap syak wasangka
yang berlebihan tentang kemungkinan perpecahan bangsa. Kekhawatiran ini justru akan
menunjukkan bahwa pemerintah pusat memang kurang memiliki political will yang kuat
untuk memberdayakan daerah.
Dengan demikian, ide untuk kembali menyeragamkan sistem pemerintahan daerah dengan
alasan untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa antara lain melalui penghapusan
daerah istimewa dan penyeragaman pemerintah desa, adalah sangat tidak kontekstual
dan tidak konseptual.
Mengingat hal tersebut, maka makalah ini mencoba membaca ke depan mengenai prospek
daerah-daerah yang memiliki hal asal-usul serta susunan asli, yang oleh karenanya dapat
dikategorikan sebagai daerah istimewa. Pembahasan akan difokuskan kepada kasus DIY
serta prospek otonomi desa pada umumnya, yang disesuaikan dengan norma yuridis baru
sebagaimana diatur dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Prospek Otonomi pada Daerah Istimewa (Kasus DIY)
Harus diakui bahwa sebagian masyarakat kita kurang mengetahui secara persis mengapa
DIY memiliki hak-hak khusus yang membedakannya dengan propinsi lain di Indonesia.
Bahkan seorang gubernurpun (c.q. Suwardi) sangat terlihat tidak memiliki pengetahuan
tentang itu. Saat menjabat Gubernur Jawa Tengah, Suwardi mengemukakan ide
penggabungan DIY ke dalam Propinsi Jawa Tengah. Ide ini dianggap sebagai gugatan
terhadap eksistensi DIY, yang jika dipenuhi akan menyebabkan hilangnya sebutan, sifat
dan kedudukan istimewa bagi DIY.
Dengan kata lain, hak-hak asal usul yang dimiliki oleh DIY akan musnah dengan serta
merta, sementara UUD 1945 secara eksplisit mengakui dan menjamin keberlangsungan
hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu, pertanyaan yang
paling mendasar dalam konteks ini adalah, bagaimana prospek daerah istimewa
khususnya DIY pada masa-masa yang akan datang?
Pertanyaan ini penting diajukan karena semakin lama orang semakin kurang menghayati
makna dan latar belakang historis, dan ini akhirnya membawa kepada pemikiran untuk
menghapuskan status daerah istimewa.
Memang patut dimaklumi, keberadaan DIY yang merupakan bagian integral dari NKRI
sering mengundang kecemburuan daerah-daerah di sekitarnya. Hal ini tidak terlepas dari
adanya hak-hak istimewa yang dimiliki DIY seperti dalam hal pengangkatan Kepala Daerah,
bidang pertanahan, dan sebagainya.
Dalam berbagai bidang tadi, terdapat kesan seolah-olah DIY memiliki legitimasi untuk
berbeda. Pada gilirannya, berbagai exclusivisme tadi memunculkan pertanyaan, apakah
tidak menjadikan berkembangnya anggapan negara dalam negara serta mengaburkan
pengertian negara kesatuan? Untuk menjawab permasalahan ini, maka pertama sekali
harus diketahui tentang ketentuan daerah istimewa serta latar belakang historis yang
melekat pada DIY.
Pada dasarnya, terbentuknya Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Paku Alaman menjadi
Daerah Istimewa Yogyakarta disebabkan oleh dua faktor pokok, yaitu hak asal-usul dan
susunan asli, serta peran historis dalam perjuangan kemerdekaan RI.
Mengenai hal asal-usul dan susunan asli ini, pasal 18 UUD 1945 secara tegas menyebutkan
sebagai berikut: "..... dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam
sistem pemerintahan negara, dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa". Ini berarti bahwa UUD 1945 mengakui kenyataan historis bahwa sebelum
proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah Swapraja yang
memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai urusan di
daerahnya.
Selanjutnya dalam penjelasan pasal 18 disebutkan bahwa: Oleh karena Negara Indonesia
itu adalah eenheidstaat, maka Indonesia tak mempunyai daerah dalam lingkungannya
yang bersifat staat juga Dalam teritoir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250
Zelfbestuurende-landschappen daerah-daerah itu mempunyai susunan yang asli, dan
oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.
Berdasarkan ketentuan itu, secara teoritis dalam Daerah Istimewa terdapat dua macam
hak, yaitu hak yang telah dimiliki sejak semula (hak yang bersifat autochtoon) atau hak
yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari Negara Indonesia, dan
hak yang dimiliki berdasarkan pemberian pemerintah.
Perwujudan dari hak-hak asal-usul atau yang bersifat autochtoon itu bisa bermacam-
macam. Hak itu dapat berupa hak untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan
pemerintahan tertentu, hak untuk memberikan beban kewajiban tertentu kepada
masyarakat, hak untuk menentukan sendiri cara pengangkatan dan pemberhentian
pimpinan daerah, dan lain-lain. Mempertahankan susunan asli juga termasuk hak asal-usul
dari daerah yang bersifat istimewa. Adapun makna susunan asli sebagaimana tercantum
dalam penjelasan pasal 18 angka II, adalah susunan yang sudah berlaku sejak semula.
Meski demikian bukan berarti bahwa selama-lamanya tidak boleh diadakan perubahan
terhadap organisasi Daerah Istimewa tersebut.
Uraian dibawah ini akan semakin memperlihatkan bahwa sejak awal berdirinya,
sebenarnya Yogyakarta sudah merupakan suatu negara, sehingga tidak bisa dilebur
begitu saja pada saat berintegrasi dengan RI.
Pada masa penjajahan Belanda, Kasultanan Yogyakarta diperlakukan sebagai negara kecil,
sehingga kedudukannya tidak diatur secara sepihak dalam ordonantie, melainkan diatur
dalam sebuah perjanjian antara Gubernur Jenderal sebagai wakil Pemerintah Hindia
Belanda dan Sri Sultan sebagai wakil Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian yang harus
diperbaharui setiap kali terjadi pergantian Sultan ini disebut politiek - contract.
Menurut politiek-contract terakhir tanggal 18 Maret 1940 (Stb. 1941 No. 47), Kasultanan
Yogyakarta masih mempunyai kekuasaan (kewenangan atau urusan) yang banyak, misalnya
mempunyai peradilan sendiri sebagai badan yudikatif meskipun hanya berwenang
mengadili perkara-perkara dari keturunan Sultan Yogyakarta mulai graad satu sampai
dengan graadempat, baik meliputi perkara sipil maupun kriminal. Bahkan sebelum
keluarnya Petunjuk Gunseikan tanggal 1 Agustus 1942, Kasultanan Yogyakarta memiliki
beberapa kelompok prajurit bersenjata sebanyak hampir 1000 orang.
Selanjutnya, dibidang perindustrian, jika daerah diluar DIY berlaku peraturan Hinder
Ordonantie (HO) yaitu setiap usaha yang menimbulkan kebisingan atau mengganggu
masyarakat sekitarnya harus mendapat ijin HO, maka di DIY terdapat peraturan yang
disebut Pranatan Reridhu yang tertuang dalam Rijksblad Kasultanan. Dibidang pengairan,
jalan-jalan dan gedung-gedung, DIY sudah memiliki dinas PDG (Pengairan, Djalan dan
Gedung), sedang diluar DIY berlaku aturan Algemene Water Reglement (AWR) tahun 1934.
Kewenangan-kewenangan otonom seperti inilah yang dimaksud dengan hak asal-usul atau
hak yang bersifat autochtoon, yang merupakan awal mula timbulnya hak istimewa dalam
Negara Kesatuan RI.
Mengingat hal-hal tersebut diatas, kiranya dapat dimengerti apabila dalam UU No. 3 Tahun
1950 tentang Pembentukan DIY, pasal 4 ayat (4) dinyatakan bahwa: Urusan-urusan rumah
tangga dan kewajiban-kewajiban lain dari pada yang tersebut dalam ayat (1), yang
dikerjakan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dibentuk menurut UU ini,
dilanjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan undang-undang.
Ketentuan ini tidak terdapat pada UU Pembentukan Propinsi lain, sebab pada waktu
pembentukannya propinsi-propinsi itu belum mempunyai kewenangan apapun, sehingga
kekuasaannya harus diisi oleh Pemerintah Pusat. Dan karena sebelumnya tidak memiliki
kewenangan dalam urusan tertentu, maka dalam UU Pembentukannya-pun tidak
diperlukan adanya ketentuan peralihan seperti tersebut diatas.
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa eksistensi DIY sampai saat ini tidak perlu
diperdebatkan. Masalahnya adalah, bagaimana prospek ke depan khususnya dengan
berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999?
Bicara masalah prospek, berarti bicara sekitar perlu tidaknya penghapusan sebutan,
kedudukan, dan hak-hak yuridis sebuah daerah istimewa dalam Negara Kesatuan RI. Hal ini
akan dielaborasi lebih lanjut pada paparan di bawah ini.
Pada prinsipnya, daerah istimewa sebagai struktur dan sifat organisasi yang spesifik, suatu
saat dapat ditiadakan bila perkembangan keadaan memang menghendaki demikian.
Organisasi sebagai alat mencapai tujuan juga senantiasa harus selalu disesuaikan dengan
perkembangan masyarakat, sehingga pada saat tertentu perlu diadakan perubahan
struktur organisasi pemerintahan, baik di Pusat maupun di Daerah.
Sejarah ketatanegaraan di Indonesia sendiri pernah mempraktekkan perubahan sebuah
Daerah Istimewa menjadi daerah otonom biasa, yakni yang terjadi pada kasus Daerah
Istimewa Surakarta. Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran sebagai daerah swapraja
berubah menjadi Karesidenan yang bersifat istimewa, sebab residennya berada langsung
dibawah pemerintah Pusat RI dan Karesidenan Surakarta itu bersifat otonom. Namun,
dalam perkembangan selanjutnya Surakarta gagal mempertahankan diri sebagai daerah
istimewa, bahkan kemudian diintegrasikan kedalam wilayah propinsi Jawa Tengah.
Dengan demikian, di satu sisi penghapusan daerah istimewa membawa pengaruh positif
yakni terciptanya keseragaman dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di
seluruh Indonesia. Disisi lain, sebuah daerah istimewa yang tinggal namanya saja tanpa
memiliki implikasi tertentu, sama artinya dengan terjadinya inkonsistensi daerah
istimewa. Lagi pula, apakah keseragaman itu merupakan satu-satunya kondisi yang dapat
melancarkan roda pembangunan serta menciptakan stabilitas nasional, masih perlu dikaji
lebih lanjut.
Dalam kaitan ini, kalimat kedudukan pemerintah daerah sejauh mungkin diseragamkan
yang terdapat dalam konsiderans Menimbang huruf c. jo. Penjelasan UU Nomor 5 tahun
1974 bagian I angka 4a (6), harus ditafsirkan bahwa penyeragaman daerah tidaklah wajib
sifatnya, tetapi yang harus diperhatikan juga adalah kondisi dinamis suatu daerah. Jadi,
istilah penyeragaman mengandung sifat supel dan dinamis, artinya meskipun secara
nasional telah ada peraturan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun
dalam hal-hal tertentu dapat dimungkinkan penyimpangan oleh suatu daerah. Dengan kata
lain, cita-cita penyeragaman itu adalah keseragaman dalam kerangka Bhinneka Tunggal
Ika, yakni keseragaman yang mengindahkan keragaman.
Terlepas dari pro dan kontra ide penyeragaman pemerintah daerah, sebelum pemerintah
memutuskan untuk menghapuskan suatu daerah istimewa, hendaknya dipertimbangkan
terlebih dahulu tanggapan masyarakat setempat, sehingga peristiwa penghapusan Daerah
Istimewa Aceh pada tahun 9171 tidak terulang lagi.
Pada umumnya, masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah suatu Daerah Istimewa
menginginkan agar kedudukan istimewa bagi daerahnya dipertahankan untuk waktu-waktu
mendatang. Demikian pula di Yogyakarta, dengan keputusan DPRD DIY No.4/K/DPRD/ 1980
tentang sebutan dan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta, terlihat sekali bahwa
masyarakat Yogyakarta menghendaki terjaminnya kelestarian sifat dan kedudukan
istimewa bagi DIY.
Kehendak, perasaan dan harapan warga Yogya akan kelestarian dan keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta terutama tercantum dalam Diktum Keputusan DPRD DIY
No.4/K/DPRD/1980, yang menghendaki agar Pemerintah Daerah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta dipertahankan sebagai suatu Pemerintah Daerah Istimewa yang monumental
berdasarkan kenyataan sejarah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini
mengingat nilai-nilai perjuangannya dimasa lalu baik sebelum maupun sesudah Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, untuk diketahui dan dijadikan suri
tauladan bagi generasi mendatang.
Melihat isi keputusan itu, jelaslah bahwa selain memilki latar belakang yang amat kuat,
eksisitensi DIY juga memiliki latar depan strategis dalam arti untuk membekali generasi
muda tentang nila-nilai historis bangsa. Oelah karena itu, agaknya tidak cukup alasan
untuk menghapus DIY atau menggabungkannya dengan propinsi lain. Di samping itu,
landasan konstitusional yang dipunyai DIY cukup menjamin kelangsungan hidupnya dengan
segala hak-hak istimewa yang melekat padanya. Sebab mengubah status dan kedudukan
DIY sama artinya dengan keharusan untuk mengubah terlebih dahulu ketentuan dan jiwa
konstitusi yang ada. Dengan demikian, secara teoritis maupun praktis, kedudukan daerah
istimewa pada umumnya dan DIY khususnya, masih layak dipertahankan pada masa-masa
mendatang.
Prospek Otonomi Desa
Perubahan kebijakan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah (termasuk
pemerintahan desa) dari UU Nomor 5 tahun 1974 dan UU Nomor 5 tahun 1979 menjadi UU
Nomor 22 tahun 1999, membawa implikasi yang sangat besar. Salah satu implikasi tersebut
adalah bahwa Desa tidak sekedar merupakan wilayah administratif sebagai kepanjangan
tangan pemerintahan Pusat di Daerah (pelaksana asas dekonsentrasi), tetapi memiliki
lebih merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi luas.
Sebagaimana halnya pada kasus DIY, otonomi yang luas pada desa sesungguhnya bukan hal
yang baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai
berikut.
Berdasarkan kerangka waktunya (time frame), perkembangan otonomi pada kesatuan
hukum masyarakat terkecil (desa) mengalami pergeseran yang sangat fluktuatif, dimana
pada satu Desa memiliki otonomi yang sangat luas (most decentralized), sedang disaat lain
Desa tidak memiliki otonomi sama sekali dan hanya berstatus sebagai wilayah
administratif (most centralized).
Pada awalnya, terbentuknya suatu komunitas bermula dari berkumpul dan menetapnya
individu-individu di suatu tepat karena terdorong oleh alasan-alasan yang mereka anggap
sebagai kepentingan bersama. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat yang masih
bersifat sederhana atau tradisional ini adalah pertama untuk hidup, kedua untuk
mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar, dan ketiga untuk mencapai
kemajuan dalam hidupnya (Kartohadikoesoemo, 1965: 5).
Kumpulan individu-individu yang membentuk desa dan yang merupakan sebuah daerah
hukum ini, secara alami memiliki otonomi yang sangat luas, lebih luas dari pada otonomi
daerah-daerah hukum di atasnya yang lahir di kemudian hari, baik yang terbentuk oleh
bergabungnya desa-desa dengan sukarela atau yang dipaksakan oleh pihak-pihak yang
lebih kuat. Otonomi atau kewenangan desa itu antara lain meliputi hak untuk menentukan
sendiri hidup matinya desa itu, dan hak untuk menentukan batas daerahnya sendiri.
Selanjutnya Kartohadikoesoemo (1965: 214) menyebutkan bahwa masyarakat sebagai
Daerah Hukum, menurut hukum adat mempunyai norma-norma sebagai berikut: berhak
mempunyai wilayah sendiri yang ditentukan oleh batas-batas yang sah, berhak mengurus
dan mengatur pemerintahan dan rumah tangganya sendiri, berhak memilih dan
mengangkat Kepala Daerahnya atau Majelis pemerintahan sendiri, berhak mempunyai
harta benda dan sumber keuangan sendiri, berhak atas tanah sendiri, dan berhak
memungut pajak sendiri.
Berdasarkan otonomi desa yang mendapatkan landasan yuridis dalam Regeringsreglement
1854 pasal 71 itu, maka hak atas tanah sepenuhnya ada ditangan rakyat desa, tidak saja
kekuasaan atas tanah pertanian, tetapi juga atas tanah yang belum digarap, hutan belukar
dan gunung jurangnya (sa-satebane sa-jurang perenge).
Hak ulayat seperti ini oleh van Vollenhoven dinamakan beschikkingrechts, yakni hak kuasa
desa yang dalam wilayahnya berhak mempergunakan tanah bagi kepentingan warganya
atau kepentingan warga desa lain dengan terlebih dahulu membayar uang recognitie
sebagai bukti bahwa dia di situ adalah orang asing atau sebagai bulu bekti / persembahan
kepada pihak yang memiliki hak atas tanah itu. Adapun bagi warga desa setempat, dapat
mempergunakan tanah itu dengan hak-hak perorangan: hak milik, hak yasan
(inlandsbezitsrecht); hak wenang pilih, hak mendahulu (voorkeursrecht); hak menikmati
hasil (genootsrecht); hak pakai (gebruiksrecht) dan hak menggarap (ontginningsrecht); hak
imbalan jabatan (ambtelijke profijtsrecht) serta hak wenang beli (naastingsrecht).
(Kartohadikoesoemo, 1965: 233; Sudijat, 1981: 6-8).
Dalam perkembangan selanjutnya terdapatlah satu gejala ketatanegaraan yakni
berkembangnya komunitas sosial politik diatas kesatuan komunitas desa yaitu Sima,
Wisaya, Watak, Mandala, dan pada masa kemudian lahirlah Istana sebagai pusat politik
negara kerajaan. Dengan kata lain, terjadi proses penyatuan desa-desa menjadi wilayah
yang lebih besar dan luas, yaitu negara kerajaan.
Peristiwa lahirnya kerajaan, menyebabkan otonomi desa mendapat pembatasan-
pembatasan. Desa tidak lagi merupakan kesatuan yang otonom, tetapi menjadi kesatuan
wilayah yang lebih luas tadi. Oleh karenanya, meskipun pada prinsipnya hak pertuanan /
hak kuasa desa tetap berlaku, tetapi dalam lingkungan yang lebih luas itu desa dibebani
hak pertuanan / hak milik raja atas wilayahnya. Hak pertuanan raja ini dengan cara
dipaksanakan dapat mendesak kedudukan hak desa dan akhirnya mendapatkan tempat
dalam hukum adat Jawa, bahwa tanah adalah milik raja.
Dalam masa-masa ini, otonomi desa menghadapi cobaan berat. Dan sejak saat itulah
terjadi proses sentralisasi otonomi, dari otonomi desa menjadi otonomi kerajaan. Gejala
seperti ini terus berlangsung hingga abad 19, yakni masa-masa munculnya pemikiran
tentang emansipasi politik, kebebasan, demokrasi dan desentralisasi bagi negara-negara
(unit kemasyarakatan) terjajah. Akhirnya, gencarnya ide-ide pembebasan individu secara
radikal mampu mengembalikan lagi otonomi desa yang sempat hilang.
Sebagai gambaran, dalam bidang agraria, Werner Roll (1983: 45) menulis bahwa
reorganisasi atau reformasi agraria yang dilaksanakan antara tahun 1912 dan 1918
menghasilkan aturan-aturan baru, yakni: penghapusan sistem feodal beserta tindakan-
tindakan sewenang-wenang yang sudah membudaya; beberapa kesatuan tempat tinggal
(desa; dukuh; kabekelan) digabung menjadi kesatuan administrasi baru seperti kelurahan
atau desa praja; Raja melepaskan hak-hak mereka atas sebagian terbesar dari tanah yang
termasuk wilayah kesatuan administrasi ini, yang kemudian menjadi wewenang anggadhuh
(hak milik pribumi) anggota masyarakat desa; serta diadakan pembagian baru dari persil-
persil tanah dan tanah garapan untuk penduduk desa.
Dari deskripsi di atas terlihat bahwa desa kembali memiliki otonomi. Arah kebijaksanaan
otonomi selanjutnya memang semakin mempercayakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan kepada kesatuan masyarakat hukum yang lebih kecil (baca: pemerintah
daerah atau desa). Memang, masalah otonomi atau penyerahan / pengakuan wewenang /
urusan ini merupakan lima masalah besar yang timbul dalam proses politik sepanjang
masa. Empat masalah lainnya adalah tentang kewarganegaraan, fungsi dan tugas negara,
sumber kekuasaan, serta kemampuan negara dalam hubungan-hubungan eksternal.
Selanjutnya pada masa pemerintahan RI, pengaturan penyelenggaraan pemerintahan desa
mendapat landasan yuridis pada pasal 18 UUD 1945 yang mengakui kenyataan historis
bahwa sebelum proklamasi kemerdekaan, di Indonesia sudah terdapat daerah-daerah
Swapraja yang memiliki berbagai hak dan wewenang dalam penyelenggaraan berbagai
urusan di wilayahnya. Ini berarti, desa secara teoritis juga memiliki hak yang bersifat
autochtoon atau hak yang telah dimiliki sejak sebelum daerah itu merupakan bagian dari
Negara Indonesia. Namun dalam penyusunan peraturan tentang Pemerintahan Desa
sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 5/1979, kenyataannya Desa bukan lagi dianggap
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang otonom, khususnya dalam masalah administrasi
pemerintahan secara umum. Terlebih lagi dengan pembentukan kelurahan, maka kesatuan
masyarakat Desa ini hanya berstatus wilayah administratif yang ditempatkan sebagai
kepanjangan tangan pemerintah Pusat (pelaksana asas dekonsentrasi).
Dalam perkembangan saat ini, keberadaan pemerintahan desa tidak (belum) diatur
terpisah atau tersendiri dalam suatu peraturan perundangan, tetapi melekat pada UU
Pemerintahan Daerah. Menurut UU Nomor 22 tahun 1999 ini, desa secara implisit memiliki
otonomi yang cukup luas, sebagaimana diatur dari pasal 94 hingga pasal 108. Dan
dikaitkan dengan konteks kemajuan masyarakat di tingkat desa yang selalu bergerak maju
kearah kompleksitas dan trend globalisasi, maka otonomi luas yang saat ini dititikberatkan
pada Kabupaten / Kota tidak mustahil harus dilimpahkan kepada kesatuan hukum
masyarakat yang lebih rendah, yakni desa.
Dalam kaitan ini, terdapat hubungan tarik menarik antara Pusat dan Darah (termasuk
desa) dalam hal penyerahan suatu kewenangan / urusan pemerintahan tertentu. Artinya,
sesuatu urusan yang semula menjadi otonomi suatu daerah dapat ditarik menjadi urusan
pusat jika ternyata urusan tersebut telah berkembang sedemikian rupa sehingga
menyangkut kepentingan yang lebih luas. Sebaliknya, mungkin sekali sesuatu soal yang
tadinya merupakan urusan negara dalam perkembangannya membutuhkan pengurusan
yang lebih khusus yang hanya dapat dilakukan di lingkungan daerah. Hal ini selaras pula
dengan asas kedaerahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yakni ketidakmampuan
pemerintah untuk mengurus semua kepentingannya dikarenakan semakin berkembangnya
masyarakat sehingga harus dilimpahkan sebagian kepada daerah.
Faktor eksternal berupa perkembangan masyarakat dengan tingkat kehidupan yang
semakin maju seperti itulah yang pada akhirnya menyebabkan menumpuknya beban urusan
di tingkat desa. Kemampuan desa yang terbatas baik dari sisi aparatur maupun sumber
daya lainnya, jelas tidak akan mampu mengimbangi semakin tingginya tingkat kesulitan
hubungan sosial politik warga di wilayahnya.
Di sinilah pada saatnya nanti dituntut keseriusan para pengambil keputusan untuk
menyempurnakan sistem pemerintahan desa, baik dari segi administrasi, manajemen,
maupun personalia dan keuangannya. Pemerintahan desa yang demikian, tidak lagi
merupakan unsur pelayan publik yang berfungsi memberikan surat keterangan, penyuluhan
maupun izin-izin tertentu; sebaliknya harus mampu memainkan peran sebagai pembuka
jalan bagi pemenuhan permintaan masyarakat (public choice), sekaligus sebagai
fasilitator yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara swadaya maupun
swadana.
Disamping itu, masalah otonomi selalu merupakan pemilihan
antara centralization dan local autonomy (otonomi daerah). Jika otonomi daerah yang
dipilih, berarti pemerintah pusat harus menyelenggarakan desentralisasi (secara harfiah
berarti melepaskan dari pusat).
Arti pentingnya desentralisasi bisa dilihat dari berbagai segi. Dilihat dari sudut politik,
desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukkan pada satu pihak, dan
merupakan tindakan pendemokrasian guna menarik partisipasi rakyat dalam
pemerintahan. Dari sudut administrasi, desentralisasi tidak lain adalah pendelegasian
wewenang dari pucuk pimpinan kepada bawahannya yang menjadi aktivitas-aktivitas
pemberian tugas, penyerahan wewenang, dan permintaan tanggung jawab. Dalam
pengertian ini desentralisasi merupakan keharusan yang mesti terdapat pada semua
organisasi.
Dari berbagai sudut pandangan yang ada, sangat menarik untuk disimak pemikiran dari
segi sosio kultural. Adalah fakta bahwa tiap-tiap daerah memiliki kekhususan-kekhususan
seperti corak geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, latar belakang sejarah dan
budaya. Spesifikasi daerah ini mengharuskan penguasa dan aparatur daerah untuk benar-
benar mengenalinya dan memanfaatkannya untuk pembangunan daerah secara optimal.
Pandangan sosio kultural ini apabila digabung dengan sudut pandang teknis organisatoris
akan dapat memberikan alasan yang jelas mengapa otonomi cenderung dilimpahkan
kepada daerah yang lebih rendah tingkatannya.
Dilihat dari segi teknik organisatoris, desentralisasi adalah alat dan teknik untuk mencapai
tujuan organisasi. Jadi desentralisasi adalah cara atau metode untuk melancarkan tugas-
tugas pemerintahan sekaligus mencapai tujuannya. Hal ini logis, sebab rakyat dari suatu
daerah itu sendirilah yang dalam babak pertama berkewajiban untuk memajukan
daerahnya.
Kebijaksanaan penyerahan urusan kepada desa sebagai unit pemerintahan terkecil, akan
membawa pengaruh positif berupa peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
serta peningkatan kualitas aparatur negara, khususnya di tingkat desa. Hal ini dapat
dicapai apabila dapat diidentifikasikan tiga kondisi, yaiu: 1) tingkat perkembangan
masyarakat, pertumbuhan penduduk dan pergeseran arah pembangunan ke daerah
terpencil; 2) kemungkinan positif dan negatif dari pelaksanaan titik berat otonomi pada
desa; dan 3) hambatan baik dari segi sumber daya aparatur maupun kelembagaan di desa.
Dengan identifkasi ketiga kondisi ini, barulah dipikirkan untuk memutuskan perlu tidaknya
otonomi daerah.
Penutup
Perubahan sistem dan mekanisme pemerintahan (di) daerah dewasa ini merupakan suatu
keniscayaan. Hal ini didorong oleh adanya fenomena bahwa penyelenggaraan
Pemerintahan di Daerah sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Nasional
dan Pembangunan Nasional, saat ini menghadapi masalah yang sangat mendasar, yaitu
bagaimana menampung dan memenuhi aspirasi serta kepentingan rakyat di daerah dalam
rangka pelaksanaan otonomi. Seiring dengan tuntutan jaman dan arah fenomena
perubahan sosial yang menghendaki terciptanya suatu tatanan, kondisi, peluang dan
kesempatan bagi masyarakat agar makin mampu mengembangkan kreativitas dan
prakarsanya, maka keberadaan, tugas, peran dan tanggung jawab pemerintahan dalam arti
luas, dirasakan semakin relevan untuk ditinjau kembali, dalam pengertian dilakukan
revitalisasi organisasi.
Dalam hubungan ini, maka penghormatan terhadap bentuk-bentuk organisasi (kesatuan
masyarakat hukum) asli sangat dibutuhkan. Hal ini sekaligus mencerminkan bahwa
kebijakan otonomi yang dianut UU Nomor 22/1999 sekaligus membawa misi demokratisasi
masyarakat lokal.
Daftar Pustaka
Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1965, Desa, Bandung: Sumur.
Roll, Werner, 1983, Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta
Jateng, Jakarta: Rajawali.
Sudijat, Iman, 1981, Hukum Adat Sketsa Asas, Yogyakarta: Liberty.
Catatan:
Naskah asli paper ini dimuat dalam Jurnal Wacana Kinerja, PKP2A I LAN Bandung, edisi Maret 1999.
Desentralisasi dan Otonomi desa Suatu Kajian dari Segi
Implementasi Pembagian Kewenangan Antara Desa Dan
Kabupaten.
Kata kunci: desentralisasi, otonomi desa, implementasi pembagian kewenangan.
Haryanto, Samsi;Suprapti*)
Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, Penelitian, Dikti, Fundamental, 2006.
Penelitian dengan pendekatan kualitatif yang mengambil lokasi Desa Blimbing Kecamatan Gatak
Kabupaten Sukoharjo ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana implementasi
pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten, (2) Faktor-faktor apa yang menjadi
penyebab tidak berjalannya implementasi pembagian kewenangan antara desa dan kabupaten,
dan (3) Kewenangan ideal apa saja yang justru dimiliki oleh desa dalam melaksanakan otonomi
desa agar dapat tercapai desa mandiri.
Dengan bersumber pada informan para implementer kebijakan pembagian kewenangan antara
desa dan kabupaten, dokumen-dokumen tertulis yang ada di Kabupaten dan desa, dan kondisi
desa penelitian, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam, focus group
discussion, dan mengumpulkan data tertulis. Uji kredibilitas informasi dilakukan melalui penerapan
teknik triangulasi.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa :
1) Implementasi pembagian kewenangan antara desa dengan kabupaten di desa penelitian
belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Bahkan pembagian kewenangan antara desa dan
kabupaten itu sendiri hingga penelitian ini berlangsung belum pernah dilakukan. Peraturan daerah
yang mengatur hal itu belum ada.
2) Faktor-faktor yang menjadi kendala tidak adanya implementasi pembagian kewenangan itu
sendiri amatlah kompleks, yakni menyangkut:
a. Belum adanya aturan hukum yang memadai yang menjadi dasar pembagian kewenangan.
Oleh karena itu implementasinya pun juga belum ada. Jika di desa telah dilaksanakan
kewenangan-kewenangan, hal itu semata-mata didasarkan pada rutinitas sebelumnya.
b. Kemampuan perangkat desa maupun anggota BPD relatif terbatas baik dalam hal tingkat
pendidikan formal, kemampuan khusus terkait dengan tuntutan juga fungsinya, maupun
pemahaman terhadap kewenangan desa itu sendiri.
c. Tingkat menghasilkan para perangkat desa dan anggota BPD belum memadai, sehingga
mengakibatkan dedikasi kerja tidak optimal. Rencana pemerintah untuk mengangkat Sekretaris
Desa menjadi PNS, di satu pihak disambut antusias oleh para perangkat desa oleh karena jelas
bisa meningkatkan penghasilan, namun di lain pihak justru merupakan masalah dan hambatan
besar bagi menguatnya otonomi desa menuju kemandirian.
3) Kewenangan ideal yang perlu dimiliki desa agar penguatan otonomi desa tercapai dan
akhirnya menuju desa mandiri adalah sebagai berikut :
a. Kewenangan untuk turut serta menentukan kebijakan Kabupaten
yang menyangkut desa.
b. Kewenangan untuk mengembangkan inisiatif dan kreativitas dalam
melaksanakan otonomi desa dan mengelola sumber pendapatan
desa
c. Kewenangan untuk menolak tugas-tugas pembantuan yang tidak
sesuai dengan aspirasi dan daya dukung desa, dan penolakan
tidak diartikan sebagai sesuatu yang negatif.
4) Berdasar pada hasil penelitian maka implikasi kebijakan yang perlu diambil disarankan
sebagai berikut:
1. Segera diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang penyerahan urusan yang menjadi
kewenangan kabupaten yang perlu diserahkan kepada desa, agar menjadi pedoman yang jelas
bagi desa untuk mengimplementasikan kewenangan tersebut.
2. Diperlukan Kebijakan Pemerintah Kabupaten maupun Lembaga Profesional seperti
Perguruan Tinggi untuk : (a) meningkatkan profesionalitas perangkat desa dan anggota BPD agar
mampu menjalankan fungsi masing-masing, dan mampu mengelola sumber pendapatan desa
secara profesional, (b) memberi keleluasaan kepada desa untuk mengembangkan kreatifitas dan
inisiatif dalam menjalankan otonomi desa.
3. Diperlukan kebijakan untuk meningkatkan penghasilan aparat melalui alternatif : (a)
Pengembangan Badan Usaha Milik Desa, bagi desa yang profesional ke arah itu, atau (b)
mengangkat perangkat desa menjadi PNS untuk desa-desa yang profesional berkembang ke arah
perubahan status menjadi kelurahan.
PELAKSANAAN OTONOMI DESA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004 DI KABUPATEN
DEMAK
PELAKSANAAN OTONOMI DESA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
DI KABUPATEN DEMAK
MAKALAH
Diajukan untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Filsafat Hukum
Dosen Pengampu : H. Jawade Hafidz, SH.MH
Disusun oleh :
KUSTIAH
MH.09.15.0794
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2 0 1 0
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Analisis 2
C. Tujuan Analisis 3
D. Manfaat Analisis 3
BAB II ANALISIS 4
A. Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Demak 6
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa 7
BAB III PENUTUP 9
A. Simpulan 9
B. Saran 9
DAFTAR PUSTAKA 10
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pengertian otonomi daerah yang melekat dalam pemerintahan daerah sangat berkaitan erat
dengan desentralisasi. Baik pemerintahan daerah, desentralisasi maupun otonomi daerah adalah
bagian dari suatu kebijakan dan praktek penyelenggaraan pemerintahan. Tujuannya adalah demi
terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, maju dan sejahtera, setiap orang bisa hidup
tenang, nyaman, wajar oleh karena memperoleh kemudahan dalam segala hal di bidang
pelayanan masyarakat.
Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menawarkan berbagai macam
paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis pada filosofi keaneka
ragaman dalam kesatuan. Paradigma yang ditawarkan antara lain :
1. Kedaulatan rakyat
2. Demokrasi
3. Pemberdayaan Masyararakat
4. Pemerataan dan Keadilan
Dengan diundangkannya Undnag-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah untuk diterapkan sebagai payung hukum pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia,
dapat memberikan implikasi yang besar bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah termasuk juga
pemerintahan desa.
Konsep tentang definisi desa sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yaitu untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Adapun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup :
a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkan
pengaturannya kepada Desa disertai pembeayaannya; yang secara langsung dapat meningkatkan
pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan / atau Pemerintah Kabupaten /
Kota; yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia
dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada
Desa.
B. Rumusan Analisis
Dari uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimana pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi pendukung dan / atau penghambat pelaksanaan otonomi
desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ?
C. Tujuan Analisis
Tujuan dilaksanakannya analisis ini adalah :
1. Untuk mengetahui pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan / atau penghambat
pelaksanaan otonomi desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
D. Manfaat Analisis
Analisis ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran akademis yakni
diharapkan menemukan konsep-konsep baru dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu
hukum pada khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan otonomi desa.
BAB II
ANALISIS
Dasar pemikiran dari Otonomi Daerah adalah bahwa Negara Indonesia adalah merupakan
negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan
harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Dengan demikian Otonomi Daerah adalah merupakan kebijaksanaan yang
sangat sesuai dengan asas desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam
Pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan
oleh pemerintah kepada daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi diartikan sebagai pemerintahan kebebasan atas
kemandirian (zelfstandigheid) bukan kemerdekaan (onafthankelijkheid), sedangkan otonomi
daerah sendiri memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :
1. Kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus sedaerah dengan keuangan
sendiri, menentukan hukum sendiri dan pemerintahan sendiri.
2. Pendewasaan politik rakyat lokal dan proses penyejahteraan rakyat.
3. Adanya pemerintahan lebih atas memberikan atau menyerahkan sebagian urusan rumah
tangganya kepada pemerintah bawahannya. Sebaliknya pemerintah bawahan yang menerima
sebagian urusan tersebut telah mampu melaksanakan urusan tersebut.
4. Pemberian hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah memungkinkan daerah tersebut
dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan
hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan
pelaksanaan pembangunan.
Otonomi nyata diartikan sebagai keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan
pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan
berkembang di daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab berarti perwujudan
pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam
bentuk tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian
otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik,
pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan
yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Berkaitan dengan Otonomi Daerah, bagi Pemerintah Desa; dimana keberadaannya berhubungan
langsung dengan masyarakat dan sebagai ujung tombak pembangunan, Desa semakin dituntut
kesiapannya baik dalam hal merumuskan Kebijakan Desa (dalam bentuk Perdes), merencanakan
pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan
pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula dalam menciptakan kondisi yang kondusif
bagi tumbuh dan berkembangnya kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan
menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi
masyarakatnya. Dengan demikian, maka cepat atau lambat desa-desa tersebut diharakan dapat
menjelma menjadi desa-desa otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi
kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.
Keberhasilan pelaksanaan Otonomi Desa ditandai dengan semakin mampunya Pemerintah Desa
memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat ke arah
kehidupan yang lebih baik. Dengan terselenggaranya Otonomi Desa, maka hal itu akan menjadi
pilar penting Otonomi Daerah, Keberhasilan Otonomi Daerah sangat ditentukan oleh berhasil
tidaknya Otonomi Desa. Melalui pengertian tersebut, prinsip utama otonomi desa adalah
kewenangan membuat keputusan-keputusan sendiri melalui semangat keswadayaan yang telah
lama dimiliki oleh desa, dalam satu kesatuan wilayah pedesaan.
Selayaknya desa dipercaya untuk mengurus dirinya dalam unit wilayah kelola desa melalui
peraturan yang dibuat secara mandiri. Ciri paling kuat pemerintahan desa-desa tradisional di
Indonesia adalah adanya peranan dana swadaya dan gotong royong. Dua ciri tersebut
merupakan modal sosial yang jauh lebih penting (dan potensial) ketimbang modal keuangan.
Modal sosial sebagai potensi kemandirian dan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan
adalah landasan berkembangnya ekonomi rakyat dan kemandirian desa guna mencapai otonomi.
1. Pelaksanaan Otonomi Desa di Kabupaten Demak berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 yaitu bahwa secara materi hukum pemerintah Kabupaten Demak telah
melaksanakan materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada dasarnya UU tersebut
masih berlaku dan relevan pada saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan telah dibuat /
ditetapkannya 7 (tujuh) Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum pelaksanaan otonomi
desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketujuh Peraturan Daerah (Perda)
tersebut adalah :
- Perda No. 1 Th. 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Penetapan dan Pengesahan
Badan Permusyawaratan Desa.
- Perda No. 2 Th. 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengesahan, Pelantikan,
Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Perda No. 3 Th. 2007 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan
Pemberhentian Perangkat Desa.
- Perda No. 4 Th. 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8
Tahun 2001 Tentang Lelangan Tanah Desa dan Dana Perimbangan Keuangan Antar Desa di
Wilayah Kabupaten Demak.
- Perda No. 6 Th. 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Desa.
- Perda No. 8 Th. 2007 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Perda No. 9 Th. 2007 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Otonomi Desa dari Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004
a. Hal-hal positif yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
merupakan faktor-faktor yang mendukung Pelaksanaan Otonomi Desa adalah sebagai berikut :
- Berkaitan dengan makna Desa bahwa Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam
system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pengertian tersebut di atas
sangatlah jelas bahwa pemerintahan desa tidak lagi diarahkan pada self governing community.
- Berkaitan dengan kewenangan Desa bahwa Desa diberikan kewenangan untuk mengurusi
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota dan tugas pembantuan dari
pemerintah dan pemerintah daerah.
- Berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang berarti masyarakat dapat
memilih Kepala Desanya sesuai yang dikehendaki yang mereka anggap mampu membawa
desanya lebih maju dari sebelumnya.
- Keberadaan Sekretaris Desa dari unsur PNS, dengan diambil / diangkatnya Sekretaris Desa dari
unsur Pegawai Negeri Sipil, maka kegiatan kepemerintahan akan dapat dikelola sesuai prinsip
manajemen pemerintahan yang baik.
b. Hal-hal terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan faktor-
faktor yang menghambat Pelaksanaan Otonomi Desa adalah sebagai berikut :
- Pengaturan mengenai Desa dalam Undang-Undang yang baru dapat dianggap memiliki
semangat sentralistik karena hanya memperkuat eksekutif (pemerintah desa) kemudian gagasan
tentang otonomi desa akan menjadi semakin kabur.
- Kekuasaan kepala desa yang selama ini menjadi raja kecil akan dapat semakin kuat karena
kewenangan kepala desa menjadi sangat besar dan tidak adanya kontrol dari rakyat yang selama
ini menjadi salah satu fungsi Badan Perwakilan Desa. Kekhawatiran lain adalah berpindahnya
fungsi kontrol ke tangan Camat selaku perangkat daerah bisa menimbulkan pola ABS (Asal
Bapak Senang).
- Terjadinya penghilangan hak otonomi rakyat karena adanya peluang desa menjadi kelurahan
dan kekayaan desa tersebut menjadi kekayaan daerah yang dikelola oleh kelurahan.
BAB III
PENUTUP
1. Simpulan
Secara umum pelaksanaan otonomi desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
sudah sesuai dengan materi yang telah ada, tetapi faktor utamanya terkait penentuan kebijakan
pemerintah daerah dalam pengaturan desa yang untuk masa sekarang perlu melibatkan unsur
Kecamatan sebagai kepanjangan tangan pemerintah daerah di wilayah, untuk disampaikan
kepada pemerintah desa meskipun secara garis koordinasi kepala desa bertanggung jawab
kepada Bupati.
2. Saran
- Untuk masalah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan otonomi desa
berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 perlu disempurnakan.
- Perlu adanya pembinaan aparat desa secara komprehensif secara rutin dan secara periodik
dengan melibatkan aparat Kecamatan dan Kabupaten serta aparat terkait melalui pembentukan
tim pembina desa dengan sasaran penggunaan dana perimbangan desa yang dirasa banyak sekali
persoalan dalam pelaksanaannya serta penataan administrasi desa secara umum.
DAFTAR PUSTAKA
Saddu Wasistono, 2001, Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah, Alqapriat Jatinangor
Sumedang, h.6.
Bayu, Suryaningrat, 1976, Pemerintahan dan Administrasi Desa, Ghalia Yayasan Beringin
KORPRI Unit Depdagri, Bandung.
Christine S.T. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia (Hukum Administrasi Daerah 1903
2001), Sinar Grafika, Jakarta.
Arikunto, Suharsimi, 2003, Manajemen Penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
Bhenyamin Hoessen, 1995, Berbagai Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Otonomi Daerah
Tingkat II. Suatu Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dari Segi Ilmu Administrasi Negara.
Desertasi untuk Gelar Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1993 dan Desentralisasi
Dan Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Naskah Pidato Pengukuhan Guru
Besar Dalam Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Indonesia, UI, Jakarta.
Pemerintah Kabupaten Demak, 2000, Perda Kabupaten Demak No. 20 Th 2000 Tentang
Pembentukan, Penghapusan, Pemecahan dan Penggabungan Kelurahan, Bagian Hukum
Kabupaten Demak.
Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Otonomi Daerah.
Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang
Pemerintahan Daerah.
Sekretariat Daerah, 2007, Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007, Bagian
Hukum Kabupaten Demak.
Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, 2006,
Peraturan Pemerintah Daerah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Kelurahan,
Dema
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN BANGGAI
Judul :
TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN OTONOMI DESA DI KABUPATEN BANGGAI
Pengarang/Penulis :
Asis Harianto, H.M. Djafar Saidi dan Faisal Abdullah
Alamat/Sumber Jurnal :
http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/07f508de53592473de5e935ee08
0bf4a.pdf
Review Jurnal :
Pelaksanaan otonomi desa pada daerah penelitian secara umum sudah
dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 32
tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 namun
belum secara maksimal khususnya untuk pelaksanaan pembangunandi
segala bidang di desa penelitian baik desa-desa yang ada di
Kecamatan Toili maupun desa-desa yang ada di Kecamatan Luwuk
Timur Kabupaten Banggai. Faktor penghambat dan pendukung
pelaksanaan otonomi desa pada desa-desa penelitian baik Kecamatan
Toili maupun Luwuk Timur Kabupaten Bangai adalah sama persis,
yaitu faktor penghambatnya adalah sarana dan prasarana sedangkan
faktor pendukungnya adalah faktor dana, faktor koordinasi dan
faktor komitmen.
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan
otonomi desa di Kabupaten Bangai adalah meningkatkan gaji Kepala
Desa dan perangkatnya, mengalokasikan dana yang cukup untuk
bantuan pembangunan desa, terutama guna alat transportasi desa
yang masih sangat kurang bahkan tidak ada.
Diposkan oleh dylla kahar raden di
KATEGORI: DAERAH
Implementasi Otonomi Desa Menurut UU No
32/2004
Rivan Mubaroq.AmKL.SH
Kamis, 27 Jan '11 21:24
Bagus +2
Beri Rating
Penyelenggaraan otonomi daerah merupakan salah satu upaya strategis
yang memerlukan pemikiran yang matang, mendasar dan berdimensi jauh
ke depan. Pemikiran itu kemudian dirumuskan dalam kebijakan otonomi
daerah yang sifatnya, menyeluruh dan dilandasi oleh prinsip-prinsip dasar
demokrasi, kesetaraan dan keadilan disertai untuk kesadaran akan
keaneka ragaman kehidupan kita bersama sebagai bangsa dalam
semangat Bhineka Tunggal Ika. Kebijakan otonomi daerah diarahkan
kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut :
1. Peningkatan pelayan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat
serta aparatur pemerintah di daerah.
2. Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan PEMDA dan
antar-PEMDA dalam kewenangan dan keuangan.'
3. Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan
kesejahteraan masyarakat di daerah.
4. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.
Desa atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya di sebut desa
adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah
yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mngurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat
yang diakui dan/atau di bentuk dalam sistem pemerintah nasional dan
berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Amandemen
UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah
keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pedelegasian dari
pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.
Sedangkan terhadap Desa, geneologis yaitu desa yang bersifat
administratif seperti desa yang di bentuk karena pemekaran desa ataupun
karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralis,
majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi daerah akan diberikan
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari
desa itu sendiri.
Sebagai perwujudan dari sistem demokrasi, dalam penyelenggaraan
pemerintah desa di bentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau
sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa
bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam
penyelenggaraan Pemerintah Desa seperti dalam pembuatan dan
pelaksanaan Peraturan Desa, Angaran Pendapatan dan Belanja Desa dan
Keputusan Kepala Desa. Di desa di bentuk lembaga ke masyarakatan
yang berkedudukan sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dalam
memberdayakan masyarakat desa.
Otonomi desa pada dasarnya mempunyai peranan yang strategis, ketika
saat ini kita semua sedang mengusung ide pembangunan yang berbasis
kerakyatan/masyarakat, pemberdayaan dsb. Desa adalah basis
masyarakat dengan segala problematiknya. Kemiskinan ada di desa, akan
tetapi di desa pula basis sebagai potensi bisnis ekonomi, sebagian besar
penduduk indonesia juga tinggal di desa. Dengan demikian, slogan yang
mengatakan membangun desa maka daerah dan negara maju bukan
hanya slogan pepesan kosong tanpa argumen yang valid. Dalam kerangka
konseptual pemikiran ini lah, maka konsep pengembangan otonomi desa
adalah alternatif yang pantas di evaluasi yang berperan strategis
dalam sistem pertahanan nasional.
Otonomi pada hakekatnya menunjukan besaran kewenangan yang dimiliki
sebuah ruang lingkup wilayah politik dan administratif. Luas atau sempitnya
kewenangan yang di ukur dengan jumlah urusan akan menunjukan
besaran otonomi tersebut. Oleh sebab itu, besaran kewenangan ini akan
berhubungan dengan tingkat kapabilitas dalam mengelola kewenangan
tersebut yang di lihat pada level kreativitasnya. Sehingga ada persepsian
yang menyatakan bahwa otonomi akan mendorong kreatifitas yang arti
kata ada pemberdayaan di sana. Tanpa ada otonomi, jangan harap akan
munculnya lahir kreativitas dan kapabilitas komunitas masyarakat
lokal.
Namun, hal yang menarik jika kita mencermati perkembangan otonomi
desa, ternyata sesungguhnya masyarakat lokal khusus masyarakat
pedesaan telah lebih dahulu memiliki bakat kreativitas dalam mengelola
berbagai problematiknya dalam ruang lingkup otonomi aslinya yang
kelihatan ada pada pola adat-istiadat mereka. Hal ini tentunya tidak sama
dengan otonomi daerah pada level Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi yang
dari segi waktu masih relatif lebih muda karena diberikan oleh negara
sebagai bentuk strategis kebijakan pemerintah.
Menyimak sejarah perkembangan otonomi desa, akan kelihatan kuatnya
komitmen untuk mengeyampingkan ruang lingkup pedesaan yang terus
berkembang dan berlangsung. Rezim otoriter dalam konteks desa
sepertinya akan terus berlanjut.UU No 32/2004 yang mengantikan UU No
22/1999 mungkin cerita yang dapat diangkat.
Pemerintah Desa berdasarkan UU No 32/2004 harus dikatakan berbeda
secara mendasar dengan pemerintah desa menurut UU No 22/1999. Di
mana pengaturan desa yang tergambar dalam UU No
32/2004 memperlihatkan kuatnya kontrol pemerintah dan menghilangkan
demokratisasi pemerintahan desa. hal ini mengingatkan pengaturan desa
dalam UU No 5/1975.
Selanjutnya menyangkut kewenangan desa, dapat di lihat bahwa terdapat
tiga sumber urusan pemerintah yang menjadi kewenangan desa
sebagaimana di atur dalam Pasal 206 UU No 32/2004 yaitu :
1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah.
3. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Kabupaten.
Penjabarannya harus hati-hati, karena terjadi ketidak-sikronan
terutama pasal 206 ayat (1) dengan pasal 200 UU No 32/2004 yaitu :
1. Dalam pemerintahan desa di Kabupaten/Kota di bentuk pemerintahan
desa yang terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa (BPD).
2. Pembentukkan, penghapusan dan/atau pengabungan desa dengan
memperhatikan asal-usulnya atas prakarsa masyarakat.
3. Desa di Kabupaten/Kota bertahap dapat di ubah atau disesuaikan
statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa Pemerintah Desa
bersama Badan Pemusyawaratan (BPD) dengan PERDA.
Pasal 206 ayat (1) menjelaskan kewenangan desa adalah urusan
pemerintahan berdasarkan hak asal-usul desa. Jenis urusan ini jelas bukan
urusan karena penyerahan dari pemerintahan Kabupaten/Kota. Padahal
dalam pasal 200dinyatakan bahwa dalam PEMDA Kabupaten/Kota di
bentuk Pemerintahan Desa. Istilah PEMDA menunjukan penyelenggaraan
pemerintahan yang bersumber dari asas desentralisasi dan tugas
pembantuan. Dengan demikian dalam Pemerintahan Desa yang di bentuk
ada urusan yang tidak bersumber kepada pembentukkannya.
Menyangkut pengaturan sistem Pemerintahan Desa, terdapat beberapa
kelemahan yang perlu dicermati, yaitu :
Pertama : Tidak diaturnya sistem pertanggung-jawaban Kepala Desa
dalam batang tubuh UU No 32/2004. Sistem pertanggung-jawaban Kepala
Desa ditemukan di dalam penjelasan umum. Kepala Desa pada dasarnya
bertanggung jawab kepada rakyat desanya yang dalam tata cara dan
prosedur pertanggung-jawabannya disampaikan kepada Bupati atau
Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD),
Kepala Desa wajib memberikan laporan pertanggung-jawabannya.
Pengaturan semacam ini tidak tepat sasaran. Karena penjelasan pada
hakekatnya bukanlah norma, namun merupakan penjelasan dari norma
sehingga terhindar dari penafsiran gramatikal ganda. Hal ini yang perlu
dicermati yaitu pola laporan pertanggung-jawaban yang bersifat vertikal
(ke atas)dan bukan horinzontal dan ke bawah (ke masyarakat dan BPD)
akan menimbulkan perubahan orientasi pengabdian Kepala Desa yang
akan lebih loyalitas kepada kehendak pihak atas ke timbang kepada rakyat
yang memilihnya dan menimbulkan dampak yaitu Pemerintahan Desa
bisa menjadi alat politik pencapaian kekuasaan dari Bupati/Walikota
dalam pemilihan umum Kepala Daerah secara langsung.
Kedua : Tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Desa di atur lebih lanjut dengan PERDA
berdasarkan Peraturan pemerintah dan pasal 208 UU No 32/2004
Ketentuan ini cukup berbahaya mengingat UU tidak secara definitif
menentukan tugas dan kewajiban kepala Desa. pengaturan semacam ini
memberi ruang hampa pada pemerintah melalui peraturan Pemerintah. Di
lain pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi yang
sangat terbatas berdasarkan pasal 209 UU No 32/2004 yaitu menetapkan
Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. dalam formulasi pengaturan yang semacam itu maka
akan sangat sulit terjadi keseimbangan dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, karena kewenangan Kepala Desa sangat elistis
dengan menyerahkan sepenuhnya pengaturan kepada PERDA.
Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam UU No 32/2004 fungsi
bersama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa dan sebagai
penampung serta penyalur aspirasi rakyat. Berbeda sama sekali dengan
Badan Perwakilan Desa (BPD) dalamUU No 22/1999, BPD berfungsi
mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi pengawasan
terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa dan Keputusan Kepala Desa.
mekanisme tata cara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di dalam UU
No 32/2004 yaitu anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD)
adalah respretatifdari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan
dengan cara musyawarah dan mufakat artinya tidak dipilih secara langsung
akan tetapi dengan ditetapkan dengan cara musyawarah. Mekanisme tata
cara pengaturan ini pada dasarnya menghilangkan prinsip nilai demokrasi
di level wilayah desa. Sedangkan di dalamUU No 22/1999 yaitu anggota
Badan Perwakilan Desa (BPD) di pilih dari dan oleh penduduk desa yang
memenuhi persyaratan. Pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD) di pilih
dari dan oleh anggota. Badan Perwakilan Desa (BPD) bersama Kepala
Desa menetapkan Peraturan Desa. Peraturan Desa tidak memerlukan
pengesahan Bupati/Walikota, tetapi wajib ditetapkan dengan tembusan
kepada Camat, Pelaksanaan Peraturan Desa ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.
Selain itu, penggantian Badan Perwakilan Desa menjadi Badan
Permusyawaratan Desa memunculkan kembali "sistem nepotisme",
kerabat-kerabat Kepala Desa menjadi kaum elit desa karena
keangotaannya ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Perubahan
pola ini dapat di anggap sebagai pengingkaran prinsip demokrasi langsung
terhadap kedaulatan rakyat.
Selanjutnya itu, mengenai aparatur Pemerintahan Desa dalam UU No
32/2004terdiri atas Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris
Desa di isi dariPegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan. Kondisi
ini pada dasarnya akan mengarahkan Pemerintahan Desa ke arah
birokratisasi yang pengabdiaannya pun akan berbeda. Di samping itu akan
munculnya kultur pegawai negeri sipil di desa dan dapat diarahkan
kepada mesin politik baru.
Di samping itu, secara politik kedudukan Sekretaris Desa dapat
membuatnya jugaloyalitas ganda, satu sisi sebagai bawahan Kepala
Desa maka ia harus tunduk kepada Kepala Desa. namun di sisi lain
sebagai Pegawai Negeri Sipil secara otomatis maka ia juga harus tunduk
kepada atasannya yaitu Bupati/Walikota. Loyalitas ganda ini lah
menyebabkan kewenangan desa untuk mengatur dirinya sendiri menjadi
hilang. Sebab masuknya birokrasi intervensi pemerintah Kabupaten/Kota
dapat dengan mudah masuk ke desa. Jika demikian, peluang pola
pembangunan yang sentralistik dan top down (dari atas) berpeluang
untuk hadir kembali.
Dari uraian di atas penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu :
1. Mempercepat pemprosesan pembahasan dan pengesahan RUU
Pemerintahan Desa menjadi UU Pemerintahan desa sebagai payung
hukum manisfestasi prinsip demokratisasi perdesaan serta dalam
sistem pertahanan nasional dalam kerangka NKRI.
2. Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa
yang dalam tata cara dan prosesdur pertanggung jawabannya
disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa wajib memberikan
keterangan laporan pertanggung jawabannya dan kepada rakyat desa
untuk menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya
akan tetapi tetap memberi kesempatan kepada masyarakat/rakyat desa
melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menanyakan
dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang
bertalian dengan pertanggung jawaban yang di maksud.
3. Mempercepat pembangunan perdesaan dalam rangka pemberdayaan
masyarakat terutama para petani dan nelayan melalui penyediaan
prasarana, pembangunan sistem agrobisnis industri kecil dan kerajinan
rakyat, pengembangan kelembagaan, penguasaan teknologi dan
pemanfaatan sumber daya alam (SDA).
gambar: diambil dari Google.
Kajian Kritis Terhadap PP 72/2005 Tentang DESA
Jul 4, '07 12:20 AM
untuk semuanya
Otonomi Desa dan Pembangunan Desa
Ruang lingkup tanggung jawab dari birokrasi bukan hanya melakukan pelayanan
publik secara universal dan optimal, melainkan birokrasi tentu harus mengupayakan
pemerataan dalam kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan (dalam arti luas) kepada
masyarakat. Akselerasi pembangunan memang telah dirasakan semenjak terselenggaranya
reformasi di berbagai sektor , tetapi kita tidak bisa menafikan masih belum adanya keadilan
dalam pembagian kue pembangunan mengakibatkan gap antar wilayah, utamanya di
pedesaan.
Disadari bahwa pembangunan pedesaan telah banyak dilakukan sejak dari dahulu
hingga sekarang, tetapi hasilnya belum memuaskan terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat pedesaan. Pembangunan pedesaan seharusnya dilihat sebagai : (1) upaya
mempercepat pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk
memberdayakan masyarakat, dan (2) upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah
yang efektif dan kokoh.
Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek oleh karena itu perlu keterkaitan dengan
bidang sektor, dan aspek di luar pedesaan (fisik dan non fisik, ekonomi dan non ekonomi,
sosbud, dan non spasial).
Menurut Rahardjo Adisasmita
1
tujuan pembangunan pedesaan jangka
panjangadalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan secara langsung melalui
peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan bina
lingkungan, bina usaha dan bina manusia, dan secara tidak langsung adalah meletakkan
dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional. Sehingga harus disadari bahwa hakekat
dari pembangunan nasional secara komprehensif adalah dengan meletakkan pondasi atau
penopang yang kokoh pada pembangunan di tingkat desa.
Untuk merealisasikan tujuan tersebut maka seiring dengan bergulirnya era
desentralisasi dan pemberlakuan otonomi daerah seharusnya mengalir pula kewenangan yang
lebih luas kepada perangkat desa untuk berpartisipasi secara langsung dalam perencanaan
pembangunan. Partisipasi ini hanya akan terwujud apabila otonomi daerah terus mengalir
menjadi otonomi desa dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.
Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa sebagai
bentuk implementasi dari UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah maka
dilegitimasilah kekuasaan pemerintah desa untuk menyelenggarakan pemerintahan secara
mandiri. Hal ini ditambah dengan dihargainya faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-
nilai tradisional, dan kearifan lokal.
Berdasarkan semua keistimewaan yang telah diberikan, tak ada alasan lagi bagi desa
untuk tidak melaksanakan otonomi desa. Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul,
apakah semudah itu? Apakah desa telah siap untuk melaksanakan otonomi tersebut?
Benarkah pemerintah telah concern untuk melaksanakan otonomi desa?
Satu hal lain yang harus kita cermati bahwa ternyata meskipun PP Nomor 72 Tahun
2005 telah memberikan ruang yang lebih luas kepada Kepala Desa dan seluruh perangkat
desa lain untuk mengatur masyarakatnya, namun masih memerlukan penyempurnaan di
beberapa pasal agar tercapai hakekat dari otonomi desa yang sesungguhnya.
Kajian Kritis terhadap PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa
Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan
masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru
yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Kalau dulu
semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan
kecamatan, untuk konteks sekarang hal itu sudah tidak berlaku lagi. Intervensi dari atas yang
dulu sangat kental terasa kini sudah mulai berkurang. Hal itu jelas membuat pemerintah desa
menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan,
dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.
Sementara itu dari sisi masyarakat, poin penting yang dirasakan di dalam era otonomi
adalah semakin transparannya pengelolaan pemerintahan desa dan semakin pendeknya rantai
birokrasi, dimana hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh positif
terhadap jalannya pembangunan desa.
Namun persoalannya, karena tidak adanya kewenangan dan tanggung jawab yang
jelas mana ruang lingkup kewenangan desa dan mana yang menjadi kewenangan kabupaten,
sumber daya ekonomi desa seringkali terserap dan pengelolaannya diklaim sepihak oleh
kabupaten. Dari sisi ini secara ekonomi, desa pada akhirnya menjadi sangat tergantung
kepada kabupaten. Antusiasme masyarakat desa untuk melakukan pembangunan berbasis
pada kebutuhan lokal lagi-lagi terhambat oleh tidak adanya ketersediaan dana yang dapat
digunakan sebagai tumpuan operasional pembangunan.
Permasalahan lain yang muncul adalah prilaku aparat birokrasi kabupaten yang tidak
mau membuka diri dan responsif terhadap tuntutan-tuntutan desa. Lemahnya sumber daya
manusia yang ada di desa selalu menjadi justifikasi bagi pemerintah kabupaten untuk tidak
memberikan peluang otonomi bagi desa. Lagi-lagi disini kita melihat adanya kesalah-
kaprahan birokrasi dalam memahami paradigma otonomi.
Sebenarnya masih banyak persoalan lainnya dari otonomi desa yang menyimpan
potensi tidak dapat terlaksananya otonomi desa secara utuh, murni dan konsekuen serta
rawan deviasi (penyimpangan). Dan benang merah dari segala persoalan tersebut mengarah
kepada kebutuhan akan diterbitkannya peraturan pemerintah yang baru yang lebih jelas dan
memberikan kepastian hukum. Dengan asumsi demikian maka dari tinjauan aspek Hukum
Tata Pemerintahan berikut beberapa pasal dalam PP 72 Tahun 2005 yang masih bermasalah
tersebut :
a. Pertanggung-jawaban Kepala Desa
Ditinjau dari sudut aliran pertanggung-jawaban (legal-accountability)
penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa versi UU No 32/2004 maupun PP No
72/2005, terlihat sangat kentara adanya tarikan ke atas. Pasal 15 ayat (2) PP No. 72/2005
menyebutkan bahwa Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota. Tanggung jawab Kepala Desa
kepada BPD hanya dalam bentuk penyampaian laporan keterangan pertanggung-jawaban,
dan kepada masyarakat hanya menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
desa.
Rumusan aturan dalam pasal 15 ayat (2) PP desa itu tentu saja terlihat kontradiktif
dengan pasal 35 huruf b PP desa, yang mengatur kewenangan BPD untuk melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa. Meskipun pada
pasal 35 huruf c PP Desa BPD diberikan kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan dan
pemberhentian kepala desa kepada Bupati/walikota, namun mengacu pada rumusan pasal 15
ayat (2) PP Desa di atas, sangat jelas terlihat ambiguitas pengaturan kewenangan
pengawasan oleh BPD.
b. Kedudukan BPD
PP No. 72/2005 tentang Desa ternyata dinilai lebih longgar dalam melakukan
desentralisasi kekuasaan terhadap desa. PP tersebut kembali menghidupkan peran BPD
sebagai parlemen desa untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan desa. Meskipun
demikian, tentu saja sebagai suatu peraturan pelaksanaan dari UU No 32/2004, PP itu tidak
banyak mampu menawarkan paradigma baru dalam menghidupkan kembali demokrasi di
desa. Garis sub ordinasi kewenangan BPD di bawah eksekutif masih dapat dilacak jejaknya
dalam PP tentang desa itu, yang pada pasal 29 menyebutkan kedudukan BPD sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa. Padahal pasal 202 ayat (1) UU No 32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan pengertian pemerintah desa hanya terdiri atas kepala desa
dan perangkat desa. Kemudian dilanjutkan dalam ayat (2) pasal yang sama bahwa yang
dimaksud perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Tidak
diperinci dan ditegaskan secara lebih jelas kedudukan BPD sebagai salah satu unsur
penyelenggara pemerintah desa.
c. Sistem Perencanaan
Menyangkut sistem perencanaan di desa terlihat pula belum adanya kehendak Negara
untuk membangun pola local self planning di desa. Pasal 63 PP Desa masih mengikuti jejak
UU No. 32/2004, yang menempatkan perencanaan desa sebagai satu kesatuan dengan sistem
perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Sementara itu, pasal 150 UU No. 32/2004
telah menegaskan bahwa sistem perencanaan daerah merupakan satu kesatuan dengan
perencanaan pembangunan nasional. Apabila ditarik garis lurus untuk menghubungkan
substansi pengaturan mengenai perencanaan di desa, daerah dan pusat, terlihat sangat jelas
yang dibangun adalah model perencanaan terpusat (centralized planning). Sentralisasi
perencanaan semacam itu sebenarnya justru mengingkari hakekat otonomi daerah, yang
seharusnya terus mengalir menjadi otonomi desa dan akhirnya menjadi otonomi rakyat.
Filosofi pembangunan yang bertumpu pada paradigma klasik (trickle down effect)
yang diintroduksikan oleh Albert Hirschmann atau lebih lebih dikenal konsep top-down, telah
menimbulkan masalah yang cukup serius seperti ketimpangan, kemiskinan, keterbelakangan,
dan sikap masa bodoh atau ketidakpedulian (antar daerah dan antar golongan masyarakat).
Pengaplikasian konsep itu secara empirik telah memperlihatkan terjadinya kecenderungan
kurang memberikan perhatian kepada masyarakat lapisan bawah (grass root). Konsep
semacam ini tidak aspiratif dan dianggap tidak bijaksana terhadap permasalahan yang
dihadapi, pemanfaatan potensi masyarakat desa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat
sebagai penerima program pembangunan.
Meskipun kini pemerintah me-mercusuarkan program bottom up planning dengan
kegiatan Musbangdes (Musyawarah Pembangunan Desa), rapat LPM tingkat kecamatan,
Rakorbang tingkat kabupaten dan propinsi hingga Rakornas tingkat pusat, namun
kenyataannya belum dapat dilaksanakan secara optimal. Bahkan kondisi riil di lapangan
terkadang ditemukan usulan yang dirumuskan dari level bawah, diintervensi oleh kekuasaan
yang berada setingkat di atasnya. Pada tingkat LPM dan Rakorbang juga seringkali
ditemukan adanya dominasi sektoral dalam proses bargaining tanpa melihat dan
mempertimbangkan usul yang muncul dari bawah.
Dalam akhir tulisan ini, penulis mendapat kesimpulan bahwa dengan adanya revisi
UU 22/1999 menjadi UU 32/2004 belum menjawab tuntas permasalahan desa, karena tersirat
dalam peraturan perundangan tersebut pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan
otonomi yang luas. Begitupun paradigma orde baru nampaknya masih dipakai pemerintah
pusat saat ini, yang menganggap desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.
PP 72/2005 sebagai peraturan pelaksana dari UU 32 Tahun 2004 perlu dikaji lebih
lanjut. Kelemahan peraturan ini sebagaimana paparan di atas harus segera dibenahi.
Tujuannya tentu untuk menciptakan tata pemerintahan desa yang ideal sesuai dengan tuntutan
dan kebutuhan masyarakat desa. Sebagaimana disampaikan Prof.DR. Ryaas Rasyid, MA.
pakar otonomi daerah dalam acara kuliah umum di hadapan mahasiswa S1 PIN bahwa perlu
dilakukan break-down terhadap UU 32/2004 menjadi tiga perundang-undangan yang secara
khusus mengatur masalah pilkada, keuangan daerah, serta pemerintahan desa berikut
pembenahannya.
Asumsi desa wajib diberdayakan karena dianggap bodoh, sudah usang. Idealnya yang
perlu dibenahi oleh pemerintah pusat adalah melepas sekat-sekat penghalang bagi desa untuk
berkembang. Sesungguhnya tidak tepat jika muncul ketakutan pemerintah, desa akan akan
memisahkan diri dari NKRI apabila diberikan kekuatan (baca : kekuasaan) yang lebih besar,
karena ketakutan tersebut sangat tidak mendasar.
Otonomi bukanlah bebas yang sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang bertanggung jawab,
bermartabat, dan bertujuan untuk kemaslahatan ummat. Sikap dilema dan kegamangan desa
seperti sekarang akan mengubah peluang menjadi hambatan ... Inikah yang kita kehendaki ?
Kata kunci: artikel-koe
Permasalahan yang Timbul dalam
Pelaksanaan Otonomi Daerah
Diterbitkan Maret 25, 2012 Tugas Kuliah , Uncategorized 32 Komentar
Kaitkata:disintegrasi, dprd, eksploitasi sumberdaya terhadap daerah, kepala daerah otonomi
daerah, korupsi di pemerintahan daerah, masalah otonomi daerah, peran masyarakat dalam
otonomi daerah, peraturan daerah, permasalahan otonomi daerah,permasalahan yang
timbul, prinsip otonomi daerah, tujuan otonomi daerah
PERMASALAHAN OTONOMI DAERAH
Oleh :
8335116615 Dwi Yunita Sari
8335118318 Rizqi Amelia Pratiwi
8335118326 Syifa Aulia
8335118330 Ruth Citra Permata
Program Studi S1 Akuntansi
Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
2012
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb.
Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan YME, karena atas berkat rahmat-Nya
penulis dapat menyelesaikan Tugas Kelompok untuk memenuhi mata kuliah Bank dan Lembaga
Keuangan Lain.
Dalam penulisan karya tulis ini penulis membahas tentang Permasalahan Dalam Otonomi
Daerah sesuai dengan tujuan instruksional khusus mata kuliah Kewarganegaraan, Program Studi
S1 Akuntansi, Jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.
Dengan menyelesaikan karya tulis ini ini, tidak jarang penulis menemui kesulitan. Namun penulis
sudah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikannya, oleh karena itu penulis mengharapkan
kritik dan saran dari semua pihak yang membaca yang sifatnya membangun untuk dijadikan
bahan masukan guna penulisan yang akan datang sehingga menjadi lebih baik lagi. Semoga karya
tulis ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak, maka
pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :
1. Bapak Yuyus Kardiman
2. Kedua orang tua yang telah memberikan dukungan serta doanya
3. Teman-teman S1 Akuntansi Non-Regular B 11 sebagai tempat untuk berdiskusi dan
bertukar pikiran
Wassalamualaikum Wr. Wb
Jakarta, Maret 2012
Penulis
DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi .
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang .
1.2. Rumusan Masalah .
1.3. Tujuan Penulisan
1.4. Manfaat Penulisan
1.5. Sistematika Penulisan ...
1.6. Metodologi Penelitian .
BAB II PEMBAHASAN
2.1. Pengertian Otonomi Daerah ...
2.2. Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia .
2.2.1. Adanya Eksploitasi Pendapatan Daerah.
2.2.2. Pemahaman konsep desentralisasi & otonomi daerah belum mantap
2.2.3. Aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai..
2.2.4. Kondisi SDM yang belum menunjang pelaksanaan otonomi daerah
2.2.5. Korupsi di Daerah
2.2.6. Potensi munculnya konflik antar daerah
BAB III PENUTUP
3.1. Simpulan
3.2. Saran
Daftar Pustaka
i
ii
1
1
2
2
3
3
4
5
6
8
10
13
21
25
28
28
iii
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari
pengertian tersebut di atas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah
pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.
Implementasi otonomi daerah telah memasuki era baru setelah pemerintah dan DPR sepakat
untuk mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua UU
otonomi daerah ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 sehingga
kedua UU tersebut kini tidak berlaku lagi.
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan
penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya
perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut
menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus
memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju,
mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan
daerahnya masing-masing.
Memang harapan dan kenyataan tidak lah akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan
berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. Namun
ketidaktercapaian harapan itu nampak nya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di
Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia.
Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi
daerah dapat tercapai.
1.2. Rumusan Masalah
Dalam penyusunan ini penulisan memberikan batasan-batasan masalah, meliputi :
1. Eksploitasi Pendapatan Daerah
2. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi
daerah yang belum mantap
3. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai
4. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi
daerah
5. Korupsi di Daerah
6. Potensi munculnya konflik antar daerah
1.3. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan ini di bagi menjadi 2 yaitu, tujuan umum dan khusus:
1.3.1 Tujuan Umum
1. Mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia
2. Meneliti penyelesaian dari permasalahan yang ada
1.3.2 Tujuan Khusus
Menyelesaikan tugas mata kuliah Kewarganegaraan tentang Permasalahan Dalam Otonomi Daerah
1.4. Manfaat Penulisan
1. Sebagai bahan pelajaran bagi mahasiswa.
2. Sebagai wacana awal bagi penyusunan karya tulis selanjutnya.
3. Sebagai literature untuk lebih memahami otonomi daerah di Indonesia.
1.5. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan Karya Tulis ini, sistematika penulisan yang digunakan adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Berisi tentang : Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan
sistematika penulisan.
BAB II PEMBAHASAN
Berisi tentang : Pembahasan mengenai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia.
BAB III PENUTUP
Berisi tentang : kesimpulan dan saran.
1.6. Metodologi Penelitian
Dalam penulisan Karya Tulis ini, metodologi penelitian yang digunakan adalah :
Studi pustaka yaitu dengan mencari referensi dari buku-buku yang berkaitan dengan
penulisan karya tulis ini
Penjelajahan internet yaitu dengan mencari beberapa informasi di mesin pencari yang tidak
penulis tidak dapatkan dari buku-buku
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Otonomi Daerah
Otonomi Daerah adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari
rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi
maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah
istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan
kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir
ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi
sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga
dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya
(dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang
melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih
dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang
dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum
dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin
dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif
peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan
dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk
memenuhi kebutuhan lokal.
2.2 Permasalahan Dalam Otonomi Daerah Di Indonesia
Sejak diberlakukannya paket UU mengenai Otonomi Daerah, banyak orang sering membicarakan
aspek positifnya. Memang tidak disangkal lagi, bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif
di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi
sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah
sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu,
pengerukan potensi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan.
Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses pemiskinan
yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa
mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut.
Akan tetapi apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbersit kekhawatiran bahwa otonomi
daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang, jika tidak segera dicari pemecahannya,
akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya? Jika jawabannya tidak, tentu akan
sangat naif. Mengapa? Karena, tanpa disadari, beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi
pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila
dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia.
Masalah-masalah tersebut antara lain :
1. 1. Adanya eksploitasi Pendapatan Daerah
2. 2. Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap
3. 3. Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai
4. 4. Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnyapelaksanaan
otonomi daerah
5. 5. Korupsi di Daerah
6. 6. Adanya potensi munculnya konflik antar daerah
Permasalahan tersebut dibahas lebih lanjut sebagai berikut :
2.2.1 Adanya eksploitasi Pendapatan Daerah
Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan
keuangannya, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan
pendapatan daerah tersebut. Dalam kewenangan semacam ini sebenarnya sudah muncul inherent
risk, risiko bawaan, bahwa daerah akan melakukan upaya maksimalisasi, bukan optimalisasi,
perolehan pendapatan daerah. Upaya ini didorong oleh kenyataan bahwa daerah harus
mempunyai dana yang cukup untuk melakukan kegiatan, baik itu rutin maupun pembangunan.
Daerah harus membayar seluruh gaji seluruh pegawai daerah, pegawai pusat yang statusnya
dialihkan menjadi pegawai daerah, dan anggota legislatif daerah. Di samping itu daerah juga
dituntut untuk tetap menyelenggarakan jasa-jasa publik dan kegiatan pembangunan yang
membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Dengan skenario semacam ini, banyak daerah akan terjebak dalam pola tradisional dalam
pemerolehan pendapatan daerah, yaitu mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi. Bagi
pemerintah daerah pola ini tentu akan sangat gampang diterapkan karena kekuatan koersif yang
dimiliki oleh institusi pemerintahan; sebuah kekuatan yang tidak applicable dalam negara
demokratis modern. Pola peninggalan kolonial ini menjadi sebuah pilihan utama karena
ketidakmampuan pemerintah dalam mengembangkan sifat wirausaha (enterpreneurship).
Apakah upaya intensifikasi pajak dan retribusi di daerah itu salah? Tentu tidak. Akan tetapi yang
jadi persoalan sekarang adalah bahwa banyak pemerintah daerah yang terlalu intensif memungut
pajak dan retribusi dari rakyatnya. Pemerintah daerah telah kebablasan dalam meminta
sumbangan dari rakyat. Buktinya adalah jika menghitung berapa item pajak dan retribusi yang
harus dibayar selaku warga daerah. Jika diteliti, jumlahnya akan mencapai ratusan item.
Beberapa bulan lalu berkembang sinisme di kalangan warga DKI Jakarta, bahwa setiap aktivitas
yang mereka lakukan telah menjadi objek pungutan Pemda DKI, sampai-sampai buang hajat pun
harus membayar retribusi. Pemda Provinsi Lampung juga bisa menjadi contoh unik ketika
menerbitkan perda tentang pungutan terhadap label sebuah produk. Logika yang dipakai adalah
bahwa label tersebut termasuk jenis papan reklame berjalan. Hal ini terlihat lucu. Karena
tampaknya Pemerintah setempat tidak bisa membedakan mana reklame, sebagai bentuk iklan,
dan mana label produk yang berfungsi sebagai identifikasi nama dan spesifikasi sebuah produk.
Kedua, jika perda tersebut diberlakukan (sepertinya kurang meyakinkan apakah perda tersebut
jadi diberlakukan atau tidak), akan timbul kesulitan besar dalam penghitungan dan pemungutan
retribusi.
Dengan dua contoh tersebut, penulis ingin mengatakan bahwa upaya pemerintah daerah dalam
menggali pendapatan daerah di era otonomi ini telah melampaui batas-batas akal sehat. Di satu
pihak sebagai warga negara kita harus ikut berpartisipasi dalam proses kebijakan publik dengan
menyumbangkan sebagian kemampuan ekonomi yang kita miliki melalui pajak dan retribusi. Akan
tetapi, apakah setiap upaya pemerintah daerah dalam memungut pendapatan dari rakyatnya
hanya berdasarkan justifikasi semacam itu? Tidak adakah ukuran kepantasan, sejauh mana
pemerintah daerah dapat meminta sumbangan dari rakyatnya?
Bila dikaji secara matang, instensifikasi perolehan pendapatan yang cenderung eksploitatif
semacam itu justru akan banyak mendatangkan persoalan baru dalam jangka panjang, dari pada
manfaat ekonomis jangka pendek, bagi daerah. Persoalan pertama adalah beratnya beban yang
harus ditanggung warga masyarakat. Meskipun satu item pajak atau retribusi yang dipungut dari
rakyat hanya berkisar seratus rupiah, akan tetapi jika dihitung secara agregat jumlah uang yang
harus dikeluarkan rakyat perbulan tidaklah kecil, terutama jika pembayar pajak atau retribusi
adalah orang yang tidak mempunyai penghasilan memadai. Persoalan kedua terletak pada adanya
kontradiksi dengan upaya pemerintah daerah dalam menggerakkan perekonomian di daerah.
Bukankah secara empiris tidak terbantahkan lagi bahwa banyaknya pungutan hanya akan
menambah biaya ekonomi yang ujung-ujungnya hanya akan merugikan perkembangan ekonomi
daerah setempat. Kalau pemerintah daerah ingin menarik minat investor sebanyak-banyaknya,
mengapa pada saat yang sama justru mengurangi minat investor untuk berinvestasi ?
2.2.2 Pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap
Desentralisasi adalah sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang menyangkut pola
hubungan antara pemerintah nasional dan pemerintah lokal. Tujuan otonomi daearah
membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan
domestik, sehingga pemerintah pusat berkesempatan mempelajari, memahami dan merespon
berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat dari padanya.Pemerintah hanya
berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis.
Desentralisasi diperlukan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan. Sebagai wahana pendidikan politik di daerah. Untuk memelihara keutuhan negara
kesatuan atau integrasi nasional. Untuk mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang dimulai dari daerah. Untuk memberikan peluang kepada masyarakat utntuk
membentuk karir dalam bidang politik dan pemerintahan. Sebagai sarana bagi percepatan
pembangunan di daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Oleh
karena itu pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi haruslah mantap.
Elemen utama dari desentralisasi adalah:
1. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur wewenang serta tanggung jawab politik dan
administratif pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten dalam struktur yang
terdesentralisasi.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi UU No. 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan
dasar hukum bagi desentralisasi fiskal dengan menetapkan aturan baru tentang pembagian
sumber-sumber pendapatan dan transfer antarpemerintah.
Undang-undang di atas mencakup semua aspek utama dalam desentralisasi fiskal dan
administrasi. Berdasarkan kedua undang-undang ini, sejumlah besar fungsi-fungsi pemerintahan
dialihkan dari pusat ke daerah sejak awal 2001 dalam banyak hal melewati provinsi.
Berdasarkan undang-undang ini, semua fungsi pelayanan publik kecuali pertahanan, urusan luar
negeri, kebijakan moneter dan fiskal, urusan perdagangan dan hukum, telah dialihkan ke daerah
otonom. Kota dan kabupaten memikul tanggung jawab di hampir semua bidang pelayanan publik
seperti kesehatan, pendidikan, dan prasarana; dengan provinsi bertindak sebagai koordinator. Jika
ada tugas-tugas lain yang tidak disebut dalam undang-undang, hal itu berada dalam tanggung
jawab pemerintah daerah.
Pergeseran konstitusional ini diiringi oleh pengalihan ribuan kantor wilayah (perangkat pusat)
dengan sekitar dua juta karyawan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung mulai
tahun 2005. Lebih penting lagi, Dana Alokasi Umum atau DAU yang berupa block grant menjadi
mekanisme utama dalam transfer fiskal ke pemerintah daerah, menandai berakhirnya
pengendalian pusat terhadap anggaran dan pengambilan keputusan keuangan daerah. DAU
ditentukan berdasarkan suatu formula yang ditujukan untuk memeratakan kapasitas fiskal
pemerintah daerah guna memenuhi kebutuhan pengeluarannya. Pemerintah Pusat juga akan
berbagi penerimaan dari sumber daya alam gas dari daratan (onshore), minyak dari daratan,
kehutanan dan perikanan, dan sumber-sumber lain dengan pemerintah daerah otonom.
Kedua undang-undang baru ini serta perubahan-perubahan yang menyertainya mencerminkan
realitas politik bahwa warga negara Indonesia kebanyakan menghendaki peran yang lebih besar
dalam mengelola urusan sendiri. Meskipun demikian, tata pemerintahan lokal yang baik pada saat
ini belum dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun sistem desentralisasi telah dilaksanakan.
Periode yang tengah dialami oleh Indonesia pasca dikeluarkannya UU No. 22/ 1999 yaitu periode
transisi atau masa peralihan sistem. Artinya, secara formal sistem telah berubah dari sentralistik
menjadi desentralisasi. Tetapi, mentalitas dari aparat pemerintah baik pusat maupun daerah
masih belum mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terjadi karena perubahan sistem tidak
dibarengi penguatan kualitas sumber daya manusia yang menunjang sistem pemerintahan yang
baru. Pelayanan publik yang diharapkan, yaitu birokrasi yang sepenuhnya mendedikasikan diri
untuk untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai pengguna jasa adalah pelayanan publik yang
ideal. Untuk merealisasikan bentuk pelayanan publik yang sesuai dengan asas desentralisasi
diperlukan perubahan paradigma secara radikal dari aparat birokrasi sebagai unsur utama dalam
pencapaian tata pemerintahan lokal.
2.2.3 Penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai
Bermula dari Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dilanjutkan dengan 7 Mei 1999, lahir UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah selanjutnya
UU No. 25/1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan daerah, menggantikan UU No.
5/1974 yang sentralistik.
Kedua undang-undang ini mengatur wewenang otonomi yang diberikan luas kepada pemerintah
tingkat kabupaten dan kota. Bupati dan walikota pun dinyatakan bukan lagi sebagai aparat
pemerintah yang hierarkis di bawah gubernur. Jabatan tertinggi di kabupaten dan kota itu
merupakan satu-satunya kepala daerah di tingkat lokal, tanpa bergantung pada gubernur.
Setiap bupati dan walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengelola daerah kekuasaannya.
Keleluasaan atas kekuasaan yang diberikan kepada bupati/walikota dibarengi dengan mekanisme
kontrol (checks and balances)yang memadai antara eksekutif dan legislatif.
Parlemen di daerah tumbuh menjadi sebuah kekuatan politik riil yang baru. Lembaga legislatif ini
secara merdeka dapat melakukan sendiri pemilihan gubernur dan bupati/walikota tanpa intervensi
kepentingan dan pengaruh politik pemerintah pusat. Kebijakan di daerah juga dapat ditentukan
sendiri di tingkat daerah atas kesepakatan pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRD). Undang-undang yang baru juga mengatur bahwa setiap peraturan daerah dapat
langsung dinyatakan berlaku setelah disepakati sejauh tidak bertentangan dengan peraturan
perundangan yang lebih tinggi tingkatannya. Hal ini kontras berbeda dengan ketentuan
sebelumnya yang mensyaratkan adanya persetujuan dari penguasa pemerintahan yang lebih
tinggi bagi setiap perda yang akan diberlakukan.
UU No 22/1999 dan UU No 25/1999 juga memberikan kerangka yang cukup ideal bagi
terwujudnya keadaan politik lokal yang dinamis dan demokratis di setiap daerah. Namun, praktik-
praktik politik yang menyusul setelah itu masih belum sepenuhnya memperlihatkan adanya
otonomi yang demokratis. Setidaknya terdapat dua penyebab utama mengapa hal ini bisa terjadi.
Pertama, pemerintah pusat rupanya tak kunjung serius memberikan hak otonomi kepada
pemerintahan di daerah. Ketidakseriusannya dapat dilihat dari pembiaran pemerintah pusat
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan lama yang tidak lagi sesuai dengan UU otonomi
yang baru. Padahal, ada ratusan Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan berbagai
peraturan lainnya yang harus disesuaikan dengan kerangka otonomi daerah yang baru. Ketiadaan
aturan pelaksanaan baru yang mendukung otonomi daerah yang demokratis menjadikan kedua UU
menyangkut otonomi daerah itu mandul dan tak efektif. Sementara di tingkat daerah,
ketiadaannya telah melahirkan kebingungan.
Kedua, desentralisasi telah menggelembungkan semangat yang tak terkendali di kalangan
sebagian elit di daerah sehingga memunculkan sentimen kedaerahan yang amat kuat. Istilah
putra daerah mengemuka di mana-mana mewakili sentimen kedaerahan yang terwujud melalui
semacam keharusan bahwa kursi puncak pemerintahan di daerah haruslah diduduki oleh tokoh-
tokoh asli dari daerah bersangkutan. Hal ini tentu saja bukan sesuatu yang diinginkan apalagi
menjadi tujuan pelaksanaan otonomi daerah. Bagaimanapun, fenomena putra daerah itu begitu
meruak di berbagai daerah.
Hubungan pusat dan daerah juga masih menyimpan ancaman sekaligus harapan. Menjadi sebuah
ancaman karena berbagai tuntutan yang mengarah kepada disintegrasi bangsa semakin besar.
Bermula dari kemerdekaan Timor Timur (atau Timor Leste) pada tanggal 30 Agustus 1999 melalui
referendum. Berbagai gelombang tuntutan disintegrasi juga terjadi di beberapa daerah seperti di
Aceh, Papua, Riau dan Kalimantan. Meskipun ada sejumlah kalangan yang menganggap bahwa
kemerdekaan Timor Timur sudah seharusnya diberikan karena perbedaan sejarah dengan bangsa
Indonesia dan merupakan aneksasi rezim Orde Baru, tetapi efek domino yang timbulkannya masih
sangat dirasakan, bahkan dalam MoU Helsinki yang menghasilkan UU Pemerintahan Aceh.Gejolak
terus berlanjut hingga, Aceh dan Papua akhirnya diberi otonomi khusus.
Menjadi harapan, karena Amandemen kedua konstitusi, telah mengubah wajah Pemerintahan
Daerah menjadi lebih demokratis dan lebih bertanggung jawab. Pasal 18 ayat (5) UUD 1945
(redaksi baru), Perubahan Kedua, berbunyi, Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-
luasnya, kecuali urusan pemreintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan
Pemerintah Pusat. Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan Pasal 18
ayat (1) dan (5) UUD 1945 (redaksi baru).
Dalam pemhaman ini, M. Laica Marzuki mengatakan, bentuk negara (de staatsvorm) RI secara
utuh harus dibaca -dan dipahami- dalam makna: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang
berbentuk Republik, yang disusun berdasarkan desentralisatie, dijalankan atas dasar otonomi yang
seluas-luasnya, menurut Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (redaksi baru) juncto Pasal 18 ayat (1) dan
(5) UUD 1945 (redaksi baru).
Lima tahun berlangsung, UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 dipandang perlu direvisi, hingga
lahirlah UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33/2004 tentang Perimbangan
Keuangan menggantikan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 tersebut.
Pasal 1 angka 7 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan
desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pemerintah Pusat,
dalam hal ini Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara RI, menurut UUD
1945 (Pasal 1 angka 1 UU Nomor 32 Tahun 2004).
Penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom bermakna
peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebutdelegation of authority.
Tatkala terjadi penyerahan wewenang secara delegasi, pemberi delegasi kehilangan kewenangan
itu, semua beralih kepada penerima delegasi. Dalam hal pelimpahan wewenang secara mandatum,
pemberi mandat atau mandator tidak kehilangan kewenangan dimaksud. Mandataris bertindak
untuk dan atas nama mandator.
Dengan demikian, dalam hal penyerahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat
kepada daerah otonom secara delegasi, untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
memberikan konsekuensi bahwasanya pemerintah pusat kehilangan kewenangan dimaksud.
Semua beralih kepada daerah otonom, artinya menjadi tanggungjawab pemerintahan daerah,
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai urusan pemerintah
pusat. Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan, bahwasanya urusan
pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi a. politik luar negeri, b.
pertahanan, c. keamanan, d. yustisi, e. moneter dan fiskal, f. agama.
Pusat tidak boleh mengurangi, apalagi menegasikan kewenangan pemerintahan yang telah
diserahkan kepada daerah otonom. Namun demikian, daerah otonom-daerah otonom tidak boleh
melepaskan diri dari Negara Kesatuan RI. Betapa pun luasnya cakupan otonomi, desentralisasi
yang mengemban pemerintahan daerah tidaklah boleh meretak-retakkan bingkai Negara Kesatuan
RI.
Secara formal normatif, arah desentralisasi sudah cukup baik. Namun, dalam tataran empiris
komitmen pemerintah pusat tidak konsisten. Praktek-praktek monopoli dan penguasaan urusan-
urusan strategis yang menyangkut pemanfaatan sumber daya alam termasuk perizinan di daerah,
dikuasai pusat.
Intervensi pusat pada daerah begitu besar. Penyerahan urusan/wewenangan yang semestinya
dilakukan dengan penyerahaan sumber keuangan tidak dilakukan. Pusat melakukan penganggaran
pembangunan daerah tanpa melibatkan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Pembiayaan fungsi-fungsi pemerintahan di daerah lebih dominan berasal dari APBN, yang
semestinya diserahkan sebagai dana perimbangan untuk APBD.
UU No. 32 Tahun 2004 ini sempat mengalami perubahan berdasarkan UU No. 8 tahun 2005 dan
UU No. 12 tahun 2008.
Tahun 2007, kemudian dikeluarkan PP No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan. Walau telah
dibagi-bagi kewenangan pusat dan daerah, namun PP ini dipandang telah menegasikan
kewenangan daerah. Revisi lebih komprehensif kemudian diwacanakan kembali pada UU No.
32/2004 untuk lebih menterjemahkan lebih kongkrit kewenangan pusat dan daerah.
2.2.4 Kondisi SDM aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan
otonomi daerah
Sejak diberlakukannya otonomi daerah. Sebagian pemerintah daerah bisa melaksanakan amanat
konstitusi meningkatkan taraf hidup rakyat, menyejahterakan rakyat, dan mencerdaskan rakyat.
Berdasarkan data yang ada 20 % pemerintah daerah mampu menyelenggarakan otonomi daerah
dan berbuah kesejahteraan rakyat di daerah. Namun masih 80 % pemerintah daerah dinilai belum
berhasil menjalankan visi, misi dan program desentralisasi.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang sehat dapat di wujudkan pertama-tama dan terutama di
tentukan oleh kapasitas yang di miliki manusia sebagai pelaksananya. Penyeenggaraan otonomi
daerah hanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya apabil manusia pelaksananya baik,dalam arti
mentalitas maupun kapasitasnya.
Pentingnya posisi manusia pelakana ini karena manusia merupakan unsur dinamis dalam
organisasi yang bertindak/berfungsi sebagai subjek penggerak roda organisasi pemerintahan. Oleh
sebap itu kualitas mentalitas dan kapasitas manusia yang kurang memadai dengan sendirinya
melahirkan impikasi yang kurang menguntungkan bagi penyelenggaraan otonomi daerah. Anusia
pelaksana pemerintah daerah dapat di kelompokkan menjadi:
1. Pemerintah daerah yang terdiri dari kepala daerah dan dewan perwakilan daerah (DPRD).
2. Alat-alat perlengkapan daerah yakni aparatur daerah dan pegawai daerah
3. Rakyat daerah yakni sebagai komponen environmental (lingkungan)yang merupakan sumber
energi terpenting bagi daerah sebagai organisasi yang bersifat terbuka.
2.2.4.1. Kepala daerah dan DPRD
Dalam negara kesatuan republik indonesia tugas kepla daerah di samping sebagai kepala daerah
juga merupakan alat pemerintah pusat yang menjalani tugas yang sangat berat. Oleh sebap itu
kualifikasi yang di tuntut seorang kepala daerah seharusnya juga memadai dalam pengertian
harus sebanding dengan beban tugas ing dengan beban tugas yang ada di pundaknya.
Dalam kenyataan syarat syarat yang di tentukan bagi seorang kepala daerah belum cukup
menjamin tuntutan kualitas yang ada. Di mana yang berkaitan dengan kapasitas (pengetahuan
dan kecakapan) hanya tiga syarat yang di penuhi masing-masing;cerdas,berkemampuan,dan
keterampilan;mempunyai kecakapan dan pengelaman kerja yang cukup di bidang
pemerintahan;berpengetahuan yang sederajat degan perguruan tinggi atau sekurang kurangnya di
persamakan dengan sarjana muda.
Demikian pula halnya dengan mentalitas tidak terdapat ukuran-ukuran yang dapat di pergunakan
sebagai tolok ukur objektif,sehinggga terdapat cukup banyak kesulitan dalam penilaian padahal
peranan mental ini sangat penting dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
Kepala daerah yang didominasi oleh pertimbangan akseptabilitas (walaupun kadang kala tidak
objektif) dari pada kualitas dan kapabilitas seseorang calon KDH.
Kepala daerah yang banyak mengorbankan uang, lebih berorientasi kepada proyek pribadi, yaitu
untuk memperoleh keuntungan secara finansial dan material.
Kepala daerah cenderung membentuk kelompok-kelompok ditengah-tengah birokrasi, sehingga
terdapat perlakuan yang diskriminatif dikalangan birokrasi.
Kepala daerah ada yang tidak konsisten terhadap visi dan misi daerah (walaupun disampaikan
pada saat menjadi calon), karena menganggap visi dan misi yang disampaikan hanya untuk
kepentingan sesaat.
Kepala daerah yang lebih berorientasi untuk mempertahankan kekuasaan walaupun dengan cara
dan kebijaksanaan yang tidak memenuhi kaidah moral dan etika bahkan menyimpang dari
peraturan dan perundangan.
Hal yang dikemukakan diatas merupakan kondisi dan gejala umum, walaupun ada yang berbuat,
berprilaku dan membuat kebijakan sesuai dengan ketentuan serta tujuan dari otonomi daerah
tersebut, namun jumlahnya tidak seberapa. Untuk itu perlu adanya perubahan sistemik dengan
cara sbb:
Untuk menjadi calon kepala daerah perlu diperhatikan kapabilitasnya, tidak hanya
akseptabilitasnya saja, oleh karena seorang kepala daerah tidak hanya pemimpin politik, tetapi
juga pimpinan pemerintah yang didalamnya terdapat ilmu, seni, dan teknis pemerintahan.
Dalam era globalisasi, penyelenggaraan pemerintahan (pelaksanaan otonomi daerah) itu tidak
terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu seorang calon kepala
daerah harus memiliki basis ilmu yang sesuai dengan tingkat kecerdasan masyarakat dan
lingkungan.
Untuk Wakil kepala daerah sebaiknya tidak harus dari orang-orang partai politik, tetapi lebih
diutamakan yang berpengalaman di birokrasi pemerintahan, sehingga wakil kepala daerah lebih
terfokus membantu kepala daerah dalam hal-hal teknis pemerintahan.
Perlu standar yang jelas tentang biaya untuk keikut sertaan dalam pemilihan kepala daerah,
sungguhpun sulit diimplementasikan tetapi sudah ada suatu ukuran atau pedoman.
Kepala daerah dihindarkan dari intervensi terhadap hal-hal yang bersifat sangat teknis seperti
administrasi keuangan, administrasi kepegawaian maupun administrasi proyek-proyek
pembangunan. Yang dilakukan kepala daerah adalah menyusun dan menetapkan kebijakan
umum, mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut serta memberikan motivasi dan pembinaan.
Dalam menjalankan kepemimpinannya, kepala daerah harus memiliki kekuasaan, sebagai mana
dikemukakan oleh Prof Dr J Kaloh: Kekuasaan paksaan (esencive power), kekuasaan resmi
(legitimate power), kekuasaan keteladanan (referent power) dan kekuasaan keahlian (exper
power).
Seperti halnya kepala daerah,DPRDpun memiliki beban tugas yang tidak ringan,karena tugas
pokoknya adalah bersama-sama kepala daerah menetapkan kebijakan daerah baik yang berupa
peraturan-peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah(APBD). Di samping itu
DPRD ujga menjalankan fungsi pengawasan atas pelakanaan kebijakan daerah oleh kepala daerah.
Dengan tugas dan fungsi semacam ini DPRD di tuntut untuk memiliki kualitas yang memadai
Dalam kenyataannya pendidikan dan pengelaman yang di miliki oleh DPRD masih di bawah rata-
rata dan masih sangat terbatas .rata- rata DPRD tidak di bekali dengan pendidikan dan
pengelaman yang cukup di bidang pemerintahan. Hal ini akan sangat berpengaruh dalam
penyelenggaraan otonomi daerah
Berdasarkan data tentang terjadinya tidak pidana korupsi di daerah sebagai contoh dari 35 daerah
otonom kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Selama 2011 kasus korupsi yang ditangani Polda
Jateng tercatat 78 kasus dengan 86 tersangka. Polda mengklaim telah menyelamatkan kerugian
negara sebanyak Rp 34.612.637.000. Jumlah tersebut naik sekitar 143 persen dari tahun 2010
yang berjumlah 32 kasus. Jumlah tersangka pada tahun lalu pun kalah jauh yang hanya berjumlah
31 orang dengan kerugian negara Rp. 23.693.274.000 (Suara Merdeka, 13/12/2011).
Sepanjang 2004-2011 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat terdapat sebanyak 158
kasus korupsi yang menimpa kepala daerah yang terdiri atas gubernur, bupati, dan wali kota.
Sementara dalam periode 2008-2011, sedikitnya terdapat 42 anggota DPR terseret kasus korupsi
(Republika, 5/12/2011).
Rakyat merasa sayang bila APBD dan APBN selalu defisit, namun kesejahteraan rakyat tidak
terasakan oleh rakyat di daerah. Maka bisa ditebak bahwa pasti ada penyimpangan dalam
pelaksanaan otonomi daerah yang sedang berjalan. Sebagai bukti visi, misi dan program otonomi
daerah tersebut tidak optimal. Berdasarkan data Kementrian Dalam negeri yang menunjukkan
bahwa 158 kasus korupsi kepala daerah. Sungguh suatu ironi pembangunan di negeri katulistiwa
ini.
Otonomi yang digadang-gadang sebagai solusi kesejahteraan rakyat di daerah sebaliknya menjadi
buah simala kama yang menelan korban kader-kader terbaik rakyat di daerah. Menjerat kepala
daerah sebagai kader terbaik di daerah terjerat kasus korupsi yang sangat menyedihkan dan
memprihatinkan.
Hal ini membawa kerugian yang besar bagi daerah. Satu sisi mekanisme pemilihan kepala daerah
yang demokratis telah mengantarkan kader terbaik daerah tampil mempimpin daerahnya sendiri
dengan harapan kedekatan psikologis bisa membangunkan semakin reformasi di daerah bisa lebih
sejahtera. Namun sebaliknya menyebabkan moralitas dan mentalitas aparatur di daerah mudah
tergiur dengan aliran dana pusat kepada daerah yang begitu besar. Sementara kemampuan
profesionalitas pengelolaan anggaran belum mendapatkan pelatihan sumber daya yang memadai,
sehingga banyak penyimpangan yang terjadi.
Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah ini maka suatu langka sistematis
harus di ambil. Upaya-upaya meningkatkan syarat pendidikan dan pengelaman berorganisasi
ataupun peningkatan frekuensi latihan,kursus,dan sebagainya,yang berkaitan dengan bidang
tugas yang menjadi tanggungjawabnya masing-masing perlu di tingkatkan.
Beberapa hal yang perlu dikemukakan yang menjadi persoalan bagi DPRD yaitu:
Dengan pola rekrutmen anggota DPRD yang lebih menekankan kepada aspek politis, maka ditemui
anggota DPRD yang rendah kualitasnya baik dari segi pengetahuan maupun pengalamannya.
Ada kecendrungan jadi anggota DPRD sebagai satu-satunya lapangan pekerjaan bukan
pengabdian sehingga lebih mementingkan imbalan yang bersifat material-finansial.
Kurang ada kemauan untuk belajar bagi peningkatan kapasitas pribadi, sehingga gagasan,
pendapat ataupun pandangan hanya didasarkan kepada faktor subjektifitas.
Penguasaan yang minim tentang kedudukan, hak dan kewajiban sebagai anggota DPRD, sehingga
sering implementasinya menempatkan diri sebagai penguasa bukan wakil rakyat.
Guna mendapatkan anggota DPRD yang berkualitas, maka hendaknya dalam persyaratan menjadi
anggota DPRD ditentukan dasar pendidikan minimal yang sesuai dengan tingkat rata-rata
pendidikan masyarakat.
Perlu pemahaman bagi anggota DPRD bahwa jabatan sebagai anggota DPRD bukan merupakan
pekerjaan semata tetapi adalah jabatan kehormatan yang tidak bergantung kepada besarnya
upah/gaji yang diterima.
Adanya kewajiban bagi setiap anggota DPRD untuk mendapatkan pembekalan dan pendalaman
terhadap hal-hal yang menyangkut legislasi, anggaran dan pengawasan. Pembekalan tersebut
hendaknya dilakukan oleh institusi pemerintah atau institusi yang profesional yang telah
mendapatkan akreditasi dari pemerintah.
Penetapan Belanja DPRD sebaiknya proporsional dengan pendapatan daerah serta dalam rangka
menunaikan fungsi serta tanggungjawab sebagai wakil dan penyalur aspirasi dari rakyat.
Otonomi daerah terlaksana dengan baik bukan hanya dengan tersediannya undang-undang dan
peraturan, tetapi sangat tergantung pada sumber daya manusia yang melaksanakannya berupa
pemahamannya, kemauannya dan kemampuannya.
2.2.4.2. Aparatur pemerintah daerah
Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah di miliki aparatur
pemerintah daerah tersendiri yang terpisah dengan aparatur pemerintah pusat yaang mampu
menyelemggarakan urusan-urusan rumah tangganya sendiri
Sebagai unsur pelaksana aparatur pemerintah daerah menduduki peranan yang sangat vital dalam
keseluruhan prose penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu tidak berlebihan bila di
katakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat bergantung kepada
kemampuan aparaturnya.
Dalam kenyataan tuntutan akan kualitas yang memadai belum sepenuhnya terpenuhi sehingga
akan menghambat proses penyelenggaraan otonomi daerah karena aparatur yang akan
bersentuhan langsung dengan tugas yang akan dilaksanakan,sehingga penyelenggaraan otonomi
daerah belum sesuai dengan yang di harapkan.
Masih rendahnya profesionalitas birokrasi, disebabkan antara lain pola rekruitmen yang belum
sempurna (menyangkut perencanaan kebutuhan dan seleksi).
Pola pembinaan karir yang belum mempunyai aturan yang jelas dan pasti, sehingga
mempengaruhi terhadap semangat dan budaya kerja birokrasi.
Penempatan pada suatu jabatan banyak dipengaruhi oleh pertimbangan like and dislike tidak the
right man on the right place, bahkan tidak didasarkan kepada kompetensi tetapi kepada
kedekatan dan bukan kepada pencapaian tujuan organisasi, tetapi kepentingan kekuasaan.
Masih berpengaruhnya kekuatan politik pada birokrasi daerah, sehingga loyalitas aparatur
pemerintah cenderung lebih kuat kepada kekuatan politik dari pada kepentingan masyarakat dan
menjalankan tugas pemerintahan.
Paradigma birokrasi yang masih belum banyak berubah seperti merasa sebagai penguasa tidak
sebagai pelayan, mengukur sesuatu pekerjaan hanya untuk kepentingan sesaat, ingin mencari
kelemahan aturan untuk kepentingan diri sendiri tidak berusaha menyempurnakan aturan, lebih
mau bekerja sendiri dari pada bekerja secara TIM dan tidak mengembangkan inisiatif, inovatif dan
kreasi,
Untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah maka suatu langkah sistematis
perlu di ambil. Upaya-upaya peningkatan syarat pendidikan dan pengelaman berorganisasi
ataupun peningkatan frekuensi latihan,kursus dan sebagainya yang berkaitan dengan bidang tugas
yang menjadi tanggung jawab masing-masing perlu di tingkatkan. Pola rekrutmen telah membaik
khusus perencanaan pengadaan dan seleksi. Namun masih diperlukan penyempurnaan tentang
perencanaan yang diarahkan kepada kebutuhan (jumlah dan kualitas) jangka panjang.
Diperlukan pembinaan aparatur yang profesional tidak hanya melalui pendidikan atau latihan,
tetapi memberi kesempatan utama mendapat jabatan atau pekerjaan kepada aparat yang telah
memiliki profesi dibidang tugas tertentu.
Dalam menempatkan seseorang pada jabatan harus dipertimbangkan betul tentang profesinya dan
melalui suatu seleksi (psiko, kesehatan dan kompetensi). Tes kompetensi tersebut, jika
dimungkinkan oleh lembaga yang ahli dan independen.
Harus ada ketentuan yang tegas, bahwa politik tidak mencampuri penentuan penempatan untuk
jabatan-jabatan struktural.
Pola Reward and Punishment ditegakkan secara adil dan profesional, sehingga tidak terkesan
sama rata atau diskriminatif.
Pola pembinaan karir para aparatur hendaknya ditetapkan secara jelas dengan suatu peraturan
perundangan sehingga akan menjadi pedoman dalam pembinaan aparatur di daerah.
22.4.3. Masyarakat
Masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi setiap kebijakan yang diberlakukan, karena
masyarakat sesungguhnya adalah pelaku utama, yang langsung bersentuhan atau
berkepentingan dengan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, sangat naif jika kita menghendaki
suatu kebijakan berhasil tanpa melibatkan masyarakat.
Persoalannya, hanya, sampai seberapa jauh kita dapat dan perlu menyertakan masyarakat dalam
suatu kebijakan serta bagaimana membangun partisipasi aktif dari suatu masyarakat yang sedang
dilanda krisis multi-dimensi, seperti masyarakat kita dewasa ini?
Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa peran-serta masyarakat secara nyata dalam proses
implementasi Otonomi Daerah berlum begitu menonjol. Kalau pun ada, yang terjadi bukanlah
untuk menunjang kelancaran kebijakan Otonomi Daerah. Peran-serta masyarakat malah membuat
kebijakan tersebut kerap dituding sebagai biang keladi terjadinya konflik horizontal di daerah.
Mengapa?
Ada beberapa hal yang perlu kita kemukakan di sini berkaitan dengan partisipasi masyarakat
dalam proses kebijakan publik. Pertama, apakah suatu UU yang kita terapkan menyentuh
langsung kepentingan rakyat banyak atau tidak? Dengan kata lain, apakah UU dimaksud
menguntungkan bagi rakyat atau tidak?
Banyak masyarakat yang apatis, acuh dan bahkan menentang suatu UU, seperti aksi buruh yang
menentang UU Perburuhan dan aksi penentangan terhadap UU Lalu-Lintas Jalan Raya beberapa
waktu lalu. Bila dikaji secara mendalam, semua penentangan masyarakat dimaksud dipicu oleh
ketidak-berpihakan UU tersebut kepada masyarakat dan cenderung untuk merugikan mereka.
Kedua, kemungkinan kebijakan Otonomi Daerah, UU atau aturan pelaksanaaanya belum sampai
kepada masyarakat dan kebijakan itu baru sebagian yang dipahami oleh para pejabat dan elite
politik daerah.
Karena terpenggalnya komunikasi seperti itu, maka dapat dipahami bila Otonomi Daerah dalam
praktiknya di lapangan malah menimbulkan permasalahan. Kebijakan yang dipahami secara
sepotong-sepotong itu cenderung melahirkan pengaturan yang aneh pula. Contohnya,
masyarakat dewasa ini di Indramayu, Jawa Barat, sudah mengadakan rapat-rapat persiapan
lebaran yang menurut kabarnya akan melarang setiap kendaraan yang melalui jalur alternatif di
wilayahnya.
Apakah larangan itu akan dikaitkan dengan sejumlah pungutan sebagai solusi agar kawasan
tersebut dapat dilalui bus-bus besar, sampai sejauh ini kita belum tahu persis keputusan yang
akan mereka ambil.
Jauh sebelum masyarakat Indramayu melakukan langkah itu, nelayan di Masalembo, Jawa Timur,
telah membuat aturan bahwa nelayan daerah lain tidak boleh menangkap ikan di kawasan itu.
Kapal nelayan yang membandel, secara beramai-ramai, akan disita.
Kapal tangkapan itu selanjutnya akan dibakar, atau dikembalikan kepada pemiliknya dengan uang
tebusan dengan jumlah tertentu. Selain itu, berbagai macam aturan lain juga dibuat masyarakat
lainnya, yang kerap memancing munculnya konflik.
Ketiga, belum ada kesadaran kita untuk melibatkan peran-serta aktif masyarakat secara nyata.
Yang terjadi adalah bahwa masyarakat sering kita pergunakan hanya sebagai pelengkap, kalau
tidak kita sebut sebagai pelengkap penderita.
Oleh karena itu, kita pun tidak begitu heran ketika kemudian terjadi berbagai kesenjangan di
dalam masyarakat. Akibatnya, kita pun tidak perlu heran bila kebijakan atau pandangan antara
elite politik dan pejabat daerah sering tidak nyambung dengan keinginan masyarakat.
Contohnya, meskipun daerah mengeluarkan suatu Peraturan Daerah, belum tentu peraturan itu
berjalan efektif, karena visi dan misi antara yang memerintah dan yang diperintah belum sama.
Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana mungkin masyarakat dapat berperan-serta aktif
dalam proses kebijakan Otonomi Daerah, sementara ia tidak mengerti mengenai apa yang
dikehendaki melalui pembentukan kebijakan tersebut. Dampaknya adalah, antara lain, bongkar-
pasang Peraturan Daerah sepertinya sudah menjadi hal yang biasa.
1. Belum dipahami oleh masyarakat atau pun pemuka masyarakat bahwa otonomi daerah itu adalah
juga merupakan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat.
2. Masih sedikit diberikan/diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola kebutuhannya, masih
diciptakan seolah-olah masyarakat tergantung kepada pemerintah.
3. Belum dilakukannya perkuatan terhadap lembaga-lembaga masyarakat yang berorientasi kepada
ekonomi dan kesejahteraan, yang diperkuat adalah yang berorientasi kepada politik dan
kekuasaan.
Lantas, bagaimana caranya agar masyarakat dapat berperan-serta secara aktif dalam
menyumbangkan pikiran dan tenaganya berkaitan dengan implementasi Otonomi Daerah?
1 Pemberian pemahaman yang terus menerus mengenai hakikat dan tujuan Otonomi daerah
kepada pemuka masyarakat, tidak hanya berbentuk penyuluhan yang formil tetapi juga non
formil, termasuk membuat kebijakan yang lebih memberi pemahaman implementatif tentang
otonomi daerah di tingkat masyarakat.
2 Memperbesar keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan kebijakan maupun usaha-usaha
peningkatan kesejahteraan (ekonomi dan sosial).
3 Memperkuat lembaga-lembaga masyarakat dari segi manajemen dan keuangan diikuti
dengan pembinaan serta pengawasan yang terus menerus.
4 Mempermudah dan memfasilitasi masyarakat untuk menjalankan kegiatan dan usaha-usaha
yang produktif ekonomis.
5 Menggiatkan pendidikan keterampilan dan alih teknologi untuk masyarakat.
Ada beberapa pendekatan yang dapat diketengahkan untuk membangun partisipasi aktif
masyarakat, yaitu: Pertama, aturan atau perundangan yang kita terapkan harus menyentuh dan
berpihak pada kepentingan masyarakat. Kita kita bisa berharap banyak bahwa masyarakat akan
mau berperan-serta aktif, sementara aturan yang ada justru cenderung memberatkan mereka.
Bila kebijakan Otonomi daerah yang diberlakukan dewasa ini belum mampu meningkatkan
partisipasi aktif masyarakat, misalnya, hal ini boleh-jadi karena UU tersebut belum menyentuh
kepentingan mereka.
Dengan keterlibatan secara aktif masyarakat dalam UU yang kita bentuk, tanpa kita ajak pun,
mereka secara otomatis akan berpartisipasi aktif. Hanya, sayangnya, dan itu yang sering terjadi,
UU atau aturan yang kita buat kerap bukan untuk kepentingan masyarakat.
Kedua, perlu publikasi yang luas dan mendalam atas setiap kebijakan yang diberlakukan. Yang
kita maksudkan publikasi disini adalah penjelasan atau sosialisasi kebijakan dimaksud kepada
masyarakat. Selama ini yang sering kita pantau dan tangkap, sosialisasi kebijakan hanya diberikan
kepada para elite politik atau pejabat tertentu, dalam jumlah yang terbatas pula, tanpa melibatkan
secara aktif peran-serta masyarakat. Padahal kita tahu, kebijakan itu adalah untuk masyarakat
dan aturan tersebut dikenakan kepada masyarakat. Sebab itu, sangat ironis jika mereka yang
menjadi obyek suatu kebijakan tidak mengetahui apa yang harus dilakukan.
Kita sebut publikasi yang luas dan mendalam artinya adalah memberikan penjelasan kepada
masyarakat dengan bahasa masyarakat, yang jelas dan mudah dimengerti, karena masyarakat
kita sangat majemuk, dengan tingkat pendidikan dan penalaran yang beragam pula. Sangat tidak
masuk akal bila kita menjelaskan suatu kebijakan kepada mereka dengan bahasa ilmiah, politik,
atau pun bahasa lain yang sulit dimengerti oleh rakyat banyak. Bila bahasa canggih atau yang
tidak memasyarakat seperti itu yang kita pergunakan, hampir pasti bahwa penjelasan yang
disampaikan tidak akan sampai atau menyentuh hati mereka.
Ketiga, kita juga perlu memilih dan mempergunakan media yang tepat guna. Artinya, media yang
dikenal dan sering bersentuhan dengan masyarakat serta menggunakan bahasa rakyat akan jauh
lebih efektif daripada media lainnya. Ia dapat berupa tabloid, majalah, surat kabar, televisi, dan
bahkan para ulama dan tokoh agama dalam masyarakat.
Dengan cara atau pendekatan seperti itu, kita yakin, pesan yang hendak kita sampaikan ke
tengah-tengah masyarakat akan sampai dengan lebih baik. Media yang belum begitu banyak
dilakukan dalam rangka sosialisasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dewasa ini,
misalnya, adalah dakwah, khotbah dan ruang-ruang pengajian. Padahal, media ini adalah
merupakan salah satu alternatif media masyarakat yang dapat dipergunakan untuk
memperkenalkan otonomi daerah secara lebih luas dan lebih efektif.
Lewat dakwah, pesan otonomi daerah akan lebih mengena, karena kesan yang ditangkap bukan
menggurui, tetapi lebih cenderung mengajak dan mengajak untuk berbuat secara konkrit untuk
kelancaran dan keberhasilan implementasi otonomi daerah. Melalui cara ini, umat diharapkan akan
berpartisipasi secara aktif bersama umat beragama lainnya.
Jadi, bila peran-serta aktif masyarakat dalam implementasi otonomi daerah sekarang belum
terlihat, bukan berarti bahwa mereka tidak perduli dan tidak menghendaki adanya kebijakan
tersebut. Tetapi, ada beberapa hal yang kurang kita perhatikan atau kita lupakan belakangan ini.
Harapan kita, lewat apa yang kita ketengahkan di atas sebagai urun rembug untuk pencapaian
tujuannya, di waktu mendatang, otonomi daerah akan dapat diterima oleh masyarakat secara baik
dan benar. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat untuk kelancaran dan keberhasilan
implementasi otonomi daerah itu pun tidak perlu lagi diragukan.
2.2.5 Korupsi di Daerah
Fenomena lain yang sejak lama menjadi kekhawatiran banyak kalangan berkaitan dengan
implementasi otonomi daerah adalah bergesernya praktik korupsi dari pusat ke daerah.
Sinyalemen ini menjadi semakin beralasan ketika terbukti bahwa banyak pejabat publik yang
masih mempunyai kebiasaan menghambur-hamburkan uang rakyat untuk piknik ke luar negeri
dengan alasan studi banding. Juga, mulai terdengar bagaimana anggota legislatif mulai
menggunakan kekuasaannya atas eksekutif untuk menyetujui anggaran rutin DPRD yang jauh
lebih besar dari pada sebelumnya. Belum lama diberitakan di Kompas (4/9) bagaimana legislatif
Kota Yogya membagi dana 700 juta untuk 40 anggotanya atau 17,5 juta per orang dengan alasan
menutup biaya operasional dan kegiatan kesekretariatan. Mengapa harus ada bagi-bagi sisa
anggaran? Tidakkah jelas aturannya bahwa sisa anggaran seharusnya tidak dihabiskan dengan
acara bagi-bagi, melainkan harus disetorkan kembali ke Kas Daerah? Dipandang dari kacamata
apapun perilaku pejabat publik yang cenderung menyukai menerima uang yang bukan haknya
adalah tidak etis dan tidak bermoral, terlebih jika hal itu dilakukan dengan sangat terbuka.
Sumber praktik korupsi lain yang masih berlangsung terjadi pada proses pengadaan barang-
barang dan jasa daerah (procurement). Seringkali terjadi harga sebuah item barang dianggarkan
jauh lebih besar dari harga pasar. Kolusi antara bagian pengadaan dan rekanan sudah menjadi hal
yang jamak. Pemberian fasilitas yang berlebihan kepada pejabat daerah juga merupakan bukti
ketidakarifan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Hibah dari pihak ketiga
kepada pejabat daerah sudah menjadi hal biasa yang tidak pernah diributkan dari dulu. Kalau
dicermati dan dinalar, berapa kenaikan kekayaan pejabat daerah setelah mereka menjabat posisi
tertentu? Seberapa drastis perubahan gaya hidup para pejabat publik itu?
Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah:
1. Korupsi Pengadaan Barang
Modus : a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.
1. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)
Modus : a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
1. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan
sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
1. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)
Modus : a. Pemotongan dana bantuan sosial
b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
5. Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari
pemerintah ke pihak luar.
6. Penyelewengan dana proyek
Modus : a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi.
b. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.
7. Proyek fiktif fisik
Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu
nihil.
8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.
Modus : a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan.
b. Penetapan target penerimaan
2.2.6 Adanya potensi munculnya konflik antar daerah
Ada gejala cukup kuat dalam pelaksanaan otonomi daerah,yaitu konflik horizontal yang terjadi
antara pemerintah provinsi dengan pemerntah kabupaten /kota,sebagai akibat dari penekanan
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang menekankan bahwa tidak ada hubungan hierarkhis
antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota,sehingga pemerintah kabupaten
/kota menganggap kedudukannya sama dan tidak taat kepada pemerintah provinsi.Ada arogansi
pemerintah kabupaten /kota,karena tidak ada sanksi apabila ada pelanggaran dari pemerintah
kabupaten /kota.
Dengan pelaksanaan otonomi daerah muncul gejala etno-sentrisme atau fenomena primordial
kedaerahan semakin kuat.Indikasi etno-sentrisme ini terlihat dalam beberapa kebijakan di daearah
yang menyangkut pemekaran daerah,pemilihan kepala daerah,rekruitmen birokrasi lokal dan
pembuatan kebijakan lainnya.
Selain itu, ancaman disintegrasi juga dapat memicu sebuah konflik. Paham pelimpahan wewenang
yang luas kepada daerah merupakan politik belah bambu yang telah lama dipupuk sejak zaman
penjajahan. Otonomi daerah telah mengkotak-kotakan wilayah menjadi daerah basah dan daerah
kering. Pengkavlingan ini semakin mencuatkan ketimpangan pembangunan antara daerah kaya
dan daerah miskin. Adanya potensi sumber daya alam di suatu wilayah, juga rawan menimbulkan
perebutan dalam menentukan batas wilayah masing-masing. Konflik horizontal sangat mudah
tersulut. Di era otonomi darah tuntutan pemekaran wilayah juga semakin kencang dimana-mana.
Pemekaran ini telah menjadikan NKRI terkerat-kerat menjadi wilayah yang berkeping-keping. Satu
provinsi pecah menjadi dua-tiga provinsi, satu kabupaten pecah menjadi dua-tiga kabupaten, dan
seterusnya. Semakin berkeping-keping NKRI semakin mudah separatisme dan perpecahan terjadi.
Dari sinilah bahaya disintegrasi bangsa sangat mungkin terjadi, bahkan peluangnya semakin besar
karena melalui otonomi daerah campur tangan asing semakin mudah menelusup hingga ke desa-
desa. Melalui otonomi daerah, bantuan-bantuan keuangan bisa langsung menerobos ke kampung-
kampung.
Sebenarnya pemberian otonomi dan desentralisasi politik pada daerah tidak otomatis menjadi
solusi untuk mempererat integrasi nasional. Bahkan sebaliknya memberi ruang bagi tumbuhnya
semangat kedaerahan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena pola hubungan antar etnis di
Indonesia selama ini tidak dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam dan komprehensif
mengenai pemaknaan terhadap karakteristik masingmasing etnis. Yang mengemuka justru pola-
pola stereotip yang mengarah pada prasangka satu sama lain. Tidak ada mekanisme yang dapat
mempersatukan etnis yang satu dengan etnis yang lain secara alamiah, bahkan mekanisme pasar
sekaligus didasarkan atas etnisitas. Misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, pembagian kerja
antara pedagang sayur dengan pedagang daging didasarkan atas etnisitasnya.
Di sisi lain, politik daerah yang dikembangkan pada era transisi ini belum menempatkan daerah
sebagai ruang politik tetapi sebagai ruang kultural. Akibatnya, proses politik dan relasi kekuasaan
di daerah pun didasarkan pada pola-pola hubungan primordial. Keinginan untuk dipimpin oleh
putra daerah merupakan kewajaran dalam ruang kultural, tapi tidak dalam ruang politik karena
ruang politik mensyaratkan persamaan hak-hak warga negara di mana pun ia berdomisili.
Pemaknaan otonomi secara kultural memandang politik lokal sebagai kesatuan nilai,
kultur, kustom, adat istiadat dan bukan sebagai konsep politik. Perspektif ini juga mengakui
kemajemukan masyarakat namun dalam arti sosio-kultural, di mana setiap masyarakat dan
lokalitas adalah unik sehingga setiap masyarakat dan lokalitas memiliki hak-hak sosial, ekonomi,
budaya, dan identitas diri yang berbeda dengan identitas nasional. Pemahaman inilah yang
kemudian memunculkan berbagai kebijakan daerah yang bernuansa etnisitas. Sedikit banyak
karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terfragmentasi, turut mempengaruhi
tumbuh dan berkembangnya etnonasionalisme.
Pola hubungan antar etnis dilakukan dalam proses yang linear tanpa adanya potensi bagi
terjadinya cross-cutting afiliation. Akibatnya, tidak ada ruang bagi bertemunya berbagai etnis
secara sosial. Sebagai misal, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Muslim, pasti akan
bersekolah di pesantren atau sekolah yang berlatar agama (Madrasah Tsanawiyah, Madrasah
Alliyah, dsb), kemudian menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi Islam, dan secara sosial
kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi bernuansa Islami, seperti HMI, dll. Secara
politik, berlakunya politik aliran menyebabkan sudah dapat dipastikan bahwa ia akan memilih
partai Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa pola interaksi antar etnis menjadi sulit dilakukan
karena tidak ada ruang baginya untuk mengenal etnis lain, apalagi memahami etnis lain di luar
stereotip yang selama ini mengemuka. Maka yang kemudian timbul dan menguat adalah identitas
etnisnya dan bukan identitas kebangsaan yang inheren dalam nasionalisme.
2.3 Penyelesaian permasalahan otonomi daerah di Indonesia
Pada intinya, masalah masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas
dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui
intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan
akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul dipermukaan sekarang, tidak lain karena
momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Otonomi telah menciptakan
kesempatan untuk mengeksploitasi potensi daerah dan sekaligus memberi peluang bagi para
pahlawan baru menganggap dirinya telah berjasa di era reformasi untuk bertindak semau gue.
Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintah daerah semestinya bisa menempuh jalan
alternatif, selain intensifikasi pungutan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif
bagi perekonomian daerah, yaitu (1) efisiensi anggaran, dan (2) revitalisasi perusahaan daerah.
Saya sepenuhnya yakin bahwa banyak pemerintah daerah mengetahui alternatif ini. Akan tetapi,
jika keduanya bukan menjadi prioritas pilihan kebijakan maka pemerintah pasti punya alasan lain.
Dugaan saya adalah bahwa pemerintah daerah itu malas! Pemerintah tidak mempunyai keinginan
kuat (strong will)untuk melakukan efisiensi anggaran karena upaya ini tidak gampang. Di samping
itu, ada keengganan (inertia) untuk berubah dari perilaku boros menjadi hemat.
Upaya revitalisasi perusahaan daerah pun kurang mendapatkan porsi yang memadai karena
kurangnya sifat kewirausahaan pemerintah. Sudah menjadi hakekatnya bahwa pemerintah
cenderung melakukan kegiatan atas dasar kekuatan paksa hukum, dan tidak berdasarkan prinsip-
prinsip pasar, sehingga ketika dihadapkan pada situasi yang bermuatan bisnis, pemerintah tidak
bisa menjalankannya dengan baik. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah
bisa menempuh jalan dengan menyerahkan pengelolaan perusahaan daerah kepada swasta
melalui privatisasi.
Dalam kaitannya dengan persoalan korupsi, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap
pemerintah daerah juga perlu diupayakan. Saya punya hipotesis bahwa pemerintah daerah atau
pejabat publik lainnya, termasuk legislatif, pada dasarnya kurang bisa dipercaya, lebih-lebih untuk
urusan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Tidak pernah sekalipun terdengar
ada institusi pemerintahan, termasuk di daerah yang terbebas dari penyalahgunaan uang rakyat.
Masyarakat harus turut aktif dalam menangkal perilaku korupsi di kalangan pejabat publik, yang
jumlahnya hanya segelintir dibandingkan dengan jumlah rakyat pembayar pajak yang diwakilinya.
Rakyat boleh menarik mandat jika wakil rakyat justru bertindak bertentangan dengan prinsip-
prinsip hukum dan mengkhianati nurani keadilan masyarakat. Begitu juga, akhirnya seorang
kepala daerah atau pejabat publik lain bisa diminta turun jika dalam melaksanakan tugasnya
terbukti melakukan pelanggaran serius, yaitu korupsi dan menerima suap atawa hibah dalam
kaitan jabatan yang dipangkunya.
Pemeritah juga seharusnya merevisi UU yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru di
bawah ini penulis merangkum solusi untuk keluar dari masalah Otonomi Daerah tanpa harus
mengembalikan kepada Sentralisasi. Jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mengatasi
masalah tersebut. Pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud.
1. Membuat masterplan pembangunan nasional untuk membuat sinergi Pembangunan di daerah.
Agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar
daerah.
2. Memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan
kegiatan menanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih.
3. Melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian korupsi yang dilakukan
kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi.
4. Melakukan pengawasan Perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan diatasnya
yang lebih tinggi.
5. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah
pembentukan dinasti politik.
6. Meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih mendagri yang
berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah.
7. Melaksanakan Good Governence dengan memangkas birokrasi (reformasi birokrasi), mengadakan
pelayanan satu pintu untuk masyarakat. Melakukan efisiensi anggaran.
8. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor SDA dan Pajak serta mencari dari sektor lain
seperti jasa dan pariwisata digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.
BAB III
PENUTUPAN
3.1. Kesimpulan
Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan
segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.Dimana untuk mewujudkan keadaan
tersebut,berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada
daerah untuk mengidentifikasikan,merumuskan,dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-
persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif
keutuhan negara- bangsa. Dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000 telah pula ditetapkan
Ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 tentang Kebijakan dalam Penyelenggaran Otonomi Daerah yang
antara lain merekomendasikan bahwa prinsip otonomi daerah itu harus dilaksanakan dengan
menekankan pentingnya kemandirian dan keprakarsaan dari daerah-daerah otonom untuk
menyelenggarakan otonomi daerah tanpa harus terlebih dulu menunggu petunjuk dan pengaturan
dari pemerintahan pusat. Bahkan,kebijakan nasional otonomi daerah ini telah dikukuhkan pula
dalam materi perubahan Pasal 18UUD 1945.
Adapun dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi oknum-oknum
di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran, munculnya pertentangan antara
pemerintah daerah dengan pusat, serta timbulnya kesenjangan antara daerah yang
pendapatannya tinggi dangan daerah yang masih berkembang.Bisa dilihat bahwa masih banyak
permasalahan yang mengiringi berjalannya otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-
permasalahan itu tentu harus dicari penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat
tercapai.
3.2. Saran
Dari kesimpulan yang dijabarkan diatas, maka dapat diberikan saran antara lain:
1. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan
otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintahan dan
antarpemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.
2. Konsep otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab tetap dijadikan acuan dengan meletakkan
pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat.
3. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintah daerah juga perlu diupayakan.
Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan
mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi membangun atas kebijakan
dan tindakan aparat pemerintah yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.
Karena pada dasarnya Otonomi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka
menyukseskan pelaksanaan Otonomi Daerah.
Pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebaiknya membuang jauh-
jauh egonya untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompoknya dan lebih
mengedepankan kepentingan masyarakat. Pihak-pihak tersebut seharusnya tidak bertindak egois
dan melaksanakan fungsi serta kewajibannya dengan baik.
DAFTAR PUSTAKA
Diklat Teknis Penganggaran di Era Desentralisasi, kerjasama LAN Depdagri.
Seminar Desentralisasi Pemerintahan Inventarisasi Penyerahan Urusan Pemerintahan Refleksi 10
tahun Otonomi Daerah, Ditjen Otda Depdagri.
Marzuki, M. Laica, 2007. Hakikat Desentralisasi Dalam Sistem Ketatanegaraan RI Jurnal
Konstitusi Vol. 4 Nomor 1 Maret 2007, Jakarta : Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah
Konstitusi RI.
Siregar, Faris. 2011. Hambatan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
Darihttp://catatankuliahpraja.blogspot.com/2011/09/hambatan-pelaksanaan-otonomi-
daerah.html, dikutip pada 27 Maret 2012
Arthur, Muhammad. 2012. Menggugah Peran Aktif Masyarakat dalam Otonomi Daerah.
Dari http://www.pelita.or.id/baca.php?id=4437, dikutip pada 27 Maret 2012
Lubis, Rusdi. 2011.PEMBINAAN SDM UNTUK PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH.
Dhttp://www.harianhaluan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2474:pembinaa
n-sdm-untuk-pelaksanaan-otonomi-daerah&catid=11:opini&Itemid=83, dikutip pada 27 Maret
2012
Undang-Undang No. 22/1999
Undang-Undang No. 32/2004
Undang-Undang No. 33/2004
Anda mungkin juga menyukai
- Jurnal SaniDokumen10 halamanJurnal SaniAna BfiBelum ada peringkat
- Penatausahaan Keuangan DaerahDokumen5 halamanPenatausahaan Keuangan Daerahsiti novia azzahraBelum ada peringkat
- Intervensi Pengembangan Organisasi 1pDokumen16 halamanIntervensi Pengembangan Organisasi 1pM ArifudiansyahBelum ada peringkat
- HUBUNGAN PUSAT DAERAHDokumen202 halamanHUBUNGAN PUSAT DAERAHNovrianti Palente0% (1)
- SKRIPSI] Tinjauan Hukum Kewenangan Pengawasan Internal Antara BPKP dan Inspektorat SulselDokumen229 halamanSKRIPSI] Tinjauan Hukum Kewenangan Pengawasan Internal Antara BPKP dan Inspektorat SulselImam Dwi SaputraBelum ada peringkat
- Bumn Dan Bumd AkuDokumen12 halamanBumn Dan Bumd AkufajBelum ada peringkat
- Perencanaan Tata Ruang Kota (RTRWK)Dokumen6 halamanPerencanaan Tata Ruang Kota (RTRWK)amaliapsptBelum ada peringkat
- Tugas 2 Filsafat AdministrasiDokumen7 halamanTugas 2 Filsafat AdministrasiRamaBelum ada peringkat
- Uu No 32 Tahun 2004 Pemerintah DaerahDokumen106 halamanUu No 32 Tahun 2004 Pemerintah DaerahNovendra HidayatBelum ada peringkat
- Analisis Organisasi PemdaDokumen2 halamanAnalisis Organisasi PemdacharliesallataBelum ada peringkat
- Tugas 3Dokumen17 halamanTugas 3Yupi EawBelum ada peringkat
- PELAYANAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCEDokumen8 halamanPELAYANAN PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCEFIRENDRI SEPRI REJKIBelum ada peringkat
- Pengadaan BarangDokumen4 halamanPengadaan BarangDony WibowoBelum ada peringkat
- Makalah APBD, Pelaksanaan Dan PenatausahaanDokumen15 halamanMakalah APBD, Pelaksanaan Dan PenatausahaanYohana GultomBelum ada peringkat
- TUGAS 2 Pengembangan Organisasi Citra UtDokumen9 halamanTUGAS 2 Pengembangan Organisasi Citra UtCitra DwirahayuBelum ada peringkat
- Kebijakan PublikDokumen12 halamanKebijakan PublikYoga Bisma LispadukaBelum ada peringkat
- Hubungan Pemerintah Pusat Dan DaerahDokumen14 halamanHubungan Pemerintah Pusat Dan DaerahUlla'x Phino0% (1)
- Tuton 1 - Adpu4430 - Noviana Eni Marlufi - 042070341Dokumen4 halamanTuton 1 - Adpu4430 - Noviana Eni Marlufi - 042070341Noviana Eni MarlufiBelum ada peringkat
- Kebijakan Publik Sebagai ProsesDokumen65 halamanKebijakan Publik Sebagai ProsesAhmad Indra HafiziBelum ada peringkat
- GCG IMPLEMENTASIDokumen4 halamanGCG IMPLEMENTASIAviia_Astrid_3126Belum ada peringkat
- Adpu4440 Tugas1Dokumen4 halamanAdpu4440 Tugas1Maheswari iiiBelum ada peringkat
- MAKALAH PolitikDokumen22 halamanMAKALAH PolitikInggito IdharBelum ada peringkat
- Makalah Ruang Lingkup Reformasi BirokrasiDokumen30 halamanMakalah Ruang Lingkup Reformasi BirokrasiAndreas Springfield GleasonBelum ada peringkat
- Dasar-Dasar Ilmu PemerintahanDokumen20 halamanDasar-Dasar Ilmu PemerintahanDifa Cucu SabriBelum ada peringkat
- Formulasi Kebijakan BPNTDokumen8 halamanFormulasi Kebijakan BPNTKezia perbina GintingBelum ada peringkat
- Reformasi Birokrasi Untuk MewujudkanDokumen18 halamanReformasi Birokrasi Untuk MewujudkanAndrü ChristoBelum ada peringkat
- Variasi Pelayanan Publik DaerahDokumen177 halamanVariasi Pelayanan Publik DaerahGylkeed JunichiBelum ada peringkat
- Tugas 1 Adm Pemerintah DaerahDokumen2 halamanTugas 1 Adm Pemerintah DaerahAgung permanaBelum ada peringkat
- Bab KoperasiDokumen10 halamanBab KoperasiRida AisyahBelum ada peringkat
- Otonomi Khusus PapuaDokumen29 halamanOtonomi Khusus Papuarama dhanty100% (1)
- REFORMASIDokumen44 halamanREFORMASIrues96100% (1)
- Analisis Keuangan JayapuraDokumen16 halamanAnalisis Keuangan JayapuraLa Ode Abdul Wahab100% (1)
- Dalam Sebuah Praktek Ketatanegaraan Tidak Jarang Terjadi Pemusatan Kekuasaan Pada Satu TanganDokumen8 halamanDalam Sebuah Praktek Ketatanegaraan Tidak Jarang Terjadi Pemusatan Kekuasaan Pada Satu Tangan@c3hBelum ada peringkat
- Peran Agama Dalam Memperkuat Integrasi NasionalDokumen1 halamanPeran Agama Dalam Memperkuat Integrasi NasionalViona Arella FabriantoBelum ada peringkat
- Adpu4442 Tugas2Dokumen2 halamanAdpu4442 Tugas2Maheswari iiiBelum ada peringkat
- Diskusi 2 PemdaDokumen3 halamanDiskusi 2 Pemdaanin mafiahBelum ada peringkat
- Tunjangan Kinerja Daerah TKD Dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Kasus Di Provinsi Gorontalo Dan Provinsi Dki JakartaDokumen15 halamanTunjangan Kinerja Daerah TKD Dan Upaya Peningkatan Kinerja Pegawai Kasus Di Provinsi Gorontalo Dan Provinsi Dki JakartaAnonymous bD2XD9100% (2)
- Diskusi 4 Teori OrganisasiDokumen2 halamanDiskusi 4 Teori Organisasianin mafiahBelum ada peringkat
- Pendaftaran Tanah 1Dokumen9 halamanPendaftaran Tanah 1Gerits ArdyBelum ada peringkat
- Sistem Administrasi NegaraDokumen123 halamanSistem Administrasi NegaraIrvhan MaleBelum ada peringkat
- PEMERINTAHAN DESADokumen10 halamanPEMERINTAHAN DESARachmad HadjaratiBelum ada peringkat
- Etika Administrasi PemerinahDokumen5 halamanEtika Administrasi PemerinahRifDikinBelum ada peringkat
- Adpu 4430 Administrasi KepegawaianDokumen4 halamanAdpu 4430 Administrasi KepegawaianLuky PratamaBelum ada peringkat
- PDF DocumentDokumen24 halamanPDF Documentdhea100% (1)
- Tugas 1 Hub Pusat Dan DaerahDokumen16 halamanTugas 1 Hub Pusat Dan Daerahnety netyBelum ada peringkat
- Diskusi 1 Admin Keuangan SMT 3Dokumen5 halamanDiskusi 1 Admin Keuangan SMT 3venyBelum ada peringkat
- Makalah Hubungan-Pemerintah-Pusat-Dan-DaerahDokumen11 halamanMakalah Hubungan-Pemerintah-Pusat-Dan-DaerahMeli YantiBelum ada peringkat
- Teori Ekonomi Politik (Ekolem) 1Dokumen30 halamanTeori Ekonomi Politik (Ekolem) 1Henny Purnama GultomBelum ada peringkat
- Karil. 9 Diskresi Pejabat PemerintahDokumen15 halamanKaril. 9 Diskresi Pejabat PemerintahRìo LàstChìld Pàrt ÌíBelum ada peringkat
- Diskusi 8 HANDokumen1 halamanDiskusi 8 HANfitri rahmadaniBelum ada peringkat
- RKP Desa Sukamaju 2013Dokumen22 halamanRKP Desa Sukamaju 2013Indra Kamuflase100% (5)
- Ujian Akhir SemesterDokumen8 halamanUjian Akhir SemesterJOKI TUGAS SMGBelum ada peringkat
- Sistem Pemerintahan DesaDokumen35 halamanSistem Pemerintahan DesaSiti MunawarohBelum ada peringkat
- Teori AkuntabilitasDokumen46 halamanTeori AkuntabilitasDede 'Ale' SudrajatBelum ada peringkat
- Makalah Urgensi PemekaranDokumen13 halamanMakalah Urgensi PemekaranPeter Ahab100% (2)
- OTONOMI DESADokumen27 halamanOTONOMI DESADestiaaBelum ada peringkat
- Agumg JayansyahDokumen6 halamanAgumg JayansyahAldi KikyBelum ada peringkat
- Dinamika Arus BawahDokumen55 halamanDinamika Arus BawahSyahrul Mustofa.S.H.,M.HBelum ada peringkat
- OTONOMI DAERAHDokumen9 halamanOTONOMI DAERAHKlinik PMCBelum ada peringkat
- Kuliah Ke 4 Politik Lokal Dan Pemerintahan LokalDokumen28 halamanKuliah Ke 4 Politik Lokal Dan Pemerintahan LokalAldy FirdausBelum ada peringkat
- Kak e PlanningDokumen8 halamanKak e PlanningHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Standar Pelayanan UgdDokumen15 halamanStandar Pelayanan UgdARgaHuBelum ada peringkat
- Undangan Cukuran-Anak ElekDokumen1 halamanUndangan Cukuran-Anak ElekHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Cover - Taman Parkir - Kota Jambi-2014Dokumen1 halamanCover - Taman Parkir - Kota Jambi-2014Heepy HariyadiBelum ada peringkat
- Bab3 OkDokumen8 halamanBab3 OkHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Bagian HDokumen1 halamanBagian HHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Ustek BDokumen1 halamanUstek BHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Makalah e Gov IsiDokumen24 halamanMakalah e Gov IsiHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Ucapan UltahDokumen1 halamanUcapan UltahHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Daftar Pengalaman PerusahaanDokumen1 halamanDaftar Pengalaman PerusahaanHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Data RivaDokumen1 halamanData RivaHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Bab 6 (Baru) Arahan Pengendalian Pemanfaatan RuangDokumen59 halamanBab 6 (Baru) Arahan Pengendalian Pemanfaatan RuangHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Daf-Isi-okt Sept 2011Dokumen2 halamanDaf-Isi-okt Sept 2011Heepy HariyadiBelum ada peringkat
- Kebutuhan Data RDTR Batang SangirDokumen2 halamanKebutuhan Data RDTR Batang SangirHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- SPPBJ EsdmDokumen5 halamanSPPBJ EsdmHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- SSKK - FSDokumen4 halamanSSKK - FSHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Permohonan Survey ESDMDokumen2 halamanPermohonan Survey ESDMHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Dok Pra - Theodore (Peta Potensi)Dokumen30 halamanDok Pra - Theodore (Peta Potensi)Heepy HariyadiBelum ada peringkat
- Proposal InovasiDokumen6 halamanProposal InovasiHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Lampiran 4 Fakta Analisis RDTRDokumen3 halamanLampiran 4 Fakta Analisis RDTRHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- BAB 3 RevisiDokumen2 halamanBAB 3 RevisiHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Dok Pra - Multi Struktur (Peta Potensi)Dokumen72 halamanDok Pra - Multi Struktur (Peta Potensi)Heepy HariyadiBelum ada peringkat
- Kak LP2BDokumen7 halamanKak LP2BHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Kerangka Kerja Acuan Kegiatan Versi Laporan KoreksiDokumen9 halamanKerangka Kerja Acuan Kegiatan Versi Laporan KoreksiHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Biaya Drainase S. Abang 2014Dokumen10 halamanBiaya Drainase S. Abang 2014Heepy HariyadiBelum ada peringkat
- KAK-MPIIDokumen9 halamanKAK-MPIIHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Proposal PinangDokumen5 halamanProposal PinangHeepy HariyadiBelum ada peringkat
- Dok Penawaran - Theodore (Peta Potensi)Dokumen20 halamanDok Penawaran - Theodore (Peta Potensi)Heepy HariyadiBelum ada peringkat
- Bab 5Dokumen27 halamanBab 5Heepy HariyadiBelum ada peringkat
- KMP REGIONAL 3 PALEMBANGDokumen36 halamanKMP REGIONAL 3 PALEMBANGDEDIBelum ada peringkat




![SKRIPSI] Tinjauan Hukum Kewenangan Pengawasan Internal Antara BPKP dan Inspektorat Sulsel](https://imgv2-1-f.scribdassets.com/img/document/392989176/149x198/30c875b973/1547005149?v=1)