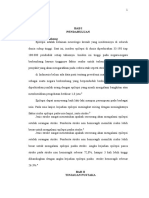Epilepsi
Epilepsi
Diunggah oleh
Starken EL HypnothiezzJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Epilepsi
Epilepsi
Diunggah oleh
Starken EL HypnothiezzHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB I
PENDAHULUAN
Epilepsi merupakan gejala dari berbagai macam penyakit yang mampu menyebabkan
sejumlah atau sekelompok sel-sel neuron otak melepaskan muatan listrik yang
berlebihan dan tidak terkontrol. Epilepsi tidak mengenal batas wilayah, ras, dan batas
sosial. Penyakit ini terjadi pada pria dan wanita serta dapat terjadi pada usia berapapun.
prevalensi epilepsi aktif kurang lebih 8,2 per 1000 penduduk..1,2,3,4
Penelitian di negara maju memperkirakan insiden penyakit epilepsi setiap tahun
kurang lebih 50 per 100.000 penduduk. Penelitian di negara berkembang menunjukkan
angka hampir dua kali lipat, yaitu 100 per 100.000 penduduk. Insiden epilepsi di negara
berkembang lebih tinggi karena risiko yang dapat menyebabkan kerusakan otak
permanen juga lebih tinggi. 5
International League Againts Epilepsy (ILAE) pada tahun 1981 menetapkan
klasifikasi epilepsi berdasarkan jenis bangkitan, Ada 2 kategori utama dalam klasifikasi
ini, yaitu Bangkitan Fokal dan Bangkitan Umum..1 Meskipun telah dilaporkan bahwa
15% kasus epilepsi didahului dengan kejang demam, kejadian kejang demam ternyata
lebih sering dibandingkan kejadian epilepsi, dan kurang dari 5% anak kejang demam
berkembang menjadi epilepsi. Seluruh jenis epilepsi, termasuk absens, tonik-klonik
umum, dan partial kompleks dapat terlihat pada pasien dengan riwayat kejang demam. 2
Faktor genetik tampaknya sangat kuat, meskipun cara diturunkannya belum jelas tetapi
autosomal dominan sederhana banyak yang disebut-sebut. Kejang demam cenderung
terjadi dalam keluarga, meskipun belum jelas diketahui cara diturunkannya.2
BAB 2
EPILEPSI
2.1.
Definisi
Kata epilepsi berasal dari kata Yunani epilambanein yang kurang lebih berarti
sesuatu yang menimpa seseorang dari luar hingga ia jatuh. Dahulu serangan epilepsi
tidak dianggap sebagai suatu penyakit, akan tetapi disebabkan oleh sesuatu diluar badan
si penderita, biasanya dianggap sebagai akibat kutukan oleh roh jahat atau setan yang
menimpa penderita. Anggapan demikian juga masih terdapat dewasa ini, terutama
dalam masyarakat yang belum terjangkau oleh ilmu kedokteran dan pelayanan
kesehatan.
Epilepsi merupakan gejala dari berbagai macam penyakit yang mampu
menyebabkan sejumlah atau sekelompok sel-sel neuron otak melepaskan muatan listrik
yang berlebihan dan tidak terkontrol. Menurut WHO, epilepsi adalah suatu keadaan
bangkitan akibat disfungsi sementara sebagian atau seluruh jaringan otak karena cetusan
listrik pada populasi neuron peka rangsangan yang berlebihan, yang dapat menimbulkan
kelainan motorik, sensorik, otonom atau psikis yang timbul secara tiba-tiba dan sesaat.
Sedangkan bangkitan epilepsi didefinisikan sebagai manifestasi klinis yang serupa dan
berulang secara paroksismal, yang disebabkan hiperaktivitas listrik sekelompok sel saraf
di otak yang spontan, dan bukan disebabkan oleh suatu penyakit otak akut
(unprovoked).
2.2. Epidemiologi
Insiden dan prevalensi epilepsi telah dilaporkan oleh beberapa peneliti dari berbagai
negara, tetapi sulit untuk dibandingkan karena definisi, cara pendekatan, klasifikasinya.
Epilepsi tidak mengenal batas wilayah, ras, dan batas sosial. Penyakit ini terjadi pada
pria dan wanita serta dapat terjadi pada usia berapapun. Diduga kebanyakan terjadi
sejak dalam kandungan, masa kanak-kanak, remaja, dan orang tua. Siapa saja dapat
terkena serangan? Kenyataannya, 5% penduduk dunia terkena serangan satu kali
seumur hidup. Sedangkan diagnosa epilepsi terbatas pada serangan yang terjadi
berulang-ulang, paling tidak dua serangan yang tiba-tiba.
Prevalensi epilepsi berbanding dengan jumlah penduduk, yang meningkat setiap
tahunnya. Beberapa penelitian di seluruh dunia memperkirakan jumlah prevalensi
epilepsi aktif kurang lebih 8,2 per 1000 penduduk. Bagimanapun, perkiraan ini mungkin
terlalu rendah untuk negara berkembang seperti Colombia, Ecuador, India, Liberia,
Nigeria, Panama, Tanzania, dan Venezuela yang prevalensinya lebih dari 10 per 1000.
Penelitian di negara maju memperkirakan insiden penyakit epilepsi setiap tahun kurang
lebih 50 per 100.000 penduduk. Penelitian di negara berkembang menunjukkan angka
hampir dua kali lipat, yaitu 100 per 100.000 penduduk. Insiden epilepsi di negara
berkembang lebih tinggi karena risiko yang dapat menyebabkan kerusakan otak
permanen juga lebih tinggi. Keadaan ini meliputi neurocysticercosis, meningitis,
malaria, komplikasi perinatal, dan malnutrisi.
ng berbeda.
Sekalipun demikian banyak peneliti menyebutkan insiden penyakit ini sekitar 20-70 per
100.000 penduduk per tahun (rata-rata 11-34/10.000 per tahun) dan prevalensinya
sekitar 4-10/1000 pada populasi umum (rata-rata sekitar 1,5-30/1000).
Di negara berkembang ditemukan angka insiden yang lebih tinggi, termasuk
Indonesia, kurang lebih sebesar 100-190 per 100.0000 penduduk. Angka ini bervariasi
menurut golongan umur dan jenis kelamin, dimana didapatkan tertinggi pada kanakkanak dan usia lanjut, menurun pada usia dewasa dan pertengahan, dan lebih banyak
pria dibandingkan dengan wanita. Dalam populasi umum , sekitar 2-5% diantaranya
beresiko mengalami kejang epilepsi. Di lain pihak, lebih dari separuh penyandang
epilepsi mengalami serangan pertamanya sebelum berusia 16 tahun.
Sekitar 77% epilepsi merupakan kasus primer idiopatik yang bisa ditemukan
pada semua golongan umur dan memuncak pada usia dewasa muda (20-30 tahun).
Sisanya terbagi menjadi simtomatik (trauma, infeksi, kelainan kongenital, lesi desak
ruang, gangguan peredaran darah otak, dll), dan kriptogenik.
Epilepsi vaskuler umumnya dijumpai pada lansia. Kasus herediter dan akibat trauma
lahir biasanya muncul pada usia muda (kurang dari 10 tahun).
2.3. Klasifikasi
Klasifikasi epilepsi dapat didasarkan pada bentuk klinis (jenis bangkitan), penyebab,
usia, gambaran EEG, dan kelainan anatomisnya. International League Againts Epilepsy
(ILAE) pada tahun 1981 menetapkan klasifikasi epilepsi berdasarkan jenis bangkitan,
Ada 2 kategori utama dalam klasifikasi ini, yaitu Bangkitan Fokal dan Bangkitan
Umum. Dimana bangkitan fokal meupakan cetusan epelepsi yang dimulai dari fokus
terlokalisir di otak, sedangkan bangkitan umum adalah cetusan umum terjadi pada
daerah yang lebih luas pada kedua belahan otak.
2.3.1 Klasifikasi Bangkitan Epilepsi menurut ILAE (1989)
I. Epilepsi berelasi dengan lokasi / fokal atau parsial
A. Idiopatik
B. Simtomatik
C. Kriptogenik
II. Epilepsi generalisata
A. Idiopatik
B. Simtomatik
C. Kriptogenik
III. Tidak terdeterminasi
IV. Situasi Khusus
2.3.2. Klasifikasi Bangkitan Epilepsi menurut ILAE (1981)
I. Bangkitan parsial
A. Bangkitan parsial sederhana
A.1. Dengan manifestasi motorik
A.2. Dengan manifestasi sensorik
A.3. Dengan manifestasi autonomik
A.4. Dengan manifestasi psikik
B. Bangkitan parsial kompleks
B.1. Dengan gambaran parsial sederhana pada awalnya diikuti dengan bangkitan
lena
B.2. Dengan bangkitan lena pada awalnya
C. Bangkitan umum sekunder
II. Bangkitan umum
A. Bangkitan Lena / absence seizures
Dbvc xvv B. Bangkitan mioklonik
C. Bangkitan klonik
D. Bangkitan tonik
E. Bangkitan atonik / astatik
F. Bangkitan tonik-klonik
III. Bangkitan epilepsi yang tidak terklasifikasi
Gambar 2. Gambaran serangan Epilepsi
2.4.
Faktor Resiko
Faktor resiko epilepsi adalah faktor-faktor yang tidak kelihatan sebagai
penyebab epilepsi secara langsung, tetapi memiliki hubungan melalui beberapa cara.
Memiliki faktor resiko epilepsi membuat seseorang memiliki resiko yang lebih besar
untuk terkena epilepsi tetapi tidak selalu harus terkena epilepsi. Dan sebaliknya
seseorang yang tidak memiliki faktor resiko belum tentu tidak terkena epilepsi.
Faktor resiko epilepsi antara lain :
Bayi dengan berat badan lahir rendah
Bayi yang pernah mengalami kejang pada usia kurang dari 1 bulan
Bayi yang lahir dengan kelainan struktur otak
Perdarahan otak
Pembuluh darah otak abnormal dalam otak
Trauma otak berat atau hipoksia otak
Tumor otak
Infeksi otak misalnya : abses, meningitis
Stroke akibat oklusi arteri
Cerebral palsy
Cacat mental
Kejang yang terjadi beberapa hari setelah trauma kepala
Riwayat keluarga dengan epilepsi
Alzheimers disease
Kejang demam
Penggunaan kokain yang ilegal
Meskipun telah dilaporkan bahwa 15% kasus epilepsi didahului dengan kejang
demam, kejadian kejang demam ternyata lebih sering dibandingkan kejadian epilepsi,
dan kurang dari 5% anak kejang demam berkembang menjadi epilepsi.
Seluruh jenis epilepsi, termasuk absens, tonik-klonik umum, dan partial
kompleks dapat terlihat pada pasien dengan riwayat kejang demam. National Institute
of Neurologic Disorder and Stroke (NINDS) Perinatal Collaborative Project (NCPP)
melaporkan tingginya risiko epilepsi diantara anak-anak dengan perkembangan
abnormal sebelum kejang demam pertama, adanya riwayat orang tua atau saudara
kandung dengan epilepsi, dan anak dengan kejang demam kompleks. Pada 60% anak
dengan kejang demam tanpa satupun faktor risiko diatas, 2% akan berkembang epilepsi
sebelum usia 7 tahun. 34% anak dengan satu faktor risiko, 3% akan menjadi epilepsi,
dan jika mempunyai 2 atau 3 faktor risiko, maka kejadian epilepsi menjadi 13 %. 5,9
Tabel. 2.1. Faktor risiko untuk mendapatkan epilepsi dari kejang demam
1. Perkembangan abnormal sebelum kejang demam pertama
2. Riwayat keluarga dengan epilepsi
3. Kejang demam kompleks
Faktor Genetik. Faktor genetik tampaknya sangat kuat, meskipun cara diturunkannya
belum jelas tetapi autosomal dominan sederhana banyak yang disebut-sebut.
Kejang
demam cenderung terjadi dalam keluarga, meskipun belum jelas diketahui cara
diturunkannya. Anak dengan kejang demam sering dijumpai keluarganya mempunyai
riwayat kejang demam. Tingginya kejadian epilepsi dalam keluarga yang mempunyai
anak dengan kejang demam tidak sepenuhnya terbukti. Risiko epilepsi juga tinggi pada
saudara kandung yang mempunyai kejang demam, tetapi tidak untuk saudara yang lain.
2.5.
Patofisiologi
Secara umum sifat epileptogenik jaringan saraf ditentukan oleh 2 faktor, yaitu
eksitabilitas dan sinkronisasi. Pada saat mendapatkan serangan epileptik yang
memegang peranan adalah adanya eksitabilitas pada sejumlah neuron atau sekelompok
neuron, yang kemudian terjadi lepas muatan listrik secara serentak pada sejumlah
neuron atau sekelompok neuron dalam waktu bersamaan, yang disebut sinkronisasi.
Terjadinya lepas muatan listrik pada sejumlah neuron secara sendiri-sendiri tidak akan
menghasilkan suatu respon fungsional, oleh karena itu harus terorganisir dengan baik
dalam sekelompok neuron serta memerlukan sinkronisasi. Adanya serangan epileptik
ditentukan oleh mekanisme yang mengganggu eksitabilitas dan sinkronisasi neuronal
tersebut.
Munculnya bangkitan epileptik yang disebabkan karena adanya gangguan
eksitabilitas dan sinkronisasi neuronal belum banyak diketahui. Hipotesis terakhir
disebutkan karena adanya (a) kelainan membran neuronal, (b) kelainan mekanisme
inhibisi, (c) kelainan mekanisme eksitasi, atau (d) kegagalan sistem pengaturan fungsi
eksitasi dan inhibisi.
Membran Neuron
Secara fisiologis, peranan membran neuron adalah untuk mempertahankan perbedaan
potensial antara ruang intraseluler dan ruang ekstraseluler. Dalam keadaan istirahat
ruang intraseluler bermuatan negatif dan ruang ekstraseluler bermuatan positif.
Potensial membran istirahat ini dipertahankan melalui proses pengeluaran ion Na dari
dalam sel dan diikuti pemasukan ion K ke dalam sel, sehingga di dalam sel kekurangan
ion Na, Cl, Ca dan kelebihan ion K. Aktivitas ini memerlukan energi yang diambil
melalui pemecahan ATP oleh enzim NA-K ATP ase.
Kelainan membran neuron pada bangkitan epilepsi dimulai dari suatu neuron
epileptik yang berperan memicu terjadinya aksi potensial. Depolarisasi yang terjadi
pada neuron epileptik tersebut bersifat paroksismal, yang disebut paroxysmal
depolarization shifts (PDSs), yaitu mempunyai amplitudo lebih tinggi, durasi lebih
lama dan diikuti oleh after depolarization yang diperpanjang. Teejadinya PDSs tersebut
tergantung masuknya ion Ca ke dalam neuron, yang disebabkan adanya kelainan
membran itu sendiri.
Mekanisme eksitasi dan inhibisi
Excitatory Postsynaptic Potentials (EPSPs) dihasilkan oleh ikatan molekul-molekul
transmitter pada reseptor-reseptor yang menyebabkan terbukanya saluran ion Na atau
ion Ca dan tertutupnya saluran ion K yang mengakibatkan terjadinya depolarisasi.
Berlawanan dengan Inhibitory Postsynaptic Potentials (IPSs) disebabkan karena
meningkatnya permeabilitas membran terhadap Cl atau K dan menyebabkan
hiperpolarisasi membran, dan biasanya terjadi pada sinaptik aksosomatik yang disebut
postsynaptic inhibitory transmission
Pada kasus epilepsi terjadi kelainan mekanisme eksitasi dan inhibisi tersebut,
sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara sisitem eksitasi dan inhibisi yang
menjadi dasar patofisiologi epilepsi
Neurotransmitter GABA
Gamma Amino Butiric Acid (GABA) adalah suatu inhibitor utama neurotransmiter pada
susunan saraf pusat. Semua struktur otak depan menggunakan aksi inhibitor dan
memegang peranan fisiopatogenesis pada kondisi neurologis tertentu, termasuk epilepsi,
kegagalan fungsi GABA dapat menghasilkan serangan (seizure)
Secara tradisional yang berperan pada inhibisi oleh GABA adalah resaptor
GABAA dalam bentuk inhibisi potensi postsinaptik (ISPSs= inhibitory post synaptic
potentials). Terikatnya GABA pada reseptor mengakibatkan saluran klorida terbuka
sehingga untuk sesaat potensial membran sel ditentukan oleh potensial keseimbanfan
klorida. Reversal potensial dari IPSP umumnya adalahsekitar -70 mV. Perubahan
voltase yang ditimbulkan GABAA tergantung pada resting potential dari sel tersebut
dan pada gradien klorida antara kompartment intra dan ekstrasel. Gradien ini tentunya
terpengaruh oleh mekanisme lalu lintas klorida. Interfensi pada proses ini akan
mendorong akumulasi klorida intrasel. Pada saat saluran GABAA terbuka sel akan
mengalami depolarisasi dan ion klorida keluar.
Perubahan induksi yang menyertai pembukaan saluran klorida menyebabkan
shunting aliran dari sel yang memulai bangkitan dan blocking ini merupakan
10
penghambat yang lebih kuat daripada yang ditimbulkan oleh mekanisme GABAA
sendiri.
Pada susunan saraf pusat juga terdapat reseptor GABAB yang terkait dengan
saluran kalium oleh suatu protein penghubung yaitu guanosine triphosphate binding
protein (G-protein) yang merupakan sistem-perantara-intrasel. Hiperpolarisasi yang
ditimbulkan oleh GABAB ini merupakan komponen inhibitorik (IPSP) yang tahan lama.
Efeknya tergantung pada konsentrasi kalium ekstrasel. Bila kalium naik efek
hiperpolarisasinya akan berkurang. Hiperpolarisasi yang ditimbulkan oleh GABAB
terutama peting dalan mengendalikan bangkitan yang berlangsung lama. Mekanisme
GABAB baru nampak bilamana pengaruh GABAB kurang menonjol. Kemampuan
memodulasi eksitabilitas oleh GABAB terkait dengan interneuron GABA-ergic.
Neuron GABA-ergic
Banyak dari neuron yang melepaskan GABA di korteks adalah interneuron
GABAergic. Sel jenis ini merupakan circuit cells beda dengan tipe sel primer (sel
piramidal dan sel projection cell). Sel yang sejenis ini juga ditemukan di neocortex dan
di hipokampus. Kelompok sel ini mempunyai kemampuan fast-spiking dan secara terus
menerus mengeluarkan inhibisi tonik terhadap sel piramidal. Praktis semua interneuron
menerima impuls dari sumber yang sama dan berfungsi inhibitorik.
Semua interneuron di hipokampus menggunakan GABA sebagai transmiternya.
Blocking terhadap pengaruh inhibisi GABAA akan menimbulkan aktivitas epileptik.
11
EPILEPSY- A CRITICAL BALANCE
EXCITATION INCREASE
INHIBITION DECREASE
SEIZURE
SEIZURE
Na+ channel antagonists
Ca2+ channel antagonists
Glutamate receptor antagonists
GABAA agonists
Enhanced GABA levels
K+ channels modulators
Gambar 2. Animasi patofisiologi epilepsi dari ketidak seimbangan eksitasi dan
inhibisi.
2.6. Diagnosis
Hal ini meliputi pemeriksaan klinis (anamnesis dari faktor risiko, pemeriksaan fisik),
dan imaging (pencitraan).
2.6.1. Pemeriksaan klinis
1. Anamnesis
Melalui anamnesis yang baik dan teratrah diperoleh informasi mengenai keluhan
dan riwayat penyakitnya, hal ini sangat penting untuk mendiagnosa epilepsi,
meliputi :
Bentuk bangkitan
Gejala sebelum, sewaktu, dan setelah bangkitan
Durasi bangkitan
Bentuk dari setiap kejadian bangkitan
Faktor pencetus bangkitan
Usia pertama kali mengalami bangkitan
12
Riwayat perinatal dan perkembangan
Riwayat penyakit yang mungkin menjadi penyebab
Riwayat pengobatan
Riwayat keluarga
2. Pemeriksaan fisik
Pada pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan fisik umum dan neurologik,
yang bertujuan mencari :
Gejala penyakit yang sering disertai bangkitan epilepsi.
Defisit neurologis yang mungkin menerangkan suatu cacat otak yang
epileptogen
Adanya cedera yang mungkin disebabkan kehilangan kesadaran saat
bangkitan epilepsi.
Tabel 2.2. Pemeriksaan Fisik
Pemeriksaan Umum
Pemeriksaan Neurologis
Tanda vital
Kepala
BB, TB, Lingkar kepala
N. Kraniales termasuk fundus okuli
Kulit
Penglihatan
Organomegali
Fungsi motorik, reflek tendon
Perkembangan
Fungsi luhur
Sensorik
2.6.2. Pemeriksaan Elektroensefalografi (EEG)
Indikasi EEG pada penderita epilepsi antara lain: (1) membantu
menegakkan
diagnosa
epilepsi;
(2)
menentukan
hubungan
antara
abnormalitas kejang dan frekwensi kejang; (3) memonitor keefektifan
obat antikonvulsan; (4) aspek psikiatrik; (5) aspek medikolegal, misalnya
kemungkinan timbulnya epilepsi pasca trauma, penentuan hukuman pada
penderita, konsultasi perkawinan, SIM dan sebagainya.
13
Gambar 3. Hasil EEG penderita epilepsi
2.6.3.
Pemeriksaan radiodiagnostik / imaging
Pemeriksaan Imaging yang dilaksanakan antara lain : Pemeriksaan CT
scan, dan MRI dilakukan atas indikasi :
2.6.4.
Semua kasus bangkitan pertama yang diduga ada kelainan struktural
Perubahan bentuk bangkitan
Terdapat defisit neurologik fokal
Bangkitan pertama kali terjadi di atas usia 25 tahun.
Pemeriksaan laboratorium
Pemeriksaan laboratorium darah rutin, elektrolit, gula darah, fungsi hati,
kadar obat dalam plasma dan lain-lain sesuai indikasi.
2.7. Prognosis
2.7.1. Prognosis Medik
Prevalensi epilepsi kronik sekitar 1 dalam 200 orang, yang berarti bahwa mayoritas
epilepsi tidak menjadi kronik. Sekali remisi lama (lebih dari 24 bulan) tercapai, resiko
untuk mengalami serangan berikutnya akan berkurang. Serangan yang sejak dini
terkendali oleh obat memiliki prognosis yang lebih baik.
2.7.2. Prognosis Psikososial
Sebagian besar penderita epilepsi dapat hidup normal. Komunikasi antara dokter, orang
tua anak penyandang epilepsi, dan lingkungan penderita epilepsi sangat penting dalam
mempengaruhi perkembangan mental dan kognitif penderita.
14
2.8. Penatalaksanaan
2.8.1 Pengobatan epilepsi
Pada anak yang sedang mengalami kejang, dilakukan perawatan yang adekuat.
Penderita dimiringkan agar jangan terjadi aspirasi ludah atau lendir dari mulut.
Jalan
nafas dijaga agar tetap terbuka, agar suplai oksigen tetap terjamin. Bila perlu diberikan
oksigen. Fungsi vital, keadaan jantung, tekanan darah, kesadaran perlu diikuti dengan
seksama. Suhu yang tinggi harus segera diturunkan dengan kompres dan pemberian
antipiretika.
Kejang harus segera dihentikan, ini adalah untuk mencegah agar tidak terjadi
kerusakan pada otak atau meninggalkan gejala sisa atau bahkan kematian. Obat yang
paling cepat untuk menghentikan kejang adalah diazepam yang diberikan secara
intravena atau intrarektal. Dosis intravena 0,30,5 mg/kg diberikan perlahan-lahan
dengan kecepatan 12 mg/menit dengan dosis maksimal 20 mg. Apabila sukar mencari
vena dapat diberikan diazepam rektal dengan dosis 0,5/kg atau 5 mg untuk berat badan
kurang dari 10 kg dan 10 mg bila berat badan lebih dari 10 kg.
Apabila kejang belum berhenti, 5-10 menit kemudian dapat diulangi lagi
pemberian diazepam dengan dosis dan cara yang sama. Bila kejang tidak berhenti,
diberikan fenitoin dengan dosis awal 10-20 mg/kg/per drip selama 20-30 menit setelah
dilarutkan dalam cairan NaCl fisiologis. Dosis selanjutnya diberikan 4-8 mg/kg/hari, 1224 jam setelah dosis awal.
Setelah kejang berhenti harus ditentukan apakan perlu pengobatan profilaksis
atau tidak, tergantung jenis kejang demam dan faktor risiko yang ada pada anak
tersebut.
Untuk mengurangi resiko terjadinya gangguan fungsi kognitif maka dalam
pengobatan epilepsi perlu diperhatikan beberapa prinsip pengobatan
Pengobatan dilakukan bila terdapat minimun 2 kali bangkitan dalam setahun
Pengobatan mulai diberikan bila diagnosis tellah ditegakkan dan setelah
penderita
dan
keluarga
menerima
penjelasan
kemungkinan efek samping
Pemilihan jenis obat sesuai jenis bangkitan
tujuan
pengobatan
dan
15
Sebaiknya pengobatan dengan monoterapi
Pemberian obat dimulai dari dosis rendah dan dinaikkan bertahapnsamapi dosis
efektif tercapai.
Pada prinsipnya pengobatan dimulai dengan obat antiepilepsi lini pertama. Bila
diperlukan penggantian obat, obat pertama diturunkan bertahap dan obat kedua
dinaikkan secara bertahap.
Bila didapat kegagalan monoterapi maka dapat diprtimbangkan kombinasi OAE
Bila memungkinkan dilakukan pemantauan kadar obat sesuai indikasi
Tabel 1. Pemilihan Obat Antiepilepsi Atas dasar Jenis Bangkitan Epilepsi
Type of seizures and
First-line drug
Second-line drug
epileptic syndrome
Simple and complex partial
Carbamazepine,
Acetazolamide, clobazam,
seizures, primary and
valproate, and
clonazepam, ethosuximide,
secondarily generalized
phenytoin
felbamate, gabapentin,
tonic-clonic seizures
lamotrigine, levetiracetam,
oxcarbazepine, Phenobarbital
Acetazolamide, clobazam,
Generalized absence
Valproate,
clonazepam, lamotrigine,
seizures
ethosuximide
Phenobarbital, primidone
Acetazolamide,
Atypical absence, tonic, and
Valproate
clonic seizures
carbamazepine, clobazam,
clonazepam, lamotrigine,
oxcarbazepine,
phenobarbital, phenytoin,
Primidone, topiramate
Clobazam, clonazepam,
Myoclonic seizures
Valproate
ethosuximide, lamotrigine,
Phenobarbital, piracetam,
primidone
16
DAFTAR PUSTAKA
1. Agoes, A. 2004, Pelatihan Epilepsi Mudah, Aman, dan Sederhana, Malang, pp. 124.
2. Aninimous.2005, Epileptic seizures and their classification, in : Panayiotopoulos,
CP. (ed) The Epilepsies, 1st ed, Bladon Medical Publishing, UK, pp.8-23
3. Budiarto, G. 1998, Patofisiologi Epilepsi, in : anonim (ed) PKB Neurologi,
Surabaya, pp. 1-20.
4. Hartono, B. 2004, The Cognitive Problems and Learning Disabilities in Epilepsy,
in : anonim (ed) Pertemuan Nasional 1 Epilepsi PERDOSSI, Semarang, pp. 194200.
5. Merrick dan Bernstam, F., Pollock, R.E. 2005, Neurology, in : Brunicardi, F Charles
et al. (eds) Schwartzs Principles of Surgery, 8th ed, McGraw Hill, New York,
pp.249-294.
6. Holmes GL.Epilepsi and other seizure disorders. Dalam: Bruce O.Berg, Ed.
Principles of child neurology; edisi ke-1. New York: McGraw-Hill, 1996; 221-33.
7. Duchowny M. Febrile seizures in childhood. Dalam: Elaine W, Ed. The treatment of
epilepsy : principle & Practice; edisi ke-2. Baltimore: William & Wilkins, 1996;
622-8.
8. Nelson K, Ellenberg JH. Predictors of epilepsy in children who have experience
febrile seizure. N Eng J Med 1976; 259:1029-33.
9. Pui C H, Crist W M. Epilepsy. In: Rudolf A M. Rudolfs Pediatrics. 19 th ed.
International edition: Appleton Lange, 1991
10. Kliegman R.M. Nelson Essentials of Pediatrics. 5th ed. China: Elsevier Saunders,
2005. p 737-40
11. Suraatmaja S., Soetjiningsih. Pedoman Diagnosis dan Terapi Ilmu Kesehatan Anak
RSUP Sanglah. Denpasar: Lab/SMF Ilmu Kesehatan Anak FK Unud/ RSUP
Sanglah, 2000.
Anda mungkin juga menyukai
- Epilepsi Perdossi-2019Dokumen15 halamanEpilepsi Perdossi-2019Akun Ke60Belum ada peringkat
- EPILEPSIDokumen39 halamanEPILEPSIDedek HandriadiBelum ada peringkat
- Referat EpilepsiDokumen26 halamanReferat EpilepsiTito WigaBelum ada peringkat
- Lennox Gastaut SyndromeDokumen14 halamanLennox Gastaut SyndromeFrans JobethBelum ada peringkat
- Makalah Kel1 EpilepsiDokumen19 halamanMakalah Kel1 EpilepsiAkbar ReformasiBelum ada peringkat
- EpilepsiDokumen16 halamanEpilepsiPasrahni DaeliBelum ada peringkat
- LP Epilepsi PD AnakDokumen28 halamanLP Epilepsi PD Anaksudiada100% (1)
- EPILEPSIDokumen55 halamanEPILEPSICut FannyBelum ada peringkat
- PDF LP Epilepsi PD Anak CompressDokumen28 halamanPDF LP Epilepsi PD Anak Compressrahmat shinobiBelum ada peringkat
- Tinjauan Pustaka EpilepsiDokumen32 halamanTinjauan Pustaka EpilepsizakyBelum ada peringkat
- Epilepsi Pada AnakDokumen39 halamanEpilepsi Pada AnakMartga Bella Rahimi100% (4)
- Rangkuman Modul 2 Blok 15Dokumen64 halamanRangkuman Modul 2 Blok 15Rizkia MulyasariBelum ada peringkat
- Lapkas EpilepsiDokumen29 halamanLapkas EpilepsiDjustiela KarrangBelum ada peringkat
- Makalah EpilepsiDokumen8 halamanMakalah EpilepsiLina Permata SariBelum ada peringkat
- EpilepsiDokumen24 halamanEpilepsialdi putra pratamaBelum ada peringkat
- Epi LepsiDokumen18 halamanEpi LepsiDanniel KamarudinBelum ada peringkat
- Epi LepsiDokumen30 halamanEpi LepsiSyahidahARBelum ada peringkat
- Rangkuman Epilepsi.Dokumen7 halamanRangkuman Epilepsi.Muhammad ZaibBelum ada peringkat
- Epilepsi AnakDokumen6 halamanEpilepsi AnakSyela IndahBelum ada peringkat
- Referat EpilepsiDokumen25 halamanReferat EpilepsinnurulhudaaBelum ada peringkat
- Case Report Session Epilepsi (Dini Fajri Omari, Muhammad Tsani)Dokumen32 halamanCase Report Session Epilepsi (Dini Fajri Omari, Muhammad Tsani)Sani muzakirBelum ada peringkat
- Anwari Delmi Dan Nurul Ainun AziziDokumen47 halamanAnwari Delmi Dan Nurul Ainun AziziNurul Ainun AziziBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan Epilepsi-1Dokumen48 halamanAsuhan Keperawatan Epilepsi-1Gitaq Tri YatmaBelum ada peringkat
- EpilepsiDokumen23 halamanEpilepsiAnonymous tnvM0c3ZBelum ada peringkat
- Refrat Secondary Generalized EpilepsyDokumen17 halamanRefrat Secondary Generalized EpilepsyPutri IsmayandaBelum ada peringkat
- Makalah EpilepsiDokumen15 halamanMakalah Epilepsidevildante2Belum ada peringkat
- 453 1111 2 PB PDFDokumen10 halaman453 1111 2 PB PDFWiwi 1998Belum ada peringkat
- Referat EpilepsiDokumen14 halamanReferat EpilepsiAnindya FirdausBelum ada peringkat
- Referat Epilepsi Najib FixDokumen26 halamanReferat Epilepsi Najib FixafridaaynBelum ada peringkat
- Epilepsi Grand MalDokumen33 halamanEpilepsi Grand Malmalini hemaBelum ada peringkat
- Vera PamungkasandaDokumen25 halamanVera PamungkasandaVera PamugkasandaBelum ada peringkat
- Tugas Proposal TripanjikDokumen23 halamanTugas Proposal TripanjikTri Panji KusumaBelum ada peringkat
- EPILEPSIDokumen5 halamanEPILEPSIMariaaaBelum ada peringkat
- LAPKAS EPILEPSI Dr. ShellaDokumen41 halamanLAPKAS EPILEPSI Dr. Shellashella depariBelum ada peringkat
- Anti Epilepsi - Kelompok 2Dokumen22 halamanAnti Epilepsi - Kelompok 2Gustia IndahBelum ada peringkat
- Lapsus Epilepsi AnakDokumen26 halamanLapsus Epilepsi AnakNoni R. Lubis100% (1)
- Epilepsi Dipiro 10Dokumen29 halamanEpilepsi Dipiro 10S2 Farmasi SainsBelum ada peringkat
- Referat EpilepsiDokumen45 halamanReferat Epilepsiannisa rizkaBelum ada peringkat
- Referat EpilepsiDokumen45 halamanReferat EpilepsiNugraha AlthalarikBelum ada peringkat
- Referat Neurobehavior Pada EpilepsiDokumen15 halamanReferat Neurobehavior Pada EpilepsiIndra SilaenBelum ada peringkat
- Makalah EpilepsiDokumen7 halamanMakalah EpilepsiAjier CanggihBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan EpilepsiDokumen19 halamanAsuhan Keperawatan EpilepsiladygresiaBelum ada peringkat
- CRS - Epilepsi Grandmal - Azhiimil Akbar - Periode Kepaniteraan 3 Januaru - 3 Februari 191yDokumen20 halamanCRS - Epilepsi Grandmal - Azhiimil Akbar - Periode Kepaniteraan 3 Januaru - 3 Februari 191yyoga setiaBelum ada peringkat
- Kelompok 1Dokumen63 halamanKelompok 1Rizkia MulyasariBelum ada peringkat
- KASUS TP EpilepsiDokumen48 halamanKASUS TP EpilepsiSarah RamirezBelum ada peringkat
- EPILEPSIDokumen23 halamanEPILEPSIKiki Rizkia100% (2)
- Epilepsi PsikogenikDokumen40 halamanEpilepsi PsikogenikPuteri Effendi Radith100% (1)
- Epilepsi 1Dokumen26 halamanEpilepsi 1Denia Haritsa AprilianiBelum ada peringkat
- Referat Epilepsi Pasca StrokeDokumen16 halamanReferat Epilepsi Pasca StrokeGhifar Ramadhan AlfauzanBelum ada peringkat
- Epilepsi-Kelompok 2Dokumen29 halamanEpilepsi-Kelompok 2kadekryanBelum ada peringkat
- Etiologi Dan EpidemiologiDokumen5 halamanEtiologi Dan EpidemiologiAnggit PramitaBelum ada peringkat
- Epilepsi ReferatDokumen26 halamanEpilepsi ReferatLaura Estelia100% (2)
- Adrian Setiaji 22010110130154 Bab2ktiDokumen30 halamanAdrian Setiaji 22010110130154 Bab2ktiDinar Yudit PermadiBelum ada peringkat
- Makalah EpilepsiDokumen28 halamanMakalah EpilepsiNurul WahyuniBelum ada peringkat
- PSIKOLOGI KECEMASAN Mengetahui untuk memahami mekanisme fungsinyaDari EverandPSIKOLOGI KECEMASAN Mengetahui untuk memahami mekanisme fungsinyaPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (8)
- Coronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Dari EverandCoronavirus Covid-19. Membela diri. Cara menghindari penularan. Bagaimana melindungi keluarga dan pekerjaan Anda. Diperbarui edisi keempat.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (2)