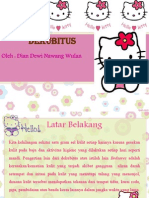Ulkus Dekubitus
Ulkus Dekubitus
Diunggah oleh
Ilmiah BagusHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Ulkus Dekubitus
Ulkus Dekubitus
Diunggah oleh
Ilmiah BagusHak Cipta:
Format Tersedia
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
DEKUBITUS
I.
PENDAHULUAN
Dekubitus dapat terjadi pada setiap usia, tetapi hal ini merupakan masalah
yang khusus dan banyak terjadi pada orang lanjut usia. Insiden kejadiannya
berkaitan erat dengan imobilitas. Istilah dekubitus diambil dari bahasa latin
decumbere yang artinya berbaring.
Dekubitus juga disebut pressure sores atau bed sores, adalah
kerusakan/kematian kulit sampai jaringan di bawah kulit, bahkan menembus otot
sampai mengenai tulang akibat adanya penekanan pada satu area yang
berlangsung terus menerus atau berulang-ulang sehingga mengakibatkan
peredaran darah setempat terhenti sehingga terjadi nekrosis. Keparahan suatu
dekubitus didasarkan pada kedalaman ulkus. Walaupun semua bagian tubuh dapat
mengalami dekubitus, bagian bawah dari tubuh beresiko tinggi dan membutuhkan
perhatian khusus. Bagian tubuh yang sering mengalami dekubitus adalah tempat
di mana terdapat penonjolan misalnya daerah sacrum, trokhanter mayor, spina
ischiadica anterior superior, tumit, siku dan kepala bagian belakang.
Imobilitas yang berlangsung lama dapat menyebabkan dekubitus.
Terjadinya dekubitus disebabkan oleh gangguan aliran darah setempat, dan
keadaan umum dari penderita.
Dekubitus merupakan suatu hal yang serius dengan angka morbiditas dan
mortalitas yang tinggi pada penderita lanjut usia. Di negara-negara maju
presentase terjadinya dekubitus mencapai 11% dan terjadi dalam 2 minggu
perawatan.
Dekubitus sangat penting dan merupakan masalah yang serius. Namun
dengan perawatan yang tepat, hampir sebagian besar dekubitus dapat
disembuhkan.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
II.
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
ETIOLOGI DAN PATOFISIOLOGI
Ada 4 faktor yang telah diterapkan dalam patogenesis dekubitus, yaitu:
1. Tekanan
2. Peregangan dan lipatan kulit
3. Gesekan kulit
4. Beberapa faktor predisposisi.
Faktor-faktor ini mengakibatkan terhambatnya aliran darah ke kulit. Selain
itu, gesekan pada kulit menghilangkan stratum korneum epidermis yang berfungsi
sebagai pelindung kulit.
1. Tekanan
Tekanan darah kapiler berkisar antara 16 mmHg - 33 mmHg. Kulit akan
tetap utuh karena sirkulasi darah terjaga bila tekanannya masih berkisar
pada batas-batas tersebut. Tetapi, sebagai contoh, bila seseorang
menderita imobil / terpancang pada tempat tidurnya secara pasif dan
berbaring diatas kasur busa biasa maka tekanan daerah sakrum akan
mencapai 60-70 mmHg, dan daerah tumit mencapai 30 - 45 mmHg.
Tekanan ini akan menimbulkan daerah iskemik dan bila berlanjut akan
terjadi nekrosis jaringan kulit.
2. Peregangan dan lipatan kulit
Bila penderita imobil, tidak dibaringkan terlentang mendatar, tetapi pada
posisi setengah duduk, akan terjadi peregangan dan lipatan kulit. Ada
kecenderungan
tubuh akan
meluncur ke bawah, apalagi bila
keadaannya basah. Seringkali hal ini dicegah dengan memberikan
penghalang, misalnya bantal-bantal kecil atau balok kayu pada kedua
telapak kaki. Upaya ini hanya mencegah pergerakkan kulit, yang
sekarang terfiksasi pada alas, tetapi rangka tulang tetap cenderung maju
ke depan. Akibatnya terjadi garis-garis penekanan atau peregangan pada
jaringan subkutan yang seakan-akan tergunting pada tempat-tempat
tertentu, dan terjadi penutupan arteriole dan arteri-arteri kecil akibat
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
terlalu teregang bahkan sampai robek. Tenaga menggunting ini disebut
Shearing forces. Akibat tambahan dari shearing forces ini, pergerakkan
tubuh diatas alas tempat berbaring, dengan fiksasi kulit pada permukaan
alas akan menyebabkan terjadinya lipatan-lipatan kulit (skin folding).
Terutama terjadi pada penderita yang kurus dengan kulit yang kendur.
Lipatan-lipatan kulit yang terjadi ini dapat menarik / mengacaukan dan
menutup pembuluh-pembuluh darah
3. Gesekan
Gesekan terjadi saat penderita bergerak maju atau ditarik dari tempat
tidurnya sehingga terjadi gesekan antara kulit dan alas tempat tidur,
gesekan ini menghilangkan stratum korneum epidermis sehingga
jaringan di bawahnya menjadi terekspose.
4. Faktor predisposisi
a. Faktor tubuh sendiri ( faktor intrinsik ) antara lain :
Status gizi, underweight atau overweight
Adanya hipoalbuminemia mempermudah terjadinya dekubitus dan
memperburuk penyembuhan Sebaliknya bila ada dekubitus akan
menyebabkan kadar albumin darah menurun.
Penyakit-penyakit neurologik, penyakit-penyakit yang merusak
pembuluh darah dan memperburuk dekubitus.
Kulit yang lembab seperti pada penderita dengan inkontinensia,
keadaan hidrasi/cairan tubuh yang kurang.
b. Faktor ekstrinsik
Kebersihan tempat tidur
Alat-alat tenun yang kusut dan kotor
Peralatan medik, sehingga penderita terfiksasi pada suatu sikap
tertentu
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Dekubitus dapat terjadi pada setiap umur, tetapi usia lanjut berpotensi
lebih besar. Hal ini disebabkan adanya hubungan antara perubahan
pada kulit dengan bertambahnya usia,yaitu :
a. Berkurangnya jaringan lemak subkutan
b. Berkurangnya jaringan kolagen dan elastin
c. Menurunnya efisiensi kolateral kapiler pada kulit sehingga kulit
menjadi lebih tipis dan rapuh
III.
PEMBAGIAN DAN LOKASI TERSERING DEKUBITUS
Mengingat patofisiologi terjadinya ulkus dekubitus, maka perlu diingat
bahwa kerusakan jaringan dibawah tempat yang mengalami dekubitus adalah
lebih luas dari ulkusnya sendiri. Dan sebelumnya perlu dipahami terlebih dahulu
tentang lapisan-lapisan kulit.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Pembagian tipe ulkus dekubitus berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk
penyembuhannya dan perbedaan suhu dari ulkus dengan kulit sekitarnya dibagi
menjadi 3 yaitu :
a. Tipe normal
Tipe ini memiliki beda temperature sampai dibawah
2,5 C
dibandingkan kulit sekitarnya dan akan sembuh dalam perawatan
sekitar 6 minggu. Ulkus ini terjadi karena iskemia jaringan akibat
tekanan, tetapi aliran darah dan pembuluh-pembuluh darah baik.
b. Tipe arteriosklerotik
Tipe ini memiliki beda temperature kurang dari 1C antara daerah
ulkus dengan kulit sekitarnya. Keadaan ini menunjukkan gangguan
aliran darah akibat penyakit pada pembuluh darah (arteriosklerotik)
ikut berperan untuk terjadinya dekubitus, disamping faktor tekanan.
Dengan perawatan, ulkus ini diharapkan sembuh dalam 16 minggu.
c. Tipe terminal
Tipe ini terjadi pada penderita yang akan meninggal dan tidak dapat
sembuh.
Berdasarkan karakteristik pembagian klinis, dekubitus terbagi atas:
a. Derajat 1. Akan terlihat kulit yang kemerahan atau kulit yang berubah
warna menjadi lebih gelap. Kulit belum rusak tetapi meradang dan
mungkin sakit, serta panas saat disentuh. Didapati pula tekstur kulit
yang mengeras seperti bunga karang yang menetap. Perbedaan warna
dari kulit, panas dan edema, indurasi atau lecet dan mengeras menjadi
tanda-tanda awal dari dekubitus.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
b. Derajat 2. Terlihat tanda-tanda
dimana kulit mulai terpecah dan
sebagian kulit yang tipis menghilang mulai dari epidermis, dermis atau
keduanya. Ulkus masih superfisial memperlihatkan gambaran yang
abrasi, melepuh dan lubang yang dangkal dengan tepi ulkus jelas.
Jaringan sekitar mungkin berbatas merah, membengkak serta terasa
perih.
c. Derajat 3. Lapisan kulit hilang seluruhnya oleh karena kerusakan yang
meluas atau nekrosis dari jaringan subkutan, serta melebar ke bawah
tetapi tidak mencapai batas fascia (pembungkus otot). Gambaran klinis
dari ulkus berupa lubang atau kawah yang dalam dan menggaung
dengan atau tanpa merusak jaringan yang berdekatan.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
d. Derajat 4. Kulit seluruhnya mengalami kerusakan yang lebih lanjut,
ada jaringan yang nekrosis, kerusakan dari otot, tulang atau jaringan
pendukung seperti tendon dan joint kapsul. Derajat 4 ini dapat
mengakibatkan infeksi pada tulang atau sendi.
Lokasi tersering pada pasien yang berbaring adalah di samping
atau belakang kepala, siku, punggung, panggul, lutut, atau di mana pun
bagian yang bersentuhan dengan tempat tidur dengan jangka waktu lama.
Hal ini terlihat pada gambar berikut:
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Pada pasien yang menggunakan kursi roda dan menghabiskan
sebagian besar waktunya untuk duduk juga dapat terkena dekubitus,
lokasi-lokasi yang sering terkena dekubitus terlihat pada gambar di bawah
ini:
IV.
FAKTOR RESIKO
Pasien-pasien tua yang tidak mampu bergerak (seperti: stroke, demensia
lanjut, patah tulang panggul), inkontinensia, malnutrisi, diabetes mellitus,
pemakaian urin kateter, fraktur merupakan pasien-pasien yang berisiko tinggi
untuk terkena ulkus dekubitus. Banyak faktor resiko bagi berkembangnya ulkus
dekubitus, namun semua penyakit yang menyebabkan ketidakmampuan untuk
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
bergerak meningkatkan faktor resiko tersebut. Penelitian pada orang-orang tua
yang dipasang alat penghitung otomatis pada tempat tidurnya ditemukan bahwa
pada pasien dengan > 51 gerakan spontan pada malam hari tidak menyebabkan
dekubitus, namun pada 90 % pasien dengan < 20 gerakan spontan pada malam
hari mengalami dekubitus.
Peningkatan umur meningkatkan angka terjadinya dekubitus. Umur
berhubungan dengan berubahnya fisiologi di kulit pasien.
Jadi faktor risiko dekubitus pada lansia adalah :
D
: Delirium, dementia, dependence.
: Elderly.
: Kontraktur.
: Urinary incontinence.
: Bowel incontinence.
: Immobility.
: Tension oxygen low.
: Under nourishment.
: Spastic.
Skala Norton sering dipakai untuk mengidentifikasi pasien-pasien dengan
risiko tinggi, dimana pada skala ini menggunakan 5 variabel yaitu: kondisi fisik,
status mental, derajat aktivitas, mobilitas, inkontinensia.
Tabel. IV. 1. Skala Norton Untuk Mendeteksi Pasien Berisiko Terkena Ulkus Dekubitus.
Nama Pasien
Skor
Tanggal
Dengan penilaian
Skor < 12
Kondisi fisik umum:
- Baik
- Lumayan
- Buruk
- Sangat buruk
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
= resiko tinggi
Skor 12 13 = resiko sedang
Skor > 14
= resiko rendah
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Kesadaran:
- Compos mentis
- Apatis
- Sopor/confuse
- Stupor/koma
Aktifitas:
- Ambulan
- Ambulan dengan bantuan
- Hanya bisa duduk
- Tidur
Mobilitas:
- Bergerak bebas
- Sedikit terbatas
- Sangat terbatas
- Tak bisa bergerak
Inkotinensia:
- Tidak ada
- Kadang-kadang
- Sering inkotinensia urn
- Inkotinensia urin dan alvi
Skor total
V.
KOMPLIKASI
Komplikasi yang terjadi akibat dekubitus adalah :
Sepsis merupakan komplikasi yang paling sering dari dekubitus.
Infeksi lokal, selulitis, dan osteomielitis.
Pyarthrosis atau ulkus yang berpenetrasi ke rongga sendi.
Hal ini terjadi pada dekubitus yang terinfeksi sangat dalam.
Amyloidosis terjadi pada dekubitus kronik.
Hal ini juga menjadi sumber penularan nokosomial di rumah sakit
karena resistensi dari antibiotic.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
10
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Tanda-tanda mulainya terjadi infeksi dari ulkus adalah :
Terdapat nanah / pus yang berwarna kuning atau hijau.
Tercium bau tidak enak dari luka.
Di sekitar luka memerah, membengkak dan empuk saat dipegang
(fluktuasi).
Tanda-tanda infeksi tersebut sudah meluas adalah :
Suhu meningkat, tidak bisa konsentrasi, detak jantung cepat dan
lemah.
VI.
PENATALAKSANAAN
Tindakan pencegahan adalah langkah pertama dalam menghindari
timbulnya dekubitus. Selain mengurangi biaya perawatan, pencegahan terjadinya
ulkus dekubitus juga merupakan langkah yang dapat mempertahankan kualitas
hidup pasien. Pencegahan untuk mencegah terjadinya luka dekubitus terdiri dari 3
kategori, yaitu :
1. Perawatan kulit dan penanganan dini
a. Diawali dengan mengenal penderita yang beresiko tinggi untuk
terjadinya dekubitus.
b. Meramalkan akan terjadinya dekubitus dengan memakai skor
Norton. Skor di bawah 14 menunjukkan adanya resiko tinggi
terjadinya dekubitus.
c. Menjaga kebersihan kulit penderita dengan memandikan setiap
hari. Sesudah dikeringkan dengan baik, digosok dengan lotion,
terutama di bagian kulit yang terdapat tonjolan-tonjolan tulang.
Bisa juga dibubuhkan bedak tabur secara teratur. Sambil digosok di
lakukan masase untuk melancarkan sirkulasi darah ke kulit.
d. Meningkatkan status kesehatan penderita
Umum : memperbaiki dan menjaga keadaan umum penderita,
misalnya hipoalbuminemia dikoreksi, nutrisi dan hidrasi yang
cukup, vitamin C dan mineral Zn ditambahkan.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
11
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Khusus : mengobati penyakit-penyakit yang ada pada penderita,
misalnya DM yang belum terkontrol dengan baik, paru, dsb.
e. Mengurangi / meratakan faktor tekanan yang mengganggu aliran
darah
Alih posisi / tidur selang-seling paling lama tiap 2 jam sekali
yaitu : 2 jam miring ke kiri, 2 jam terlentang, 2 jam miring ke
kanan.
2. Penggunaan berbagai matras atau kasur
Saat ini telah dikembangkan berbagai macam kasur anti dekubitus
yang berisi sabut kelapa / keset, karena serabut-serabut halus pada keset
sabut kelapa tersebut dapat lebih melancarkan peredaran darah, sehingga
oksigenasi ke jaringan-jaringan tubuh yang iskemik juga dapat diperbaiki.
Selain kasur dari bahan sabut kelapa juga telah banyak dibuat bantal anti
dekubitus yang juga terbuat dari bahan sabut kelapa/keset tersebut.
Kasur khusus untuk lebih membagi rata tekanan yang terjadi pada
tubuh penderita. Karena pada kasur tidur busa biasa, berat tubuh pasien
hanya didistribusikan pada beberapa tempat tertentu, sehingga resiko
terjadi dekubitus menjadi besar.
Gambar VI.1. Penderita berbaring terlentang di atas kasur busa
biasa.
Berat tubuh penderita akan didistribusikan pada beberapa tempat tertentu.
Resiko terjadinya dekubitus besar sekali.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
12
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Gambar VI.2. Penderita berbaring terlentang di atas kasur biasa,
tetapi dibantu dengan beberapa bantal kecil penyangga tubuh.
Berat tubuh berhasil dibagi lebih merata, sehingga resiko terjadinya
dekubitus diperkecil.
Gambar VI.3.Penderita berbaring di atas kasur khusus (kasur anti
dekubitus) dengan memakai sistem gelombang udara yang naik turun
bergantian.
Berat tubuh lebih berhasil dibagi merata, resiko dekubitus lebih diperkecil.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
13
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Gambar VI.4.Penderita berbaring di atas kasur air, dengan
temperatur air dapat diatur sesuai yang diinginkan.
Beban berat tubuh benar-benar merata pada seluruh bagian tubuh yang
kontak dengan alas, sehingga faktor tekanan sangat diperkecil dan resiko
terjadinya dekubitus akibat faktor ini menjadi minimal.
Regangan pada kulit dan lipatan kulit yang menyebabkan sirkulasi
darah setempat terganggu, dapat dikurangi antara lain dengan cara:
-
Menjaga posisi pasien, apakah dengan ditidurkan rata di tempat
tidurnya, atau didudukkan di kursi.
-
Memberi bantalan dari balok penyangga pada kedua kaki, bantal-
bantal kecil untuk menahan tubuh penderita, kue donat ( dekubitus ring )
untuk tumit,
ini semua dapat mendukung usaha pencegahan dan
pengobatan dekubitus.
3. Edukasi pasien
Tim medis yang terlibat didalam edukasi pasien agar menyadari bahwa
tindakannya dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
pasien untuk mencegah terjadinya luka dekubitus, akan sangat
mempengaruhi pasien untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan
terjadinya dekubitus.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
14
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Pengobatan bila sudah terjadi dekubitus
Bila sudah terjadi dekubitus, maka harus ditentukan terlebih dulu derajat
dari dekubitus tersebut. Karena tindakan medisnya akan disesuaikan
dengan derajat tersebut.
a. Dekubitus derajat I
Bila reaksi peradangan masih terbatas pada epidermis, maka kulit yang
kemerahan dibersihkan hati-hati dengan air hangat dan sabun, lalu diberi
lotion, kemudian dimasase 2-3 kali sehari.
b. Dekubitus derajat II
Perawatan ulkus / luka yang sudah terjadi harus memenuhi syarat-syarat
aseptik dan antiseptik.
Daerah yang luka digosok dengan es dan dihembus dengan udara hangat
bergantian untuk merangsang sirkulasi. Dapat diberikan salep antibiotik
topikal
untuk
merangsang
tumbuhnya
jaringan
muda/granulasi.
Penggantian balutan dan salep jangan terlalu sering karena dapat merusak
pertumbuhan jaringan yang diharapkan.
c. Dekubitus derajat III
Ulkus lebih dalam, ulkus menggaung sampai pembungkus otot dan sudah
terinfeksi, maka diusahakan luka selalu bersih dan eksudat diusahakan
dapat mengalir keluar. Balutan jangan terlalu tebal, sebaiknya transparan
sehingga permeabel untuk masuk-keluarnya udara / oksigen dan
penguapan. Kelembaban luka dijaga
agar tetap basah, karena dapat
mempermudah regenerasi sel-sel kulit. Luka yang kotor dapat dicuci
dengan larutan NaCl fisiologis dan diberi antibiotik lokal dan sistemik.
Pilihan untuk antibiotik lokal : Salep kloramfenikol 2%. Pilihan untuk
antibiotik sistemik : antibiotik spektrum luas, seperti amoksisilin 4 x 500
mg selama 15-30 hari , atau siklosporin 1-2 g/hari selama 3-10 hari.
d. Dekubitus derajat IV
Terdapat perluasan ulkus sampai ke tulang dan sering disertai jaringan
nekrotik. Maka semua langkah-langkah di atas tetap dilakukan dan
jaringan nekrotik yang ada harus dibersihkan, karena akan menghalangi
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
15
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
pertumbuhan jaringan / epitelisasi. Setelah jaringan nekrotik dibuang dan
luka bersih, penyembuhan luka
dapat secara alami. Beberapa usaha
mempercepat penyembuhan dengan memberikan oksigenasi pada daerah
luka, tindakan dengan ultrasono untuk membuka sumbatan-sumbatan
pembuluh darah dan transplantasi kulit setempat. Setelah ulkus sembuh,
harus diperhatikan kemungkinan timbulnya kembali ulkus di daerah yang
sama.
Proses penyembuhan luka dekubitus
Penyembuhan luka dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu :
1. Fase inflamasi (lag fase)
Fase inflamasi berlangsung sejak terjadinya luka sampai kirakira hari kelima. Pembuluh darah yang terputus pada luka akan
menyebabkan perdarahan dan tubuh akan berusaha menghentikannya
dengan vasokonstriksi, pengerutan ujung pembuluh yang putus
(retraksi), dan reaksi hemostatis. Hemostatis terjadi karena trombosit
yang keluar dari pembuluh darah saling melengket, dan bersama
dengan jala fibrin yang terbentuk membekukan darah yang keluar dari
pembuluh darah. Sementara itu terjadi reaksi inflamasi.
Sel mast dalam jaringan ikat menghasilkan serotonin dan
histamine yang meningkatkan permeabilitas kapiler sehingga terjadi
eksudasi cairan, penyebukan sel radang, disertai vasodilatasi setempat
yang menyebabkan udem dan pembengkakan. Tanda dan gejala klinik
reaksi radang menjadi jelas berupa warna kemerahan karena kapiler
melebar (rubor), suhu hangat (kalor), rasa nyeri (dolor) dan
pembengkakan (tumor).
Aktifitas seluler yang terjadi adalah pergerakan leukosit
menembus dinding pembuluh darah (diapedesis) menuju luka karena
daya kemotaksis. Leukosit mengeluarkan enzim hidrolitik yang
membantu mencerna bakteri dan kotoran luka. Limfosit dan monosit
yang kemudian muncul ikut menghancurkan dan memakan kotoran
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
16
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
luka dan bakteri ini (fagositosis). Fase ini disebut juga fase lamban
karena reaksi pembentukan kolagen baru sedikit dan luka hanya
dipertautkan oleh fibrin yang amat lemah.
2. Fase proliferasi (fase fibroplasia)
Fase proliferasi disebut juga fase fibroplasia karena yang
menonjol adalah proses proliferasi fibroblast. Fase ini berlangsung dari
akhir fase inflamasi sampai kira-kira akhir minggu ketiga. Fibroblast
berasal dari sel mesenkim yang belum berdiferensiasi, menghasilkan
mukoplisakarida, asam aminoglisin dan prolin yang merupakan bahan
dasar kolagen serat yang akan mempertautkan tepi luka.
Pada fase fibroplasia ini, luka dipenuhi sel radang, fibroblast
dan kolagen membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan
permukaan yang berbenjol halus yang disebut jaringan granulasi.
Epitel tepi luka yang terdiri dari sel basal terlepas dari dasarnya dan
berpindah mengisi permukaan luka. Tempatnya kemudian diisi oleh sel
baru yang terbentuk dari proses mitosis. Proses migrasi hanya bisa
terjadi ke arah yang lebih rendah atau datar, sebab epitel tak dapat
bermigrasi ke arah yang lebih tinggi. Proses ini baru berhenti setelah
epitel saling menyentuh dan menutup seluruh permukaan luka. Dengan
tertutupnya permukaan luka, proses fibroplasia dengan pembentukan
jaringan granulasi juga akan berhenti dan mulailah proses pematangan
dalam fase penyudahan.
3. Fase remodeling ( fase resorbsi )
Pada fase ini terjadi proses pematangan yang terdiri dari
penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai dengan
gaya gravitasi dan akhirnya perupaan kembali jaringan yang baru
terbentuk. Fase ini dapat berlangsung berbulan-bulan dan dinyatakan
berakhir kalau semua tanda radang sudah lenyap. Tubuh berusaha
menormalkan kembali semua yang menjadi abnormal karena proses
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
17
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
penyembuhan. Udem dan sel radang diserap, sel muda menjadi
matang, kapiler baru menutup dan diserap kembali, kolagen yang
berlebih diserap dan sisanya mengerut sesuai dengan regangan yang
ada. Selama proses ini dihasilkan jaringan parut yang pucat, tipis dan
lemas serta mudah digerakkan dari dasar.
Langkah-langkah pokok yang harus dilakukan adalah :
1. Melihat adanya faktor resiko atau tidak.
2. Perawatan kulit yang beresiko dan pengobatan sedini mungkin apabila
terjadi tanda-tanda akan timbul luka tekan yaitu kulit tampak
kemerahan.
3. Suportif terhadap permukaan kulit dalam pengaturan posisi dan secara
mekanik
4. Pemberian asuhan kepada seluruh tingkat pelaksana rawat kesehatan
pasien, seperti keluarga, pramurukti dan lain-lain.
PENYEMBUHAN LUKA DENGAN MADU
Beberapa
penelitian
menunjukkan
bahwa
madu
mempunyai efek bakterisid (membunuh kuman), hal ini
mempermudah penyembuhan secara natural dari ulkus
diabetikum, ulkus dekubitus, luka bakar, luka potong, bisul,
kulit retak dan lain-lain. Percobaan pada tahun 1999 2000 di
Rumah Sakit Waikato, Hamilton, New Zealand menunjukkan keberhasilan
pengobatan madu pada ulkus yang tidak responsive terhadap pengobatan dan pada
luka kronik.
Madu dapat melembabkan luka sehingga memberikan hasil penyembuhan
luka yang baik. Hal ini disebabkan oleh:
1. Keadaan yang lembab mempercepat proses penyembuhan.
Pertumbuhan jaringan baru diperlambat jika luka kering.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
18
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
2. Keadaan lembab mengurangi terjadinya jaringan parut.
Keropeng (serum yang mengering) merupakan usaha natural tubuh untuk
menjaga luka agar tetap lembab. Tetapi pertumbuhan sel di bawah keropeng
tersebut akan menghasilkan jaringan parut. Jadi penggunaan madu dapat
mencegah pembentukan keropeng.
3. Mengurangi rasa sakit terutama jika balutan/kasa diganti.
Pada luka yang kering, keropeng mudah melekat pada balutan/kasa dan hal ini
akan menimbulkan rasa nyeri dan menyebabkan jaringan kulit yang baru akan
ikut terlepas.
Madu mampu menyembuhkan luka karena efek bakterisid dari hydrogen
peroxide. Ketika madu diberikan pada luka, enzim glukose oxidase yang terdapat
pada madu merangsang pengeluaran antiseptik hydrogenperoxide secara berlahan.
Pengeluaran ini sampai pada keadaan dimana cukup efek antibakterinya tetapi
tidak merusak jaringan yang sehat. Aktivitas antibakteri hydrogen peroxide
bermacam-macam tergantung :
1. Jenis bunga (ada beberapa nectar yang mengandung catalase yang dapat
merusak hydrogen peroxide).
2. Cara pemrosesan madu, hal ini disebabkan enzim glucose oxidase yang
memproduksi hydrogen peroxide mudah rusak oleh panas, zat cair/gas,
sinar matahari.
3. Enzim katalase yang terdapat pada jaringan tubuh dan serum dapat
merusak hydrogen peroxide serta mengurangi efek anti bakterialnya.
Madu dapat membantu penyembuhan luka karena :
1. Membersihkan luka
Madu mempunyai efek debridemant, efek osmotik dari madu mampu
mengangkat kotoran dari dasar luka. Efek osmotik madu mampu menjaga
luka agar tetap bersih, lembab dan mencegah luka melekat pada kasa.
Kerusakan jaringan dan rasa sakit jadi berkurang sewaktu kasa/balutan
diganti.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
19
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
2. Madu memberikan nutrisi yang diperlukan oleh jaringan seperti vitamin,
mineral dan asam amino.
3. Madu merangsang regenerasi jaringan dengan cara :
Merangsang angiogenesis dimana pembuluh darah baru ini akan
memberikan oksigen dan nutrisi pada jaringan.
Merangsang pertumbuhan sel epitel.
4. Madu mempunyai efek seperti insulin.
5. Efek antiradang madu mempercepat penyembuhan, mengurangi rasa sakit
dan bengkak.
6. Madu dapat mengurangi bau pada luka dengan cara membunuh bakteri
yang memproduksi amonia.
7. Madu tidak merusak kulit yang sehat dan dapat mengurangi kebutuhan untuk
transplantasi jaringan.
VII. KESIMPULAN
Dekubitus terjadi akibat seseorang berada pada satu posisi dalam jangka
waktu yang panjang dan tanpa adanya perpindahan posisi. Tekanan di kulit yang
bersentuhan dengan alasnya tersebut menyebabkan iskemi jaringan sehingga
menyebabkan dekubitus. Faktor penyebab dekubitus adalah masalah imobilitas.
Bila dapat diusahakan pemerataan kontak bagian-bagian tubuh dengan permukaan
alas tidur akan dapat mengurangi besarnya faktor tekanan.
Hampir seluruh dekubitus dapat dicegah dengan banyak teknik seperti
edukasi, diet, berpindah posisi setiap 2 jam, kebersihan diri dan rencana
perorangan. Pengelolaan diawali dengan kewaspadaan mengenal penderita dengan
resiko tinggi terjadi dekubitus, yang dapat dinilai dengan sistem skor dari Norton.
Setelah terjadi dekubitus tindakan medik disesuaikan dengan derajat / stadium
dari dekubitus. Sekarang ini penggunaan madu untuk merawat luka dekubitus
memberikan hasil penyembuhan yang baik.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
20
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
RANGKUMAN DEKUBITUS
Istilah dekubitus diambil dari bahasa latin decumbere yang artinya
berbaring. Dekubitus dapat terjadi pada setiap umur, tetapi hal ini merupakan
masalah yang khusus dan banyak terjadi pada lanjut usia. Ini dikarenakan adanya
hubungan antara pertambahan usia dengan perubahan pada kulit. Insiden kejadian
decubitus ini berkaitan erat dengan imobilitas.
Dekubitus juga disebut pressure sores atau bed sores, adalah
kerusakan/kematian kulit sampai jaringan di bawah kulit, bahkan menembus otot
sampai mengenai tulang akibat adanya penekanan pada satu area yang
berlangsung terus menerus atau berulang-ulang sehingga mengakibatkan
peredaran darah setempat terhenti sehingga terjadi nekrosis. Bagian tubuh yang
sering mengalami dekubitus adalah tempat di mana terdapat penonjolan misalnya
daerah sacrum, trokhanter mayor, spina ischiadica anterior superior, tumit, siku
dan kepala bagian belakang.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya dekubitus, antara lain :
tekanan, peregangan dan lipatan kulit, gesekan kulit, serta beberapa faktor
predisposisi.
Pembagian tipe ulkus dekubitus berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk
penyembuhannya dan perbedaan suhu dari ulkus dengan kulit sekitarnya dibagi
menjadi 3 yaitu: tipe normal, tipe arteriosklerotik, tipe terminal. Ada pula tipe
ulkus berdasarkan karakteristik pembagian klinis, yaitu derajat 1,2,3,4. Dekubitus
juga dapat terjadi pada pasien yang sering duduk dikursi roda dalam jangka
waktu yang lama.
Skala Norton sering digunakan untuk mengidentifikasi pasien dengan
faktor risiko yang tinggi, dimana pada skala ini menggunakan 5 variabel yaitu:
kondisi fisik, status mental, derajat aktivitas, mobilitas, inkontinensia.
Komplikasi yang terjadi akibat dekubitus adalah: sepsis, infeksi lokal,
selulitis, dan osteomielitis, pyarthrosis atau ulkus yang berpenetrasi ke rongga
sendi dan amyloidosis.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
21
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
Tindakan pencegahan adalah langkah pertama dalam menghindari
timbulnya dekubitus. Pencegahan ini meliputi :perawatan kulit dan penanganan
dini , penggunaan berbagai matras atau kasur, dan edukasi pada pasien.
Pengobatan pada ulkus dekubitus berdasarkan pada derajat dari dekubitus
tersebut.
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
22
Dekubitus
Chandra R. Wulan, S.Ked (406102038)
DAFTAR PUSTAKA
1. Darmojo R.B., Martono H.H., Buku Ajar Geriati, FKUI, Jakarta 1999.
2. Djuanda A., Prof., Dr., Ilmu Penyakit kulit dan Kelamin edisi ketiga, FKUI,
Jakarta 1999.
3. Doyle D., Hanks G.W.C., Mc Donald N., Palliative Medicine Second editior,
Oxford Univesity, London 1998.
4. Hazzard W.R., Andres R., Bierman E.L, Priciples of Geriatric Medicine and
Gerontology 2 ad edition. Vol.1., Mc Graw Hill Inc., New York 1990.
5. Siregar R.S., Prof., Dr., Atlas Berwarna Saripati Penyakit Kulit, EGC, Jakarta
1996.
6. www. Ahcpr. gov/clinic. Com
7. www. Bed-sores.info/bed sore from. html.
8. www. Epuap.org/grading. html.
9. www. Fpnotebook.com
10. www. Home. cogeco.com
11. www. Nopressuresores.com
12. www. Reposedirect.com/grade.html
13. www.Seniorjournal.com
Kepaniteraan Geriatri
Fakultas Kedokteran Universitas Tarumanagara
Panti Werdha Kristen Hana
Periode 28 Januari 2 Maret 2013
23
Anda mungkin juga menyukai
- Ulkus Dekubitus - Robin KKJ BedahDokumen20 halamanUlkus Dekubitus - Robin KKJ BedahWolfy D HaroldBelum ada peringkat
- 2-Bab I - Lapsus Lontara 3 Saraf-Audi - ParapareseDokumen33 halaman2-Bab I - Lapsus Lontara 3 Saraf-Audi - ParapareseSulvina IbrahimBelum ada peringkat
- DRK SelulitisDokumen12 halamanDRK SelulitisNORHIDA WIDIARTIBelum ada peringkat
- Memahami Berbagai Jenis Luka Dan Asuhan Keperawatan LukaDokumen41 halamanMemahami Berbagai Jenis Luka Dan Asuhan Keperawatan LukaAthenaDewiBelum ada peringkat
- LP Tutorial Kasus 2 Manajemen KeperawatanDokumen16 halamanLP Tutorial Kasus 2 Manajemen Keperawatanmarizka putriBelum ada peringkat
- Askep IMADokumen14 halamanAskep IMAnandangBelum ada peringkat
- Ketrampilan Infus-Injeksi IntravenaDokumen14 halamanKetrampilan Infus-Injeksi IntravenakemalBelum ada peringkat
- Klinik Perawatan Luka "Wound Care": I. Pendahuluan A. Nama UsahaDokumen14 halamanKlinik Perawatan Luka "Wound Care": I. Pendahuluan A. Nama UsahaSyarifahBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan Pada Penurunan KesadaranDokumen21 halamanAsuhan Keperawatan Pada Penurunan Kesadarankiki71% (7)
- TriaseDokumen6 halamanTriaseagus sukisnoBelum ada peringkat
- Penerimaan Pasien BaruDokumen8 halamanPenerimaan Pasien BaruMutiara MukhtarBelum ada peringkat
- Makalah Standar Pengukuran Resiko JatuhDokumen26 halamanMakalah Standar Pengukuran Resiko JatuhUlfani DewiBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan IbsDokumen8 halamanLaporan Pendahuluan IbsIsmiBelum ada peringkat
- Pengaruh Nutrisi Terhadap Penyembuhan LukaDokumen27 halamanPengaruh Nutrisi Terhadap Penyembuhan LukaWidiyanti100% (2)
- Makalah Penatalaksanaan Pada DekubitusDokumen15 halamanMakalah Penatalaksanaan Pada DekubitusNurul Hidayati Putri RohmaniaBelum ada peringkat
- Leaflet KemoDokumen3 halamanLeaflet KemoLa Gaya RembezBelum ada peringkat
- Panduan RJPDokumen4 halamanPanduan RJPyustina arieBelum ada peringkat
- Kelompok 3 Ronde KeperawatanDokumen19 halamanKelompok 3 Ronde KeperawatanYoqi Pratama77Belum ada peringkat
- SAP Perawatan LukaDokumen9 halamanSAP Perawatan LukaYustina sri lestariBelum ada peringkat
- Pijat Perut Kelompok 5Dokumen14 halamanPijat Perut Kelompok 5Putri AyuBelum ada peringkat
- Laporan SGD LBM 4Dokumen25 halamanLaporan SGD LBM 4Dinda Amalia SBelum ada peringkat
- Cara Penyampaian Kabar Buruk Pada Orang Dengan Penyakit TerminalDokumen6 halamanCara Penyampaian Kabar Buruk Pada Orang Dengan Penyakit TerminalTisya DarmawantiBelum ada peringkat
- Sap Pemberian KemoterapiDokumen6 halamanSap Pemberian KemoterapiOktavi CahyaniBelum ada peringkat
- DEKUBITUSDokumen19 halamanDEKUBITUSEvita Puspa100% (1)
- Terapi Komplementer Dalam Keperawatan KomunitasDokumen7 halamanTerapi Komplementer Dalam Keperawatan KomunitasMarchelinBelum ada peringkat
- Edward JennerDokumen7 halamanEdward JennerNur Aulia SBelum ada peringkat
- 2.5 Tahap TerminalDokumen22 halaman2.5 Tahap TerminalAgnes PandianganBelum ada peringkat
- 5 Terapi Komplementer OK PDFDokumen11 halaman5 Terapi Komplementer OK PDFMia Rusmiati Annisa100% (2)
- EVDDokumen6 halamanEVDAzizah FadhilahBelum ada peringkat
- Refleksi Kasus Cvcu 1Dokumen3 halamanRefleksi Kasus Cvcu 1gunawan filmBelum ada peringkat
- Lapsus Kulit SelulitisDokumen16 halamanLapsus Kulit SelulitisAstuti Clara SimanjuntakBelum ada peringkat
- TanatologiDokumen48 halamanTanatologiAnuZ13thBelum ada peringkat
- Askep DMDokumen14 halamanAskep DMTu AdiBelum ada peringkat
- Kedaruratan Onkologi. ReferatDokumen18 halamanKedaruratan Onkologi. ReferatRandi DwiyantoBelum ada peringkat
- Derajat Luka BakarDokumen4 halamanDerajat Luka BakarfahrunnisaBelum ada peringkat
- Makalah Askep Sindrom KlinefelterDokumen18 halamanMakalah Askep Sindrom KlinefelterAyik HandayaniBelum ada peringkat
- Jurnal - Pemfigus VulgarisDokumen8 halamanJurnal - Pemfigus VulgarisOktaviaBelum ada peringkat
- Tahapan OperasiDokumen45 halamanTahapan OperasiAfni ABelum ada peringkat
- Askep CP Pada AnakDokumen15 halamanAskep CP Pada AnakDesi Sagita DarfidBelum ada peringkat
- SOP Asuhan KeperawatanDokumen2 halamanSOP Asuhan KeperawatanAgnes Bengan100% (2)
- Sak KatarakDokumen8 halamanSak KatarakMaimunah RahmawatiBelum ada peringkat
- Satuan Acara Penyuluhan KBDokumen11 halamanSatuan Acara Penyuluhan KBaromaBelum ada peringkat
- Slide Merina Aspek Legal Keperawatan BencanaDokumen47 halamanSlide Merina Aspek Legal Keperawatan BencanaPuputi Wulandari100% (3)
- Asuhan Keperawatan GBSDokumen30 halamanAsuhan Keperawatan GBSAnonymous xQ6dDy37Belum ada peringkat
- Naskah Roleplay Pre Conference Dan Operan Shift Kelompok 3 MankepDokumen13 halamanNaskah Roleplay Pre Conference Dan Operan Shift Kelompok 3 MankepSissy LestariBelum ada peringkat
- DEKUBITUSDokumen24 halamanDEKUBITUSShare KeperawatanBelum ada peringkat
- Kebijakan KeperawatanDokumen15 halamanKebijakan Keperawatanyuni dwi kartikaBelum ada peringkat
- ASKEPCHOLELITHIASISDokumen15 halamanASKEPCHOLELITHIASISGiok Gogok GiokBelum ada peringkat
- Prinsip Penanganan Bencana (Part 8)Dokumen65 halamanPrinsip Penanganan Bencana (Part 8)kanesetianiBelum ada peringkat
- Perawatan Luka GangrenDokumen4 halamanPerawatan Luka Gangrenelissa oktaviaBelum ada peringkat
- Skin GraftDokumen26 halamanSkin GraftFirda yantiBelum ada peringkat
- Tugas Makalah Keperawatan Anak I (TEPID SPONGE)Dokumen10 halamanTugas Makalah Keperawatan Anak I (TEPID SPONGE)Candra AyuBelum ada peringkat
- Sak GastritisDokumen14 halamanSak Gastritisdwisetiani100% (1)
- Askep Ca Cervik Palliatif-RefhDokumen47 halamanAskep Ca Cervik Palliatif-Refh1a HebatBelum ada peringkat
- RPS - Mata Kuliah Profesi Keperawatan Gadar Dan Kritis Blended 2020-2021Dokumen26 halamanRPS - Mata Kuliah Profesi Keperawatan Gadar Dan Kritis Blended 2020-2021Yusni MeteBelum ada peringkat
- Askep Lansia Resiko DecubitusDokumen17 halamanAskep Lansia Resiko DecubitusZakiatunahmadBelum ada peringkat
- Ulkus DekubitusDokumen20 halamanUlkus Dekubitussakisaki910% (1)
- DDGNL DHMHDokumen20 halamanDDGNL DHMHdian ayuBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan Ulkus DekubitusDokumen10 halamanLaporan Pendahuluan Ulkus DekubitusMuhamad Pathu RohmanBelum ada peringkat
- TEORIDokumen19 halamanTEORIsofiakamalaBelum ada peringkat