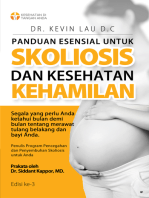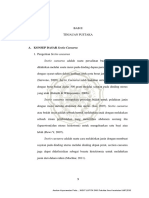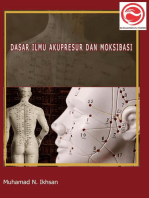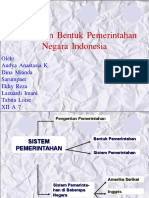Prolapsus Genitalia
Prolapsus Genitalia
Diunggah oleh
nerdwaldoHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Prolapsus Genitalia
Prolapsus Genitalia
Diunggah oleh
nerdwaldoHak Cipta:
Format Tersedia
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Prolapsus genitalia yaitu turunnya organ genital ke dalam introitus vagina
bahkan bisa hingga keluar dari introitus vagina disebabkan karena lemahnya
ligamentum dan otot-otot penyokong organ genital. Prolapsus genitalia dapat
berupa uretrokel, uretrovesikokel, vesikokel (sistokel), prolapsus uteri,
enterokel dan rektokel (Junizaf, 2002).
Prolapsus uteri adalah pergeseran letak uterus ke bawah sehingga seviks
berada didalam introitus vagina hingga berada diluar introitus atau
keseluruhan uterus berada diluar introitus vagina. Telah banyak dilakukan
penelitian dan diketahui bahwa faktor presdisposisi untuk terjadinya
prolapsus uteri adalah melahirkan karena adanya trauma pada saat persalinan
yang menyebabkan melemahnya otot-otot dan ligamentum penyokong uterus
(Junizaf, 2007).
Studi di Amerika Serikat dengan 16000 pasien menunjukkan frekuensi
prolapsus uteri sebesar 14,2%. Rata-rata usia dilakukannya tindakan bedah
untuk prolapsus uteri adalah 54,6 tahun. Perbedaan frekuensi berdasarkan ras
atau suku bangsa dimungkinkan berhubungan dengan faktor genetik. Sekitar
lebih dari 50% prolapsus uteri paling sering terjadi pada wanita yang sudah
lebih dari sekali melahirkan (multipara) (DeLancey, 2003).
Di Indonesia pendataan prolapsus uteri masih dikelompokkan menjadi
prolapsus genital, dari data rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta
pada tahun 1995-2000 telah dirawat 240 kasus prolapsus genitalia. Kasus
tersebut adalah kasus prolasus genitalia yang telah menimbulkan keluhan dan
memerlukan penanganan. Pada penelitian yang dilakukan Djafar Siddik tahun
1968-1970 diperoleh kasus prolapsus genitalia sebesar 65 kasus dari 5371
kasus ginekolgi di rumah sakit Dr. Pringadi Medan, 69% dari temuan kasus
tersebut adalah wanita dengan umur 40 tahun. Sedangkan di rumah sakit
Jamil Padang didapatkan 94 kasus selama kurun waktu 5 tahun (1993-1998)
dan 40,03% terjadi pada wanita dengan grandemultipara (Junizaf, 2002;
Erman, 2001).
Penelitian tahun 1999-2003 yang dilakukan oleh Amir Fauzi dan K.
Anhar telah menjadi lebih spesifik terhadap kejadian prolapsus uteri di
Indonesia dan pada penelitiannya menemukan 43 kasus prolapsus uteri di
rumah sakit Mohd. Hoesin Palembang. Kasus terbanyak yaitu 29 kasus
prolapsus uteri didapatkan pada penderita dengan grandemultipara (47,44%),
dan 14 kasus lainnya pada penderita dengan multipara (32,56%) (Erman,
2001; Junizaf, 2002; Kemas, 2003). Penelitian terbaru yang dilakukan oleh
Said Alfin K pada rumah sakit Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh menemukan
bahwa dari total 2163 pasien ginekologi yg dirawat di RSUZDA dari tahun
2007-2010, 71 diantaranya merupakan penderita prolapsus uteri (Said, 2011).
Walaupun sudah dlakukan di beberapa kota di Indonesia tetapi belum
terdapat penelitian tentang kejadian prolapsus uteri di wilayah kerja rumah
sakit Margono Soekarjo Purwokerto. Sehingga peneliti merasa tertarik untuk
melakukan penelitian terhadap hubungan antara kejadian prolapsus uteri
dengan paritas di rumah sakit Margono Soekarjo Purwokerto periode Januari
- Desember 2011.
B. Rumusan Masalah
Adakah hubungan antara paritas dengan kejadian prolapsus uteri di RS
Margono Soekarjo Purwokerto periode 01 Januari 2007 31 Desember 2011
C. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Mengetahui hubungan antara paritas dengan kejadian prolapsus uteri di
RS Margono Soekarjo Purwokerto periode 01 Januari 2007 31
Desember 2011.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui tingkat paritas penderita prolapsus uteri di RS
Margono Soekarjo Purwokerto periode 01 Januari 2007 31
Desember 2011.
b. Mengetahui jumlah kejadian prolapsus uteri di RS Margono
Soekarjo Purwokerto periode 01 Januari 2007 31 Desember 2011.
D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis
a. Menambah pengetahuan dan khasanah ilmu dalam bidang
Obstetri dan Gynekologi terutama tentang kejadian prolapsus
uteri.
b. Menjadi sumber informasi dan data dasar khususnya tentang
kejadian Prolapsus uteri.
c. Sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
Dapat dijadikan bahan atau bekal bagi tenaga kesehatan dalam
memberikan pelayanan kesehatan terutama dalam upaya pencegahan
dengan memberikan penyuluhan tingginya paritas wanita memiliki
faktor resiko lebih besar terjadinya prolapsus uteri.
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Anatomi Panggul
1. Panggul
Pelvis dibentuk oleh 4 buah tulang, yaitu:
a. Dua buah ossae coxae yang membentuk dinding anterior dan lateral.
b. Os. sacrum dan os. coccygis (bagian dari columna vertebralis)
membentuk dinding dorsal pelvis (Wiknjosastro, 2007).
Panggul dibagi oleh apertura pelvis superior (pintu atas panggul)
yang dibentuk oleh promontorium sacralis di sebelah dorsal, linea
iliopectinea yang tersusun atas linea terminalis dengan pecten ossis pubis
di sebelah lateral, dan symphysis os pubis di sebelah anterior, menjadi:
a. Pelvis major
Merupakan bagian yang terdapat di depan vertebrae lumbalis
sebagai batas dorsal; fossa iliaca dengan m. iliacus berada di sebelah
lateral dan dinding abdomen bagian bawah di sebelah ventral. Pelvis
spurium ini juga merupakan bagian rongga perut. Fungsinya
menahan alat-alat atau organ-organ rongga perut dan menahan uterus
yang
berisi
fetus
pada
wanita
hamil
sejak
bulan
ketiga
(Wiknjosastro, 2007).
b. Pelvis minor, yaitu rongga di bawah apertura pelvis superior
tersebut.
1) Mempunyai pintu masuk panggul; apertura pelvis superior dan
pintu keluar; apertura pelvis inferior yang berupa 2 buah segitiga
yang bersekutu pada alasnya (yakni garis yang menghubungkan
kedua tuber ischiadica).
a) Segitiga bagian dorsal trigonum anale dibentuk oleh kedua
lig. sacrotuberosa dan puncaknya terletak pada os
coccygis.
b) Segitiga bagian ventral trigonum urogenitale dibentuk oleh
ramus inferior ossis pubis dan ramus inferior ossis ischii
sebelah kiri dan kanan, dan puncaknya terletak pada
symphysis ossium pubis (yang diperkuat oleh lig.
arcuatum pubis) (Wiknjosastro, 2007).
c. Cavum pelvis (rongga panggul) terletak di antara pintu masuk dan
pintu keluar panggul, berupa saluran pendek yang melengkung
dengan bagian cekung ke depan (Thomson, 2003).
2. Dasar panggul
Karena manusia berdiri tegak lurus, maka dasar panggul perlu
mempunyai kekuatan untuk menahan semua beban yang diletakkan
padanya, khususnya isi rongga perut dan tekanan intraabdominal.Beban
ini ditahan oleh lapisan otot-otot dan fasia yang apabila mengalami
tekanan dan dorongan berlebihan atau terus-menerusdapat timbul
prolapsus genitalis (Wiknjosastro, 2007).
Pintu bawah panggul terdiri atas diafragma pelvis, diafragma
urogenital, dan lapisan-lapisan otot yang berada diluar (penutup genitalia
eksterna).
Diafragma pelvis merupakan penutup bagian bawah dari rongga
perut, dan terbentuk oleh muskulus levator ani dan muskulus koksigeus
yang menyerupai sebuah mangkok serta fasia endopelvik (Wiknjosastro,
2007).
Muskulus
levator
ani
ini
terbagi
menjadi
iliokoksigeus,
pubokoksigeus, dan puborektalis, walaupun jauh subdivisinya disebut
pubouretralis, dan pubovaginalis dimana serabut-serabut levator ani
berinsersi dalam fasia yang menutupi uretra (Wiknjosastro, 2007).
Otot pubokoksigeus berjalan dari permukaan dalam tulang pubis
bagian anterior dan median membentang ke belakang menuju bagian
belakang rectum, setelah mengelilingi rectum dan vagina kembali ke
tulang pubis di sisi lain (Wiknjosastro, 2007).
Bagian lateral dari otot tersebut disebut iliokoksigeus yang
membentang dari spina ischiadika dan arkus tendius yang menutup otot
obturatorius interna terus kebelakang dan berinsersi di pinggir lateral
tulang koksigeus dan sacrum bagian bawah (Wiknjosastro, 2007).
Otot levator ani kanan-kiri membentuk levator plate yang kuat sekali
dan terbentang dari titik penggabungannya di belakang hiatus levator
dan terus ke belakang dan berinsersi di tulang koksigeus, central perineal
body, dan pada ligament anokoksigeus (Wiknjosastro, 2007).
Di bawah otot levator ani terdapat diafragma urogenital yang
menutup
hiatus
genitalis,
dibentuk
oleh
aponeurosis
muskulus
transversus perinei profundus dan muskulus transversus superfisialis
berjalan antara arkus pubis kanan-kiri. Di dalam sarung aponeurosis itu
terdapat muskulus rhabdosfingter urethrae (Wiknjosastro, 2007).
Lapisan paling luar (distal) dibentuk oleh muskulus bulbokavernosus
yang melingkari genital eksterna, muskulus perinei transversus
superfisialis, muskulus iskhiokavernosus dan muskulus sfingter ani
eksternus (Wiknjosastro, 2007).
Semua otot dibawah pengaruh saraf motorik dan dapat dikejangkan
aktif. Fungsi otot-otot tersebut diatas adalah sebagai berikut:
a. Muskulus levator ani berfungsi mengerutkan lumen rectum,
vagina, uretra dengan cara menariknya ke arah dinding tulang
pubis, sehingga organ-organ pelvis di atasnya tidak dapat turun
(prolaps), mengimbagkan tekanan intraabdominal dan tekanan
atmosfer, sehingga ligament-ligamen tidah perlu bekerja
mempertahankan letak organ-organ pelvic di atasnya, sebagai
sandaran uterus, vagina bagian atas, rectum dan kantung kemih.
Bila otot levator rusak atau mengalami defek maka ligament
seperti ligament kardinale, sakro uterine mempunyai kerja yang
berat (Wiknjosastro, 2007).
b. Diafragma urgenital berfungsi memberi bantuan pada otot
levator ani menahan organ-organ pelvis (Wiknjosastro, 2007).
c. Muskulus sfingter ani eksternus diperkuat oleh muskulus levator
ani menutup anus (Wiknjosastro, 2007).
d. Muskulus bulbokavernosus mengecilkan introitus vagina di
samping meperkuat fungsi muskulus sfingter vesisae internus
yang terdiri atas otot polos (Wiknjosastro, 2007).
Pada introitus vaginae ditemukan juga bulbus vestibuli yang terdiri
atas jaringan yang mengandung banyak pembuluh darah sehingga dapat
membesar jika pembuluh darah terisi (Wiknjosastro, 2007).
3. Jaringan penunjang alat genital
Uterus berada di rongga panggul dalam ateversiofleksio sedemikian
rupa sehingga bagian depannya setinggi simfisis pubis dan bagian
belakang setinggi artikulasio sakrokoksigea (Wiknjosastro, 2007).
Jaringan
ikat
di
parametrium,
dan
ligamentum-ligamentum
membentuk suatu sistem penunjang uterus, sehingga uterus terfiksasi
relatif cukup baik (Wiknjosastro, 2007).
Jaringan-jaringan itu ialah:
a. Ligamentum kardinale sinistrum dan dekstrum (mackenrodt)
merupakan ligamentum yang terpenting untuk mencegah agar
uterus tidak turun. Ligamentum ini terdiri atas jaringan ikat tebal,
dan berjalan dari serviks dan puncak vagina ke arah lateral ke
dinding pelvis. Didalamnya ditemukan banyak pembuluh darah,
antara lain vena dan arteri uterina (Wiknjosastro, 2007).
b. Ligamentum
sakrouterinum
sinistrum
dan
dekstrum,
yakni
ligamentum yang juga menahan uterus supaya tidak banyak
bergerak, berjalan, melengkung dari bagian belakang serviks kiri dan
10
kanan melalui dinding rektum ke arah os sakrum kiri dan kanan
(Wiknjosastro, 2007).
c. Ligamentum rotundum sinistrum dan dekstrum, yakni ligamentum
yang menahan uterus dalam antefleksi, dan berjalan dari sudut
fundus uteri kiri dan kanan ke daerah inguinal kiri dan
kanan(Wiknjosastro, 2007).
d. Ligamentum puboservikale sinistrum dan dekstrum, berjalan dari os
pubis melalui kandung kencing, dan seterusnya sebagai ligamentum
vesikouterinum sinistrum dan dekstrum ke serviks (Wiknjosastro,
2007).
e. Ligamentum latum sinistrum dan dekstrum, yakni ligamentum yang
berjalan dari uterus ke arah lateral, dan tidak banyak mengandung
jaringan ikat. Sebetulnya ligamentum ini adalah bagian peritoneum
viserale yang meliputi uterus dan kedua tuba, dan berbentuk lipatan.
Di bagian lateral dan belakang ligamentum ini ditemukan indung
telur (ovarium sinistrum dan dekstrum). Untuk memfiksasi uterus
ligamentum ini tidak banyak artinya (Wiknjosastro, 2007).
f. Ligamentum infundibulopelvikum, yakni ligamentum yang menahan
tuba Falopii, berjalan dari arah infundibulum ke dinding pelvis. Di
dalamnya ditemukan urat saraf, saluran-saluran limfe, arteria dan
vena ovarika. Sebagai alat penunjang ligamentum ini tidak banyak
artinya (Wiknjosastro, 2007).
11
g. Ligamentum ovarii propium sinistrum dan dektrum, yakni
ligamentum yang menahan tuba Falopii, berjalan dari sudut kiri dan
kanan belakang fundus uteri ke ovarium (Wiknjosastro, 2007).
Ligamentum-ligamentum dan jaringan-jaringan di parametrium tidak
semuanya berfungsi sebagai penunjang uterus. Terdapat ligamentumligamentum yang mudah sekali dikendorkan, sehingga alat-alat genital
mudah berganti posisi. Ligamentum latum sebenarnya hanya satu lipatam
peritoneum yang menutupi uterus dan kedua tuba, dan terdiri atas
mesosalpink, mesovariun, dan mesometrium. Di lipatam tersebut
ditemukan jaringan ikat yang letaknya disebut intraligamenter (di dalam
ruangan ligamentum latum). Ruangan tersebut berhubungan pula dengan
ruangan retroperitoneal yang terdapat di atas otot-otot dasar panggul dan
di daerah ginjal (Wiknjosastro, 2007).
4. Sistem uropoetik di rongga panggul
Ureter yang di abdomen letaknya retroperitoneal masuk ke pelvis
minor melewati arteria iliaka interna dan melintasi arteri uterina dekat
pada serviks hampir tegak lurus, dan akhirnya bermuara di kandung
kencing sisi belakang di trigonum Lieutaudi (Wiknjosastro, 2007).
Vesika urinaria (kandung kencing) umumnya mudah menampung
350 ml, akan tetapi dapat pula terisi cairan 600 ml atau lebih. Bagian
kandung kencing yang mudah berkembang adalah bagian yang diliputi
oleh peritoneum viserale. Pada dasar kandung kencing terdapat trigonum
Lieutaudi, yang bersamaan dengan uretra, dihubungkan oleh septum
vesiko-uretro-veginale dengan dinding depan vagina. Di trigonum
12
Lieutaudi bermuara kedua (atau lebih) ureter. Dasar kandung kencing ini
terfiksasi, tidak bergerak atau tidak mengembang seperti bagian atas yang
diliputi oleh serosa. Di septum septum vesiko-uretro-vaginale terdapat
fasia yang dikenal sebagian fasia Halban (Wiknjosastro, 2007).
Dinding kandung kencing mempunyai lapisan otot polos yang kuat,
beranyaman seperti anyaman tikar. Selaput kandung kencing di daerah
kandung kencing di daerah trigonum Lieutaudi licin dan melekat pada
dasarnya. Pada daerah kandung kencing dan bagian atas uretra terdapat
muskulus lissosfingter, terdiri atas otot polos, dan berfungsi menutup
jalan urine setempat (Wiknjosastro, 2007).
Uretra panjangnya 3,5-5 cm berjalan dari kandung kencing kedepan
di bawah dan belakang simfisis, dan bermuara di vulva. Pada wanita
yang berbaring arahnya kurang lebih horisontal. Di sepanjang uretra
terdapat muskulus sfingter. Yang terkuat adalah muskulus lissosfingter
dan muskulus rhabdosfingter. Yang terakhir ini adalah bagian dari
diafragma urogenitale (Wiknjosastro, 2007).
5. Rektum
Rektum berjalan melengkung sesuai dengan lengkungan os sakrum,
dari atas ke anus. Antara rektum dan uterus terbentuk ekskavasio
rektouterina, terkenal sebagai kavum Douglasi, yang diliputi oleh
peritoneum viserale. Dalam klinik rongga ini mempunyai arti penting:
rongga ini menonjol jika ada cairan (darah atau asites) atau ada tumor di
daerah tersebut. Dasar rongga tersebut terletak 5-6 cm di atas anus. Anus
ditutup oleh muskulus sfingter ani eksternus, diperkuat oleh muskulus
13
bulbokavernosus, muskulus levator ani, dan jaringan ikat perineum
(Wiknjosastro, 2007).
B. Prolapsus Uteri
1. Definisi
Prolapsus uteri adalah turunnya uterus dari tempat yang biasa oleh
karena kelemahan otot atau fascia yang dalam keadaan normal
menyokongnya (Junizaf, 2007)
2. Etiologi
a. Genetik dan Ras
Pada penelitian (Schaffer, 2005) telah dibuktikan bahwa wanita
berkulit hitam, dan dan wanita Asia menunjukkan risiko terendah
terjadinya prolapsus, sedangkan wanita Hispanik tampaknya
memiliki risiko tertinggi. Meskipun perbedaan dalam komponen
kolagen telah dibuktikan antara ras, namun perbedaan tulang
panggul dalam settiap ras mungkin juga berperan. Misalnya,
perempuan kulit hitam, umumnya arcus pubis < 90 derajat dan
umumnya bentuk panggulnya adalah android atau antropoid. Bentuk
panggul ini mengurangi resiko untuk terjadinya prolapsus uteri
dibandingkan dengan ras barat dimana rata-rata bentuk panggulnya
ginekoid.
b. Usia dan Menopause
Pada wanita yang telah lanjut usia atau usia lebih dari 60 tahun
dan mengalami menopause hal ini menyebabkan karena turunnya
kadar estrogen pada wanita yang telah menopause, kekurangan
14
estrogen ini yang menyebabkan berkurangnya komponen jaringan
ikat elastin yang mengakibatkan elastisitas struktur pada otot dasar
panggul menurun dan menjadi lemah (Baziad, 2008; Moeloek, 2005;
DeLancey, 2003).
c. Tekanan Intraabdomen
Peningkatan tekanan intraabdominal yang berlangssung lama
diyakini mempunyai peranan dalam patogenesis Prolapsus uteri.
Contohnya dalam kasus ini adalah pasien yang sering mengangkat
beban yang berat, batuk kronis dan berulang serta adanya massa
intraabdomen berupa cairan (acites) dan padat (tumor). Selain itu,
penyakit paru obstruktif kronik (PPOK) juga telah terlibat dalam
pengembangan POP (Moeloek, 2005; DeLancey, 2003).
d. Multiparitas
Kelahiran merupakan faktor resiko terbesar karena berperan
langsung terhadap trauma obstetrik yang dialami organ-organ panggul,
kelahiran akan menimbulkan peregangan otot-otot dasar panggul dan
jika terjadi beberapa kali kelahiran makan akan terjadi trauma
berulang yang mengakibatkan kelemahan otot-otot dan ligamentum
dasar panggul yang menyokong uterus (Moeloek, 2005; DeLancey,
2003).
15
3. Patofisiologi
Persalinan per
vaginam
Trauma Obstetri
Usia dan
Menoupose
sering mengangkat beban,
batuk kronis dan berulang,
massa intraabdomen
(tumor, acites) , PPOK
(usia >60 tahun)
Berkurangnya kadar
hormon estrogen
Laserasi
Peregangan otot, fascia, dan
ligamentum dasar panggul
Otot, fascia, dan ligamentum
kehilangan elastisitas dan
kekuatannya
Prolapsus Uteri
Skema 2.1. Patofisiologi Prolapsus Uteri (Smith, 1989; Norton, 1990;
Junizaf, 2007).
4. Gejala
Gejala-gejala prolapsus sangat berbeda dan bersifat individual.
Kadangkala penderita yang satu berbeda dengan yang lainnya dan
prolapsus yang cukup berat dapat tidak mempunyai keluhan apapun,
sebaliknya penderita lain dengan prolapsus yang ringan saja telah
mempunyai banyak keluhan.
Prolapsus uteri dapat menyebabkan gejala sebagai berikut :
a. Miksi sering dan sedikit-sedikit. Mula-mula pada siang hari,
kemudian bila lebih berat juga pada malam hari.
16
b. Perasaan seperti kandung kencing tidak dapat dikosongkan
seluruhnya.
c. Stress incontinence, yaitu tidak dapat menahan kencing jika batuk,
mengejan. Kadang-kadang dapat terjadi retensio urine pada sistokel
besar sekali.
d. Pengeluaran serviks uteri dari vulva mengganggu penderita waktu
berjalan dan bekerja. Gesekan portio uteri oleh celana menimbulkan
lecet sampai luka dan dekubitus pada portio uteri.
e. Leukorea karena kongesti pembuluh darah di daerah serviks dan
karena infeksi serta luka pada portio uteri (Sakala EP, 1997; Erman,
2001; Junizaf, 2002; DeLancey, 2003)
5. Klasifikasi
Di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo/FK UI pembagian
prolapsus uteri sebagai berikut:
1. Prolapsus derajat I, bila serviks uteri belum melewati introitus
vagina tetapi uterus terletak di bawah kedudukan normal,
2. Prolapsus uteri derajat II, bila serviks sudah melewati introitus
vagina,
3. Prolapsus uteri derajat III, bila seluruh uterus sudah melewati
introitus vagina (Junizaf, 2007).
Menurut
International
Continence
Society
Terminology
menggunakan POP Quantification membagi klasifikasi prolapsus sebagai
berikut :
17
Tabel 2.1. Staging Prolapsus Uteri
No prolapse is demonstrated. Points Aa, Ap, Ba, and Bp are all at 3
Stage
cm and either point C or D is between TVL (total vaginal length) cm
andVL2) cm (ie, the quantitation value for point C or D is
[TVL2] cm).
The criteria for stage 0 are not met, but the most distal portion of the
Stage I
Stage
prolapse is > 1 cm above the level of the hymen (ie, its quantitation
value is < 1 cm).
The most distal portion of the prolapse is
1 cm proximal to or
II
distal to the plane of the hymen (ie, its quantitation value is
1 cm but
Stage
+1 cm).
The most distal portion of the prolapse is > 1 cm below the plane of
the hymen but protudes no further than 2 cm less than the total vaginal
III
length in centimeters (ie, its quantitation value is > +1 cm but < +
Stage
IV
[TVL2] cm).
Essentially, complete eversion of the total length of the lower genital
tract is demonstrated. The distal portion of the prolapse protrudes to at
least (TVL2) cm (ie, its quantitation value is
+[TVL2] cm).
In most instances, the leading edge of stage IV prolapse is the cervix
or vaginal cuff scar.
6. Diagnosis
a.
Anamnesis
Gejala yang timbul akan diperberat saat berdiri atau berjalan
dalam waktu lama dan pulih saat berbaring. Pasien merasa lebih
18
nyaman saat pagi hari, dan gejala memberat saat siang hari karena
banyaknya aktifitas (DeLancey, 2003).
b.
Pemeriksaan fisik
Pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan pelvis lengkap, termasuk
pemeriksaan rektovaginal untuk menilai tonus sfingter. Alat yang
digunakan adalah spekulum Sims atau spekulum standar tanpa bilah
anterior. Penemuan fisik dapat lebih diperjelas dengan meminta
pasien meneran atau berdiri dan berjalan sebelum pemeriksaan. Hasil
pemeriksaan fisik pada posisi pasien berdiri dan kandung kemih
kosong dibandingkan dengan posisi supinasi dan kandung kemih
penuh dapat berbeda 1-2 derajat prolaps. Prolaps uteri ringan dapat
dideteksi hanya jika pasien meneran pada pemeriksaan bimanual
(DeLancey, 2003).
Pemeriksaan fisik juga harus dapat menyingkirkan adanya
kondisi serius yang mungkin berhubungan dengan prolaps uteri,
seperti infeksi, strangulasi dengan iskemia uteri, obstruksi saluran
kemih dengan gagal ginjal, dan perdarahan. Jika terdapat obstruksi
saluran kemih, terdapat nyeri suprapubik atau pada pemeriksaan
perkusi kandung kemih berbunyi timpani. Jika terdapat infeksi, dapat
ditemukan discharge serviks purulen (DeLancey, 2003).
7. Komplikasi
Komplikasi yang dapat menyertai prolapsus uteri menurut Junizaf.
2007 adalah:
a. Keratinisasi mukosa vagina dan porsio uteri.
19
Prosidensia uteri disertai dengan
keluarnya dinding vagina
(inversio), karena itu mukosa vagina dan serviks uteri menjadi tebal
serta berkerut dan berwarna keputih-putihan.
b. Dekubitus.
Jika serviks uteri terus ke luar dari vagina maka ujungnya bergeser
dengan paha pada pakaian dalam, sehingga hal ini dapat
menyebabkan luka dan radang yang lambat laun dapat menjadi ulkus
yang disebut ulkus dekubitus. Dalam keadaan demikian perlu
dipikirkan kemungkinan suatu keganasan, lebih-lebih pada penderita
yang berusia lanjut. Pemeriksaan sitologi biopsi perlu dilakuakan
untuk mendapatkan kepastian akan adanya proses keganasan
tersebut.
c. Hipertrofi serviks uteri dan elongasio kolli.
Jika serviks uteri turun ke dalam vagina sedangkan jaringan penahan
dan penyokong uterus masih kuat maka akibat tarikan ke bawah di
bagian uterus yang turun serta karena pembendungan pembuluh
darah, maka serviks uteri mengalami hipertrofi dan menjadi panjang
pula. Hal yang terakhir ini dinamakan elongasio kolli. Hipertrofi
ditentukan dengan pemeriksaan pandang dan perabaan. Pada
elongasio kolli serviks uteri pada perabaan lebih panjang dari
biasanya.
d. Gangguan miksi dan stress inkontinensia.
Pada prolapsus uteri tutunnya uterus dapat mengakibatkan
penyempitan pada ureter sehingga dapat menyebabkan terjadinya
hidroureter dan hidronefrosis.
e. Infeksi saluran kencing.
Adanya retensi air kencing akan mudah menimbulkan infeksi.
Sistitis yang terjadi dapat meluas ke atas dan dapat menyebabkan
pielitis dan pielonefritis yang akhirnya keadaan tersebut dapat
menyebabkan gagal ginjal.
f.Infertilitas..
20
Serviks uteri yang turun sampai dekat pada introitus vagina atau
sama sekali ke luar dari vagina sehingga tidak akan mudah terjadi
kehamilan
g. Kesulitan pada waktu persalinan.
Jika wanita dengan prolapsus uteri hamil maka pada waktu
persalinan dapat menimbulkan kesulitan dikala pembukaaan
sehingga kemajuan persalinan jadi terhalang
8. Penatalaksanaan
Penatalaksanan pada prolapsus uteri bersifat individual, terutama
pada mereka yang telah ditemukan gejala yang menimbulkan keluhan
dan pada pasien prolapsus uteri dengan komplikasi, namun secara umum
penatalaksanan dengan kasus ini terdiri dari dua cara yakni konservatif
dan operatif (Junizaf, 2007; Decherrney, 2007; Schorge, 2008).
a. Pengobatan Konservatif
Pengobatan cara ini tidak seberapa memuaskan tetapi cukup
membantu para penderita dengan prolapsus uteri. Cara ini biasanya
diberikan pada penderita prolapsus ringan tanpa keluhan, pada
penderita yang masih ingin mendapatkan anak lagi, penderita yang
menolak untuk melakukan tindakan operasi dan pada kondisi yang
tidak memungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi (Junizaf,
2007).
Tindakan yang dapat diberikan pada penderita antara lain,
adalah:
1) Latihan-latihan otot dasar panggul.
Latihan ini sangat berguna pada penderita prolapsus uteri
ringan terutama yang terjadi pada penderita pasca persalinan
21
yang belum lewat enam bulan. Tujuannya untuk menguatkan
otot-otot dasar panggul dan otot-otot yang mempengaruhi miksi.
Latihan ini dilakukan selama beberapa bulan. Latihan ini disebut
dengan latian kegel atau lebih dikenal dengan nama senam
kegel. Caranya adalah di mana penderita disuruh menguncupkan
anus dan jaringan dasar panggul seperti biasanya setelah buang
air besar atau penderita disuruh membayangkan seolah-olah
sedang
mengeluarkan
menghentikannya
air
(Decherrney,
kencing
dan
2007;
Moeloek,
tiba-tiba
2005;
DeLancey, 2003).
2) Stimulasi otot-otot dengan alat listrik.
Kontraksi otot-otot dasar panggul dapat pula ditimbulkan
dengan alat listrik, elektrodenya dapat dipasang di dalam
pessarium yang dimasukkan ke dalam liang vagina (Moeloek,
2005; DeLancey, 2003; Junizaf, 2007).
3) Pengobatan dengan pessarium.
Pengoabatan dengan pessarium sebetulnya hanya bersifat
paliatif saja, yakni menahan uterus ditempatnya selama alat
tersebut digunakan. Oleh karena itu jika pessarium diangkat
maka timbul prolapsus kembali. Prinsip pemakaian pessarium
ialah bahwa alat tersebut mengadakan tekanan pada dinding
vagina bagian atas sehingga bagian dari vagina tersebut beserta
uterus tidak dapat turun dan melewati vagina bagian bawah. Jika
pessarium terlalu kecil atau dasar panggulnya terlalu lemah
22
maka pessarium akan jatuh dan prolapsus uteri akan timbul
kembali (Moeloek, 2005; DeLancey, 2003; Junizaf, 2007).
b. Pengobatan Operatif
Prolapsus uteri biasanya disertai dengan adanya prolapsus
vagina, sehingga jika dilakukan pembedahan untuk prolapsus uteri
maka prolapsus vagina perlu ditangani pula secara bersamaan.Ada
kemungkinan terdapat prolapsus vagina yang membutuhkan
pembedahan, padahal tidak ada prolapsus uteri atau prolapsus uteri
yang ada belum perlu dilakukan tindakan operasi. Indikasi untuk
melakukan operasi pada prolapsus vagina ialah jika didapatkan
adanya keluhan pada penderita (Junizaf, 2007).
Indikasi untuk melakukan operasi pada prolapsus uteri
tergantung
dari
beberapa
faktor,
seperti
umur
penderita,
kemungkinannya untuk masih mendapatkan anak lagi atau untuk
mempertahankan uterus, tingkatan prolapsus uteri dan adanya
keluhan yang ditemukan pada penderita (Junizaf, 2007).
C. Paritas
Paritas (para) menurut kamus kedokteran Dorland adalah seorang wanita
yang pernah melahirkan keturunan yang mampu hidup tanpa memandang
apakah anak tesebut hidup pada saat lahir (Dorland, 2002).
Paritas dapat diklasifikasikan menurut jumlahnya, yaitu sebagai berikut:
1. Primipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak, yang cukup
besar untuk hidup didunia luar.
23
2. Multipara adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak lebih dari
satu kali dan kurang dari lima.
3. Grandemultipara adalah wanita yang telah melahirkan 5 anak atau lebih
(Varney, 2006).
D. Hubungan Paritas dengan Prolapsus Uteri
Prolapsus uteri terdapat dalam berbagai tingkatan, dari yang paling
ringan sampai prolapsus uteri totalis. Terutama akibat persalinan, khususnya
persalinan per vaginam yang susah dan terdapatnya kelemahan-kelemahan
ligamentum dan otot yang tergolong dalam fascia endopelvis dan fascia dasar
panggul (Decherrney AH, 2007; Junizaf, 2007).
Proses persalinan pervaginam meneyebabkan peregangan dan robekan
ligamentum dan otot-otot pada dasar panggul. Proses persalinan per vaginam
yang berulang kali (lebih dari empat kali) dan terjadi terlampau sering merupakan
faktor utama dan merupakan penyebab paling signifikan dari terjadinya prolaps
uteri pada wanita. Kelainan prolapsus ini dapat menimbulkan gejala ataupun tanpa
menimbulkan gejala tergantung pada beratnya kelainan itu sendiri, ini juga yang
menjadikan salah satu faktor atas indikasi dilakukannya tindakan operatif pada
kasus prolapsus uteri. Selain faktor tersebut masih terdapat beberapa faktor lain
seperti umur penderita, keinginan untuk masih mendapatkan anak dan atau untuk
mempertahankan uterus (Smith, 1989; Norton, 1990; Junizaf, 2007).
24
E. Kerangka Teori
Genetik dan Ras
Massa intraabdominal, berupa cairan (acites), dan atau padat (tumor)
Usia dan Menopause
Batuk kronis dan berulang
Sering mengangkat
berat
Kejadian Prolapsus U
Tekanan intraabdomen
PPOK
Primipara
Multiparitas
Paritas
Grande Multipara
Skema 2.2. Kerangka Teori Penelitian
F. Kerangka Konsep
Paritas
Prolapsus Uteri
25
Skema 2.3. Kerangka Konsep Penelitian
G. Hipotesis
Terdapat hubungan antara paritas dengan kejadian prolapsus uteri di rumah
sakit Margono Soekarjo Purwokerto Periode Januari - Desember 2011..
26
III. METODE PENELITIAN
A. Rancangan Penelitian
Rancangan
penelitian
ini
menggunakaan
rancangan
analitik
observasional asosiasi dengan pendekatan studi case control untuk
mengetahui hubungan atara variabel bebas berupa paritas dengan variabel
terikat berupa kejadian prolapsus uteri.
B. Populasi dan Sampel Penelitian
1. Populasi
a. Populasi Target
Populasi target pada penelitian ini adalah semua pasien wanita
dengan prolapsus uteri di rumah sakit Margono Soekarjo
Purwokerto.
b. Populasi Terjangkau
Populasi terjangkau pada penelitian ini adalah semua pasien wanita
dengan prolapsus uteri yang dirawat inap di rumah sakit Margono
Soekarjo Purwokerto periode Januari Desember 2011.
c. Populasi Sampel
Populasi sampel pada penelitian ini adalah populasi terjangkau yang
memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.
2. Sampel
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah total sampling,
dengan kelompok kontrol diambil dengan teknik pengambilan simple
random sampling dengan jumlah menyesuaikan jumlah kelompok kasus.
Estimasi besar sampel minimal menurut Lemeshow(1997) yaitu :
27
n1=n2 =
(Z 2 PQ+ Z P 1Q 1+ P2 Q 2)
2
( P 1P 2)
2
n1=n2=
n1=n2=
( 1,96 0,43875+ 0,842 0,3775 )
2
0,35
1,922
0,1225
n1=n2= 30,093
Keterangan :
n = Jumlah minimal sampel penelitian
Z = Standar deviasi normal dengan derajat kemaknaan 95%
(1,96)
Z = Kekuatan penelitian (80%) =0,842
OR = Odd Ratio = 5,667
P2 = Proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada
populasi 50% (0,5)
( ) P2
P1 = ( )
P 2+ ( 1P 2 )
(P 1+P 2)
P=
2
Q =1P
Sampel penelitian yang diambil memenuhi kriteria berikut:
a. Kriteria inklusi untuk kelompok kasus
1) Pernah melahirkan secara per vaginam.
2) Sudah dilakukan tindakan operatif berupa histerektomi
b. Kriteria inklusi kelompok kontrol
1) Pernah melahirkan secara per vaginam.
2) Tidak terdiagnosis prolapsus uteri.
c. Kriteria eksklusi kelompok kasus
28
1) Sampel dengan data sekunder tidak lengkap
2) Tidak memiliki riwayat peningkatan intraabdominal, dilihat dari
pekerjaan, lama bekerja, riwayat batuk kronis berulang, dan ada
tidaknya massa di abdomen berupa cairan (acites) dan padat
(tumor)
3) Berusia lebih dari 60 tahun.
d. Kriteria eksklusi kelompok kontrol
1) Sampel dengan data sekunder tidak lengkap
2) Tidak memiliki riwayat peningkatan intraabdominal, dilihat dari
pekerjaan, lama bekerja, riwayat batuk kronis berulang, dan ada
tidaknya massa di abdomen berupa cairan (acites) dan padat
(tumor)
3) Berusia lebih dari 60 tahun.
C. Variabel Penelitian
1. Variabel Bebas (Independen Variable)
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah paritas
2. Variabel Terikat (Dependen Variable)
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kejadian prolapsus uteri
D. Definisi Operasional Variabel
1. Prolapsus Uteri
adalah turunnya uterus dari tempat yang biasa oleh karena kelemahan otot
atau fascia yang dalam keadaan normal menyokongnya diperoleh dari
data dalam catatan medik
Sumber data
: Data sekunder
29
Skala
: Kategorikal, Nominal
Kategori
: Terjadi prolaps
Tidak terjadi prolaps
2. Paritas
Adalah seorang wanita yang pernah melahirkan keturunan secara per
vaginam yang mampu hidup tanpa memandang apakah anak tesebut
hidup pada saat lahir.
Sumber data
: Data sekunder
Skala
: Kategorikal, Ordinal
Kategori
: Primipara
Multipara
Grande Multipara
E. Prosedur Pengumpulan Data
1. Instrument yang digunakan :
Data sekunder yang didapatkan dari catatan rekam medik selama
kurun waktu satu tahun dan Checklist yang berisi tentang:
a. Nomor register catatan medik.
b. Umur.
c. Jumlah anak.
d. Keluhan.
e. Paritas yang dikategorikan dalam primipara, multipara dan grande
multipara.
f. Kejadian prolapsus uteri yang digolongkan menjadi prolaps dan tidak
prolaps.
30
2. Cara Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder
yaitu dengan melihat catatan medik pasien dalam hal ini ibu yang pernah
melahirkan per vaginam di RSMS dengan di diagnosis prolapsus uteri
sebagai kelompok kasus dan yang tidak terjadi prolapsus uteri sebagai
kelompok kontrol. Adapun cara pengambilan data dalam penelitian ini
adalah :
a. Peneliti mengajukan ijin pada direktur rumah sakit Margono Soekarjo
Purwokerto.
b. Setelah mendapat ijin, peneliti mengamati catatan medik pasien untuk
mendapat data yang diperlukan.
c. Dari populasi yang didapatkan selama satu tahun, diambil secara
keseluruhan untuk digunakan sebagai sampel penelitian.
d. Sampel yang memenuhi kriteria inklusi dipilih dan dilakukan
pencatatan data dengan mengisi lembar checklist sesuai dengan data
yang dibutuhkan berdasarkan catatan medik pasien.
F. Analisa Data
Analisis data pada penelitian ini meliputi analisis univariat dan
analisis bivariat. Analisis data menggunakan program SPSS (Statistical
Package for the Social Sains). Analisis univariat digunakan untuk
mendiskripsikan tiap variabel dan hasil penelitian, kemudian dihitung
frekuensi dan presentasenya. Analisis bivariat digunakan untuk
menyatakan hubungan analisis terhadap dua variabel yakni hubungan
antara kejadian prolapsus uteri dengan paritas, analisis bivariat
31
menggunakan uji Chi-Square jika uji Chi-Square tidak memenuhi syarat
maka digunakan uji Kolmogorov-Smirnov sebagai uji alternatif.
G. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian atau pengambilan data sampel akan dilakukan selama satu bulan
yaitu pada bulan Juni 2012. Penelitian dilakukan di Bagian Rekam Medik/
Catatan Medik RS Margono Soekarjo Purwokerto.
Anda mungkin juga menyukai
- Pemeriksaan GinekologiDokumen19 halamanPemeriksaan GinekologiSuhayatra Putra100% (1)
- Pembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisDari EverandPembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (13)
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanDari EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Kortikosteroid Pada Penyakit KulitDokumen25 halamanKortikosteroid Pada Penyakit KulitnerdwaldoBelum ada peringkat
- Prolaps Uterus, Sistokel, RektokelDokumen39 halamanProlaps Uterus, Sistokel, RektokelmelindaBelum ada peringkat
- Referat Prolaps UteriDokumen21 halamanReferat Prolaps UteriSilvi Qiro'atul AiniBelum ada peringkat
- Referat Retensi Urin PostpartumDokumen31 halamanReferat Retensi Urin PostpartumErick Rangga JuniorBelum ada peringkat
- Retensi UrinDokumen19 halamanRetensi UrinRizna Said100% (2)
- PrurigoDokumen17 halamanPrurigonerdwaldoBelum ada peringkat
- Referat Prolapsus UteriDokumen37 halamanReferat Prolapsus UteriEva Indreswari Tandisalla100% (1)
- Referat Inkontinensia Urin WD Siti Zurrahmah-K1B121037Dokumen48 halamanReferat Inkontinensia Urin WD Siti Zurrahmah-K1B121037qashri ulyaBelum ada peringkat
- Makalah UroginekologiDokumen17 halamanMakalah UroginekologiEtik Yuliarini WidodoBelum ada peringkat
- Prolaps Organ PanggulDokumen28 halamanProlaps Organ PanggulWahyudi WirawanBelum ada peringkat
- Anatomi Dasar Panggul NewDokumen19 halamanAnatomi Dasar Panggul NewgeraldersBelum ada peringkat
- Referat Prolapsus UteriDokumen23 halamanReferat Prolapsus UteriFahreza Fajar MuharamBelum ada peringkat
- FishboneDokumen41 halamanFishbonenerdwaldoBelum ada peringkat
- Tumor FiloidesDokumen31 halamanTumor FiloidesnerdwaldoBelum ada peringkat
- Konse Teori Prolaps UteriDokumen15 halamanKonse Teori Prolaps UterisitiR nurpiyahBelum ada peringkat
- Mutiara Dumalangga S - 132023143065 - LP Prolaps UteriDokumen14 halamanMutiara Dumalangga S - 132023143065 - LP Prolaps Uterimutiara dumalangga0% (1)
- Laporan Pendahuluan Prolaps UteriDokumen22 halamanLaporan Pendahuluan Prolaps UteriSILVIA SAISELARBelum ada peringkat
- Laporan Kasus ObginDokumen28 halamanLaporan Kasus ObginLim RidaBelum ada peringkat
- Prolaps Uteri - 1Dokumen46 halamanProlaps Uteri - 1wira agieBelum ada peringkat
- PDF Referat Prolapsus UteriDokumen38 halamanPDF Referat Prolapsus UteriAnthy EreguaBelum ada peringkat
- Prolapsus UteriDokumen37 halamanProlapsus UteriAmarendra WardhanaBelum ada peringkat
- Prolapsus GenitaliaDokumen38 halamanProlapsus GenitaliaGustiAngriAngalanBelum ada peringkat
- LP Prolaps UteriDokumen13 halamanLP Prolaps UteriAstrideBelum ada peringkat
- Referat Prolaps UteriDokumen18 halamanReferat Prolaps Uteriainil mardiahBelum ada peringkat
- Prolapsus UteriDokumen39 halamanProlapsus UterirezkadehaBelum ada peringkat
- BAIQ CIPTA HARDIANTI 22010111140197 Lap - KTI Bab2 PDFDokumen23 halamanBAIQ CIPTA HARDIANTI 22010111140197 Lap - KTI Bab2 PDFfauziahandnBelum ada peringkat
- BAB II Prolapsus UteriDokumen36 halamanBAB II Prolapsus UteriRazaa HoeddinBelum ada peringkat
- Saluran Keluar Vagina Prolapsus UteriDokumen21 halamanSaluran Keluar Vagina Prolapsus UteriNur Hikmah HarmitaBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan: Cephalopelvic Disproportion (CPD)Dokumen23 halamanLaporan Pendahuluan Asuhan Keperawatan Pada Klien Dengan: Cephalopelvic Disproportion (CPD)Lia BarkaturBelum ada peringkat
- Referat Prolapsus UteriDokumen36 halamanReferat Prolapsus UteriAgung ArifiantoBelum ada peringkat
- Prolaps UteriDokumen18 halamanProlaps Uterikusuma santhiBelum ada peringkat
- Anorektal EmbrioDokumen32 halamanAnorektal EmbriokinausmanBelum ada peringkat
- Prolaps Organ PangulDokumen24 halamanProlaps Organ PangulAdhy PallyBelum ada peringkat
- Malformasi AnorekalDokumen20 halamanMalformasi AnorekalOdiet RevenderBelum ada peringkat
- LaporanDokumen30 halamanLaporanOtong hBelum ada peringkat
- Rectokel 1Dokumen15 halamanRectokel 1lia indri fadilaBelum ada peringkat
- Refka1 ObgynDokumen33 halamanRefka1 ObgynMirna auliaBelum ada peringkat
- LAPORAN PENDAHULUAN HillDokumen19 halamanLAPORAN PENDAHULUAN Hillindah khalizahBelum ada peringkat
- Teknik Pemeriksaan Radiografi Pelvis DasDokumen12 halamanTeknik Pemeriksaan Radiografi Pelvis DasRatna Aulia RahmawatiBelum ada peringkat
- Sesar KikiDokumen18 halamanSesar KikiKIKIBelum ada peringkat
- Mekanisme Dan Pengendalian BerkemihDokumen18 halamanMekanisme Dan Pengendalian BerkemihChompz MuMu PhantarsBelum ada peringkat
- MAKALAH SC LikeDokumen35 halamanMAKALAH SC LikeIraratu DariyesBelum ada peringkat
- Skenario 1 Reproduksi & Tumbuh KembangDokumen45 halamanSkenario 1 Reproduksi & Tumbuh KembangPutri NurfadhilahBelum ada peringkat
- LP Dika Post SCDokumen18 halamanLP Dika Post SCNur azizahBelum ada peringkat
- PDokumen44 halamanPAmee Vixa0% (1)
- Prolapsus UteriDokumen28 halamanProlapsus Uteriditha arisqaBelum ada peringkat
- LP Hernia Inguinalis FixDokumen17 halamanLP Hernia Inguinalis Fixindah khalizahBelum ada peringkat
- Prolaps UteriDokumen23 halamanProlaps UterinurhayatinufussBelum ada peringkat
- Prolaps UterusDokumen53 halamanProlaps Uterusngurah warsitaBelum ada peringkat
- LP CPD MaternitasDokumen21 halamanLP CPD MaternitasNorma LindaBelum ada peringkat
- Widit Lupita Sari Bab Ii PDFDokumen34 halamanWidit Lupita Sari Bab Ii PDFHendra KusumaBelum ada peringkat
- Cacervix, Prolaps UteriDokumen77 halamanCacervix, Prolaps UteriemmyBelum ada peringkat
- Syaifulazim / Prolapsus UteriDokumen21 halamanSyaifulazim / Prolapsus UteriSyaiful AzimBelum ada peringkat
- Diktat UrogenitaliaDokumen37 halamanDiktat UrogenitaliaSyukri La Ranti100% (3)
- Resume Prolaps Uteri Lopis Cristian Renyaan Nim 17 04 041Dokumen70 halamanResume Prolaps Uteri Lopis Cristian Renyaan Nim 17 04 041Lopis Cristian RenyaanBelum ada peringkat
- Latar BelakangDokumen11 halamanLatar BelakangHusnaini Hawari II100% (1)
- Sel Elektrokimia Merupakan Suatu Sistem Yang Terdiri Atas Dua ElektrodeDokumen9 halamanSel Elektrokimia Merupakan Suatu Sistem Yang Terdiri Atas Dua ElektrodenerdwaldoBelum ada peringkat
- NeurodermatitisDokumen24 halamanNeurodermatitisnerdwaldoBelum ada peringkat
- Sistem Dan Bentuk PemerintahanDokumen30 halamanSistem Dan Bentuk PemerintahannerdwaldoBelum ada peringkat
- Presus 1Dokumen39 halamanPresus 1AnnisaFildzaHashfiBelum ada peringkat
- Antihistamin Pada Penyakit KulitDokumen20 halamanAntihistamin Pada Penyakit KulitnerdwaldoBelum ada peringkat
- Penyakit Kulit MikosisDokumen22 halamanPenyakit Kulit MikosisnerdwaldoBelum ada peringkat
- Insect BiteDokumen6 halamanInsect BitenerdwaldoBelum ada peringkat
- Pemeriksaan BakteriDokumen24 halamanPemeriksaan BakterinerdwaldoBelum ada peringkat
- GerintologiDokumen26 halamanGerintologinerdwaldoBelum ada peringkat