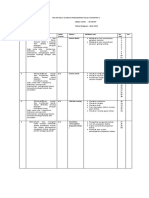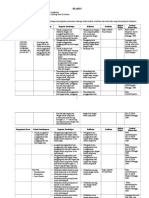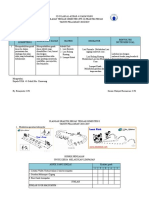Ekspedisi Lintas Kalimantan
Diunggah oleh
Sabana RinjaniHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Ekspedisi Lintas Kalimantan
Diunggah oleh
Sabana RinjaniHak Cipta:
Format Tersedia
Ekspedisi Lintas Kalimantan: Menyapa Arus, Mencumbu Riam (2)
Posted by Tajid Yakub on July 18th, 2006 retweet Perahu tenggelam, untung di pinggir sungai. Irang yang bermesin 8 PK mencoba kembali. Mesin meraung dan mengeluarkan suara keras, perahu tergoncang dahsyat. Riam Bakang masih terlalu kuat. Irang mengalah dan tak mau mengambil resiko seperti Sawang. Perahu dipinggirkan dan tak diteruskan menantang riam. Seluruh perahu akhirnya diseret dan didorong melewati batu di pinggir sungai. Semua orang bekerja keras, melewatkan perahu-perahu satu demi satu. Di tengah riuh deram air dan keras teriakan manusia, perahu-perahu panjang berhasil diseret dan mulai mengumandang suara motornya. Perahu terus menerobos riam. Awak sampan terus bekerja keras, menyeret dan mendorong perahu bila sungai berdasar dangkal. Riam Hororoy terlewati di tengah-tengah hujan lebat. Mesin-mesin motor beberapa kali terhenti, tetapi motoris-motoris sudah siap memperbaiki dan lengkap pula membawa peralatan. Menjelang sore, akhirnya Tanjunglokang di depan mata. Satu keluarga kulit putih, pendeta asal Amerika, mentjemput rombongan dengan suka cita. Orang-orang Dayak Suku Punan berjajar di pinggir sungai, siap membantu dalam lintasan berikut menerobos Pegunungan Muller. Petualang-petualang Amerika ini pun heran, sebab orang-orang Dayak ternyata tak memakai cawat kulit kayu. Menuju Hulu Kapuas Perjalanan nanti tergantung pada cuaca, jadi tak bisa diperkirakan berapa hari bisa sampai di Longapari, ujar Dalung, temenggung (kepala adat) Tanjunglokang Dalung, orang Dayak suku Punan, pemimpin 34 pengangkut barang ekspedisi, telah berulang kali melintasi hutan lebat yang membatasi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Biasa kami orang jalan tiga hari saja, tapi entah berapa hari kalau dengan barang berat-berat begini, kata Dalung memperhatikan perlengkapan ekspedisi. Dalung berbadan kekar, penuh dihiasi tato di tangan dan lehernya. Dengan mandau tergantung di pinggang, Dalung menimbulkan kesan ganas. Tapi Dalung baik sekali dan dihormati, sudah memimpin orang-orang Punan sejak tahun 1950-an. Bersama Singka, kepala kampung Tanjunglokang, Dalung berangkat menembos rimba memimpin pengangkut barang Suku Punan dan beberapa suku lain seperti Bukat, Penihing, dan seorang Cina. Ditambah James Bove, anak pendeta kebangsaan Amerika, yang sudah enam tahun tinggal bersama orang-orang Punan. Mudah-mudahan hujan tak mengganggu, sebab jalan kita menyusuri sungai. Berbahaya kalau banjir, ujar Dalung. Delapan perahu panjang sarat barang dan manusia, menentang Sungai Bungan lagi. Muya, Gilang, Selawi, Jahun, Iwung, Tolunya, Owang, dan Sayid tegak di buritan, memegang
tangkai mesin-mesin motor pendorong perahu. Mereka sigap mengamati riak sungai di depan, dibantu petunjuk arah awak perahu di moncong perahu. Riam di sini jahat, tapi kami sudah hapal betul sungai ini, ujar Tolunya. Sungai makin sempit, batu-batu besar mencuat di mana-mana, tetapi perahu-perahu ramping gesit sekali menyelusup. Raungan motor perahu, mengusik ketenangan hutan lebat, menggemakan suara di celah-celah perbukitan di jajaran Pegunungan Muller. Di depan Riam Kotohocap, jahat sekali, kata Gilang memberi peringatan. Suara terdengar menggemuruh, air menggelinding di atas batu dan berbuih. Cepat sekali orang-orang Punan itu melompat dan hinggap di batu, lalu menarik dan mendorong perahu melewati riam. James Bove tiba-tiba terpelanting dan tercebur di air deras, untung cepat tangannya menyambar pohon mencuat di tengah riam. Pucat sekali mukanya. Makan siang di biuara Sungai Bulit, nikmat rasanya melahap ikan besar tangkapan orangorang Dayak pengangkut barang. Di bagian hulu sungai ini, dahulu orang-orang Punan bertempat tinggal. Pohon buah-buahan yang kini ada di sana, sisa tanaman yang masih sering diambil. Sayang sekarang bukan musim berbuah, kalau tidak pasti kenyang kita makan durian, kata Dalung si kepala adat. Motor terus mendengungkan suara berisik, perahu-perahu panjang melesat terus membelah sungai, memotong riam dan menyelusup di antara batu. Orang-orang Dayak itu terus berteriak penuh semangat, seperti sedang berangkat perang saja layaknya. Sekarang lintasan memudiki Sungai Bulit. Tampak bukit batu bertebing curam di kiri dan kanan. Itu Diang (bukit) Balu dan itu Diang Peang, War Muya menunjuk-nunjuk Di depan lagi, menjulang tebing batu setinggi tak kurang seratus limapuluh meter. Bukit Bowok, di sinilah orang-orang Punan dahulu meletakkan saudara-saudaranya yang mati dalam lungun (peti mati). Malam hampir menjelang, rombongan mendarat dan membuka kemah di Nanga Taran. Perahu-perahu diangkat ke darat dan mesin-mesin disembunyikan, sebab dari sini perjalanan mesti dilanjutkan dengan berjalan kaki saja. Orang-orang Dayak cepat sekali menebang pohon dan memotong dedaunan, lalu membangun pondok sederhana tempat berteduh dan tidur. Hebat, belum lagi selesai kita membangun tenda, mereka sudah selesai dengan pondoknya, komentar John Long mengagumi. Menerobos Pegunungan Muller Dalung berjalan di depan dengan mandau terhunus, menerobos hutan pekat di jajaran Pegunungan Muller. Mulutnya terus mengunyah sirih, sebentar-sebentar meludahkan cairan merah, meninggalkan bekas di sepanjang lintasan. Di punggungnya menggantung kewo (ransel dari rotan) sarat muatan. Kaki terus melangkah, memudiki anak-anak sungai yang turun ke Sungai Bulit. Napas mulai tersengal menahan beban di punggung, tapi hati bersemangat betul hendak melintas dan menuju belahan pulau di sebelah timur. Tiba di punggung bukit, lintasan lantas menurun mengikuti anak sungai yang mengalir ke Sungai Bungan. Dua batu besar teronggok di tengah aliran sungai kecil, orang-orang Dayak pengangkut barang sama-sama berhenti dan mengeluarkan mandau dari sarungnya. Sebentar kami mengasah mandau. Ini kebiasaan sejak nenek moyang dulu, ujar Singka.
Di depan terbentang Sungai Bungan. Airnya mengalir deras sekali, meliuk-liuk di antara batu-batu besar. Di dasarnya, berserakan batu-batu besar dan kecil. Rombongan kini menyeberangi sungai menuju dataran di sebelah. Tangan mencekal tongkat kayu, penopang badan agar tak terseret arus deras. Untung sungai tak dilanda banjir, kalau tidak wah mungkin kita harus menunggu sampai surut, kata Ajung, orang Dayak berbadan kekar dan indah bak binaragawan. Peruntungan bukan cuma hari itu, sebab banjir tak sempat melanda sungai sepanjang perjalanan melintasi Pegunungan Muller, kendati hujan sempat turun beberapa kali. Tak ada jalan setapak di lintasan ini, hanya aliran sungai menjadi petunjuk arah. Kalau sungai terlalu dalam, maka lintasan agak melambung di tebing di pinggir-pinggir sungai, melipir di tanah gembur dan becek Bergantian, tubuh-tubuh pejalan kaki ini terpelanting jauh lantaran licinnya lintasan. Terdengar keras suara tembakan. Muya menghamburkan peluru milik polisi pengawal rombongan, menembak rusa di seberang sungai. Peluru menghantam perut hewan malang ini, tapi tak sempat membunuhnya seketika. Muya tak jadi makan daging rusa, sebab binatang ini menghilang. Suara ribut pagi-pagi sekali mengagetkan dan membangunkan tidur. Johny, si orangutan menghilang. Dia kembali ke asalnya di hutan belantara, tetapi masih mampukah ia hidup di lingkungan seperti ini? Kini rombongan meninggalkan Sungai Bungan, memudiki Sungai Bocai. Sungai Bungan bersejarah bagi kami, di bagian hulu sana lima orang Belanda pernah dipenggal kepalanya, cerita Dalung. Saya ikut memenggal kepala mereka, sebab tak sempurna orang mati kalau tak dipisahkan kepalanya, ujar Dalung tenang. Tapi itu dulu, waktu saya masih kecil. Sekarang tak ada lagi pengayauan. Lepas Sungai Bocai, lintasan lantas mengarah ke punggung-punggung bukit. Tanjakantanjakan terjal menghadang di depan, napas seperti mau putus menahan berat. Punggung terasa basah, keringat mengalir terus-terusan. Bukit Tipong memang tinggi, tapi lewat dari sini kita sampai di perbatasan Kalimantan Timur, ujar Muya terengah-engah. Hampir tiba di puncak bukit, terlihat lagi aliran kecil Sungai Bocai. Makin ke atas, kecil-kecil saja aliran sungai. Di atas itu Sungai Bocai yang mengalir ke barat bermula, mengalirkan airnya ke Sungai Bungan, lalu bertemu dengan aliran besar Sungai Kapuas. Kaki terus melangkah ke atas, meninggalkan pangkal Sungai Bocai, mengarah ke hulu Sungai Hubung yang menumpahkan airnya ke Sungai Mahakam di sebelah timur. Kedua pangkal surgai yang mengalirkan air ke kedua sungai besar di Kalimantan ini, ternyata cuma berpisah sepuluh meter saja Kini menyusuri Sungai Hubung, menuju ke timur. Untung tak banyak batu di dasar sungai, hingga mempermudah langkah kaki dan melonggarkan napas sedikit. Hati makin bersemangat, kendati kondisi badan makin melorot turun. Dari Sungai Hubung, jalan mendaki menerobos bukit kecil, turun di Sungai Aramete dan akhirnya tembus sudah ke Longapari, kampung paling ujung di Sungai Mahakam. Seminggu lebih berjalan menerobos pegunungan dan menyusuri sungai, kini terasa singkat saja.
John Long bersama gadis Bukat, dekat Putussibau (Norman Edwin) Membelah Sungai Mahakam Kondisi air cukup baik, mari kita berangkat, ujar Dabung, motoris terkenal di Sungai Mahakam. Tiga buah perahu panjang berangka kokoh, lengkap dengan mesin 40 PK, menghiliri sungai berair deras penuh riam Sungai Mahakam lebar sekali, riamnya besar dan berbahaya Di riam tadi, tahun lalu seorang Prancis tenggelam dan mati, cerita Dabung, lepas Kiham (riam) Toham. Anyet, Miang, dan Luhat tangkas sekali mengemudikan perahu motor. Dabung tenang duduk di moncong perahu terdepan, cermat mengamati riak permukaan sungai, sebentar-sebentar mengangkat tangan menunjuk Iintasan sungai yang aman dilewati. Dialah motoris pertama di Sungai Mahakam sejak tahun 1955, berpengalaman banyak dan tahu betul menjinakkan riam. Lewat Kampung Longpahangai, menghadang jajaran riam bergelombang besar. Ini Kiham Napohidah, sebagian orang jalan kaki saja, kata Dabung meminggirkan perahu. Tiga perahu cepat sekali menyelinap dan menerobos air memutih, masuk ke lidah air menghindar batubatu besar di kiri dan kanan. Suara motor tak lagi terdengar, hilang ditelan suara gemuruh air. Perahu terus bergoncang keras melewati jajaran riam.
Di depan Kiham Kaneheng, coba tebak ada apa di depan, teriak Dabung bersemangat. Gemuruh air makin keras terdengar, kabut tipis muncul dari balik tebing batu di sebelah kanan, air terjun! Ah, tak rugi berpayah-payah datang ke sini. Tiga perahu membelok masuk ke Sungai Boh, disambut Riam Burung. Motor, meraung, perahu tak laju-laju ditahan derasnya air. Riam Huluk kiai menghadang, terpaksa beberapa penumpang mesti turun dan berjalankan menghindar. Seperti berdemonstrasi, tiga perahu bermotor besar memilih lintasan masing-masing, diselingi teriakan nyaring pengemudinya.
Dayung dan tolak galah di Sungai Benaan (Norman Edwin) Awan hitam membayang di depan, ketika perahu bersiap menghadapi Riam Batu Belah. Cepat sedikit membuat foto, kalau hujan tak bisa kita lewat di riam ini, teriak Dabung menunjuk langit. Hujan tak jadi membuat banjir Sungai Boh, perahu-perahu lancar saja menuju Muara Sungai Benaan. Sebuah rumah mungil di tanah miring, berdiri di atas tiang di tengah belantara Muara Sungai Benaan. Suara mesin motor ces (perahu kecil bermotor) terdengar lamat-lamat dari arah hulu Sungai Boh. Hurang Hang, orang Dayak Bahau asal Longbagun, baru kembali mendulang emas. Bersama istri dan seorang anaknya, Hurang sudah dua tahun berdiam di tempat sepi ini. Mata pencahariannya adalah menampung rotan yang dikumpulkan orang-orang di pedalaman, lalu dijualnya di Longbagun. Mendulang emas cuma sambilan, ujarnya sambil memperlihatkan bubuk emas yang baru diperolehnya hari itu. Mesin ditinggalkan di Muara Sungai Benaan, kini perahu cuma didayung, ditarik, dan didorong galah panjang. Sungai terlalu dangkal, bisa hancur mesin menghantam batu, ujar Dabung menjelaskan. Semangat sekali orang-orang Dayak Bahau melajukan perahu, menentang arus dan riam Sungai Benaan. Teriakan-teriakan melengking seperti menambah kekuatan buat menarik atau mendorong perahu. Menjelang sore rombongan tiba di Kubu Tanyit, tempat menambat perahu sebelum berjalan kaki menuju Mahak. Memudiki Sungai Tanyit, kaki sekarang melangkah lebar mendekati bukit. Lagi-lagi napas tersengal menahan beban barang dan bobot badan, melancarkan peluh mengalir dari seluruh badan.
Rick Ridgeway tampak limbung dan berjalan perlahan sekali. Saya tak enak badan, kata Ridgeway menyeka keringat. Malam datang, rombongan hampir terpecah-pecah dan cuma menemukan sedikit air. Badan penat sekali, tak peduli lagi dengan keadaan dan lelap tidur di hammock antara dua pohon.
Frank Morgan, John Long, Jim Slade, dan Jim Bridwell berdayung di Sungai Kayan (Norman Edwin). Esok hari lintasan masih turun dan naik saja, melewati anak-anak bungai dan melipir lerenglereng terjal. Ridgeway makin mengkhawatirkan, sakitnya parah dan tak kuat lagi berjalan kaki. Ranselnya kini beralih ke punggung seorang Dayak Kenyah yang berjumpa di hutan. Setapak demi setapak Ridgeway merambat jalan, ditemani si besar tinggi John Long. Hari sudah malam, ketika Ridgeway melangkahkan kaki masuk ke rumah panjang di Kampung Mahak Baru, permukiman orang Dayak Kenyah. Untung di sini ada pesawat perintis. Ridgeway cepat diterbangkan ke Tarakan untuk dirawat. Rick Ridgeway kena penyakit tipus, menyebabkan anggota ekspedisi berkurang lagi setelah Johny si orangutan. Karam di Sungai Boh. Pesawat kecil berbaling-baling satu terbang semakin rendah, lalu rodanya menyentuh tanah. Suara mesin terdengar keras, hembusan angin baling-balingnya menerbangkan debu-debu di lapangan bertanah merah. Pesawat terbang milik MAF (Mission Aviation Fellowship = Persekutuan Penerbangan Missi Gerejani) itu baru saja mendarat di Longnawang di hulu Sungai Kayan, Kalimantan Timur. Belasan orang menghambur mendekati pesawat, memandang dengan heran para penumpang beserta perlengkapannya. Anda anggota Ekspedisi Lintas Kalimantan? sapa Liet Ingai, Camat Kayan Hulu. Lintasan ekspedisi sudah lebih dari separuh. Tetapi Ridgeway tak lagi bisa mengikuti sisa perjalanan. Dia tengah meringkuk di rumah sakit di Samarinda karena kena tipus. Rick masih beruntung, sebab kalau terlambat diselamatkan mungkin dia sudah mati, ujar Perry, pilot MAF yang menerbangkan Ridgeway dari Mahak Dokter menduga dia terkena pula malaria, sambungnya. Tapi kepastiannya nanti di laboratorium.
Musibah tak cuma sampai di situ. Sebuah perahu karam waktu melintasi riam, lalu hancur menumbuk batu di Sungai Boh. Keadaan semakin memburuk, hingga akhirnya seluruh rombongan kembali ke Mahak, mengatur rencana lagi. Waktu semakin susut, kesehatan sebagian anggota ekspedisi menurun, menyebabkan diambil keputusan di luar rencana semula. Jim Slade dan Stan Boor, dipandu enam orang Kenyah pilihan, kembali menjelajah Sungai Boh, arah ke hulu, sementara yang lain diterbangkan dengan pesawat ke Longnawang. Jarak lima hari lewat sungai dan darat, diringkas menjadi cuma dua puluh menit dengan pesawat kecil berbaling. baling satu. Ini tak menyenangkan, tapi tak ada cara yang lebih baik dalam situasi sekarang, ucap Peter Pilafian menghibur. Riam Berkabut Tak usah ikut-ikutan mereka, riam-riam di sini jahat sekali, kata Jalung Kajan, Kepala Kampung Longnawang. Dia khawatir betul dengan rencana ekspedisi menuruni Sungai Kayan dengan perahu karet, tak bermesin pula. Kalian tak bakal selamat melewati Riam Afun, ujarnya lagi menakut-nakuti. Di seluruh Kalimantan, cuma riam ini yang belum terlewati. Dari seluruh aliran Sungai Kayan, jajaran riam yang dimulai di Giram (riam) Afun tak pernah dilewati manusia. Riam di situ besar sekali dan menimbulkan kabut saking derasnya, ucap Liet Ingai sambil mencoret-coret kertas putih, menggambarkan bentuk riam. Orang Kenyah menamakannya Afun, artinya awan atau kabut. Tapi kami lebih sering menyebutnya Riam Ampun, kalian akan mengerti kenapa. Di peta dan beberapa kepustakaan, riam itu tercatat dengan nama Kiham (riam) Biawon. Kehebatan dan keangkeran Riam Afun sudah terdengar sejak di Sungai Mahakam. Tahun 1975 seorang motoris dari Mahakam pernah mencoba kehebatan riam ini. Dengan perahu karet bermesin 40 PK, motoris yang sedang mengikuti survai geologi Prancis ini gagah sekali mendekat Riam Afun dari sebelah hilir. Riam Afun masih jauh di hulu, tapi motoris ini sudah kehilangan akal dan minta ampun menghadapi riam-riam di bawahnya, lalu mengurungkan niatnya melewati Riam Afun. Dia segera memutar moncong perahunya ke hilir, memacu kembali ke bawah. Di sini malapetakanya, perahunya dihantam gelombang besar dan terbalik di riam-riam. Nasib masih belum buruk buat motoris ini, perahu kembali tegak didorong riak riam besar. Lain pula pengalaman enam orang Kenyah. Dengan perahu besar bermotor ganda, mereka mencoba menuruni riam berkabut itu. Perahu besar itu tak berdaya dipermainkan riam besar bergelombang tinggi, lalu dilontar dan hancur menghantam batu besar dan tebing curam di kiri dan kanan sungai. Enam orang Kenyah yang perkasa itu tak pernah ditemukan lagi. Nasib yang sama, dialami oleh orang-orang Than dari Serawak, sekitar tahun 40-an. Mereka tak mengenal Sungai Kayan, tapi nekad mendayung melewati riam-riam di situ. Setiba di Riam Afun, arus deras menyeret perahu dan seluruh orang Than itu ditelan gelombang besar, tak pernah ditemukan lagi. Saya sendiri pernah melihat rombongan babi menyeberang sungai, lalu terseret dan hilang di riam itu, ujar Liet Ingai melengkapi cerita seram.
Jim Slade, andalan ekspedisi menyusuri sungai ini, termangu mendengar cerita tak menyenangkan perihal riam-riam di Sungai Kayan. Saya ingin mencoba riam-riam itu, tapi tak ada salahnya kalau dilakukan survai udara dahulu. ujarnya. Dengan pesawat MAF, jago menyusuri sungai beraliran deras dari Amerika ini menghabiskan waktu beberapa jam untuk mempelajari riam-riam di bagian hulu. Agaknya, beberapa riam memang tak mungkin dilalui, ujarnya selesai pengamatan. Penyusuran Sungai Kayan akhirnya tak jadi dilakukan dengan mendayung, padahal tiga perahu karet sudah nongkrong di Longnawang. Kita sudah kehilangan banyak waktu, jadi tak sempat lagi kalau harus berdayung, jelas John Long. Terlebih lagi, Frank Morgan yang bergabung di Longnawang, cuma punya waktu seminggu dan harus segera kembali ke Jakarta. Saya senang sekali kalau bisa mendayung, tapi Frank mesti cepat-cepat kembali, kata Jim Slade. Frank MorDan, warga negara Amerika Serikat yang sudah 12 tahun tinggal di Jakarta, berandil besar merancang dan melancarkan ekspedisi ini. Frank banyak sekali menolong, jadi kami harus membantunya sekarang, ujar Jim Slade seperti menyesali. Dengan perahu besar bermotor ganda, penjelajahan Sungai Kayan menjadi cepat. Ding Njuk, dibantu adiknya, kompak sekali menjalankan motor-motor penggerak perahu, melewati riamriam besar dan menghindari batu-batu sepanjang sungai. Di kiri dan kanan tampak pohonpohon berdaun merah seperti memayungi pinggiran sungai. Itu pohon lacan, ikan-ikan senang makan buahnya, kata Ding Njuk. Rupanya ada rombongan lain yang sedang menyusuri sungai. Empat ratus orang Suku Bakung dari Kampung Metun, tengah bergerak pindah menuju kawasan pantai timur Kalimantan. Satu kecenderungan di Apo Kayan (dataran tinggi Kayan) sejak lama. Di pedalaman, kebutuhan hidup sulit sekali dipenuhi, cerita Gung Ajang, Kepala Kampung Metun. Bayangkan, sering kami tak makan garam dan gula di sana, belum lagi tembakau. Kampung Metun lenyap sudah ditinggalkan penghuninya, seperti kampung-kampung lain di banyak tempat di Apo Kayan. Akhir Ekspedisi Perahu karet masih sempat didayung, meskipun cuma sekedar untuk bersenang-senang. Hempasan riam mengayun perahu karet, terasa mengasyikkan dan selalu diiringi tawa riang. Tetapi belum lagi sampai di Giram Afun, riam besar sudah menghadang, seperti memperingatkan ada bahaya besar menanti. Ini Riam Teku, kami tak berani melewatinya, ujar Ding Njuk. Riam ini sama jahatnya dengan Riam Afun, tapi tak panjang seperti di sana. Perahu kayu bermotor ganda dipinggirkan, penumpangnya berjalan kaki mengitari riam besar itu. Tangan mengayuh dayung, perahu meluncur pelan dimainkan riam kecil. Dinding-dinding terjal mengapit sungai membentuk lembah yang dalam sekali di kawasan itu. Di atas dinding batu yang tinggi, tampak dinding menggantung besar sekali. Lubang-lubang menganga di atas dinding batu, menimbulkan kesan seram, tapi juga mengagumkan. Daerah ini seperti di Colorado, komentar Stan Boor, Yah, Colorado di tengah hutan belantara, sambut Jim Bridwell.
Tiba-tiba terdengar keras suara gemuruh air. Di depan, air tenang sekali, tak ada tanda ada riam. Hampir di kelokan, arus air tiba-tiba terasa sangat deras dan kelihatan air memutih di depan sana. Kabut tipis mengaburi riak air yang memutih itu. Riam Afun!! Serentak tangan mengayun dayung, menghindar agar tak terseret perahu karet kecil ini dan terjebak di riam berbahaya. Jim Slade berdiri memandang jajaran riam yang berkabut itu. Suara gemuruh bukan main kerasnya, membuat tenggorokan mengencang, karena mesti berteriak-teriak kalau berbicara. Sungai Kayan tampak ganas sekali. Airnya memutih dan mengalir deras, membentuk gelombang-gelombang besar dan lekukan-lekukan dalam yang mengerikan. Kelokan-kelokan tajam membuat air deras menghantam dinding batu tepian sungai, membalikkan gelombang besar ke belakang. Hempasan air yang menggulir di batu-batu besar, mengacaukan sgluruh permukaan sungai. Jim Slade cuma mengangkat bahu, Riam ini tak mungkin dilewati, ujarnya Dari seluruh sungai hampir di seluruh dunia yang pernah saya arungi, cuma riam ini yang paling buruk dan sangat berbahaya, kata Slade, mencoha meyakinkan. Di Sungai Hindus. Pakistan, ada juga riam seperti ini. Tapi , Riam Afun memang paling berbahaya. Giram Afun masih menjadi misteri. Tak seorangpun yang mampu melewatinya, tak pula petualang-petualang Amerika Serikat yang kenyang makan asam garam dalam menjelajahi semua tempat di seluruh dunia ini. Jajaran riam berkabut dan.bersuara keras itu, terpaksa dihindari. Satu setengah hari berjalan turun naik bukit-bukit di lembah sungai, barulah rombongan turun kembali ke Sungai Kayan di Busang Tingang. Dari sana, ekspedisi memasuki hari-hari terakhir. Kita kembali ke peradaban, ujar John Long memandang pelabuhan laut Tarakan. Ekspedisi melintasi Kalimantan selesai sesuai dengan jadwal, enam minggu, kendati tak semua berjalan lancar dan cocok dengan rencana. (Norman Edwin)
Norman Edwin, John Long, Stan Boor, Peter Pilafian, Rick Ridgeway, dan Jim Slade di Bandar Udara Tarakan (Jim Bridwell)
Anda mungkin juga menyukai
- Rubrik Penilaian PenjasDokumen5 halamanRubrik Penilaian PenjasJonoCinta100% (2)
- Bayu Yogo Pratomo - INSTRUMEN PENILAIAN Bola Voli SD Kelas VIDokumen6 halamanBayu Yogo Pratomo - INSTRUMEN PENILAIAN Bola Voli SD Kelas VIBayuyogo PratomoBelum ada peringkat
- Instrumen Evaluasi Renang Gaya BebasDokumen6 halamanInstrumen Evaluasi Renang Gaya BebasTsumetai Dan'sBelum ada peringkat
- Modul Ajar Atletik Lari Jarak Pendek Kls 7 SMT 1Dokumen23 halamanModul Ajar Atletik Lari Jarak Pendek Kls 7 SMT 1Rut Angelika SiahaanBelum ada peringkat
- Kisi-Kisi Praktek Pjok 2023Dokumen3 halamanKisi-Kisi Praktek Pjok 2023Dyah Kinanti100% (1)
- Penilaian Keterampilan KtpsDokumen7 halamanPenilaian Keterampilan KtpsKhurnais SaharaBelum ada peringkat
- 12 Kisi - Kisi - PjokDokumen8 halaman12 Kisi - Kisi - PjokimamtobBelum ada peringkat
- RPP Kelas 8 - Bola KecilDokumen5 halamanRPP Kelas 8 - Bola KecilSuci IlhamiBelum ada peringkat
- Gerak Lokomotor Kelas2Dokumen11 halamanGerak Lokomotor Kelas2NorezaBelum ada peringkat
- Kisi - Kisi Ujian Praktek Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Smp/Mts Kota Depok TAHUN PELAJARAN 2013-2014Dokumen5 halamanKisi - Kisi Ujian Praktek Mata Pelajaran: Pendidikan Jasmani Olahraga Dan Kesehatan Smp/Mts Kota Depok TAHUN PELAJARAN 2013-2014kirigaya kazutoBelum ada peringkat
- Materi Ujian Praktek PJOK TPK Kab. BDGDokumen11 halamanMateri Ujian Praktek PJOK TPK Kab. BDGMuhamad YusufBelum ada peringkat
- RPP Kelas 8 - TOLAK PELURUDokumen4 halamanRPP Kelas 8 - TOLAK PELURUSuci IlhamiBelum ada peringkat
- Kisi-Kisi Per RPP Bola VoliDokumen4 halamanKisi-Kisi Per RPP Bola VoliWahyu RahmadhaniBelum ada peringkat
- LKPD (Lompat Jauh)Dokumen13 halamanLKPD (Lompat Jauh)Hamonangan LimbongBelum ada peringkat
- Permen 37 Tahun 2018 - 61. KI-KD SMA - PJOKDokumen6 halamanPermen 37 Tahun 2018 - 61. KI-KD SMA - PJOKrobyBelum ada peringkat
- RPP Pjok Kelas 4 SMT 2 Tema 9 ST 1 PB 4Dokumen5 halamanRPP Pjok Kelas 4 SMT 2 Tema 9 ST 1 PB 4bambangBelum ada peringkat
- RPP Bab 6 Senam LantaiDokumen9 halamanRPP Bab 6 Senam Lantairavii ramadhanBelum ada peringkat
- Laporan Lomba Tarik TambangDokumen12 halamanLaporan Lomba Tarik TambangNi Putu Yuni WidiasihBelum ada peringkat
- Ujian Praktek PJOK 2022-2023Dokumen16 halamanUjian Praktek PJOK 2022-2023Khasbi AlfarisiBelum ada peringkat
- LKPD Tolak Peluru - 1Dokumen2 halamanLKPD Tolak Peluru - 1Sandy EkaBelum ada peringkat
- Contoh LKPDDokumen6 halamanContoh LKPDGalih Kurniawan Suwarno PutraBelum ada peringkat
- LKPD Tenismeja Kelas7Dokumen5 halamanLKPD Tenismeja Kelas7syuhada haziq100% (1)
- RPP Pjok Kelas 4 SMT 2 Tema 8 ST 2 PB 4Dokumen5 halamanRPP Pjok Kelas 4 SMT 2 Tema 8 ST 2 PB 4Raden Wahyu Djoyodiningrat50% (2)
- RPP Penjas 5Dokumen71 halamanRPP Penjas 5nipfun100% (1)
- Tkji LengkapDokumen3 halamanTkji LengkaplitaaldilaBelum ada peringkat
- Format Soal Ujian Praktek Kls IX 2013-2014Dokumen9 halamanFormat Soal Ujian Praktek Kls IX 2013-2014Apep GunawanBelum ada peringkat
- Kisi-Kisi Ujian Praktik PJOK SDN SINDANGSARI THN 2022 - 2023Dokumen27 halamanKisi-Kisi Ujian Praktik PJOK SDN SINDANGSARI THN 2022 - 2023samar boongBelum ada peringkat
- Analisis Prinsip Lay Up Shot Bola BasketDokumen7 halamanAnalisis Prinsip Lay Up Shot Bola BasketNurSyamsudinFikriPenjasBelum ada peringkat
- PJOK BasketDokumen3 halamanPJOK BasketangelBelum ada peringkat
- RPP Penjas Orkes SD Kelas 2Dokumen3 halamanRPP Penjas Orkes SD Kelas 2budiblack4531Belum ada peringkat
- LKPD Aktivitas Air - Gaya Renang - Tabina Amanda Aurelia Surya - XI MIPA 4Dokumen8 halamanLKPD Aktivitas Air - Gaya Renang - Tabina Amanda Aurelia Surya - XI MIPA 4Tabina Amanda Aurelia SuryaBelum ada peringkat
- RPP Penjas Bola Volly SMPDokumen12 halamanRPP Penjas Bola Volly SMPVery NantianoBelum ada peringkat
- RPP 1 Lembar Pjok Kelas 9 - Jalan CepatDokumen2 halamanRPP 1 Lembar Pjok Kelas 9 - Jalan CepatdonnyBelum ada peringkat
- Kisi Kisi Soal Penjas 8Dokumen7 halamanKisi Kisi Soal Penjas 8Susiew PoenxingindtsdjatieclmxtmnBelum ada peringkat
- LKPD Sepak BolaDokumen9 halamanLKPD Sepak BolaHendra WiriyadiBelum ada peringkat
- Instrumen PenilaianDokumen6 halamanInstrumen PenilaianSuhairi SuhairiBelum ada peringkat
- Soal Praktik PJOK Kls 6Dokumen23 halamanSoal Praktik PJOK Kls 6ErsaBelum ada peringkat
- Bahan AjarDokumen10 halamanBahan Ajararis munawarBelum ada peringkat
- 03 RPP Kelas 3 - Materi Gerak ManipulatifDokumen5 halaman03 RPP Kelas 3 - Materi Gerak ManipulatifFajar KusumoningradBelum ada peringkat
- Power Point Sepak BolaDokumen13 halamanPower Point Sepak BolaOpa Shabu ShabuBelum ada peringkat
- Kisi - Kisi Ujian Praktek PJOKDokumen2 halamanKisi - Kisi Ujian Praktek PJOKmus santo100% (1)
- Prosem Pjok Kelas 1 Semester 2Dokumen8 halamanProsem Pjok Kelas 1 Semester 2M ArifBelum ada peringkat
- Silabus Penjas Kls XDokumen28 halamanSilabus Penjas Kls XRoni SaputraBelum ada peringkat
- Contoh Rubrik PenilaianDokumen1 halamanContoh Rubrik PenilaianFitrah Saputra100% (1)
- Penetapan IPK PJOK Kelas 7 K13Dokumen8 halamanPenetapan IPK PJOK Kelas 7 K13Rizkiyana HidayahBelum ada peringkat
- Kisi Ujian Praktek PenjasDokumen3 halamanKisi Ujian Praktek PenjasJenal Aripin100% (3)
- Materi Ajar AKTIVITAS PUSH UPDokumen9 halamanMateri Ajar AKTIVITAS PUSH UPPendi HaristantyaBelum ada peringkat
- Kisi Kisi Penjas Kelas 5Dokumen2 halamanKisi Kisi Penjas Kelas 5Ilham MBelum ada peringkat
- Dikripsi Pjok 5Dokumen2 halamanDikripsi Pjok 5Santi NovitaBelum ada peringkat
- RPP SMA 1 Lembar 2020 Senam LantaiDokumen1 halamanRPP SMA 1 Lembar 2020 Senam LantaiArgadhia 038100% (1)
- Makalah Senam AerobikDokumen12 halamanMakalah Senam Aerobikmaman riyadiBelum ada peringkat
- Soal Kelas 8Dokumen6 halamanSoal Kelas 8Adi ismailBelum ada peringkat
- RPP BOLA Basket Chest PassDokumen13 halamanRPP BOLA Basket Chest Passkdr cuyBelum ada peringkat
- Silabus PJOK Kelas 9 Semester 1 Dan 2Dokumen25 halamanSilabus PJOK Kelas 9 Semester 1 Dan 2obyBelum ada peringkat
- Penilaian Proses Teknik Dasar Permainan BolavoliDokumen1 halamanPenilaian Proses Teknik Dasar Permainan BolavoliPolen Akbar100% (1)
- RPP Kebugaran JasmaniDokumen19 halamanRPP Kebugaran JasmaniJuheri Sirait100% (1)
- Skenario Tugas PE Kelas 9 - Ujian Praktek - Kebugaran JasmaniDokumen1 halamanSkenario Tugas PE Kelas 9 - Ujian Praktek - Kebugaran JasmaniGabriel MujurBelum ada peringkat
- LIPAN BARA DL BUKIT JEPAKDokumen7 halamanLIPAN BARA DL BUKIT JEPAKELRINE BINTI JOHINI MoeBelum ada peringkat
- Batu NongDokumen4 halamanBatu NongMenik AndromedaBelum ada peringkat
- Cerita SundaDokumen2 halamanCerita SundaRafi SugemaBelum ada peringkat