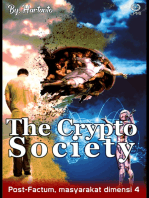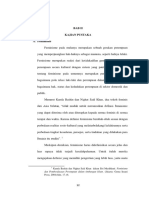Feminisme Di Dunia Islam
Diunggah oleh
Eka Cahya PrimaHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Feminisme Di Dunia Islam
Diunggah oleh
Eka Cahya PrimaHak Cipta:
Format Tersedia
Sorotan Terhadap Strategi Pemberdayaan Politik Perempuan
Oleh : Siti Muslikhati, S.IP., M.Si. Pendahuluan
Kesadaran akan terjadinya penindasan baik fisik maupun mental terhadap perempuan dalam suatu masyarakat, lapangan pekerjaan dan dalam keluarga telah memotivasi munculnya aksi dari laki-laki maupun perempuan untuk dengan sengaja mengubah keadaan tersebut. Aksi ini kemudian menamakan dirinya dengan sebutan feminisme.1 Para pejuang awal gerakan ini di abad ke-18 menganggap bahwa posisi perempuan yang terbelakang terjadi semata-mata karena kebanyakan perempuan terkungkung dalam dunia domestik, sehingga mereka buta huruf, tidak mempunyai keahlian dan miskin.2 Apa yang kemudian mereka perjuangkan adalah dengan menuntut diperbolehkannya perempuan terlibat dalam dunia publik, terutama sektor ekonomi dan pendidikan. Seiring dengan bergulirnya nuansa demokratisasi yang sekuler, gerakan perempuan pun makin menyadari betapa sesungguhnya keterbelakangan mereka bukanlah semata karena kebodohan dan kemiskinan, tetapi bersifat struktural sistemik. Mereka memandang adanya ketimpangan dan ketidakadilan terhadap perempuan dalam sistem masyarakat, yang mana sistem ini terbentuk karena pengendalian masyarakat oleh dominasi laki-laki dalam budaya patriarkhi. Mereka menyadari bahwa sesungguhnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dan pendidikan tidak secara otomatis meningkatkan status perempuan. Diperlukan perjuangan yang lebih bersifat strategis untuk menyelesaikan permasalahan perempuan, yaitu lewat keterlibatannya dalam lapangan politik. Asumsi bahwa hanya perempuan yang paling tahu persoalan perempuan semakin memotivasi para pejuang perempuan untuk melakukan pemberdayaan politik perempuan. Target terpentingnya adalah diberikan dan diakuinya keterlibatan perempuan dalam jantung kendali masyarakat, yaitu posisi penentu kebijakan (the authorities), apakah legislatif ataupun eksekutif.3 Cara berpikir seperti ini yang kemudian juga menjadi arah dan orientasi gerakan perempuan Islam. Senyatanya, ide-ide feminisme yang dilontarkan kelompok-kelompok tersebut nampaknya cukup berpotensi menitikkan air liur kaum muslimah yang lapar perjuangan, yakni mereka yang mempunyai semangat dan idealisme yang tinggi untuk mengubah kenyataan yang ada menjadi lebih baik. Karena, di samping didukung teknik penyuguhan yang ilmiah, ide-ide feminisme itu dikemas dengan jargon-jargon emosional yang dapat menyentuh lubuk-lubuk perasaan mereka, seperti jargon perjuangan hak-hak wanita, penindasan wanita, subordinasi wanita dan lain-lain. Selain itu, realitas masyarakat yang berbicara terkadang memang menampilkan sosok kaum wanita yang memilukan : terpuruk di bidang kesehatan, pendidikan, pekerjaan, kesejahteraan, politik, sosial dan lain-lain. Walhasil, tak diingkari gerakan-gerakan perempuan itu berpotensi menyedot simpati para muslimah. Lalu, mesti bagaimana kaum muslimah bersikap ? Untuk menentukan sikap yang rasional, seorang muslim/ah perlu untuk terlebih dulu melakukan pengkajian terhadap fenomena yang akan disikapinya. Pengkajian itu melalui setidaknya dua tahapan, yaitu pertama, tahapan memahami fakta (dalam hal ini fakta feminisme) dan kedua, memahami bagaimana Sang Pencipta manusia, alam dan kehidupan ini mengatur masalah tersebut. Tulisan ini merupakan awalan untuk melakukan pengkajian yang pertama. Pertanyaan yang akan kita jawab dalam tulisan ini adalah betulkah ketika perempuan memegang kendali kebijakan, persoalan perempuan bisa terselesaikan. Tulisan ini akan mencoba membedah pentingnya aktifitas politik dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian meninjau secara kritis agenda pemberdayaan politik perempuan perspektif feminisme, sekaligus memberikan alternatif bagi pemberdayaan politik perempuan yang shohih. Urgensi Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat Manusia, di dalam kehidupan bersamanya dengan manusia lain di masyarakat, pasti membutuhkan pengaturan agar mereka bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan harmonis. Bisa dikatakan bahwa pengaturan ini merupakan kebutuhan khas kehidupan manusia, karena hanya manusia lah yang memiliki potensi akal yang memungkinkannya untuk melakukan pilihan-pilihan dalam kehidupannya. Sehingga jika kehidupan bersama manusia yang berakal itu 1 Lihat pengertian feminisme dalam Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, Persoalan Pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya, 1995,hal.5 dan lihat juga dalam Mansour Faqih, ed., Membincang Feminisme : Diskursus Gender Perspektif Islam , hal. 235. 2 Jurnal Perempuan, Edisi 14, hal. 4. 3 Lihat bagan tentang Sistem Politik Demokrasi dalam G.K. Robert & Jill Lovecy, West European Politics Today (Manchester Univ. Press, 1984)
terjadi tanpa pengaturan, maka kerusakan yang ditimbulkan karena kebebasan manusia akan jauh lebih dahsyat. Pengaturan di sini mencakup apa yang boleh / harus dilakukan atau ditinggalkan oleh seluruh warga masyarakat secara keseluruhan maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan pembagian peran, tugas dan tanggung jawabnya. Politik pada esensinya berbicara tentang bagaimana permasalahan-permasalah manusia (konflik-konflik kepentingan di antara manusia) di dalam kehidupan bersama bisa diselesaikan dengan cara-cara yang adil, cara-cara yang bisa diterima oleh warga masyarakat. Proses politik di dalam masyarakat kemudian menghasilkan output berupa kebijakan (policy) yang berupa hukum atau peraturan perundangan yang lain. Di sinilah kita bisa memahami bahwa politik bisa diartikan sebagai pengaturan urusan-urusan rakyat. Jika politik diartikan sebagai kekuasaan pun, dalam kehidupan masyarakat mana pun pasti ada pihak yang berkuasa, dalam arti memiliki wewenang untuk mengatur, dan pihak yang diatur.4 Adanya aktifitas pengaturan inilah sesungguhnya yang mampu menciptakan kehidupan bersama. Aktifitas pengaturan ini (yaitu politik) yang sesungguhnya dibutuhkan dalam kehidupan bersama manusia (masyarakat). Hanya saja tidak semata-mata karena sudah ada aktifitas politik, kemudian masyarakat harmonis. Jika politik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, sementara adakalanya masyarakat itu baik, dalam hal kehidupan bersama mereka harmonis, teratur dan kebutuhankebutuhan warganya relatif terpenuhi dengan baik, adakalanya juga. orang mengalami kondisi masyarakat yang menyesakkan. Dalam kedua kondisi masyarakat tersebut kita bisa menyaksikan adanya aktifitas politik. Sampai di sini kita memahami bahwa politik itu sifatnya netral, bisa baik bisa buruk, bisa suci bisa kotor. Selamanya politik itu dibutuhkan dalam kehidupan bersama manusia. Masalah masyarakat itu akan baik atau buruk, akan harmonis atau konfliktual, tentunya sangat tergantung jenis pengaturan yang diberlakukan di masyarakat. Jenis pengaturan ini akan mengikuti proses-proses pemikiran dan perasaan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya ditinjau dari aplikasi jenis pengaturannya, keberhasilan pengaturan urusan masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan kemajuan masyarakat tergantung tidak hanya pada pemimpinnya, tetapi pada seluruh warga masyarakat tersebut. Terkait dengan peran politik perempuan di masyarakat kita, terjadi dua fenomena kontradiktif yang tidak proporsional. Satu sisi perempuan masih dianggap sebagai warga nomor dua, yang mereka cukup dikungkung dalam wilayah domestik seputar sumur, dapur dan kasur. Keterlibatan mereka di masyarakat dianggap sesuatu yang tabu dan menyalahi kodrat kewanitaannya. Seluruh aktifitas publik (termasuk politik) adalah dunianya laki-laki. Namun di sisi lain, wanita diposisikan sebagai warga yang sederajat dengan pria, yang keterlibatan mereka di dunia publik merupakan suatu keharusan, dengan alasan kesetaraan dengan pria. Sehingga para wanita menjadi sesibuk pria dalam dunia publiknya, kemudian dunia domestiknya menjadi urutan ke sekian. Kaum feminisme bisa dikatakan mewakili kelompok yang kedua ini. Arah Gerakan Feminisme Feminisme memulai gerakannya dari adanya kesadaran bahwa kondisi perempuan jauh tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Meskipun kemudian terdapat banyak teori yang proposisinya saling tumpang tindih, namun ada kesamaan umum dari teori-teori tersebut, yaitu asumsi yang dipakai tentang sistem patriarkhi. Asumsi feminisme tentang sistem patriarkhi adalah negatif, dimana sistem ini telah menempatkan perempuan pada posisi subordinat. Secara tradisional, manusia di berbagai belahan dunia menata diri atau tertata dalam bangunan masyarakat patriarkhi. Pada masyarakat seperti ini, laki-laki ditempatkan superior terhadap perempuan di berbagai sektor kehidupan, baik domestik maupun publik5. Dikotomi domestik-publik (juga nature dan culture) yang terbentuk dalam konteks tertentu telah menempatkan perempuan (mewakili sifat nature) pada kiprah-kiprah dalam sektor domestik, sementara laki-laki (mewakili sifat culture) ditempatkan sebagai kelompok yang berhak mengisi sektor publik. Cara-cara seperti ini ikut mereproduksi realitas tentang stratifikasi bidang kegiatan, di mana bidang publik dinilai lebih tinggi daripada domestik. Peradaban pun diasumsikan bergerak dari alam (perempuan) ke budaya (laki-laki).
4 R.G. Soekadijo, Antropologi Politik. Robert Michels dengan Hukum Besi Oligarkinya menyatakan bahwa tidak akan ada masyarakat tanpa suatu kelas dominan atau kelas politik. Lihat dalam Ichlasul Amal, Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, (Yogyakarta : PT Tiara Wacana, 1988), hal. 63. 5 Irwan Abdullah, Sangkan Paran Gender (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997), hal. 4-22.
Dalam perspektif feminis, spesifikasi peran-peran manusia (laki-laki dan perempuan) dalam masyarakat dipandang timpang (tidak egaliter). Artinya konstruksi sosial selama ini dianggap sangat berpihak kepada laki-laki, dan pada saat yang sama sangat menyudutkan kaum Hawa. Beberapa hal yang bisa dianggap tidak menguntungkan perempuan adalah pertama, terjadi marginalisasi perempuan dengan menganggap aktifitas perempuan sebagai tidak produktif dan bernilai rendah. Kedua, perempuan berada dalam kondisi tersubordinasi oleh laki-laki, terutama dalam pengambilan keputusan. Ketiga, terjadi penindasan pada perempuan karena beban pekerjaan yang lebih panjang dan berat. Keempat, terjadinya kekerasan dan penyiksaan (violence) terhadap perempuan baik secara fisik maupun mental.6 Oleh kondisi-kondisi sosial seperti itulah mereka kemudian mengibarkan bendera perjuangannya dalam meraih kebebasan (emansipasi) dan melepaskan diri dari belenggu ikatan apa pun. Transformasi sosial yang diperlukan untuk mengatasi hal tersebut adalah proses dekonstruksi peran gender dalam seluruh aspek kehidupan, di mana terrefleksi perbedaan-perbedaan gender yang telah melahirkan ketidakadilan gender. Kemudian terjadi rekonstruksi sehingga tercipta hubungan yang secara fundamental baru dan lebih baik. Kultur hegemonik harus diubah menjadi struktur non-represif, yang membebaskan. Oleh karena itu perlu ditumbuhkan adanya budaya yang memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menentukan perannya.7 Untuk memenuhi kebutuhan strategis, mereka melakukan metode pemberdayaan kaum perempuan melalui consciousness raising8 ,yaitu dengan menyatukan pengalaman anggota kelompok perempuan untuk membuat mereka sadar akan diskriminasi yang sedang berjalan.Tuntutan agar tidak memandang sifat kewanitaan mereka dan memberikan kesempatan yang sama di sektor publik, tercermin dari teriakan Sarah Grimke (1837) berikut: Kami tidak minta untuk diistimewakan atau berusaha merebut kekuasaan tertentu. Yang sebenarnya kami inginkan adalah sederhana, bahwa mereka mengangkat kaki mereka dari tubuh kami dan membiarkan kami berdiri tegap sama seperti manusia lainnya yang diciptakan Tuhan9. Ide-ide feminisme menjadi isu global semenjak PBB mencanangkan Dasawarsa I untuk Perempuan pada tahun 19751985. Sejak itu, isu-isu keperempuanan mewabah dan menular dalam berbagai bentuk forum baik di tingkat internasional, nasional, regional, maupun lokal. PBB di bawah kendali AS jelas berperan besar dalam penularan isu-isu tersebut, baik dalam forum yang khusus membahas perempuan -seperti forum di Mexico tahun 1975, Kopenhagen tahun 1980. Nairobi tahun 1985, dan terakhir di Beijing tahun 1995-- maupun forum tingkat dunia lainnya, seperti Konferensi Hak Asasi Manusia (HAM). KTT Perkembangan Sosial, serta KTT Bumi dan Konferensi Kependudukan. Dengan melihat pada berbagai forum internasional tersebut, kita bisa menyebutkan bahwa upaya peningkatan peran perempuan di sektor publik (dalam kehidupan masyarakat) tercermin dalam upaya melibatkan perempuan secara aktif dalam arus besar pembangunan. 10 Pada awal perkembangannya, sekitar tahun 1970-an, peningkatan peranan perempuan diinterpretasikan sebagai Women in Development (WID). Wawasan ini merupakan strategi arus utama developmentalism, sekaligus merefleksikan pengaruh Parsonian Structural-functionalism, yang lebih menunjukkan penerimaan atas struktur sosial yang ada. WID Titik berat perhatiannya lebih pada bagaimana mengintegrasikan perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, dengan fokus pada produktifitas kerja perempuan. Ketika program WID gagal dalam memperbaiki posisi perempuan, pada perkembangan selanjutnya, wawasan Women and Development (WAD), yang dicetuskan oleh kaum feminis-Marxis, menarik kesimpulan bahwa semata-mata keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak akan mengangkat status mereka, tetapi justru memperkokoh dependensi ekonomi kaum proletar (termasuk perempuan). Dalam hal ini pendekatan ini cenderung kurang mengindahkan sifat penindasan gender perempuan. Sehingga untuk meningkatkan status, kedudukan dan peran perempuan harus ada upaya mengubah struktur internasional supaya menjadi lebih adil, dengan tetap menekankan pada keterlibatan perempuan pada kegiatan mendatangkan pendapatan. Sejak tahun 1990, UNDP (United Nations Development Program), melalui laporan berkalanya Human Development Report (HDR) telah memperkenalkan indikator baru dalam menilai 6 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996) 7Ibid, hal. 66. 8 Kathie Sarachild, Feminist Revolution (New York : Random House, 1975). 9 Dikutip dari Cott (1987:66), The Suffragist, November 30,1920. 10 Moeljarto Tjokrowinoto, Pembangunan Dilema dan Tantangan (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), hal. 84-86.
keberhasilan pembangunan, yang selama ini hanya diukur dengan pertumbuhan GDP. Indikator baru ini adalah Human Development Index (HDI), yaitu pembangunan kualitas manusia. Seiring dengan kepedulian UNDP tersebut, terjadi pergeseran konsep pemberdayaan perempuan. Dari wawasan WID yang lebih menganggap perempuan sebagai sumber daya pembangunan, kemudian menjadi WAD dengan penekanan perempuan sebagai agen pembangunan, kemudian pada tahun 1995 diperkenalkan wawasan Gender and Development (GAD) dengan penekanan pada kesadaran tentang kesetaraan gender (gender equality) dalam menilai kesuksesan pembangunan. Perhitungan yang dipakai adalah GDI (Gender Development Index), yaitu kesetaraan laki-laki perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta GEM (Gender Empowerment Measure), yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik. Indikator kesetaraan yang sempurna (perfect equality) adalah 50/50.11 Pergeseran ini menegaskan bahwa untuk memajukan perempuan diperlukan lebih dari sekedar mengintegrasikan mereka dalam pembangunan, tetapi yang utama sekali adalah mengubah pola relasi gender yang merugikan perempuan menuju kepada keadilan gender, lewat keterlibatan perempuan dalam penentuan kebijakan (decision-making process). Strategi Pemberdayaan Politik Perempuan Upaya pemberdayaan politik perempuan, yang menjadi agenda besar akhir-akhir ini, merupakan bentuk kesadaran akan pentingnya aktifitas politik di dalam kehidupan masyarakat. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia publik, ternyata tidak memberikan basis penting bagi tawar menawar kekuasaan. Karena arena publik belum siap menerima keterlibatan perempuan, yang terjadi justru perluasan ideologi familialisme di arena publik. Di dunia publik, perempuan tetap diposisikan sebagai istri/ibu, yang tenaganya kurang layak untuk dihargai (sebagaimana tugas-tugas istri/ibu di dunia domestik adalah pengabdian) , sekaligus tubuh dan keperempuanan dia yang lebih banyak dimanfaatkan, sehingga dia tetap tidak memiliki kebebasan, terhadap tubuhnya sendiri sekalipun. Gerakan perempuan menghadapi kenyataan pahit mengingat sampai berakhirnya abad ke20 tingkat keterwakilan perempuan dalam dua struktur penentu kebijakan (pemegang kedaulatan/legislatif dan pemegang kekuasaan/eksekutif) sangatlah tidak proporsional. Selama ini dari data yang ada, jumlah suara yang disumbangkan perempuan dalam setiap pemilu lebih dari 52%. Tetapi keterwakilan dalam legislatif ataupun eksekutif jauh di bawah angka tersebut. Jumlah kursi parlemen di seluruh dunia yang diduduki perempuan hanya 10% dan kursi perdana menteri hanya 6%. Tingkat pertisipasi yang kecil dari perempuan di dunia terhadap sektor publik terutana politik di dalam lingkaran kekuasaan adalah isu penting yang hampir selalu menjadi agenda perjuangan para feminis. Mereka menganggap hal ini disebabkan oleh hambatan-hambatan aktual yang mencegah perempuan terlibat secara adil dalam posisi politik, apakah karena domestikasi perempuan ataukah ketimpangan gender yang merugikan perempuan. Menurut mereka, untuk mengeluarkan perempuan dari kungkungan ini, sekaligus membuka jalan bagi kiprah politik perempuan, dibutuhkan mekanisme yang lebih efisien untuk meningkatkan representasi perempuan dalam politik.12 Dalam hal ini sistem kuota menyajikan suatu mekanisme yang demikian. Ada 9 negara yang tercatat sebagai negara yang sukses dalam bidang politik berkat tingginya tingkat sensitifitas gender di tampuk kekuasaan setelah memutuskan pemberlakuan kuota, yaitu Swedia 42,7%, Denmark 37,4%, Finlandia 36,5%, Norwegia 36,4%, Belanda 36%, Islandia 34,9%, Jerman 30,9%, Selandia Baru 30,8% dan Mozambik 30%.13 Bagi aktifis perempuan Indonesia, bulan-bulan ini merupakan bulan yang bersejarah karena telah diadopsinya ketentuan kuota 30 % bagi keterwakilan perempuan di legislatif dalam UU Pemilu 2003, pasal 65 ayat 1. Tinjauan kritis Ada beberapa hal yang perlu dikritisi dari agenda strategis gerakan feminisme di dalam menyelesaikan permasalahan perempuan melalui pemberdayaan politik perempuan tersebut. Pertama, tentang kampanyre mendobrak domestikasi perempuan, sekaligus mendobrak pandangan yang bersifat patriarkhal. Menurut mereka, pola budaya patriarkhal yang membagi peran perempuan 11 Ratna Megawangi, Membiarkan Berbeda : Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender (Jakarta : Mizan, 1999), hal. 24. Tentang pemberdayaan perempuan dalam berbagai bidang tersebut, lihat dalam Report of the Fourt World Conference on Women, United Nations Publication, 1995, hal. 82. 12 Drude Dahlerup, Menggunakan Kuota Untuk Meningkatkan Representasi Politik Perempuan, dalam Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah, Bukan Sekedar Hiasan, (Jakarta : Yayasan Jurnal Perempuan, 1999). 13 Suara Muhammadiyah, No 07 Th. Ke-88 April 2003.
dalam dunia domestik dan laki-laki dalam dunia publik, telah menghasilkan ideologi ibuisme yang menjadi penghalang wanita berkiprah dalam dunia publik, sekaligus menjadi penghalang kebebasan individu dalam meraih materi. Domestikasi perempuan menyebabkan mereka tidak mandiri secara ekonomi dan tergantung secara psikologis. Masalahnya sebenarnya bukanlah pada adanya pembagian peran tersebut, tetapi lebih pada pensikapan terhadap peran, yang ini dipengaruhi oleh cara pandang masyarakat. Feminisme terlahir dalam konteks sosio-historis khas di Barat terutama pada abad XIXXX M. Peran domestik dianggap lebih rendah dibandingkan peran publik karena cara pandang masyarakat kapitalistik, yang menempatkan materi di atas segalanya, sekaligus menjadikan kebebasan individu sebagai agenda terpenting. Ukuran seseorang bermanfaat atau tidak dalam masyarakat tersebut ditentukan oleh seberapa banyak dia menghasilkan materi. Peran domestik yang tidak produktif menjadi posisi yang dianggap tidak signifikan.Dalam sosio-historis seperti ini sesungguhnya wajar jika ketertindasan perempuan terjadi. Sehingga mereka mengusulkan untuk wanita dibebaskan dari dunia domestik dan dibebaskan terjun ke dunia publik, yaitu berkiprah aktif dalam produktifitas materi, atau perempuan dibebaskan untuk menetapkan peran apa yang dipilihnya. Tetapi tetap pilihan ke arah peran-peran domestik saja dianggap bukan pilihan yang menyelesaikan masalah. Hanya saja, ketika prosentase perempuan yang terlibat dalam dunia kerja meningkat, ternyata masalah perempuan tidak terselesaikan, tetapi bahkan penindasan dan pensubordinasian perempuan merembet dalam wilayah publik (dunia kerja).14 Berarti masalahnya bukanlah pada apakah kehidupan domestik atau publik yang menjamin posisi wanita terangkat, tetapi lebih pada sistem apa yang diberlakukan. Kapitalisme memiliki karakter yang tidak manusiawi dan selalu menimbulkan ketimpangan, karena sifatnya yang materialistic individualistik parsial. Kedua, tentang kesetaraan gender 50/50 dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Ada asumsi yang tidak sesuai dengan realitas dan terlalu dipaksakan untuk menyebutkan bahwa indicator setaranya laki-laki dan perempuan di dalam kancah kehidupan adalah semata-mata secara kuantitatif menunjukkan angka fifti-fifti. Asumsi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kapasitas, kesukaan dan kebutuhan yang sama, sehingga harus melakukan pekerjaan yang sama tidaklah sesuai dengan kenyataan empiris. Karena secara de facto ada kemampuan yang bersifat universal (misal dalam hal kapasitas dan potensi akal dan jenis-jenis kebutuhan hidup), yang dalam hal insaniah ini laki-laki dan perempuan bisa disamakan. Akan tetapi ada juga kemampuan yang bersifat spesifik seperti hamil, melahirkan, menyusui. Hal yang spesifik ini mengarahkan pada pilihan-pilihan aktifitas yang berbeda juga. Tuntutan kaum feminis mengenai penghapusan diskriminasi di sector publik antara pekerja laki-laki dan perempuan sering menimbulkan rasa ambivalensi antara di satu sisi perlakuan yang sama dalam masalah hak gaji dan jenjang karier, dan di sisi lain dengan mendapatkan perlakuan berbeda (perlakuan khusus pada perempuan) pada masalah-masalah cuti hamil, haid, melahirkan, lembur malam dan sebagainya. Dengan melihat ada saatnya kemampuan dan kapasitas laki-laki dan perempuan sama (kemampuan universal insaniah), kemudian pada saat yang lain keragaman biologis antara laki-laki dan perempuan juga merupakan fakta yang tidak terpisahkan, maka secara de facto kesetaraan 50/50 memang hampir tidak mungkin tercapai.15 Ketiga, tentang kampanye melibatkan perempuan dalam politik. Sesungguhnya mereka menyadari bahwa keterlibatan dalam ekonomi tanpa diikuti dengan keterlibatan dalam politik tidak akan menyelesaikan masalah perempuan. Namun mereka memahami politik dengan sudut pandang yang sempit. Politik dalam perspektif feminis selalu diartikan sebagai kekuasaan dan legislasi. Akibatnya ide pemberdayaan peran publik perempuan melalui jalur politik selalu diarahkan untuk menjadikan kaum perempuan mampu menempatkan diri dan berkiprah di elit kekuasaan, lembaga legislasi, atau minimal berani memperjuangkan aspirasinya sendiri secara independen tanpa tanpa pengaruh maupun tekanan pihak apapun. Maka para penggiat feminis, selalu mempermasalahkan kuantitas perempuan yang duduk dalam lembaga legislasi. Keterwakilan aspirasi perempuan tercermin dengan banyaknya jumlah yang dapat duduk pada badan-badan tinggi negara yang membuat undang-undang. Kuota 30% bagi perempuan Indonesia di DPR yang terangkum dalam UU Pemilu pasal 65 adalah bukti bahwa mereka mengartikan politik dengan sudud pandang yang sempit. Artinya pada pemberdayaan politik perempuan tampak sekali nuansa perjuangannya melalui mekanisme demokrasi, sekaligus untuk mengusung demokrasi. Sebagai konsekuensi dari asas kebebasan dan kedaulatan di tangan rakyat (sekaligus mengabaikan kedaulatan Tuhan), demokrasi memang menawarkan posisi penentu kebijakan sebagai posisi yang menggiurkan, karena lewat posisi inilah kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang akan terakomodir. Asumsi berikutnya 14 Muhammad Albar, Wanita Karir dalam Timbangan Islam, terj. Amir Hamzah F. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2000), hal. 110-128. 15 Ratna Megawangi, Op. Cit., hal. 32.
adalah bahwa lewat mekianisme representasi (perwakilan) kepentingan-kepentingan seseorang atau sekelompok orang akan sampai pada pusat pembuatan keputusan. Asumsinya, yang paling tahu tentang kepentingan buruh adalah kelompok buruh, yang paling tahu tentang kepentingan perempuan adalah kelompok perempuan. Hal ini adalah cara pandang yang tidak sesuai dengan realitas, karena kemampuan seseorang untuk mengetahui/memahami kepentingan orang yang diwakilinya, bahkan kepentingannya sendiri pun adalah sangat terbatas. Apalagi ditambah dengan bahwa dirinya sendiri pun mempunyai kepentingan, sehingga kecenderungan mengedepankan kepentingan sendiri, atau minimal kelompok kecilnya saja ketika memproses input menjadi sangat besar. Mereka yang kemudian masuk dalam dunia politik pun, karena berangkat dari memaknai politik seperti itu menjadi tidak punya tanggung jawab terhadap rakyat. Target mereka adalah kekuasaan. Masalah kekuasaan itu untuk apa dan siapa tidak begitu diperhatikan oleh mereka. Melibatkan rakyat dalam aktifitas politik sampai saat ini hanyalah sekedar arahan keterlibatan dalam pemilu. Aktor-aktor politik praktis, seperti parlemen, pemerintah, bahkan parpol pun hanya membutuhkan rakyat menjelang pemilihan keanggotaan mereka, tetapi selebihnya tidak terjadi proses sosialisasi politik dan pendidikan politik yang terprogram, sistematis dan terus menerus. Wajar jika tidak pernah terjadi diskusi politik yang fair antara penguasa dengan rakyat. Artinya terpenuhinya keterwakilan perempuan pun tidak menjamin bahwa masalah perempuan terselesaikan, kemudian keadilan dan keharmonisan tercapai. Tampilnya perempuan dalam tampuk kekuasaan di Bangladesh, Pakistan dan juga Indonesia tidak ada korelasinya dengan penyelesaian masalah perempuan. Di negara-negara yang relatif bagus tingkat kesetaraan laki-laki dan perempuannya dalam legislative pun tidak serta merta menyelesaikan masalah perempuan. Yang terjadi justru muncul masalah samping seperti aborsi, terancamnya keberlangsungan manusia dan sebagainya. Mencari Problem Solving yang Shahih Perempuan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Realitasnya memang Allah telah menciptakan manusia dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam masyarakat. Keduanya diberi potensi yang sama dari sisi insaniahnya, berupa akal dan kebutuhan-kebutuhan hidup. Adanya potensi inilah yang mendorong keduanya untuk terjun ke dalam kancah kehidupan secara bersama, kemudian saling tolong menolong (taawun) dalam menyelesaikan urusan atau persoalan bersama di antara mereka (beraktifitas politik). Jika ada permasalahan dalam kebersamaan ini, harus kita telusuri apa penyebab masalah tersebut. Penyebab masalah bisa ditelusuri dari tiga kemungkinan, yaitu kesalahan pada sistem yang diberlakukan saja, atau kesalahan pada pelaksanaan sistem saja atau dua-duanya. Tentunya kesalahan pada pelaksanaan sistem saja bisa kita selesaikan dengan mempertahankan sistem tersebut dan menambal sulam seperlunya. Namun kesalahan pada sistem, biasanya berimplikasi pada sekaligus pelaksanaannya tidak beres, tidak bisa kita lakukan dengan semata-mata tambal sulam sana sini tetap dalam kerangka sistem tersebut. Yang harus dilakukan adalah mengganti sistem terlebih dahulu sembari menyiapkan sistem yang lebih bagus, sekaligus mempersiapkan orang-orang yang kualified untuk mengisi sistem tersebut. Ketertindasan perempuan sesungguhnya lebih terjadi pada masyarakat Kapitalisdemokratik, seperti yang sudah dipaparkan pada tinjauan kritis. Dan terbukti bahwa menyelesaikan masalah dengan menyandarkan pada kesombongan sistem tersebut, dalam artian kepongahannya untuk menolak kedaulatan Tuhan, selalu gagal untuk menciptakan keadilan dan keharmonisan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah perempuan bukan terletak pada apakah wanita ada di dunia domestik atau di dunia publik, ataukah apakah wanita memegang tampuk kekuasaan atau tidak, tetapi lebih pada perspektif yang digunakan dalam merumuskan kebijakan. Mekanisme kapitalisme demokrasi itulah yang terbukti memberi andil besar di dalam menciptakan ketidakadilan, tidak hanya antara laki-laki dan perempuan tetapi juga antar komponen yang ada dalam masyarakat tersebut secara keseluruhan.
Kehadiran gerakan perempuan Islam yang juga menyuarakan pentingnya aktifitas politik perempuan, harus kita akui sebagai adanya langkah maju dalam cara berpikir muslimah karena mereka sudah tidak canggung merambah wilayah politik. Islam sebagai agama spiritual dan politik menunjukan bahwa siapa saja (termasuk muslimahnya) harus memiliki kepedulian terhadap perkara politik. Wujud pemberdayaannya seperti apa, tentunya sangat tergantung pada arah dan orientasi gerakan tersebut. Sehingga strategi gerakan perempuan Islam harusnya tidak terjebak pada mekanisme ideologi yang tidak shohih dan tidak manusiawi. Tindakan yang logis adalah dengan mengganti sistem kapitalis demokrasi tersebut dengan sistem Islam, karena hanya sistem Islam yang shohih sehingga mampu menciptakan keadilan seluruh manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik muslim maupun non-muslim, baik kaya maupun miskin.16 Kesimpulan Mentransfer ide ini ke tengah umat Islam, yang memiliki sejarah dan nilai yang khas Islam, jelas merupakan generalisasi sosiologis yang terlalu dipaksakan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Klaim bahwa wawasan sosiologis bersifat universal, mengandung kepongahan yang dapat mengakibatkan dilema serius bagi para sosiolog. Robert M. Marsh menandaskan : Sosiologi telah dikembangkan di sebuah sudut kecil dunia dan, dengan demikian, amat terbatas sebagai suatu skema universal.17 Dari hasil pengkajian terhadap upaya-upaya pemberdayaan politik perempuan, tampak harusnya kita tidak terlalu silau dengan gemerlap feminisme. Apa yang harus kita bangun adalah bagaimana menciptakan kepercayaan diri pada identitas yang sudah kita miliki. Tentunya dengan pertama kali memperkuat benteng / fondasi bagi identitas tersebut. Mudah-mudahan kita selalu tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang senantiasa melakukan pemikiran dan pendalaman sebelum menentukan pilihan. Wallaahu alam bi-ash-showab.
16 Lihat dalam Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam (Jakarta : Gema Insani Press) 17 Robert M. Marsh, Comperative Sosiology, Brace and World, New York, 1967, hlm 19.
Anda mungkin juga menyukai
- Teori-Teori FeminismeDokumen37 halamanTeori-Teori FeminismeEsTe Chomah100% (8)
- Artikel Peran Perempuan Dalam Politik Di Era ReformasiDokumen7 halamanArtikel Peran Perempuan Dalam Politik Di Era ReformasiSelphi CristianiBelum ada peringkat
- Teori FeminisDokumen72 halamanTeori Feminishonam100% (1)
- Gender, Feminism, and International RelationsDokumen15 halamanGender, Feminism, and International Relationsmeyrzashrie100% (1)
- Makalah Pandangan Islam Terhadap FeminismeDokumen14 halamanMakalah Pandangan Islam Terhadap FeminismeSerly Poetri AnjanyBelum ada peringkat
- Alfian Ulia Amri Review Teori FeminismeDokumen5 halamanAlfian Ulia Amri Review Teori FeminismeAlfian Ulia AmriBelum ada peringkat
- Review Teori Feminis LiberalDokumen4 halamanReview Teori Feminis LiberalNoor RochmanBelum ada peringkat
- Tugas FeminismeDokumen5 halamanTugas FeminismeFesilia MarzukiBelum ada peringkat
- Makalah Gerakan Feminisme Dan AlirannyaDokumen8 halamanMakalah Gerakan Feminisme Dan AlirannyaRanie MoerbifalaBelum ada peringkat
- Kelompok 2 2205135870 2205113148 2205135868 2205135877 2205110868Dokumen10 halamanKelompok 2 2205135870 2205113148 2205135868 2205135877 2205110868Bella SafiraBelum ada peringkat
- Perempuan Dan Peranannya Dalam MasyarakatDokumen13 halamanPerempuan Dan Peranannya Dalam MasyarakatGusmira WitaBelum ada peringkat
- Gender Dan PembangunanDokumen8 halamanGender Dan PembangunanAnnisa SekarBelum ada peringkat
- Kriminologi FeminisDokumen27 halamanKriminologi FeminisNorman PrachayaBelum ada peringkat
- Tugas Finel Teori Sastra 30 Des.Dokumen11 halamanTugas Finel Teori Sastra 30 Des.nursiawatidfch0604Belum ada peringkat
- Jejaring KebijakanDokumen11 halamanJejaring Kebijakanahmad dhaniBelum ada peringkat
- Uas Sosiologi Gender, Ferdianto P. KarimaleyDokumen5 halamanUas Sosiologi Gender, Ferdianto P. Karimaleykazekage naraBelum ada peringkat
- Tugas Kelompok PresentasiDokumen10 halamanTugas Kelompok PresentasiYaa TamrinBelum ada peringkat
- Resume Buku Gender Dan Politik (MK Gender Dan Politik Sem 4)Dokumen10 halamanResume Buku Gender Dan Politik (MK Gender Dan Politik Sem 4)Zahira OktafiaBelum ada peringkat
- Paradigma FeminismeDokumen7 halamanParadigma FeminismeDhany SimilikitiBelum ada peringkat
- A - 203507082 - Syaharani Amelia HusenDokumen6 halamanA - 203507082 - Syaharani Amelia HusenSyaharani Amelia HusenBelum ada peringkat
- Tugas Sosiologi GenderDokumen4 halamanTugas Sosiologi Genderkazekage naraBelum ada peringkat
- MPS FeminismeDokumen20 halamanMPS FeminismeAnnisa CameliarBelum ada peringkat
- Tgs Filsafat HukumDokumen10 halamanTgs Filsafat Hukumhairulhasandi98Belum ada peringkat
- Kultur Patriaki Melahirkan Feminimisasi KemiskinanDokumen6 halamanKultur Patriaki Melahirkan Feminimisasi KemiskinanGilang Rollimuzaby FattahBelum ada peringkat
- S281 Muhadjir Darwin Maskulinitas Posisi Laki Laki Dalam Masyarakat PatriarDokumen7 halamanS281 Muhadjir Darwin Maskulinitas Posisi Laki Laki Dalam Masyarakat PatriarAbd RifaiBelum ada peringkat
- Teori-Teori FeminisDokumen6 halamanTeori-Teori FeminisHilman Phew FauziBelum ada peringkat
- PAR Rizki Fadilah PermanaDokumen3 halamanPAR Rizki Fadilah Permanartq muhyiddienBelum ada peringkat
- d0219039 Hammam Arya P Utsmedgen2021Dokumen11 halamand0219039 Hammam Arya P Utsmedgen2021Hamam AryaBelum ada peringkat
- Makalah Feminisme Dalam IslamDokumen19 halamanMakalah Feminisme Dalam Islamriska yuniar sundari100% (1)
- S1 SKRIPSI - PUBLIC 2007 Anggraini - Miftachur - Rochmah CompleteDokumen113 halamanS1 SKRIPSI - PUBLIC 2007 Anggraini - Miftachur - Rochmah CompleteMahakBelum ada peringkat
- Tugas 3 - Gender & Pembangunan - Wahyu Ari Sandana - c1g018181Dokumen4 halamanTugas 3 - Gender & Pembangunan - Wahyu Ari Sandana - c1g018181wahyu arisandanaBelum ada peringkat
- Rangkuman BahanDokumen35 halamanRangkuman BahanShanaz QisthinaBelum ada peringkat
- Teori Feminisme Dan Teori GenderDokumen3 halamanTeori Feminisme Dan Teori GenderIan M PurbaBelum ada peringkat
- Partisipasi Politik Perempuan KudusDokumen22 halamanPartisipasi Politik Perempuan KudusWeling KuningBelum ada peringkat
- Kel 4 Makalah Teori FeminismeDokumen14 halamanKel 4 Makalah Teori FeminismeLila OktaviaBelum ada peringkat
- Teori FEMINISMEDokumen27 halamanTeori FEMINISMEIal Saint BlackersBelum ada peringkat
- Teori Sistem Dunia Dan FeminismeDokumen6 halamanTeori Sistem Dunia Dan FeminismeMumtaz Amru RabbaniBelum ada peringkat
- Teori FeminismeDokumen5 halamanTeori FeminismeAprilia Ika ABelum ada peringkat
- Definisi SosialDokumen5 halamanDefinisi SosialNur Suci FitriyaniBelum ada peringkat
- Analisis Gender Dan Transformasi SosialDokumen11 halamanAnalisis Gender Dan Transformasi SosialMillenaBelum ada peringkat
- Teori Feminisme RadikalDokumen5 halamanTeori Feminisme Radikalwibiono100% (1)
- Feminisme RadikalDokumen5 halamanFeminisme RadikalDewi YunitaBelum ada peringkat
- Beberapa Aliran FeminismeDokumen7 halamanBeberapa Aliran FeminismeTaloeBelum ada peringkat
- Bab Ii e GhanaDokumen7 halamanBab Ii e GhanaMuhamad Azhar FatoniBelum ada peringkat
- Aliran Dalam FeminismeDokumen10 halamanAliran Dalam FeminismeArdaniah Mufti IIBelum ada peringkat
- Teori Feminisme RadikalDokumen4 halamanTeori Feminisme Radikalbambang wibionoBelum ada peringkat
- Jurnal Bahasan Gender Untuk SkripsiDokumen12 halamanJurnal Bahasan Gender Untuk SkripsiMusik AddictBelum ada peringkat
- Proyek Feminis Tentang Pengakuan Eksplisit Bahwa Gender Dan Perbedaan Gender Meliputi Semua Aspek Kehidupan SosialDokumen3 halamanProyek Feminis Tentang Pengakuan Eksplisit Bahwa Gender Dan Perbedaan Gender Meliputi Semua Aspek Kehidupan SosialAbil JayaBelum ada peringkat
- Menakar Isu Feminisme Dan TantangannyaDokumen14 halamanMenakar Isu Feminisme Dan TantangannyaThelightness NurBelum ada peringkat
- Tugas 3 - Epistemologi Berbasis GenderDokumen4 halamanTugas 3 - Epistemologi Berbasis GendertenricapasitiBelum ada peringkat
- BAB I Skrispsi AWK Model Sara Mills Pada Film Dangal Mengenai Pegulat PerempuanDokumen9 halamanBAB I Skrispsi AWK Model Sara Mills Pada Film Dangal Mengenai Pegulat Perempuangitamputri2801Belum ada peringkat
- Feminisme Paper PDFDokumen61 halamanFeminisme Paper PDFFareza Havid SahisnuBelum ada peringkat
- Menimbang Respon Feminis Terhadap GlobalisasiDokumen29 halamanMenimbang Respon Feminis Terhadap GlobalisasihanifahBelum ada peringkat
- Jawaban Pengantar Sosiologi - Pande Aman Lubis - A Reg 2020Dokumen2 halamanJawaban Pengantar Sosiologi - Pande Aman Lubis - A Reg 2020Pande LubisBelum ada peringkat
- Nasionalisme Dan Resolusi KonflikDokumen5 halamanNasionalisme Dan Resolusi KonflikViola KehiBelum ada peringkat
- FeminismeDokumen4 halamanFeminismeAfi Satria Nugroho100% (1)
- Feminism Theory - En.idDokumen6 halamanFeminism Theory - En.idNurul RahmiBelum ada peringkat
- Makalah FeminismeDokumen23 halamanMakalah FeminismeBagaz TrabalistraBelum ada peringkat
- Artikel Antropologi Gender Dan Seksual-1untanDokumen15 halamanArtikel Antropologi Gender Dan Seksual-1untanyoganteng2812Belum ada peringkat