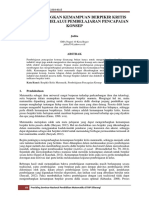Keterampilan Berpikir Kreatif - Kritis
Keterampilan Berpikir Kreatif - Kritis
Diunggah oleh
Sitti RahmasariJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Keterampilan Berpikir Kreatif - Kritis
Keterampilan Berpikir Kreatif - Kritis
Diunggah oleh
Sitti RahmasariHak Cipta:
Format Tersedia
A.
Keterampilan Berpikir Kreatif
Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu hal penting agar seseorang dapat memiliki kreativitas. Torrance (Carin & Sund, 1995), dan Lawson (1979)., & Taeffinger., et al (1982), bahwa berpikir kreatif ... the process of 1) sensing difficulties problems, gapsor information, missing elements, something asked; 2) making guesses and formulating ideas or hypotheses about these deficiencies; 3) evaluating and testing these guesses and hypotheses; 4) possibily revising retesting them, and finally; 5) communicating the results. Bertolak dari definisi tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif sebagai sesuatu proses kreatif, yaitu merasakan adanya kesulitan, masalah kesenjangan informasi, adanya unsur yang hilang dan ketidakharmonisan, mendefinisikan masalah secara jelas, membuat hipotesis, pengujian hipotesis kembali atau bahkan mendefinisikan ulang masalah dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. Berpikir kreatif akan mudah diwujudkan dalam lingkungan belajar yang secara langsung memberikan peluang bagi siswa untuk berpikir terbuka dan fleksibel tanpa adanya rasa takut atau malu. Sebagai contoh, situasi belajar yang dibentuk harus memfasiltasi terjadinya diskusi, mendorong seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Menurut Carin & Sund (1995) untuk menimbulkan kreativitas dalam pembelajaran perlu memperhatikan aspek-aspek (1) mengembangkan kepercayaan yang tinggi dan meminimalisir ketakutan; (2) mendorong terjadinya komunikasi secara bebas; (3) mengadakan pembatasan tujuan dan penilaian secara individu oleh siswa; dan (4) pengendalian tidak terlalu ketat. Berpikir kreatif dapat terjadi secara sengaja dan tidak sengaja (tiba-tiba). Berpikir kreatif secara tidak sengaja dapat berlangsung walaupun tidak menggunakan teknik khusus, seperti suatu kesempatan yang menyebabkan Anda berpikir tentang sesuatu dengan sudut pandang yang berbeda dan selanjutnya Anda menemukan suatu perubahan yang menguntungkan. Perubahan yang lainnya dapat terjadi perlahan karena semata-mata menggunakan perkembangan kecerdasan dan logika. Jika mengunakan pemikiran kreatif secara tidak sengaja atau perkembangan logika akan memerlukan waktu lama untuk menghasilkan kemajuan dan peningkatan. Mengingat pesatnya persaingan dunia maka hal tersebut sangat tidak menguntungkan. Lain halnya dengan berpikir kreatif secara sengaja. Berpikir kreatif secara sengaja dapat dikembangkan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk mengembangkan ide baru. Teknik-teknik tersebut menyebabkan penggabungan dari ide-ide untuk me-munculkan gagasan-gagasan dan proses-proses baru. Pembelajaran berbasis
portofolio merupakan salah satu teknik khusus yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Berpikir kreatif dapat berkembang pesat dengan menggunakan pembelajaran berbasis portofolio karena model pembelajaran ini mampu memfasilitasi hampir keseluruhan kemampuan siswa, yakni keterampilan mengembangkan pengetahuan yang sudah dimiliki oleh siswa, keterampilan memprediksi dari informasi terbatas, keterampilan menemukan masalah, keterampilan menyusun hipotesis, keterampilan menguji hipotesis, dan
keterampilan memandang informasi dari sudut pandang yang berbeda.
B. Keterampilan Berpikir Kritis
Berpikir kritis merupakan suatu aktivitas evaluatif (bersifat menilai) untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Carin & Sund, 1995). Gerhard (1971) mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses kompleks yang melibatkan penerimaan dan penguasaan data, analisis data, evaluasi data dengan mempertimbangkan aspek kualitatif dan kuantitatif, serta melakukan seleksi atau membuat keputusan beradasarkan hasil evaluasi (Carin & Sund, 1995). Splitter (1991) mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan bertanggung jawab yang memudahkan pengelolaan yang baik. Hal ini dikarenakan berpikir kritis: (a) didasarkan atas suatu kriteria; (b) adalah instropeksi diri; (c) membuat orang peka terhadap keadaan. Orang yang berpikir kritis, secara sadar dan rasional berpikir tentang pikirannya dengan maksud untuk diterapkan pada situasi yang lain (Carin & Sund, 1995) Berpkir kritis sangat diperlukan oleh setiap individu untuk menyikapi permasalahan kehidupan yang dihadapi. Dengan berpikir kritis, seseorang dapat mengatur, menyesuaikan, mengubah, atau memperbaiki pikirannya sehinggga dia dapat bertindak lebih tepat. Penyesuaian-penyesuaian ini tidaklah acak atau bersifat instink, tapi didasarkan pada standar atau rambu-rambu yang oleh Lipman disebut kriteria (criteria) dan oleh Ennis dan kawankawannya disebut nalar (reasons). Orang yang berpikir kritis, berpikir dan bertindak secara normatif, siap bernalar tentang kualitas dari apa yang mereka lihat, dengar atau yang mereka pikirkan (Carin & Sund, 1995).
Guru sebagai pendidik berkewajiban untuk menolong siswa mengembangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritisnya. Kewajiban ini diemban oleh para pendidik karena pendidik dan siswanya hidup dalam suatu kondisidemokratis yang sangat menghargai nalar dan berpikir secara nalar. Pentingnya mengajarkan berpikir kritis tidak dapat diabaikan lagi, karena berpikir kritis merupakan proses dasar dalam suatu keadaan dinamis yang memungkinkan siswa untuk menanggulangi dan mereduksi ketidak tentuan masa datang (Carin & Sund, 1995). Kemampuan berpikir kritis akan memungkinkan siswa untuk dapat menentukan informasi apa yang penting didapatkan, diubah, ditransformasi dan dipertahankan. Pengalaman bermakna yang melibatkan berpikir kritis dapat membantu siswa: (1) membuat keputusan didasarkan pada evaluasi komponen-komponen yang terlibat; (2) menentukan validitas kesimpulan, keyakinan dan opini yang dinyatakan orang lain; (3) melihat keyakinan, perasaan, sikap dan pemikirannya sendiri berkaitan dengan situasi yang ada, dan membiarkan siswa untuk memperkuat gagasan dan keyakinannya serta menentukan sendiri nilai-nilai yang akan dihargainya (Carin & Sund, 1995). Pengembangan keterampilan berpikir kritis telah cukup lama diperhatikan sebagai tujuan utama pendidikan (Resnick, 1987). Akan tetapi, studi-studi yang melakukan asesmen kemampuan berpikir kritis siswa, mengungkapkan bahwa keterampilan berpikir kritis tidak berkembang tanpa usaha secara eksplisit dan disengaja ditanamkan dalam pengembangannya. Seorang siswa tidak akan dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dengan baik tanpa ditantang untuk berlatih dalam konteks bidang studi yang dipelajarinya. Dengan demikian, guru-guru dalam semua disiplin ilmu memegang peranan penting dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pemodelan atau aktualisasi berpikir kritis dalam kehidupan guru, dapat diharapkan membantu mempermudah penanaman dan pengembangan keterampilan berpikir kritis siswa.
Usaha-usaha pendidikan untuk meningkatkan keterampilan berpikir telah banyak dilaporkan akhir-akhir ini. Satu dari beberapa pendekatan yang umum diupayakan adalah pendekatan infusion (infusion approach), dimana pengembangan berpikir kritis dimasukkan ke dalam disiplin pelajaran reguler (Carin & Sund, 1995). Pendekatan ini disandarkan pada anggapan atau pemikiran, bahwa keterampilan kognitif domain spesifik dan domain umum, saling mempengaruhi satu sama lain dalam kognisi seseorang. Keterampilan seseorang dalam satu bidang, dapat memberi kontribusi pada kinerja siswa dalam bidang yang lain (Carin & Sund, 1995). Pendekatan infusion dapat membantu mengembangkan keterampilan berpikir serta pemahaman yang baik terhadap disiplin ilmu yang dipelajari (Carin & Sund, 1995). Dalam kurikulum berpikir kritis menurut Ennis (1991) terdapat dua belas indikator berpikir kritis yang dikelompokkan dalam lima kelompok keterampilan berpikir (Costa, A.L . (1985), yaitu: a. Memberikan penjelasan sederhana, yang meliputi: (1) memfokuskan pertanyaan; (2) menganalisis pertanyaan; (3) bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau tantangan. b. Membangun keterampilan dasar, yaitu meliputi: (4) mempertimbangkan apakah sumber dapat dipercaya atau tidak; (5) mengamati dan mempertimbangkan suatu laporan hasil observasi. c. Menyimpulkan, yaitu terdiri dari: (6) mendeduksi dan mempertimbangkan hasil deduksi; (7) menginduksi dan mempertrimbangkan hasil induksi; (8) membuat dan menentukan nilai pertimbangan. d. Memberikan penjelasan lanjut, meliputi: (9) mendefinisikan istilah dan definisi pertimbangan dalam tiga dimensi; (10) mengidentifikasi asumsi.
e. Mengatur strategi dan taktik, meliputi: (11) menentukan tindakan; (12) berinteraksi dengan orang lain. Kedua belas indikator keterampilan berpikir kritis tersebut dirinci lebih lanjut menjadi keterampilan berpikir kritis yang lebih khusus, tetapi hanya sebagian diantara yang sesuai untuk pembelajaran fisika. Indikator-indikator keterampilan berpikir kritis yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran fisika, antara lain adalah: a. Memfokuskan pertanyaan: (a) mengidentifikasi atau merumuskan pertanyaan. b. Menganalis pertanyaan: (a) mengidentifikasi kesimpulan; (b) mengidentifikasi alasan yang dikemukakan; (c) mengidentifikasi alasan yang tidak dikemukakan; (d) menemukan persamaan dan perbedaan. c. Bertanya dan menjawab pertanyaan tentang suatu penjelasan atau tantangan: (b) menjawab pertanyaan tentang alasan utama; (d) memberi contoh. d. Menginduksi dan mempertimbangkan hasil induksi: (a.2) menggeneralisasikan; (b.3) memberikan asumsi yang masuk akal. e. Membuat dan menentukan nilai pertimbangan: (c) menerapkan prinsip yang dapat diterima; mempertimbangkan alternatif; (e) menimbang dan memutuskan. Dalam beberapa hal, mengembangkan keterampilan berpikir kritis adalah seperti halnya mengembangkan keterampilan motorik, dimana keduanya memerlukan latihanlatihan. Kita harus memilih jenis-jenis latihan yang diperlukan. Peranan guru sebagai pendidik untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam diri siswa adalah sebagai fasilitator dan motivator. Guru sebagai fasilitator dan motivator, tidak perlu memberi tahu siswa tentang apa yang harus dipikirkan. Tujuan pentung dari pengembangan berpikir kritis adalah agar siswa berpikir oleh dirinya sendiri. Kadang-kadang pertanyaan yang diberikan guru adalah cara yang baik. Jenis pertanyaan divergen dan bersifat evaluatif memungkin adanya kesempatan
bagi siswa merefleksikan gagasan dan kegiatannya, sehingga siswa dapat melihat motivasi, kegiatan dan argumentasi mereka seolah-olah mereka adalah orang lain. Guru harus melatih mereka dengan cara yang ramah dan dapat dimengerti. Siswa menginginkan untuk diperlakukan secara hormat. Penghinaan dan ejekan yang diterima seseorang akan menghambat produktivitas berpikir kritis orang tersebut (Carin & Sund, 1995) Dengan demikian, seorang guru harus menjaga harga diri siswa agar mereka tidak merasa diserang dan terancam ketika ditanya.
A. Berpikir Kreatif 1. Pengertian berpikir kreatif Secara umum berpikir merupakan suatu proses kognitif , suatu aktifitas mental untuk memperoleh pengetahuan. Proses berpikir dihubungkan dengan pola perilaku yang lain dan memerlukan keterlibatan aktif pemikir melalui hubungan kompleks yang dikembangkan melalui kegiatan berpikir. Hubungan ini dapat saling terkait dengan struktur yang mapan dan dapat diekspresikan oleh pemikir melalui bermacam-macam cara. Jadi berpikir merupakan upaya yang kompleks dan reflektif, bahkan juga pengalaman yang kreatif (Costa, 1985). Keterampilan berpikir selalu berkembang, dapat dipelajari, dan dapat dilatihkan (de Bono, 2007). Keterampilan merupakan suatu kemampuan melakukan sesuatu dengan baik. Kinerja keterampilan meliputi pengetahuan mengenai apa yang harus dilakukan, kapan dilakukan dan bagaimana melakukannya. Keterampilan berpikir adalah keterampilan-keterampilan yang relatif spesifik dalam memikirkan sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memahami sesuatu informasi berupa gagasan, konsep, teori dan sebagainya. Pengetahuan dan keterampilan berpikir merupakan suatu kesatuan yang saling menunjang. Berdasarkan prosesnya keterampilan berpikir dapat dikelompokkan dalam keterampilan berpikir dasar dan keterampilan berpikir kompleks (Liliasari,2005). Proses berpikir dasar merupakan gambaran dari proses berpikir rasional yang mengandung sejumlah langkah dari yang sederhana menuju yang kompleks. Sedangkan proses berpikir kompleks yang disebut keterampilan berpikir tingkat tinggi ada empat macam, yaitu pemecahan masalah, pengambilan keputusan, berpikir kritis dan berpikir kreatif (Costa, 1985). Di dalam penelitian ini hanya difokuskan pada aspek keterampilan berpikir kreatif.
Bagaimana peranan keterampilan berpikir dalam membangun mental dan kepribadian manusia?. Carin & Sund (1975); Gordun (1961) (Lawson, 1979), menyatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif merupakan komponen emosional yang lebih penting daripada intelektual, dan irasional. de Bono (2007), menggambarkan bagaimana kita harus berpikir kreatif untuk memperbaiki kehidupan, melakukan inovasi desain, menciptakan perubahan dan memperbaiki sistem. Liliasari (2005), mengemukakan bahwa keterampilan berpikir sangat menentukan dalam membangun kepribadian dan pola tindakan dalam kehidupan setiap insan Indonesia, karena itu pembelajaran sains perlu diberdayakan untuk mencapai maksud tersebut. Bertolak dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa keterampilan berpikir kreatif merupakan salah satu aspek kognitif yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran sains di kelas. Pengertian berpikir kreatif yang berhubungan dengan bidang pendidikan seperti yang dikemukakan oleh Lawson (1979)., & Taeffinger., et al (1982), bahwa berpikir kreatif adalah the process of 1) sensing difficulties problems, gaps ini information, missing element, something asked; 2) making guesses and formulating hypotheses about these deficiencies; 3) evaluating and testing these guesses and hyptheses; 4) posiibly revising and retesting them; and finally; 5) communicating the results. Bertolak dari definisi tersebut menunjukkan bahwa berpikir kreatif sebagai sesuatu proses kreatif, yaitu merasakan adanya kesulitan, masalah kesenjangan informasi, adanya unsur yang hilang dan ketidakharmonisan, mendefiniskan masalah secara jelas, membuat dugaan-dugaan tersebut dan kemungkinan perbaikannya, pengujian kembali atau bahkan mendefinisikan ulang masalah dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. De Bono (2007) mengemukakan bahwa berpikir kreatif adalah keterampilan : 1) merancang, 2) melakukan perubahan dan perbaikan, dan 4) memperoleh gagasan baru. Lipman (2003) (McGregor, 2007), mengemukakan bahwa keterampilan berpikir kreatif berhubungan dengan imagination, independence, experimentation, holism, expression, selftranscendence, surprise, generativity, maleuticity and inventiveness provide descriptor of valuable characteristics of creative thinking . Definisi ini lebih menekankan pada karakteristik berpikir kreatif diantaranya adalah imajinasi, eksperimentasi, holisme, ekspresi, transendensidiri, kejutan, pembangkitan, dan daya temu.
Menurut Colling & Amabile (1999); Runco & Chand, (1995); Nelson (2005); (Northcott, 2007), Creative thinking is linked to knowledge, motivation, problem finding, ide finding, and evalutaion. Hal ini menunjukkan bahwa berpikir kreatif itu terkait dengan pengetahuan, motivasi, menemukan masalah, menemukan ide atau gagasan baru, dan mengevaluasi. Menurut Liliasari (2005), keterampilan berpikir kreatif adalah kemampuan mengembangkan atau menemukan ide atau gagasan asli, estetis dan konstruktif, yang berhubungan dengan pandangan dan konsep serta menekankan pada aspek berpikir intuitif dan rasional khususnya dalam menggunakan informasi dan bahan untuk memunculkan atau menjelaskannya dengan perspektif asli pemikir. Northcott (2007), menyatakan bahwa ada dua proses mendasar, yang terjadi selama proses berpikir kreatif, yakni proses kognitif (apa yang kita tahu), dan nonkognitif (apa yang kita rasakan). Tan (2009) memandang keterampilan berpikir kreatif sebagai bentuk kecairan kognitif yang mendukung kemampuan seseorang merepresentasikan simbolsimbol. Berdasarkan dari beberapa definisi berpikir kreatif tersebut dapat dikatakan bahwa berpikir kreatif dicirikan oleh : merasakan adanya kesulitan, masalah kesenjangan informasi, adanya unsur yang hilang dan ketidakharmonisan, mendefiniskan masalah secara jelas, mendapat gagasan baru, membuat dugaan-dugaan dan kemungkinan perbaikannya, pengujian kembali atau bahkan mendefinisikan ulang masalah dan akhirnya mengkomunikasikan hasilnya. 2. Tahap-tahap dan Indikator-indikator berpikir kreatif dalam pembelajaran McGregor (2007) berpendapat bahwa keterampilan berpikir memiliki pola berpikir divegen yang di dalamnya: 1) bukan karakteristik dari pola pikir yang dimiliki beberapa orang yang berbakat; 2) berpikir kreatif dapat diterapkan melalui teknik yang bervriasi; 3) program berpikir kreatif dapat digunakan dalam mengembangkan keterampilan berpikir kreatif; 4) subjektivitas atau objektivitas dari proses pembelajaran dapat mempengaruhi pola berpikir kreatif; 5) kesadaran guru dalam mengembangkan keterampilan kreatif dapat membantu mereka untuk berkembang. Lawson (1979) mengungkapkan tiga tahap dan beberapa indikator dalam pengembangan berpikir kreatif dalam pembelajaran. Ketiga tahapan dan indikator tersebut sebagai berikut. Tahap Pertama, yakni meningkatkan antisipasi. Indikator-indikatornya adalah 1) menghadapi ambiguitas dan ketidakpastian; 2) mengajukan pertanyaan untuk meningkatkan dugaan dan harapan; 3) menciptakan kesadaran; 4) kebutuhan di masa datang atau kesulitan yang akan dihadapi; 5) membangun dari pengetahuan pebelajar yang sudah ada; 6) menstimulasi rasa
ingin tahu dan keinginan untuk tahu; 7) membuat rasa familiar yang aneh menjadi keanehan yang familiar; 8) membebaskan diri dari rangkaian hambatan; 9) melihat information yang sama dari sudut pandang yang berbeda; 10) mengajukan pertanyaan yang provokatif untuk membuat pebelajar berpikir tentang informasi yang ada dengan cara yang berbeda; 11) membuat pebelajar berpikir tentang informasi yang ada dengan cara yang berbeda; 12) membuat perkiraan dari informasi yang terbatas; 13) tujuan dari pelajaran dibuat jelas yang menunjukkan hubungan antara pebelajar yang diharapkan dan masalah sekarang atau yang akan datang; 14) hanya struktur yang cukup untuk memberikan petunjuk dan arahan; 15) mengambil langkah selanjutnya yang diketahui; dan 16) kesiapan fisik atau tubuh sebagai pemanasan untuk informasi yang akan disampaikan. Tahap kedua, pada tahap berhubungan dengan menemukan hal-hal yang diharapkan dan tidak diharapkan serta memperdalam ekspektasi. Indikator-indikatornya adalah ) meningkatnya kesadaran terhadap masalah dan kesulitan; 2) menerima keterbatasan yang membangun sebagai tantangan daripada membuat improvisasi secara sinis dengan apa yang tersedia; 3) mendorong karakteristik dan predisposisi kepribadian yang kreatif; 4) mempraktekkan proses pemecahan masalah secara kreatif dalam sebuah cara sistematis dalam menangani masalah dan informasi yang dimiliki; 5) mengelaborasi informasi dengan hati-hati; 6) menyajikan informasi yang tidak lengkap dan memberikan kesempatan pebelajar mengajukan masalah untuk melengakapi kesenjangan; 7) menumpangtindihkan elemen yang tidak relevan; 8) membuat pertanyaan terbuka; 9) Mencari kejujuran dan realisasi; 10) mengidentifikasi dan mendorong penerimaan keahlian baru untuk mencari informasi; 11) meningkatkan dan dengan sengaja membuat kejutan; dan 12) mendorong pebelajar melakukan visualisasi. Tahap ketiga, yakni menuju kearah yang lebih jauh dan terus maju. Indikator-indikatornya meliputi 1) bermain dengan ambiguitas; 2) memperdalam kesadaran terhadap sebuah masalah, kesulitan, atau kekurangan informasi; 3) mengakui potensi keunikan pebelajar; 4) meningkatkan perhatian/ keingintahuan terhadap suatu masalah; 5) menantang respons atau solusi yang konstruktif.; 6) melihat hubungan yang jelas antara informasi baru dan karir di masa yang datang; 7) menerima batasan dengan kreatif dan membangun; 8) menggali lebih dalam menuju kearah di balik sesuatu yang nyata dan diterima; 9) membuat pemikiran yang berbeda dan diterima, mengembangkan informasi yang diterima; 10) mendorong solusi elegan, solusi dari benturan konflik dan misteri yang tidak terpecahkan; 11) melakukan eksperimen; 12) membuat keanehan yang familiar atau sesuatu familiar yang aneh; 13) mendorong proyeksi masa depan; 14) mengajak pada ketidakkemunkinan; 15) menciptakan humor dan melihat sesuatu yang lucu dalam informasi yang diberikan; 16) mendorong penilaian yang
berbeda dan penggunaan beberapa prosedur menyelesaikan masalah; 17) menghubungkan informasi yang satu dengan informasi dari disiplin yang berbeda; 18) melihat informasi yang sama dengan beberapa cara yang berbeda; 19) mendorong manipulasi ide dan / atau objek; 20) merumuskan hipotesis dan mengujinya; dan 21) berkonfrontasi dan meneliti paradoks. Iriany, dkk (2009), mengememukakan ada empat aspek keterampilan berpikir kreatif, yakni: 1) membangkitkan keingintahuan dan hasrat ingin tahu; 2) membangun pengetahuan yang telah ada pada siswa; 3) memandang informasi dari sudut pandang yang berbeda; dan 4) meramal dari informasi yang terbatas. Bertolak dari beberapa definisi dan indikator berpikir kreatif tersebut maka di dalam penelitian ini dibatasi pada indikator-indikator berpikir kreatif mengembangkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik, membangkitkan keingintahuan dan hasrat ingin tahu, memandang informasi dari sudut pandang yang berbeda, memprediksi dari informasi yang terbatas, merumuskan masalah, merumuskan hipotesis berdasarkan fenomena yang diamati fenomena yang diamati serta menguji hipotesis. 3. Fase Berpikir Kreatif Dalam berpikir kreatif proses yang terjadi ternyata melalui beberapa fase tertentu. Suatu ide tidak dapat dengan tiba-tiba muncul di dalam benak kita. Ide-ide terjadi setelah berbagai macam simbol diolah di alam bawah sadar kita. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam terjadinya berpikir kreatif mau tidak mau akan melewati beberapa fase. Menurut Wallas (1926); Chauhan (1978); & Munandar (2009), mengemukakan fase-fase perkembangan berpikir kreatif yang dilaporkan oleh para novelis, artis, dan komposer. Fase-fase perkembangan tersebut adalah 1) persiapan, 2) inkubasi, 3) iluminasa, dan 4) revisi. a. Fase persiapan Dalam fase ini, individu memusatkan perhatian pada masalah, membangkitkan keingintahuan dan hasrat ingin tahu, mengorganisasikan data, merumuskan masalah dan memprediksi informasi yang terbatas, mengemukakan hipotesis yang relevan dengan masalah yang dihadapi. b. Fase inkubasi Pada fase inkubasi, individu membangun pengetahuan yang telah dimiliki untuk menguji hipotesis dan menyusun kembali serta mentes ide-ide dengan memandang informasi yang berbeda, mengajukan pertanyaan. Pada fase ini individu benar-benar melibatkan diri dan
mengalami masalah yang dihadapi. Sekalipun nampak tidak ada kegiatan serat kemajuan yang nyata, namun masalah tersebut sedang dalam penyelesaian secara tidak disadari. c. Fase iluminasi Pada fase ini individu tiba-tiba memperoleh suatu inspirasi tentang tema dan hubungan antara berbagai komponen dari problem yang dihadapi. d. Fase revisi Fase revisi merupakan fase yang terakhir di dalam proses berpikir kreatif. Pada fase ini individu memikirkan, mengevaluasi, melakukan perubahan dan perbaikan masalah, menyusun hipotesis kembali. 4. Prinsip-prinsip Umum Berpikir Kreatif Menurut Perkins (Costa, 1985) ada enam prinsip umum berpikir kreatif sebagai berikut. a. Estitika berpikir kreatif melibatkan standar praktis. Orang kreatif berusaha ingin tahu sesuatu yang mendadasar, luas, dan kuat. Sebagai contoh Einstein dengan estitikanya menuntunya menolak teori kuantum, walaupun pada mulanya memberikan kontribusi terhadap perkembangan teorinya. b. Berpikir kreatif tergantung kepada tujuan yang akan dicapai. Orang kreatif mengeksplorasi tujuan dan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam mengenali sifat masalah dan menemukan suatu solusi yang standar, dan bersedia untuk mengubah pendekatan dikemudian hari, dan bahkan mendefiniskan ulang masalah apabila diperlukan. c. Berpikir kreatif lebih cenderung tidak terpusat pada satu kompetensi. Orang kreatif mempertahankan standar yang tinggi, menerima kebingunan, ketidakpastian dan resiko kegagalan yang lebih tinggi sebagai bagian dari proses, dan belajar untuk melihat kegagalan, dan bahkan menarik dan menantang. d. Berpikir kreatif lebih banyak bersifat subjektif. Orang kreatif mempertimbangkan berbagai sudut pandang berbeda, melakukan evaluasi, dan menemukan ide-ide yang praktis. e. Berpikir kreatif tergantung pada instrinsik daripada ekstrinsik dan motivasi. Orang kreatif dapat memilih apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukan. Mereka memahami tugas sebagaimana kompetensi mereka miliki, melihat apa yang mereka lakukan sebagai sesuatu yang berharga dalam dirinya sendiri, dan menikmati kegiatan yang dilakukan.
5. Tahap Pembelajaran Lawson (1979) mengemukakan tiga tahap dalam mengajar untuk mengembangkan keterampilan berpikir kreatif. Ketiga tahap tersebut adalah sebagai berikut. Tahap pertama. Sebelum keterampilan berpikir kreatif dapat diaktifkan, sesuatu harus meningkatkan kenerja ke antisipasi (ancitipation) dan harapan dan mempersiapkan pelajar untuk melihat hubungan yang jelas antara apa yang ia diharapkan belajar dan/karir masa depannya. Tahap kedua. Diperlukan untuk membantu para pelajar untuk membangkitkan keingintahuan dan hasrat ingin tahu, membangun pengetahuan yang telah dimiliki peserta didik, mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah dan merumuskan dugaan-dugaan sementara, melakukan prediksi dari informasi yang terbatas, memandang informasi dari berbagai sudut pandang yang berbeda, memperoleh informasi lebih lanjut, perjumpaan yang tak terduga dan terus memperdalam ekspektasi. Tahap ketiga. Memberikan latihan dalam melakukan sesuatu dengan informasi baru, baik pada saat itu sedang diperoleh atau sesudahnya. Dasar pemikiran model pembejaran tersebut di atas menurut Lawson (1979) adalah 1) terdapat kecenderungan orang lebih suka belajar kreatif dengan mengeksplorasi, mempertanyakan, bereksperimen, manipulasi, mengatur hal-hal, pengujian, dan memodifikasi gagasan atau solusi; 2) beberapa individu memiliki preferensi yang kuat untuk belajar kreatif, peserta didik termotivasi belajar apabila diizinkan untuk menggunakan keterampilan berpikir kreatif mereka dan cara-cara kreatif mereka memproses informasi untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan membuat sedikit kemajuan ketika guru bersikeras mengajar secara otoritas; dan 3) membangun motivasi peserta didik dalam hal: a) mencari informasi; mengidentifikasi kesulitan atau kesenjangan informasi; c) mencari solusi alternatif, membuat dugaan atau perkiraan, d) merumuskan hipotesis, memikirkan kemungkinan, dan meramalkan; e) melakukan pengujian, mengubah, tes ulang, dan menyempurnakan dari hipotesis atau produk kreatif lainnya; dan f) mengkomunikasi hasil. B. Pemahaman Konsep Pemahaman konsep merupakan kemampuan menangkap makna dan arti dari materi pelajaran yang dipelajari oleh peserta didik (Pickard, 2007). Dari pernyataan ini, peserta didik dituntut tidak sebatas mengingat atau merecall kembali pelajaran. Namun lebih dari itu peserta didik mampu mendefinisikan. Hal ini menunjukkan peserta didik telah memahami materi pelajaran walau tidak berubah. Pemahaman meliputi tiga aspek yaitu :
1. Translasi, meliputi dua komponen : 1) menerjemahkan sesuatu dari bentuk abstrak ke bentuk yang lebih kongkret; 2) menerjemahkan suatu simbol kedalam bentuk lain seperti : menerjemahkan tabel, grafik, simbol matematik dan sebagainya. 2. Interpretasi, meliputi tiga kemampuan : 1) membedakan antara kesimpulan-kesimpulan yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan; 2) memahami rangka suatu pekerjaan secara keseluruhan; dan 3) memahami dan menafsirkan isi berbagai macam bacaan. 3. Ekstrapolasi meliputi tiga kemampuan : 1) menyimpulkan dan menyatakan lebih eksplisit; 2) memprediksi konsekuensi-konsekuensi dari tindakan yang digambarkan dari sebuah komunikasi; 3) sensitif atau peka terhadap faktor yang mungkin membuat prediksi menjadi akurat. Menurut Rosser (Dahar,1996) konsep adalah suatu abstrak yang mewakili satu kelas objekobjek kejadian, kegiatan-kegiatan atau hubungan-hubungan yang mempunyai atribut-atribut yang sama. Oleh karena itu, orang mengalami stimulus-stimulus yang berbeda-beda, orang membentuk konsep sesuai dengan pengelompokan stimulus-stimulus dengan cara tertentu. Karena konsep-konsep itu dalah abstraksi berdasarkan pengalaman dan karena tidak ada dua orang yang memiliki pengalaman yang sama persis, maka konsep-konsep yang dibentuk orang berbeda juga. Walau berbeda tetapi cukup untuk berkomunikasi menggunakan nama-nama yang diberikan pada konsep-konsep itu yang telah diterima berasamanya. Menurut Dahar (1996), konsep merupakan kategori-kategori yang kita berikan pada stimulus-stimulus yang ada di lingkungan kita. Konsep-konsep menyediakan skema-skema terorganisasi untuk menentukan hubungan di dalam dan di antara kategori-kategori. Konsep-konsep merupakan dasar bagi proses-proses mental yang lebih tinggi untuk merumuskan prinsip-prinsip dan generalisai-generalisasi.
Peningkatan yang terjadi sebelum dan sesudah pembelajaran dihitung dengan rumus gain ternormalisasi (N-Gain) sebagai berikut. (Meltzer, 2002; Colleta,V.P & Philips.J.A, 2005)
g
keterangan:
S post
S post S pre S maks S pre
.................................................(8)
= Skor tes akhir
S pre
= Skor tes awal = Skor maksimum
S maks
Kriteria tingkat N Gain adalah sebagai berikut. (Meltzer, 2002) Tabel 3.9. Kategori Tingkat N Gain Batasan g > 0,7 0,3 g 0,7 g< 0,3 Kategori Tinggi Sedang Rendah
Setelah nilai rata-rata gain yang dinormalisasi untuk kedua kelompok diperoleh, maka selanjutnya dibandingkan untuk melihat perbedaan peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kreatif . Jika nilai rata-rata gain yang dinormalisasi dari suatu pembelajaran lebih tinggi dari nilai rata-rata gain yang dinormalisasi dari pembelajaran lainnya, maka dikatakan bahwa pembelajaran tersebut lebih efektif dalam peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan berpikir kreatif dibandingkan pembelajaran lain (Ogilvie,200).
a. Data Pemahaman Konsep Untuk memperoleh data pemahaman konsep calon guru fisika pada materi gelombang dan optika dengan menggunakan instrumen pemahaman konsep. Instrumen ini digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep calon guru fisika sebelum dan sesudah pembelajaran berbasis simulasi komputer pada kelompok eksperimen dan pembelajaran konvensional pada kelompok kontrol. Instrumen tes untuk pemahaman konsep ini mencakup ranah kognitif yang terdiri atas tiga aspek, yaitu pemahaman menerjemahkan (translation), pemahaman menafsirkan (interpretation), dan pemahaman mengekstrapolasi (extrapolation). Instrumen untuk tes tertulis ini berbentuk tes objektif (pilihan ganda) mengenai konsep
gelombang dan optika. Instrumen tes yang digunakan pada saat tes awal dan tes akhir merupakan instrumen tes yang sama.
Anda mungkin juga menyukai
- Kurikulum HumanistikDokumen4 halamanKurikulum HumanistikMuhammad Fadhli0% (1)
- Pengembangan KurikulumDokumen5 halamanPengembangan KurikulumAlfira HuwaidaBelum ada peringkat
- Makalah MPK Indah Agustriyani-1Dokumen17 halamanMakalah MPK Indah Agustriyani-1Indah AgustriyaniBelum ada peringkat
- Pendidikan Karakter Berbasis Multiple IntelligenceDokumen10 halamanPendidikan Karakter Berbasis Multiple IntelligenceSurya FahroziBelum ada peringkat
- PLH Atau Ekopedagogik - Kelompok 6Dokumen21 halamanPLH Atau Ekopedagogik - Kelompok 6febrianto rizalBelum ada peringkat
- Tugas Implementasi KurikulumDokumen2 halamanTugas Implementasi KurikulumMoh ZaldiBelum ada peringkat
- Gaya BelajarDokumen5 halamanGaya BelajarSetiyo PrajokoBelum ada peringkat
- Pendekatan Pembelajaran KonstruktivismeDokumen21 halamanPendekatan Pembelajaran Konstruktivismemariaelfrida denoBelum ada peringkat
- Model Pembelajaran Discovery LearningDokumen14 halamanModel Pembelajaran Discovery LearningMuhammad IqbalBelum ada peringkat
- Liana Widya Astuti - Group Investigation - PPTDokumen11 halamanLiana Widya Astuti - Group Investigation - PPTLianaBelum ada peringkat
- Perspektif Islam Terhadap Budaya SelametanDokumen37 halamanPerspektif Islam Terhadap Budaya SelametanLora AgustianaBelum ada peringkat
- Contoh Review Jurnal PendidikanDokumen1 halamanContoh Review Jurnal PendidikanRida Rasyida100% (1)
- Faktor Faktor Penghambat Pelaksanaan Profesionalisasi Guru Di IndonesiaDokumen2 halamanFaktor Faktor Penghambat Pelaksanaan Profesionalisasi Guru Di IndonesiaHerlina SiburianBelum ada peringkat
- Instrumen Karakter MahasiswaDokumen11 halamanInstrumen Karakter MahasiswaMahendra PrasetyoBelum ada peringkat
- Media Pembelajaran Aqidah AkhlakDokumen3 halamanMedia Pembelajaran Aqidah AkhlakQƧэMakiNtEЯLukДkaЯnaMuDaNkuTэЯ LДNjuЯmэNciNteMu'TuKƧeLaMaNyДBelum ada peringkat
- Sukiman - Pengembangan Media PembelajaranDokumen265 halamanSukiman - Pengembangan Media PembelajaranPemuda Desa PucanglabanBelum ada peringkat
- Penelitian Tindakan KelasDokumen36 halamanPenelitian Tindakan KelasFred Nuhuna TBelum ada peringkat
- Kepedulian SosialDokumen7 halamanKepedulian SosialZainal Abid100% (1)
- Mengeksplorasi Teori-Teori Pengajaran Demokratis Rudolf DreikursDokumen24 halamanMengeksplorasi Teori-Teori Pengajaran Demokratis Rudolf DreikursFU Jin100% (1)
- Konseptual Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat TinggiDokumen26 halamanKonseptual Pembelajaran Berorientasi Keterampilan Berpikir Tingkat TinggiVirakiswandaBelum ada peringkat
- Herry K. Katu (PERENCANAAN) PDFDokumen13 halamanHerry K. Katu (PERENCANAAN) PDFHerry KristianBelum ada peringkat
- Tugas Makalh PBL Abad 21Dokumen11 halamanTugas Makalh PBL Abad 21Arif Rahmat HidayatBelum ada peringkat
- The Pembelajaran PKN Di SDDokumen9 halamanThe Pembelajaran PKN Di SDDaniaBelum ada peringkat
- Bab 11 PSP Merevisi Materi Pembelajaran (Revising Instructional Materials)Dokumen17 halamanBab 11 PSP Merevisi Materi Pembelajaran (Revising Instructional Materials)Ochim Mihar PungpangBelum ada peringkat
- Makalah Alat Pendidikan Menurut Ki Hajar DewantaraDokumen1 halamanMakalah Alat Pendidikan Menurut Ki Hajar DewantaraAmran HalimBelum ada peringkat
- Contoh Jurnal PTKDokumen10 halamanContoh Jurnal PTKAgung Perdana Jaken CuyBelum ada peringkat
- Makalah Sekolah Dan Dunia KerjaDokumen2 halamanMakalah Sekolah Dan Dunia KerjaYuzran Zhymaldazz ChancadBelum ada peringkat
- Hasil BelajarDokumen9 halamanHasil BelajararyaBelum ada peringkat
- Landasan Pengembangan KurikulumDokumen19 halamanLandasan Pengembangan KurikulumDhea SagithaBelum ada peringkat
- Proposal Skripsi Tentang Sekolah AlamDokumen36 halamanProposal Skripsi Tentang Sekolah AlamAkhmad RiyadiBelum ada peringkat
- Pembelajaran Tematik IntegratifDokumen184 halamanPembelajaran Tematik Integratifanon_572156840Belum ada peringkat
- GK Tipe Berpikir Siswa Field Dependent Dan Field Independent Dalam Menyelesaikan Soal Kesebangunan Di KelasIX MTSN KrianDokumen10 halamanGK Tipe Berpikir Siswa Field Dependent Dan Field Independent Dalam Menyelesaikan Soal Kesebangunan Di KelasIX MTSN KrianINDRAKURNIAWANSIRBelum ada peringkat
- Bullying Dan SolusinyaDokumen13 halamanBullying Dan SolusinyaAfina Larasati KamilBelum ada peringkat
- Pedoman Wawancara Pendidikan Agama IslamDokumen154 halamanPedoman Wawancara Pendidikan Agama IslamUjang Ruhiyat IIBelum ada peringkat
- Desain Kurikulum Berbasis BudayaDokumen12 halamanDesain Kurikulum Berbasis BudayaFitria HandayaniBelum ada peringkat
- Kel 4 Pembelajaran Tematik SDDokumen34 halamanKel 4 Pembelajaran Tematik SDZurotulBelum ada peringkat
- Model PembelajaranDokumen10 halamanModel PembelajaranRatih DewantiBelum ada peringkat
- RPP Bab 13Dokumen10 halamanRPP Bab 13Suriyadi AliBelum ada peringkat
- Hubungan Pancasila Dan IPSDokumen19 halamanHubungan Pancasila Dan IPSdon juanzxBelum ada peringkat
- Peningkatan Mutu Penilaian-Soal HOTsDokumen33 halamanPeningkatan Mutu Penilaian-Soal HOTsInci HarisBelum ada peringkat
- Evaluasi PembelajaranDokumen18 halamanEvaluasi PembelajaranDisha RamfineliBelum ada peringkat
- Menciptakan Sekolah Berkarakter PDFDokumen8 halamanMenciptakan Sekolah Berkarakter PDFPratiwi NurussalamahBelum ada peringkat
- RPP Kelas 2 SD Cipocok JayaDokumen8 halamanRPP Kelas 2 SD Cipocok JayaWisnu WhisyaBelum ada peringkat
- Makalah Inovasi Blended LearningDokumen9 halamanMakalah Inovasi Blended LearningFajar SidiqBelum ada peringkat
- Proposal PenelitianDokumen20 halamanProposal PenelitianMega SeptianaBelum ada peringkat
- Facilitating Learning Adalah Proses Atau Peran Di Mana Seseorang, Seperti S - 20231031 - 231102 - 0000Dokumen6 halamanFacilitating Learning Adalah Proses Atau Peran Di Mana Seseorang, Seperti S - 20231031 - 231102 - 0000Enok SuryatiBelum ada peringkat
- Penulisan Butir Soal, 260208Dokumen56 halamanPenulisan Butir Soal, 260208dlavegaburgerBelum ada peringkat
- RPP Model Talking ChipsDokumen2 halamanRPP Model Talking ChipsIzkar Mie Kare100% (1)
- Kel 7 Filsafat Idealisme, Realisme, Dan MaterialismeDokumen12 halamanKel 7 Filsafat Idealisme, Realisme, Dan MaterialismeseptianeriBelum ada peringkat
- Rps Seni Budaya Dan Prakarya 2021Dokumen5 halamanRps Seni Budaya Dan Prakarya 2021Rhesti Laila ulfaBelum ada peringkat
- Meningkatkanhasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran TGT Dalam Mata Pelajaran PKNDokumen8 halamanMeningkatkanhasil Belajar Siswa Dengan Menggunakan Model Pembelajaran TGT Dalam Mata Pelajaran PKNdavid setiawanBelum ada peringkat
- Finalisasi Led Paud Fix 2021Dokumen149 halamanFinalisasi Led Paud Fix 2021Guru Terbang ChannelBelum ada peringkat
- Makalah Model Pembelajaran Cooperative Learning Kel 6Dokumen8 halamanMakalah Model Pembelajaran Cooperative Learning Kel 6Aditya AlesisBelum ada peringkat
- Proposal Baru 2Dokumen40 halamanProposal Baru 2Muh Dimas AnugrahBelum ada peringkat
- Kel 6 AmpDokumen13 halamanKel 6 Ampnadiatussolikhah100% (1)
- Berfikir KritisDokumen6 halamanBerfikir KritisWahyuni Chiety EuroBelum ada peringkat
- Mahasiswa Kritis EssayDokumen5 halamanMahasiswa Kritis EssayHarya Dimas HendrasmaraBelum ada peringkat
- Makalah Berfikir KritisDokumen16 halamanMakalah Berfikir Kritisdita puspitaBelum ada peringkat
- Menumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Pada SiswaDokumen6 halamanMenumbuhkan Kemampuan Berpikir Kritis Pada SiswaJerry PrambodiaBelum ada peringkat
- 4 adımda problem çözme: Psikoloji ve karar biliminden en iyi stratejileri kullanarak sorunları anlama ve çözmeDari Everand4 adımda problem çözme: Psikoloji ve karar biliminden en iyi stratejileri kullanarak sorunları anlama ve çözmeBelum ada peringkat