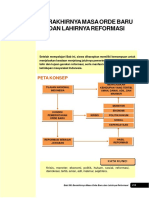Pembangunan Gedung DPR
Diunggah oleh
unarimaDeskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Pembangunan Gedung DPR
Diunggah oleh
unarimaHak Cipta:
Format Tersedia
Pembangunan Gedung DPR
Tak ada yang salah kecuali tidak etis dengan dilanjutkannya rencana pembangunan gedung baru DPR. Sempat tertunda, akhirnya semua fraksi setuju.
Namun, selain tidak etis, keputusan itu ironis dan absurd. Gedung dibangun di tengah jeritan kemiskinan rakyat, di tengah dambaan rakyat terbebas dari merosotnya kinerja tiga lembaga demokratis, termasuk rendahnya balutan dugaan korupsi di lembaga DPR. Melanjutkan rencana pembangunan gedung baru 36 lantai ibarat menutup empati dan simpati dengan kondisi rakyat, menafikan kritik perilaku tak terpuji, seperti pelesiran dengan nama studi banding, malas menghadiri sidang, rendahnya produk legislasi, atau keukeuh-nya memperjuangkan peningkatan fasilitas pribadi. Pernyataan bahwa sudah dianggarkan, perlu kelengkapan sarana dan keamanan kerja dalam ranah kondisi saat ini menegaskan asumsi absurd dan ironi kinerja DPR. Mereka bergeming atas biaya Rp 1,6 triliun itu senilai jaminan kesehatan masyarakat bagi 22 juta penduduk miskin. Satu anggota beserta staf ahli menempati ruang kerja seluas 120 meter persegi dianggap sudah seharusnya. Keberatan bukannya belum pernah disampaikan. Departemen Teknis Kementerian Pekerjaan Umum bahkan menyatakan hasil pemeriksaan visual dan detail atas gedung lama, Nusantara I, belum mengkhawatirkan. Sikap yang berkembang ialah, menjadi wakil rakyat tak lebih dari profesi dalam arti memperoleh bayaran. Lebih parah lagi lantas dihidupi sikap dan semangat segera balik modal setelah kantong dan tenaga terkuras mengejar jabatan wakil rakyat. Berpolitik sebagai pengorbanan dan panggilan hanya dalam rumusan ideal-utopis. Gambaran umum suramnya kinerja DPR tidak mengecualikan masih banyaknya anggota DPR yang peduli akan keluhuran berpolitik. Namun, justru karena itu yang muncul ke permukaan adalah kinerja kurang terpuji. Wajah institusi wakil rakyat terlihat buram. Kesan itu, antara lain, dipertegas dalam persetujuan rencana pembangunan gedung baru. Semangat menyatu dengan jeritan rakyat pun ditinggalkan. Dalam konteks ini yang kita rasakan lebih mendesak adalah ruwatan penghuninya, bukan bangunan gedung fisik. Meruwat berarti memulihkan kembali seperti keadaan semula. Meruwat lembaga perwakilan rakyat berarti mengembalikan semangat dasar dan misi pokok kedudukan wakil rakyat, memaknai kembali kesucian/keluhuran berpolitik. Konkretnya, tempatkan rakyat sebagai pusat sensitivitas yang diwujudkan dengan perhatian dan hati, satukan dengan jeritan rakyat. Niscaya, dengan kembalinya semangat dan hati prorakyat, ada kebesaran hati membatalkan rencana pembangunan gedung itu; justru ketika hari-hari belakangan ini rakyat butuh topangan atas lemahnya kepemimpinan dan buruknya kinerja kabinet.
Harga Tinggi Guncang Tunisia
Gelombang kerusuhan terus berlangsung di Tunis, ibu kota Tunisia, sebagai protes terhadap pengangguran, harga-harga yang melambung tinggi, dan korupsi. Pemerintahan Presiden Zine El Abidine Ben Ali, yang sudah berkuasa 23 tahun, berusaha menggunakan pendekatan represif untuk menghentikan gelombang kerusuhan. Aparat kepolisian, misalnya, melepaskan tembakan secara brutal, yang menurut aktivis buruh menewaskan paling tidak 50 orang sejak akhir pekan lalu. Versi pemerintah menyebut angka 21 orang tewas. Pendekatan kekerasan itu juga diperlihatkan dengan mengerahkan tank dan panser. Jam malam dan larangan ke luar rumah diberlakukan di Tunis hari Kamis kemarin. Namun, pendekatan represif ternyata tidak efektif, bahkan kontraproduktif. Tindakan represif itu justru memprovokasi masyarakat, terutama kaum muda, untuk meningkatkan aksi protes. Gelombang protes yang terus merebak luas membuat posisi Presiden Ben Ali yang berusia 74 tahun semakin terdesak. Pemimpin yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tak berdarah itu berusaha mengambil hati rakyat dengan membebaskan semua pemrotes yang ditahan, sekaligus memecat Menteri Dalam Negeri Rafik Belhaj Kacem. Mendagri Kacem dianggap ikut bertanggung jawab atas jatuhnya banyak korban tewas akibat kebrutalan polisi, yang memang berada di bawah kewenangan Kementerian Dalam Negeri. Namun, pemecatan Kacem dan pembebasan semua pemrotes yang ditahan tidak meredakan amukan kemarahan rakyat terhadap persoalan pengangguran, harga-harga tinggi, korupsi, dan tindakan represi penguasa. Masyarakat yang tertekan dan frustrasi oleh harga-harga yang melambung tinggi dan angka pengangguran sampai 30 persen melampiaskan kemarahan dengan melakukan perusakan dan kerusuhan di jalan-jalan. Pemerintahan Ben Ali tampak kewalahan dan tampak kehilangan cara untuk menghadapi gelombang protes yang dirasakan paling keras selama 23 tahun kekuasaannya. Para pengamat cenderung berspekulasi, gelombang protes yang sudah berlangsung beberapa pekan terakhir tidak hanya menggoyahkan, tetapi bisa saja menjatuhkan pemerintahan Ben Ali. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya sudah hilang karena Ben Ali gagal menciptakan lapangan kerja, sementara praktik korupsi dibiarkan merebak luas. Banyak kasus dalam sejarah, sebuah pemerintahan ambruk karena gagal membangun ekonomi. Mulai muncul pertanyaan, apakah Presiden Ben Ali yang sudah berkuasa 23 tahun dan kini berusia 74 tahun mampu melepaskan diri dari kemelut sekarang ini. Jauh lebih penting lagi, bagaimana Tunisia mampu melewati ujian berat ini agar terhindar dari kekacauan yang lebih buruk. Kemelut di Tunisia semakin menarik diikuti dari dekat.
Setahun Gempa DIY-Jateng
Hari ini tanggal 26 Mei diperingati tepat satu tahun terjadinya gempa di DIY dan Jawa Tengah. Berbagai acara digelar, dengan seremoni puncak yang dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersamaan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Tentu yang lebih penting didalami adalah persoalan substansial di sekitar bencana alam yang menghancurkan ribuan rumah penduduk, tempat usaha, sekolah, maupun fasilitas umum lainnya. Seberapa jauh program pemulihan telah berjalan, berapa persen gedung sekolah yang dibangun kembali, sampai yang bersifat nonfisik seperti masalah sosial dan psikologis yang menimpa masyarakat sebagai dampak gempa. Sejauh ini, pemulihan berjalan relatif cepat. Hal itu berkat dukungan pemerintah lewat penyaluran dana maupun gerak masyarakat lewat berbagai kegiatan seperti penghimpunan dana, bantuan renovasi dan pembangunan kembali sekolah-sekolah, serta masih banyak lagi. Namun semua belum bisa selesai dalam waktu setahun. Masih banyak yang harus diselesaikan, dan itu memerlukan manajemen yang baik serta koordinasi antarlembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah, domestik maupun asing. Yang melegakan adalah partisipasi aktif dari banyak lembaga untuk menangani problem pascagempa. Tidak saja berupa dana, tetapi juga langkah nyata. Banyak pelajaran berharga bisa dipetik. Kita tahu pada awal terjadi gempa, pada masa tanggap darurat, segala sesuatunya kurang berjalan mulus, termasuk dalam penanganan korban di rumah sakit. Juga ketika terjadi kekacauan data jumlah rumah rusak, bahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan janji yang tak masuk akal, yakni bantuan Rp 35 juta per kepala keluarga yang rumahnya roboh. Kekisruhan koordinasi terjadi, karena setiap lembaga ingin bergerak sendirisendiri. Akibatnya ada satu daerah yang cepat tertangani, namun ada daerah yang terlantar. Dalam batas-batas tertentu hal itu wajar terjadi, tetapi selebihnya harus diakui sebagai kelemahan. Ternyata memang rumit dan butuh manajemen yang rapi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai pengawasan. Berkembang pengetahuan baru tentang manajemen bencana, dan itulah yang harus dibina sejak awal sebagai syarat bekal aparat pemerintah serta para relawan kemanusiaan dari berbagai lembaga. Ketersediaan dana saja tidak cukup, karena operasional di lapangan sangat membutuhkan keterampilan khusus, terutama dalam pengelolaan dan pengorganisasian. Soal dana juga rawan penyelewengan, sehingga bagaimana mekanisme pengawasan perlu diatur sedemikian rupa. Yang sangat dibutuhkan adalah transparansi. Bagaimana pun ada hikmah tersembunyi di balik setiap musibah. Kita makin menyadari, selain tindakan tanggap darurat dan pemulihan, yang tidak kalah penting adalah kesiapan masyarakat terutama untuk memperkecil risiko terjadinya bencana. Inilah yang dikenal dengan istilah risk reduction management. Misalnya sosialisasi tentang langkah-langkah preventif dan tindakan cepat ketika terjadi bencana alam. Dan, semua itu harus melibatkan masyarakat. Konsep yang dikembangkan selalu mengarah pada kegiatan berbasis masyarakat. Maka diadakanlah misalnya simulasi bagaimana penduduk menyelamatkan diri ketika terjadi tsunami atau letusan gunung Merapi.
Biografi Ki Hajar Dewantara
Ki Hajar Dewantara Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889.Terlahir dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak saat itu, ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. Ia menamatkan Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda) Kemudian sempat melanjut ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera), tapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar antara lain Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, Tjahaja Timoer dan Poesara. Pada masanya, ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam dan patriotik sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya.
Selain ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Pada tahun 1908, ia aktif di seksi propaganda Boedi Oetomo untuk mensosialisasikan dan menggugah kesadaran masyarakat Indonesia pada waktu itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.
Kemudian, bersama Douwes Dekker (Dr. Danudirdja Setyabudhi) dan dr. Cipto Mangoenkoesoemo, ia mendirikan Indische Partij (partai politik pertama yang beraliran nasionalisme Indonesia) pada tanggal 25 Desember 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka.
Mereka berusaha mendaftarkan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum pada pemerintah kolonial Belanda. Tetapi pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg berusaha menghalangi kehadiran partai ini dengan menolak pendaftaran itu pada tanggal 11 Maret 1913. Alasan penolakannya adalah karena organisasi ini dianggap dapat membangkitkan rasa nasionalisme rakyat dan menggerakan kesatuan untuk menentang pemerintah kolonial Belanda. Kemudian setelah ditolaknya pendaftaran status badan hukum Indische Partij ia pun ikut membentuk Komite Bumipoetra pada November 1913. Komite itu sekaligus sebagai komite tandingan dari Komite Perayaan Seratus Tahun Kemerdekaan Bangsa Belanda. Komite Boemipoetra itu melancarkan kritik terhadap Pemerintah Belanda yang bermaksud merayakan seratus tahun bebasnya negeri Belanda dari penjajahan Prancis dengan menarik uang dari rakyat jajahannya untuk membiayai pesta perayaan tersebut. Sehubungan dengan rencana perayaan itu, ia pun mengkritik lewat tulisan berjudul Als Ik Eens Nederlander Was (Seandainya Aku Seorang Belanda) dan Een voor Allen maar Ook Allen voor Een (Satu untuk Semua, tetapi Semua untuk Satu Juga). Tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda yang dimuat dalam surat kabar de Expres milik dr. Douwes Dekker itu antara lain berbunyi: "Sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang kita sendiri telah merampas kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Pikiran untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka dan sekarang kita garuk pula kantongnya. Ayo teruskan penghinaan lahir dan batin itu! Kalau aku seorang Belanda. Apa yang menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku terutama ialah kenyataan bahwa bangsa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu pekerjaan yang ia sendiri tidak ada kepentingannya sedikitpun". Akibat karangannya itu, pemerintah kolonial Belanda melalui Gubernur Jendral Idenburg menjatuhkan hukuman tanpa proses pengadilan, berupa hukuman internering (hukum buang) yaitu sebuah hukuman dengan menunjuk
Anda mungkin juga menyukai
- Membedakan Fakta Dan Opini Pada Editorial Dengan Membaca IntensifDokumen4 halamanMembedakan Fakta Dan Opini Pada Editorial Dengan Membaca IntensifTiean Bocah SupperBelum ada peringkat
- Revolusi MelatiDokumen6 halamanRevolusi MelatiFahmi MandelaBelum ada peringkat
- Ekonomi PembangunanDokumen5 halamanEkonomi Pembangunanwalialili 75Belum ada peringkat
- Pamflet Solidaritas: Agenda Rakyat Menegakkan KeadilanDokumen38 halamanPamflet Solidaritas: Agenda Rakyat Menegakkan KeadilanInstitut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI)Belum ada peringkat
- Membela Korban Pembangunan Waduk Kedung OmboDokumen6 halamanMembela Korban Pembangunan Waduk Kedung OmboLadhina Restilia AndreaniBelum ada peringkat
- Cover MuhadjirDokumen39 halamanCover MuhadjirEdi SuryadiBelum ada peringkat
- Susi Astirinah - Tugas PKN - Wawasan NusantaraDokumen2 halamanSusi Astirinah - Tugas PKN - Wawasan NusantaraSusi AstrinahBelum ada peringkat
- Tugas PKNDokumen10 halamanTugas PKNAzhura WasalwaaBelum ada peringkat
- AZZAHROTUN NAFIISAH - 21901091132 - UTS Administrasi PembangunanDokumen5 halamanAZZAHROTUN NAFIISAH - 21901091132 - UTS Administrasi PembangunanIwan TBBelum ada peringkat
- Tugas 2Dokumen10 halamanTugas 2sdn16 tanjunglagoBelum ada peringkat
- Tugas 2 Pend. KewarganegaraanDokumen8 halamanTugas 2 Pend. KewarganegaraanSayuti NainggolanBelum ada peringkat
- Reformasi Merupakan Suatu Gerakan Yang Menghendaki Adanya Perubahan Kehidupan BermasyarakatDokumen4 halamanReformasi Merupakan Suatu Gerakan Yang Menghendaki Adanya Perubahan Kehidupan BermasyarakatnindifkBelum ada peringkat
- Makalah ReformasiDokumen17 halamanMakalah Reformasibaywilliem002juliBelum ada peringkat
- Sikap Terhadap Pengaruh Dan Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa Dan NegaraDokumen12 halamanSikap Terhadap Pengaruh Dan Implikasi Globalisasi Terhadap Bangsa Dan NegaraJan Eduart SipayungBelum ada peringkat
- 15 The Promotion of Human Development and Human RightsDokumen9 halaman15 The Promotion of Human Development and Human RightsNdyka BongBelum ada peringkat
- Demokrasi Dan PembangunanDokumen28 halamanDemokrasi Dan PembangunanFauziah Sang Scientist100% (1)
- Tugas Kompetensi 1Dokumen6 halamanTugas Kompetensi 1Alfi SyahriBelum ada peringkat
- Resume Makalah PKNDokumen12 halamanResume Makalah PKNhabibahhabibah1208Belum ada peringkat
- Makalah Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Dan Sosial Pasca 21 Mei 1998Dokumen17 halamanMakalah Sejarah Perkembangan Politik Ekonomi Dan Sosial Pasca 21 Mei 1998Dina Marcelina50% (2)
- TUGAS 2 Artikel Pendidikan KewarganegaraanDokumen8 halamanTUGAS 2 Artikel Pendidikan Kewarganegaraanbintangyudhistira21Belum ada peringkat
- Tugas KewarganegaraanDokumen4 halamanTugas KewarganegaraanFaisal SyukrillahBelum ada peringkat
- Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Kegiatan PendidikanDokumen9 halamanDampak Krisis Ekonomi Terhadap Kegiatan PendidikanRola Mesrani SimbolonBelum ada peringkat
- Proses Pertumbuhan Dan Mobilitas Penduduk Dan PerkembanganDokumen9 halamanProses Pertumbuhan Dan Mobilitas Penduduk Dan PerkembanganThedhy Riansyah'Belum ada peringkat
- T2, Artikel PKNDokumen10 halamanT2, Artikel PKNw7615495Belum ada peringkat
- Joki UtDokumen9 halamanJoki Utsandaniki bersatuBelum ada peringkat
- Artikel Modul 5-DikonversiDokumen8 halamanArtikel Modul 5-Dikonversieddy goodboy78% (32)
- Makalah ReformasiDokumen12 halamanMakalah ReformasiRopi KomalaBelum ada peringkat
- Hak Asasi Manusiakaum Buruh Di Era GlobalisasiDokumen10 halamanHak Asasi Manusiakaum Buruh Di Era Globalisasi20. Komang Ayu Sukma GinantiBelum ada peringkat
- Nur Halizah - 2102001010037Dokumen6 halamanNur Halizah - 2102001010037muhammad firdausBelum ada peringkat
- AKSI DEMO DI ERA REFORMASI KewarganegaraanDokumen21 halamanAKSI DEMO DI ERA REFORMASI KewarganegaraanDearni Binereni PurbaBelum ada peringkat
- M.RISWANDHA IMAWAN F23122123 Tugas KTB BDokumen8 halamanM.RISWANDHA IMAWAN F23122123 Tugas KTB BM Riswandha ImawanBelum ada peringkat
- Putri Maharani D10119065Dokumen9 halamanPutri Maharani D10119065Agung PranawijayaBelum ada peringkat
- TUGAS III Kewarganegaraan Digital Dalam Membangun Good and Clean GovernmentDokumen9 halamanTUGAS III Kewarganegaraan Digital Dalam Membangun Good and Clean Governmentmelinakusuma52Belum ada peringkat
- Tugas Tutorial 2 PKN Aprida Lumengkewas FixsDokumen10 halamanTugas Tutorial 2 PKN Aprida Lumengkewas FixsAFIFAH NOVALIA DETUBelum ada peringkat
- Artikel Hak Asasi Manusia Di Era GlobalisasiDokumen9 halamanArtikel Hak Asasi Manusia Di Era GlobalisasiAriel SaketuBelum ada peringkat
- Tugas Tutorial 2 PKNDokumen11 halamanTugas Tutorial 2 PKNAFIFAH NOVALIA DETUBelum ada peringkat
- Penyebab Runtuhnya Orde BaruDokumen9 halamanPenyebab Runtuhnya Orde BaruAri DestriadiBelum ada peringkat
- Tugas 2 DewiDokumen7 halamanTugas 2 DewiAisha AdminBelum ada peringkat
- Tugas 2 Pendidikan KewarganegaraanDokumen7 halamanTugas 2 Pendidikan Kewarganegaraanzfauzia918Belum ada peringkat
- Akuntansi ResumeDokumen3 halamanAkuntansi ResumeAriyanti RizkaBelum ada peringkat
- Globalisasi Terhadap PolitikDokumen6 halamanGlobalisasi Terhadap PolitikLisani ErizaBelum ada peringkat
- PKN Tugas2 - Zianatussa'adahDokumen8 halamanPKN Tugas2 - Zianatussa'adahZian ZianBelum ada peringkat
- Teori Modernisasi Berfokus Pada Kehidupan Masyarakat Pra Modern Beserta Ciri KehidupanDokumen3 halamanTeori Modernisasi Berfokus Pada Kehidupan Masyarakat Pra Modern Beserta Ciri KehidupanMuhammad Ammar KurniaBelum ada peringkat
- Krisis Moneter, Gejolak Politik Dan Perlunya Reformasi Pendidikan PDFDokumen13 halamanKrisis Moneter, Gejolak Politik Dan Perlunya Reformasi Pendidikan PDFUbaidillahCanuBelum ada peringkat
- Reformasi Di IndonesiaDokumen18 halamanReformasi Di Indonesiarafika rahim100% (1)
- (Fix) Makalah Kewarganegaraan GlobalisasiDokumen14 halaman(Fix) Makalah Kewarganegaraan GlobalisasiDiiChaa Just Littlegirl100% (1)
- Pendidikan Kewarganegaraan - Roscha Aleska Y. BuaDokumen9 halamanPendidikan Kewarganegaraan - Roscha Aleska Y. Buadilawedyanida.2021Belum ada peringkat
- Pertemuan 13 ReformasiDokumen29 halamanPertemuan 13 ReformasihafitsaauliaBelum ada peringkat
- Resume Analisis Isu KonetmporerDokumen10 halamanResume Analisis Isu KonetmporerTeguh PriyantoBelum ada peringkat
- 6 - 7 Sisfo - Raja Pranatha Doloksaribu - Resume Pertemuan 14Dokumen5 halaman6 - 7 Sisfo - Raja Pranatha Doloksaribu - Resume Pertemuan 14Kingsley ThousandBelum ada peringkat
- UAS - Dea Sahda Nawa - 201103010020Dokumen4 halamanUAS - Dea Sahda Nawa - 201103010020Dea NawaBelum ada peringkat
- Periode Akhir Orde BaruDokumen20 halamanPeriode Akhir Orde BaruKunthi Silviana PangestiBelum ada peringkat
- Internet Dan Demokrasi PRINTDokumen6 halamanInternet Dan Demokrasi PRINTSasaBelum ada peringkat
- Tugas 2 Pendidikan Kewarganegaraan Annisa SalsaDokumen8 halamanTugas 2 Pendidikan Kewarganegaraan Annisa SalsaAnnisa Salsa CahyaniBelum ada peringkat
- Ips Kls 9 Bab 13Dokumen18 halamanIps Kls 9 Bab 13Yenyen OktarriBelum ada peringkat
- Timbulnya Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia - BRPDokumen8 halamanTimbulnya Gerakan Reformasi 1998 Di Indonesia - BRPBachtiar Rachmad Pudya100% (7)
- The Three Shades from the Past to the Present Malay VersionDari EverandThe Three Shades from the Past to the Present Malay VersionBelum ada peringkat
- The Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionDari EverandThe Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionBelum ada peringkat
- Kris BudimanDokumen10 halamanKris BudimanunarimaBelum ada peringkat
- Kelas11 Kimia Nenden FauziahDokumen198 halamanKelas11 Kimia Nenden FauziahunarimaBelum ada peringkat
- Soal KimiaDokumen8 halamanSoal KimiaunarimaBelum ada peringkat
- Larutan Dan KelarutanDokumen34 halamanLarutan Dan KelarutanunarimaBelum ada peringkat
- Larutan Dan Kelarutan Part 1Dokumen58 halamanLarutan Dan Kelarutan Part 1unarimaBelum ada peringkat
- Sediaan AerosolDokumen23 halamanSediaan Aerosolunarima33% (3)
- Sediaan AerosolDokumen23 halamanSediaan Aerosolunarima33% (3)
- Rekayasa TrafikDokumen4 halamanRekayasa TrafikunarimaBelum ada peringkat
- Makalah Speech CodingDokumen31 halamanMakalah Speech CodingunarimaBelum ada peringkat
- Makalah TrafikDokumen13 halamanMakalah TrafikunarimaBelum ada peringkat
- Diferensiasi Sosial Dan Stratifikasi SosialDokumen6 halamanDiferensiasi Sosial Dan Stratifikasi SosialunarimaBelum ada peringkat
- Gaya Hidup Masyarakat Desa Dan KotaDokumen9 halamanGaya Hidup Masyarakat Desa Dan Kotaunarima100% (1)