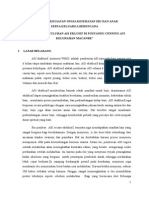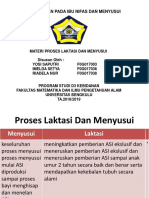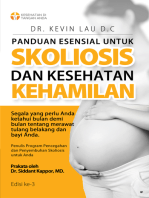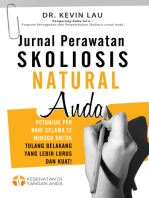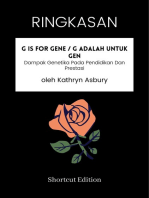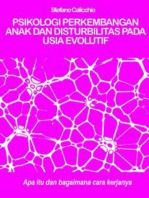Daftar Isi Jurnal Ed.9
Daftar Isi Jurnal Ed.9
Diunggah oleh
Monica MarcelaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Daftar Isi Jurnal Ed.9
Daftar Isi Jurnal Ed.9
Diunggah oleh
Monica MarcelaHak Cipta:
Format Tersedia
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
RISET FORMATIF PSP ASI EKSLUSIF SUKU MAKASSAR
SULAWESI SELATAN 2011
Muhammad Syafar, Watief A. Rachman
Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Hasanuddin, Makassar, Email:syafar.muhammad@yahoo.co.id
Abstract
Pada era sekarang 80% bayi di Indonesia tidak lagi menyusui sejak 24 jam pertama
sejak mereka lahir, dimana seharusnya ibu memberikan ASI yang merupakan makanan utama
yang sangat diperlukan bayi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi
dalam peningkatan pemahaman mengenai pengetahuan, sikap dan perilaku tentang ASI Ekslusif.
Dalam riset ini dilakukan survey dan eksplorasi informasi melalui wawancara mendalam pada ibu
yang melakukan ASI Ekslusif, ibu yang tidak melakukan ASI Ekslusif, serta bidan yang merupakan
petugas kesehatan. Hasil yang diperoleh, pemahaman Ibu hamil tentang ASI Ekslusif dan IMD
masih kurang khususnya tentang manfaat ASI. Kendala pelaksanaan IMD kadang berasal dari
larangan orang tua untuk melakukan hal tersebut karena dianggap sebagai hal yang baru. Ibu
hamil memberikan sikap positif terhadap pemberian ASI Ekslusif karena ASI adalah makanan dan
minuman yang praktis dan murah. Tindakan ibu hamil dalam pemberian ASI Ekslusif dan IMD
dipengaruhi oleh adanya beberapa kepercayaan ibu, seperti ASI saja tidak cukup untuk membuat
bayi kenyang sehingga perlu makanan tambahan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan perlu
dilakukan pemberdayaan Ibu Hamil melalui pengembangan KIE dalam bentuk komunikasi
berantai dan adanya kemitraan bidan dan dukun yang bernilai positif untuk memberikan
informasi terkait dengan kepercayaan dalam pemberian ASI Ekslusif dan IMD.
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Perilaku, ASI Ekslusif
Abstract
Nowadays 80% of infants in Indonesia are no longer breast-feeding since 24 hours the
first since they were born, where mother should breast feed which is the main food that baby
needed. The research was conducted to obtain data and information in an increased
understanding of the knowledge, attitudes and behaviors about exclusive breastfeeding. In this
study conducted a survey and exploration of information through in-depth interviews among
women who did exclusive breastfeeding, the mother who does not do exclusive breastfeeding, and
midwives who are health workers. The results obtained, the understanding of pregnant women
about exclusive breastfeeding and the IMD is still lacking, especially on the benefits of breast.
IMD implementation constraints often come from parents’ prohibition to ban it because it was
considered as a novelty. Pregnant women gave a positive attitude towards exclusive breast feeding
because it is the food and drinks with are practical and inexpensive. Pregnant women treatment
and IMD Exclusive breastfeeding is influenced by the presence of some beliefs, such as breast milk
alone is not enough to make a baby satisfied so need additional foods. This study concludes is
necessary to Pregnant Women empowerment through the development of KIE in the form of serial
communication and the partnership between midwife and herbalist who is positive to provide
information related to the belief in exclusive breastfeeding and Early Initiation.
Key words: Knowledge, Attitudes, Behavior, Breastfeeding.
1 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
I. Pendahuluan
P emberian ASI sangat penting bagi tumbuh kembang yang optimal baik fisik
maupun mental dan kecerdasan bayi. Oleh karena itu pemberian ASI perlu
mendapat perhatian para ibu dan tenaga kesehatan agar proses menyusui dapat
terlaksana dengan benar. Di Indonesia pada saat ini terdapat 80% bayi tidak lagi menyusui sejak
24 jam pertama sejak mereka lahir .
Hasil Riskesdas (2010), menunjukan bahwa terjadi penurunan persentase bayi yang
mendapatkan ASI Ekslusif sampai dengan 6 bulan. Pada tahun 2010 yang mendapatkan ASI
ekslusif hanya 15%. Inisiasi menyusu dini kurang dari 1 jam setelah bayi lahir adalah 29,3%.
Provinsi Sulawesi Selatan menunjukan inisiasi dini menyusui kurang dari 1 jam adalah 30,1% dan
pada kisaran 1-6 jam yaitu 34,9%.Sedangkan jumlah bayi yang diberi ASI ekslusif di Sulawesi
Selatan tahun 2008 yaitu 48,64%, terjadi penurunan dari tahun 2006 yaitu 57,48% dan tahun 2007
yaitu 57,05% .
Ibu hamil adalah pihak sangat strategis dalam konteks ini. Mereka adalah pelaku pemberi
ASI ekselusif, pelaku IMD sekaligus penerima manfaat (beneficiary) dan pemangku kepentingan
(stakeholder) yang wajib terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tentang ASI eskelusif.
Namun, pengetahuan mereka sendiri tentang hal ini relative masih rendah. Akses dari partisipasi
mereka terhadap proses politik bahkan lebih jauh lagi.
Riset formatif PSP (pengetahuan, sikap, dan perilaku) ini bertujuan sebagai baseline data
yang akan digunakan dalam memberdayakan ibu hamil sebagai kelompok pembelajar melalui
kelas ibu hamil dan kelompok advokasi kebijakan ASI Eksklusif. Kelas ibu hamil merupakan
program unggulan penanggulangan AKI dan AKB di lokasi penelitian.
II. BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Informan
Penelitian ini dilaksanakan di 3 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak
berasal dari suku Makassar, yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, dan Kabupaten Takalar.
Sebelum melakukan riset formatif telah terdapat data yang diperoleh berdasarkan survey awal
dalam bentuk kuantitatif. Sehingga berdasarkan hasil survei tersebutlah kemudian dipilih
beberapa informan yang memenuhi kriteria penelitian untuk menggali informasi mereka lebih
mendalam. Dengan kriteria: ibu yang memberikan ASI Ekslusif dan IMD, Ibu yang tidak
memberikan ASI Ekslusif dan IMD, serta petugas kesehatan dalam hal ini bidan, karena
merekalah yang bersentuhan langsung pada ibu hamil dan menyusui.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui indepth interview (wawancara mendalam). Data
yang dikumpulkan meliputi pemahaman ibu hamil terhadap ASI Ekslusif dan IMD, makanan
pendamping ASI, Pantangan dan anjuran bagi ibu menyusui, serta peranan suami dalam
mendukung pemberian ASI Ekslusif dan IMD. Wawancara dilakukan melalui peggunaan pedoman
wawancara yang telah diuji coba sebelumnya.
Analisis Data
Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian mengikuti petunjuk Miles dan
Huberman (1992), yakni dilakukan melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan
penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sesuai dengan
pengkategorian tema dan reduksi data. Sebelum dilakukan analisis pengkategorian tema, data
tersebut di narasikan dalam bentuk transkip hasil wawancara. Setelah dilakukan reduksi, data
kemudian disajikan dalam bentuk naratif untuk selanjutnya di verifikasi sebagai kesimpulan yang
kredibel.
2 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pemahaman Terhadap ASI Ekslusif dan IMD
Pada ibu yang memberikan ASI Ekslusif, menurut mereka ASI merupakan Air susu yang
tidak memiliki campuran lain berbeda dengan susu formula yang telah tercampur dengan gula dan
zat lainnya. Selain itu juga dipahami ASI Ekslusif sebagai ASI yang pertama kali keluar dan
berwarna kuning, serta diberikan sementara untuk bayi. Sedangkan pada ibu yang tidak
memberikan ASI Ekslusif, mereka memahaminya sebagai ASI yang diberikan untuk anak yang
baru lahir sampai berusia 2 tahun. Pada umumnya informan banyak memahami ASI Ekslusif
sebagai suatu hal yang sama dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), sebab memiliki manfaat yang
sama diantara keduanya. IMD yang dipahami sebagai makanan tambahan pada bayi, sama halnya
dengan ASI memiliki manfaat untuk merangsang perkembangan sistem otak bayi sehingga pintar
dan tentunya tidak mudah sakit. Pemahaman terhadap IMD banyak diutarakan informan
berdasarkan langkah-langkah IMD. Meletakkan bayi diatas perut dan diatas dada sebagai upaya
yang dilakukan untuk merangsang penghentian perdarahan saat persalinan juga diungkapkan
informan. Terdapat juga informan yang memahami IMD sebagai salah satu jenis makanan
tambahan.
Selain itu ASI Ekslusif juga dianggap dapat mempererat hubungan kedekatan antara bayi
dan ibu, sebab ASI Ekslusif dipahami sebagai kolostrum yakni ASI yang pertama kali keluar dan
bermanfaat dalam aspek emosional antara bayi dan Ibu. Di beberapa masyarakat tradisional,
kolostrum ini dianggap sebagai susu yang sudah rusak dan tak baik diberikan pada bayi karena
warnanya yang kekuningkuningan. Selain itu, ada yang menganggap bahwa kolostrum dapat
menyebabkan diare, muntah dan masuk angin pada bayi. Sementara, kolostrum sangat berperan
dalam menambah daya kekebalan tubuh bayi. Kolostrum tidak selalu dipandang positif,
pemahaman akan kolostrum sebagai kotoran dipayudara yang harus dibuang juga diungkapkan ibu
hamil. Kolostrum adalah cairan pra-susu yang dihasilkan oleh induk mamalia dalam 24-36 jam
pertama setelah melahirkan (pasca-persalinan). Kolostrum mensuplai berbagai faktor kekebalan
(faktor imun) dan faktor pertumbuhan pendukung kehidupan dengan kombinasi zat gizi (nutrien)
yang sempurna untuk menjamin kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan kesehatan bagi bayi yang
baru lahir (Yesie, 2010). Ahli filsafat, Keraf dan Dua (2001) mengatakan bahwa pengetahuan
dibagi menjadi 3 macam, yaitu tahu bahwa, tahu bagaimana, dan tahu akan. Pada riset ini
pengetahuan yang dimiliki oleh informan yang tidak memberikan ASI Ekslusif masih sebatas pada
tingkat ”tahu bahwa” sehingga tidak begitu mendalam dan tidak memiliki keterampilan untuk
mempraktekkannya. Jika pengatahuan informan lebih luas dan mempunyai pengalaman tentang
ASI Eksklusif baik yang dialami sendiri maupun dilihat dari teman, tetangga atau keluarga, maka
subjek akan lebih terinspirasi untuk mempraktekkannya.
Pengalaman dan pendidikan wanita semenjak kecil akan mempengaruhi sikap dan
penampilan mereka dalam kaitannya dengan menyusui di kemudian hari (Pinem, 2010). Seorang
wanita yang dalam keluarga atau lingkungan sosialnya secara teratur mempunyai kebiasaan
menyusui atau sering melihat wanita yang menyusui bayinya secara teratur, akan mempunyai
pandangan yang positif tentang pemberian ASI. Di daerah penelitian yang mempunyai ”budaya
susu formula / botol”, gadis dan wanita muda di daerah tersebut tidak mempunyai sikap positif
terhadap menyusui, sesuai dengan pengalaman sehari-hari. Tidak mengherankan bila wanita
dewasa dalam lingkungan ini hanya memiliki sedikit bahkan tidak memiliki sama sekali informasi,
pengalaman cara menyusui, dan keyakinan akan kemampuannya menyusui.
Demikian hal-nya pemahaman terkait dengan IMD. Pada umumnya informan banyak
memahami ASI Ekslusif sebagai suatu hal yang sama dengan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), sebab
memiliki manfaat yang sama diantara keduanya. IMD yang dipahami sebagai makanan tambahan
pada bayi, sama halnya dengan ASI memiliki manfaat untuk merangsang perkembangan sistem
otak bayi sehingga pintar dan tentunya tidak mudah sakit. Pemahaman terhadap IMD hanya
sebatas langkah-langkah IMD. Meletakkan bayi diatas perut dan diatas dada sebagai upaya yang
3 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
dilakukan untuk merangsang penghentian pendarahan saat persalinan. Sebagaimana hasil
wawancara dengan informan penelitian sebgaai berikut :
“Di taruh dada untuk merangsang ibu untuk pendarahan berhenti”
(Renata, 22 thn, )
Segera setelah bayi dilahirkan, secara normal refleks mencari dan mengisap pada bayi
sangat kuat, dan ibunya pun biasanya ingin sekali untuk segera melihat dan memegang bayinya.
Sentuhan kulit ke kulit antara ibu dengan bayinya segera setelah bayi itu dilahirkan dan
membiarkan bayi itu mengisap puting susu ibunya, akan sangat bermanfaat dan membantu
dimulainya hubungan lekat antara ibu dan bayi disamping juga akan merangsang pengeluaran ASI.
Isapan bayi pada puting susu ibu akan merangsang keluarnya oksitosin, yang akan mempercepat
lepasnya plasenta dan kontraksi rahim dalam kala tiga (Depkes RI, 2005)
Kepercayaan ibu menyusui terhadap hal-hal yang dianggap sebagai pantangan atau larangan
saat menyusui juga dipercaya sebagai suatu hal yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan
bayi, sebab makanan yang dikonsumsi oleh ibu menyusui akan berdampak pada bayi, bahkan
sayuran berupa daun-daunan seperti daun kelor dianggap sebagai makanan pantangan sebab
dipercaya dapat mengakibatkan kotoran bayi berwarna hijau. Tidak hanya itu, terdapat juga
larangan mengkonsumsi makanan yang mengandung cabe/lombok (pedis) karena akan
menyebabkan bayi diare. Adanya pantangan makanan juga dipengaruhi oleh kepercayaan secara
turun temurun orang tua dalam memberikan wejangan atau nasehat serta kebiasaan yang dilakukan
untuk ditiru. Makanan yang sebenarnya dibutuhkan oleh ibu menyusui untuk memenuhi kebutuhan
protein misalnya telur, juga dianggap sebagai pantangan yang tidak boleh dikonsumsi sejak dulu
bahkan saat ibu hamil, sebab dapat menimbulkan efek alergi pada bayi. Pantangan ini bahkan telah
dianjurkan saat ibu hamil. Menurut Afifah, (2007) Salah satu factor tingginya gizi buruk adalah
pola makanan dan konsumsi nutrisi tingkat keluarga yang rendah terkait pemahaman dan
kebiasaan yang dilakukan sejak dulu, pada dasarnya telur merupakan sumber kolin, nutrisi
penting untuk perkembangan janin dan bayi. Ibu hamil yang mendapatkan cukup kolin dalam
makanannya bisa membantu mengurangi risiko cacat lahir tertentu pada bayi, dan mendukung
perkembangan otak dan memorinya.
Kehadiran makanan pantangan yang tidak boleh dikonsumsi sejak masa kehamilan sampai
persiapan menyusui, dilakukan dengan alasan untuk membantu kelancaran persalinan agar bayi
dapat lahir sehat serta prosuksi ASI lancar. pemahaman jika mengkonsumsi seafood yang bergizi
tinggi seperti udang dan cumi-cumi merupakan hal yang dilarang dan tidak boleh dikonsumsi
karena dipercaya dapat mempersulit ibu dan bayi saat proses persalinan.
Adanya pemahaman terkait makanan pantangan yang bertolak belakang dengan konsep gizi
ibu hamil, menjadi focus petugas kesehatan yakni bidan. Pemberian informasi dilakukan dengan
aktif sebagai fasilitator di kelas ibu hamil. persepsi yang bertolak belakang dengan prinsip
kesehatan disosialisasikan oleh bidan secara persuasive.
Sikap Terhadap ASI Ekslusif dan IMD
Pemberian ASI Ekslusif dan IMD dilakukan dengan alasan utama dipengaruhi oleh
manfaat yang diperoleh dengan melakukan kedua hal tersebut. Manfaat pemberian ASI tidak
hanya menguntungkan bagi bayi, tetapi juga menguntungkan dalam membantu perekonomian
rumah tangga karena pengeluaran untuk makanan bayi tidak memerlukan biaya sehingga ibu dapat
berhemat. Manfaat lain ASI Ekslusif juga dianggap dapat mempererat hubungan antara bayi dan
ibu, sebab memahami ASI Ekslusif sebagai kolostrum yakni ASI yang pertama kali keluar dan
bermanfaat dalam aspek emosional antara bayi dan Ibu. Adanya persepsi ini menimbulkan sikap
positif pada ibu untuk memberikan ASI pada bayi mereka.
Namun, terdapat juga ibu yang tetap melakukan IMD meskipun tidak mengetahui secara
pasti manfaat dari tindakan tersebut. Perilaku ini merupakan perilaku positif yang didasarkan pada
4 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
keyakinan budaya “pamali” yang lekat dengan kehidupan social masyarakat setempat. Informan
meyakini ASI yang pertama kali keluar tidak boleh dibuang dianggap sebagai perilaku pamali
yakni pantangan yang berasal dari mitos (kepercayaan yang diwariskan secara turun temurun).
Informan lain, menganggap kolostrum sebagai susu yang sudah rusak dan tidak baik
diberikan pada bayi karena warnanya yang kekuning -kuningan. Selain itu, ada yang menganggap
bahwa kolostrum dapat menyebabkan diare, muntah dan masuk angin pada bayi. Sementara,
kolostrum sangat berperan dalam menambah daya kekebalan tubuh bayi ( Afifah, 2007).
Menurut Cox (2006), dalam 48 jam kehidupannya, bayi tidak membutuhkan air susu
terlalu banyak, hanya setengah sendok teh kolostrum saat pertama menyusu dan 1-2 sendok teh di
hari kedua. Cairan kental yang sangat sedikit seperti seulas cat itu akan melapisi saluran
pencernaan bayi dan menghentikan masuknya bakteri ke dalam darah yang menimbulkan infeksi
pada bayi. Pemberian kolostrum dapat dilakukan dengan baik jika early initiation dilakukan oleh
bidan atau perawat. Ibu yang berhasil menyusui pada jam pertama dan minggu pertama setelah
persalinan maka ia akan berhasil memberikan ASI Eksklusif pada bayinya.
Salah satu faktor tidak berhasilnya pemberian ASI Ekslusif pada bayi bukan karena
kesengajaan dari ibu-nya. Namun, disebabkan oleh produksi ASI Ekslusif yang kurang sehingga
perlu pemberian susu formula. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai
berikut :
”Karena waktu lahir ini 3 hari ASInya nda ada. Terus dibelikan mi dot. Dikasi dot”
(Bunga, 38 thn)
Pemberian susu formula diberikan biasanya dengan alasan utama karena ASI belum
keluar dan bayi masih kesulitan menyusu sehingga bayi akan menangis bila dibiarkan saja.
Biasanya bidan akan langsung memberikan nasihat untuk memberikan susu formula terlebih
dahulu. Bahkan pembuatan susu formula dilakukan sendiri oleh bidan atau perawat, dan mereka
menyediakan jasa sterilisasi botol. Hal ini akan memberi pengaruh negatif terhadap keyakinan ibu
bahwa pemberian susu formula adalah obat paling ampuh untuk menghentikan tangis bayi.
Kurangnya keyakinan terhadap kemampuan memproduksi ASI untuk memuaskan bayinya
mendorong ibu untuk memberikan susu tambahan melalui botol (Hasrimayana, 2009).
Namun, pada beberapa masyarakat didaerah penelitian yang persalinannya ditolong oleh
dukun bayi kadang memberikan prelaktal berupa madu, kelapa muda, dan kurma yang merupakan
anjuran dari dukun bayi. Akan tetapi informan yang ditolong oleh dukun terlatih dan bidan tidak
memberikan madu sebagai prelaktal karena tidak dianjurkan oleh bidan. Anjuran ini sesuai dengan
WHO yang melarang pemberian madu kepada bayi dibawah 1 tahun karena terdapat kandungan
Clostridium botulinum, spora yang membahayakan dan mematikan.
Tindakan Terhadap ASI Ekslusif dan IMD
Pada penerapan pemberian ASI Ekslusif belum bisa tercapai secara maksimal karena
dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk didalamnya faktor pekerjaan dan faktor budaya. Factor
pekerjaan yakni Ibu yang aktif dan bekerja di luar rumah sebagai pegawai misalnya yang memiliki
aktifitas rutin sangat sulit melakukan ASI Ekslusif, hal ini banyak ditemui didaerah perkotaan.
Sedangkan faktor budaya sangat erat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat yang didasarkan
pada pengalaman orang tua atau mertua. Adanya pemahaman jika memberikan ASI saja tanpa
makanan tambahan lain seperti pisang akan membuat bayi lapar, sebab ASI saja tidak dapat
mengeyangkan dan dianggap sebagai minuman saja. Namun beberapa hambatan tersebut dapat
diatasi dengan adanya kelas ibu hamil yang dilakukan rutin untuk memberikan informasi dan
membantu ibu hamil menghadapi stress yang kadang timbul saat menjelang partus.
Kelas Ibu hamil (KIH) untuk Kabupaten Takalar merupakan salah satu program unggulan
penanggulangan AKI dan AKB di daerah tersebut. KIH ini rutin diadakan setiap bulan dengan
konsep informasi edukasi melalui belajar kelompok dengan seorang fasilitator yang merupakan
petugas kesehatan, dalam prakteknya lebih sering oleh bidan desa yang dilakukan dengan
mengunjungi tiap desa/kelurahan. Dalam KIH berbagai informasi diberikan khususnya mengenai
5 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
gizi, persiapan sebelum melahirkan, resiko dan tanda bahaya pada ibu hamil, dll. Beberapa
infoman merasa keberadaan KIH sangat bermanfaat dalam menambah wawasan mereka.
Pemberian PASI pada bayi dapat memberikan manfaat yang besar karena menurut informan
dengan memberikan makanan tambahan pada bayi maka bayi akan cepat kenyang. Berbeda jika
hanya mengutamakan ASI saja terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi.
Sebagaimana hasil wawancara dengan informan sebagai berikut :
‘’Manfaatnya, dapat membantu bayi kenyang, tidak cepat lapar, kalau
anu biasa (ASI) nda cukup to’ nda kenyangi’
(Musdalifah, 22 thn)
Pemberian PASI yang terlalu dini pada bayi biasanya karena anjuran keluarga dekat
terutama nenek (ibu informan). Alasan umumnya karena bayi menangis terus meskipun telah
disusui dan diberi susu formula. Pada beberapa masyarakat tradisional di Indonesia kita bisa
melihat konsepsi budaya yang terwujud dalam perilaku berkaitan dengan pola pemberian makan
pada bayi yang berbeda dengan konsepsi kesehatan modern. Sebagai contoh, pemberian ASI
menurut konsep kesehatan modern ataupun medis dianjurkan selama 2 (dua) tahun dan pemberian
makanan tambahan berupa makanan padat sebaiknya dimulai sesudah bayi berumur 4 bulan.
Sesuai disertasi Maas (2004), bahwa pada suku Sasak di Lombok, ibu yang baru bersalin
memberikan nasi pakpak (nasi yang telah dikunyah oleh ibunya lebih dahulu dan didiamkan
selama satu malam) kepada bayinya agar bayinya tumbuh sehat dan kuat. Mereka percaya bahwa
apa yang keluar dari mulut ibu merupakan yang terbaik untuk bayi. Sementara ada masyarakat
Kerinci di Sumatera Barat, pada usia sebulan bayi sudah diberi bubur tepung, bubur nasi nasi,
pisang dan lain-lain. Ada pula kebiasaan memberi roti, pisang, nasi yang sudah dilumatkan
ataupun madu, teh manis kepada bayi baru lahir sebelum ASI keluar.
Pemberian MP-ASI yang terlalu dini tidak tepat karena akan menyebabkan bayi kenyang
dan akan mengurangi keluarnya ASI. Selain itu bayi menjadi malas menyusu karena sudah
mendapatkan makanan atau minuman terlebih dahulu. Pemberian MP-ASI terlalu dini seperti nasi
dan pisang justru akan menyebabkan penyumbatan saluran cerna karena liat dan tidak bisa dicerna
atau yang disebut phyto bezoar sehingga dapat menyebabkan kematian dan menimbulkan risiko
jangka panjang seperti obesitas, hipertensi, atherosklerosis, dan alergi makanan (Afifah, 2007).
KESIMPULAN
Pemahaman Ibu hamil terkait pemberian ASI Ekslusif dan IMD masih kurang sehingga
dalam pemberian ASI Ekslusif dan IMD masih dipengaruhi oleh adanya beberapa kepercayaan
seperti pemberian ASI Ekslusif pada bayi tidak cukup untuk membuat bayi kenyang maka perlu
makanan tambahan lainnya, pemberian madu saat pertama lahir yang dipercayai dapat
mencerdaskan bayi. Hal inilah yang menjadi penyebab tidak berhasilnya pemberian ASI Ekslusif
bagi bayi. Sehingga perlu dilakukan pemberdayaan Ibu Hamil melalui pengembangan KIE dalam
bentuk komunikasi berantai dan adanya kemitraan bidan dan dukun yang bernilai positif untuk
memberikan informasi terkait dengan kepercayaan dalam pemberian ASI Ekslusif dan IMD.
6 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
DAFTAR PUSTAKA
1. Kamalia. 2005. Faktor berpengaruh dalam ASI Ekslusif. Artikel. http://
http://pmi.rejanglebongkab.go.id/faktor-berpengaruh-ASI-penting-/
2. Aprilia, Yesie. 2010. Analisis Sosialisasi Program Inisiasi Menyusu Dini Dan Asi Eksklusif
Kepada Bidan Di Kabupaten Klaten.http://eprints.undip.ac.id/23900/1/Yesie_Aprillia.pdf
Diakses pada tanggal 30 mei 2012.
3. Dinkes Sulawesi Selatan. 2010. Profil Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Hasrimayana. 2009. Hubungan Antara Sikap Ibu Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di
Wilayah Kerja Puskesmas Kedawung II Sragen. http://etd.eprints.ums.ac.id/4934/1/
J210070116.pdf. Diakses pada tanggal 30 mei 2012.
5. Josefa, Khrist Gafriela. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pemberian Asi
Eksklusif Pada Ibu (Studi Kasus Di Wilayah Kerja Puskesmas Manyaran, Kecamatan
Semarang Barat). http://eprints.undip.ac.id/33391/1/Khrist_Gafriela.pdf. Diakses pada
tanggal 31 Mei 2012
6. Pinem, Susanti Eriva Sari. 2010. Faktor-Faktor Penghambat Ibu Dalam Pemberian ASI
Eksklusif Di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan.
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/20264/8/pdf. Diakses pada tanggal 30 Mei
2012
7 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN DAN POLA PENCARIAN PENGOBATAN TERHADAP
“LAKI-LAKI YANG BERHUBUNGAN SEKS DENGAN LAKI-LAKI” (LSL) DI KOTA
MAKASSAR
Farit Rezal¹, Muh. Syafar1, Sudirman Natsir1
¹ Bagian Promosi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar
ABSTRAK
Infeksi Menular Seksual (IMS) telah lama dikenal dan beberapa diantaranya sangat
populer di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini tampak kecenderungan meningkatnya
prevalensi IMS hingga 10% pada beberapa kelompok Pekerja Seks Komersial (PSK) dan sebesar
35% pada kelompok homoseksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perilaku LSL
dalam melakukan upaya pencegahan setelah menderita IMS dan pola pencarian pengobatan
terhadap IMS. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi, informan yang
dalam penelitian ini adalah komunitas LSL di Kota Makassar yang pernah menderita IMS.
Informan dipilih dengan Snowball Research Strategies dan dianalisis dengan menggunakan
metode content analysis (analisis isi). Hasil penelitian menunjukan bahwa yang melatar belakangi
informan memilih identitas seksual sebagai LSL adalah kekerasan seksual, pergaulan tidak sehat
semasa remaja, kekecewaan terhadap lawan jenis dan faktor ekonomi. Orientasi seksual yang
berbeda memicu perilaku seksual informan yang berisiko terhadap penularan IMS dimana
kepercayaan awam merupakan usaha pencegahan yang mereka tempuh pada saat berhubungan
seksual baik dengan pasangan laki-laki maupun perempuannya. Peran Yayasan Gaya Celebes,
media informasi, serta konseling yang mereka ikuti menginisiasi perubahan perilaku komunitas
LSL di Kota Makassar untuk melakukan hubungan seksual yang aman. Namun dalam usaha
pengobatan komunitas ini masih menerapkan konsep menjadi dokter buat diri sendiri, karena
dipengaruhi oleh norma subjektif pada saat mereka tertular IMS. Hasil penelitian ini
menyarankan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji beberapa upaya-upaya
pencegahan medis tidak hanya terbatas pada kepercayaan awam yang merupakan perspektif
keliru komunitas ini dan pola pencarian pengobatan IMS. Selain itu lintas sektoral dapat membuat
rancangan sebuah model penyuluhan efektif berupa iklan di beberapa hotspot di tempat-tempat
nongkrong para LSL.
Kata Kunci : LSL, Pencegahan, Pola Pengobatan, Infeksi Menular Seksual
ABSTRACT
Sexually Transmitted Infections (STIs) have long been known and some are very popular
in Indonesia. Recent years the increasing prevalence of STIs seemed trend up to 10% in some
groups of commercial sex workers (CSWs) and by 35% in the homosexual group. This study aimed
to explore the behavior of MSM in prevention efforts after suffering from IMS and the search
pattern of IMS treatment. This research is a qualitative phenomenological approach, informants in
this study is the MSM community in Makassar who had suffered from IMS. Informants selected by
Snowball Research Strategies and analyzed using content analysis methods (content analysis). The
results showed that the background of sexual identity as an informant chose LSL is sexual abuse,
unhealthy relationships during adolescence, disillusionment with the opposite sex and economic
factors. Different sexual orientation trigger risky sexual behavior informant against transmission
of STIs which is a common belief that they are following prevention efforts at the time of sexual
intercourse with a male partner or female. The role of the Foundation Style Celebes, information
media, and counseling that they follow to initiate behavior change MSM community in Makassar
for safe sex. But in community treatment are still applying the concept to become a doctor for
yourself, because it is influenced by subjective norms when they are infected with STIs. The results
of this study suggest further research that examines some of the medical prevention efforts are not
just limited to common belief that a false perspective of this community and the search pattern of
8 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
STI treatment. In addition it can create a cross-sectional design of an effective model of education
in the form of advertisements on some hotspots in places of the MSM hanging out.
Keyword: MSM, Prevention, Treatment Patterns, Sexually Transmitted Infections
PENDAHULUAN
I nfeksi Menular Seksual telah lama dikenal dan beberapa diantaranya sangat populer
di Indonesia, yaitu sifilis dan gonorhea. Dahulu kelompok penyakit ini dikenal
sebagai Penyakit Kelamin (veneral disease) yang hanya terdiri dari 5 jenis penyakit
yaitu gonorhoe (kencing nanah), sifilis (raja singa, ulkus mole, limfogranuloma inguinale
(bungkul) dan granuloma inguinale (Djajakusumah, 2008). Menurut Aral, et al (2007) pada akhir
abad ke-20 dapat dibuktikan bahwa pada waktu mengadakan hubungan seksual dapat terjadi
infeksi oleh lebih dari 20 jenis kuman, sehingga muncullah istilah Sexually Transmitted Disease
(STD) atau Penyakit Menular Seksual (PMS).
Infeksi Menular Seksual (IMS) sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan
masyarakat di seluruh dunia, baik di negara maju (industri) maupun di negara berkembang.
Insiden maupun prevalensi yang sebenarnya di berbagai negara tidak diketahui dengan pasti. IMS
merupakan satu kelompok penyakit yang penularannya terutama melalui hubungan seksual
(Calvet, 2009).
Di Indonesia beberapa tahun terakhir ini tampak kecenderungan meningkatnya prevalensi
IMS misalnya prevalensi sifilis meningkat sampai 10% pada beberapa kelompok PSK (Pekerja
Seks Komersial), 35% pada kelompok waria dan 2% pada kelompok ibu hamil dan kalangan LSL.
Prevalensi gonore meningkat sampai 30 – 40% pada kelompok berisiko dan juga pada penderita
IMS yang berobat ke rumah sakit. Demikian juga prevalensi HIV pada beberapa kelompok
perilaku risiko tinggi meningkat tajam sejak tahun 1993 (Daili, 2004).
Perilaku seksual di kelompok risiko tinggi komunitas LSL memberikan kontribusi
penularan penyakit menular seksual yang signifikan. Data menunjukkan bahwa cara penularan
kasus AIDS terbanyak melalui heteroseksual (53,1%), disusul IDU (37,9%), LSL (3,0%), perinatal
(2,6%), transfusi darah (0,2%) dan tidak diketahui (3,2%) (Depkes, 2010).
Penelitian yang dilakukan pada tahun 2007 di enam kota menunjukkan prevalensi
(perbandingan antara LSL yang HIV-positif dan LSL yang HIV-negatif) mencapai 5,2 persen.
Artinya, dari 100 LSL terdapat 5,2 LSL yang mengidap HIV. Berdasarkan data tersebut dapat
diperkirakan di masa yang akan datang kalangan LSL dapat memberikan kontribusi yg besar
terhadap penularan HIV AIDS. Yayasan Riset AIDS Amerika, AMFAR menyimpulkan bahwa
ternyata LSL berisiko 19 kali lebih besar tertular HIV dibandingkan masyarakat umum (Fay et al,
2010).
Beberapa hasil penelitian menyatakan bahwa kalangan LSL merupakan kelompok risiko
tinggi terpapar kasus. Di sisi lain diketahui bahwa kurangnya program pencegahan terhadap IMS
yang ditujukan untuk kalangan LSL, karena kesulitan untuk mendeteksi kelompok ini yang
disebabkan para LSL dapat hidup selaras dengan masyarakat tanpa menunjukkan ciri yang khas.
Akibat kurangnya program yang ditujukan untuk kalangan LSL maka dapat dipastikan
perilaku pencegahan mereka terhadap IMS dan HIV dan AIDS sangat kurang sehingga mereka
masih memiliki potensi yang besar untuk menularkan HIV dan penyakit menular seksual yang
lainnya. Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius karena dapat diperkirakan jumlahnya akan
semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Kota Makassar sebagai ibukota Propinsi Sulawesi Selatan merupakan pintu gerbang
utama memasuki wilayah Sulawesi Selatan. Berbagai aktifitas ekonomi, sosial, maupun budaya
mampu menempatkan Kota Makassar sebagai salah satu kota metropolitan di wilayah timur
Indonesia dengan ciri pergaulan yang semakin bebas. Bertitik tolak dari uraian dan latar belakang
tersebut dirumuskan masalah penelitian yakni bagaimana upaya-upaya pencegahan dan pola
pencarian pengobatan/perawatan terhadap IMS di kalangan LSL Kota Makassar.
9 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
BAHAN DAN METODE
Jenis dan rancangan penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang
memungkinkan penulis memahami permasalahan individu secara lebih mendalam dan kompleks,
memberikan gambaran secara holistik, disusun dari kata-kata, mendapatkan informasi rinci yang
diperoleh dari informan dan berada dalam setting alamiah. Adapun desain penelitian yang
digunakan adalah fenomenologi, yakni penelitian yang didasarkan pada gejala-gejala yang
berkembang di lapangan (Babbie, 1998).
Lokasi dan waktu penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan fokus
penelitian pada kalangan LSL sesuai dengan hasil observasi pendahuluan. Pemilihan lokasi
ditentukan berdasarkan data yang diperoleh. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan pada bulan
Maret sampai Juli tahun 2012.
Informan penelitian
Informan dalam penelitian ini merupakan LSL yang terhimpun dalam Komunitas Gaya
Celebes Makassar yang mengetahui permasalahan dengan jelas, dapat dipercaya menjadi sumber
informasi yang baik serta mampu mengemukakan pendapat secara baik dan benar. Informan diberi
ruang seluas-luasnya menyampaikan gagasannya untuk menyampaikan apa saja yang diketahui
tentang topik yang diteliti (Rahardjo, 2010).
Teknik pemilihan informan
Teknik pengambilan informan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan metode
snowball research strategies. Metode ini merupakan sebuah teknik pemilihan non-random, yakni
informan diperoleh pertama-tama dengan cara menghubungi seseorang atau sekelompok orang
dalam hal ini pihak Yayasan Gaya Celebes Makassar. Kemudian peneliti meminta mereka untuk
memberikan saran tentang orang yang dipandang memiliki informasi penting dan bersedia untuk
berpartisipasi dalam penelitian.
Pengolahan dan analisis data
Pengumpulan data primer ini diperoleh dengan observasi dan melakukan wawancara
mendalam (indepth interview), yaitu berupa dialog secara individu menggunakan pertanyaan-
pertanyaan bebas agar informan mengutarakan pandangan, pengetahuan, perasaan serta sikap dan
perilaku berupa pengalaman pribadi yang berkaitan dengan konsep preventif dan pola pencarian
pengobatan terhadap penularan IMS. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipasi
yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati perilaku serta melihat kondisi
fisik dan lingkungan para LSL yang dijadikan informan.
Pengolahan dan analisis data
Data yang diperoleh dari wawancara mendalam ini dianalisis dengan menggunakan
metode analisis isi (content analysis). Menurut Creswell (1994) analisis isi adalah teknik
penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan kesahihan data
dapat diliat dengan memerhatikan konteksnya, analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau
isi komunikasi, logika dasar dalam komunikasi, bahwa setiap komunikasi selalu berisi pesan
dalam sinyal komunikasi itu, baik secara verbal maupun non verbal, dalam penelitian ini
Pengolahan datanya dilakukan dengan cara deskriptif isi (contents analysis). Selanjutnya
dilaporkan atau diverifikasi dan disajikan dalam gambaran deskriptif. Adapun urutan analisa isi
adalah data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan.
HASIL PENELITIAN
Pengetahuan LSL tentang IMS
Hasil analisis data diketahui informan kurang dapat menjelaskan dengan baik definisi dari
IMS. Mereka hanya mengetahui ”nama jalanan” dari IMS yaitu penyakit kelamin dan hanya
mempunyai pemahaman sebatas cara pencegahan terhadap penularan IMS. Beberapa Informan
10 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
dalam penelitan ini juga tidak dapat menyebutkan secara lengkap jenis-jenis dari IMS, dan hanya
mengetahui gejala yang di timbulkan dari IMS.
Dari hasil wawancara, salah seorang informan mengatakan bahwa IMS dapat tertular
melalui hubungan seks (intercourse) yang tidak aman (unsave sex) yaitu tidak memakai pengaman
(kondom), dan mengatakan IMS dapat tertular lewat ciuman. Adapun mengenai dampak atau
akibat yang ditimbulkan apabila seseorang menderita IMS telah diketahui oleh seluruh informan
dalam penelitian ini.
Latar belakang menjadi LSL
Seluruh informan yang diteliti mengakui pertama kali menjalani kehidupan sebagai seorang
LSL sejak mereka berusia remaja. Usia termuda LSL ditinjau dari pertama kali mereka menjalani
kehidupan tersebut adalah 13 tahun. Usia tertua pertama kali menjalani kehidupan sebagai
seorang LSL adalah 21 tahun. Adapun yang melatarbelakangi mereka untuk menjalani kehidupan
sebagai seorang LSL diantaranya adalah pelecehan seksual (sexsual violence) yang di lakukan oleh
anggota keluarganya, pergaulan tidak sehat semasa remaja, faktor ekonomi serta
ketidakharmonisan dengan orang tua, merasakan kekecewaan terhadap wanita.
Seorang LSL dapat melakukan hubungan seksual dengan perempuan, sesamanya laki-laki,
hingga waria. Kehidupan sosial informan yang cenderung menutup diri di lingkungan sekitar
mereka menyebabkan mereka cenderung untuk melakukan hubungan seksual (intercourse) di
tempat-tempat yang mereka anggap aman dan mampu menyembunyikan identitas seksual mereka.
Jenis hubungan seksual (intercourse) yang dilakukan oleh pasangan LSL sangat beragam, mulai
dari oral, anal hingga vaginal.
Perilaku pencegahan sebelum dan setelah menderita IMS
Semua informan telah pernah mengalami infeksi menular seksual dengan jenis yang berbeda-beda
mulai dari sifilis, gonore, sampai pada kondilomata. Sebelum menderita IMS informan masih
mempercayai, kepercayaan awam yang terbentuk di komunitas ini dimana kepercayaan awam
merupakan usaha pencegahan yang mereka tempuh pada saat berhubungan seksual baik dengan
pasangan laki-lakinya maupun perempuannya.
Adapun keinginan atau minat informan penelitian untuk bertindak, sehubungan dengan niat untuk
melakukan upaya pencegahan terhadap IMS antara lain dengan menggunakan kondom, konseling
dan memeriksakan kesehatan. Seluruh informan mengakui mendapatkan alat pelindung dengan
membeli, mendapatkan dari pendamping serta outlet yang telah disediakan di tempat mereka
bekerja.
Dari segi kerugian menggunakan kondom, hampir semua informan menyatakan bahwa tidak ada
kerugian yang meraka rasakan dalam menggunakan kondom. Bahkan seluruh informan setuju
terhadap penggunaan kondom ketika berhubungan seksual. Mereka menyadari akan penyakit yang
bisa, kapan saja menyerang mereka kembali. Namun mereka menjumpai beberapa kendala, seperti
kehilangan kesadaran saat mabuk, ketersediaan kondom, rasa malu untuk membelinya serta
ketidakinginan pasangannya untuk menggunakan kondom.
Hampir semua informan mengakui kalau pemakaian alat pelindung (kondom) untuk mencegah
terkena/tertular IMS, merupakan motivasi dan dorongan dari teman. Lain halnya dengan
keyakinan informan untuk mau memeriksakan diri yang diperoleh dari pengalaman melakukan
perilaku yang sama sebelumnya atau yang diperoleh dari melihat orang lain dan anjuran dari
konselor maupun teman dekat. Keyakinan informan untuk memeriksakan kesehatan merupakan
salah satu bentuk keseriusan informan terhadap pencegahan IMS. Selain pengetahuan informan
serta pengalaman pernah menderita IMS, ditentukan juga oleh ketersediaan waktu informan, akses
menuju tempat pelayanan kesehatan
Pola pencarian pengobatan terhadap IMS
Beberapa upaya pengobatan terhadap IMS yang dilakukan oleh informan adalah konsep
trial and error, mengikuti anjuran teman pergaulannya dan langsung memeriksakan kesehatannya
di pusat pelayanan kesehatan. Informan yang menerapkan konsep trial-error mengakui mengikuti
11 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
anjuran dari orang lain serta mitos-mitos yang ada di lingkungannya untuk melakukan usaha
pengobatan pada waktu menderita IMS.
Semua informan berusaha untuk menggunakan kondom selama melakukan intercourse,
dengan pasangan laki-lakinya. Mereka menyadari bahwa dengan menggunakan kondom maka
akan mencegah penularan IMS, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau (2008)
yang menyatakan bahwa perilaku seks aman, dengan menggunakan kondom secara konsisten
selama 6 bulan pada saat berhubungan seksual dengan pasangan laki-laki, di provinsi Yunan
sebesar 59%.
Seluruh informan mengakui mendapatkan alat pelindung dengan membeli. Terkadang juga
mendapatkan alat pelindung (kondom) dari manajemen, pacar maupun yang sering di bagikan oleh
KPA. Aktivitas seks yang aktif menjadikan LSL termasuk salah satu kelompok berisiko untuk
menderita IMS sehingga komitmen untuk berperilaku seks aman (save sex) dengan menggunakan
alat pelindung juga dirasakan informan.
Sebagian besar masih terperangkap di dalam kepercayaan awam (lay belief) dalam usaha
pencegahan yang berkembang di komunitas ini pada waktu berhubungan seksual dengan pasangan
laki-lakinya, Masih ada yang mempercayai bahwa apabila pasangannya terlihat bersih dan
menarik, terjalinnya kepercayaan dan keintiman, menggunakan pelumas seperti (hand body, baby
oil) pada waktu berhubungan anal sex, serta tidak membiarkan pasangannya ejakulasi di dalam
dirinya tapi membuat pasangannya ejakulasi di luar dirinya. Ada lagi yang percaya bahwa dengan
teratur berolahraga, dan minum antibiotik maka mereka akan terhindar dari IMS,
Komunitas LSL pada saat mereka berhubungan seksual dengan pasangan wanitanya
mereka sama sekali tidak menggunakan pengaman untuk usaha pencegahan terhadap penularan
IMS karena dipengaruhi perspektif mereka yang keliru, sering kali komunitas LSL ini tidak
melakukan save sex, karena mereka mengganggap pasangan wanitanya itu dari keluarga baik-baik
serta sudah terjalin hubungan keintiman yang berlangsung lama, karena perspektif yang keliru itu
mereka dapat dengan mudah menulari pasangan wanitanya, karena perilaku seksual komunitas ini
rentan untuk tertular IMS, hal ini sejalan dengan penelitian Lau (2008) yang menyatakan tingginya
pravalensi penggunaan kondom yang tidak konsisten di kalangan LSL, selama 6 bulan
berhubungan seksual dengan pasangan wanitanya sebesar 71,9 %.
PEMBAHASAN
Perilaku seksual LSL
Menurut Notoatmodjo (2007), perilaku adalah suatu yang kompleks, merupakan resultan
dari berbagai macam aspek internal maupun eksternal, psikologis maupun fisik. Perilaku tidak
berdiri sendiri karena ia selalu berkaitan dengan faktor-faktor lain. Jika dilihat dari aspek eksternal
dan psikologis, maka dapat diketahui bahwa para LSL mendapatkan tekanan yang sangat besar
pada kedua aspek tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Harawa dkk (2008) bahwa yang
melatar belakangi pria keturunan Afrika-Amerika untuk menjadi seorang LSL adalah karena
adanya riwayat kekerasan seksual, kekecewaan terhadap pasangan perempuannya, kekecewaan
karena belum memiliki anak hingga karena faktor ekonomi.
Penelitian yang dilakukan di Amerika oleh Cochran dan Mays (2011) menyatakan perilaku
seksual LSL yang melakukan hubungan seksual mulai dari ciuman, vaginal,oral hingga anal tanpa
pengaman (kondom) pada pria berusia 17- 59 tahun, menjadi faktor utama kematian dini di
kalangan LSL Amerika. Sekitar 13% meninggal terkait infeksi virus HIV dan AIDS, sejalan
dengan penelitian ini. Informan yang bekerja sebagai tukang pijat mengakui melakukan hubungan
seks secara vaginal maupun oral dan anal setelah mereka melakukan pemijatan kepada kliennya,
LSL yang bekerja di panti pijat jauh lebih mudah mengidap HIV dan AIDS dan mempunyai faktor
risiko 13% untuk meninggal di usia muda, dapat disimpulkan bahwa perilaku seksual mereka
sangat aktif dan bervariasi, serta memiliki risiko yang besar untuk tertular IMS.
Perilaku pencegahan terhadap IMS
12 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Semua informan berusaha untuk menggunakan kondom selama melakukan intercourse,
dengan pasangan laki-lakinya. Mereka menyadari bahwa dengan menggunakan kondom maka
akan mencegah penularan IMS, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lau (2008)
yang menyatakan bahwa perilaku seks aman, dengan menggunakan kondom secara konsisten
selama 6 bulan pada saat berhubungan seksual dengan pasangan laki-laki, di provinsi Yunan
sebesar 59%.
Seluruh informan mengakui mendapatkan alat pelindung dengan membeli. Terkadang juga
mendapatkan alat pelindung (kondom) dari manajemen, pacar maupun yang sering di bagikan oleh
KPA. Aktivitas seks yang aktif menjadikan LSL termasuk salah satu kelompok berisiko untuk
menderita IMS sehingga komitmen untuk berperilaku seks aman (save sex) dengan menggunakan
alat pelindung juga dirasakan informan.
Sebagian besar masih terperangkap di dalam kepercayaan awam (lay belief) dalam usaha
pencegahan yang berkembang di komunitas ini pada waktu berhubungan seksual dengan pasangan
laki-lakinya, Masih ada yang mempercayai bahwa apabila pasangannya terlihat bersih dan
menarik, terjalinnya kepercayaan dan keintiman, menggunakan pelumas seperti (hand body, baby
oil) pada waktu berhubungan anal sex, serta tidak membiarkan pasangannya ejakulasi di dalam
dirinya tapi membuat pasangannya ejakulasi di luar dirinya. Ada lagi yang percaya bahwa dengan
teratur berolahraga, dan minum antibiotik maka mereka akan terhindar dari IMS,
Komunitas LSL pada saat mereka berhubungan seksual dengan pasangan wanitanya
mereka sama sekali tidak menggunakan pengaman untuk usaha pencegahan terhadap penularan
IMS karena dipengaruhi perspektif mereka yang keliru, sering kali komunitas LSL ini tidak
melakukan save sex, karena mereka mengganggap pasangan wanitanya itu dari keluarga baik-baik
serta sudah terjalin hubungan keintiman yang berlangsung lama, karena perspektif yang keliru itu
mereka dapat dengan mudah menulari pasangan wanitanya, karena perilaku seksual komunitas ini
rentan untuk tertular IMS, hal ini sejalan dengan penelitian Lau (2008) yang menyatakan tingginya
pravalensi penggunaan kondom yang tidak konsisten di kalangan LSL, selama 6 bulan
berhubungan seksual dengan pasangan wanitanya sebesar 71,9 %.
Fakta yang ditemukan peneliti, bukan hanya faktor kepercayaan awam (lay belief) yang
membuat mereka untuk tidak berperilaku seks aman (save sex) tapi juga karena faktor hilangnya
kesadaran diri akibat pengaruh dari minuman beralkohol pada waktu berhubungan seksual
(intercourse) dengan pasangan laki-lakinya, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh
Saman dkk (2010) yang menemukan seseorang yang dalam pengaruh alkohol, dengan nilai OR
1,28 kali dapat terjangkiti virus HIV, karena melakukan hubungan seksual tanpa pengaman selama
hubungan seksual terakhir dalam keadaan mabuk.
Sedangkan selama berhubungan dengan pasangan wanitanya mereka mengakui bahwa
stigma negatif pasangan wanitanya akan kondom membuat mereka mengabaikan perilaku seks
aman (save sex), di samping informan yang bekerja dipanti pijat merasa karena untuk kepuasan
klien serta dorongan ekonomi yang membuat mereka tidak berperilaku seks aman. Alpert (1970)
mengungkapkan bahwa perilaku kesehatan individu cenderung dipengaruhi oleh kepercayaan
orang yang bersangkutan terhadap kondisi kesehatan yang diinginkan, dan kurang didasarkan pada
pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu biologi. Kenyataannya memang mendukung pernyataan
ini. Terhadap kondisi kesehatan yang terganggu masing-masing individu mempunyai cara yang
berbeda-beda dalam mengambil tindakan pencegahan atau pengobatannya.
Pola pencarian pengobatan terhadap IMS
Becker (1974) dalam Notoatmodjo (2007) dengan skema Model Kepercayaan
menyimpulkan bahwa untuk meramalkan perilaku sakit maupun sehat (variabel tergantung)
dipengaruhi oleh faktor sosiopsikologis (persepsi sakit, persepsi kegawatan penyakit, dan
sebagainya), faktor-faktor demografis, faktor struktural seperti keadaan sosial ekonomis,
kemampuan memperoleh kesehatan, dan sebagainya, pengaruh media massa, pengaruh dokter,
perhitungan cost benefit dari tindakan dan sebagainya. Begitu juga dengan informan yang akan
mencari pengobatan jika secara subjektif sudah melihat kegawatan terhadap diri atau penyakitnya.
13 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Hal ini dipengaruhi juga dengan kondisi ekonomi dari subjek yang merasa kalau tidak terlalu
penting atau mengalami kegawatan maka tidak perlu mencari pengobatan.
Sesuai dengan karakteristik informan, pada umumnya memiliki tingkat pendidikan yang
rendah dengan dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, salah satunya adalah biaya pendidikan. Hasil
analisis data yang diperoleh, diketahui bahwa pada umumnya, informan penelitian ini hanya
mengenyam pendidikan sekolah menengah umum. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mampu
menyelesaikan pendidikan dijenjang universitas, sehingga persepsi kegawatan akan penyakit lebih
di pengaruhi oleh norma subjektif (teman dekat, keluarga, orang lain).
Menurut Ngatimin (2005), persepsi setiap individu sangat dipengaruhi oleh kepercayaan
(belief) yang dianggap sebagai nilai budaya individu tersebut, kepercayaan komunitas LSL dalam
mencari pola pengobatan terhadap IMS dipengaruhi oleh kepercayaan mereka akan teman dekat,
keluarga serta informasi-informasi yang diperoleh dari orang lain, dimana menerapkan konsep
“menjadi dokter untuk diri sendiri”. Pada beberapa informan yang melakukan pengobatan dengan
meminum ramuan dan herbal (obat-obatan cina) mengakui mendapatkan informasi tentang
pengobatan tersebut dari keluarga dan teman dekat mereka. Sementara informan lain yang
mengkonsumsi anti biotik mengakui melakukan pengobatan terhadap IMS, menerapkan konsep
trial-error dimana usaha mereka untuk mengobati IMS di dapatkan dari informasi-informasi yang
mereka sering dengar dari orang lain.
Menurut Beyrer dkk (2010), individu yang memiliki pengetahuan yang cukup, keadaan
sosial ekonomis, kemampuan memperoleh akses kesehatan, dan pengaruh media massa, mereka
cenderung berperilaku positif, dalam hal ini sejalan dengan pengakuan informan yang melakukan
usaha pengobatan terhadap IMS tidak dipengaruhi oleh norma subjektif, mereka mengabaikan
pandangan tersebut dan langsung memeriksakan kesehatan mereka di pusat pelayanan kesehatan
karena akses untuk memperoleh kesehatan di dapatkan dengan mudah, kemampuan ekonomi yang
cukup, disertai dengan pengetahuan akan penularan IMS yang cukup.
Usaha pengobatan komunitas LSL terhadap IMS yang berpatokan pada konsep menjadi
dokter sendiri inilah yang membuat sulitnya mendeteksi pravalensi kejadian IMS di komunitas ini
sehingga untuk program pencegahan pun masih sulit untuk dilakukan.
SIMPULAN DAN SARAN
Setelah dilakukan penelitian, maka dapat diambil simpulan bahwa usaha yang dilakukan
sebagian besar informan terhadap pencegahan IMS adalah dengan penggunaan alat pelindung
(kondom), memeriksakan kesehatan serta konseling ke pelayanan kesehatan. Sedangkan pola
pencarian pengobatan terhadap IMS yang dilakukan oleh lima informan masih menerapkan konsep
menjadi dokter buat diri sendiri dengan meminum ramuan, obat cina dan antibiotik yang
informasinya diperoleh dari teman, keluarga maupun LSM yang mendampinginya. Sementara dua
informan lainnya memilih untuk langsung memeriksakan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan
ketika menderita IMS.
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat disampaikan
yakni pentingnya Penguatan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dalam bidang pencegahan
terhadap Infeksi Menular Seksual (IMS), serta melakukan penjangkauan (outreach) secara berkala
dan berkesinambungan, untuk membina dan mengarahkan kalangan LSL dalam program untuk
mendapatkan informasi, konseling, pengobatan, pengarahan dan kontrol.
DAFTAR PUSTAKA
Alpert, J.J. et al. 1970. Attitudes and satisfactions of low-income families receiving
comprehensive pediatric care. Am J Public Health Nations Health. Vol.3 No.6. Maret
1970: 499–506
Aral, O. Sevgi et al. 2007. Behavioral Intervention for Prevention and Control of Sexually
Transmitted Diseases.Goergia: Springer Science and Business Media
14 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Babbie, Earl. 1998. The Practice of Social Research. California: WadsWorth.
Beyrer, Chris. 2010. The Expanding Epidemics of HIV Type 1 Among Men Who Have Sex With
Men in Low- and Middle-Income Countries: Diversity and Consistency. American
Journal of Epidemiology. April 2010
Calvet, M. Helene. 2009. Sexually Transmitted Diseases Other than Human Immunodeficiency
Virus Infection in Older Adults. Clinical Infectious Diseases Journal. Vol. 36 2009:
609–14
Creswell, John W, 1994 Research Design Qualitative & Quantitative Approach. London: SAGE
Daili, S, 2001. Penyakit Menular Seksual. Edisi Kedua, Cetakan ke-1. Jakarta: Balai Penerbit
FKUI.
Depkes RI. 2010. Profil Kesehatan Indonesia tahun 2010.
Djajakusumah. 2008.IMS. (Online), (http://igama.org/index.php?option=com_content&task=
view&id=591&Itemid=1diakses 27Maret 2012)
Fay, Heather et al. 2010. Stigma, Health Care Access, and HIV Knowledge Among Men Who
Have Sex With Men in Malawi, Namibia, and Botswana. AIDS Education Prevention.
Vol.19 N0.4 2010: 346–64
Ngatimin,Rusli. 2005. Ilmu Perilaku Kesehatan. Makassar: Yayasan PK-3
Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta: Rineka Cipta
Rahardjo, M. 2010. Antara Rumusan Masalah dan Fokus Penelitian.(Online).(http://
mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/292-antara-rumusan-masalah-dan-fokus-penelitian-
bahan-kuliah-metpen-s1-s2-dan-s3-.html Diakses 18 April 2011).
15 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
EVALUASI PROGRAM PROMOSI K3 TERHADAP PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA
DI PT. KATINGAN TIMBER
CELEBES MAKASSAR
Aminah1, Muh. Syafar2, Syamsiar Russeng3
1
Balai Besar Keselamatan Kesehatan Kerja Makassar
2
Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Hasanuddin
3
Jurusan Kesehatan Kerja, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin
Abstrak
Masalah Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) secara umum di Indonesia masih sering
terabaikan. Pelaksanaan K3 yang baik akan menciptakan lingkungan kerja yang selamat dan
sehat sehingga mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Penelitian ini
bertujuan menganalisis pelaksanaan program promosi K3 dalam upaya pencegahan kecelakaan
kerja di Perusahaan PT. KTC Makassar. Penelitian dilaksanakan pada PT KTC Makassar dengan
menggunakan pendekatan fenomenologis. Informan penelitian adalah manajemen perusahaan,
petugasK3, tenaga kerja dan melakukan pengecekan keabsahan data secara triangulasi.
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis
dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan program K3 di
perusahaan PT KTC Makassar belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya pelaksanaan
program promosi K3 berupa penyuluhan, pelatihan, pemasangan poster, instruksi dan rambu-
rambu K3 di perusahaan, akibat kurangnya komitmen manajemen perusahaan tentang K3. Hal ini
berdampak pada pemahaman terhadap pengetahuan K3, sikap, dan praktek K3 yang rendah
sehingga tidak mendukung upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja
Kata kunci : Promosi K3, Pencegahan Kecelakaan Kerja
Abstract
Occupational Safety health Issues (OSH) in general in Indoesia is still often overlooked.
A good implementation OSH will create safe work environment and healthy so as to prevent
accidents and occupational diseases. The aim of the research is to analyze the implementation of
Occupational Safety health promotion program for the prevention of occupational accident in
PT.Katingan Timber Celebes, Makassar. The research was a qualitative study with
phenomenology approach conducted in PT.Katingan Timber Celebes Makassar, based on many
considerations. The methods of obtaining the data were in-depth interview, observation and
documentation. The selection of informants was based on representation of manajement,
employees, and officials of occupational Safety health and done by checking the data validity
using triangulation. The results of the research reveal that the implementation that the
information of occupational safety health promotion program in PT Katingan Timber Celebes,
Makassar is not optimal. This is indicated by the low implementation of occupational safety
Health promotion program (couseling, training, poster, instruction, and signposts of occupational
safety halth Promotion Program) in the company, the lack of commitment from company
manajement on occupational safety health promotion program which affects the understanding on
occupational safety health promotion program, and the low attitude and practice of occupational
safety health promotion program which does not support the efforts of preventing the occurrence
of occupational accident
Key words: Occupational Safety Health Promotion, Prevention of Occupational Accident
16 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
PENDAHULUAN
E ra globalisasi dan pasar bebas akan berlaku tahun 2020 mendatang. Merupakan
salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam hubungan ekonomi perdagangan
barang dan jasa antara Negara termasuk Indonesia adalah penerapan di bidang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Karena itu masalah K3 menjadi isu global dan sangat
penting dalam dunia industri, apalagi kemudian dikaitkan dengan perlindungan tenaga kerja dan
hak azasi manusia serta kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan dan pencegahan
kecelakaan dijelaskan bahwa perusahaan wajib melindungi keselamatan pekerja yaitu dengan
memberi penjelasan kepada tenaga kerja tentang kondisi dan bahaya tempat kerja, alat pelindung
diri, yang diharuskan dalam tempat kerja, serta cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan
pekerjaan (Suma’mur, 1989).
Sebagai pelajaran di PT Kutai Chip Meal (KCM), di kawasan Teluk Waru, Kariangau,
Balikpapan Barat, dimana secara operasional telah menjalankan program Keselamatan dan
Kesehatan kerja (K3) yang dinilai memenuhi standar, namun perusahaan tersebut belum memiliki
Sistim Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3). Kendati demikian, sudah dibentuk
Panitia Pembina K3 (P2K3) yang bertugas memandu sistem keselamatan kerja. Contohnya, sistem
pengawasan di perusahaan pengolahan kayu tersebut terbilang canggih. Hampir di setiap sudut
lokasi terpasang closed circuit television (CCTV) yang dikontrol terpusat. Dari sisi safety sudah
bagus dan memenuhi standar, namun seorang karyawan subkontraktor PT KCM, mengalami
kecelakaan kerja. Korban diduga terpeleset dan jatuh di atas conveyor. Saat itu, dia tidak sempat
menyelamatkan diri dan masuk ke lubang tempat mesin penghancur kayu, membuat tubuh korban
hancur dan bercampur serbuk kayu.
PT. Katingan Timber Celebes (KTC) merupakan salah satu perusahaan besar di Makassar
yang memproduksi kayu log menjadi kayu lapis yang berkualitas tinggi. Pekerja di PT. KTC juga
tidak terlepas dari masalah kecelakaan kerja. Berdasarkan data PT. Jamsostek angka kecelakaan
kerja pada perusahaan PT. KTC masih cukup tinggi. Dengan demikian penelitian ini ditujukan
untuk memperoleh informasi tentang upaya-upaya program promosi K3 terhadap pencegahan
kecelakaan kerja di Perusahaan PT. KTC Makassar.
BAHAN DAN METODE
Lokasi Penelitian
Pemilihan lokasi penelitian pada perusahaan PT. KTC berdasarkan pertimbangan alasan
adanya resiko bahaya di tempat kerja yang bersumber dari alat (mesin, gergaji), bahan (kayu), dan
sisa hasil produksi (serbuk) serta dari tenaga kerja (perilaku K3 yang rendah), angka kecelakaan
kerja tinggi dan kesediaan perusahaan untuk menjadi tempat penelitian.
Desain Penelitian
Studi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
Dengan melihat variabel terdiri dari : variabel pelatihan, penyuluhan, pemasangan poster,
instruksi K3 dan rambu K3 yang diduga mempunyai relasi terhadap pembentukan pengetahuan
dan sikap untuk kemudian menjadi dasar praktek pencegahan kecelakaan kerja.
Pemilihan Informan
Informan dalam penelitian ini keseluruhannya adalah pekerja yang bekerja di PT. KTC.
Jumlah informan yang diambil sebanyak 15 orang dipilh secara purposive sampling (sengaja),
terdiri dari HRD, asisten manajer, safety officer, tenaga kerja produksi yang mewakili masing-
masing unit/bagian (rotary, hot press, grading, operator boiler, operator forklift dll).
pengumpulan data
Sesuai dengan bentuk pendekatan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data
yang digunakan adalah melalui wawancara yang mendalam, observasi dan dokumen.Untuk
mengumpulkan data dalam kegiatan penelitian menggunakan cara-cara atau teknik pengumpulan
17 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
data tertentu, sehingga proses penelitian dapat berjalan dengan lancar. Sumber dan jenis data
terdiri atas kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain..Wawancara mendalam
dilengkapi dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, alat perekam, pencatatan.
Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Dari
hasil observasi dapat menggali persepsi pekerja (Emik), melihat, merasakan dan menghayati dari
sudut pandang mereka terhadap pelaksanaan program promosi K3 dan manfaat yang dirasakan
oleh pekerja berkaitan dengan pencegahan kecelakaan kerja.
Analisis Data
Dalam penelitian ini analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data
dilakukan. Di awal penelitian data yang baru, dianalisis untuk mengetahui data apalagi yang mesti
dicari dan didalami, serta untuk menyusun strategi agar dapat masuk lebih dalam ke dalam
komunitas pekerja. Dipertengahan dan menjelang berakhir penelitian data dianalisis lagi, untuk
melakukan pemeriksaan keabsahan data. Selanjutnya data dianalisis untuk mengungkap makna
temuan penelitian dan pengambilan kesimpulan. Untuk menjamin keabsahan data maka peneliti
melakukan pengecekan data secara triangulasi. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi dengan
sumber dan metode. Triangulasi dengan sumber ini dilaksanakan kepada petugas pengelola
program K3 dan pekerja di pabrik serta staf manajemen atau supevisor perusahaan dengan tujuan
untuk membandingkan data dari informan yang berbeda. Sedangkan Triangulasi dengan metode
yaitu dengan cara pengecekan derajat kepercayaan hasil penemuan penelitian dengan
menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi atau
pengamatan/ observasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Di perusahaan PT KTC telah dilakukan program promosi K3 dalam bentuk penyuluhan
K3, pelatihan K3 serta pemasangan poster, instruksi dan rambu-rambu K3, dengan harapan tenaga
kerja dapat memahami dan melaksanakan program K3 di Perusahaan dan melakukan upaya-upaya
pencegahan kecelakaan kerja misalnya melakukan pemeriksaan kesehatan kerja, pemeriksaan
lingkungan kerja dan pemakaian APD yang sesuai peraturan perundang-undangan.
Penyuluhan K3
Berdasarkan hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa pada umumnya informan
tidak pernah mendapatkan penyuluhan K3 di perusahaan ataupun dari pihak luar sebagai
penyelenggara. Oleh karena adanya kebijakan manajemen penyuluhan hanya dilakukan dua kali
setahun dan hanya diikuti oleh satu orang mewakili satu unit dan diprioritaskan pada tenaga kerja
baru, sehingga jumlah karyawan yang 1861 orang dan tingginya jumlah tenaga kerja yang masuk-
keluar tidak akan dapat menjangkau semuanya. Hal ini akan berpengaruh terhadap peningkatan
pengetahuan tenaga kerja tentang K3. Sebaiknya promosi K3 dalam bentuk penyuluhan harus
diberikan pada semua pekerja tanpa membedakan tenaga kerja baru atau lama, tenaga kerja tetap
atau yang status kontrak (out sourcing) bahkan pada semua level dari tenaga kerja produksi sampai
ke level manajer, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang K3 dengan
harapan dapat merubah sikap dan tindakan berorientasi keselamatan dan kesehatan kerja saat
melakukan aktifitas di tempat kerja.
Penyuluhan K3 adalah kegiatan pendidikan K3, yang dilakukan dengan menyebarkan
pesan, menanamkan keyakinan, sehingga TK tidak saja sadar, tahu dan mengerti, tetapi juga mau
dan bisa melakukan anjuran yang ada hubungannya dengan K3. Publikasi K3 dalam bentuk
penyuluhan sangat bermanfaat untuk memberikan pemahaman pada tenaga kerja mengenai
pentingnya K3. Dari hasil wawancara mendalam memberikan petunjuk bahwa setidaknya telah
tiga tahun aktifitas penyuluhan K3 tidak pernah dilakukan oleh manajemen perusahaan.
Sesuai hasil penelitian Tarigan (2008) dalam penelitiannya melihat penerapan penyuluhan
tentang SMK3 yang dilaksanakan secara berkala dan selalu melibatkan seluruh pekerja bahkan
adakalanya dihadiri oleh pengambil kebijakan (manajer dan supervisor), keadaan ini dilakukan
untuk memastikan bahwa kemampuan dan ketrampilan pekerja terhadap SMK3 semakin
18 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
meningkat. Berdasarkan hasil penelitan Tarigan (2008) nampak bahwa penerapan SMK3
berdampak posititf bagi perusahaan, dapat terlihat dari minimnya angka kecelakaan kerja
dilingkungan pabrik kelapa sawit, serta diperolehnya beberapa penghargaan tentang keselamatan
kerja . Sesuai penelitian Mahuri (2010), dijelaskan bahwa perlu diadakan penyuluhan dan
pelatihan K3 secara rutin bagi karyawan PT. Primatexco Indonesia untuk menumbuhkan
kesadaran akan pentingnya K3 dan tindakan tegas bagi karyawan yang melanggar peraturan serta
adanya tanda-tanda peringatan bahaya terutama di tempat-tempat yang berpotensi menyebabkan
kecelakaan kerja.
Pelatihan K3
Pelatihan yang telah dilaksanakan oleh PT. KTC adalah pelatihan pemadam kebakaran,
serta pelatihan yang berkaitan dengan mutu dan lingkungan, namun pelatihan spesifikasi K3 tidak
pernah dilakukan sejak tiga tahun terakhir. Pelatihan merupakan salah satu faktor yang diperlukan
oleh TK untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Pelatihan yang dimaksud dalam penelitian
ini adalah pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan keselamatan kesehatan kerja. Adanya
pelatihan K3 yang diberikan oleh perusahaan akan membuat karyawan bekerja dengan lebih
berhati-hati dan dapat melindungi diri dari kecelakan kerja yang mungkin terjadi.
Pengetahuan dan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan khusus,
apalagi dilihat dari latar belakang pendidikan mereka pada umumnya tidak memiliki spesialisasi
bidang K3 atau ahli K3, bahkan operator pun hanya dengan latar belakang pendidikan SLTP.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa kurangnya peran
manajemen dalam menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang profesional dalam menjalankan tugasnya
di tempat kerja, bahkan tenaga kerja spesialis pun (operator forklift) belum pernah mendapatkan
pelatihan khusus berkaitan dengan tugasnya, sehingga wawasan tentang K3 sangat kurang dan
dapat mempersulit dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut H. W. Heinrich, penyebab kecelakaan
kerja yang sering ditemui adalah perilaku yang tidak aman sebesar 88%, kondisi lingkungan yang
tidak aman sebesar 10%, atau kedua hal tersebut di atas terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu,
pelaksanaan pelatihan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dapat mencegah perilaku yang
tidak aman dan memperbaiki kondisi lingkungan yang tidak aman.
Berdasarkan hasil penelitian Tarigan (2008) bahwa efek dari pelatihan yang diikuti oleh
tenaga kerja sangatlah besar, seperti timbulnya kesadaran untukmenggunakan APD, mematuhi jam
kerja terutama saat bekerja yang membutuhkan kekompakan, meningkatnya kesadaran menangani
prkrrjaan sesuai tugas masing-masing. Tujuan utama pelatihan K3 adalah pada prinsipnya untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya,
sehingga tenaga kerja menjadi semakin terampil dan terlatih dan lebih berhati-hati dalam bekerja.
Sesuai hasil penelitian Kusuma (2010) menunjukkan bahwa dengan adanya pelatihan K3 bagi
karyawan sebagai salah satu elemen pelaksanaan program K3 di PT. Bitratex Industries dapat
memberi manfaat pengurangan absentisme akibat kurangnya bahkan ada informan yang tidak
pernah membolos kerja akibat mengalami kecelakaan atau PAK. Hal ini menunjukkan bahwa
frekwensi kecelakan kerja dan/PAK sangat kecil. Untuk meningkatkan perilaku K3 sehingga
mengurangi kecelakaan kerja maka diperlukan pelatihan K3 untuk meningkatkan kompetensi dan
pemahaman K3 pada seluruh line management dan tenaga kerja.
Salah satu metode belajar yang sangat efektif adalah belajar sambil
melakukan/mempraktekkan (learning by doing). Belajar pada dasarnya adalah melatih dan
menumbuhkan kemampuan, pengetahuan dan sikap melalui pembiasaan sehingga terjadi
perubahan perilaku/ kebiasaan. Pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan kemampuan dan
keterampilan yang dimiliki tenaga kerja. Produktivitas akan meningkat bila tenaga kerja mampu
menjalankan pekerjaan mereka dengan baik. Keterampilan kerja yang baik dapat diperoleh melalui
program pelatihan K3 baik yang umum maupun spesialis atau keterampilan K3 khusus, seperti
boiler atau forklift. Keadaan ini selaras dengan hasil penelitian Nurmalinda (2008) menunjukkan
bahwa pekerja yang telah dilatih K3 lebih mengetahui tata cara bekerja yang lebih sehat serta tidak
19 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
membahayakan, sehingga dalam penelitian ini kecenderungan kecelakaan terjadi pada pekerja
yang tidak pernah mengikuti pelatihan K3.
Hasil penelitian Angkat.S, menunjukkan efek dari pelatihan K3 sangatlah besar, seperti
timbulnya kesadaran untuk menggunakan APD, mematuhi jam keja, meningkatnya kesadaran
dalam hal menangani pekerjaan sesuai dengan tugas masing-masing, efek lainnya adalah semakin
meningkatnya kinerja dan efisisensi kerja. Hal ini ditunjukkan dari semakin bersihnya lingkungan
kerja terutama pada bagian mesin produksi, yaitu dengan tidak ditemukannya lagi ceceran minyak/
solar/ oli di sekitar mesin, bahkan tidak ditemukan penumpukan sisa-sisa bahan atau sampah pada
area kerja.
Pemasangan Poster, Instruksi, dan Rambu-rambu K3
Pada penelitian ini, promosi K3 melalui poster, instruksi, atau rambu-rambu K3 yang
dilakukan perusahaan kurang efektif, ini dapat dilihat dari gambar dan pesan-pesan yang
ditampilkan kurang jelas maknanya, kurang menarik dan penempatan yang tidak strategis, bahkan
nyaris tak terbaca oleh karena sudah sangat usang. Padahal adanya informasi-informasi yang tepat
sasaran akan mempengaruhi tenaga kerja untuk bertindak dengan memperhatikan keselamatan
dan kesehatannya. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian Lestari,T. Trisyulianti. E pada
penelitian hubungan K3 dengan produktivitas kerja karyawan pengolahan PTPN VIII Gunung Mas
Bogor, menjelaskan bahwa publikasi keselamatan kerja memiliki nilai korelasi yang paling
rendah, dikarenakan publikasiyang dilakukan oleh perusahaan tidak efektif, dapat dilihat dari
gambar dan pesan-pesan yang kurang menarik dan penempatan yang tidak strategis.
Jika poster yang dipakai menunjukkan kesan humor dan menarik, dan diganti setiap
minggunya, para tenaga kerja pasti tertarik untuk membacanya. Untuk tempat yang strategis
hindari tempat pemasangan yang harus mendongak baru terbaca, tetapi di tempat-tempat yang
pada umumnya tenaga kerja setiap hari berada di tempat tersebut, misalnya di kantin, di lemari
penyimpanan, dekat peyediaan air minum, disamping toilet, dll yang terpasang di dinding dan
dapat terlihat dengan mudah.
Berdasarkan hasil penelitian Szczygyelska (2011) menjelaskan bahwa sikap dapat
dipengaruhi dari penyediaan informasi tentang Occupational Safety Health (OSH), pemberian
informasi K3 yang menarik melalui poster tidak hanya menarik perhatian pekerja, tetapi dapat
mempengaruhi sikap mereka terhadap keselamatan kerja Penyediaan informasi yang sesuai bagi
pekerja/buruh dan semua pihak yang terkait dapat digunakan untuk memotivasi dan mendorong
penerimaan serta pemahaman umum dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan kinerja,
misalnya pemasangan poster dengan warna dan gambar yang menarik yang bertuliskan “
pokoknya, resiko terkena bahaya tidak boleh ada disini “.
Perusahan harus mempunyai prosedur untuk menjamin bahwa informasi K3 terbaru di
komunikasikan ke semua pihak dalam perusahaan. Ketentuan dalam prosedur tersebut dapat
menjamin pemenuhan kebutuhan. Berdasarkan hasil penelitian Tarigan (2008), menjelaskan
bahwa upaya-upaya SMK3 telah dilakukan manajemen perusahaan Pabrik Kelapa Sawit, misalnya
pengadaan papan pengumuman yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya kecelakaan
kerja di area pabrik. Sesuai hasil penelitian wicaksono (2011), pada proyek pembangunan
apartemen puncak permai Surabaya, diperoleh alternatif pengendalian resiko yang dapat dilakukan
pada resiko material terjatuh adalah inspeksi K3 harian, pemasangan barrigation,traffic cone serta
rambu K3.Adanya poster, instruksi dan rambu-rambu K3 sebagai tanda peringatan dan tanda
bahaya di tempat kerja membuat tenaga kerja bekerja dengan lebih berhati-hati, karena
lingkungan kerja yang aman dan sehat akan meningkatkan motivasi kerja sehingga juga akan
meningkatkan produktivitas kerja.
Pengetahuan
Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengetahuan informan tentang K3 bagi manajemen
dan petugas K3 (safety Officer) cukup baik, tetapi pada umumnya informan tenaga kerja produksi
20 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
belum memahami K3, dikarenakan informan tersebut tidak pernah mengikuti pelatihan atau
penyuluhan K3. Untuk mewujudkan keberhasilan program promosi K3, salah satu aspek yang
perlu diperhatikan adalah sumber daya manusisa (SDM) yang berkualitas dalam hal ini Tenaga
Kerja (TK), maka harus memiliki suatu pengetahuan yang baik, karena pengetahuan sangat
penting dalam memberikan wawasan seseorang terhadap sikap dan tindakan atu praktek.
Pengetahuan tentang manfaat K3, akan mempunyai sikap yang positif terhadap hal
tersebut. Selanjutnya sikap yang positif akan turut serta dalam kegiatan akan menjadi tindakan
apabila mendapat dukungan sosial dan tersedianya fasilitas perusahaan. Faktor yang
mempengaruhi pengetahuan adalah pengalaman individu terhadap sesuatu obyek dan informasi
yang diterima oleh individu. Pengetahuan akan K3 cenderung disertai dengan penerapan sikap.
Tentunya hal ini berperan penting dalam mengurangi tingkat kecelakaan kerja. Sehingga
diperlukan suatu program yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan atau mengurangi
kemungkinan suatu kecelakaan terjadi pada para tenaga kerja
Sesuai hasil penelitian Markannen (2004). menjelaskan bahwa adanya pelatihan
keselamatan pada karyawan membuat karyawan menjadi semakin terlatih dan terampil serta lebih
berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya sehingga tujuan pelatihan yang diadakan oleh
perusahaan untuk melatih karyawan dalam menghindari terjadinya kecelakaan kerja dan
melindungi diri apabila terjadi kecelakaan kerja dapat tercapai. Hasil penelitian ini juga sesuai
dengan hasil penelitian Mahuri (2010), menyatakan bahwa ada hubungan yang cukup kuat antara
pengetahuan keselamatan kerja dengan pelaksanaan pencegahan kecelakaan kerja pada karyawan.
Pengaruh pengetahuan K3 terhadap praktek dapat bersifat langsung maupun melalui perantara
“sikap”. Suatu sikap tidak otomatis terwujud dalam bentuk praktek. Untuk terwujudnya sikap agar
terjadi suatu perbuatan atau tindakan diperlukan faktor pendukung misalnya sikap tehadap
pentingnya APD, tetapi manajemen tidak mendukung dalam penyediaan APD, sehingga praktek
TK untuk upaya pencegahan kecelakaan kerja tidak akan terjadi.
Sikap
Beberapa definisi Sikap diantaranya adalah bentuk evaluasi atau reaksi perasaan, sikap
seseorang terhadap obyek, perasaan mendukung atau memihak. Keberhasilan suatu program
promosi K3 sangat dipengaruhi oleh sikap penerimaan dan dukungan dari manajemen serta
seluruh tenaga kerja. Hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sikap informan dalam
upaya program promosi K3 umumnya menerima dan mendukung, dapat dilihat dari adanya
organisasi standar atau STD (Siaga Tanggap Darurat) sebagai organisasi yang programnya sama
dengan P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan Kesehatan Kerja), namun dari pihak manajemen
melihat ada kendala dalam pelaksanaan program-program tersebut khususnya pada pembiayaan
sehingga dalam hal ini manajemen mengharapkan dukungan lintas sektor seperti Disnakertrans
dan PT Jamsostek, sehingga program K3 dalam kegiatan promosi K3 untuk menurunkan angka
kecelakaan kerja dapat berjalan optimal.
Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian salawati (2009) menyatakan bahwa 10
responden yang bersikap setuju, sebanyak 4 pekerja (40%) pernah mengalami kecelakaan kerja,
hal ini menunjukkan bahwa pekerja yang bersikap setuju mengalami juga kecelakaan kerja karena
pekerja tersebut ada yang tidak memperoleh promosi K3 yang baik, ada yang tidak pernah
mengikuti pelatihan, ada yang berpengetahuan kurang dan ada yang bertindakan salah saat
bekerja. Hasil penelitian dapat dibandingkan pada hasil penelitian Schzielska (2011) yang
mengatakan bahwa ada hubungan bermakna antara sikap terhadap keselamatan kerja dan
melakukan prosedur yang sesuai keselamatan kerja sehingga dapat menciptakan suasana kerja
yang aman terhindar dari kecelakaan kerja.Penerapan program K3 di suatu perusahaan diarahkan
kepada kemandirian perusahaan dan sangat tergantung dari rasa tanggung jawab manajemen dan
tenaga kerja terhadap tugas dan kewajiban masing-masing, serta upaya-upaya untuk menciptakan
cara kerja dan kondisi kerja yang selamat.
Saat ini industri telah dituntut untuk menerapkan Manajemen Kualitas (ISO-9000, QS-
9000) serta Manajemen Lingkungan (ISO-14000) maka bukan tidak mungkin tuntutan terhadap
21 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
penerapan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja juga menjadi tuntutan pasar
internasional. Untuk menjawab tantangan tersebut Pemerintah yang diwakili oleh Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan sebuah peraturan perundangan mengenai Sistem
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang tertuang dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja Nomor : PER.05/MEN/1996.
Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Tarigan (2008) yang mengungkapkan bahwa
manajemen Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan memiliki komitmen yang kuat untuk
mengembangkan serta mempertahankan SMK3 di lingkungan kerja sehingga diperoleh situasi dan
kondisi kerja yang lebih kondusif dan mampu menekan angka kecelakaan kerja sampai pada
tingkat Zero Accident. Komitmen yang kuat dan perhatian yang besar dari manajemen perusahaan
mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja dapat memotivasi karyawan untuk
memperhatikan keselamatan dan kesehatannya sewaktu bekerja.
Praktek Pencegahan Kecelakaan Kerja.
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dimana informan
menganggap kecelakaan tersebut terjadi karena sudah nasib, namun jika dilihat dari sebelum
terjadi kecelakaan faktor keadaanlah merupakan sebab kecelakaan dimana mesin tidak bisa
dioperasikan dalam arti peralatan tidak aman (Unsafe Condition), atau pada kasus lain dimana
akibat menggunakan kaca mata pelindung yang tidak layak sehingga debu-debu kayu masih tetap
dapat masuk ke mata, gambaran ini menunjukkan bahwa tenaga kerja melakukan tindakan yang
salah karena menggunakan APD yang tidak cocok. Dari kedua kasus ini pada dasarnya kecelakaan
kerja terjadi akibat tindakan yang tidak aman (Unsafe act) dan kondisi yang tidak memungkinkan
(unsafe Condition), ini sesuai dengan teori Domino dari Heinrich bahwa sekitar 88% kecelakaan
kerja disebabkan oleh tindakan yang salah, sehingga dengan melihat kasus ini maka pendekatan
pencegahan yang paling tepat adalah bagaimana merubah perilaku tenaga kerja untuk berperilaku
K3, sehingga dapat bekerja tetap selamat, sehat dan produktif.
Hasil penelitian ini sama terhadap hasil penelitian Kemala, A. “Pelaksanaan K3 dan efek
psikososial Lingkungan Kerja Pada Pabrik SSP II PT. KS Unit Peleburan” menjelaskan bahwa
kondisi lingkungan kerja pabrik memiliki efek psikososial, dimana kondisi lingkungan pabrik yang
panas, bising, menghirup zat kimia berbahaya dan debu yang ada diman-mana, menyarankan
untuk meminimalkan resiko kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan karyawannya antara lain :
meyediakan APD sesuai jumlah karyawan, mengecek apakah karyawan sudah mematuhi atau
menggunakan APD sesuai dengan kondisi kerjanya serta memberikan hukuman pada karyawan
yang lalai dalam menggunakan APD.
Sesuai hasil penelitian dari salawati (2009) juga menunjukkan bahwa ada hubungan
antara promosi K3 dengan terjadinya kecelakaan kerja di Laboratorium Patologi Klinik RSUZA
Banda Aceh. Pada penelitian ini memperlihatkan bahwa pekerja yang memperoleh promosi K3
yang tidak baik mengalami kecelakaan kerja lebih tinggi daripada pekerja yang memperoleh
promosi K3 yang baik. Hasil penelitian Tarigan ( 2008), menjelaskan bahwa ada pengaruh
penerapan SMK3 pada perusahaan Pabrik Kelapa Sawit Tanjung Medan, dapat terlihat dari
minimnya angka kecelakaan kerja di lingkungan pabrik serta diperolehnya beberapa penghargaan
tentang keselamata kerja seperti sertifikat “Zero Accident” pada tahun 2005 dan empat kali meraih
sertifikat “Bendera Emas” dan tiga kali “Bendera Perak” pada audit SMK3 periode tahun 2000 –
2006.
Hasil penelitian yang sama dari Angkat (2008) menjelaskan bahwa penggunaan APD
berpengaruh terhadap kecelakaan kerja yang mana TK yang tidak menggunakan APD lebih
banyak mengalami kecelakaan kerja dari pada TK yang menggunakan APD. Dalam pelaksanaan
program kegiatan K3, maka sangatlah mendasar fungsi organik manajemen untuk menggerakkan
setiap tenaga kerja yang ada diperusahaan tanpa melihat status tenaga kerja tetap atau kontrakan
(out sourcing) untuk melakukan aktivitas-aktivitas dalam pencapaian tujuan dan sasaran K3.
22 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Dari pembahasan diatas nampak bahwa kecelakaan dapat terjadi bila timbul keadaan
tidak aman dan atau tindakan tidak aman, kedua penyebab utama terjadinya kecelakaan ini muncul
antara lain karena sikap dan perilaku karyawan yang bersangkutan yaitu tidak tahu (adanya
bahaya), tidak mau tahu (adanya ancaman bahaya) dan tidak mampu (menghadapi bahaya) :
karena tidak pernah dilatih K-3 sehingga tidak berpengalaman melaksanakan pekerjaan dengan
cara aman dan selamat. Akibat dari kecelakaan adalah kerugian yang dapat berupa cidera/
disability yang menimpa karyawan bahkan kematian, kerusakan harta benda atau kerugian proses
operasi. Dalam pasal 86 UU No.13 tahun 2003, dinyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh
mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan
kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.
Kelemahan sistem manajemen mempunyai peranan yang sangat besar sebagai penyebab
kecelakaan, karena sistem manajemenlah yang mangatur unsur-unsur produksi. Sehingga sering
dikatakan bahwa kecelakaan merupakan manifestasi dari adanya kesalahan manajemen dalam
proses produksi. Oleh karena itu manajemen beserta seluruh pekerja harus mempromosikan
pendekatan sistem manajemen Keselamatan Kesehatan kerja (K3), seperti pendekatan yang
ditetapkan dalam panduan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK3).
Menetapkan kebijakan akan komitmen terhadap program K3, yang dipromosikan melalui program
penyuluhan K3, pelatihan K3, pemasangan poster, instruksi/rambu-rambu K3 serta di dukung
penyediaan fasilitas-fasilitas K3 seperti APD yang sesuai peraturan perundang-undangan dan
pelaksanaan program-program K3 yang berkesinambungan dan menyeluruh misalnya pemeriksaan
kesehatan awal, berkala dan khusus serta pemeriksaan lingkungan kerja dalam upaya pencegahan
kecelakaan kerja.
KESIMPULAN DAN SARAN
Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan K3 belum optimal. Selain itu pemasangan poster,
instruksi dan rambu-rambu K3 belum dilaksanakan dengan maksimal karena engetahuan K3 pada
TK produksi sangat kurang. Di sisi lain Sikap TK terhadap K3 mendukung namun tidak didukung
oleh manajemen perusahaan untuk penyediaan anggaran khusus terhadap program K3 seperti
penyediaan APD yang layak baik kualitas maupun kuantitas dan pemeriksaan kesehatan serta
pemeriksaan lingkungan kerja yang sesuai peraturan perundang-undangan . Terlebih lagi para
tenaga kurang disiplin menerapkan perilaku K3. Dari hasil analisa angka kecelakaan tertinggi pada
bagian Rotary, merupakan tempat dengan kebisingan yang melebihi NAB, yang mana penyebab
kecelakaan akibat kondisi dan tindakan yang tidak aman (kelalaian, ketidaktahuan).
Sebaiknya manajemen perusahaan membuat komitmen untuk menetapkan kebijakan
penerapan K3 yang optimal serta dikomunikasikan kebijakan tersebut pada semua level tenaga
kerja baik tenaga kerja tetap maupun out sourcing. Melaksanakan program-program kebijakan K3
seperti upaya promosi K3, penyediaan APD yang sesuai peraturan perundang-undangan,
pemeriksaan kesehatan kerja, dan pemeriksaan lingkungan kerja yang berkesinambungan dan
menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas kepada tenaga kerja yang melanggar kebijakan K3
yang telah ditetapkan perusahaan.
23 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
DAFTAR PUSTAKA
Angkat, S. (2008). Analisis Upaya Pencegahan Kecelakaan Kerja pada pekerja bangunan
Perusahaan. X.(tesis), (serial online) diunduh 17 November 2011. Dari USU
Reposittory http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/6653/1/09E00804.pdf,
Cahyani, P (2009). Pemetaan sitem organisasi sebagai reflexi budaya Keselamatan Kerja
K3 hak dasar perlindungan tenaga kerja (2011) . M power. Volume.6. Nomer 2 : 8 – 9
Kerangka Konsep Promosi Keselamatan Kesehatan Kerja (serial online) diunduh 29 Desember
2010. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/.../---ro.../wcms_145827.pdf,
Kusuma, I.J. (2010). Pelaksanaan Program K3 Karyawan PT. Bitratex Industries.(serial online)
diunduh 24 Maret 2012. http://eprints.undip.ac.id/26498/2/Jurnal.pdf.
Markkanen, P.K. (2004). Kertas kerja K3 di Indonesia. (serial online) diunduh 12 Januari 2012.
http://www.ilo.org/wcmsps/group5/public/Casia/Cro-bangkok/cilo-jakarta/
documents/publication.
Mahuri. (2010). Hubungan Pengetahuan Keselamatan Kerja dengan Pelaksanaan Pencegahan
Kecelakaan Kerja (serial 0nline) diunduh 12 Januari 2012.
http://mahurianasla.blogspot.com/2010/11/hubungan-pengetahuan-keselamatan-
kerja.html.
Nurmalinda, Y. (2008). Analisis pengaruh Keselamatan Kesehatan Kerja serta Lingkungan Kerja
terhadap Produktivitas Kerja PT. Sinar Sosro Tanjung Morowa Medan. USU
Reposittory,(serial online) diunduh 17 november 2011
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4241/1/09E00231.pdf.
Perusahaan wajib siapkan peralatan standar K3 (2011). M power. Volume 6. Nomer 4 : 34 – 35
Program PascaSarjana Universitas Hasanuddin (2012). Pedoman penulisan Artikel Jurnal Ilmiah
Cetakan Pertama: Maret. Nomor: 380/UN4/PL.09/2012.
Salawati, L. (2009). Hubungan perilaku, manajemen K3 dengan terjadinya kecelakaan di
Laboratorium Patologi Klinik di Rumah Sakit Umum dr. Zainal Abidin. Banda Aceh,
(tesis) (serial online) diunduh 10 Desember 2011
http://repository.usu.ac.id/123456789/6947/1/09E02292.pdf. .
Szczygielska, A. (2010). Factors effected on components of employees attitude towards working
safety., (serial online) diunduh 8 Maret 2012.
http://www.wos2010.no/assets/presentations/129.pdf.
Suma’mur, (1989). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. PT. Toko Gunung Agung:
Jakarta.
Tarigan, Z. (2008). Analisis Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja di Pabrik Kelapa
Sawit (PKS) Tanjung Medan PTPN V Provinsi Riau, (tesis) (serial online) di unduh
9 Desember 2011. http:/repository. usu.ac.id/ bitstream/ 123456789/7036/
1/09E00262.pdf,
Wicaksosno,I.K dan Singgih, M.L. (2011). Manajemen Resiko K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja)
pada Proyek Pembangunan Apartemen Puncak Permai Surabaya., (serial online)
diunduh 15 Januari 2012. http://digilib.its.ac.id/ITS-Master-3100011042383/15046.
24 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
HUBUNGAN PEMASARAN SOSIAL DENGAN PENINGKATAN JUMLAH KUNJUNGAN
DI RUMAH SAKIT Dr. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR
Amirullah, Muh. Syafar1, Asiah Hamzah2
1
Bagian Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin
Bagian Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin
2
Bagian AKK, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin
Abstrak
Keputusan yang paling mendasar yang harus dibuat sebuah rumah sakit adalah perihal
pelayanan yang akan ditawarkan kepada pasar sasaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis
hubungan pemasaran sosial (produk, harga, tempat, dan promosi) dengan peningkatan jumlah
kunjungan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Jenis penelitian adalah survey
analitik dengan metode potong lintang. Sampel sebanyak 87 pasien rawat jalan yang
menggunakan jasa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Data dianalisis dengan
menggunakan uji Chi-Square pada α < 5 %. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan
antara produk dengan peningkatan jumlah kunjungan (p = 0,000). Ada hubungan antara harga
dengan peningkatan jumlah kunjungan (p = 0,000). Ada hubungan antara tempat dengan
peningkatan jumlah kunjungan (p = 0,000). Ada hubungan antara promosi dengan peningkatan
jumlah kunjungan (p = 0,000). Promosi memiliki kontribusi yang paling besar terhadap
peningkatan jumlah kunjungan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar (Wald = 31,199).
Pihak rumah sakit diharapkan dapat mengemas layanan produk, menggunakan penetapan harga,
memperhatikan aspek tempat, dan meningkatkan promosi pada pelanggan.
Kata Kunci : pemasaran sosial, peningkatan jumlah kunjungan
Abstract
Most elementary decision which must be made by a hospital is service subject on the
market to target market. The aim of the research was to analyze the correlation between social
marketing (product, price, place, and promotion) and raising of visit amount in Dr. Tadjuddin
Chalid Hospital Makassar. The research approach was survey analysis and cross sectional study
approach. The samples were 87 outpatients which using health service at Dr. Tadjuddin Chalid
Hospital Makassar. Data was collected through questionnaires, and was analyzed with Chi-
Square test with α < 5 %. The results of the research indicated that there is a correlation between
product and raising of visit amount (p = 0,000), between price and raising of visit amount (p =
0,000), between place and raising of visit amount (p = 0,000), and between promotion and raising
of visit amount (p = 0,000). Promotion has the biggest contribution to raising of visit amount
(Wald = 31,199). Hospital expected by a product service gold, using pricing, paying attention to
place aspect, and improve the promotion to customer.
Keywords: social marketing, raising of visit amount
25 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
PENDAHULUAN
K eputusan yang paling mendasar yang harus dibuat sebuah rumah sakit adalah
perihal pelayanan yang akan ditawarkan kepada pasar sasaran. Pada dasarnya
setiap rumah sakit menawarkan suatu bauran pelayanan bauran pelayanan ini
secara periodik ditinjau dan dimodifikasi dengan melakukan penambahan pelayanan atau
pengurangan pelayanan. Setiap pelayanan baru yang ditawarkan pasti mengundang risiko. Risiko
ini diharapkan dapat dihilangkan atau setidak-tidaknya dikurangi dengan adanya riset pemasaran
yang baik, pengembangan pelayanan, dan upaya-upaya komunikasi. Demikian pula penghapusan
atau pelayan juga mengandung risiko, yaitu boleh jadi siklus hidup pelayanan itu masih dapat
dipertahankan seandainya dilakukan strategi pemasaran yang lebih baik (Hartono, 2010). Pada
dasarnya pemasaran sosial tidak berbeda dengan pemasaran komersial. Pemasaran sosial
menggunakan teknis analisis yang sama: riset pasar pengembangan produk, penentuan harga,
keterjangkauan, dan promosi. penerapan sosial merupakan penerapan konsep dan taktik pemasaran
untuk mendapat manfaat sosial (Notoatmodjo, 2010).
Berdasarkan Laporan RS Tadjuddin Chalid tahun 2012, menunjukkan bahwa angka
kunjungan di Rumah Sakit Tadjuddin Chalid Makassar tidak stabil, karena dapat dilihat dari data
tahun 2009 ke tahun 2010 terjadi peningkatan jumlah kunjungan, namun kembali terjadi
penurunan pada tahun 2011 walaupun kembali meningkat di tahun 2012 tetapi tidak signifikan.
Berdasarkan survey pendahuluan dan wawancara yang dilakukan pada beberapa pasien
rawat jalan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid Makassar, mereka umumnya kurang puas
terhadap produk. Pasien kurang mengetahui dengan jelas bahwa di RS Dr. Tadjuddin Chalid
tersedia layanan untuk pasien umum selain penderita kusta, pasien kurang percaya tenaga
kesehatan RS akan memberikan pelayanan terbaik, perilaku tenaga pelayanan kesehatan kurang
menumbuhkan kepercayaan pasien untuk berobat di RS, tenaga kesehatan di tiap-tiap unit RS
kurang bertindak cepat dalam memberikan pelayanan, pasien kurang meyakini bahwa setelah
menjalani perawatan di RS akan mengalami kesembuhan, pelayanan yang diberikan kurang
lengkap sesuai kebutuhan pasien, serta pelayanan di RS kurang cepat dan pasien biasa menunggu
lama. Berdasarkan penelitian Dewi (2009), bahwa tidak ada hubungan antara persepsi pasien tentang
bauran pemasaran product dengan loyalitas pasien di RS Baptis Kediri (p-value = 0,604, p > 0,05).
Pasien juga umumnya kurang puas terhadap harga. Pasien merasa tarif pelayanan yang
diterapkan di RS Dr. Tadjuddin Chalid kurang terjangkau, besarnya tarif yang diberlakukan
kurang sesuai dengan manfaat yang pasien rasakan setelah menjalani perawatan, proses
pembayaran yang dilakukan lama dan panjang, pelayanan RS membebankan biaya administrasi
tambahan kepada pasien, kurang memudahkan pasien dalam pembayaran setelah menerima
pelayanan, serta pelayanan RS membebankan biaya pemeriksaan tambahan kepada pasien.
Berdasarkan penelitian Asrianti (2007), menunjukkan bahwa didapatkan nilai t hitung price 1,275
< t tabel 1,671 atau p = 0,206, < 0,05 berarti tidak ada pengaruh price terhadap keputusan pasien
memanfaatkan rawat inap di RSU Sawerigading Kota Palopo.
Pasien umumnya kurang puas terhadap tempat. Pasien merasa lokasi RS Dr. Tadjuddin
Chalid kurang strategis, lokasi RS kurang dekat dengan tempat tinggal pasien, kondisi ruang
tunggu kurang bersih, kondisi ruang periksa kurang bersih, kondisi lingkungan sekitar kurang
bersih, alat untuk periksa kurang bersih, alat untuk periksa kurang lengkap sesuai kebutuhan
pasien, penampilan petugas pemberi pelayanan kurang rapi, serta fasilitas penunjang di RS kurang
lengkap. Berdasarkan penelitian Akase (2010), bahwa lokasi (p = 0,018, < 0,05) berhubungan dengan
minat memanfaatkan poliklinik mata BLUD RSU Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo.
Serta pasien umumnya kurang puas terhadap promosi. Pasien merasa kurang mendengar
informasi tentang RS Dr. Tadjuddin Chalid, pasien kurang mendapat informasi/penyuluhan dari
pihak RS tentang layanan yang tersedia, pasien kurang menerima informasi tentang RS dari teman
atau kerabat, promosi yang dilakukan RS kurang memasyarakat, pasien kurang mendapat
informasi melalui promosi yang dilakukan RS melalui media, promosi yang dilakukan RS kurang
meningkatkan kunjungan pasien, serta pelayanan tenaga kesehatan kurang sesuai dengan informasi
26 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
yang pasien butuhkan. Berdasarkan penelitian Dewi (2009), bahwa tidak ada hubungan antara
persepsi pasien tentang bauran pemasaran promotion dengan loyalitas pasien di RS Baptis Kediri (p-
value = 0,201, p > 0,05).
Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti
hubungan pemasaran sosial dengan peningkatan jumlah kunjungan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin
Chalid Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pemasaran sosial (produk,
harga, tempat, dan promosi) dengan peningkatan jumlah kunjungan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin
Chalid Makassar.
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di RS. Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. Penelitian ini merupakan
penelitian survey analitik dengan Metode Potong Lintang.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien pengguna layanan RS Dr. Tadjuddin
Chalid Makassar sebanyak 657 orang. Sedangkan sampel penelitian adalah pasien rawat jalan
yang menggunakan jasa pelayanan kesehatan di RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar saat penelitian
berlangsung. Besarnya sampel dihitung berdasarkan rumus besar sampel untuk populasi kurang
dari 10.000 (Notoatdmodjo, 2002), diperoleh sampel sebanyak 87 responden. Penarikan sampel
dengan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu sampel (individu) yang sukar ditemui
dengan alasan sibuk, tidak mau diganggu, tidak bersedia menjadi responden, atau alasan lainnya.
Oleh karena itu siapa saja yang ditemui dan bersedia menjadi sampel atau responden.
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis univariat, yang berfungsi
memberikan gambaran karakteristik populasi dan penyajian hasil deskriptif melalui frekuensi dan
distribusi dari variabel bebas dan variabel terikat. Analisis bivariat, dilakukan untuk mencari ada
tidaknya hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat dengan menggunakan
uji Chi-Square, dengan program SPSS versi 17. Analisis multivariat, dilakukan untuk melihat
variabel bebas yang paling berhubungan dengan variabel terikat dengan menggunakan uji Regresi
Logistik, dengan program SPSS versi 17.
HASIL
Karakteristik Responden
Tabel karakteristik responden memperlihatkan bahwa dari 87 responden pasien rawat
jalan, sebagian besar menilai produk yakni cukup baik sebesar 81,6 %, menilai harga yakni cukup
terjangkau sebesar 79,3 %, menilai tempat yakni cukup baik sebesar 75,9 %, menilai promosi
yakni cukup baik sebesar 72,4 %, dan sebagian besar responden jumlah kunjungannya meningkat
sebesar 73,6 %.
Analisis Bivariat
Tabel hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa pada responden yang menilai produk
yang cukup baik, ternyata jumlah kunjungannya lebih banyak yang meningkat sebesar 87,3 %
dibanding yang tidak meningkat sebesar 12,7 %. Sedangkan pada responden yang menilai produk
yang kurang baik, ternyata jumlah kunjungannya lebih banyak yang tidak meningkat sebesar 87,5
% dibanding yang meningkat sebesar 12,5 %. Ada hubungan antara produk dengan peningkatan
jumlah kunjungan, dengan p = 0,000 (p < 0,05).
Responden yang menilai harga yang cukup terjangkau, ternyata jumlah kunjungannya
lebih banyak yang meningkat sebesar 85,5 % dibanding yang tidak meningkat sebesar 14,5 %.
Sedangkan pada responden yang menilai harga yang kurang terjangkau, ternyata jumlah
kunjungannya lebih banyak yang tidak meningkat sebesar 72,2 % dibanding yang meningkat
sebesar 27,8 %. Ada hubungan antara harga dengan peningkatan jumlah kunjungan, dengan p =
0,000 (p < 0,05).
27 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Responden yang menilai tempat yang cukup baik, ternyata jumlah kunjungannya lebih
banyak yang meningkat sebesar 89,4 % dibanding yang tidak meningkat sebesar 10,6 %.
Sedangkan pada responden yang menilai tempat yang kurang baik, ternyata jumlah kunjungannya
lebih banyak yang tidak meningkat sebesar 76,2 % dibanding yang meningkat sebesar 23,8 %.
Ada hubungan antara tempat dengan peningkatan jumlah kunjungan, dengan p = 0,000 (p < 0,05).
Responden yang menilai promosi yang cukup baik, ternyata jumlah kunjungannya lebih
banyak yang meningkat sebesar 93,7 % dibanding yang tidak meningkat sebesar 6,3 %. Sedangkan
pada responden yang menilai promosi yang kurang baik, ternyata jumlah kunjungannya lebih
banyak yang tidak meningkat sebesar 79,2 % dibanding yang meningkat sebesar 20,8 %. Ada
hubungan antara promosi dengan peningkatan jumlah kunjungan, dengan p = 0,000 (p < 0,05).
Analisis Multivariat
Tabel hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa dari keempat pemasaran sosial
(produk, harga, tempat, dan waktu), semuanya masuk dalam uji multivariat karena nilai p < 0,25.
Setelah melewati hingga step 4, diperoleh hanya variabel promosi yang berpengaruh terhadap
peningkatan jumlah kunjungan. Promosi mempunyai nilai p = 0,000. Dengan demikian, maka
variabel promosi yang paling erat hubungannya dengan peningkatan jumlah kunjungan (Wald =
31,199).
PEMBAHASAN
Hubungan produk dengan peningkatan jumlah kunjungan, terdapat 12,7 % pasien yang
meskipun menilai produk yang cukup baik, namun jumlah kunjungannya tidak meningkat.
Ternyata sebagian besar responden yang menilai produk yang cukup baik, juga mengalami
peningkatan jumlah kunjungan. Sebaliknya terdapat 12,5 % pasien yang meskipun menilai produk
yang kurang baik, namun jumlah kunjungannya meningkat. Ternyata sebagian besar responden
yang menilai produk yang kurang baik, juga tidak mengalami peningkatan jumlah kunjungan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Setyabudi (2009), bahwa dalam
social marketing (pemasaran sosial) yang dimaksud dengan produk adalah sesuatu yang
ditawarkan untuk dibeli, yang berbentuk perilaku yang diharapkan dan manfaat perilaku tersebut.
Hal yang ditawarkan tersebut bisa termasuk juga sebuah barang dan layanan untuk mendukung
perubahan perilaku dari sasaran. Dalam pemasaran komersial hal tersebut sering dikatakan sebagai
paket manfaat yang ditawarkan pada pasar untuk memenuhi kebutuhan pasar.
Hasil uji statistik dengan Fisher’s Exact Test menunjukkan nilai p = 0,000, dimana nilai p
< 0,05, maka Ho ditolak. Berarti ada hubungan antara produk dengan peningkatan jumlah
kunjungan. Di samping itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Poernomo (2009),
bahwa tidak ada hubungan antara persepsi pasien tentang bauran pemasaran product dengan
loyalitas pasien (p-value = 0,604; p > 0,05) di Poliklinik Rawat Jalan RS Baptis Kediri. Penelitian
ini tidak sejalan pula dengan penelitian Dewi (2009), bahwa tidak ada hubungan antara persepsi
pasien tentang bauran pemasaran product dengan loyalitas pasien di RS Baptis Kediri (p-value =
0,604, p > 0,05). Serta penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Akase (2010), bahwa tidak
terdapat hubungan antara produk dengan minat memanfaatkan produk unggulan poliklinik mata
BLUD RSU Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo (p = 0,208, > 0,05).
Hubungan harga dengan peningkatan jumlah kunjungan, Terdapat 14,5 % pasien yang
meskipun menilai harga yang cukup terjangkau, namun jumlah kunjungannya tidak meningkat.
Ternyata sebagian besar responden yang menilai harga yang cukup terjangkau, juga mengalami
peningkatan jumlah kunjungan. Sebaliknya terdapat 27,8 % pasien yang meskipun menilai harga
yang kurang terjangkau, namun jumlah kunjungannya meningkat. Ternyata sebagian besar
responden yang menilai harga yang kurang terjangkau, juga tidak mengalami peningkatan jumlah
kunjungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Khairunnisa (2010),
bahwa harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang. Demi
mendapatkan sebuah barang atau jasa yang diinginkannya seorang konsumen harus rela membayar
sejumlah uang. Hal ini juga harus diperhatikan oleh perusahaan, jika perusahaan menetapkan
28 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
harga yang tinggi dengan maksud untuk menjadikan barang atau jasa produksinya dalam kategori
luxuries, maka harga yang semakin tinggi dapat menjadikan barang itu akan semakin dicari
konsumen, akan tetapi akan berbeda jika bidikan barang yang digunakan untuk umum maka harga
yang harus digunakan pun menyesuaikan dengan kemampuan pasar.
Hasil uji statistik dengan Fisher’s Exact Test menunjukkan nilai p = 0,000, dimana nilai p
< 0,05, maka Ho ditolak. Berarti ada hubungan antara harga dengan peningkatan jumlah
kunjungan. Di samping itu, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Poernomo (2009), bahwa
ada hubungan antara persepsi pasien bauran pemasaran tentang price dengan loyalitas pasien (p-
value = 0,016; p ≤ 0,05) di Poliklinik Rawat Jalan RS Baptis Kediri. Penelitian ini sejalan pula
dengan penelitian Dewi (2009), bahwa ada hubungan antara persepsi pasien tentang bauran pemasaran
price dengan loyalitas pasien di RS Baptis Kediri (p-value = 0,016, p > 0,05). Namun penelitian ini
tidak sejalan dengan penelitian Asrianti (2007), bahwa didapatkan nilai t hitung price 1,275 < t
tabel 1,671 atau p = 0,206, < 0,05 berarti tidak ada pengaruh price terhadap keputusan pasien
memanfaatkan rawat inap di RSU Sawerigading Kota Palopo.
Hubungan tempat dengan peningkatan jumlah kunjungan, Terdapat 10,6 % pasien yang
meskipun menilai tempat yang cukup baik, namun jumlah kunjungannya tidak meningkat.
Ternyata sebagian besar responden yang menilai tempat yang cukup baik, juga mengalami
peningkatan jumlah kunjungan. Sebaliknya terdapat 23,8 % pasien yang meskipun menilai tempat
yang kurang baik, namun jumlah kunjungannya meningkat. Ternyata sebagian besar responden
yang menilai tempat yang kurang baik, juga tidak mengalami peningkatan jumlah kunjungan.
Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010), bahwa
tempat berarti lokasi dimana produk dapat diperoleh. Tempat atau jalur distribusi perlu
diperhitungkan dengan baik. Semakin luas jaringan distribusinya, semakin mudah konsumen untuk
memperoleh produk tersebut. Kemudahan akses terhadap lokasi usaha bagi semua para pelanggan
dan calon pelanggan potensial. Tempat yang menarik bagi konsumen adalah tempat yang paling
strategis, menyenangkan, dan efisien. Memilih lokasi dekat dengan pelanggan perlu untuk
mempertahankan daya saing. Selain faktor kedekatan dengan pelanggan, faktor kenyamanan juga
mutlak diperhatikan.
Hasil uji statistik dengan Pearson Chi-Square menunjukkan nilai p = 0,000, dimana nilai
p < 0,05, maka Ho ditolak. Berarti ada hubungan antara tempat dengan peningkatan jumlah
kunjungan. Di samping itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian Akase (2010), bahwa lokasi (p =
0,018, < 0,05) berhubungan dengan minat memanfaatkan poliklinik mata BLUD RSU Dr. M. M.
Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo. Serta penelitian ini sejalan pula dengan penelitian Asrianti
(2007), menunjukkan bahwa didapatkan nilai t hitung place 2,638 > t tabel 1,671 atau p = 0,010, <
0,05 berarti ada pengaruh place terhadap keputusan pasien memanfaatkan rawat inap di RSU
Sawerigading Kota Palopo Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Poernomo
(2009), bahwa tidak ada hubungan antara persepsi pasien tentang bauran pemasaran place dengan
loyalitas pasien (p-value = 0,062; p > 0,05) di Poliklinik Rawat Jalan RS Baptis Kediri.
Hubungan promosi dengan peningkatan jumlah kunjungan, Terdapat 6,3 % pasien yang
meskipun menilai promosi yang cukup baik, namun jumlah kunjungannya tidak meningkat.
Ternyata sebagian besar responden yang menilai promosi yang cukup baik, juga mengalami
peningkatan jumlah kunjungan. Sebaliknya terdapat 20,8 % pasien yang meskipun menilai
promosi yang kurang baik, namun jumlah kunjungannya meningkat. Ternyata sebagian besar
responden yang menilai promosi yang kurang baik, juga tidak mengalami peningkatan jumlah
kunjungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo (2010),
bahwa promosi berarti mengkonsumsikan keunggulan dan membujuk konsumen atau kelompok
sasaran untuk menggunakan produk yang ditawarkan. Berbagai metode untuk
mengkomunikasikan keunggulan, manfaat produk tertentu kepada pelanggan potensial dan aktual.
Yang perlu diperhatikan dalam promosi adalah pemilihan bauran promosi yang sangat penting
untuk dilaksanakan, metode tersebut terdiri atas aktivitas periklanan, penjualan langsung,
informasi dari mulut ke mulut, dan pemasaran langsung. Promosi dilakukan untuk mengikat semua
29 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
pemasaran jadi unsur promosi ini tidak lepas dari unsur produk, harga, maupun tempat, karena
ketiga unsur ini juga merupakan alat promosi. Paduan semua unsur tersebut harus dapat
membangun citra produk yang tentu saja harus sejalan dengan citra dari konsumen.
Hasil uji statistik dengan Pearson Chi-Square menunjukkan nilai p = 0,000, dimana nilai
p < 0,05, maka Ho ditolak. Berarti ada hubungan antara promosi dengan peningkatan jumlah
kunjungan. Di samping itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian Akase (2010), bahwa terdapat
hubungan antara promosi (p = 0,018, < 0,05) dengan minat memanfaatkan poliklinik mata BLUD
RSU Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian Poernomo (2009), bahwa tidak ada hubungan antara persepsi pasien tentang
bauran pemasaran promotion dengan loyalitas pasien (p-value = 0,201; p > 0,05) di Poliklinik
Rawat Jalan RS Baptis Kediri. Penelitian ini tidak sejalan pula dengan penelitian Dewi (2009),
bahwa tidak ada hubungan antara persepsi pasien tentang bauran pemasaran promotion dengan loyalitas
pasien di RS Baptis Kediri (p-value = 0,201, p > 0,05).
Pada analisis multivariat, Setelah menggunakan metode Backward Stepwise Wald yang
membuang variabel yang paling tidak bermakna satu per satu sampel dimana variabel yang
bermakna memiliki nilai p < 0,25, maka dapat dilihat bahwa dari keempat pemasaran sosial
(produk, harga, tempat, dan waktu), semuanya masuk dalam uji multivariat karena nilai p < 0,25.
Setelah melewati hingga step 4, diperoleh hanya variabel promosi yang berpengaruh terhadap
peningkatan jumlah kunjungan. Promosi mempunyai nilai p = 0,000. Dengan demikian, maka
variabel promosi yang paling erat hubungannya dengan peningkatan jumlah kunjungan (Wald =
31,199). Hal itu berarti promosi memiliki kontribusi yang paling besar terhadap peningkatan
jumlah kunjungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Notoatmodjo
(2010), bahwa pemasaran sosial dapat diartikan sebagai perancangan, penerapan, dan
pengendalian program yang ditujukan untuk meningkatkan penerimaan suatu gagasan atau praktik
tertentu pada suatu kelompok sasaran. Pada dasarnya pemasaran sosial tidak berbeda dengan
pemasaran komersial. Pemasaran sosial menggunakan tekhnis analisis yang sama, yakni riset
pasar, pengembangan produk, penentuan harga, keterjangkauan, dan promosi. Dapat disimpulkan,
bahwa pemasaran sosial adalah penerapan konsep dan tekhnik pemasaran untuk mendapatkan
manfaat sosial. Sesuai pula dengan teori yang dikemukakan oleh Sulistiadi (2002), bahwa konsep
promosi di rumah sakit adalah bagaimana pasien tahu tentang jenis pelayanan yang ada di rumah
sakit, bagaimana mereka termotivasi untuk menggunakan, lalu menggunakan secara
berkesinambungan, dan menyebarkan informasi itu kepada rekan-rekannya. Promosi merupakan
proses mengkomunikasikan variabel bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh
organisasi dalam memasarkan produk. Hal itu sesuai pula dengan teori yang dikemukakan oleh
Sabarguna (2005), bahwa promosi atau pemasaran di rumah sakit masih dianggap sebagai sesuatu
yang wajar.
Di samping itu, penelitian ini sejalan dengan penelitian Akase (2010), bahwa terdapat
hubungan antara promosi (p = 0,018, < 0,05) dengan minat memanfaatkan poliklinik mata BLUD
RSU Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan penelitian Poernomo (2009), persepsi pasien tentang price (p = 0,026) dan persepsi pasien
tentang process (p = 0,033) yang memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap loyalitas
pasien, bukan dari faktor promotion di Poliklinik Rawat Jalan RS Baptis Kediri.
KESIMPULAN DAN SARAN
Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa ada hubungan antara produk,
harga, tempat, dan promosi dengan peningkatan jumlah kunjungan. Diharapkan pihak rumah sakit
diharapkan dapat mengemas layanan produk dengan program-program baru yang dapat
meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi rumah sakit. Pihak rumah sakit diharapkan
dapat menggunakan penetapan harga berkaitan dengan peristiwa khusus untuk menarik lebih
banyak pelanggan; menawarkan kombinasi yang tepat dari mutu dan jasa yang baik dengan harga
yang pantas, misalnya menyediakan pelayanan pemeriksaan tertentu dengan harga paket, paket
30 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
hemat, dll; studi tarif untuk menentukan tarif yang sesuai kemampuan pasien tetapi tidak
merugikan rumah sakit; mengembangkan pangsa pasar dengan meningkatkan pelayanan asuransi
dan meningkatkan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan; serta struktur pasar rumah sakit saat
ini menjadi semakin kompetitif sehingga rumah sakit perlu melakukan penetapan tarif dengan
melihat pesaing. Pihak rumah sakit diharapkan dapat memperhatikan aspek tempat sehingga dapat
dijangkau masyarakat serta alur distribusi pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh segenap
masyarakat. Pihak rumah sakit diharapkan dapat meningkatkan promosi melalui upaya
meningkatkan komunikasi dengan pelanggan lama melalui strategi relationship marketing;
meningkatkan kegiatan di komunitas rumah sakit yang sudah berjalan dan membentuk komunitas
baru sesuai dengan kebutuhan pasien; mendata pasien yang lama yang tidak kembali periksa ke
poliklinik dan mencari penyebabnya; serta menyediakan nomor telepon/sms khusus untuk
customer service sehingga pelanggan mudah bertanya, mengajukan saran, atau mengeluh terhadap
pelayanan rumah sakit. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan metode kualitatif untuk
mengeksplor alasan kepuasan dan ketidakpuasan konsumen.
DAFTAR PUSTAKA
Akase, I. T. (2010). Hubungan Bauran Pemasaran Terhadap Minat Penggunaan Produk Unggulan
Poliklinik Mata di BLUD RSU Dr. M. M. Dunda Limboto Kabupaten Gorontalo (Tesis).
Makassar : Universitas Hasanuddin.
Asrianti. (2007). Analisis Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Pasien Memanfaatkan
Rawat Inap RSU Sawerigading Kota Palopo Tahun 2007 (Tesis). Makassar : Universitas
Hasanuddin.
Conway. (2012). Reducing Hospital Associated Infection: A Role for Social Marketing. Journal
University of Salford Manchester.
Dewi. (2009). Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Loyalitas Pasien di Poliklinik Rawat Jalan
RS Baptis Kediri (Tesis). Semarang : Universitas Diponegoro.
Donovan, R. J. (2011). The Role for Marketing in Public Health Change Programs. Journal
Australian Review of Public Affairs Volume 10, Number 1: July 2011, 23–40.
Evans, W. D. (2008). Social Marketing Campaigns and Children’s Media Use. Journal Future of
Children Vol. 18 No. 1.
Hartono, B. (2010). Manajemen Pemasaran untuk Rumah Sakit. Jakarta : Rineka Cipta.
Khairunnisa. (2010). Pemasaran Sosial. Jakarta : Rineka Cipta.
Nichols, L, et al. (2004). Social Marketing as a Framework for Recruitment: Illustrations From the
REACH Study. Journal Aging Health.
Notoatmodjo, S. (2002). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
_____________. (2010). Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasinya. Jakarta : Rineka Cipta.
Poernomo. (2009). Analisis Pengaruh Persepsi Pasien Tentang Bauran Pemasaran Terhadap
Loyalitas Pasien Di Poliklinik Rawat Jalan Rs Baptis Kediri (Tesis). Semarang :
Universitas Diponegoro.
Sabarguna. (2005). Pengambilan Keputusan Pemasaran di Rumah Sakit. Yogyakarta :
Konsorsium RS Islam.
Setyabudi, D. (2009). Manajemen Pemasaran Modern. Yogyakarta : Liberty Offset.
Sulistiadi, W. (2002). Fungsi Pemasaran Rumah sakit di Indonesia: Serba Tanggung ?. Jurnal
Marsi Vol.3 No.3 Oktober 2002.
31 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Lampiran :
Tabel 1 Karakteristik Responden
No. Kategori Jumlah Persentase
Produk
1. Cukup Baik 71 81,6
2. Kurang Baik 16 18,4
87 100
Harga
1. Cukup Terjangkau 69 79,3
2. Kurang Terjangkau 18 20,7
87 100
Tempat
1. Cukup Baik 66 75,9
2. Kurang Baik 21 24,1
87 100
Promosi
1. Cukup Baik 63 72,4
2. Kurang Baik 24 27,6
12 100
Peningkatan Jumlah Kunjungan
1. Meningkat 64 73,6
2. Tidak Meningkat 23 26,4
87 100
Sumber : Data Primer, 2012
Tabel 2 Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen di Rumah Sakit Dr.
Tadjuddin Chalid Makassar
Peningkatan Jumlah Kunjungan Total
Kriteria
Tidak
Meningkat % % n %
Meningkat
Produk
Cukup Baik 62 87,3 9 12,7 71 100
p = 0,000
Kurang Baik 2 12,5 14 87,5 16 100
Jumlah 64 73,6 59 26,4 87 100
Harga
Cukup Terjangkau 59 85,5 10 14,5 69 100
Kurang Terjangkau 5 27,8 13 72,2 18 100 p = 0,000
Jumlah 64 73,6 23 26,4 87 100
32 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Tempat
Cukup Baik 59 89,4 7 10,6 66 100
Kurang Baik 5 23,8 16 76,2 21 100 p = 0,000
Jumlah 64 73,6 23 26,4 87 100
Promosi
Cukup Baik 59 93,7 4 6,3 63 100
Kurang Baik 5 20,8 19 79,2 24 100 p = 0,000
Jumlah 64 73,6 23 26,4 87 100
Sumber : Data Primer, 2012
Tabel 3 Hasil Regresi Logistik Variabel Independen dengan Variabel Dependen
Peningkatan Jumlah Kunjungan B S.E. Wald df p
Step 1 :
Produk 2,278 1,430 2,539 1 0,111
Harga -0,747 1,531 0,238 1 0,626
Tempat -0,798 1,656 0,232 1 0,630
Promosi 3,804 1,248 9,288 1 0,002
Step 2 :
Produk 2,143 1,435 2,231 1 0,135
Harga -1,096 1,432 0,586 1 0,444
Promosi 3,473 0,988 12,365 1 0,000
Step 3 :
Produk 1,435 1,051 1,864 1 0,172
Promosi 3,202 0,895 12,812 1 0,000
Step 4 :
Promosi 4,026 0,721 31,199 1 0,000
Sumber : Data Primer, 2012
33 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
PEOPLE’S PARTICIPATORY IN INCREASING MEN’S
ACCEPTOR IN FAMILY PLANNING PROGRAM (FP)
IN PALU
Aminuddin 1, Mappeaty Nyorong 2, Nurhaedah Jafar 3
1
Politeknik Kesehatan KemenKes Palu
2
Bagian Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar
3
Bagian Gizi, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin Makassar
Abstrak
Penggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita
sebagai pasangan, sehingga metode kontrasepsi yang dipilih mencerminkan kebutuhan serta
keinginan suami dan istri. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran partisipasi
masyarakat dalam meningkatkan akseptor pria dalam program keluarga berencana (KB) di Kota
Palu. Penelitian ini menggunakan desain Kualitatif dengan Pendekatan fenomenologi. Pemilihan
informan dilakukan dengan metode Snowball Sampling. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian
menunjukan bahwa pengetahuan akseptor KB pria tentang keluarga berencana secara umum
masih rendah, masih ada anggapan bahwa vasektomi sama dengan di kebiri, merasa tabu dan
pandangan yang negatif terhadap pengguna kondom, keluarga sangat mendukung bila suami
mengambil alih peran sebagai akseptor KB, bentuk dukungan yang diberikan bersama-sama pergi
ke petugas kesehatan atau mengambilkan alat kontrasepsi di sarana pelayanan kesehatan, dalam
pengambilan keputusan adalah otonomi penuh dari suami sebagai kepala rumah tangga. Program
KB yang dilakukan dalam meningkatkan akseptor pria sudah sampai ke daerah pelosok,
memberikan penyuluhan melalui mobil penerangan, membentuk konselor sebaya dan pusat
informasi konseling remaja, program yang dilakukan masih tertuju pada KB aktif, Peran petugas
kesehatan adalah melakukan konseling, membentuk kelompok ibu, anak dan suami di setiap
Posyandu, sasaran lebih diprioritaskan kepada masyarakat pra sejahtera dan yang mempunyai
anak banyak, mempertahankan akseptor aktif. Saran perlu sosialisasi khusus untuk program KB
pria, memberikan pemahaman yang jelas tentang program KB serta melakukan pencatatan
akseptor KB yang lengkap di semua pelayanan kesehatan.
Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Akseptor KB, Program Keluarga Berencana
Abstract
The use of contraception is a shared responsibility between men and women a partners,
so that the chosen method of contraception reflects the needs and the wishes of the husband and
wife. This study aims to obtain a picture of people's participation in the program increase male
acceptors of family planning (FP) in Palu. This study uses a qualitative design with a
phenomenological approach. The selection of informants was conducted by Snowball Sampling.
Data collection methods used were interviews, and documentation. The results showed that
knowledge of family planning acceptors men about family planning in general is still low, there is
still a presumption that vasectomy is equal to the gelding, was taboo and negative views toward
condom, the family is very supportive when her husband took over the role of family planning
acceptors, forms of support given together go to the health worker or get birth control in health
care facilities, autonomy in decision making is full of the husband as head of household. Planning
programs conducted in increasing acceptor men had come to the rural areas, providing
34 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
information through the car lighting, form peer counselors and counseling youth information
centers, conducted programs still on active family planning, The role of health workers is to do
counseling, forming groups of women, children and husbands in every, higher priority targets to
the people who have pre prosperous and many children, maintains anactive acceptor. Advice
necessary socialization for male family planning programs, providing a clear understanding of
family planning programs and conduct a complete listing of family planning acceptors in all
health care.
Keywords : Community Participation, Acceptors KB, Family Planning Program
PENDAHULUAN
P enggunaan kontrasepsi merupakan tanggung jawab bersama antara pria dan wanita
sebagai pasangan, sehingga metode kontrasepsi yang dipilih mencerminkan
kebutuhan serta keinginan suami dan istri (BKBPP, 2011).
Dalam penggunaan kontrasepsi pria seperti kondom, pantang berkala, senggama terputus
dan vasektomi, suami mempunyai tanggung jawab utama, sementara bila istri sebagai pengguna
kontrasepsi, suami mempunyai peranan penting dalam mendukung istri dan menjamin efektivitas
pemakaian kontrasepsi. Suami dan istri harus saling mendukung dalam penggunaan metode
kontrasepsi karena KB dan kesehatan reproduksi bukan hanya urusan pria atau wanita saja (Satria,
2005).
Partisipasi pria/suami dalam KB adalah tanggung jawab pria/suami dalam kesertaan ber-
KB, serta berperilaku seksual yang sehat dan aman bagi dirinya, pasangan dan keluarganya.
Bentuk partisipasi pria/suami dalam KB dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung
(Endang, 2006).
Rendahnya partisipasi pria dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi pada
dasarnya tidak terlepas dari operasional program KB yang selama ini dilaksanakan mengarah
kepada wanita sebagai sasaran (BKKBN, 2007). Upaya mengajak para pria untuk menjadi peserta
KB diawali dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai masalah KB Pria,
jenis dan cara kontrasepsi pria, kelebihan maupun keterbatasannya (Hertimaryani, 2007).
Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi pria dalam KB
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : akses informasi KB pria terbatas termasuk di
dalamnya terbatasnya pilihan metode kontrasepsi pria dan ketersediaan dukungan jaringan
pelayanan KB pria serta rendahnya dukungan sosial budaya dari para tokoh agama dan tokoh
masyarakat terhadap KB pria (Meylani, 2010).
Program Keluarga Berencana (KB) pria di Kota Palu masih sepi peminat. Menurut Kepala
Sub Bagian (Kasubag) informasi dan penyediaan data Badan Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Kota Palu, mengakui masih minimnya peminat program KB
pria karena ada anggapan di masyarakat bahwa vasektomi sama dengan kebiri dan akan
mempengaruhi terhadap masalah seksualitas, sedangkan penggunaan kondom masih banyak
diantara masyarakat tidak mengetahui cara penggunaan kondom dengan benar terkadang dalam
berhubungan suami istri banyak kondom yang biasa bocor, pria yang mengikuti metode kondom
tidak pernah mengambil sendiri alat kontrasepsi tersebut melainkan diambilkan oleh istri mereka
(BKBPP, 2012).
Pada Tahun 2011 data peserta KB aktif pada bulan Januari sampai dengan bulan November
Tahun 2011 MOW 6.708, IUD 18.454, IMP 32.803, STK 141.278, Pil 139.596, MOP 922 dan
KDM 9.741. Data peserta KB baru bulan Januari sampai dengan bulan November Tahun 2011
MOW 723, IUD 4.470, IMP 8.158, STK 42.010, Pil 38.956, MOP 323 dan KDM 11.646
(BKKBN Sulteng, 2012). Penelitian bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi
masyarakat dalam meningkatkan akseptor pria dalam program keluarga berencana (KB) di Kota
Palu (BKBPP Kota Palu, 2012).
35 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
BAHAN DAN METODE
Lokasi dan Rancangan Penelitian
Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Palu sebagai objek penelitian dengan
pertimbangan masih rendahnya partisipasi akseptor pria dalam mengikuti program keluarga
berencana.
Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitiatif dengan pendekatan fenomenologi.
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman dan penafsiran yang mendalam mengenai
makna, kenyataan dan fakta yang relefan (Suwandi, 2008).
Pemilihan Informan Penelitian
Informan dalam penelitian ini akseptor KB pria 8 orang, istri akseptor 8 orang, pemegang
program KB 2 orang dan petugas kesehatan 6 orang. tehnik pengambilan informan dalam
penelitian ini dilakukan metode snowball sampling (Mulyadi, 2011).
Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian
kualitatif pada umumnya menggunakan teknik wawancara mendalam (indepth interview),
observasi dan studi dokumen (Komariah, 2011).
Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini analisis narasi (narrative analiysis).
Data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam. Hasil ditulis dalam bentuk catatan lapangan,
kemudian disalin dalam bentuk transkrip wawancara (verbatim wawancara), Mereduksi data (data
etik) Data yang terkumpul dalam bentuk cacatan lapangan dijadikan satu dalam bentuk transkrip
kemudian dibuat koding. Penyajian data (data emik) Penyajian data dapat dilakukan dengan tabel,
gambar, bagan maupun teks naratif. Penarikan kesimpulan (konsep) Dari data yang disajikan,
kemudian data dibahas dan dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu dan secara
teoritis dengan perilaku kesehatan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induksi
(Hendriansyah, 2010).
HASIL PENELITIAN
Pengetahuan akseptor KB pria
Sesuai dengan hasil wawancara dengan responden diketahui bahwa pengetahuan akseptor
tentang keluarga berencana bervariasi sesuai dengan yang dikutip berikut :
Pertanyaan : Menurut bapak pengertian KB apa ?, Tujuan dan manfaat KB ?
“ Supaya istri tidak hamil lagi, Agar istri sehat dan tidak banyak anak, Sebenarnya saya
tidak mau pakai kondom tapi karena istri sakit-sakit bila minum pil jadi saya yang pakai kondom,
biar istri sehat “. (F.D.R, 14 Maret 2012)
“ Menurut saya KB itu artinya untuk mengurangi kehamilan ibu. Tujuannya itu….artinya tidak
menambah kehamilan ibu, Artinya tidak terlalu banyak beban bagi keluarga. “. (A.R.S, 15 Maret
2012)
“ Membatasi supaya anak tidak banyak. Tujuannya supaya mengurangi anak juga pokoknya
baguslah….. Manfaatnya ya artinya agar supaya kehamilan itu agak lambatlah, dari segi lain
barangkali biar sehat “. (S, 17 Maret 2012)
“ Menurut saya mengatur jarak kelahiran anak-anak. Karena maetua selalu sakit-sakit kalau ikut
KB biasa pusing dan badannya kurus. Sangat membantu terutama masalah ekonomi lebih ringan,
anak-anak juga sekolahnya lebih terjamin “. (B.D, 23 Maret 2012)
“ Menurut saya keluarga berencana itu sangat menguntungkan bagi masyarakat bila mereka
mengerti. Tujuan utamanya untuk kesehatan istri saya karena kalau maetua yang ikut KB tidak
36 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
cocok selalu sakit-sakit kalau minum pil. Menurut saya semenjak saya di vasektomi badan tambah
sehat terutama belakang saya tidak pernah lagi sakit-sakit biar 1 jam saya membungkuk tidak ada
saya rasa sakit “. (S.L.M, 24 Maret 2012)
Pengetahuan responden tentang, macam-macam kontrasepsi, KB alamiah serta pemahaman
tentang vasektomi dan kondom berbeda-beda seperti yang di kutipan berikut :
Pertanyaan : Menurut bapak macam-macam kontrasepsi untuk pria apa saja ?, Metode KB
alamiah ?, bagaimana pemahaman bapak tentang Vasektomi/kondom ?
“ KB alamiah pernah dengar tapi nda tau seperti apa itu, kalau vasektomi ditakutkan adanya
infeksi sesudah operasi, namanya juga operasi walaupun kecil tapi bikin takut “. (F.D.R, 14
Maret 2012).
“ Belum pernah dengar saya, Kalau vasektomi ini artinya tidak bisa kita lagi terjadi benih hampir
sama dengan di kebiri karena yang saya dengar waktu di Rumah Sakit di ikat katanya “ (A.R.S,
48 th, SMA, 15 Maret 2012).
“ Cuma ini saja…. tidak ada lain yang saya tahu, malu juga kita mau Tanya-tanya risih juga kita
khan, karena masih tabu ditelinganya orang. Kalau alamiah mungkin secara tanggal ….tapi tidak
pernah juga saya pelajari takut juga saya nanti kebobolan lagi (M.F, 31 th, SMA, 16 Maret
2012).
“ Masih ada rasa malu kita kalau ambil sendiri karena masih tabu kalau kita membicarakan
tentang kondom di masyarakat. makanya lebih bagus diambilkan, beda kalau perempuan ambil
pil itu biasa-biasa saja tapi kalau laki-laki nanti pandangan orang bisa negative. Ya…… kondom
itu yang bagus dari vasektomi karena kalau vasektomi mesti di operasi lagi takut kalau ada efek
sampingnya dikemudian hari Semenjak saya pakai kondom saya tambah kuat makanya saya rasa
ini yang paling bagus (S, 37 th, STM, 17 Maret 2012).
“ Saya tidak tahu itu KB alamiah apa, pernah saya dengar tapi saya tidak tahu persis seperti apa
itu. Vasektomi itu bagus karena kita tidak perlu khawatir istri kita hamil lagi. Menurut saya ini
yang bagus karena kita tidak repot lagi (D.S, 41, SMA, 20 Maret 2012).
“ Tidak tahu saya hanya vasektomi ini saja yang saya tahu, Pernah saya dengar tapi tidak saya
lakukan Cuma orang-orang bilang pake air diminum dan dibaca-baca, kalau berhubungan di
kase keluar diluar saya bilang itu berdosa kita karena dibuang bukan pada tempatnya saya tidak
mau ikut seperti begitu. (S.D.R, 41 th, SD, 22 Maret 2012).
Dukungan keluarga
Dukungan keluarga terutama istri sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pria
dalam mengikuti program KB. Berikut hasil wawancara mendalam terhadap informan yaitu :
Pertanyaan : Sudah berapa lama suami ibu menjadi akseptor KB ?, siapa yang menganjurkan
suami ibu untuk mengikuti program KB ? dan bentuk dukungan yang ibu berikan kepada suami
sebagai akseptor ?
“ Baru sekitar setengah tahun. saya anjurkan untuk vasektomi saja tapi takut dia dengan operasi.
Jadi pake kondom saja dulu katanya Kalau itu biasa cuma mengikuti masa subur saja……
Memberitahu kepada bapak supaya mau di vasektomi apa ragu juga saya jangan-jangan nanti itu
kondomnya bocor atau apa, tapi untuk sementara pakai kondom saja kata dulu karena takut dia
kalau di operasi”. (S.K.R, 26 th, SMP, 14 Maret 2012)
37 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
“ Sudah satu tahun lebih. Saya yang pertama menganjurkan… ya karena tadi itu masalah
kesehatan. Biasa kalau malas ambil di puskesmas paetua beli di apotek atau kalau tidak saya
yang ambilkan di puskesmas apa malu dia ambil di puskesmas “. (N.R.S, 25 th, SMP, 16 Maret
2012)
“ Sudah lebih lima tahun. Bapak sendiri karena saya tidak cocok dengan pil karena badan saya
tambah besar dan sering sakit-sakit bila saya yang ikut KB. Saya yang ambilkan itu kondom di
puskesmas kalau tidak paetua beli apotek apa malu dia kalau datang ke Puskesmas ambil kondom
“. (S.M, 27 th, SMA, 17 Maret 2012)
“ Sudah sekitar 6 tahun dia ikut vasektomi. Kita ada dengar dari pak RT lalu saya kase tahu dia
komiu ikut vasektomi dia bilang nanti liat dulu tapi lama kelamaan langsung dia sendiri bilang
ia. Saya bilang bagus itu supaya kita sehat dan kalau ada keluhan kita sama-sama ke petugas
kesehatan “. (Z.B.D, 35 th, SD, 22 Maret 2012)
“ Baru ada 1 tahun lebih. Saya yang menyuruh juga, saya bilang coba kata bapak lagi yang ber
KB, dia bilang iya nanti saya coba dan ternyata dia suka juga karena tidak repot seperti kalau
pake kondom. Saya bilang bagus juga kalau bapak yang ber KB, karena kalau saya yang minum
pil biasa lupa dan pusing-pusing, Menemani ke dokter untuk periksa setelah operasi lalu “.
(N.H, 43 th, SPRG, 23 Maret 2012)
“ Sekitar 3 tahun. Saya yang menyuruh untuk ikut vasektomi, karena saya sering sakit-sakit.
Sebenarnya saya yang mau di operasi tapi begitu diruang operasi tekanan darah saya tinggi jadi
dibatalkan, Memberikan pengertian kepada bapak supaya dia yang ikut KB awalnya dia tidak
mau tapi lama-lama dia mau juga mungkin kasihan barangkali dia lihat saya kalau minum pil
atau suntik sering sakit-sakit“. (S.N.D, 41 th, SMP, 25 Maret 2012)
“ Bapak ikut vasektomi sudah 2 tahun. Saya yang menyuruh bapak untuk di vasektomi karena
anak sudah banyak, tapi sebelumnya kami dengar dari pak sulaeman yang sudah di vasektomi.
Alhamdulillah semenjak bapak di vasektomi saya menjadi lebih sehat “. (M.R.N, 37 th, SMP, 21
April 2012)
Program keluarga berencana
“ Yang sudah dilaksanakan di Kota Palu adalah pelayanan KB yang menjangkau daerah-daerah
khusus seperti daerah miskin seperti di daerah LEKATU di daerah Palu Barat daerah sulit jalan
ke Salena. Kami melakukan penyuluhan melalui mobil unit penerangan KB (MUPEN) melalui
pemutaran film, kerjasama dengan KORPRI melakukan penyuluhan bagi PNS golongan 1 dan 2
serta tenaga honorer dengan menghadirkan dokter spesialis sebagai narasumber. Kami juga
menghadirkan bapak-bapak yang sudah ikut vasektomi. Ada juga konselor sebaya. Dana untuk
penyuluhan sangat terbatas dan kami belum pernah menganggarkan penyuluhan KB pria baru
penyuluhan secara umum saja “. (K.T, 49 th, S2, 28 Maret 2012)
“ Program yang dilakukan masih tertuju pada KB aktif. Belum ada program khusus untuk
akseptor KB pria karena pilihan untuk KB pria lebih sedikit. Tidak ada sosialisasi secara khusus
tentang program KB pria karena itu domain dari BKKBN Kota kita sebagai pelaksana atau
eksekutor dilapangan seperti bila ada KB KES mereka yang menyiapkan pasiennya kami
menyiapkan tenaganya. Masih kurang, karena pemahamannya masyarakat yang menganggap
bahwa persoalan hamil dan tidak hamil itu adalah urusannya perempuan. Ada juga pemahaman
38 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
dari istrinya bahwa bila suaminya divasektomi sama dengan dikebiri dan mempengaruhi dalam
hubungan suami istri “. (N.S.R, 52 th, S2, 04 April 2012)
Peran petugas kesehatan
Peran petugas kesehatan dalam meningkatkan cakupan akseptor KB bervariasi. Berikut
hasil wawancara mendalam dan terhadap yaitu :
Pertanyaan : Kegiatan apa yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi pria dalam program
KB ? Bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta KB di pelayanan kesehatan ?
“ Biasa bergabung atau kumpul-kumpul dengan kelompok dasa wisma atau kegiatan PKK yang
ada dikelurahan, Ada juga program dari BKKBN bagi bapak-bapak yang mau di vasektomi
diberikan kompensasi uang selama 3 hari termasuk motivatornya “ (S.H, 11 Maret 2012)
“ Biasa kita berikan penyuluhan kepada ibunya dulu, kita anjurkan kalau datang supaya bersama
suaminya lalu kita berikan penyuluhan. kalau ibu tidak mau ber KB karena alasan tidak cocok
dengan alat kontrasepsi, kita berikan pilihan untuk suami ber KB seperti kondom. Jarang
penyuluhan dari PLKB masing-masing jalan sesuai dengan program masing-masing, kami di
Puskesmas hanya melayani saja “. (M, 09 April 2012)
“ Biasa pasien yang datang melahirkan disini kita sarankan untuk ber KB. Torang (kami) hanya
menunggu yang datang saja di Puskesmas sedangkan yang memberikan penyuluhan di
masyarakat ada PLKB yang memang tugasnya dorang (mereka) Bagaimana tidak ada bapak-
bapak yang datang ambil kondom di Puskesmas alasannya malu dorang sama torang, ada juga
yang gengsi berKB. Sedangkan petugas kesehatan yang ikut KB kondom malu bila dia ditau
menggunakan kondom “. (N.Y, 13 April 2012)
“ Biasa di Posyandu kami lakukan penyuluhan tapi hanya kepada ibu-ibunya saja karena bapak-
bapaknya jarang yang hadir katanya sibuk bekerja. torang (kami) anjurkan bila sudah
melahirkan supaya ibu atau bapaknya berKB Kami membentuk kelompok ibu-ibu hamil di setiap
posyandu, kalau untuk vasektomi bapak-bapaknya belum mau karena menganggap vasektomi
sama dengan di kebiri “. (R.T, 15 April 2012)
“ Vasektomi itu menurut orang awam sama dengan dikebiri kita harus memotivasi sasaran pada
keluarga pra sejahtera dan yang banyak anaknya. Kita juga kerja sama dengan lintas sektoral
dan program dengan menghadirkan bapak-bapak yang sudah divasektomi dihadirkan sehingga
mereka percaya. membentuk kelompok ibu anak suami (KIAS), yang akseptor aktifnya kita perlu
pembinaan supaya dipertahankan dipelayanan kesehatan kita kerja sama dengan bidan “
(H.N.M, 16 April 2012)
PEMBAHASAN
Pengetahuan akseptor KB pria
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan akseptor tentang program
keluarga berencana masih rendah responden belum mengetahui dengan jelas tentang keluarga
berencana secara umum. Keikut sertaan responden pada program KB karena alasan kesehatan istri
dimana bila istrinya yang menggunakan pil atau suntik sering sakit-sakit sehingga tidak dapat
beraktivitas dan melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga responden mengambil alih peran
dengan mengikuti program KB. Pemahaman responden terhadap vasektomi masih keliru dimana
ada sebagian responden yang menganggap vasektomi sama dengan di kebiri. Ketidak ikut sertaan
beberapa responden dalam mengikuti vasektomi karena ada rasa ketakutan dalam tindakan operasi
serta efek samping dari operasi seperti infeksi dan ketakutan akan kegagalan dari tindakan operasi.
Responden masih malu untuk membeli kondom di apotek secara terang-terangan dan mengambil
39 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
kondom di pelayanan kesehatan karena adanya pandangan yang negatif di masyarakat bila
menggunakan kondom akan di pergunakan tidak semestinya sehingga masyarakat tabu untuk
membicarakan kondom dan responden menganggap bahwa lebih baik diambilkan oleh istri.
Dukungan keluarga
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa keluarga sangat mendukung suami untuk
mengikuti keluarga berencana di mana manfaat yang dirasakan sangat banyak diantaranya menjadi
tubuh menjadi lebih sehat dan punya kesempatan untuk mengurus anak dan rumah tangga dengan
baik, bentuk dukungan yang diberikan adalah dengan pergi mengontrol ke petugas kesehatan bila
ada keluhan dari suami, mengambilkan kondom di sarana pelayanan kesehatan. Istri memberikan
kepercayaan penuh kepada suami untuk memilih metode kontrasepsi yang di ikuti karena suami
mempunyai otonomi yang kuat untuk menentukan metode apa yang di ikuti. Dimana keadilan dan
kesetaraan gender didalam keluarga khususnya pada pengambilan keputusan sebagian besar masih
didominasi suami, termasuk dalam pengaturan jumlah anak. Perempuan tidak mempunyai
kekuatan untuk memutuskan metoda kontrasepsi yang diinginkan, antara lain karena
ketergantungan kepada keputusan suami, Selain itu kontrol laki-laki terhadap perempuan dalam
hal memutuskan untuk ber-KB sangat dominan. Menurut Lubis (2009), pengaruh istri dan
kompensasi memiliki pengaruh terhadap keputusan untuk menjadi akseptor vasektomi.
Pemegang program KB
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa program keluarga berencana sudah
menjangkau daerah-daerah khusus dan daerah terpencil, memberikan penyuluhan kepada
masyarakat melalui berbagai media di antaranya dengan pemutaran film yang berkaitan dengan
program KB, membentuk konselor sebaya, membentuk pusat informasi konseling remaja (PIK
remaja) diberbagai perguruan tinggi.
Peran petugas kesehatan
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peran petugas kesehatan dalam
meningkatkan cakupan akseptor KB terutama KB pria sangat besar. Kegiatan yang dilakukan
adalah melakukan pembinaan dan memberikan konseling kepada pasangan yang ingin mengikuti
program KB, membentuk kelompok ibu anak dan suami (KIAS) di setiap posyandu dengan
harapan pria dapat mengikuti program KB.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kami menyimpulkan bahwa pengetahuan akseptor KB pria tentang keluarga berencana
masih rendah, pemahaman yang keliru tentang vasektomi yang menganggap vasektomi sama
dengan kebiri dan persepsi yang negative dari masyarakat kepada pengguna kondom sehingga
masyarakat merasa tabu untuk membcarakan kontrasepsi kondom. Keluarga sangat mendukung
bila suami mengambil alih peran sebagai pesertan KB, bentuk dukungan yang diberikan menemani
suami untuk pergi ke petugas kesehatan dan mengambil kondom di pelayanan kesehatan. Program
keluarga sudah menjangkau daerah yang sulit, memberikan penyuluhan melalui mobil unit
penerangan, pemutaran film, membentuk konselor sebaya dan pusat informasi konseling remaja di
perguruan tinggi. Peran petugas kesehatan memberikan konseling, membentuk kelompok ibu,
anak dan suami disetiap posyandu, sasaran lebih di prioritaskan kepada masyarakat pra sejahtera,
mempunyai anak banyak dan mempertahankan akseptor aktif. Saran perlu sosialisasi khusus untuk
program KB pria, memberikan pemahaman yang jelas tentang program KB serta melakukan
pencatatan akseptor KB yang lengkap di semua pelayanan kesehatan.
40 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
DAFTAR PUSTAKA
BKKBN. (2007). Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB. BKKBN. Bandung
BKBPP, (2012), Data Peserta KB Kota Palu Tahun 2011
BKBPP, (2011), Keluarga Berencana (KB) Pria sepi Peminat,
(www.scribd.com/doc/31708276/prorgram KB di Indonesia), Diakses Tanggal 12
Desember 2011
Endang, (2006). Buku Sumber Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Gender, dan
Pembangunan Kependudukan. BKKBN & UNFPA. Jakarta
Hertimaryani, (2007), Cara Tepat Memilih Alat Kontrasepsi Keluarga Berencana Untuk Wanita
(http;//sexhealthworld.blogspot.com) diakses 10 Januari 2012
Komariah Aan and Satori Djaman, (2011). Metodologi penelitian Kulaitatif. Penerbit Alfa Beta
Bandung
Meilani, (2010), Pelayanan keluarga Berencana. Fitramaya, Yogyakarta
Mulyadi, E. Metode Perancangan Penelitian Menggunakan Pendekatan kualitatif. Pusat
Pengembangan Bahan Ajar, UMB. (Online)
(pksm.mercubuana.ac.id/new/elearning/files.../910189797720775548.doc),
diakses 04 April 2012.
Satria, (2005). Isu Gender dalam Kesehatan Reproduksi. Pusat Pelatihan Gender dan Peningkatan
Kualitas Perempuan BKKBN. Jakarta
Suwandi and Basrowi, (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Penerbit Rineka Cipta
41 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
HUBUNGAN PENGETAHUAN, SIKAP, DAN KETERSEDIAAN FASILITAS DENGAN
PRAKTIK PETUGAS PENGUMPUL LIMBAH MEDIS DI RSUD ABDUL WAHAB
SJAHRANIE SAMARINDA
Jasmawati1, Prof.Dr.dr.H.Muh.Syafar1,MS, Dr.Hj. Nurhaedar Jafar, Apt, M. Kes2
1
Bagian Promosi Kesehatan, Fakultas Kesehatan Masyarakat,
Universitas Hasanuddin,
2
Bagian Gizi, Fakultas Kesehatan masyarakat,
Universitas Hasanuddin
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan ketersediaan
fasilitas yang dimiliki petugas pengumpul limbah medis dengan praktik petugas pengumpul
limbah medis. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survey dengan pendekatan
metode Cross Sectional Study. Populasi penelitian ini adalah semua petugas pengumpul limbah
medis yang ada di RSUD AWS Samarinda dengan jumlah 45 orang dengan total sampling. Data
dianalisis dengan uji statistik Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada
hubungan antara pengetahuan dengan praktik petugas pengumpul limbah medis. Praktik yang
baik dalam mengumpul limbah medis umumnya dilakukan oleh petugas yang memiliki
pengetahuan baik (91,2 %) dibandingkan petugas yang berpengetahuan cukup (72,7 %). Tidak
ada hubungan antara sikap dengan praktik petugas pengumpul limbah medis. Praktik baik lebih
banyak dilakukan oleh petugas yang bersikap positif (90,6 %) dibandingkan petugas yang
bersikap negatif (76,9 %). Tidak ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktik
petugas pengumpul limbah medis. Praktik baik lebih banyak dilakukan oleh petugas dengan
ketersediaan fasilitas baik (90 %) dibandingkan petugas dengan ketersediaan fasilitas kurang baik
(60 %). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan kepada pihak manajemen RSUD
AWS Samarinda lebih memperhatikan tingkat pengetahuan petugas agar mereka dapat berpraktik
yang baik dalam mengumpul limbah medis. Perlunya perhatian pihak manajemen RSUD AWS
Samarinda dalam meningkatkan sikap petugas agar berpraktik yang baik dalam mengumpul
limbah medis. Pentingnya perhatian dan pengawasan dari pihak manajemen RSUD AWS
Samarinda dalam penyediaan fasilitas bagi petugas serta pentingnya komitmen petugas dalam
menggunakan fasilitas tersebut yang telah disediakan oleh pihak rumah sakit.
Kata Kunci : Pengetahuan, Sikap, Fasilitas, Praktik, Petugas
ABSTRACT
This Research aim to know relation between knowledge, attitude, and availability of facility with
practice officer of compiler of medical waste. This research represent research having the
character of survey with approach of method of Cross Sectional Study. Population is all officer of
compiler of medical waste exist in RSUD AWS Samarinda with amount 45 people totally sampling.
Data analysed with statistical test of Chi-Square. Result of research indicate there no relation
between knowledge with practice officer of compiler of medical waste, there no relation between
attitude with practice officer of compiler of medical waste, and there no relation between
availibility of facility with practice officer of compiler of medical waste. Recomendation to result
of research, hence suggested to management of RSUD AWS Samarinda to be giving training and
education to officer of compiler of medical waste hospital which still have unfavourable
knowledge and negative attitude in doing its work. Needed attention and observation of ready
hospital management specially facility in supporting management of medical waste. To officer of
compiler of medical waste garbage so that remain to commitment in taking care of and using
facility supporter of work which have been provided by hospital.
Keyword : Knowledge, Attitude, Facility, Practice, Officer
42 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
PENDAHULUAN
R umah sakit sebagai suatu industri jasa yang memberikan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat baik yang bersifat kuratif dan rehabilitatif. Namun, selain
memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitarnya, rumah sakit memberikan
pula berbagai kemungkinan dampak negative berupa pencemaran, apabila pengelolaan limbahnya
tidak dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan secara
menyeluruh (Muslim, 2002). Rumah sakit dapat menimbulkan bahaya bagi para penderita dan
pekerjanya, baik bagi para dokter, perawat, teknisi, dan semua yang berkaitan dengan pengelolaan
rumah sakit maupun perawatan penderita (Kusnoputranto, 2000). Rumah sakit sebagai salah satu
pelayanan umum yang berfungsi menangani, merawat dan mengobati orang sakit akan
menghasilkan limbah dengan kuantitas dan kualitas yang perlu diperhatikan, karena didalamnya
mengandung bahan berbahaya dan beracun (Adikoesoemo, 2002).
Pengumpulan limbah medis dipisahkan antara limbah medis dengan non medis, termasuk
pemisahan dan pengumpulan limbah medis berdasarkan karakteristik. Pemisahan limbah medis
sejak dari ruangan merupakan langkah awal memperkecil kontaminasi limbah non medis. Menurut
Muliartha dalam Cyber Tokoh tahun 2008, pengangkutan limbah medis dengan non medis
dilakukan secara terpisah, diperlukan troli khusus sebab limbah medis digolongkan ke dalam
limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) yang sifatnya mudah meledak, terbakar, reaktif,
beracun, bersifat korosif dan bisa menyebabkan infeksi serius seperti hepatitis dan HIV-AIDS.
Limbah medis yang dihasilkan rumah sakit dapat berdampak negative terhadap kesehatan
masyarakat apabila penanganan limbahnya tidak sesuai dengan Kepmenkes RI No. 1204 tahun
2004, misalnya tidak dilakukan pemisahan antara limbah medis dengan non medis, tempat
penampungan sampah di masing-masing ruangan tidak memenuhi standar, petugas pengumpul
limbah medis tidak memakai APD, pengangkutan limbah medis menuju ke tempat pembuangan
sementara menggunakan troli/gerobak terbuka, jalur yang digunakan adalah jalur umum yang
biasa digunakan untuk pasien dan pengunjung rumah sakit, tidak ada label baik di tempat sampah
maupun di troli.
Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan Retno tahun 2005 di RSUP Dr.Sardjito,
menyatakan bahwa berdasarkan hasil uji chi square diperoleh p=0,000, yang berarti ada hubungan
yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku pengumpul sampah. Berdasarkan hasil uji chi
square diperoleh bahwa p=0,003, yang berarti ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan
fasilitas dengan perilaku pengumpul sampah.Limbah medis yang dihasilkan rumah sakit dapat
berdampak negative terhadap kesehatan masyarakat apabila penanganan limbahnya tidak sesuai
dengan Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004, misalnya tidak dilakukan pemisahan antara limbah
medis dengan non medis, tempat penampungan sampah di masing-masing ruangan tidak
memenuhi standar, petugas pengumpul limbah medis tidak memakai APD, pengangkutan limbah
medis menuju ke tempat pembuangan sementara menggunakan troli/gerobak terbuka, jalur yang
digunakan adalah jalur umum yang biasa digunakan untuk pasien dan pengunjung rumah sakit,
tidak ada label baik di tempat sampah maupun di troli.
Limbah medis dapat menyebabkan kasus nosokomial. Kasus nosokomial dapat terjadi di
bagian kesehatan lingkungan rumah sakit melalui pencemaran limbah rumah sakit, khususnya
petugas pengumpul limbah yang bersentuhan langsung pada proses pengumpulan dan pengelolaan
limbah tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian Burhanuddin tahun 2000 di Jawa Timur,
menunjukkan bahwa rumah sakit yang sanitasi lingkungannya tidak memenuhi standar
Kepmenkes RI No. 1204 tahun 2004 akan mendukung meningkatnya kasus nosokomial.
Pola perilaku petugas yang kurang memperhatikan aspek sanitasi lingkungan seperti tidak
melakukan pemisahan limbah sesuai jenisnya, tidak melewati jalur khusus limbah dan lainnya
serta kurangnya kesadaran petugas dalam penggunaan APD seperti tidak menggunakan masker
atau sarung tangan ketika bekerja dapat meningkatkan jumlah kasus nosokomial karena dapat
terjadi infeksi melalui udara atau tertusuk jarum bekas dan lainnya. Pada dasarnya perilaku
didasari oleh pengetahuan, kesadaran dan sikap dari individu (Notoatmodjo, 2007). Hal ini
43 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
menyebabkan ada hubungan antara perilaku petugas dengan kejadian kasus nosokomial. Petugas
pengumpul limbah harus dapat berperilaku sesuai dengan standar persyaratan kesehatan
lingkungan rumah sakit yang berlaku.
Rumah Sakit Umum Daerah A.W. Sjahranie (RSUD AWS) Samarinda menjadi Top
Reveral, yaitu rumah sakit rujukan puncak di Kalimantan Timur sehingga jumlah pasien tinggi
dengan jumlah kunjungan bulan Oktober 2008 sebanyak 12.948 pasien. RSUD AWS
menghasilkan produksi limbah medis sebesar 70,5 kg/hari. Penanganan limbah medis di RSUD
AWS dilakukan oleh cleaning service yang ditugaskan di masing-masing ruangan. Setiap dua kali
sehari petugas mengambil sampah di masing-masing ruangan untuk dibawa ke pembuangan
sementara dan dibakar di incenerator.
Unit-unit rumah sakit yang menghasilkan limbah medis di antaranya ruang
perawatan/rawatinap, IGD, laboratorium, instalasi farmasi, poliklinik, ICU, ICCU dan persalinan.
Fasilitas pelayanan kesehatan tersebut tentunya menghasilkan limbah seperti jarum suntik,
kasaverban, kapas suntik, ampul, infusan, obat kadaluarsa, sisa bungkus obat, pot urine, jaringan
tubuh, sarung tangan dan masih banyak yang lainnya. Hasil limbah tersebut jika tidak ditangani
dengan serius mendatangkan resiko yang cukup berbahaya seperti terjadi infeksi pada karyawan
maupun pasien dalam jangka waktu panjang.
Berdasarkan hal tersebut maka penulis ingin mengetahui hubungan pengetahuan, sikap dan
ketersediaan fasilitas pembuangan limbah medis dengan praktik petugas pengumpul limbah
medisdi RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2012.
METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat survey dengan pendekatan metode Cross
Sectional Study, dimana data yang menyangkut variabel bebas dan variabel terikat akan
dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan dan hasilnya akan dianalisa secara deskriptif dan
analitik (Notoatmodjo, 2005), yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan
pengetahuan, sikap dan ketersediaan fasilitas yang dimiliki dengan praktik petugas pengumpul
limbah medis di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda tahun 2012.
Tempat dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda jalan Palang Merah
Indonesia, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda. Waktu penelitian dilakukan setelah
dilaksanakan kegiatan seminar proposal yaitu pada bulan Juli 2012. Untuk lebih jelasnya
mengenai jadwal pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada lampiran.
Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah semua petugas pengumpul limbah medis yang ada di
RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda dengan jumlah 45 orang. Sampel dalam penelitian ini
adalah cleaning service yang bertugas mengumpul limbah medis. Pengambilan sampel secara total
sampling dari populasi dengan jumlah 45 orang.
Variabel Penelitian
Variabel bebas : Pengetahuan, sikap dan ketersediaan fasilitas yang dimiliki petugas pengumpul
limbah medis.
Variabel terikat : Praktik petugas pengumpul limbah medis.
Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dengan pengambilan data primer yakni Observasi dan
pembagian Kuisioner yang berisi pertanyaan mengenai identitas petugas pengumpul sampah,
pengetahuan petugas pengumpul sampah medis mengenai sampah medis, alat pelindung diri yang
dipakai, dampak negatif sampah medis dan pengelolaan sampah medis. Kuisioner ditujukan
kepada responden. Dan pengambilan Data Sekunder, yang dapat diperoleh dari pihak RSUD
44 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda, berupa data jumlah tempat tidur, jumlah pekerja dan profil
rumah sakit.
Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan adalah pedoman penelitian berupa kuisioner dan
lembar observasi, alat tulis dan peneliti.
Validitas dan Reliabilitas
Validitas dengan menggunakan Teknik korelasi product moment yang rumusnya yaitu
sebagai berikut :
N(EXY)(EX EY)
R=
VI (NEX – EX) (NEX – EY)
Keterangan :
X = Pertanyaan nomor x
Y = Skors total
XY = Skors pertanyaan nomor x dikali skors total.
Reliabilitas, Cara perhitungan reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan teknik tes-tes ulang, dimana dengan teknik ini kuesioner yang sama diteskan
(diujikan) kepada sekelompok responden yang sama sebanyak dua kali. (Notoatmodjo, 2005).
Pengolahan dan Penyajian Data
Pengolahan data dengan Coding, Skoring, Tabulasi, Editing, kemudian penyajian data.
Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisa secara univariat dan bivariat.Analisis Univariat, data
yang diperoleh dari tiap variabel, disajikan dalam tabel yang telah dipersiapkan dan kemudian
angka-angka dalam tabel dianalisa secara deskriptif, dan analisis bivariat yang bertujuan untuk
mengetahui hubungan dua variabel, biasanya menggunakan pengujian statistik.
HASIL PENELITIAN
Karakteristik Responden
Berdasarkan kelompok umur responden ditemukan bahwa umur 20-29 tahun sebanyak 30
orang (66,7 %), umur 30-39 sebanyak 14 orang (31,1 %), dan umur 40-49 tahun sebanyak 1 orang
(2,2 %). Masa kerja responden ditemukan bahwa masa kerja 0-5 tahun sebanyak 30 orang (66,7
%), masa kerja 6-10 tahun sebanyak 8 orang (17,8 %), dan masa kerja > 10 tahun sebanyak 7
orang (15,6 %). Pendidikan terakhir responden ditemukan bahwa SMP sebanyak 7 orang (15,6 %)
dan SMA sebanyak 38 orang (84,4 %). Sistem perekrutan petugas sanitasi khususnya pengumpul
limbah medis yang dilakukan oleh pihak rumah sakit menetapkan bahwa minimal berpendidikan
SMA, namun dalam penelitian ini masih ditemukan petugas dengan pendidikan SMP. Hal ini
disebabkan petugas tersebut direkrut dengan pertimbangan bahwa mereka telah lama menjadi
petugas pengumpul limbah di rumah sakit sebelum kriteria perekrutan tersebut diberlakukan.
Perilaku Petugas
Berdasarkan pengetahuan responden diperoleh bahwa responden dengan pengetahuan baik
sebanyak 34 orang (75,6 %) dan pengetahuan cukup sebanyak 11 orang (24,4 %). Sikap petugas
pengumpul limbah medis ditemukan bahwa sikap positif sebanyak 32 orang (71,1 %) dan negatif
13 orang (28,9 %). Praktik petugas pengumpul limbah medis ditemukan bahwa petugas dengan
praktik baik sebanyak 39 orang (86,7 %) dan praktik kurang baik sebanyak 6 orang (13,3 %).
Pengetahuan Petugas Pengumpul Limbah Medis
Berdasarkan hasil jawaban responden diperoleh bahwa terdapat beberapa pernyataan
(nomor 3, 7, dan 9) petugas menjawab dengan benar 100 %. Pernyataan yang masih kurang
mendapat jawaban benar dari responden adalah nomor 1 dan 6 masing-masing 64,4 % dan 66,7 %.
Sikap Petugas Pengumpul Limbah Medis
Berdasarkan hasil jawaban sikap responden diperoleh bahwa sikap paling banyak setuju
(53,3 %) terdapat pada pernyataan pembakaran sampah medis dilakukan di incenerator.
45 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Sebaliknya pada pernyataan yang sama diperoleh bahwa semua petugas menyatakan sangat tidak
setuju.
Analisis Bivariat
Hubungan Pengetahuan dengan Praktik Petugas Pengumpul Limbah Medis, diperoleh
bahwa dari 34 responden yang memiliki pengetahuan baik dengan praktik baik dalam mengumpul
limbah medis sebanyak 31 orang (91,2 %) dan praktik kurang baik sebanyak 3 orang (8,8 %).
Bahwa dari 11 responden yang memiliki pengetahuan cukup dengan praktik mengumpul sampah
yang baik sebanyak 8 orang (72,7 %) dan praktik yang kurang baik sebanyak 3 orang (27,3 %).
Hasil uji statistic Chi Square diperoleh nilai p value sebesar 0,146 > α (0,05), hal ini berarti tidak
ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik petugas pengumpul limbah medis.
Hubungan Sikap dengan Praktik Petugas Pengumpul Limbah Medis, diperoleh bahwa dari
32 responden yang memiliki sikap positif dengan praktik baik dalam mengumpul limbah medis
sebanyak 29 orang (90,6 %) dan praktik kurang baik sebanyak 3 orang (9,4 %). Sedangkan dari 13
responden yang memiliki sikap negatif dengan praktik mengumpul sampah yang baik sebanyak 10
orang (76,9 %) dan praktik yang kurang baik sebanyak 3 orang (23,1 %). Hasil uji statistic Chi
Square diperoleh nilai p value sebesar 0,334 > α (0,05), hal ini berarti tidak ada hubungan antara
sikap dengan praktik petugas pengumpul limbah medis.
Hubungan Ketersediaan Fasilitas dengan Praktik Petugas Pengumpul Limbah Medis,
diperoleh bahwa dari 40 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas baik dengan praktik baik
dalam mengumpul limbah medis sebanyak 36 orang (90 %) dan praktik yang kurang baik
sebanyak 4 orang (10 %). Sedangkan dari 5 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas kurang
baik dengan praktik mengumpul sampah yang baik sebanyak 3 orang (60 %) dan praktik yang
kurang baik sebanyak 2 orang (40 %). Hasil uji statistic Chi Square diperoleh nilai p value sebesar
0,125 > α (0,05), hal ini berarti tidak ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktik
petugas pengumpul limbah medis.
PEMBAHASAN
Hubungan Pengetahuan dengan Praktik Petugas Pengumpul Limbah Medis
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan
praktik petugas pengumpul sampah medis. Hal ini disebabkan sebagian besar petugas pengumpul
limbah memiliki pengetahuan baik (75,6 %) dan melakukan pengumpulan secara baik (86,7 %).
Sehingga petugas pengumpul sampah yang memiliki pengetahuan dan praktik kurang baik
ditemukan relatif sedikit. Pengetahuan dan praktik yang baik oleh petugas dalam mengumpulkan
limbah dipengaruhi oleh pendidikan mereka. Petugas pengumpul limbah rata-rata memiliki
pendidikan tinggi yakni SMA (84,4 %).
Penelitian lain juga diperoleh hal serupa bahwa banyak petugas yang belum memakai alat
pelindung diri seperti masker dan sarung tangan dalam mengumpul limbah rumah sakit (Nenny,
2006). Pengetahuan responden tentang pengelolaan sampah dibangun berdasar kemampuan
berpikir sesuai dengan kenyataan yang responden lihat dan temukan di lingkungan sekitar
responden berada. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan merupakan hasil seseorang
melakukan penginderaan terhadap obyek tertentu (Notoatmodjo, 1998). Pengetahuan responden
mengenai cara pengelolaan limbah yaitu penampungan dan pemusnahan dengan memisahkan
limbah medis dengan non medis, sehingga responden sepakat bahwa antara tempat sampah medis
dan non medis harus berbeda. Hal ini sesuai dengan tata cara penanganan sampah bahwa sampah
dari setiap ruang/unit harus dipisahkan sesuai dengan kategori atau jenis sampah dan dimasukkan
ke dalam tempat sampah yang telah disediakan oleh staf/personil yang bekerja pada ruang/unit
yang bersangkutan (Bagoes, dkk, 2003).
Hubungan Sikap dengan Praktik Petugas Pengumpul Limbah Medis
Bahwa dari 32 responden yang memiliki sikap positif dengan praktik baik dalam
mengumpul limbah medis sebanyak 29 orang (90,6 %). Sikap responden terhadap pengelolaan
sampah adalah bahwa responden memandang pengelolaan sampah sangat penting dilakukan. Hal
46 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
ini dapat dinilai berdasarkan jawaban responden yang menyatakan setuju dilakukan pembakaran
sampah medis di incinerator (97,7 %).
Sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa masih terdapat responden yang
memiliki sikap positif tetapi praktik yang kurang baik (9,4 %). Salah satu faktor yang memperkuat
penyebab terjadinya perilaku responden yang demikian adalah seorang teman. Satu orang teman
melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, orang lain cenderung untuk
menirunya. Hal ini sesuai dengan teori bahwa salah satu penyebab terjadinya perubahan perilaku
adalah seorang teman (Azwar, 2002).
Bahwa dari 13 petugas pengumpul limbah medis yang memiliki sikap negatif tetapi praktik
mengumpul sampah yang baik sebanyak 10 orang (76,9 %). Hal ini disebabkan pengalaman kerja
responden yang sudah cukup lama (misalnya bekerja telah > 10 tahun) sebagai petugas
mengumpul limbah medis rumah sakit. Meskipun responden menyatakan setuju bahwa tempat
limbah medis tidak diberikan label (37,7 %), akan tetapi karena kebiasaan yang sudah lama
dilakukan dan dianggap benar, mendorong mereka untuk tetap membuang limbah pada kantong
plastik yang sama jenis dan sifatnya.
Sikap yang terbentuk tergantung pada pengetahuan seseorang, semakin tinggi pengetahuan
seseorang terhadap sesuatu, semakin positif sikap yang terbentuk. Pembentukan sikap responden
dalam mengumpul limbah medis sesuai dengan pengalaman pribadi di lapangan. Berdasarkan
pengalaman pribadi responden tersebut, sikap responden terhadap tempat limbah khususnya
kantong pembungkus limbah medis tidak sesuai dengan ketentuan dari Depkes RI dalam hal
ketentuan mengganti kantong plastik secara rutin dengan plastik yang bersih dan setelah terisi
penuh 2/3 bagian. Namun hal tersebut tidak merupakan suatu kesalahan yang fatal dikarenakan
Departemen Kesehatan memberikan kelonggaran kepada setiap institusi untuk memiliki ketentuan
tersendiri berkaitan dengan pengadaan tempat sampah.
Hubungan Ketersediaan Fasilitas dengan Praktik Petugas Pengumpul Limbah Medis
Keberadaan tempat sampah limbah medis yang sudah dalam kondisi kurang memadai, akan
berpengaruh terhadap perilaku petugas dalam melakukan pengumpulan sampah. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh bahwa dari 40 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas baik dengan
praktik baik dalam mengumpul limbah medis sebanyak 36 orang (90 %). Sebagian besar petugas
menyatakan bahwa terdapat tempat sampah limbah medis, tempat sampah yang tersedia berbeda
warna dan dilengkapi dengan kantong plastik. Ketersediaan fasilitas yang berkaitan langsung
dengan pekerjaan pengumpulan limbah medis akan diikuti dengan tindakan yang baik oleh
petugas. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Idkha, 2009 di Rumah Sakit Khusus di
Surabaya Timur menunjukkan bahwa pihak rumah sakit melakukan mitra pengolahan limbah
medis dengan cara memenuhi biaya yang ditawarkan.
Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan
praktik pengumpul limbah medis. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Retno, 2005 yang
menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara ketersediaan fasilitas dengan perilaku
pengumpul sampah di RSUP Dr. Sardjito. Hasil penelitian Purwoutomo, 2004 menyatakan bahwa
ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktek pengumpul sampah medis di RSD
Raden Soejati.
Suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan. Untuk terwujudnya sikap agar
menjadi suatu perbuatan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang
memungkinkan, antara lain adalah fasilitas. Tim kerja dari WHO menyatakan bahwa penyebab
seseong berperilaku tertentu salah satunya adalah keberadaan sumber daya. Surnber daya di sini
mencakup.keberadaan fasilitas (Notoatmodjo, 2003).
Keberadaan tempat sampah limbah medis yang sudah dalam kondisi kurang memadai, akan
berpengaruh terhadap perilaku petugas dalam melakukan pengumpulan sampah. Berdasarkan hasil
penelitian diperoleh bahwa dari 40 responden yang memiliki ketersediaan fasilitas baik dengan
praktik baik dalam mengumpul limbah medis sebanyak 36 orang (90 %). Sebagian besar petugas
menyatakan bahwa terdapat tempat sampah limbah medis, tempat sampah yang tersedia berbeda
47 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
warna dan dilengkapi dengan kantong plastik. Ketersediaan fasilitas yang berkaitan langsung
dengan pekerjaan pengumpulan limbah medis akan diikuti dengan tindakan yang baik oleh
petugas.
KESIMPULAN DAN SARAN
Tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan praktik petugas pengumpul limbah
medis. Praktik yang baik dalam mengumpul limbah medis umumnya dilakukan oleh petugas yang
memiliki pengetahuan baik (91,2 %) dibandingkan petugas yang berpengetahuan cukup (72,7
%).Tidak ada hubungan antara sikap dengan praktik petugas pengumpul limbah medis. Praktik
baik lebih banyak dilakukan oleh petugas yang bersikap positif (90,6 %) dibandingkan petugas
yang bersikap negatif (76,9 %). Tidak ada hubungan antara ketersediaan fasilitas dengan praktik
petugas pengumpul limbah medis. Praktik baik lebih banyak dilakukan oleh petugas dengan
ketersediaan fasilitas baik (90 %) dibandingkan petugas dengan ketersediaan fasilitas kurang baik
(60 %). Saran Kepada pihak manajemen RSUD AWS Samarinda lebih memperhatikan tingkat
pengetahuan petugas agar mereka dapat berpraktik yang baik dalam mengumpul limbah medis,
Perlunya perhatian pihak manajemen RSUD AWS Samarinda dalam meningkatkan sikap petugas
agar berpraktik yang baik dalam mengumpul limbah medis. Pentingnya perhatian dan pengawasan
dari pihak manajemen RSUD AWS Samarinda dalam penyediaan fasilitas bagi petugas serta
pentingnya komitmen petugas dalam menggunakan fasilitas tersebut yang telah disediakan oleh
pihak rumah sakit.
DAFTAR PUSTAKA
Adikoesoemo, Suparto. 2002. Manajemen Rumah Sakit. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
Aktawalora, Maksentinus, 2008. Pengelolaan Limbah Medis Padat di RSUD Dr. M. Haulussy
Ambon. Jurnal Kesehatan.
Altin,S., A. Altin, B. Elevli, O.Cerit. 2002 dalam Idkha 2009. Determination of Hospital Waste
Composition and Disposal Methods:a Case Study. Turkey:Polish Journal of
Environmental Studies. 12. 251-255
Arestria, Dian Fitri. 2009. Analisis Sistem Pengelolaan Limbah Medis dan Non Medis di
Rumkitpolpus RS. Sukanto. Jurnal Kesmas UI
Adisasmito, Wiku. 2007. Sistem Manajemen Lingkungan Rumah Sakit. Jakarta : PT. Rajawali
Press.
Bagoes, dkk. 2003. Perilaku Petugas Kebersihan Rumah Sakit dalam Pengelolaan Sampah di RS.
Nirmala Suri Sukoharjo. Jurnal Unismus
Depkes RI. 2000. Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Padat dan Limbah Cair di Rumah
Sakit. Jakarta : Dirjen PPM dan PLP dan Dirjen Pelayanan Medik.
Depkes RI. 2004.Kepmenkes RI No 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan
Lingkungan Rumah Sakit.Jakarta.
Dewi, Arie, Rina. 2002. Sistem Pengelolaan Limbah Medis di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta.
Jurnal Kesmas UI.
Elfianty, Rina. 2003. Pelaksanaan Minimisasi Limbah dan Pengolahan Limbah Klinis Rumah
Sakit Husada. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta : FKM UI.
El-Salam, M. M. A. dalam Idkha 2009. Hospital Waste Management in El-Beheira Governorate,
Egypt. Journal of Environmental Management. 91. 618-629
Hapsari, Riza. 2010. Analisis Pengelolaan Sampah dengan Pendekatan Sistem di RSUD DR.
Moewardi Surakarta. Jurnal Kesehatan Lingkungan, Vol. 2, No.1, Juli 2010:17-24
Kusnoputranto, Haryoto. 2000. Kesehatan Lingkungan. Jakarta : FKM UI.
Margono. 2006. Gambaran Sistem Pengolalaan Limbah Medis di RSUD Dr. H. Abdoel Moeloek
Provinsi Lampung. Skripsi Tidak Diterbitkan. Jakarta : FKM UI.
Moleong, L. J. 2005.Metode Penelitian Kualitatf. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
48 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Nenny, T., Soedjajadi. 2006. Evaluasi Pengelolaan Sampah Padat di Rumah Sakit. Jurnal
Kesehatan Lingkungan, Vol. 3, No.1, JULI 2006:21 -34
Ngatimin, Rusli. 2005. Ilmu Perilaku kesehatan. Makassar : Yayasan PK3.
Notoatmodjo Soekidjo. 2003.Ilmu Kesehatan Masyarakat Prinsip-Prinsip Dasar.Jakarta : PT.
Rineka Cipta.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2003.Pendidikan dan Perilaku Kesehatan.Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2005.Metode Penelitian Kesehatan.Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2007.Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
Nurchotimah, Enung. 2004. Pengelolaan Sampah Medis di Rumah Sakit Kanker Dharmais.
Skripsti Tidak Diterbitkan. Jakarta : FKM UI
Purwoutomo, 2004. Hubungan Tingkat Pengetahuan dan Ketersediaan Fasilitas Pembuangan
Sampah Medis dengan Praktek Petugas Pengumpul Sampah Medis di RSD. Raden
Soejati Purwodadi. Jurnal Kesehatan Lingkungan
Profil Rumah Sakit Abdoel Wahab Sjahranie. 2011. Samarinda
Reinhardt, Peter, A, et al. 1996. Pollution Prevention and Waste Minimization in Laboratories.
USA : CRS Press.
Retno. 2005. Tugas Akhir Penelitian di RSUP Dr. Sardjito. Yogyakarta : UGM.
Sarkar SKA., Haque MA., 2006 dalam Hapsari 2010. Hospital Waste Management in Sylhet City.
ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences. 2006; 1 (2).
49 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
PERLATIHAN APLIKASI METODE PENELITIAN KUALITATIF
BAGI MAHASISWA KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR
(Suriah Dan Indra Fajarwati)*
*Jurusan Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku,
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin
Abstrak
Mahasiswa sebagai calon peneliti membutuhkan metode yang tepat dalam pengumpulan
data dan menyajikan hasil penelitiannya sesuai dengan metode yang digunakan. Saat ini
ditemukan banyak kesulitan yang dialami mahasiswa utamanya mahasiswa dibidang kesehatan
dalam menggunakan metode penelitian kualitatif. Kegiatan ini bertujuan memberikan kemampuan
kepada mahasiswa dalam menyusun proposal menggunakan pendekatan kualitatif, terampil dalam
melakukan probing dan memandu FGD (Focus Group Discussion), mengembangkan instrumen
kualitatif, mengolah dan menganalisis data kualitatif, melakukan interpretasi data kualitatif serta
menyajikannya sebagai laporan hasil penelitian dengan metode kualitatif. Peserta perlatihan
adalah mahasiswa kesehatan tingkat akhir sebanyak 20 orang yang telah lulus mata kuliah
penelitian kualitatif dan sudah memiliki topik penelitian yang akan menggunakan metode
kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Hasil kegiatan antara lain: meningkatnya
pengetahuan mahasiswa tentang metode penelitian kualitatif yang dinilai dari hasi pre dan post
test perlatihan, meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam melakukan probing dan FGD,
menyusun proposal dan melakukan analisis serta interpretasi data kualitatif.
Kata kunci: Perlatihan, Metode Kualitatif, Mahasiswa Kesehatan
Abstract
The students as a researcher applicants need the appropriate methods for data collection
and present their results of research should according to the method used. Currently, founded
many difficulties experienced by the students, mainly the students of health which used qualitative
research methods. The purpose of this activity is to give the ability for the students in developing a
proposal by using a qualitative approach, have skilled to use of probing and guiding FGD (Focus
Group Discussion), developed a qualitative instrument, manage and analyze qualitative data,
doing interpretations and present it as a report in the research by using qualitative methods. The
participant of this training is the last grade of the student of health, as many 20 students who
passed the courses of qualitative research, and already has a research topic that will be used a
qualitative research method as approach of their research. The results of activities including;
improving the student knowledge about qualitative research methods, which assessed from the pre
and post test training, increasing the ability of students to make probing and focus groups, develop
proposals and the analysis and interpretation of qualitative data.
Key words: Training, Qualitative methods, Student of health.
I. Pendahuluan
M etode penelitian kualitatif muncul karena terjadi perubahan paradigma
dalam memandang suatu realitas, fenomena atau gejala. Dalam paradigma
ini realitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik atau utuh,
kompleks, dinamis dan penuh makna, sehingga berkembanglah metode penelitian kualitatif untuk
mengungkap suatu gejala sosial secara holistik. Metode penelitian kualitatif sering disebut
metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah.
50 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Metode penelitian kualitatif pada awalnya banyak digunakan dalam bidang ilmu sosial
dan antropologi, namun akhir-akhir ini, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang
telah banyak digunakan dibidang kesehatan. Meskipun kualitatif seringkali dianggap kurang
bermakna karena tidak dapat digeneralisasikan dan dianggap sangat subyektif, namun peneliti
dapat memanfaatkan kelemahan ini sebagai peluang untuk melihat masalah yang sensitif dalam
konteks sosial maupun individu. Subyek penelitian yang terbatas, dan jika terdapat kebutuhan
untuk menggali suatu informasi secara mendalam dari perspektif individu, maka penelitian
kualitatif menjadi solusi. Penelitian kualitatif banyak mengungkapkan kata sebagai hasil penelitian
yang tidak akan pernah terwakilkan oleh angka dan uji statistik.
Dalam perkembangan penggunaan metode kualitatif, tidak jarang ditemui hasil studi yang
dangkal akibat adanya kesalahan dalam menggunakan pendekatan kualitatif seperti melakukan
kuantifikasi terhadap data kualitatif, kurang menggali pendapat atau opini dari subyek penelitian
serta tidak berhasil dalam melakukan sintesis hasil kualitatif. Tuntutan untuk melaksanakan
penelitian kualitatif yang tepat cukup besar. Mengumpulkan data kualitatif merupakan
pelaksanaan kegiatan yang intensif, yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan
bertahun-tahun. Data kualitatif sebenarnya sangat menarik, merupakan sumber dari deskripsi yang
luas dan berlandasan kokoh serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam
latar sosial. Dengan data kualitatif, dapat diikuti dan dipahami alur peristiwa secara kronologis,
menilai sebab akibat dalam lingkup pemikiran orang-orang yang berada dalam konteks sosial yang
diteliti dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Data kualitatif cenderung dapat
menuntun peneliti untuk memperoleh temuan-temuan yang tak terduga sebelumnya dan untuk
membentuk kerangka pemikiran yang baru, sehingga dapat membantu peneliti untuk melangkah
lebih jauh dari praduga dan kerangka kerja awal.
Hasil temuan kualitatif apabila disusun dalam bentuk alur peristiwa, memunyai kesan
yang lebih nyata, hidup dan penuh makna, sehingga memungkinkan untuk bisa meyakinkan
pembaca, peneliti lainnya, pembuat kebijakan dan praktisi, dari pada sekedar hasil yang disajikan
dalam bentuk angka-angka. Untuk itulah sangat dibutuhkan kemampuan dari peneliti kualitatif
untuk dapat menyusun, mengumpulkan data dan menyajikan hasil kualitatif dengan tepat.
Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah
data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap tetapi
data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut. Masalah yang kemudian
timbul adalah dibutuhkan kemampuan dari peneliti untuk mengungkap makna dibalik opini,
perilaku dan konteks sosial.
Mahasiswa sebagai calon peneliti membutuhkan metode yang tepat dalam pengumpulan
data dan menyajikan hasil penelitiannya sesuai dengan metode yang digunakan. Saat ini
ditemukan banyak kesulitan yang dialami mahasiswa utamanya mahasiswa dibidang kesehatan
dalam menggunakan metode penelitian kualitatif, dikarenakan metode ini membutuhkan
keterampilan tertentu dalam menyusun proposal, mengumpulkan data, menganalisis data dan
menyajikan hasil interpretasi data kualitatif.
II. Bahan dan Metode
Sasaran perlatihan
Adapun sasaran perlatihan ini yaitu mahasiswa kesehatan tingkat akhir sebanyak 20 orang
yang telah lulus mata kuliah penelitian kualitatif dan sudah memiliki topik penelitian yang akan
menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya.Tahapan dan proses
kelayakan peserta yaitu:
- Evaluasi input: pengetahuan dasar tentang metode penelitian kualitatif dan memiliki topik
penelitian atau draft proposal penelitian kualitatif
- Evaluasi proses: pre dan post test peserta perlatihan untuk menilai penguasaan materi sebelum dan
setelah perlatihan serta penilaian terhadap proses diskusi, simulasi dan presentasi mahasiswa
selama perlatihan berlangsung
51 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
- Output: meningkatkan pengetahuan peserta perlatihan tentang metode penelitian kualitatif,
meningkatkan kemampuan peserta perlatihan dalam melakukan probing dan memandu diskusi
dengan teknik FGD, meningkatkan kemampuan peserta perlatihan dalam menyusun proposal
kualitatif, dan meningkatkan kemampuan peserta perlatihan dalam menganalisis dan melakukan
interpretasi data kualitatif
Waktu dan tempat perlatihan
Perlatihan dilaksanakan pada tanggal 9-11 November 2012 di Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Hasanuddin, Kota Makassar.
Materi, metode dan narasumber
Adapun materi yang disampaikan dalam kegiatan ini antara lain: konsep dasar penelitian
kualitatif, karakteristik penelitian kualitatif, penentuan masalah dalam penelitian kualitatif, jenis-
jenis desain dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif,
menyusun instrumen pengumpulan data dalam penelitian kualitatif analisis data kualitatif dan
menyusun serta mengembangkan proposal penelitian kualitatif. Beberapa metode yang digunakan
dalam perlatihan ini antara lain: ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi belajar lapangan dan
presentasi. Kemudian pemateri kegiatan yaitu: Prof. Dr. dr. H. M. Syafar, MS, Dr. Suriah, SKM,
MKes dan Indra Fajarwati Ibnu, SKM, MA
Uraian selengkapnya berkenaan dengan materi dan kegiatan perlatihan dapat dilihat pada
matriks berikut:
Matriks 1. Materi, Metode dan Pemateri Kegiatan Perlatihan
Hari Materi Pemateri Metode
1 Konsep dasar penelitian kualitatif Prof. Dr. dr. H. M. Syafar, MS Ceramah dan diskusi
Karakteristik penelitian kualitatif Indra Fajarwati Ibnu, SKM, MA Ceramah, diskusi dan studi
kasus
Penentuan masalah dalam Prof. Dr. dr. H. M. Syafar, MS Ceramah, diskusi dan studi
penelitian kualitatif kasus
2 Jenis-jenis desain dalam penelitian Dr. Suriah, SKM, MKes Ceramah, diskusi dan studi
kualitatif kasus
Metode pengumpulan data dalam Indra Fajarwati Ibnu, SKM, MA Ceramah, studi kasus,
penelitian kualitatif simulasi, belajar lapangan
Menyusun instrument Dr. Suriah, SKM, MKes Ceramah, studi kasus dan
pengumpulan data dalam simulasi
penelitian kualitatif
Analisis data kualitatif Dr. Suriah, SKM, MKes Ceramah, studi kasus dan
simulasi
3 Menyusun dan mengembangkan Dr. Suriah, SKM, MKes Ceramah, studi kasus dan
proposal penelitian kualitatif Indra Fajarwati Ibnu, SKM, MA simulasi
Penyajian proposal peserta Prof. Dr. dr. H. M. Syafar, MS Presentasi dan diskusi
perlatihan Dr. Suriah, SKM, MKes
Indra Fajarwati Ibnu, SKM, MA
III. Hasil dan Pembahasan
Proses
Mahasiswa yang menjadi peserta perlatihan ini merupakan mahasiswa kesehatan tingkat
akhir yang telah lulus mata kuliah metode penelitian kualitatif dan telah memiliki topik penelitian
yang menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk dapat menjadi peserta perlatihan, mahasiswa
52 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
melalui beberapa seleksi yaitu; seleksi topik penelitian, memperhatikan persetujuan pembimbing
atas topik mahasiswa, dan pre-test pengetahuan dasar mengenai metode penelitian kualitatif.
Perlatihan diawali dengan memberi pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep
dasar dan karakteristik penelitian kualitatif, pemahaman ini menjadi acuan bagi peserta perlatihan
dalam menyusun dan mengembangkan masalah penelitian dengan pendekatan kualitatif. Setelah
menentukan dan mengembangkan masalah kualitatif, selanjutnya mahasiswa dipandu agar mampu
memilih desain kualitatif yang tepat sesuai dengan masalah penelitiannya. Beberapa desain yang
dimaksud seperti; studi kasus, fenomenologi, etnografi, grounded theory dan biografi.
Berdasarkan pengembangan desain penelitian dan kerangka penelitian yang telah yang
disusun, peserta penelitian kemudian diarahkan menyusun instrumen dan menentukan metode
pengumpulan data kualitatif, beberapa metode pengumpulan data yang dimaksudkan antara lain;
wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi kelompok terarah atau focus group discussion
dan pengamatan atau observasi. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan kemampuan
menganalisis data kualitatif. Untuk kebutuhan sesi ini peserta perlatihan melakukan kunjungan
lapangan, kemudian data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis data kualitatif
seperti; analisis domain, taksonomi, content analysis, tema kultural dan analisis komparasi.
Tahapan analisis data kualitatif yang disampaikan kepada peserta latihan yaitu; menyusun data
dalam bentuk transkrip, mereduksi data menjadi rangkaian inti (melakukan abstraksi data),
membuat matriks untuk menentukan pola atau kategorisasi data kualitatif dan melakukan
interpretasi data.
Dibagian akhir perlatihan, mahasiswa dipandu menyusun proposal penelitian lengkap
kemudian mereka mempresentasikannya dihadapan fasilitator dan narasumber perlatihan. Proposal
kualitatif yang telah disusun mahasiswa selanjutnya mendapatkan masukan dan perbaikan dari tim
fasilitator dan narasumber, dan diharapkan direvisi untuk kemudian menjadi peroposal penelitian
hasil perlatihan yang siap diajukan ke sidang seminar proposal mahasiswa.
Metode
Beberapa metode yang digunakan dalam kegiatan perlatihan antara lain: ceramah,
diskusi, studi kasus, simulasi, belajar lapangan dan presentasi. Semua materi disampaikan dengan
metode ceramah yang dipadukan dengan metode pembelajaran lainnya seperti diskusi, studi kasus
dan simulasi, kecuali untuk sesi presentasi proposal. Untuk materi konsep dasar penelitian
kualitatif, penentuan masalah dan jenis-jenis desain kualitatif selalu disertai dengan diskusi dan
studi kasus, agar dapat menajamkan pemahaman peserta perlatihan mengenai pendekatan
kualitatif. Pada sesi metode pengumpulan data dan menyusun instrumen, peserta perlatihan diajak
melakukan kunjungan lapangan agar dapat menerapkan langsung teknik pengumpulan data
kualitatif, seperti wawancara dan FGD dan observasi. Sedangkan untuk materi analisis data
kualitatif ditambahkan metode simulasi, agar mahasiswa mampu mempraktikkan cara analisis data
kualitatif dengan tepat.
Pada bagian akhir perlatihan, metode yang digunakan adalah presentasi dan diskusi.
Mahasiswa membuat presentasi dan menyampaikannya dihadapan narasumber, kemudian
masukan dan perbaikan dari narasumber terhadap proposal yang disajikan didiskusikan bersama
peserta perlatihan. Keseluruhan metode yang digunakan dalam penelitian diharapkan dapat
membantu perserta perlatihan lebih memahami dan terampil dalam menggunakan metode
penelitian kualitatif sebagai pendekatan yang digunakan dalam menyusun proposal penelitiannya.
Evaluasi Kegiatan
Evaluasi yang dinilai dari keberhasilan kegiatan perlatihan yaitu melalui evaluasi
pengetahuan peserta perlatihan berkenaan dengan metode penelitian kualitatif. Nilai skor
pengetahuan sebelum dan setelah perlatihan dapat dilihat pada tabel berikut:
53 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Tabel 1. Nilai Pre dan Post Test Peserta Perlatihan
No Kode Nilai Pre test Nilai Post test Total Nilai Akhir
1 JK 78 93 171 85.5
2 AKG 78 94 172 86
3 RFH 77 90 167 83.5
4 MIA 76 91 167 83.5
5 HS 75 95 170 85
6 MAM 72 87 159 79.5
7 MA 72 85 157 78.5
8 EV 70 85 155 77.5
9 MT 68 80 148 74
10 AMW 65 75 140 70
11 SK 76 91 167 83.5
12 MAL 72 89 161 80
13 AP 78 90 168 84
14 RW 76 91 167 83.5
15 OC 75 90 165 82
16 NF 72 85 157 78.5
No Kode Nilai Pre test Nilai Post test Total Nilai Akhir
17 RUM 77 85 162 80.5
18 SW 73 85 158 79
19 NN 66 80 146 73
20 SWY 68 80 148 74
54 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Berdasarkan data pada tabel 1 nampak bahwa dari 20 peserta perlatihan, rata-rata skor
akhir peserta meningkat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perlatihan metode kualitatif
yang diberikan kepada mahasiswa kesehatan selama tiga hari dengan berbagai metode
pembelajaran, dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang metode penelitian kualitatif.
IV. Simpulan dan Saran
Berdasarkan pencapaian hasil kegiatan, maka simpulannya sebagai berikut: terjadi
peningkatan pengetahuan mahasiswa tentang metode penelitian kualitatif yang dinilai dari hasi pre
dan post test perlatihan, mahasiswa mampu melakukan probing dan FGD, menyusun proposal dan
melakukan analisis serta interpretasi data kualitatif. Dengan demikian disarankan agar pihak
Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas agar mereplikasi kegiatan sejenis dan dibuat berkelanjutan
sehingga semua mahasiswa kesehatan dapat memiliki keterampilan dalam menulis proposal
kualitatif dan menyajikan hasil penelitiannya.
Daftar Pustaka
Blumer, H. (1986). Symbolic interactionism (Perspective and method). Berkeley: University of
California Press.
Bryman, A., & Burgess, R.G. (Ed) (1999). Qualitative research (Vols I-IV). London: SAGE
Publications.
Emzir, (2010). Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Faisal, S. (1990). Penelitian kualitatif (dasar-dasar dan aplikasi). Malang: YA3.
Flick, U. (2002). An introduction to qualitative research (2nd ed). London: SAGE Publications.
Kemenkes RI. (2000). Prosedur penilaian cepat (rapid assessment procedures). Jakarta: Pusat
Data Kesehatan Kemenkes RI.
Miles, J.M., & Huberman, A.M., (1992). Analisis data kualitatif. Jakarta: UI Press. Penerjemah:
Tjetjep Rohendi Rohidi.
Morse, J.M., & Field, P.A. (1995). Qualitative research methods for health professionals (2nd ed).
London: SAGE Publications.
Murti, B. (2006). Desain dan ukuran sampel untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif di bidang
kesehatan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Nasution, (1992). Metode penelitian naturalistik kualitatif. Bandung: Tarsito.
Saryono., & Anggraeni, M.D. (2011). Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan.
Yogyakarta: Nuha Medika.
Satori, D., & Komariah, A. (2011). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Spradley, J.P. (1997). Metode etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
Sugiyono, (2010). Memahami penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta.
Taylor, S.J., & Bodgan, R. (1984). Introduction to qualitative research methods (2nd ed). New
York: A Wiley-Interscience Publication.
UI. (1991). Perlatihan metode penelitian kualitatif. Depok: PUSKA UI.
USAID. (1994). Buku petunjuk memandu diskusi kelompok terarah. Washington DC: USAID.
Yin, R.K., (2000). Studi kasus (Desain dan metode). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
WHO. (1994). Qualitative research methods for health programmes. Geneva: Division of Mental
Health WHO.
55 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
PERILAKU PETUGAS DALAM PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK DI RSUP. Dr.
WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSSAR
Masniati1, Mappeaty Nyorong2, Alimin Maidin3
1
Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Selatan
2
Jurusan Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Hasanuddin
3
JurusanManajemen Administrasi Rumah sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas
Hasanuddin
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis perilaku petugas dalam pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok di RSUP Dr. wahidin Sudirohusoda Makassar.Peneltian ini bersifat kualitatif
melalui pendekatan fenomenologi. Informan peneltian adalah petugas rumah sakit yangdiambil
melalui metode snowball sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data
(emik), interpretasi (etik), dan penarikan kesimpulan dari intisari wawancara. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa petugas menyadari perilaku merokok merupakan perilaku yang berbahaya
bagi kesehatan manusia, tetapi masih mempertahankan perilaku merokok dengan alas an-alasan
tertentu. Alasan-alasan yang mendasari perilaku merokok adalah menghilangkan stress akibat
beban kerja yang banyak, relaksasi, dan lebih berkonsentrasi dalam bekerja. Petugas rumah sakit
masih merokok dalam lingkungan rumah sakit. Petugas rumah sakit belum mendapatkan
dukungan untuk menghentikan ketergantungan terhadap rokok karena RSUP Dr. Wahidin
Sudirohusodo belum memiliki layanan poli terapi berhenti merokok.
Kata Kunci : Perilaku merokok. Petugas, Kawasan Tanpa Rokok.
ABSTRACT
The aim of the research was to analyze the behavior of apparatus in the implementation
of non-smoking area (KTR) at RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar.The research
employed a qualitative design with phenomenology approach. Informers were the apparatus of the
hospital selected with snowballsampling method. Data was collected by indepth interview,
observation and documentation. Data analysis was coducted through stages of data collection,
reduction, interpretation, drawing conclusion, and summary of interview. The results of the
research indicated that the apparatus were aware that smoking was a dangerous habit for health,
but they still keep their smoking habit with reasons such as: overcoming stress from exessive work
load, relaxation, more concentration in work, and they also keep smoking in the hospital
environment. They had not received any support to get rid of smoking addiction because the RSUP
Wahidin Sudirohusodo has not had any politheraphy service to quit smoking.
Keywords: Smoking habit.apparatus, non-smoking area.
PENDAHULUAN
K ebiasaan merokok dianggap dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok,
namun di lain pihak merokok juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi si
perokok sendiri maupun orang di sekitarnya. Isteri atau suami dan anak-anak
akan menjadi korban bagi si perokok yang selalu merokok dalam rumah. Berbagai kandungan zat
yang terdapat di dalam rokok memberikan dampak negatif bagi tubuh penghisapnya. Sebuah
laporan yang di rilis World Health Organization (WHO, 2008) pada awal tahun 2008
memperkirakan bahwa 1 miliar orang di seluruh dunia akan meninggal akibat rokok apabila
56 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
pemerintah di berbagai negara tidak serius dalam mengatasi kondisi epidemik terhadap
penggunaan tembakau.
Indonesia, menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 dan 2010,
terjadi kecenderungan peningkatan umur mulai merokok pada usia lebih muda. Data Riskesdas
2010 menunjukkan, umur pertama kali merokok pada usia 5 - 9 tahun sebesar 1,7 persen, usia 10 -
14 tahun sebesar 17,5 persen, usia 15 - 19 tahun sebesar 43 persen, usia 20 - 24 tahun sebesar 14,6
persen, 25 - 29 tahun sebesar 4,3 persen dan usia 30 tahun ke atas sebesar 3,9 persen.
Sulawesi Selatan, berdasar hasil riskesdas tahun 2010 di atas, bahwa prevalensi perokok
sebesar 31,6 persen. Sedangkan konsumsi rokok 1 - 10 batang per hari sebesar 47,3 persen,
konsumsi rokok 11 - 20 batang per hari sebesar 46,0 persen, konsumsi rokok 21 - 30 batang per
hari sebesar 2,0 persen, dan lebih dari 31 batang perhari sebesar 4,6 persen.
Menurut Ngatimin (2005), merokok merupakan lifestyle yang menantang program
hidup sehat, apalagi jika dilakukan oleh petugas kesehatan. Merokok tidak dapat di atasi dengan
larangan, tetapi harus diciptakan kesadaran kepada yang bersangkutan untuk berhenti merokok
atas kemauan sendiri.Hal ini sangat beralasan, karena dengan aturan yang sangat ketatpun kalau
tidak dibarengi dengan pengendalian diri dari yang bersangkutan maka sulit menghilangkannya.
Menurut Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 rumah sakit adalah institusi pelayanan
kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit sebagai sebagai
tempat pelayanan kesehatan berkewajiban memberlakukan lingkungan rumah sakit sebagai
kawasan tanpa rokok. Tujuannya adalah melindungi masyarakat dengan memastikan bahwa
tempat-tempat umum bebas asap rokok. Kawasan tanpa asap rokok harus menjadi norma, terdapat
empat alasan kuat untuk mengembangkan kawasan tanpa rokok, yaitu untuk melindungi anak-anak
dan bukan perokok dari risiko terhadap kesehatan, mencegah rasa tidak nyaman, bau dan kotoran
dari ruang rokok, untuk mengembangkan opini bahwa tidak merokok adalah perilaku yang lebih
normal dan kawasan tanpa rokok mengurangi secara bermakna konsumsi rokok dengan
menciptakan lingkungan yang mendorong perokok untuk berhenti atau yang terus merokok untuk
mengurangi konsumsi rokoknya.
RSUP.Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah menerapkan larangan merokok
dalam lingkungan rumah sakit yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi RSUP.Dr.
Wahidin Sudirohusodo No.HK. 05. 09. 01. 1640, tapi kenyataannya masih terlihat dengan kasat
mata adanya petugas rumah sakit yang merokok dilingkungan rumah sakit.Dengan demikian
penelitian ini ditujukan menganalisis perilaku merokok petugas terhadap pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar.
BAHAN DAN METODE
Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo
Makassar, mengingat di rumah sakit tersebut sudah menerapkan aturan Kawasan Tanpa Rokok di
lingkungan rumah sakit.
Desain Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan
fenomenologi.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban atau informasi yang mendalam
tentang pendapat dan perasaan seseorang yang memungkinkan untuk mendapat hal-hal yang
tersirat tentang sikap, kepercayaan, motivasi dan perilaku individu (Polit & Hungler 2001).
Pemilihan InformanPenelitian
Informan dalam penelitian ini sebanyak 11 orang, dengan karakteristik petugas rumah
sakit yang merokok, dan bersedia menjadi informan penelitian. Menggunakan tehnik snowball
sampling.
Pengumpulan Data
57 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian
kualitatif pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumen.Atas
dasar konsep tersebut, maka ketiga teknik pengumpulan data diatas digunakan dalam penelitian
ini.
Analisis Data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti petunjuk Miles &
Huberman (dalam Sugiyono:2010), yakni dilakukan melalui 3 alur sebagai berikut: 1.Reduksi
Data, 2. Penyajian data, 3.Penarikan kesimpulan
HASIL DAN PEMBAHASAN
Dari hasil penelitian yang diperoleh di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo perilaku
petugas dalam pelaksanaan kawasan tanpa rokok dibahas secara sistematis sebagai berikut:
Tahapan Persiapan Perilaku Merokok
Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan menunjukkan bahwa dalam
tahap persiapan perilaku merokok seseorang belum mencoba rokok, Perkembangan sikap yang
positif melihat orangtua yang merokok, kakak yang merokok,teman sebaya yang merokok serta
tayangan iklan rokok memberikan gambaran yang menyenangkan tentang rokok.
Salah satu faktor lingkungan penting yang memengaruhi seseorang untuk mendapatkan
informasi tentang rokok adalah dari iklan.Iklan-iklan merokok digambarkan sebagai lambang
kejantanan, kematangan, kedewasaan dan bahkan lambang popularitas. Iklan yang menyesatkan,
antara lain yang menghubungkan rokok dengan kejantanan, dunia glamour, olahraga dan
sebagainya.
Tahap Permulaan Perilaku Merokok
Tahap permulaan perilaku merokok, tahap ini juga disebut tahap perintisan, yaitu tahap
apakah seseorang akan meneruskan atau tidak terhadap perilaku merokok. Reaksi negatif terhadap
rokok seperti rasa rokok yang tajam dan panas merupakan faktor yang menyebabkan seseorang
untuk tidak meneruskan perilaku merokok.
Kebanyakan dari remaja mengacuhkan rasa ini dan meneruskan perilaku merokok
mereka.
Saat pertama kali mengkonsumsi rokok, gejala-gejala yang mungkin terjadi adalah
batuk-batuk, lidah terasa bergetir, terasa hambar dan perut terasa mual.
Hal ini terjadi karena zat rokok berupa racun yang ditolak oleh tubuh. Namun
penolakan ini lambat laun akan berubah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi jika merokok
tetap dilanjutkan. Hal ini terjadi karena saraf-saraf akan semakin toleran terhadap racun yang terus
menerus masuk ke dalam tubuh.
Teman sebaya adalah tempat eksperimen pertama yang memungkinkan perilaku untuk
mencoba merokok.Sebuah studi oleh Leventhal dkk (1967) menemukan bahwa umumnya anak
muda mencoba rokok pertama mereka pada saat bersama dengan teman-teman sebayanya dan
disertai dengan dukungan dari teman-teman tersebut.
Punya teman-teman yang merokok merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi
setiap remaja untuk memulai merokok.Sekitar 75% pengalaman mengisap rokok pertama pada
remaja dilakukan bersama teman-temannya (Yusuf LN, 2004). Hasil penelitian di salah SMP
Negeri di Makassar menunjukkan 64,4% responden mempunyai teman perokok dan 52,2%
diantaranya sering ditawari rokok (Rahmat, 2007).
Sesuai dengan penelitian Iqbal (2008) di Depok menemukan 59,8% remaja menyatakan
pernah merokok. Diantara responden kurang dari 10 tahun. 34,4% pada usia 10 - 15 tahun, 53,1%
pada usia 16-20 dan 4,7% pada usia lebih dari 20 tahun.
Penelitian ini sejalan dengan hasil Riskesdas 2010, prevalensi menurut umur pertama
merokok untuk Sulawesi Selatan 5 - 9 tahun 2,1%, 10 - 14 tahun 21,7%, 15 - 19 tahun 41,1%, 20 -
24 tahun 13,44%, 25 - 29 tahun 3,9% dan lebih dari 30 tahun 3,4%.
58 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Dalam penelitian Komalasari dan Helmi menemukan bahwa teman sebaya mempunyai
peran yang sangat berarti bagi remaja, karena masa remaja tersebut remaja mulai memisahkan diri
dari orang tua dan mulai bergabung pada kelompok sebaya. Kebutuhan untuk diterima seringkali
membuat remaja berbuat apa saja agar dapat di terima kelompoknya dan terbebas dari sebutan
“pengecut” dan “banci”.
Seperti yang dikemukakan oleh Abu Al-Ghifari (2003), alasan remaja laki-laki merokok
adalah mereka membayangkan bahwa dengan merokok maka merekan dianggap sudah dewasa,
tidak lagi anak kecil, dan bisa memasuki kelompok teman sebaya sekaligus kelompok yang
mempunyai ciri gaya tertentu yaitu merokok. Alasan utama lainnya remaja merokok adalah karena
ajakan atau paksaan teman atau pengaruh teman atau pengaruh lingkungan yang sukar
ditolak.Bergabung dengan suatu kelompok tertentu bagi remaja masa kini mungkin merupakan hal
yang penting, remaja ingin diidentifikasikan sebanyak mungkin dengan teman-teman sebaya
mereka.
Tahap Menjadi Seorang Perokok
Oskamp (1984) mengatakan bahwa seseorang menjadi perokok apabila orang tersebut
telah mengkonsumsi rokok sebanyak 4 batang per hari.
Hasil analisis analisis data di peroleh bahwa tingkat konsumsi rokok sampai 4 batang
per hari setelah mereka mempunyai penghasilan sendiri, sehingga mampu membeli rokok dengan
uangnya sendiri, serta ketersediaan dan harga rokok yang terjangkau.
Tahap Mempertahankan Perilaku Merokok
Tahap mempertahankan perilaku merokok merupakan tahap akhir, ketika faktor
psikologis dan mekanisme biologis menyatu agar perilaku merokok dipelajari terus-menerus.
Penelitian menemukan berbagai variasi alasan psikologis untuk terus merokok diantaranya
adalah: kebiasaan, ketergantungan, penurunan kecemasan, relaksasi, pergaulan dan social reward,
Stimulasi dan keterbangkitan (arousal).
Sesuai hasil analisis data diperoleh bahwa mempertahankan perilaku merokok karena
tingkat kecanduan terhadap nikotin.Nikotin merupakan zat kimia utama dalam rokok yang
menyebabkan orang menderita ketergantungan rokok. Setelah menghisap rokok, kadar nikotin
dalam darah meningkat tajam dalam 11 hingga 15 detik. Bolus nikotin ini kemudian akan
mengaktifkan suatu sistem yang disebut brain reward system dengan cara melepaskan dopamin.
Nikotin dari rokok secara langsung merangsang reseptor asetilkolin pada neuron yang berisi
dopamin.Stimulasi reseptor asetilkolin inilah yang menyebabkan timbunan dopamin di pusat
brain-reward sistem.Aktivasi brain-reward sistem menimbulkan perasaan senang, seperti yang
ditimbulkan oleh aktivitas seksual atau makan.Kadar puncak nikotin, aktivasi brain-reward sistem
yang sementara, diikuti dengan turunnya kadar nikotin secara bertahap, sampai pada suatu titik
withdrawal yang hanya dapat dihilangkan dengan menghisap rokok selanjutnya. Jadi,
ketergantungan timbul dari hubungan temporal antara ritual menghisap rokok dan input sensorik
dengan stimulasi berulang dan hilangnya gejala withdrawal.
Ketergantungan ini dipersepsikan sebagai kenikmatan yang memberikan kepuasan
psikologis.Gejala ini dapat dijelaskan dari konsep tobacco dependence (ketergantungan
rokok).Artinya, perilaku merokok merupakan perilaku yang menyenangkan dan bergeser menjadi
aktivitas yang obsesif. Secara manusiawi, orang cenderung menghindari ketidakseimbangan dan
lebih senang mempertahankan apa yang selama ini dirasakan sebagai kenikmatan sehingga dapat
dipahami jika para perokok sulit untuk berhenti merokok.
Klinke & Meeker (dalam Aritonang, 1997) bahwa motif para perokok adalah
relaksasi.Dengan merokok dapat mengurangi ketegangan, memudahkan konsentrasi dan
pengalaman yang menyenangkan.
Banyak alasan yang lain yang menjadi pembenaran yang irrasional dalam
mempertahankan perilaku merokok mereka. Selain faktor adiktif dalam rokok, kebiasaan merokok
dipicu oleh kondisi lingkungan yang mayoritas perokok.Lingkungan yang mayoritas perokok ini
59 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
cenderung menciptakan kondisi dimana sulitnya menolak rokok yang ditawarkan rekan-rekan
perokok lainnya, sehingga mereka pun tetap merokok.
Kebiasaan merokok bukan sekedar masalah ketergantungan nikotin tetapi menyangkut
masalah behavior. Gerak merokok ibarat semacam ritual yang dimulai membuka bungkus rokok,
diikuti dengan menyalakan api, lalu mulai menghisap rokok. Tidak mudah untuk meminta
seseorang menghentikan sesuatu yang merupakan ritual sehari-harinya.
Upaya Untuk Berhenti Merokok
Menghentikan perilaku merokok bukanlah usaha mudah, terlebih lagi bagi perokok di
Indonesia. Hasil survei yang dilakukan LM3 (Lembaga Menanggulangi Masalah Merokok), dari
375 responden yang dinyatakan 66,2% perokok pernah mencoba berhenti merokok, tetapi mereka
gagal. Kegagalan ini ada berbagai macam: 42,9% tidak tahu caranya, 25,7% sulit berkonsentrasi
dan 2,9% terikat oleh sponsor rokok (Fawzani dan Triratnawati, 2005).
Hasil analisis data diperoleh bahwa petugas yang yang merokok pernah berhenti
merokok karena alasan penyakit tertentu bukan bantuan terapi atau pengobatan, tapi upaya itu
sangat disayangkan karena gagal akhirnya kambuh lagi untuk merokok.Karena merokok adalah
suatu adiksi (kecanduan).Otak seorang perokok membutuhkan nikotin lebih dan lebih lagi agar
dapat berkonsentrasi dengan baik.Ketika tidak ada asupan nikotin dari rokok (karena perokok
berhenti mendadak), gejala putus nikotin bisa terjadi, dan dibutuhkan kesabaran dan motivasi yang
sangat kuat untuk melawannya.
Keinginan untuk terus merokok disebabkan karena kuatnya ketergantungan terhadap
nikotin. Dibutuhkan kemauan yang kuat dan bantuan medik.
RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo sampai saat ini belum tersedia layanan poli terapi
berhenti merokok, maka dianggap sangat penting untuk smenyediakan layanan poli terapi berhenti
merokok dan Bimbingan Konseling bagi perokok, mengingat perilaku merokok para petugas
sudah berlangsung lama dan bersifat adiktif sehingga petugas yang merokok dapat terlepas dari zat
adiktif nikotin tersebut.
Hambatan-hambatan yang dihadapi untuk berhenti merokok.Dari pernyataan informan
dari hasil wawancara mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi informan dalam upaya
berhenti merokok adalah pengaruh dari lingkungan teman-teman kantor yang merokok,
tersedianya rokok dengan mudah di beli dengan harga terjangkau.
Sikap
Sikap merupakan respon yang masih tertutup terhadap suatu obyek.Sikap belum
merupakan suatu tindakan atau aktivitas tetapi merupakan predisposisi dari perilaku.
Sikap merupakan kecenderungan untuk bereaksi secara positif (menerima) ataupun
negatif terhadap suatu obyek.Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu obyek di
lingkungan tertentu sebagai penghayatan terhadap obyek.
Hasil analisis data diperoleh dari pernyataan sikap dari para perokok menyatakan bahwa
merokok berbahaya bagi kesehatan mereka, tapi pernyataan sikap tersebut masih diikuti dengan
perilaku merokok.Hal ini disebabkan ketergantungan yang dipersepsikan sebagai kenikmatan yang
memberikan kepuasan psikologis dan menjadi perilaku yang menyenangkan.
Pada dasarnya merokok sudah disadari sebagai perilaku yang buruk.Namun keinginan
tersebut terus mengikuti seseorang yang sudah pernah merokok.Hal ini disebabkan zat adiktif yang
terdapat dalam rokok yang menyebabkan kecanduan.Untuk menghilangkan kebiasaan itu
dibutuhkan tekad yang dari perokok tersebut.Pengendalian diri merupakan jawaban yang tepat atas
persoalan ini.Apapun teorinya, intinya pengendalian diri.
Peraturan Tentang Larangan Merokok
RSUP.Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sudah menerapkan peraturan tentang
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) mulai tahun 2007.Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah
disosialisasikan kepada seluruh petugas dengan pemasangan tanda himbauan tentang larangan
merokok di kawasan rumah sakit.Hal ini dimaksudkan agar sebagai institusi pelayanan kesehatan
dapat memberi contoh yang baik sekaligus wujud konsistensi untuk memerangi perilaku yang
60 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
tidak sehat tersebut.Hal ini memang sudah menjadi aturan bahwa setiap pegawai di lingkungan
rumah sakit di larang merokok dalam lingkungan rumah sakit.
Observasi yang dilakukan di rumah sakit ini menunjukkan pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok (KTR) ini belum optimal.Berdasarkan catatan lapangan, kami menemukan fakta bahwa
kegiatan merokok dapat dilakukan diberbagai tempat seperti kantin.Beberapa dokumentasi dalam
bentuk foto ditemukan orang-orang yang merokok ditempat-tempat yang disebutkan di atas.Selain
di kantin, merokok juga sering dilakukan di ruangan kerja. Bukan hanya pada saat jam istirahat,
tetapi juga pada saat jam kerja. Hal ini kami temukan pada salah satu informan, yang pada saat
wawancara berlangsung peneliti menjadi perokok pasif.
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di RSUP. DR. Wahidin Sudirohusodo
merupakan salah satu cara untuk mengurangi jumlah perokok dan menghindari perokok pemula
bagi petugas khususnya serta pengguna rumah sakit lainnya (pasien, penjaga pasien dan
pengunjung rumah sakit), meski pelaksanaan aturan ini belum maksimal.
Teguran lisan dianggap kurang efektif dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok di
Rumah Sakit, tidak memberikan efek jera buat petugas yang merokok. Pihak rumah sakit
diharapkan berperan penting dalam pengawasan KTR ini, untuk mencapai hasil yang optimal,
menciptakan lingkungan rumah sakit bebas asap rokok.
Pelaksanaan Kawasan Tanpa rokok (KTR) harusnya bersifat menyeluruh, untuk semua
pengguna rumah sakit: pengunjung, pasien, penjaga pasien dan pengguna rumah sakit lainnya.
Diharapkan esensi dari pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dirumah sakit ini
adalah bukan semata pemasangan tanda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), tapi lebih mendalam lagi
bagaimana mencarikan solusi bagi perokok dari upaya berhenti merokok.
Lingkungan
Ada banyak alasan yang melatarbelakangi perilaku merokok.Secara umum menurut
Kurt Lewin perilaku merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu.Artinya perilaku
merokok selain disebabkan faktor-faktor dalam diri, juga disebabkan oleh faktor lingkungan
(Helmi dan Komalasari).
Permulaan untuk merokok terjadi pengaruh lingkungan sosial. Modeling (meniru
perilaku orang lain) menjadi salah satu determinan dalam memulai perilaku merokok. Perilaku
merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu, artinya perilaku merokok selain
disebabkan faktor dalam diri (seperti perilaku memberontak dan suka mengambil resiko) dan
faktor lingkungan (seperti orang tua yang merokok dan teman sebaya yang merokok).
Penyebab lingkungan yang mempengaruhi perilaku merokok adalah:
Pengaruh Teman Kerja
Berbagai fakta mengungkapkan bahwa semakin banyak teman merokok maka semakin besar
kemungkinan teman-temannya adalah perokok juga dan demikian sebaliknya.
Faktor Kepribadian
Orang mencoba untuk merokok karenan alasan ingin tahu atau ingin melepaskan diri dari rasa
sakit dan membebaskan diri dari kebosanan.
Pengaruh Iklan
Melihat iklan di media massa dan elektronik yang menampilkan gambaran bahwa perokok adalah
lambang kejantanan atau glamour, membuat orang seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku
seperti yang ada dalam iklan tersebut.
KESIMPULAN DAN SARAN
Perilaku merokok petugas sudah berlangsung lama, dilihat dari tahapan-tahapan
Perilaku merokok petugas sudah berlangsung cukup lama, Ini dapat dilihat dari tahapan perilaku
merokok petugas yang dimulai tahapan inisiasi merokok (tahap mencoba untuk merokok) di mulai
dari usia remaja, berlanjut ketahap menjadi perokok, dan sampai sekarang masih mempertahankan
perilaku merokok, ini berarti bahwa kekuatan nikotin yang sangat kuat yang menyebabkan para
61 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
petugas sulit berhenti merokok.Sikap terhadap perilaku merokok. Para petugas menyadari bahwa
perilaku merokok adalah perilaku yang berbahaya, perilaku yang mubazir, tapi mereka tetap
merokok karena alasan menghilangkan stress,rasa jenuh, setelah selesai beraktivitas.Penerapan
Kawasan Tanpa Roksok (KTR) di RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo belum maksimal. Masih
terdapat perokok pada tempat yang dilarang merokok. Pengawasan terhadap penerapan dan sanksi
bagi pelanggar aturan belum maksimal.
DAFTAR PUSTAKA
Abu Alghifari. (2003). Remaja Korban Mode, Bandung: Mujahid Press.
Aritonang, M. R. (1997). Fenomena Wanita Merokok, Jurnal Psikologi. Universitas Yogyakarta.
Fawzani dan Triatnawati.(2005). Terapi Berhenti Meroko (Studi Kasus 3 Perokok Berat). Jurnal
Makara, 15 – 22.
Iqbal, Muhammmad Fariz.( 2008). Perilaku Merokok Remaja Dilingkungan RW 22 kelurahan
Sukatani Kecamatan Cimanggis Depok Tahun 2008.(Online).
(http://www.digilib.ui.ac.id//opac/themes/libri 2/ detail.jsp?id=123594 & lokasi =
local, diakses 12 Februari 2012).
Ngatimin H. M. Rusli. (2005). Ilmu Perilaku Kesehatan. Yayasan PK-3: Makassar.
Oskamp, S. (1984).Applied Social Psychology.Buckingham: Open University Press.
Polit D. F & Hungler, B. P. (2001). Nursing Research: Principle and Methods 6 th ed
Philedelphia: Lippin Cott Williams & Wilkins.
Rachmat, Muhammad. (2007). Studi Perilaku Merokok Remaja Pada SMP Negeri 8 Makassar
Tahun 2007.Skripsi tidak diterbitkan. Makassar: FKM UNHAS.
Sugiyono.(2010). Metode Penelitian Kuantitaif, Kualitatif dan R & D. Cetakan ke-13. Alfabeta:
Bandung.
Yusuf LN, Syamsu.(2004). Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja. Rosdakarya: Bandung.
62 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
PENGARUH KONSELING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN DAN
SIKAP IBU TENTANG ANTENATAL CARE DI RUMAH SAKIT
KHUSUS DAERAH IBU DAN ANAK SITI FATIMAH MAKASSAR
Mariani 1, Ridwan M. Thaha.2, M. Tahir Abdullah 3
1
Akademi Kebidanan Minasa Upa Makassar
2
Konsentrasi Promosi Kesehatan , Universitas Hasanuddin Makassar
3
Konsentrasi Kesehatan Reroduksi , Fakultas Kesehatan Masyarakat,Universitas Hasanuddin
akassar
ABSTRAK
Antenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk memeriksakan
keadaan ibu dan janinnya secara berkala yang di ikuti dengan pengawasan ante natal. Indonesia
diperkirakan setiap dua jam perempuan mengalami kematian karena hamil atau melahirkan
akibat komplikasi pada masa hamil atau persalinan. Tingginya angka kematian dan kesakitan di
Indonesia maupun di Sulawesi Selatan yang disebabkan oleh beberapa faktor risiko yang tidak
ditunjang dengan pemeriksaan kehamilan secara berkala. Penelitian ini bertujuan mengetahui
adanya pengaruh konseling terhadap pengetahuan dan sikap ibu tentang Antenatal Care di
Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
Jenis Penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen (pre test – post test control group
design). Desain ini melibatkan tiga kelompok subjek. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Sakit
Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar tahun 2012. Sampel ditentukan berdasarkan kriteria inklusi
dengan jumlah sampel sebanyak 90 orang. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji Paired
Sample T Test.
Hasil Penelitian menunjukkan ada pengaruh pre-post non konseling pada kelompok kontrol dan
perlakuan yaitu pengetahuan dengan nilai t (sig.tailed) < 0.05, sikap dengan nila t=0.19 > α
=0.05 yang berarti tidak ada pengaruh, sedangkan pada kelompok perlakuan masing-masing
menunjukkan ada pengaruh dengan nilai t=0.00 < α =0.05. Terjadi peningkatan pengetahuan dan
perubahan sikap sebelum dan sesudah perlakuan.
Penelitian ini menyarankan memberikan konseling yang didukung dengan media dalam
pelayanan dengan itu infomasi yang diberikan dapat diterima atau ditangkap melalui panca indra
dengan jelas sehingga tujuan dari konseling dapat tercapai secara efektif dan efisien.
Kata Kunci : Antenatal Care, Konseling
ABSTRACT
Antenatal care (ANC) is a pregnancy examination performed to check the state of the mother and
fetus are regularly followed by ante natal surveillance. Indonesia is expected every two hours of
women dying due to pregnancy or childbirth due to complications during pregnancy or childbirth.
The high morbidity and mortality in Indonesia and in South Sulawesi caused by several risk
factors that are not supported with regular prenatal care. This study aims to find out the effect of
counseling on knowledge and attitudes about the IBI Antenatal Care in the Hospital for Special
Regional Maternal and Child Siti Fatimah Makassar.
This type of study used was a quasi experiment (pre test - post test control group design). The
design involved three groups of subjects. The research was conducted at the Maternal and Child
Hospital Fatimah Sti Makassar in 2012. Sample is determined based on the inclusion criteria with
63 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
a sample of as many as 90 people. The collected data were analyzed with the test Paired Sample T
Test.
The study results showed no effect of non-pre-post counseling and treatment in the control group,
namely knowledge of the value of t (sig.tailed) <0.05, the attitude of the indigo t = 0.19> α = 0.05
which means no influence, while in each treatment group each menunjukkanada influence the
value of t = 0.00 <α = 0.05. An increase knowledge and change attitudes before and after
treatment.
This study suggests that counseling is supported by the media in the service with information that
can be received or captured through the five senses clearly that the purpose of counseling can be
achieved effectively and efficiently.
Keywords: Antenatal Care, Counselling
PENDAHULUAN
A
ntenatal care (ANC) adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan untuk
memeriksakan keadaan ibu dan janinnya secara berkala yang di ikuti dengan
pengawasan anten atal. Pengawasan ante natal memberikan manfaat dengan
ditemukannya berbagai kelainan yang menyertai kehamilan secara dini sehingga dapat
diperhitungkan dan dipersiapkan langkah-langkah dalam pertolongan persalinan (Sinkim, 2008).
World Health Organitation setiap tahun terjadi 210 juta kehamilan di seluruh dunia. Dari
jumlah ini 20 juta perempuan mengalami kesakitan sebagai akibat kehamilan, sekitar 8 juta
mengalami komplikasi yang mengancam jiwa, dan lebih dari 500.000 meninggal, sebanyak
240.000 dari jumlah ini atau hampir 50% terjadi di negara-negara Asia Selatan dan Tenggara.
Hingga saat ini angka kematian ibu di Indonesia menjadi isu yang sangat serius dan
masih tertinggi di ASEAN. Angka Kematian Ibu di Indonesia tahun 2010 adalah 226/100.000
kelahiran hidup. Dengan perhitungan ini, diperkirakan setiap dua jam perempuan mengalami
kematian karena hamil atau melahirkan akibat komplikasi pada masa hamil atau persalinan.
Bahkan masih jauh dari target Millennium Development Goals (MDGs) untuk menurunkan AKI
di Indonesia sebanyak 125/100.000 kelahiran hidup (Anonim, 2011).
Tingginya angka kematian ibu di Indonesia maupun di Sulawesi Selatan terkait dengan
rendahnya kuliatas berbagai program dalam upaya penurunan AKI yang telah dilaksanakan oleh
pemerintah seperti Safe Motherhood (SM) dengan salah satu pilarnya yaitu antenal care (ANC)
(Anggrita, 2011).
Jumlah kematian ibu di Sulawesi Selatan tahun 2010 sebanyak 121 orang dengan
penyebab terbanyak adalah perdarahan yaitu 63 orang (52.07%), hipertensi dalam kehamilan 28
orang (23.14%), infeksi 1 orang (0.83%), abortus 1 orang (0.83%), partus lama 1 orang (0.83%)
dan penyebab lain 26 orang (21.48%) (Dinkes Sulsel, 2011).
BAHAN DAN METODE
Rancangan penelitian
Rancangan penelitian yang digunakan adalah quasi eksperimen (pre test post tes control
group design), dimana desain ini melibatkan dua kelompok subjek, satu kelompok diberikan
kuesioner pre tes kemudian diberikan konseling kemudian uji post test, dan satu kelompok lainnya
diberikan konseling menggunakan media dan diuji pre tes kemudian dikonseling kembali
menggunakan media dan diuji post test. Dari desain ini efek dari satu perlakuan terhadap variabel
dependen akan diuji dengan cara membandingkan keadaan variabel dependen pada kelompok
eksperimen setelah dikenai perlakukan dengan kelompok kontrol yang tidak dikenai perlakuan.
Lokasi dan Waktu Penelitian
64 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Lokasi penelitian di Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar
karena merupakan Rumah Sakit Pendidikan yang melayani masyarakat dari berbagai golongan.
Waktu penelitian di laksanakan pada bulan April-Mei 2012.
Populasi dan sampel
Populasi merupakan seluruh subyek penelitian atau subyek yang akan diteliti, populasi dalam
penelitian ini adalah semua ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada bulan Maret 2012
sebanyak 300 orang.
Menurut Nursalam, 2010 besar sampel dapat diambil 10-20% dari populasi, sehingga
besar sampel dalam penelitian ini adalah 300 x 10% = 30 sampling sehingga total sampel untuk
tiga kelompok yang berbeda yaitu; Kasus Kontrol sebanyak 30 sampel, Pre-Post Konseling tanpa
Media sebanyak 30 sampel, dan Pre-Post Konseling dengan media sebanyak 30 sampel.
Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrument kuesioner, dan buku
register KIA. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu melalui kuesioner dan data
sekunder yaitu melalui buku register kehamilan maupun data dari Dinas Kesehatan Provinsi
Sulawesi Selatan.
Data yang telah terkumpul kemudia diolah (editing, coding, dan scoring) dan selanjutnya
diolah dengan menggunakan uji Paired Sample t test.
HASIL
Analisis Bivariat
Pengetahuan
Data pada tabel 1 menunjukkan ada perubahan pengetahuan baik pada kelompok kontrol
maupun kelompok perlakukan Berdasarkan uji statistik Paired Sampel Test menunjukkan nilai t
(sig.tailed) < 0.05 yang menunjukkan ada pengaruh pre-post non konseling terhadap pengetahuan
ibu tentang Antenatal Care di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
Sikap
Data pada tabel 2 menunjukkan ada perubahan sikap baik dari kelompok kontrol maupun
kelompok perlakukan. Uji statistik dengan Paired Sampel Test pada kelompok kontrol nilai t =
0.19 > α =0.05 yang berarti tidak ada pengaruh pre-post non konseling terhadap sikap ibu tentang
Antenatal Care di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
Sedangkan pada kelompok perlakukan masing-masing menunjukkan nilai t = 0.00 < α
=0.05 menunjukkan ada pengaruh
pre-post konseling tanpa media dan yang menggunakan media terhadap pengetahuan dan
sikap ibu tentang Antenatal Care di RSKD Ibu dan Anak Siti Fatimah Makassar.
PEMBAHASAN
Adanya perubahan pengetahuan pada ibu hamil walaupun tidak dilakukan intervensi atau
konseling disebabkan karena pengetahuan bukan hanya didapatkan dari pemberian informasi tetapi
dari pengalaman, baik dari pengalaman sendiri maupun orang lain.
Pengetahuan juga dapat diperoleh dari pendidikan seseorang, makin tinggi pendidikan
seseorang maka makin mudah mereka menerima informasi baik informasi dari petugas kesehatan
maupun dari orang yang ada disekitarnya serta pengetahuan dapat juga didapatkan dari
kepercayaan yang merupakan suatu sikap untuk menerima suatu pernyataan atau pendirian tanpa
menunjukkan sikap pro atau atau kepercayaan. Sering diperoleh dari orang tua, kakek atau nenek.
Seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan keyakinan dan tanpa adanya pembuktian
terlebih dahulu. Kepercayaan berkembang dalam masyaralat yang mempunyai tujuan dan
65 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
kepentingan yang sama. Kepercayaan dapat tumbuh bila berulang kali mendapatkan informasi
yang sama (Notoatmodjo, 2005).
Tidak adanya pengaruh pada variabel sikap menunjukkan bahwa sikap walaupun baik
tetapi manifestasi sikap itu tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih
dahulu dari perilaku yang tertutup. Sikap dapat pula terwujud didalam suatu tindakan tergantung
pada situasi pada saat itu.melihat kondisi dan situasi tempat pemeriksaan antenatal di RSKDIA Siti
Fatimah Makssar tidak memilik tempat khusus untuk melakukan konseling,sebab salah satu faktor
penghambat untuk melakukan konseling adalah situasional.
Newcomb seorang ahli psikologis sosial, menyatakan bahwa sikap itu merupakan
kesiapan atau kesediaan untuk bertindak dan bukan merupakan pelaksanaan motif tertentu. Sikap
belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi merupakan predisposisi tindakan suatu
perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi terbuka atau tingkah
laku terbuka.
Hal ini sesuai dengan konsep dasar bahwa konseling adalah pertolongan dalam bentuk
wawancara yang menuntut adanya komunikasi, interaksi yang mendalam, dan usaha bersama
antara konselor (bidan) dengan konseli (klien) untuk mencapai tujuan konseling yang dapat berupa
pemecahan masalah, pemenuhan kebutuhan, ataupun perubahan tingkah laku atau sikap dalam
ruang lingkup pelayanan kebidanan dan orang yang mendapat konseling dapat mengekspresikan
pikiran dan perasaannya dengan cara tertentu sesuai dengan situasi, melalui pengalaman terbaru,
memandang kesulitan lebih objektif sehingga dapat menghadapi masalahnya dengan tidak terlalu
cemas dan tegang.
Setelah klien diberikan konseling diharapkan adanya kemandirian klien dalam hal
peningkatan kemampuan klien dalam upaya mengenal masalah, merumuskan alternatif pemecahan
masalah, dan menilai hasil tindakan secara tepat dan cermat.
Kesuksesan konseling dapat juga dipengaruhi oleh responden atau konseling (orang yang
menerima pesan) sebagaimana yang terlihat pada distrubusi pendidikan sampel yang sebagian
besar SMA (65.6%) sehingga mereka lebih mudah untuk menerima informasi dan motivasi.
Sebagian besar responden juga dengan hamil ke dua artinya sudah ada pengalaman
sebelumnya sehingga pengalaman yang merugikan pada kehamilan pertama kemungkinan besar
akan ditinggalkan dan pengalaman yang menguntungkan itu yang dipertahankan pada kehamilan
berikutnya, seperti pada konsep sebelumnya bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman
baik diri sendiri maupun orang lain sehingga akan mempengaruhi keputusan klien untuk
mengambil keputusan yang menguntungkan bagi diri dan janinnya.
Faktor lain yang menyebabkan konseling dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap
seseorang adalah kesiapan sarana dan prasarana yang mendukung proses konseling seperti,
kemampuan konselor untuk berkomunikasi secara efektif, sederhana, pendek dan langsung, suara
konselor mampu mempengaruhi arti pesan, kecepatan bicara dan tempo bicara yang tepat dan
memberikan dukungan emosional kepada klien (Cristina, 2003).
Agar konseling berjalan efektif, efisien dan terjadi perubahan tingkah laku dari klien
sesuai yang diharapkan konselor perlu kiranya dipersiapkan faktor yang menunjang konseling
seperti , alat KIE, sikap dan penampilan konselor.
Klien yang diberikan konseling menggunakan media akan lebih lama mengingat pesan
yang telah disampaikan, sebagaimana penelitian pelatihan yang berdasarkan kompetensi bahwa
jika pesan disampaikan secara verbal, setelah 3 jam materi tersebut tersisa hanya 25% dan setelah
3 hari materi tersebut hanya tersisa 10-20%, sedangkan jika menggunakan media, setelah 3 jam
materi yang tersisa 80% dan setelah 3 hari materi yang tersisa masih 65%.
66 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Terjadi perubahan pengetahuan sebelum dan sesudah perlakukan baik pada kelompok
perlakuan maupun pada kelompok kontrol. Sedangkan sikap Terjadi perubahan sebelum dan
sesudah perlakukan baik pada kelompok perlakuan maupun pada kelompok kontrol.
Saran
Penelitian ini menyarankan memberikan konseling yang didukung dengan media
dalam pelayanan dengan itu infomasi yang diberikan dapat diterima atau ditangkap melalui panca
indra dengan jelas sehingga tujuan dari konseling dapat tercapai secara efektif dan efisien.
DAFTAR PUSTAKA
Budiarto, 2004, Metode Penelitian Kesehatan, EGC, Jakarta
Cristina L, 2003, Komunikasi dan Konseling Kebidanan, Nuha Medika, Jakarta
Cunningham Gant, 2006, Obstetri Williams, Edisi 21, Jakarta
Dwi asihani,hubungan antara pengetahuan dan sikap ibu hamil tentang antenatal care dengan
kunjungan pemeriksaan kehamilan di Rumah bersalin permata bunda stagen.
dr. Siti Candra, SpOG, Moch. Gatot Heri P, S.Kp, Nur Islami Dewi Hubungan tingkat
pengetahuan dan sikap tentang antenatal care di posyandu wilayah kerja puskesmas
arjowinangun kota malang.Malang
Endeh Trismawati, 2010, Pengaruh Konseling terhadap Tingkat Pengetahuan Ibu tentang ANC, Jurnal
STIKES Insan Unggulan Surabaya
Fakih Hidayat 2010, hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap prilaku kunjungan
pemeriksaan kehamilan, Cirebon.
Kate, 2010, Angka Kematian Ibu Masih Memprihatinkan, online (http://www.korantempo.go.id )
diakses 1 Desember 2011
Kiki Anggrita, 2011, Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keteraturan ANC,
http://www.jurnalskripsi.com online diakses 10 Desember 2011
Monica, RT ,2009 Analisis prilaku ibu hamil terhadap antenatal care pada etnis toraja di
Kabupaten Tana Toraja.Jurnal Promosi Kesehatan,Makassar.
Profil Dinas Kesehatan, 2010, Angka Kematian Ibu, Sulawesi Selatan
Saputra, 2009, Pentingnya Antenatal Care, online (http://www.kuliah bidan,com) diakses 1
Desember 2011
Sriningsih, 2011, hubungan dan pengetahuan dan Bidan tentang penerapan standar antenatal
care dengan jumlah kunjungan ibu hamil dalam pemeriksaan antenatal, Ponegoro.
Yuliani 2010, hubungan pengetahuan dan sikap ibu hamil terhadap prilaku kunjungan
pemeriksaan kehamilan .Jakarta.
67 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Tabel 2. Pengaruh Konseling terhadap Sikap Ibu pada Kelompok Kontrol dan Kelompok
Perlakuan
K.Kontrol Kons.tanpa Media Kons.dgn Media
Sikap
Pre Post Pre Post Pre Post
Baik 17 20 17 23 13 20
Kurang 13 10 13 7 17 10
Jumlah 30 30 30 30 30 30
α = 0.05 0.19 0.00 0.00
Sumber : Data Primer, 2012
Tabel 1. Pengaruh Konseling terhadap Pengetahuan Ibu pada Kelompok Kontrol dan Kelompok
Perlakuan
K.Kontrol Kons.tanpa Media Kons.dgn Media
Pengetahuan
Pre Post Pre Post Pre Post
Baik 19 25 13 20 23 27
Sedang 11 5 16 10 7 3
Kurang 0 0 1 0 0 0
Jumlah 30 30 30 30 30 30
α = 0.05 0.03 0.00 0.00
Sumber : Data Primer, 2012
68 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
ADVOCACY CONCEPT IMPLEMENTATION OF MALARIA CONTROL POLICY IN
ALOR DISTRICT HEALTH OFFICE OF EAST NUSA TENGGARA
PROVINCE YEAR 2009
Moh. Tupong Effendi, Ridwan M. Taha and Muh. Syafar
Abstract
This study aims to determine the implementation of health policy advocacy undertaken by the
Department of Health to policy makers in the district. Alor in an effort to control malaria in Alor
regency in the year 2009.
This study was qualitative case study approach. District health department heads. Alor, head of
health promotion, head of P2M and health workers who are in health promotion and P2M District
Health Office. Alor. In this research, which became another informant is a regional-level policy
makers, including Legislator (Commission C) and the Local Government (Pemda). information
was collected through in-depth interviews (depth interview).
Results showed that 1) Advocacy has been done by the district health office. Alor, using strategies
menyampikan programs directly to Parliament, in its achievement of increasing the budget from
year to year does not happen. This condition is caused by parliament has not wage his perception
as a result of the implementation of advocacy. 2) From the advocacy carried out with the result
that a political commitment from the government and the parliament that will continue to support
malaria control efforts undertaken by the health department, but the lack of escorts is either done
by the health department of commitment and policy, not realized. Support policy for malaria
pengedalian programs are only recommendations and can not be used as the impetus that allows
for implementation of malaria control programs in every sector. 3) Efforts to build a support
system, social support and community empowerment is only carried out in accordance with the
official program, and not supported by the device are expected to direct the attention of policy-
related elements. There is only the Village District and other government agencies who try to enter
the program at their respective work areas, but not well realized.
The health department recommended that carefully built strategy in advocating that advocacy
goals can be achieved. Efforts to securing the commitment must be made by the health department
until the application process. Consistency of local government and parliament in the realization of
the policy must be maintained, because it became a separate benchmarks for the implementation
of malaria control programs in the district. Alor.
Keywords : Implementation of the concept of advocacy for malaria control policy.
Pendauluan
Paradigma Pembangunan kesehatan yang menekankan upaya promotif dan preventif
sebagai mainstream program kesehatan merupakan sebuah pergeseran paradigma yang signifikan
akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal tersebut disebabkan pendekatan promotif
lebih berorientasi untuk meningkatkan kesadaran untuk membentuk dan membangun masyarakat
yang sehat secara mandiri dengan memanfaatkan potensi lokal masyarakat sendiri, hal ini berarti
kemampuan masyarakat untuk mengelolah masalahnya adalah menjadi sangat penting dengan
pendekatan dan strategi promosi kesehatan berupa advokasi, kemitraan, dan pemberdayaan
masyarakat (WHO 1984) .
Dalam upaya kesehatan promotif dan preventif, peningkatan derajat kesehatan melalui
upaya promosi kesehatan diharapkan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kondisi
kesehatan masyarakat, kendatipun demikian upaya promosi kesehatan yang meliputi advokasi,
bina suasana, dan pemberdayaan masyarakat telah dilalakukan namun hasil yang diperoleh justru
belum menunjukan hasil yang maksimal. Hal ini masih berhubungan dengan tingkat akurasi dan
kebutuhan masyarakat terhadap program yang dilakukan.
69 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Banyaknya penyakit yang kian merebak untuk saat ini dan dimasa-masa mendatang
khusnya malaria, merupakan penyakit yang perkembangannya hampir tidak mampu diatasi oleh
masyarakat dan provider kesehatan masyarakat.
Penyakit malaria merupakan penyakit menular disebabkan oleh Plasmodium (Klas
Sporozoa) yang menyerang sel darah merah. Di Indonesia dikenal 4 (empat) macam spesies parasit
malaria yaitu P. vivax sebagai penyebab malaria tertiana, P. falciparum sebagai penyebab malaria
tropika yang sering menyebabkan malaria otak dengan kematian, P. malariae sebagai penyebab
malaria quartana, P.ovale sebagai penyebab malaria ovale yang sudah sangat jarang ditemukan
(Depkes RI, 1999; Depkes RI, 2000).
Faktor kesehatan lingkungan fisik, kimia, biologis, dan sosial budaya sangat berpengaruh
terhadap penyebaran penyakit malaria di Indonesia (Harijanto, 2000). Kemampuan bertahannya
penyakit malaria disuatu daerah ditentukan oleh berbagai faktor yang meliputi adanya parasit
malaria, nyamuk Anopheles, manusia yang rentan terhadap infeksi malaria, lingkungan dan iklim
(Prabowo, 2004).
Dari data yang diperoleh, maka terlihat bahwa di Nusa Tenggara Timur (NTT), malaria
telah menjadi penyakit endemis yang merata di seluruh kabupaten. Khusus untuk Kabupaten Alor,
pada tahun 2008-2009 kasus malaria merupakan kejadian penyakit yang menempati urutan kedua
dari 18 kasus setelah penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang menyerang semua
umur. Kejadian malaria untuk Kabupaten Alor mencapai 17,65%, dari jumlah penduduk
Kabupaten Alor sebesar 152.542 (Data malaria Dinkes Kabupaten Alor, 2008).
Hasil penelitian menunjukkan persentase rata-rata kejadian malaria yang tersebar diseluruh
Kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Alor, dan persisnya bahwa malaria sering berganti
posisi dengan ISPA diurutan 1 dan 2 pada prevalensi kejadian penyakit. Dengan kodisi yang ada
kemudian, maka selain mengikuti program pengendalian penyakit malaria dari pihak kesehatan,
masyarakat juga sering mengambil inisiatif untuk menggunakan cara-cara tradisional (Effendi
Tupong, perilaku pencarian pengobatan malaria, 2007).
Laporan Dinas Kesehatan Kab. Alor menunjukkan bahwa pada tahun 2006 terjadi
penurunan angka kejadian malaria, namun pada tahun 2007 kembali meningkat dan ini terlihat
pada terjadinya kejadian luar biasa (KLB) malaria yang terjadi di Desa Mebung dan menetap di
urutan pertama hingga sekarang (Dinkes Kab. Alor, 2009).
Peran petugas kesehatan sangat menentukan dalam upaya mengendalikan persoalan yang
diungkapkan diatas. Salah satu bentuk intervensi petugas kesehatan yaitu memberikan penyuluhan
kesehatan tentang pemberantasan sarang nyamuk penyebab malaria. Penyuluhan kesehatan
masyarakat bertujuan agar masyarakat menyadari mengenai masalah penanggulangan dan
pemberantasan malaria, sehingga mengubah pola perilaku untuk hidup sehat dan bersih.
Kurang berhasil atau kegagalan suatu program kesehatan, sering disebabkan oleh kurang
atau tidak adanya dukungan dari para pembuat keputusan, baik ditingkat nasional, maupun lokal
(Provinsi, kabupaten atau kecamatan). Akibat kurang adanya dukungan itu, antara lain rendahnya
alokasi anggaran untuk program kesehatan, kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya
kebijakan yang menguntungkan bagi kesehatan dan sebagainya.
Kabupaten Alor sebagai daerah yang endemis malaria mendapat perhatian dari pemerintah
daerah, hal ini terlihat melalui adanya pembahasan anggaran bersama oleh pemerintah daerah dan
DPRD untuk penyakit menular terutama malaria. Dalam pembahasan anggaran yang kemudian
dinamai dengan “Anggur Merah (anggaran untuk rakyat menuju sejahterah)” ini, pemerintah
menekankan perlunya menaikkan anggaran untuk upaya pengendalian kejadian malaria. (Ombay
News, 2009).
Oleh karena rumitnya upaya promosi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran dan
kemauan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatannya inilah, maka pada Delarasi Alma
Ata kemudian dirumuskanlah 3 stategi pokok yang darinya diharapkan mampu mengadakan
perubahan perilaku masyarakat, yakni advokasi, sosial support, dan empowerment of the people.
70 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Dan dari ketiga strategi ini, yang biasa dipakai untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk
mendukung program adalah advokasi.
Advokasi mencakup mengidentifikasi mitra, membentuk persekutuan, mengarahkan
dukungan, menetapkan jaringan, mobolisasi pendapat umum, melobi dukungan untuk pembuatan
keputusan, memperoleh dukungan dari penerima advokasi dan memusatkan perhatian terhadap
penentang. Advokasi sangat tergantung pada penggunaan media massa, komunikasi interpersonal,
dan informasi lain, pendidikan dan saluran-saluran komunikasi.
Orang yang paling sering menjadi target dari usaha-usaha advokasi adalah berbagai
pembuat keputusan, pembuat kebijakan, pemuka pendapat, pemimpin agama, orang yang
mengontrol akses terhadap sumber-sumber penting seperti media, dan orang-orang yang
berpengaruh. Kelompok-kelompok lain seperti masyarakat sipil, persekutuan, organisasi non
pemerintah (LSM), sektor swasta, dan media juga menjadi target dan mitra usaha-usaha advokasi.
Seiring dengan banyaknya program kesehatan yang dibuat oleh dinas kesehatan kota, maka
pengawalan penuh atas program pengendalian malaria menjadi sesuatu yang harus dilakukan,
karena masalah ini telah menjadi persoalan yang tidak pernah terselesaikan ditingkat gross roots.
Merujuk pada sejumlah permasalah diatas, maka peneliti berusaha meneliti tentang “Implementasi
Konsep Advokasi Terhadap Kebijakan Pengendalian Penyakit Malaria Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009”.
Bahan dan Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu untuk
mengeksplorasi dan mencari penjelasan empirik mengenai implementasi konsep advokasi terhadap
kebijakan pengendalian malaria pada Dinas Kesehatan Kab. Alor NTT.
Dilakukan dengan wawancara mendalam dengan maksud memperoleh informasi yang
sebanyak-banyaknya sehingga mampu menjawab tujuan ini. Tipe wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in dept interview) terhadap informan yang
dipilih.
Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini secara khusus menganalisis tentang impelementasi konsep advokasi terhadap
kebijakan pengendalian malaria pada Dinas Kesehatan Kab. Alor, dengan fokus pada komitmen
politik, dukungan kebijakan, dukungan sistem, dukungan sosial, dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun hasil penelitian kami sebagai berikut:
A. Komitmen Politik
Komitmen para pembuat kebijakan atau penentu kebijakan di tingkat daerah dan di sektor
manapun terhadap permasalahan kesehatan dan upaya pemecahan permasalahan kesehatan
atau penyakit malaria. Dalam kegiatan ini yang ingin diketahui adalah seberapa jauh
komitmen politik para eksekutif dan legislatif terhadap masalah kesehatan masyarakat
ditentukan oleh pemahaman mereka terhadap masalah-masalah kesehatan.
Sebagaimana yang menjadi tujuan advokasi yakni berusaha untuk mendapatkan komitmen
politik, maka kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Alor juga
mengarahkan perhatiannya pada aspek tersebut. Dari kegiatan advokasi yang dilaksanakan
oleh Dinkes kepada legislator, maka komitment politik yang dibangun adalah bahwa karena
persoalan yang menjadi isi advokasi adalah sama dengan apa yang menjadi program pada
saat kampanye sehingga tidak sulit untuk menyatukan komitment. Kemudian sebagai orang
yang mewakili masyarakat Alor dan karena masalah malaria merupakan masalah yang sulit
untuk dikendalikan, maka legislator sangat mendukung program penngendalian malaria yang
terjadi di Kab. Alor. Pernyataan ini sesuai dengan ungkapan informan sebagai berikut ini :
“Sebenarnya dalam kampanye politik mereka sudah memasukkan persoalan ini sebagai
point kampanye sehingga tidak terlalu sulit untuk membangun komitment. Kemudian yang
menjadi komitment mereka adalah mereka akan selalu mendukung program Dinas dalam
pengendalian malaria” (AN, Dinas Kesehatan).
71 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Informasi yang diungkapkan tentang komitment politik legislative sama dengan informasi
yang diungkapkan oleh pihak legislatif. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai
berikut :
“Sebenarnya komitmnet politik itu telah ada pada saat kami mengadakan kampanye politik,
bahwa kami akan senantiasa mendukung program-program kesehatan agar masyarakat
selalu sehat. Hal semacam ini juga kami katakan pada saat Dinkes membicarakan hal ini
dengan kami. Sebagai dewan kami berkomitmen akan menjadikan hal ini sebagai masalah
penting untuk direalisasikan. Ini juga akan menjadi program penting kami, apalagi kami kan
berada di komisi C yang bertugas untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan
kesehatan” (MM, komisi C DPRD Kab. Alor).
Pada pelaksanaannya dilapangan ternyata komitment bersama oleh kedua bela pihak yang
dibangun tidak sepenuhnya direalisasi. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya bentuk
kebijakan yang dikeluarkan oleh legislator sebagai bentuk kongkrit dari komitment politik
yang telah ada. Hal ini diungkapkan oleh informan Dinkes sebagai berikut :
“Komitment politik yang kita bangun bersama dengan dewan yang katanya akan mendukung
sepenuhnya pengendalian malaria ternyata hanya sebatas konsep dan tidak ada realisasi
atau tindak lanjutnya” (MD, Dinas Kesehatan).
Keberhasilan membangun komitment pembuat kebijakan tidak terlepas dari stategi yang
dibangun untuk kegiatan advokasi. Membangun strategi yang baik merupakan sebuah
keharusan dalam kegiatan advokasi, karena keberhasilan advokasi tergantung pada strategi
yang digunakan. Dinas kesehatan Kabupaten Alor dalam melakukan advokasi dengan
membangun strategi dengan cara berusaha untuk menyampaikan program secara lansung
kepada para pengambil kebijakan. Hal ini terkait dengan informasi yang diungkapkan oleh
informan sebagai berikut :
“Kita mengadakan pendekatan kepada para pengambil kebijakan dengan cara mendatangi
mereka secara satu persatu untuk menyampaikan program yang kami anggap penting,
khususnya malaria” (MS, Dinas Kesehatan).
Selain mengadakan lobi politik dengan cara menyampikan program secara lansung kepada
para pengambil kebijakan, Dinas Kesehatan Kab. Alor juga membangun strategi advokasi
dengan mempublikasi program serta persoalan kesehatan yang menjadi materi advokasi
melalui media cetak dan elektronik untuk mempengaruhi kebijakan. Hal ini senada dengan
yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut ini :
“Selain kita sampaikan masalah ini ke mereka, selain itu juga kita sering muat masalah ini
di media seperti di Koran, kita muat juga di radio, karena kita anggap bahwa mungkin akan
lebih baik klo ini juga jadi pengetahuan masyarakat sehingga cepat-cepat ada dukungan”
(MS, Dinas Kesehatan).
Advokasi adalah serangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan secara sistematis demi
mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan yang dibangun, karena output yang baik
bergantung pada bagaimana yang yang terjadi dalam kegiatan advokasi.
Selain membangun strategi, dukungan kebijakan yang diberikan oleh para pengambil
kebijakan pada masalah yang diadvokasi tidak terlepas dari langkah strategis yang diambil
oleh advocator dalam melaksanakan kegiatan advokasi. Dasar asumsi diatas bersinergi
dengan advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Alor, bahwa ada langkah
strategis yang diambil untuk menyampaikan program dan untuk mempengaruhi kebijakan
kesehatan. Hal sesuai dengan yang diungkapkan sebagai berikut :
72 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
“Kita membawa pogram yang dikhususkan untuk pengendalian malaria untuk disampaikan
kepada para pengambil kebijakan. Kita menyampaikan kepada mereka serta kita berusaha
meyakinkan betul bahwa upaya pengendalian malaria sangat penting, sehingga harus ada
dukungan kebijakan” (MD, Dinas kesehatan).
Banyaknya sebab yang mempengaruhi kejadian malaria sehingga sulit bagi Dinkes untuk
berusaha mencegah/mengendalikannya. Masalah yang dimaksud antara lain : Alor adalah
daerah endemis malaria, faktor ekonomi (kemiskinan) serta perilaku masyarakat yang tidak
mengarah pada kesehatan. Selain itu, ada juga masalah yang terjadi pada internal Dinas
kesehatan yang menjadi kendala tersendiri sehingga malaria sulit dikendalikan, masalah
internal Dinas kesehatan antara lain : kekurangan dana operasional, kekurangan sumber daya
yang dapat diberdayakan untuk upaya pengendalian malaria, serta sarana atau prasaraan
(fasilitas pendukung) yang tidak memadai.
Beberapa factor diatas yang menjadi kendala bagi Dinas kesehatan dalam upaya
pengendalian malaria di Kab. Alor, oleh karena itu Dinas Kesehatan berusaha untuk
menjadikan masalah-malasah tersebut menjadi pijakan atau alasan untuk membangun
komitment bersama para pembuat kebijakan.
Pentingnya komitment pemerintah dalam mendukung program dapat dijadikan sebagai tolak
ukur bagi masyarakaat untuk konsisten bersama Dinkes dalam upaya pengendalian penyakit
malaria. Seperti yang diketahui bahwa persoalan kesehatan tidak terlepas dari situasi dan
kondisi politik daerah segingga konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan komitment
politik menjadi poin tersendiri bagi terlaksananya program secara maksimal.
Sama seperti legislative, pemerintah daerah juga memberikan komitmentnya kepada Dinas
kesehatan untuk senantiasa mendukung terlaksananya program pengendalian malaria. Seperti
yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :
“Sekalipun tidak secara eksplisit kami sebutkan dalam program pemerintah yakni Tri Krida,
namun persoalan kesehatan tetap menjadi issu utama yag wajib selalu dilihat.
Pada program Gubernur yang Anggur Merah secara eksplisit disebutkan mengenai
penanganan penyakit menular termasuk malaria sehingga kami selalu berpatokan ke situ
juga.
Komitment politik kami adalah kami akan selalu mendukung Dinkes dalam bentuk apapun
untuk pengendalian penyakit khususnya penyakit malaria karena hal ini juga menjadi tugas
kami” (informan LD).
Konsistensi komitment politik yang dibangun pemerintah dapat diukur melalui program-
program umum pemerintah yang dijadikan program utama selama lima (5) tahunan.
Pemerintah Daerah dalam hal ini kepala Daerah (Bupati) Alor mempunyai program tiga
program pokok yang dinamakan Trikrida yang antara lain : memperkuat kelembagaan,
ekonomi kerakyatan dan peningkatan sumber daya manusia. Dalam program trikrida tersebut
tidak secara spesifik menyebut kesehatan sebagai salah satu sektor yang akan disentuh.
Komitmen politik dapat diwujudkan antara lain dengan pernyataan-pernyataan, baik secara
lisan maupun tulisan, dari para pejabat eksekutif maupun legislatif, mengenai dukungan atau
persetujuan terhadap issu-issu kesehatan. Misalnya pembahasan mengenai anggaran untuk
sektor kesehatan, pembahasan rencana undang-undang lingkungan oleh parlemen, dan
sebagainya.
B. Dukungan Kebijakan
Dukungan politik tidak akan berarti tanpa dikeluarkannya kebijakan yang kongkrit dari para
pembuat keputusan tersebut. Oleh sebab itu setelah adanya komitmen politik dari para
eksekutif maka perlu ditindak lanjuti dengan advokasi lagi agar dikeluarkan lagi kebijakan
untuk mendukung program yang telah memperoleh komitmen politik tersebut. Dukungan
73 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
kebijakan ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerimtah maupun peraturan daerah,
surat keputusan pimpinan institusi maupun baik pemerintah maupun sawasta, instruksi
maupun surat edaran dari para pemimpin lembaga/institusi.
Advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Alor selain mendapat komitment
politik, dukungan kebijakan juga dikeluarkan oleh pemerintah Daerah dalam bentuk
rekomendasi kepada setiap kecamatan dan desa untuk senantiasa memasukkan program
pengendalian penyakit malaria pada kegiatan musrenbang wilayah serta diimplementasikan.
Hal ini terlihat pada informasi yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :
“Pada saat kami mengadakan advokasi kami memperoleh dukungan kebijakan yakni ada
rekomendasi Bupati kepada seluruh Kecamatan dan Desa yang berada di Kabupaten Alor
untuk memasukkan program pengendalian malaria pada Musrenbang di setiap Kec. Dan
Desa” (MS, Dinas Kesehatan).
Kepedulian pemerintah daerah terhadap kejadian penyakit malaria di Kab. Alor dapat dilihat
pada dikeluarkannya rekomendasi tersebut. Rekomendasi lahir sebagai bentuk pendukung
program pengendalian malaria, rekomendasi juga dijadikan sebagai alat untuk mengikat
berbagai elemen yang turut berpartisipasi dalam upaya pengendalian malaria. Kemudian
karena rekondasi yang ada adalah dikeluarkan oleh pemerintah daerah maka target utamanya
adalah kecamatan dan desa ang berada di Kab. Alor.
Realitas lapang menunjukkan hal yang lain, bahwa karena tidak adanya pengawalan oleh
Dinkes yang dilakukan terhadap rekomendasi yang dikeluarkan, maka pada pelaksanaannya
mengalami kendala. Target sasaran tidak sepenuhnya melaksanakan dalam bentuk kerja-kerja
nyata dilapangan sehingga harapan untuk mengendalikan malaria tidak tercapai.
Dimasukkannya program-program pengendalian malaria pada musrenbang wilayah menjadi
program-program yang tidak berjalan karena tidak aplikatif.
Banyak alasan yang menengarai mengapa sehingga program tidak dapat terlaksana dengan
baik dilapangan yakni rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan hidup sehat,
karena kesibukan masyarakat dalam mencari nafkah hidup, kemudian diperparah dengan
kurangnya sumber daya dan anggaran yang dapat diberdayakan untuk pelaksanaan program.
Sebagaimana pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Alor juga
mengemukakan bahwa sebenarnya mendukung program pengendalian malaria dengan
menigkatkan anggaran untuk dana operasional Dinas Kesehatan dalam penanggulangan
malaria namun terkendala pada urusan politik daerah. Ada ketimpangan prosedur pada
pembahasan anggaran daerah, karena anggaran sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah
daerah dan DPRD hanya menyepakati. Anggaran daerah yang dialokasikan ke setiap
Depatemen/Dinas yang berada di Kab. Alor ditentukan secara sepihak oleh pemerintah
Daerah dan tidak ada pembahasan bersama oleh kedua institusi tersebut (Legislatif-
eksekutif). Tindakan pemerintah daerah yang demikian dengan alasan bahwa karena
Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak memungkinkan untuk dilakukan hal demikian.
Namun pada kenyataannya pernyataan Pemda tidak sebangun dengan kenyataan di lapangan,
hal ini terlihat pada Departemen atau Dinas lain yang mendapatkan anggaran yang lebih
besar dibandingkan dengan Dinas Kesehatan, bahkan besaran anggaran yang diperoleh oleh
departemen/dinas tersebut tidak sebanding dengan kapasitas/ tugasnya.
Berangkat dari kenyataan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa untuk mendapatkan
aggaran yang memadai tergantung pada konstalasi politik daerah. Departemen atau Dinas
yang mendapatkan anggaran lebih adalah mereka yang mempunyai kekuatan untuk
mempengaruhi pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan.
Pemerintah daerah hanya beralasan bahwa kalau sangat mendukung program, namun
meningkatkan anggaran untuk operasional pengendalian penyakit malaria agak sulit karena
diseuaikan dengan pendapatan asli daerah.
74 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Tidak adanya anggaran khusus untuk pengendalian kejadian malaria sehingga sangat sulit
bagi Dinas Kesehatan mempengaruhi keterlibatan sektor lain untuk berperan. Dukungan
sistem dalam pengendalian kejadian malaria di tingkat kabupaten Alor selama ini hanya
berupa pertemuan koordinasi dengan mengundang Dinkes, Diknas, Kesra, Setda dan
Bappeda untuk membahas perkembangan kejadian malaria di Kab. Alor. Biaya pelaksanaan
pertemuan ini menggunakan anggaran rutin operasional Dinkes untuk program pengendalian
malaria.
Upaya mengadvokasi serta mengawal kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal
oleh Dinas kesehatan, karna berbagai macam kendala yang terjadi di dalamnya. Mulai dari
kesulitan mengajak atau mengumpulkan para pengambil kebijakan, kekurangan anggaran
kegiatan, sampai pada kekurangan sumber daya manusia.
Keberhasilan suatu kegiatan advokasi dikarenakan oleh intensitas advokator dalam meminta
dan mengawal kebijakan, faktor kualitas lobi politik atau negosiasi, serta ditunjang oleh
sumber daya manusia yang yang memiliki kualitas baik dan dapat diandalkan.
Terealisasi atau tidak terealisasinya kebijakan yang dukeluarkan oleh pengambil kebijakan
tidak terlepas dari seberapa besar konsistensi dinas kesehatan dalam mengawal komitmen
serta kebijakan yang diberikan. Tidak terjadinya realisasi kebijakan dengan baik dikarenakan
oleh dinas kesehatan telah merasa berhasil setelah diberikan komitmen politik dan tidak
sepenuhnya diteruskan dengan upaya pengawalan terhadap kebijakan ada. Oleh karena itu
sehingga komitmen atau kebijakan yang ada tidak dapat dilanjutkan dan tidak dapat
terealisasi dengan baik.
Masalah yang dialami oleh Dinas kesehatan Kab. Alor adalah selain kekurangan anggaran
kegiatan advokasi, sumber daya manusia (tenaga) juga menjadi masalah tersendiri karena
tenaga yang bekerja pada bagian promosi kesehatan adalah semuanya orang-orang dengan
keahlian di bidang/jurusan yang lain dan tidak ada satu pun tenaga promosi kesehatan
(Dinkes Kab. Alor tidak mempunyai tenaga promosi kesehatan). Seperti yang diungkapkan
oleh informan sebagai berikut :
“Sulit sekali kami menemukan para pengambil kebijakan untuk membicarakan persoalan
program dengan alasan mereka sibuk. Sumber daya manusia yang dikerahkan untuk
melakukan kegiatan advokasi minim. Sama sekali tidak ada tenaga promosi kesehatan yang
bisa diharapkan mampu melakukan kegiatan tersebut.” (AN, Dinas Kesehatan).
Bagaiamanpun baiknya strategi advokasi yang direncanakan, namun tidak didukung oleh
seorang advokator yang baik dan mempunyai kemampuan dan pengetahuan komunikasi,
maka dapat saja tujuan advokasi tidak tercapai. Advokator bisa diambil dari lingkungan
sistem dan bisa juga dipakai orang di luar sistem yang mempunyai komitment dan perhatian
yang tinggi dengan masalah yang akan diadvokasi.
Tidak adanya tenaga ahli promosi kesehatan pada Dinas kesehatan Kab. Alor merupakan
salah faktor yang ikut menghambat keberlangsungan advokasi serta kualitas mempengaruhi
kebijakan. Provider promosi kesehatan dalam hal ini mempunyai kompetensi khusus dalam
upaya mempengaruhi kebijakan dan praktik, yang meliputi kemampuan petugas promosi
kesehatan pada bisnis yang mempengaruhi kebijakan yaitu dalam bentuk spesifik kebijakan
pemerintah yang berdampak pada kesehatan, secara langsung maupun tidak langsung.
Karena kurangnya pengawalan baik dari advokator terhadap kebijakan yang telah
dikeluarkan sehingga implikasinya tidak terlihat pada target sasaran. Ikut atau tidanya taget
sasaran bergantung pada seberapa besar kekuatan atau daya dorong kebijakan dalam
mempengaruhi sikap target.
C. Dukungan Sistem
Adanya sistem atau organisasi kerja yang memasukan unit pelayanan atau program kesehatan
dalam suatu institusi atau sektor pembangunan adalah mengindikasinya dukungan sistem.
Agar suatu program atau kegiatan berjalan dengan baik maka perlu adanya sistem mekanisme
75 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
atau prosedur kerja yang jelas dan mendukungnya. Oleh sebab itu sistem kerja atau
organisasi kerja yang melibatkan kesehatan perlu dikembangkan.
Upaya pengendalian vektor banyak terkait dengan perubahan dan manipulasi lingkungan,
selain memerlukan kerja sama lintas sektor untuk mengurangi perindukan vektor dan kontak
manusia-vektor patogen. Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Alor
untuk penanggulangan malaria melalui kerjasama lintas sektor selama ini belum maksimal.
Beberapa acara pertemuan antara Dinkes dengan dinas terkait dalam membahas
penanggulangan malaria pada awalnya menarik bagi dinas lain, namun dalam praktik
lapangan tidak sepenuhnya dapat berjalan. Kebijakan lintas sektor penanggulangan malaria
bertujuan supaya pemberantasan berjalan terpadu.
Advokasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan tidak secara maksimal membangun
dukungan sistem/kerja sama lintas sektor untuk mendukung upaya pengendalian malaria,
yang ada hanyalah institusi pemerintahan kecamatan dan desa yang memasukkan program
pengendalian malaria untuk dijadikan sebagai program tahunan kecamatan dan desa, namun
semuanya hanyalah sebatas program dan tidak terealisasi. Seperti yang diungkapkan oleh
informan sebagai berikut :
“Kalau untuk dukungan sistem kami melihat bahwa hal ini yang sangat kurang karena pada
instansi-instansi tidak pernah berlaku atau diterapkannya program pengendalian malaria,
yang berlaku hanya pada institusi pemerintahan seperti kecamatan dan desa” (MS, Dinas
Kesehatan).
Salah satu langkah stategis dari kegiatan advokasi berusaha mengarahkan kebijakan untuk
diterapkan pada institusi-institusi penting yang dinilai mempunyai korelasi atau hubungan
terhadap kesehatan, dengan demikian program yang dicanangkan tidak hanya masyarakat
yang dijadikan sebagai objek, namun harus ada pelibatan instansi untuk mendapatkan
dukungan sistem.
Banyak alasan yang mengebabkan tidak adanya dukungan sistem terhadap program
pengndalian malaria, mulai dari kurangnya pengaruh kebijakan terhadap sistem, kurangnya
anggaran operasional, sampai pada alasan kesibukan masing-masing instansi terhadap
programnya. Seperti yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :
“Pimpinan instansi tidak terlalu respon dengan program karena alasan tidak ada dengan
dong sibuk dengan dong pu program” (TA, Dinas Kesehatan).
Rendahnya kesadaran akan hidup sehat menjadi polemik tersendiri bagi terlaksananya sebuah
program secara sistemik. Orang lebih menganggap bahwa karena malaria adalah sebuah
penyakit dan berkaitan dengan kesehatan sehingga yang bertanggung jawab hanyalah Dinas
Kesehatan dan bukan yang lain.
Pengendalian malaria yang berhasil ialah dengan menempatkan program pengendalian ke
dalam bagian integral pembangunan kesehatan nasional dan didukung oleh kerjasama lintas
sektor pada semua tingkat, melibatkan peran serta anggota masyarakat dan orang-orang yang
bekerja di bidang pendidikan, pertanian, lingkungan, sanitasi dan pembangunan masyarakat.
Lintas sektor kesehatan merupakan hubungan yang dikenali antara bagian atau bagian-bagian
dari sektor-sektor berbeda, dibentuk untuk mengambil tindakan pada suatu masalah agar hasil
atau hasil antara kesehatan tercapai dengan cara yang lebih efektif, berkelanjutan atau efisien
dibanding sektor kesehatan bertindak sendiri.
D. Dukungan Sosial
Penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh masyarakat. Program
pengendalian malaria yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan mendapat perhatian dan
dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat, ini terlihat dari kikutsertaan LSM dalam
melakukan kegiatan advokasi. Global Fund (GF) adalah LSM yang biasa berpartisipasi
76 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
dalam program pengendalian malaria. Bantuan Global Fund (GF) yang lain adalah
membagikan kelambu berinsektisida kepada masyarakat.
Partisipasi dan kerja sama antara global fund dalam mengendalikan malaria menjadi sangat
penting mengingat selama ini dinas kesehatan agak kewalahan dalam hal anggaran. Dengan
kerja sama ini, global fund selalu menutupi kekurangan dari dinas kesehatan dalam hal
pencegahan penyakit malaria dengan pembagian kelambu berinsektisida dan upaya-upaya
pendmpingan masyarakat lainnya. Seperti yang disampaikan oleh informan berikut :
“kita biasa dibantu oleh global found jadi klo kita ada kekurangan na dorang selalu
membantu, semisal waktu dong bantu pengadaan kelambu berinsektisida untuk dibagikan ke
masyarakat” (AN, Dinkes).
Dukunngan juga diberikan oleh tokoh-tokoh agama dan masyarakat terhadap program
malaria. Namun karena alasan kesibukan masyarakat mencari nafkah iduplah yang
menyebabkan program tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang diungkapkan
oleh informan sebagai berikut :
“Sebenarnya ada tangapan dan dukungan positif yang diberikan oleh masyarakat terhadap
program yang kami keluarkan untuk program malaria namun dengan alasan kesibukan
mencari nafkah keluarga maka tidak mampu direalisasikan dengan baik program malaria
itu” (MS, Dinas Kesehatan).
Respon positif masyarakat terhadap program sangatlah baik, namun Ekonomi dan upaya
pemenuhan kebutuhan keluarga adalah alasan utama mengapa sehingga program kesehatan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik. seperti yang diketahui bahwa tingkat ekonomi
masyarakat Kab. Alor adalah dibawah rata-rata sehingga masyarakat disibukkan dengan
memikirkan persoalan tersebut dan terlalu memikirkan hal yang lain.
Namun demikian, tokoh masyarakat dan tokoh agama senantiasa memberikan dukungan
terhadap program. Mereka menganggap bahwa karena masalah malaria merupakan persoalan
penting yang wajib mendapat dukungan masyarakat agar dapat tertangani. Bentuk dukungan
para tokoh adalah dengan menyampaikan upaya-upaya preventif kepada masyarakat. Seperti
yang diungkapkan oleh informan sebagai berikut :
“Bentuk dukungan kongkrit yang diberikan adalah sering diserukan oleh tokoh agama
disetiap kegiatan keagamaan apalagi kalau musim hujan seperti ini, dan sering juga
disampaikan oleh kepala-kepala lingkungan atau tokoh lingkungan untuk menjaga
lingkungan agar tetap bersih, dan agar kalau tidur memakai kelambu” (AN, Dinas
Kesehatan).
Kebiasaan masyarakat Kab. Alor adalah apabila informasi-informasi penting yang ingin
disampaikan maka rumah-rumah ibadahlah yang menjadi tempat pling strategis untuk
disampikan, hal ini dengan alasan karena kesibukan masyarakat dengan berbagai
pekerjaannya tidak mungkin diukpulkan pada sebuah tempat, berkumupl di rumah ibadah
ketika beribada menjadi kesempatan emas untuk menyampaikan masalah. Hal ini yang
dilakukan oleh parah tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk melancarkan program, namun
karena alasan kesibukan maka program tidak terlaksana dengan baik.
Secara teknis, dukungan social adalah menjalin kemitraan untuk pembentukan opini public
dengan berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh
agama, lembga swadaya masyarakat (LSM), dunia swasta, media massa, organisasi profesi,
dan lain-lain.
Penciptaan lingkungan yang kondusif untuk kesehatan tidak terlepas dari campur tangan
pengambil kebijakan disetiap sektor untuk membantu mengarahkan masyarakat dalam
menunjang setiap program untuk direalisasikan.
77 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Dukungan sosial dalam kesehatan dimaksudkan untuk menggalakkan partisipasi tokoh
masyarakat, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah dan non pemerintah bekerja sama
berdasar kesepakatan dan fungsi masing-masing.
E. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh kemampuan
untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan dilakukan yang terkait
dengan diri mereka, termasuk mngurangi hambatan pribadi dan hambatan sosial dalam
pengambilan tindakan. Pemberdayaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan rasa
percaya diri untuk menggunakan kemampuannya, diantaranya melalui pendayagunaan
potensi lingkungan.
Karena advokasi tidak mendapat hasil yang maksimal dan mengingat kompleknya masalah
kesehatan yang terjadi di Kab. Alor, dan untuk merealisasikan program yang dicanangkan
maka upaya yang dilakukan adalah dengan pemberdayaan terhadap masyarakat. Asumsinya
adalah berusaha menggunakan potensi yang ada dalam masyarakat untuk melancarkan
program kesehatan uatamanya pengendalian malaria. Bentuk pemberdayaan masyarakat yang
dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab. Alor adalah dengan melakukan pelatihan kepada
orang-orang yang direkrut untuk menjadi kader dalam upaya pengendalian malaria. Hal ini
sesuai dengan informan sebagai berikut :
“Yang kami lakukan untuk masalah pemberdayaan adalah dengan melakukan
pengkaderan/pelatihan kepada masyarakat untuk mengenal dan mengetahui persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan malaria serta upaya pencegahannya. Mereka inilah yang
diharapkan menjadi pioner di masyarakat untuk perubahan perilaku dan upaya menekan
kejadian malaria” (TA, Dinas Kesehatan).
Bentuk pemberdayaan lain yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan adalah dengan membentuk
poskesdes. Poskesdes Adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang
dibentuk di desa dalam rangka mendekatkan/ menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi
masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan informan sebagai berikut :
“Selain itu Dinkes juga membentuk Poskesdes untuk menangani persoalan yang kesehatan
kesehatan yang berkembang di wilayah masing-masing” (MS, Dinas Kesehatan).
Kabupaten Alor sebagai kabupaten dengan intensitas kejadian malaria tertinggi mestilah
secara cerdas mengdakan pemberdayaan masyarakat untuk mensukseskan program.
Pengembangan sektor pemberdayaan masyarakat adalah penting mengingat pada
masyarakatlah menjadi orientasi program.
Mengembangkan pendekatan Pemberdayaan Masyarakat akan meningkatkan efektifitas dan
efesiensi penggunaan sumber daya yang mengarah pada upaya pengendalian penyakit
malaria di Kab. alor. Pendekatan ini akan meningkatkan relevansi program Dinas Kesehatan
terhadap masyarakat lokal dan meningkatkan kesinambungannya, dengan mendorong rasa
memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pengendalian malaria.
Kesimpulan
1. Advokasi telah dilakukan oleh dinas kesehatan Kab. Alor, dengan menggunakan strategi
menyampikan program secara langsung kepada DPRD, dalam pencapaiannya yaitu
peningkatan anggaran dari tahun ke tahun tidak terjadi. Kondisi ini disebabkan DPRD belum
berupah persepsinya sebagai akibat pelaksanaan advokasi.
2. Dari advokasi yang dilakukan dengan hasil yakni mendapat komitment politik dari pemerintah
dan DPR bahwa akan senantiasa mendukung upaya pengendalian malaria yang dilakukan oleh
dinas kesehatan, namun kurangnya pengawalan yang baik yang dilakukan oleh dinas kesehatan
terhadap komitmen dan kebijakan tersebut, tidak direalisasikan. Dukungan kebijakan terhadap
78 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
program pengedalian malaria hanya bersifat rekomendasi serta tidak dapat dijadikan sebagai
daya dorong yang memungkinkan bagi terlaksananya program pengendalian malaria disetiap
sektor.
3. Upaya membangun dukungan sistem, dukungan sosial serta pemberdayaan masyarakat hanya
dilakukan sesuai dengan program dinas, dan tidak didukung oleh perangkat kebijakan yang
diharapkan mengarahkan perhatian elemen terkait. Hanya ada institusi pemerintahan
Kecamatan dan Desa yang berusaha memasukkan program pada masing-masing wilayah kerja,
namun tidak terealisasi dengan baik.
Saran
1. Perlu membangun strategi secara matang sebelum mengadakan advokasi, dengan demikian hal
yang diavokasikan dapat direspon secara baik oleh penentu kebijakan. Kemudian untuk
membangun strategi yang baik maka diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang baik pula,
olehnya dinas kesehatan Kab. Alor seyogyanya merekrut tenaga-tenaga promosi kesehatan
yang berkompetensi untuk melakukan kegiatan advokasi.
2. Harus ada kesiapan advokator Dinas Kesehatan untuk melakukan proses Pengawalan terhadap
komitment yang telah ada sampai komitmen tersebut dapat terealisasi. Begitu juga terhadap
apapun kebijakan yang telah keluar, baik pemberi kebijakan dan Advokator kesehatan harus
konsisten mengawal dan merealisasikannya sehingga dapat dilihat sebagai sebuah kebijakan
yang mempunyai kekuatan dan dapat diikuti oleh komponen-komponen yang menjadi target
program.
3. Konsistensi Pemda dan DPRD dalam merealisasikan kebijakan harus dijaga, karena hal ini
menjadi kekuatan yang memungkinkan bagi terlaksananya program pengendalian penyakit
malaria di Kab. Alor. Konsistensi diperlukan karena Kebijakan yang dikeluarkan akan
dijadikan sebagai dorongan tersendiri bagi partisipasi publik atau masyarakat dan pada sektor
manapun untuk menyukseskan program pengendalian malaria di Kab. Alor.
DAFTAR PUSTAKA
Anonym, Advokasi Dalam Promosi Kesehatan, http://syaehaceh wordpress.com diakses pada
tanggal 22 juni 2010
Azwar, Agus; 1996. Antropologi Kesehatan Indonesia, EGC. Jakarta.
Bungin B; 2000. Metodelogi Penilitian Kualitatif, Rajawali. Jakarta.
Bustan M.N. 1997. Pengantar Epidemiologi, FKM – UNHAS, Ujung Pandang.
Depkes RI, 2002, Buku Panduan Strategi Promosi Kesehatan Di Indonesia, Direktorat Promosi,
Jakarta
Depkes RI, 2003, Kiat-Kiat Advokasi Kesehatan, Pusat Promosi Kesehatan Depkes RI, Jakarta
Depkes RI Penyakit Malaria, Penyakit Malaria Dan TBC Menyebabkan 170.000 Kematian Setiap
Tahun Di Indonesia, http://www.Google.com/ .
Depkes RI, Malaria Akan Diturunkan 50 Persen di 12 Propinsi http://www.Google.com/ .
Dinkes Kab. Alor, 2008. Angka kejadian Malaria (Data Malaria). Alor
Dinkes Kab. Alor, 2008. Profil Dinas Kesehatan.
Direktorat Promkes; 2001. Buku panduan Strategi Promosi Kesehatan, Jakarta
Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan RI, Modul Advokasi 2007
Direktorat Jenderal pemberantasan penyakit menular dan penyehatan lingkungan. 2001. Buku
Pedoman Pemberantasan Penyakit Berbasis Lingkungan, Jakarta : Departemen
Kesehatan RI.
Dunn, Wiliam; 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua, Gadja Mada University
Press, Yogyakarta.
Effendi T.; 2007. Perilaku Pencarian Pengobatan Malaria Masyarakat Alor.
79 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Jurnal Promosi Kesehatan
NUSANTARA INDONESIA
Graef, Judith. A. 1996. Komunokasi Untuk Kesehatan dan Perubahan Prilaku, Gajah Mada
University Press. Yokyakarta.
Harijanto P.N. 2000. Malaria-Epidemiologi Patogenesis Manisfestasi Klinis Dan Penangananya,
EGC. Jakarta.
H Sudrajat, SB Mencegah Malaria. www.cgh.com.sg/health/witra sejati/2007 Malaria htm,
diakses 9 September 2009
Manto; 2008. Advokasi Kampanye Bebas Malaria. Universitas Gadjah Mada
Masse dkk; 2009.Distribusi Penggunaan Kelambu Berinsektisida. Universitas Gadjah Mada
Moleong dan lexy, j.2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya Offset Bandung.
Muhadjir, H.N. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi II, Rake Sarasin, Yogyakarta.
Notoatmodjo, S; 1997. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Rineka cipta jaya. Jakarta.
......................... 2005. Promosi Kesehatan Teori Dan Aplikasi, Rineka Cipta.
.......................... 2002. Pendidikan Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Jakarta Rineka Cipta. Jakarta.
......................... 2002. Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta. Jakarta.
Pribadi, Wita Dkk. 1991. Kumpulan Makalah Simposium Malaria, FKUI. Jakarta.
Prijono, Oninys; 1996. Konsep kebijakan dan pemberdayaan, CSIS, Jakarta.
Sabarguna; 2004. Pemasaran Rumah Sakit, Konsorsium, Yogyakarta.
Sudarwan; D. 2002. Menjadi Peneliti Kualitatif, Pustaka Setia. Bandung
Sugiono.; 2005 Memahami Penilitian Kualitatif, CV.Alfabeta. Bandung.
Tan Hoan T, Kirana Rahardja; 2002. Obat-Obat Penting, PT. Alex Media Komputindo. Jakarta.
Topatimasang, Roem, dkk, 2000, Merubah Kebijakan Publik, Insist, Yogyakarta.
80 Nomor 9 Edisi 9 Jai-Juni 2012
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah ASI Ekslusif Di Suku MakassarDokumen14 halamanMakalah ASI Ekslusif Di Suku MakassarNur AnnisaBelum ada peringkat
- F4 Asi Eksklusif (Jessi)Dokumen4 halamanF4 Asi Eksklusif (Jessi)rendyjiwonoBelum ada peringkat
- ASI EksklusifDokumen4 halamanASI EksklusifAhmad Az HariBelum ada peringkat
- Determinan Perilaku Pemberian Asi Eksklusif Di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten BarruDokumen12 halamanDeterminan Perilaku Pemberian Asi Eksklusif Di Desa Manuba Kecamatan Mallusetasi Kabupaten BarruAgus AlfarisiBelum ada peringkat
- Laporan PKM f3 ASI Ekslusif FIXDokumen3 halamanLaporan PKM f3 ASI Ekslusif FIXDaudBelum ada peringkat
- Bab IDokumen8 halamanBab Iinnah syamBelum ada peringkat
- F3 ASI EkslusifDokumen3 halamanF3 ASI EkslusifMuh. Wirasto ismailBelum ada peringkat
- Bab 1 2 3Dokumen39 halamanBab 1 2 3Golfried NababanBelum ada peringkat
- PROPOSAL - Fix 3Dokumen57 halamanPROPOSAL - Fix 3Siti RomadhoniBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen12 halaman1 PBEconomics DetectiveBelum ada peringkat
- Hubungan Pengetahuan & Motivasi Ibu Terhadap Pemberian ASI Ekslusif PDFDokumen10 halamanHubungan Pengetahuan & Motivasi Ibu Terhadap Pemberian ASI Ekslusif PDFAndrewYehuBelum ada peringkat
- Bab IDokumen6 halamanBab IIsmi Nur Aulia. S P.18.008Belum ada peringkat
- Laporan Ukm f1 Dan f3Dokumen16 halamanLaporan Ukm f1 Dan f3Sri PUSPITA dewiBelum ada peringkat
- 350 663 1 SMDokumen9 halaman350 663 1 SMRisma AliffiaBelum ada peringkat
- 87-Article Text-182-1-10-20150629Dokumen5 halaman87-Article Text-182-1-10-20150629citra mutiarahatiBelum ada peringkat
- Bab I PendahuluanDokumen6 halamanBab I Pendahuluanbangsa sanusiBelum ada peringkat
- MIni Project YogiDokumen32 halamanMIni Project YogiMoh SholehBelum ada peringkat
- MelluDokumen25 halamanMelluRisna NABelum ada peringkat
- Ibu Menyusui Dan LaktasiDokumen13 halamanIbu Menyusui Dan LaktasiriadelanurmanahBelum ada peringkat
- BAB 1 monika-1Dokumen22 halamanBAB 1 monika-1Monika GintingBelum ada peringkat
- Sharla Raissaqinah Syafril - 2210333025 - Artikel IlmiahDokumen9 halamanSharla Raissaqinah Syafril - 2210333025 - Artikel IlmiahSharla RaissaqinahBelum ada peringkat
- KonsepDokumen2 halamanKonsepwindaBelum ada peringkat
- Bab 1Dokumen5 halamanBab 1AzzalfaAftaniBelum ada peringkat
- Proposal AdeDokumen59 halamanProposal AdeNurmaidaBelum ada peringkat
- Proposal Si Gizi Elmi NoviaDokumen27 halamanProposal Si Gizi Elmi NoviaNovery AdyBelum ada peringkat
- 18.+JK+VOL+15+NO+3+September+2023+hal+1149-1156+(Kodariyah)(1)Dokumen8 halaman18.+JK+VOL+15+NO+3+September+2023+hal+1149-1156+(Kodariyah)(1)ayukBelum ada peringkat
- Penelitian Asi EksklusifDokumen69 halamanPenelitian Asi EksklusifYudhyPoenyaBelum ada peringkat
- Proposal Penawaran KerjasamaDokumen6 halamanProposal Penawaran Kerjasamahesti dianarpsBelum ada peringkat
- Menyusui Dari Perspektif Sosial Budaya 2Dokumen10 halamanMenyusui Dari Perspektif Sosial Budaya 2Hua LahhBelum ada peringkat
- Ukm (F3)Dokumen7 halamanUkm (F3)Dinda yulia DalimuntheBelum ada peringkat
- Jurnal Nifas 1 PDFDokumen16 halamanJurnal Nifas 1 PDFSukma ArdiBelum ada peringkat
- Gambaran Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian MPDokumen47 halamanGambaran Pengetahuan Ibu Tentang Pemberian MPYepi Aboucath100% (1)
- Jurnal 4 DindaDokumen5 halamanJurnal 4 DindaYusi nursiamBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan A. Latar BelakangDokumen18 halamanBab I Pendahuluan A. Latar BelakangFerisa paraswatiBelum ada peringkat
- Revisi Skripsi FixDokumen78 halamanRevisi Skripsi FixFebriani ArsitaBelum ada peringkat
- Laktasi MakalahDokumen11 halamanLaktasi MakalahagungBelum ada peringkat
- 59 154 1 PBDokumen8 halaman59 154 1 PBDea Ananda SipahutarBelum ada peringkat
- Bab IDokumen8 halamanBab IShilvia rizka yuniartiBelum ada peringkat
- Proposal RuhanaDokumen27 halamanProposal Ruhanabidan ruhanaBelum ada peringkat
- Jurnal Kesehatan MasyarakatDokumen8 halamanJurnal Kesehatan MasyarakatAndi IrfansyahBelum ada peringkat
- Tugas Evidence Base Dalam Praktik KebidananDokumen52 halamanTugas Evidence Base Dalam Praktik KebidananadinatauguyBelum ada peringkat
- Bab IDokumen7 halamanBab IRizki Ramadhan SyahputraBelum ada peringkat
- Analisis Jurnal - Rahma Putri Septiani - NIM. 201901029 - R3A KeperawatanDokumen12 halamanAnalisis Jurnal - Rahma Putri Septiani - NIM. 201901029 - R3A Keperawatan201901003 Andi Asrizal NingrawanBelum ada peringkat
- Laporan Kegiatan Seminar KesehatanDokumen10 halamanLaporan Kegiatan Seminar Kesehatanindah lailyBelum ada peringkat
- F3 Mp-AsiDokumen5 halamanF3 Mp-AsiDhevrina Cii PandaBelum ada peringkat
- ASI Eksklusif KIADokumen3 halamanASI Eksklusif KIAEritaBelum ada peringkat
- PROPOSAL PENELITIAN Asi Eksklusif Setelah RevisiDokumen38 halamanPROPOSAL PENELITIAN Asi Eksklusif Setelah RevisiAqila Salsabilah100% (1)
- Makalah Hasil Telaah Jurnal Kesehatan Tentang Asi EkslusifDokumen15 halamanMakalah Hasil Telaah Jurnal Kesehatan Tentang Asi EkslusifSiti Yuriah SiyuBelum ada peringkat
- Faktor - Faktor Yang Menghambat Ibu Dalam Pemberian ASI EksklusifDokumen11 halamanFaktor - Faktor Yang Menghambat Ibu Dalam Pemberian ASI Eksklusifsuprijati05Belum ada peringkat
- SENTRI: Jurnal Riset IlmiahDokumen15 halamanSENTRI: Jurnal Riset IlmiahDina NovBelum ada peringkat
- Jurnal Asi EklusifDokumen6 halamanJurnal Asi Eklusifmonica p yuliantiBelum ada peringkat
- Makalah Imd Dan AsiDokumen11 halamanMakalah Imd Dan AsiPhutrii SuatBelum ada peringkat
- Laporan Penyuluhan ASI Eksklusif & PMTDokumen5 halamanLaporan Penyuluhan ASI Eksklusif & PMTAudra Firthi Dea NoorafiattyBelum ada peringkat
- Panduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanDari EverandPanduan Esensial untuk Skoliosis dan Kesehatan KehamilanPenilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (4)
- Program Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaDari EverandProgram Pencegahan dan Penyembuhan Skoliosis Untuk AndaPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (9)
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Dari EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)
- Merawat penyakit kencing manis tanpa ubatDari EverandMerawat penyakit kencing manis tanpa ubatPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (3)
- RINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyDari EverandRINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyBelum ada peringkat
- Pembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisDari EverandPembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (13)
- PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- SK Desa Kab Bireuen THN 2013Dokumen4 halamanSK Desa Kab Bireuen THN 2013Rudy Addailami, SKMBelum ada peringkat
- SOAL UAS MK. Kesehatan MasyarakatDokumen1 halamanSOAL UAS MK. Kesehatan MasyarakatRudy Addailami, SKMBelum ada peringkat
- Data Per Kec - BireuenDokumen34 halamanData Per Kec - BireuenRudy Addailami, SKMBelum ada peringkat
- Proposal Upaya Menurunkan Angka Kematian IbuDokumen52 halamanProposal Upaya Menurunkan Angka Kematian IbuLeo Fernando100% (3)
- 5110 Pemerintah Kab. BireuenDokumen40 halaman5110 Pemerintah Kab. BireuenRudy Addailami, SKMBelum ada peringkat