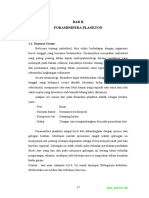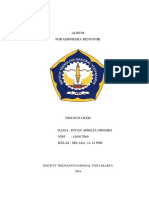Laporan Resmi Praktikum Mikropalentologi
Laporan Resmi Praktikum Mikropalentologi
Diunggah oleh
NinagstinaJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Laporan Resmi Praktikum Mikropalentologi
Laporan Resmi Praktikum Mikropalentologi
Diunggah oleh
NinagstinaHak Cipta:
Format Tersedia
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang
Paleontologi berasal dari kata, Paleo yang berarti masa lampau/kuno dan
onthos yang berarti kehidupan kehidupan. Paleontologi adalah merupakan suatu
ilmu yang mempelajari sisa-sisa makhluk hidup purba, baik dari fosil-fosilnya
maupun jejak-jejak kehidupan yang telah mengalami proses pembatuan.
Sedangkan fosil adalah sisa-sisa dari kehidupan masa lampau ataupun segala
sesuatu yang menunjukkan kehidupan yang telah membatu dan yang paling muda
berumur pleistosen. Pada umumnya fosil ini terjadi pada lingkungan sedimen
Istilah Mikropaleontologi tidak lepas dari pengertian paleontologi.
Paleontologi adalah salah satu cabang geologi yang mempelajari tentang sisa-sisa
organisme purba, baik dari fosil-fosilnya maupun jejak-jejak kehidupan yang telah
mengalami proses pembatuan.
Fosil adalah sisa-sisa dari kehidupan masa lampau atau segala sesuatu
yang menunjukkan kehidupan yang telah membantu dan yang paling muda
berumur plistosein. Pada umumnya fosil ini terjadi di lingkungan sedimen, dalam
hal ini didalam batuan beku sama sekali tidak dijumpai fosil. Secara garis besar,
Paleontologi di bagi menjadi 2, yaitu :
Paleobotani: mempelajari sisa-sisa organisma purba yang berasal dari
tumbuh-tumbuhan.
Paleozoolog: mempelajari sisa-sisa organisma purba yang berasal dari
binatang.
Mikropaleontologi adalah cabang dari ilmu pada ilmu paleontologi yang
khusus mempelajari sermua sisa-sisa yang berukuran kecil sehingga pada
pelaksanaannya harus menggunakan alat bantu mikroskop. Contoh mikrofosil
adalah hewan foraminifera.
Foraminifera adalah merupakan mikrofosil yang sangat penting dalam
studi mikropaleontologi. Hal ini disebabkan karena jumlahnya yang sangat
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 1
melimpah pada batuan sedimen. Secara defenisi foraminifera adalah
organisme bersel tunggal yang hidup secara aquatik (terutama hidup di
laut), mempunyai satu atau lebih kamar-kamar yang terpisah satu dengan
yang lainnya oleh sekat-sekat (septa) yang ditembusi oleh lubang-lubang
halus (foramen).
Hewan foraminifera contohnya adalah plankton dan benthos, hidup pada
dasar laut. Plankton bentuk testnya adalah bulat dan susunan kamarnya
adalah trochospiral, sedangkan benthos bentuk testnya adalah pipih dan
susunan kamar planispiral. Kedua-duanya ini adalah merupakan bagian
dari fhilum protozoa. Pengertian Mikrofosil Menurut Jones (1936). Setiap
fosil (biasanya kecil) untuk mempelajari sifat-sifat dan strukturnya
dilakukan di bawah mikroskop. Umumnya fosil ukurannya lebih dari 5
mm namun ada yang berukuran sampai 19 mm seperti genus fusulina yang
memiliki cangkang- cangkang yang dimiliki organisme, embrio dari foil-
fosil makro serta bagian-bagian tubuh dari fosil makro yang mengamainya
menggunakan mikroskop serta sayatan tipis dari fosil-fosil, sifat fosil
mikro dari golongan foraminifera kenyataannya foraminifera mempunyai
fungsi/berguna untuk mempelajarinya
1. Foraminifera
Foraminifera sangat penting dalam geologi karena memiliki bagian yang keras
dengan ciri masiing-masing foram, antara lain :
a. Planktonik (mengambang), ciri-ciri :
-. Susunan kamar trochospiral
-. Bentuk test bulat
-. Komposisi test Hyaline
b. Benthonik (di dasar laut), ciri-ciri :
-. Susunan kamar planispiral
-. Bentuk test pipih
-. Komposisi test adalah aglutine dan aranaceous
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 2
Gambar 1.1 Skema Kehidupan & Kelimpahan Foraminifera di Laut
2. Morfologi Foraminifera
Bentuk luar foraminifera, jika diamati dibawah mikroskop dapat
menunjukkan beberapa kenampakan yang bermacam-macam dari cangkang
foraminifera, meliputi :
-. Dinding, lapisan terluar dari cangkang foraminifera yang berfungsi
melindungi bagian dalam tubuhnya. Dapat terbuat dari zat-zat organik yang
dihasilkan sendiri atau dari material asing yang diambil dari sekelilingnya.
-. Kamar, bagian dalam foraminifera dimana protoplasma berada.
-. Protoculum, kamar utama pada cangkang foraminifera.
-. Septa, sekat-sekat yang memisahkan antar kamar.
-. Suture, suatu bidang yang memisahkan antar 2 kamar yang berdekatan..
-. Aperture, lubang utama pada cangkang foraminiferra yang berfungsi
sebagai mulut atau juga jalan keluarnya protoplasma
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 3
C
C D A
B
D
A B
Keterangan : A : Proloculus D
B : Kamar D C
C : Aperture B
D : Suture
E : Umbilicus
A B
Susunan kamar foraminifera plankton dibagi menjadi :
Planispiral yaitu sifatnya berputar pada satu bidang, semua kamar terlihat
dan pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsal sama. Contoh:
Hastigerina
Trochospiral yaitu sifat berputar tidak pada satu bidang, tidak semua
kamar terlihat, pandangan serta jumlah kamar ventral dan dorsal tidak
sama. Contohnya : Globigerina.
Streptospiral yaitu sifat mula-mula trochospiral, kemudian planispiral
menutupi sebagian atau seluruh kamar-kamar sebelumnya. Contoh:
Pulleniatina.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 4
Gambar 1.2. Penampang Ventral, Dorsal dan Sentral Foraminifera
1.2 Maksud dan Tujuan
Maksud dari diadakannya praktikum mikropaleontologidi semester
keempat jurusan teknik Geologi STTNAS Yogyakarta adalah mendidik
mahasiswa agar mempunyai kemampuan dalam menguasai materi praktikum dan
mempunyai keterampilan dalan menggunakan atau meninditifikasi fosil secara
mikrosekopis. Penguasaan materi praktikum dapat diperoleh dari kuliah
mikropalentologi.
Tujuan dari diadakannya praktikum mikropalentologi di semester
keempat jurusan teknik Geologi STTNAS Yogyakarta adalah membantu
mahasiswa dalam praktikum di laboratorium palentologiataupun di lapangan
geologi sehingga mempunyai cukup bekal dalam menentukan kandungan suatu
fosil dalam sebuah singkapan atau batuan contohnya. Selain itu,dengan
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 5
mempunyai kemampuan penguasaan materi praktikum dapat digunakan di
kehidupan / lingkungan kerja nantinya sebagai seorang geologist yang handal
tentunya dan tentunya dapat mengentahui suatu umur batuan.
1.3 Metode
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam laporan praktikum ini,
penulis menggunakan metode sebagai berikut :
a. Metode Studi Pustaka
Metode studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang metode wawancara dan
observasi yang telah dilakukan. Pengumpulan informasi yang dibutuhkan
dilakukan dengan mencari referensi – referensi yang berhubungan dengan
penelitian yang dilakukan, referensi dapat diperoleh dari buku – buku atau internet
Metode penelitian secara garis besar dapat dibagi menjadu dua, yaitu :
1. Pekerjaan lapangan, yaitu pengambilan data singkapan batuan dan
pengambilan sampe untuk di teliti lebih lanjut.
2. Pekerjaan Laboratorium, yaitu proses pengamatan fosil menggunakan
mikroskop dan pemerian nama mikrofosil serta penentuan umur dan
lingkungan pengendapan
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 6
BAB II
DASAR TEORI
II. 1 Mikropaleontologi
Mikropalenteologi cabang ilmu palenteologi yang khusus membahas
semua sisa-sisaorganisme yang biasa disebut mikro fosil.yang dibahas antara lain
adalah mikrofosil,klasifikasi, morfologi, ekologi dan mengenai kepentingannya
terhadap stratigrafi.
Pengertian Mikrofosil Menurut Jones (1936) Setiap fosil ( biasanya kecil )
untuk mempelajari sifat-sifat dan strukturnya dilakukan di bawah mikroskop.
Umumnya fosil ukurannya lebih dari 5 mm namun ada yang berukuran sampai 19
mm seperti genus fusulina yang memiliki cangkang- cangkang yang dimiliki
organisme, embrio dari fosil - fosil makro serta bagian-bagian tubuh dari fosil
makro yang mengamainya menggunakan mikroskop sertasayatan tipis dari fosil-
fosil, sifat fosil mikro dari golongan foraminifera kenyataannyaforaminifera
mempunyai fungsi/berguna untuk mempelajarinya.
Foraminifera adalah organisme bersel tunggal (protista) yang mempunyai
cangkangatau test (istilah untuk cangkang internal). Foraminifera diketemukan
melimpah sebagai fosil,setidaknya dalam kurun waktu 540 juta tahun. Cangkang
foraminifera umumnya terdiri darikamar-kamar yang tersusun sambung
menyambung selama masa pertumbuhannya. Bahkan ada yang berbentuk paling
sederhana, yaitu berupa tabung yang terbuka atau berbentuk boladengan satu
lubang. Cangkang foraminifera tersusun dari bahan organik, butiran pasir
atau partikel-partikel lain yang terekat menyatu oleh semen, atau kristal CaCO3
(kalsit atauaragonit) tergantung dari spesiesnya.
Foraminifera yang telah dewasa mempunyai ukuran berkisar dari 100
mikrometer sampai 20 sentimeter. Penelitian tentang fosil foraminifera
mempunyai beberapa penerapan yang terus berkembang sejalan dengan
perkembangan mikropaleontologi dan geologi.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 7
Dari cara hidupnya dibagi menjadi 2 (dua) :
1. Pellagic (mengambang)
a. Nektonik (bergerak dilaut)
b. Lanktonik (bergerak pasif) mengikuti keadaan sekitarnya
2. Benthonic (pada dasar laut)
a. secile (mikrofosil yang menambat/menempel)
b. Vagile (merayap pada dasar laut)
Dari dua bagian itu digunakan pada ilmu perminyakan dimana dari kedua fosil itu
identik dengan hdrokarbon yang terdapat pada trap (jebakan). Dalam geologi
struktur dimana dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya sesar, kekar serta
lipatan.Foraminifera juga bermanfaat dalam biostratigrafi, paleoekologi,
paleobiogeografi, dan eksplorasi minyak dan gas bumi.
1. Biostratigrafi
Foraminifera memberikan data umur relatif batuan sedimen laut. Ada
beberapa alasan bahwa fosil foraminifera adalah mikrofosil yang sangat berharga
khususnya untuk menentukan umur relatif lapisan-lapisan batuan sedimen laut.
Data penelitian menunjukkan foraminifera ada di bumi sejak jaman Kambrium,
lebih dari 500 juta tahun yang lalu.Foraminifera mengalami perkembangan secara
terus-menerus, dengan demikian spesies yang berbeda diketemukan pada waktu
(umur) yang berbedabeda. Foraminifera mempunyai populasi yang melimpah dan
penyebaran horizontal yang luas, sehingga diketemukan disemua lingkungan laut.
Alasan terakhir, karena ukuran fosil foraminifera yang kecil dan pengumpulan
atau cara mendapatkannya relatif mudah meskipun dari sumur minyak yang
dalam.
2. Paleoekologi dan Paleobiogeografi
Foraminifera memberikan data tentang lingkungan masa lampau (skala
Geologi).Karena spesies foraminifera yang berbeda diketemukan di lingkungan
yang berbeda pula,seorang ahli paleontologi dapat menggunakan
fosil foraminifera untuk menentukanlingkungan masa lampau tempat foraminifera
tersebut hidup. Data foraminifera telah dimanfaatkan untuk memetakan posisi
daerah tropik di masa lampau, menentukan letak garis pantai masa lampau, dan
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 8
perubahan perubahan suhu global yang terjadi selama jaman es.Sebuah sampel
kumpulan fosil foraminifera mengandung banyak spesies yang masih
hidupsampai sekarang, maka pola penyebaran modern dari spesies-spesies
tersebut dapatdigunakan untuk menduga lingkungan masa lampau di tempat
kumpulan fosil foraminiferadiperoleh, ketika fosil foraminifera tersebut
masih hidup. Jika sebuah sampel mengandungkumpulan fosil foraminifera yang
semuanya atau sebagian besar sudah punah, masih ada beberapa petunjuk yang
dapat digunakan untuk menduga lingkungan masa lampau. Petunjuktersebut
adalah keragaman spesies, jumlah relatif dari spesies plangtonik dan
bentonik(prosentase foraminifera planktonik dari total kumpulan foraminifera
planktonik dan bentonik), rasio dari tipe-tipe cangkang (rasio Rotaliidae,
Miliolidae, dan Textulariidae), dan aspek kimia material penyusun cangkang.
Aspek kimia cangkang fosil foraminifera sangat bermanfaat karena
mencerminkansifat kimia perairan tempat foraminifera ketika tumbuh. Sebagai
contoh, perbandingan isotopoksigen stabil tergantung dari suhu air. Sebab air
bersuhu lebih tinggi cenderung untukmenguapkan lebih banyak isotop yang lebih
ringan. Pengukuran isotop oksigen stabil padacangkang foraminifera plangtonik
dan bentonik yang berasal dari ratusan batuan teras intidasar laut di seluruh dunia
telah dimanfaatkan untuk meme-takan permukaan dan suhu dasar perairan masa
lampau. Data tersebut sebagai dasar pemahaman bagaimana iklim dan arus
lauttelah berubah di masa lampau dan untuk memperkirakan perubahan-
perubahan di masa yangakan datang (keakurasiannya belum teruji).
3. Eksplorasi Minyak
Foraminifera dimanfaatkan untuk menemukan minyak bumi. Banyak
spesiesforaminifera dalam skala biostratigrafi mempunyai kisaran hidup yang
pendek. Dan banyak pula spesies foraminifera yang diketemukan hanya
pada lingkungan yang spesifik atau ter-tentu. Oleh karena itu, seorang ahli
paleontologi dapat meneliti sekeping kecil sampel batuanyang diperoleh selama
pengeboron sumur minyak dan selanjutnya menentukan umur geologidan
lingkungan saat batuan tersebut terbentuk.
Sejak 1920-an industri perminyakan memanfaatkan jasa penelitian
mikropaleontologidari seorang ahli mikrofosil. Kontrol stratigrafi dengan
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 9
menggunakan fosil foraminiferamemberikan sumbangan yang berharga dalam
mengarahkan suatu pengeboran ke arahsamping pada horison yang mengandung
minyak bumi guna meningkatkan produktifikasminyak. Selain ketiga hal tersebut
dia atas foraminifera juga memiliki kegunaan dalamanalisa struktur yang terjadi
pada lapisan batuan. Sehingga sangatlah penting untukmempelajari foraminifera
secara lengkap.
Dari cara hidupnya dibagi menjadi 2 :
1. Pellagic (mengambang)
a. Nektonic (bergerak aktif)
b. Lanktonic (bergerak pasif) mengikuti keadaan sekitarnya
2. Benthonic (pada dasar laut)
a. Secile (mikro fosil yang menambat/menepel)
b. Vagile (merayap pada dasar laut)
Dari dua bagian itu digunakan pada ilmu perminyakan dimana dari kedua
fosil ituidentik dengan hidrokarbon yang terdapat pada trap (jebakan). Dalam
geologi strukturdimana dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya sesar,
kekar serta lipatan.
II.1.1 Kegunaan Mikrofosil
Beberapa manfaat fosil antara lain sebagai berikut:
1. Dalam korelasi untu membantu korelasi penampang suatu daerah dengan
daerah lain baik bawah permukaan maupun di permukan.
2. Menentukan umur misalnya umur suatu lensa batu pasir yang terletak di
dalam lapisan serpih yang tebal dapat ditentukan dengan mikrofosil yang
ada dalam batuan yangmelingkupi.
3. Membantu studi mengenai spesies.
4. Dapat memberikan keterangan-keterengan palenteologi yang penting
dalam menyusunsuatu standar section suatu daerah.
5. Membantu menentukan batas-batas suatu transgresi/regresi serta tebal/tipis
lapisan.
Berdasarkan kegunaannya dikenal beberapa istilah, yaitu :
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 10
1. Fosil indeks/fosil penunjuk/fosil pandu
Yaitu fosil yang dipergunakan sebagai penunjuk umur relatif. Umumnya
fosil inimempuyai penyebaran vertikal pendek dan penyebaran lateral luas,
serta mudah dikenal.Contohnya : Globorotalina Tumida penciri N18 atau
Miocen akhir.
2. Fosil bathymetry/fosil kedalaman
Yaitu fosil yang dipergunakan untuk menentukan lingkungan kedalaman
pengendapan.Umumnya yang dipakai adalah benthos yang hidup di
dasar. Contohnya : Elphidium spp penciri lingkungan transisi.
3. Fosil horizon/fosil lapisan/fosil diagnosticYaitu fosil yang mencirikan
khas yang terdapat pada lapisan yang bersangkutan. Contoh : Globorotalia
tumida penciri N18.
4. Fosil lingkunganYaitu fosil yang dapat dipergunakan sebagai penunjuk
lingkungan sedimentasi. Contohnya: Radiolaria sebagai penciri
lingkungan laut dalam.
5. Fosil iklimYaitu fosil yang dapat dipergunakan sebagai petunjuk iklim
pada saat itu. Contohnya : Globigerina Pachyderma penciri iklim dingin.
II.1.2 Tahapan Penelitian Mikrofosil
1. Sampling
Sampling adalah proses pengambilan sampel dari lapangan. Jika untuk fosil
mikro maka yang diambil adalah contoh batuan. Batuan yang diambil haruslah
batuan yang masih dalam keadan insitu, yaitu batuan yang masih ditempatnya.
Fosil-fosil mikro yang terdapat dalam batuan, mempunyai bahan pembentuk
cangkang dan morfologi yang berbeda, namun demikian hampir seluruh
mikrofosil mempunyai satu sifat fisik yang sama, yaitu ukurannya yang sangat
kecil dan kadang sangat mudah hancur (getas). Sifat fisik yang demikan
menyebabkan adanya perlakuan khusus yang diperlukan dalam pengambilan
sampel. Sangat diperlukan ketelitian serta perhatian yang seksama dalam
pengambilan sampel, memisahkannya dari material lain, lalu menyimpannya di
tempat yang aman/terlindung dari kerusakan secara kimiawi dan fisik.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 11
Pengambilan sampel batuan di lapangan hendaknya dengan
memperhatikan tujuan yang akan dicapai. Untuk mendapatkan sampel yang baik
diperhatikan interval jarak tertentu terutama untuk menyusun biostratigrafi. Ada
beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengambilan sampel di lapangan,
yaitu :
Kriteria Pengambilan Batuan
Metode sampling
Kwalitas Sample
Jenis sampel
Fosil mikro pada umumnya dapat dijumpai pada batuan berfraksi halus.
Namun perlu diingat bahwa jenis-jenis fosil tertentu hanya dapat dijumpai pada
batuan-batuan tertentu. Kesalahan pengambilan sampel berakibat pada tidak
dijumpai fosil yang diinginkan. Fosil foraminifera kecil dapat dijumpai pada
batuan napal, kalsilutit, kalkarenit halus, batupasir karbonatan halus. Fosil
Foraminifera besar, dapat dijumpai pada Kalkarenit, dan Boundstone.
a. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel batuan
Kriteria-kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel batuan, yaitu :
1. Memilih sampel batuan insitu dan bukan berasal dari talus, karena
dikhawatirkan fosilnya sudah terdisplaced atau tidak insitu.
2. Batuan yang berukuran butir halus lebih memungkinkan mengandung fosil,
karena batuan yang berbutir kasar tidak dapat mengawetkan fosil. Batuan yang
dapat mengawetkan fosil antara lain batulempung (claystone), batuserpih
(shalestone), batunapal (marlstone), batutufa napalan (marly tuffstone),
batugamping bioklastik, batugamping dengan campuran batupasir sangat halus.
3. Batuan yang lunak akan memudahkan dalam proses pemisahan fosil.
4. Jika endapan turbidite diambil pada endapan berbutir halus, yang diperkirakan
merupakan endapan suspensi yang juga mencerminkan kondisi normal.
b. Metode Sampling
Metode Sampling, meliputi :
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 12
Spot Sampling
Spot Sampling adalah dengan interval tertentu, merupakan metoda terbaik untuk
penampang yang tebal dengan jenis litologi yang seragam, seperti pada lapisan
serpih tebal,
batu gamping dan batulanau. Pada metoda ini dapat ditambahkan dengan “channel
sample”
(parut sampel) sepanjang + 30 cm pada setiap interval 1,5 meter.
Channel Sampling (sampel paritan)
Channel Sampling dapat dilakukan pada penampang lintasan yang pendek (3-5 m)
pada suatu litologi yang seragam. Atau pada perselingan batuan yang cepat,
channel sample dilakukan pada setiap perubahan unit litologi. Spot Sampling juga
dilakukan pada lapisan serpih yang tipis atau sisipan lempung pada batupasir atau
batu gamping, juga pada serpih dengan lensa tipis batugamping.
Kwalitas Sampel
Pengambilan suatu contoh batuan untuk analisis mikropaleontologi harus
memenuhi
kriteria berikut ini :
- Bersih
Sebelum mengambil contoh batuan yang dimaksud, kita harus membersihkannya
dari lapisan-lapisan pengotor yang menyelimutinya. Bersihkan dengan pisau kecil
dari pelapukan ataupun akar tumbuh-tumbuhan, juga dari polen dan serbuk sari
tumbuh-tumbuhan yang hidup sekarang. Khusus untuk sampel pada analisa
palynologi, sampel tersebut harus terlindung dari udara terbuka karena dalam
udara banyak mengadung polen dan serbuk sari yang dapat menempel pada
batuan tersebut. Suatu cara yang cukup baik, bisa dilakukan dengan memasukkan
sampel yang sudah dibersihkan tersebut kedalam lubang metal/fiberglass yang
bersih dan bebas karat. Atau dapat juga kita mengambil contoh batuan yang agak
besar, baru kemudian sesaat akan dilkukan preparasi kita bersihkan dan diambil
bagian dalam/inti dari contoh batuan tersebut.
- Representif dan Komplit
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 13
Harus dipisahkan dengan jelas antara contoh batuan yang mewakili suatu sisipan
ataupun suatu lapisan batuan. Untuk studi yang lengkap, ambil sekitar 200 – 500
gram batuan sedimen yang sudah dibersihkan. Untuk batuan yang diduga sedikit
mengandung mikrofosil berat contohnya lebih baik dilebihkan. Sebaliknya pada
analisa nannoplankton hanya dibutuhkan beberapa gram saja untuk setiap
sampelnya.
- Pasti
Apabila sampel tersebut terkemas dengan baik dalam suatu kemasan kedap air
(plastik) yang diatasnya tertulis dengan tinta tahan air, segala keterangan penting
tentang sampel tersebut seperti nomor sampel, lokasi (kedalaman), jenis batuan,
waktu pengambilan dan sebagainya maka hasil analisa sampel tersebut akan pasti
manfaatnya.
c. Jenis-jenis Sampel
Secara garis besar, jenis sampel apat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :
Sampel permukaan (surface sample)
Sampel permukaan adalah sample yang diambil pada permukaan tanah. Lokasi
dan posisi stratigrafinya dapat diplot dalam peta. Sampel yang baik adalah yang
diketahui posisi stratigrafinya terhadap singkapan yang lain, namun terkadang
pada pengambilan sampel yang acak baru diketahui sesudah dilakukan analisa
umur. Sampel permukaan sebaiknya diambil dengan penggalian sedalam > 30 cm
atau dicari yang masih relatif segar (tidak lapuk).
Sampel bawah permukaan (sub surface sample)
Sampel bawah permukaan adalah sampel yang diambil dari suatu pengeboran.
Dari cara pengambilannya, sampel bawah permukaan ini dapat dipisahkan
menjadi 4 bagian, yaitu :
1. inti bor (core): seluruh bagian lapisan pada kedalaman tertentu diambil secara
utuh.
2. sampel hancuran (ditch-cutting): lapisan pada kedalaman tertentu dihancurkan
dan dipompa ke luar dan kemudian ditampung.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 14
3. sampel sisi bor (side-wall core): diambil dari sisi-sisi dinding bor dari lapisan
pada kedalaman tertentu.
4. Setiap pada kedalaman tertentu pengambilan sampel harus dicatat dengan
cermat dan kemungkinan adanya fosil-fosil runtuhan (caving).
2. Proses Penguraian Batuan (Secara Umum)
Karena fosil mikro terdapat dalam masa batuan, sehingga dalam penyajian
fosilnya harus dipisahkan dari masa batuan yang ada. Secara umum penyajian
fosil mikro meliputi tahap-tahap:
Proses Penguraian batuan, yaitu:
a. Penguraian batuan (fisika/kimia)
Proses penguraian secara fisik
Cara ini digunakan terutama untuk batuan sedimen yang belum begitu kompak
dan dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu :
Batuan sedimen ditumbuk dengan palu karet sampai menjadi pecahan-pecahan
dengan diameter 3-6 mm
Pecahan-pecahan batuan direndam dalam air
Kemudian direas-remas dalam air
Diaduk dengan mesin aduk atau alat pengaduk yang bersih
Dipanaskan selama 5-10 menit
Didinginkan
Umumnya batuan sedimen yang belum begitu kompak, apabila mengalami
proses-proses tersebut akan terurai.
Proses penguraian secara kimia
Bahan-bahan larutan kimia yang biasa digunakan dalam penguraian batuan
sedimen antara lain : asam asetat, asam nitrat dan hydrogen piroksida.
Penggunaan larutan kimia sangat tergantung dari macam butir pembentuk batuan
dan jenis semen. Oleh sebab itu, sebelum dilakukan penguraian batuan tersebut
perlu diteliti jenis butirannya, masa dasar dan semen. Hal ini dikerjakan dengan
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 15
seksama agar fosil mikro yang terkandung didalamnya tidak rusak atau ikut larut
bersama zat pelarut yang digunakan Contoh:
Batulempung dan Lanau: penguraian batuan dilakukan dengan menggunakan
larutan Hydrogen Pyroksida (H2O2)
b. Proses Pengayakan
Dasar proses pengayakan adalah bahwa fosil-fosil dan butiran lain hasil
penguraian terbagi menjadi berbagai kelompok berdasarkan ukuran butirnya
masing-masing yang ditentukan oleh besar lubang. Namun, perlu diperhatikan
bahwa tidak semua butiran mempunyai bentuk bulat, tetapi ada juga yang panjang
yang hanya bisa lolos dalam kedudukan vertikal. Oleh karena itu, pengayakan
harus digoyang sehingga dengan demikian berarti bahwa yang dimaksudkan
dengan besar butir adalah diameter yang kecil / terkecil Pengayakan dapat
dilakukan dengan cara basah dan cara kering :
Cara kering
Keringkan seluruh contoh batuan yang telah terurai
Masukkan kedalam ayakan paling atas dari unit ayakan yang telah tersusun baik
sesuai dengan keperluan
Mesin kocok dijalankan selama + 10 menit
Contoh batuan yang tertinggal di tiap-tiap ayakan ditimbang dan dimasukkan
dalam botol/plastik contoh batuan
Cara basah
Cara ini pada prinsipnya sama dengan cara kering, tetapi pada umumnya
menggunakan ayakan yang kecil. Pengayakan dilakukan dalam air sehingga
contoh batuan yang diperoleh masih harus dikeringkan terlebih dahulu.
c . Proses Pemisahan Fosil
Fosil-fosil dipisahkan dari butiran lainnya dengan menggunakan jarum. Untuk
menjagaagar fosil yang telah dipisahkan tidak hilang, maka fosil perlu disimpan di
tempat yang aman. Setelah selesai pemisahan fosil, penelitian terhadap masing-
masing fosil dilakukan. Alat dan bahan yang digunakan.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 16
3. Preparasi Fosil (Secara Spesifik)
Preparasi adalah proses pemisahan fosil dari batuan dan material pengotor
lainnya. Proses ini pada umumnya bertujuan untuk memisahkan mikrofosil yang
terdapat dalam batuan dari material-material lempung (matrik) yang
menyelimutinya. Untuk setiap jenis mikrofosil, mempunyai teknik preparasi
tersendiri. Polusi, terkontaminasi dan kesalahan dalam prosedur maupun
kekeliruan pada pemberian label, harus tetap menjadi perhatian agar mendapatkan
hasil optimum. Beberapa contoh teknik preparasi untuk foraminifera & ostracoda,
nannoplankton dan pollen dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
a. Foraminifera kecil & Ostracoda
Untuk mengambil foraminifra kecil dan Ostracoda, maka perlu dilakukan
preparasi dengan metoda residu. Metoda ini biasanya dipergunakan pada batuan
sedimen klastik halus- sedang, seperti lempung, serpih, lanau, batupasir
gampingan dan sebagainya.
Caranya adalah sebagai berikut, yaitu:
Ambil ± 100 – 300 gram sedimen kering.
Apabila sedimen tersebut keras-agak keras, maka harus dipecah secara perlahan
dengan menumbuknya mempergunakan lalu besi/porselen.
setelah agak halus, maka sedimen tersebut dimasukkan ke dalam mangkok dan
dilarutkan dengan H2O2 (10 – 15%) secukupnya untuk memisahkan mikrofosil
dalam batuan tersebut dari matriks (lempung) yang melingkupinya.
Biarkan selama ± 2-5 jam hingga tidak ada lagi reaksi yang terjadi.
Setelah tidak terjadi reaksi, kemudian seluruh residu tersebut dicuci dengan air
yang deras diatas saringan yang berukuran dari atas ke bawah adalah 30-80-100
mesh.
Residu yang tertinggal pada saringan 80 & 100 mesh, diambil dan kemudian
dikeringkan didalam oven (± 600 C).
Setelah kering, residu tersebut dikemas dalam plastik residu dan diberi label
sesuai dengan nomor sampel yang dipreparasi.
Sampel siap dideterminasi.
Alat dan bahan yang digunakan untuk preparasi foraminifera kecil dan ostracoda:
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 17
Saringan dengan 40 – 60 – 100 mesh
Wadah pengamatan mikrofosil.
b. Foraminifera besar
Istilah foram besar diberikan untuk golongan foram bentos yang memiliki
ukuranrelative besar, jumlah kamar relative banyak, dan struktur dalam kompleks.
Umumnya foram besar banyak dijumpai pada batuan karbonat khususnya
batugamping terumbu dan biasanya berasosiasi dengan algae yang menghasilkan
CaCO3 untuk test foram itu sendiri. Di Indonesia foraminifera bentos besar sangat
banyak ditemukan dan bisa digunakan untuk menentukan umur relatif batuan
sedimen dengan menggunakan zonasiforaminifera bentos besar berdasarkan
Adams (1970), dengan demikian untuk menganalisanya dilakukan dengan
mempergunakan sayatan tipis. Prosedurnya adalah sebagai berikut :
Contoh batuan yang akan dianalisis disayat terlebih dahulu dengan mesin
penyayat/gurinda.
Arah sayatan diusahakan memotong struktur tubuh foraminifera besar yang ada
didalamnya.
Setelah mendapatkan arah sayatan yang dimaksud, contoh tersebut ditipiskan
pada kedua sisinya. Poleskan salah satu sisi contoh tersebut dengan
mempergunakan bahan abrasif (karbondum) dan air.
Setelah itu, tempel sisi tersebut pada objektif gelas (ukuran internasional 43 x 30
mm) dengan mempergunakan Kanada Balsam.
Tipiskan kembali sisi lainnya hingga contoh tersebut menjadi transparan dan
biasanya ketebalan sekitar 30-50 μm.
Setelah ketebalan yang dimaksud tercapai, teteskan Kanada Balsam secukupnya
dan kemudian ditutup dengan “cover glass”. Beri label.
Sampel siap dideterminasi
c. Nannoplankton
Pengamatan dilakukan di bawah mikroskop optik. Dapat dilakukan dengan dua
metode preparasi, yaitu:
Quick smear-slide/metode poles
Smear slide/metode suspense
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 18
Ambil satu keping contoh batuan segar sebesar ± 10 gr., bersihkan dari kotoran
yang menempel dengan sikat halus.
Cungkil bagian dalam dari sampel tersebut dan letakkan cukilan tersebut di atas
objektif gelas.
Beri beberapa tetes aquades untuk melarutkan batuannya dan ratakan.
Buang kerikil-kerikil yang kasar yang tidak larut.
Panaskan dengan hot plate objektif gelas tersebut hingga larutan tersebut kering.
Setelah kering, bersihkan/tipiskan dengan cover glass supaya lebih homogen
dan tipis.
Biarkan mendingin, beri label, sampel siap dideterminasi.
Smear Slide / Metode suspensi
Membutuhkan waktu yang lama, namun hasilnya lebih baik.
Ambil contoh batuan dengan berat 10-25 gr. Bersihkan dan usahakan diambil
dari sampel yang segar.
Larutkan dalam tabung gelas dengan aquades dan sedikit Natrium bikarbonat
(Na2Co3).
Masukkan tabung tersebut kedalam ultrasonik vibrator ±1 jam tergantung pada
kerasnya sampel.
Saring larutan tersebut dengan mesh 200, kemudian tampung suspensi dan
butiran halusnya kedalam bejana gelas.
Biarkan suspensi tersebut mengendap.
Teteskan 1-2 tetes pipet kecil dari larutan tersebut di atas gelas objektif dan
panaskan dengan hot plate.
Setelah kering teteskan kanada balsam dan dipanaskan hingga lem tersebut
matang dan tutup dengan cover glass.
Dinginkan dan beri label.
Sampel siap dideterminasi.
d. Polen
Untuk melepaskan pollen/spora dari mineral-mineral yang melimgkupinya, dapat
dilakukan dengan beberpa tahap preparasi yang mebutuhkan ketelitian dan
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 19
ditunjang oleh fasilitas laboratorium yang lengkap, seperti cerobong asap, ruang
asam, tabung-tabung reaksi, sentrifugal dan sebagainya. Beberapa larutan kimia
yang dibutuhkan adalah: HCl, HF, KOH, dan HNO3
B. Penyajian Mikrofosil
Dalam penyajian mikrofosil ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu:
Observasi
Observasi adalah pengamatan morfologi rincian mikrofosil dengan menggunakan
miroskop. Setelah sampel batuan selesai direparasi, hasilnya yang berupa residu
ataupun berbentuk sayatan pada gelas objek diamati di bawah mikroskop.
Mikroskop yang dipergunakan tergantung pada jenis preparasi dan analisis yang
dilakukan. Secara umum terdapat tiga jenis mikroskop yang dipergunakan, yaitu
mikroskop binokuler, mikroskop polarisasi dan mikroskop scanning-elektron
(SEM).
Determinasi
Determinasi merupakan tahap akhir dari pekerjaan mikropaleontologis di
laboratorium, tetapi juga merupakan tahap awal dari pekerjaan penting
selanjutnya, yaitu sintesis. Tujuan determinasi adalah menentukan nama genus
dan spesies mikrofosil yang diamati, dengan mengobservasi semua sifat fisik dan
kenampakan optik mikrofosil tersebut.
Deskripsi
Berdasarkan observasi yang dilakukan pada mikrofosil, baik sifat fisik maupun
kenampakan optiknya dapat direkam dalam suatu deskripsi terinci yang bila perlu
dilengkapi dengan gambar ilustrasi ataupun fotografi. Deskripsi sangat penting
karena merupakan dasar untuk mengambil keputusan tentang penamaan
mikrofosil yang bersangkutan.
Ilustrasi
Pada tahap ilustrasi, gambar dan ilustrasi yang baik harus dapat menjelaskan
berbagai sifat khas tertentu dari mikrofosil itu. Juga, setiap gambar ilustrasi harus
selalu dilengkapi dengan skala ataupun ukuran perbesarannya.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 20
Penamaan
Seorang sarjana Swedia Carl Von Line (1707–1778) yang kemudian melatinkan
namanya menjadi Carl Von Linnaeus membuat suatu hukum yang dikenal
denganLaw Of Priority, 1958 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa nama
yang telah dipergunakan pada suatu individu tidak dipergunakan untuk individu
yang lain. Nama kehidupan pada tingkat genus terdiri dari satu kata sedangkan
tingkat spesies terdiri dari dua kata, tingkat subspecies terdiri dari tiga kata.
Nama-nama kehidupan selalu diikuti oleh nama orang yang menemukannya.
Contoh penamaan fosil sebagai berikut:
– Globorotalia menardi exilis Blow, 1998, arti dari penamaan adalah fosil hingga
subspesies
diketemukan oleh Blow pada tahun 1969
– Globorotalia ruber elogatus (D’Orbigny), 1826, arti dari n. sp adalah spesies
baru.
– Pleurotoma carinata Gray, Var Woodwardi Martin, arti dari penamaan adalah
Gray memberikan nama spesies sedangkan Martin memberikan nama varietas.
– Globorotalia acostaensis pseudopima Blow, 1969,s arti dari n.sbsp adalah
subspecies.
– Dentalium (s.str) ruteni Martin, arti dari penamaan adalah fosil tersebut sinonim
dengan dentalium rutteni yang diketemukan Martin.
– Globorotalia of tumd, arti dari penamaan ini adalah penemu tidak yakin apakah
bentuk tersebut betul Globorotalia tumida tetapi dapat dibandingkan dengan
spesies ini.
– Spaeroidinella aff dehiscen, arti dari penamaan tersebut adalah fosil ini
berdekatan (berfamily) dengan sphaeroidinella dehiscens. (aff = affiliation)
– Ammobaculites sp, artinya mempunyai bermacam-macam spesies
– Recurvoides sp, artinya spesies (nama spesies belum dijelaskan
II.2 Foraminifera
Keanekaragaman Foraminifera yang melimpah dan memiliki morfologi yang
kompleks, fosil Foraminifera berguna untuk biostratigrafi dan memberikan
tanggal relative yang akurat terhadap batuan. Sedangkan industri minyak sangat
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 21
tergantung pada Foraminifera yang dapat menentukan deposit minyak potensial
(Ryo, 2010). Fosil Foraminifera terbentuk dari elemen yang di temukan di laut
sehingga fosil ini berguna dalam paleoklimatologi dan paleoceanografi. Fosil
Foraminifera ini dapat digunakan untuk merekonstruksi iklim masa lalu dengan
memeriksa isotop stabil rasio oksigen dan sejarah siklus karbon dan produktivitas
kelautan dengan memeriksa rasio isotop karbon.
Selain itu, menurut Muhtarto dan Juana (2001), Foraminifera dapat
digunakan untuk menentukan suhu air laut dari masa ke masa sejarah bumi.
Semakin rendah suhu pada zaman mereka hidup maka semakin kecil dan semakin
kompak ukuran selnya dan lubang untuk protoplasma makin kecil. Dengan
mempelajari cangkang forams dari sampel yang diambil dari dasar laut dan
menghubungkan kedalaman sampel dengan waktu maka suhu samudra dapat
diperkirakan sepanjang sejarah. Hal ini membantu menghubungkannnay dengan
zaman es di bumi dan memahami pola cuaca umum yang terjadi di masa lalu.
Pada pola geografis fosil Foraminifera juga digunakan untuk
merekonstruksi arus laut. Ada beberapa jenis Foraminifera tertentu yang hanya
ditemukan di lingkungan tertentu sehingga ini dapat digunakan untuk mengetahui
jenis lingkungan di mana sedimen laut kuno disimpan (Ryo, 2010). Selain itu,
Foraminifera juga digunakan sebagai bioindikator di lingkungan pesisir termasuk
indicator kesehatan terumbu karang. Hal ini dikarenakan kalsium karbonat rentan
terhadap pelarutan dalam kondisi asam, sehingga Foraminifera juga terpengaruh
pada perubahan iklim dan pengasaman laut. Pada arkeologi beberapa jenis
merupakan bahan baku batuan. Beberapa jenis batu seperti Rijang, telah
ditemukan mengandung fosil Foraminifera. Jenis dan konsentrasi fosil dalam
sampel batu dapat digunakan untuk mencocokkan bahwa sampel diketahui
mengandung jejak fosil yang sama (Ryo, 2010).
Foraminifera adalah organisme satu sel yang memiliki cangkang kalsit dan
merupakan salah satu organisme dari kingdom protista yang sering dikenal
dengan rhizopoda (kaki semu). Foraminifera adalah kerabat dekat Amoeba, hanya
saja amoeba tidak memiliki cangkang untuk melindungi protoplasmanya. Jenis-
jenis Foraminifora begitu beragam. Klasifikasi Foraminifera biasanya didasarkan
pada bentuk cangkang dan cara hidupnya.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 22
Gambar 2.1 Siklus hidup Forsminifera, memperlihatkan perkembangan
seksual dan pembelahan diri ( Amstrong dan Brasier, 2005 ).
Berdasarakan cara hidupnya, foraminifera dibagi menjadi 3, yaitu:
1. Foraminifera plantonik
2. Foraminifera bentonik
3. Foraminifera besar
Berdasarkan bentuk cangkangnya, foraminifera terbagi menjadi 3, yaitu:
1. Arenaceous (Foraminifera bercangkang pasiran)
2. Porcelaneous (Foraminifera bercangkang gampingan tanpa pori)
3. Hyalin (Foraminifera bercangkang gampingan berpori)
Foraminifera bentik hidup di lapisan sedimen hingga kedalaman beberapa
puluh sentimeter, sedangkan Foraminifera planktonik hidup didaerah perairan.
Foraminifera planktonik tersebar luas di laut-laut terbuka dengan kedalam air
lebih dari 10 meter. Brdasarkan ukuran mikroskopis, kekerasan cangkang, serta
sebaran geografis dan geologisnya, jenis hewan ini sangat potensial untuk
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 23
digunakan sebagai petunjuk kondisi suatu lingkungan, baik pada masa kini
maupun masa lalu.
Gambar 2.2 foraminifera plangtonik Globigerinoides sacculifer
Cangkang foraminifera bentik memiliki ukuran yang berkisar antara 5 μ
hingga beberapa sentimeter. Foraminifera bentik memiliki bentuk cangkang yang
rumit dan memiliki arsitektur yang kompleks. Seperti misalnya:
Foraminifera bercangkang pasiran biasa ditemukan di lingkungan yang ekstrim
seperti perairan payau atau di perairan laut dalam. Disebut pasiran karena
kenampakkan permukaan cangkang terlihat kasar seperti taburan gula pasir.
Foraminifera bercangkang gampingan tanpa pori biasa hidup soliter dengan
membenamkan cangkangnya ke dalam sedimen kecuali bagian mulutnya
(aperture) yang muncul kepermukaan sedimen. Dinamakan Porselaneous karena
pada cangkang dewasa, kenampakan foraminifera porcellaneous tampak seperti
jambangan porselen dengan bentuk kamar bersegi atau lonjong.
Foraminifera gampingan berpori merupakan jenis yang memiliki variasi bentuk
cangkang sangat banyak seperti lampu kristal dengan ornamen rumit, bening dan
berkilau.
Cangkang foraminifera terbuat dari kalsium karbonat (CaCO 3) dan
fosilnya dapat digunakansebagai petunjuk dalam pencarian sumber daya minyak,
gas alam dan mineral. Selain itu karena keanekaragama dan morfologinya
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 24
kompleks, fosil Foraminifera juga berguna untuk biostratigrafi, dan dapat
memberikan tanggal relatif terhadap batuan. Beberapa jenis batu, seperti batu
gamping biasanya banyak ditemukan mengandung fosil foraminifera dengan cara
itu peneliti dapat mencocokan sampel batuan dan mencari sumber asal batuan
tersebut berdasarkan kesesuaian jenis fosil foraminifera yang dimilikinya.
II.2.1 Ciri Fisik
Secara umum tubuh tersusun oleh protoplasma yang terdiri dari endoplasma
dan ectoplsma. Alat gerak berupa Pseudopodia ( kaki semu ) yang berfungsi juga
untuk mencari makanan.
Gambar 2.3 : Bentuk umum dari foraminifera ( Amstrong dan Brasier, 2005 )
II. 2.2 Cangkang
Dalam mempelajari fosil foraminifera biasanya dilakukan dengan
mengamati cangkangnya. Hal ini disebabkan bagian lunaknya ( protoplasma )
sudah tidak dapat ditemukan. Cangkang Foraminifera tersusun oleh : dinding,
kamar, proloculus, septa, sutura dan aperture
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 25
Gambar 2.4 : Bagian – bagian dari cangkang foraminifera
a. Dinding
Merupakan lapiran terluar dari cangkang, dapat tersusun dari zat – zat organic
maupun material asing. Dinding cangkang foraminifera berdasarkan pada resen
fauna adalah :
Dinding Chitin / tektin : bentuk dinding paling primitip. Berupa zat
organic menyerupai zat tanduk, fleksibel dan transparan, berwarna kuning
dan tidak berpori. Contoh golongan Miliolidae.
Dinding Aglutin / Arenaceous : dinding yang tersusun oleh mineral asing.
Jika penyusunnya hanya butir – butir pasir disebut Arenaceous. Jika
banyak material seperti mika dsb,. Disebut Aglutin.
Dinding Silikaan : dinding ini jarang ditemukan , bias dari organism itu
sendiri atau mineral sekunder.
Dinding Gampingan : terdiri dari 4 tipe dinding, yaitu :
1. Dinding Porselen : tidak berpori, berwarna opak dan putih. Contoh :
Quinquwloculina.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 26
2. Dinding Hyaline : bersifat bening dan transparan serta berpori. Contoh :
Golongan Globigerinidae, Nodosaridae.
3. Dinding Granular : terdiri dari Kristal – Kristal kalsit granular, dalam
sayatan tipis agak gelap.
4. Dinding Kompleks : terdapat pada golongan Fusulinidae.
b. Kamar
Merupakan bagian dalam foraminifera dimana protoplasma berada. Bentuk
dari kamar dapat membulat sampai pipih. Antar kamar dipisahkan oleh septa di
bagian dalamnya, pada bagian luar disebut suture. Suturenya sendiri dapat
berbentuk lurus ( rectilinear ), melengkung atau tertekan.
Kamar pertama pada cangkang foraminifera disebut proloculum. Proloculum
dapat disusun hanya satu kamar atau duasampai tiga kamar yang berukuran sama.
Dibedakan dengan kamar berikutnya adalah pertambahan ukurannya yang lebih
besar pada kamar berikutnya.
Bagan sisi luar dari cangkang atau kamar – kamar disebut peri – peri. Pada genus
tertentu biasanya terdapat hiasan.
Susunan Kamar
Berdasarkan jumlah kamar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
Monothalamus, hanya terdiri dari satu kamar
Polythalamus, tersusun oleh jumlah kamar yang banyak.
Monothalamus :
Berdasarkan bentuknya di bagi menjadi beberapa :
- Bulat
- Botol
- Tabung
- Kombinasi botol dan tabung
- Planispiral dsb.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 27
Gambar 2.5 : Bentuk cangkang monothalamus : bulat ( Saccamina ), botol (
Lagena ), tabung ( Bathysiphon ), dan planispiral ( Ammodiscus ).
Polythalamus
Cangkang foraminifera disusun oleh lebih dari 1 kamar. Terdapat 3
jenis kamar susunan kamar, yaitu :
1. Uniserial, berupa satu baris susunan kamar yang seragam, contoh:
Nodosaria, dan Siphonogenerina.
2. Biserial, berupa dua baris susunan kamar yang berselang-seling, contoh:
Bolivina dan Textularia.
3. Triserial, berupa tiga baris susunan kamar yang berselang-seling, contoh:
Uvigerina dan Bulimina.
Berdasarkan keseragaman susunan kamar dikelompokkan menjadi:
1. Uniformed test: jika disusun oleh satu jenis susunan kamar, misal
uniserial saja atau biserial saja.
2. Biformed test: jika disusun oleh dua macam susunan kamar yang berbeda,
misal diawalnya triserial kemudian menjadi biserial. Contoh:
Heterostomella.
3. Triformed test: terdiri dari tiga susunan kamar yang berbeda. Contoh:
Valvulina.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 28
Gambar 2. 6: Bentuk cangkang Polythalamus ( Culiver, 1987)
c. Aperture
lobang utama pada cangkang yang biasanya terdapat pada bagian kamar
terakhir. Aperture berfungsi untuk keluarnya protoplasma dan memasukkan
makanan. Tidak semua foraminifera mempunyai aperture terutama foraminifera
besar.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 29
Gambar 2.7 : aperture
Aperture merupakan salah satu kunci untuk mengenali genus dari
foraminifera. Dapat dibedakan berdasarkan:
- Bentuk
- Posisi
- Sifat
Bentuk Aperture
1. Bulat sederhana, terletak diujung kamar terakhir. Contoh: Lagena,
Bathysiphon, dan Cornuspira.
2. Memancar (radiate), berupa lobang bulat dengan kanal-kanal yang
memancar dari pusat lobang. Contoh: Nodosaria, Dentalina, Saracenaria,
dan Planularia.
3. Phialine, berupa lobang bulat dengan bibir dan leher. Contoh: Uvigerina,
Amphicoryna dan Marginulina.
4. Crescentic, berbentuk tapal kuda atau busur panah. Contoh: Nodosarella,
Pleurostomella, dan Turrilina.
5. Virguline/bulimine, Berbentuk seperti koma (,) yang melengkung.
Contoh: Virgulina, Bulimina, dan Cassidulina.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 30
6. Slit like, berbentuk sempit memanjang. Contoh: Sphaerodinella,
Sphaerodinellopsis, Pulleniatina.
7. Ectosolenia, aperture yang mempunyai leher pendek. Contoh Ectosolenia
dan Oolina.
8. Entosolenia, aperture yang mempunyai leher dalam (internal neck).
Contoh: Fissurina, Entosolenia.
9. Multiple, beberapa lobang bulat, kadang berbentuk saringan (cribrate)
atau terdiri dari satu lobang dengan beberapa lobang kecil (accessory).
Contoh: Elphidium, Globigerinoides, Cribrohantkenina.
10. Dendritik, berbentuk seperti ranting pohon, terletak pada septal- face.
Contoh: Dendritina.
11. Bergigi, berbentuk lobang melengkung dimana pada bagian dalamnya
terdapat sebuah tonjolan (single tooth). Contoh: Quinqueloculina dan
Pyrgo.
12. Berhubungan dengan umbilicus, berbentuk busur, ceruk ataupun
persegi, kadang dilengkapi dengan bibir, gigi-gigi, atau ditutupi selaput
tipis (bula). Contoh: Globigerina, Globoquadrina, dan Globigerinita.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 31
Gambar 2.8 : Aperture Foraminifera kecil ( Shrock & Twenhofel, 1956 )
Posisi Aperture
1. Aperture terminal, yaitu aperture yang terletak pada ujung kamar yang
terakhir. Contoh: Cornuspira, Nodosaria, Uvigerina.
2. Aperture on apertural face, yaitu aperture yang terdapat pada bagian
kamar yang terakhir. Contoh: Cribohantkenina, Dendritina.
3. Aperture peripheral, yaitu aperture yang memanjang pada bagian tepi
(peri-peri). Contoh: Cibicides.
4. Aperture umbilical, aperture yang terletak pada umbilikus (sumbu
perputaran). Sebagian besar plangtonik memiliki aperture ini.
Sifat Aperture
1. Aperture Primer : aperture utama, biasanya terdapat di kamar terakhir.
2. Aperture Sekunder : aperture lain yang dijumpai juga di kamar terakhir
3. Aperture Asesori : aperture yang merupakan hiasan saja, terletak di luar
kamar terakhir.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 32
d. Hiasan
Ornamentasi adalah struktur-struktur mikro yang menghiasi bentuk fisik
dari cangkang foraminifera. Ornamentasi ini kadang-kadang sangat khas untuk
cangkang foraminifera tertentu, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu
criteria dalam klasifikasi.
1. Keel, selaput tipis yang mengelilingi bagian periphery. Contoh:
Globorotalia, Siphonina.
2. Costae, galengan vertikal yang dihubungkan oleh garis- garis sutura yang
halus. Contoh: Bulimina, Uvigerina.
3. Spine, duri-duri yang menonjol pada bagian tepi kamar. Contoh:
Hantkenina, Asterorotalia.
4. Retral processes, merupakan garis sutura yang berkelok- kelok, biasa
dijumpai pada Amphistegina.
5. Bridged sutures, garis-garis sutura yang terbentuk dari septa yang
terputus-putus. Biasa dijumpai pada Elphidium.
6. Reticulate, dinding cangkang yang terbuat dari tempelan material asing
(arenaceous).
7. Punctate, bagian permukaan luar cangkang yang berpori bulat dan kasar.
8. Smooth, permukaan cangkang yang halus tanpa hiasan.
II.3 Foraminfera Plangtonik
Jumlah spesies foraminifera sangat kecil jika dibandingkan dengan
ribuan spesies dari golongan benthos. Meskipun jumlah spesiesnya sangat sedikit,
golongan ini mempunyai arti penting, terutama dalam penentuan umur batuan.
Golongan ini tidak peka terhadap perubahan lingkungan, sehingga bagus untuk
korelasi stratigrafi.
Secra umum cukup mudah untuk membedakan antar foraminifera kecil
plangtonik dengan foramininfera kecil benyhonik. Foraminifera plangtonik
memiliki cirri umum sebagai berikut :
- Test atau cangkang : bulat, beberapa agak prismatik.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 33
- Susunan kamar : pada umumnya terputar trochospiral.
- Komposisi test : gamping hyaline.
- Hidup di laut dengan mengambang.
Foraminifera planktonik jumlah genusnya sedikit, tetapi jumlah spesiesnya
banyak. Plankton pada umumnya hidup mengambang di permukaan laut dan fosil
plankton ini dapat digunakan untuk memecahkan masalah-masalah geologi, antara
lain :
Sebagai fosil petunjuk
Korelasi
Penentuan lingkungan pengendapan
Foraminifera plankton tidak selalu hidup di permukaan laut, tetapi pada
kedalaman tertentu ;
Hidup antara 30 – 50 meter
Hidup antara 50 – 100 meter
Hidup pada kedalaman 300 meter
Hidup pada kedalaman 1000 meter
Ada golongan foraminifera plankton yang selalu menyesuaikan diri
terhadap temperatur, sehingga pada waktu siang hari hidupnya hampir di dasar
laut, sedangkan di malam hari hidup di permukaan air laut. Sebagai contoh adalah
Globigerina pachyderma di Laut Atlantik Utara hidup pada kedalaman 30 sampai
50 meter, sedangkan di laut atlantik tengah hidup pada kedalaman 200 sampai 300
meter. Plangkton adalah organisme yang hidupnya melayang atau mengambang di
daerah pelagic. Namun demikian ada juga plankton yang memiliki kemampuan
renang cukup kuat sehingga dapat melakukan migrasi harian.
II.3.1 Morfologi Foraminifera Plangtonik
Dalam mendiskripsi foraminifera plangtonik baik dalam penentuan gesnus
maupun spesies harus diperhatikan antara lain :
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 34
A. Susunan Kamar
1. Planispiral : terputar pada satu bidang, semua kamar terlihat, pandangan dan
jumlah kamr ventral dan dorsal sama.
2. Trochospiral : terputar tidak pada satu bidang, tidak semua kamar terlihat,
pandangan pada ventral dan dorsal berbeda.
- Pandangan Ventral : jumlah kamar yang terlihat adalah putaran kamar
terakhir, terlihat adanya aperture utama, terlihat adanya umbilicus.
- Pangdang Dorsal : biasanya seluruh kamar bias terlihat, terlihat adanya
putaran, kamar pertama terlihat.
3. Streptospiral yaitu sifat mula-mula trochospiral, kemudian planispiral
menutupi sebagian atau seluruh kamar-kamar sebelumnya. Contoh:
Pulleniatina.
B. Bentuk
Bentuk test adalah bentuk keseluruhan dari cangkang foraminifera,
sedangkan bentuk kamar merupakan bentuk masing-masing kamar pembentuk
test. Penghitungan kamar foraminifera dimulai dari bagian dalam dan pada again
terkecil dimana biasanya mendekati aperturenya. Dibedakan menjadi dua yaitu
bentuk kamar dan bentuk test. Bentuk kamar dapat globular, rhomboid menyudut,
atau kerucut menyudut. Bentuk test dapat membulat atau ellips.
C. Suture
Suture adalah garis yang terlihat pada dinding luar test dan merupakan
perpotongan antara septa dan dinding kamar. Macam-macam bentuk suture
adalah:
- Tertekan (melekuk), rata atau muncul dipermukaan test.
- Lurus, melekuk lemah, sedang dan kuat.
- Suture yang mempunyai hiasan.
Dalam penentuan genus foraminifera, suture sangat berguna. Suture dapat tertekan
atau tidak. Pendeskripsian meliputi pandangan dorsal maupun vetral.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 35
Gambar 2.9 : bentuk Suture
D. Jumlah Kamar dan Putaran
Jumlah kamar sangat mempengaruhi penamaan, untuk itu perlu
dilakukan, terutama pada kamar terakhir. Selain itu diperhatikan pula
pertambahan ukuran kamar, apakah berangsur maupun berubah mendadak. Perlu
diperhatikan pula arah putaran apak searah jarum jam ( dextral ) maupun
berlawanan arah jarum jam ( sinistral ). Mengklasifikasikan foraminifera, jumlah
kamar dan jumlah putaran perlu diperhatikan karena spesies tertentu mempunyai
jumlah kamar pada sisi ventral yang hampir pasti, sedangkan pada sisi dorsal
akan berhubungan erat dengan jumlah putaran.
Jumlah putaran yang banyak umumnya mempunyai jumlah kamar yang
banyak pula, namun jumlah putaran itu juga jumlah kamarnya dalam satu spesies
mempunyai kisaran yang hampir pasti. Pada susunan kamar trochospiral jumlah
putaran dapat diamati pada sisi dorsal, sedangkan pada planispiral jumlah putaran
pada sisi ventral dan dorsal mempunyai kenampakan yang sama.Cara menghitung
putaran adalah dengan menentukan arah perputaran dari cangkang. Kemudian
menentukan urutan pertumbuhan kamar-kamarnya dan menarik garis pertolongan
yang memotong kamar 1 dan 2 dan pula menarik garis tegak lurus yang melalui
garis pertolongan pada kamar 1 dan 2.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 36
E. Aperture
Aperture adalah lubang utama dari test foraminifera yang terletak pada
kamar terakhir. Khusus foraminifera plankton bentuk aperture maupun variasinya
lebih sederhana. Umumnya mempunyai bentuk aperture utama interiomarginal
yang terletak pada dasar (tepi) kamar akhir (septal face) dan melekuk ke dalam,
terlihat pada bagian ventral (perut).
Macam-macam aperture yang dikenal pada foraminifera plankton:
1. Aperture Primer
a. Interiomarginal Umbilical : aperture yang terdapat pada bagian
umbilical atau pusat putaran
b. Interiomarginal Umbilical Extra Umbilical : aperture yang memanjang
dari umbilical dampai peri – peri ( tepi )
c. Interiomarginal Ekuatorial : aperture yang terletak di daerah ekuator ,
biasanya pad aputaran yang planispiral. Biasanya terlihat
padapandangan samping.
2. Aperture Sekunder
Merupakan lubang yang lain dari aperture primer dan lebih kecil, atau
lobang tambahan dari aperture primer.
F. Komposisi Test
Kebanyakan dari foraminifera plangtonik mempunyai dinding tess
gamping hyaline.
G. Hiasan
Hiasan adalah aneka struktur mikro yang menghiasi bentuk fisik cangkang
foraminifera. Hiasan ini merupakan cerminan dari upaya mikroorganisme ini
dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Berdasarkan letaknya hiasan dapat
dibagi menjadi:
1. Pada Suture, antara lain;
Suture bridge : bentuk suture menyerupai jembatan
Suture limbate : bentuk suture yang tebal
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 37
Retral processes : bentuk suture zig-zag
Raised bossed : suture yang berbentuk benjolan-benjolan
2. Pada Umbilicus, antara lain;
Deeply umbilicus : umbilicus yang berlubang dalam
Open umbilicus : umbilicus yang terbuka lebar
Umbilicuc plug : umbilicus yang mermpunyai penutup
Ventral umbo : umbilicus yang menonjol di permukaan.
3. Pada Peripheri, antara lain;
Keel : lapisan tepi yang tipis dan bening
Spine : bentuk luar daripada cangkang menyerupai duri
4. Pada Aperture, antara lain;
Lip atau rim : bibir aperture yang menebal
Flap : bibir aperture menyerupai anak lidah
Tooth : bentuk menyerupai gigi
Bulla dan Tegilla :Bulla berbentuk segi enam teratur, Tegilla berbentuk
segi enam tidak teratur .
5. Pada Permukaan Test, antara lain;
Smooth : permukaan yang licin
Punctate : permukaan yang berbintik-bintik
Reticulate : permukaan seperti sarang madu
Pustucolate : permukaan dipenuhi oleh tonjolan-tonjolan bulat
Hiasan sangat penting karena sangat khas pada genus tertentu. Misal Spine khas
pada Hantkenina, Keel pada Globorotalia.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 38
II.3.2 Sistematika Foraminifera Plangtonik
Terdapat 3 famili yang sering dijumpai pada foraminifera plangtonik (
Cushman, 1950 ). Ketiga family tersebut adalah Globigerinidae, Globorotalidae
dan Hantkeninidae. Jumlah genus sekitar 23.
A. Famili Globigerinidae
Trochoid, aperture umbilikal, pada kamar terakhir cenderung
planispiral, test tersusun zat gampingan, permukaan test kasar berstruktur
cancellate, sebagian besar memiliki duri-duri halus, aperture biasanya besar.
Muncul sejak Kapur Awal sampai sekarang. Genus yang masuk dalam famili ini
adalah: Globigerina, Globigerinoides, Globigerinatella, Globigerinella,
Globogerinelloides, Hastigerina, Hastigerinella, Orbulina, Pulleniatina,
Sphaeroidinella, Candeina, dan Candorbulina.
1. Genus: Globigerina d’Orbigny 1826
Test terputar trochoid, kamar globular, komposisi gampingan, aperture
pada bagian ventral membuka ke umbilical dan berbentuk koma. Muncul: Kapur –
Resen.
Gambar 2.10 : Globigerina Bulloides
2. Genus: Globigerinoides Cushman, 1927
Secara fisik hampir menyerupai globigerina, namun memiliki aperture
sekunder/tambahan pada bagian dorsal. Muncul: Tersier – Resen.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 39
Gambar 2.11 : Globigerinoides Ruba
3. Genus: Hastigerina Thomson, 1876
Pada awal putaran trochoid, pada kamar akhir planispiral-involute,
gampingan kuat, memiliki ornamen duri yang kasar dan pipih serta memusat pada
kamarnya. Muncul: Miosen – Resen.
Gambar 2.12 : Hastigerina Parapelagica
4. Genus: Orbulina d’Orbigny, 1839
Test pada awalnya menyerupai Globigerina, namun dalam
perkembangan kamar terakhir menutupi hampir semua kamar-kamar sebelumnya.
Tidak mempunyai aperture yang nyata. Muncul: Miosen – Resen.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 40
Gambar 2.13 : Urbulina Universa
5. Genus: Pulleniatina, Cushman, 1927
Test pada awalnya menyerupai Globigerina, dengan dinding cancellate
serta spine halus, involute, aperture lonjong – busur pada dasar kamar Muncul:
Tersier Akhir – Resen.
Gambar 2.14 : Pullenia Obliquiloculata
6. Genus: Sphaeroidinella Cushman, 1927
Test pada awalnya menyerupai Globigerina, dinding cancellate kasar
dengan spine halus. Dua atau Tiga kamar terakhir terpisahkan dengan jelas.
Muncul: Miosen – Resen.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 41
Gambar 2.15 : Sphaeroidina Dehiscens
B. Famili Globorotalidae
Trochoid rendah, bentuk test ellips bikonvek – planokonvek, dengan
bentuk kamar beberapa bulat sebagian rhomboid. Aperture umbilical ekstra
umbilikal ( dari umbilikal sampai peri – peri ), berbentuk busur. Test tersusun zat
gampingan, permukaan test halus, sebagian besar memiliki duri-duri halus.
Jumlah kamar akhir (pandangan ventral) lebih dari 4. Muncul sejak Kapur Awal
sampai sekarang. Genus yang masuk dalam famili ini adalah: Globorotalia dan
Globotruncana.
1. Genus Globorotalia Cushman, 1927
Test trochoid rendah, berbentuk bikonvek. Kadang mempunyai hiasan
keel pada peri – peri, kamar sub globular s.d. sub rhomboid. Aperture
interomarginal umbilical ekstra umbilical.
Gambar 216 : Globorotalia Scitula
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 42
2. Genus Globotruncana Cushman, 1927
Test trochoid pada awalnya, bentuk kamar membulat, pandangan dorsal dan
ventral datar atau cembung, hiasan keel, aperture umbilical.
Gambar 2.17 : Globotruncana Marianosi
C. Famili Hantkeninidae
1. Genus Hantkenina Cushman, 1927
Test planispiral dengan putaran tertutup, secara umum involute, dinding
gampingan, hiasan berupa tanduk pada setiap kamar.
Gambar 2.18 : Hantkenina Alabamensis
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 43
II.4 Foraminifera Benthonik
Fosil foraminifera benthonik sering dipakai untuk penentuan lingkungan
pengendapan, sedangkan fosil foram benthonik besar dipakai untuk penentuan
umur. Fosil benthonik ini sangat berharga untuk penentuan lingkungan purba.
Foraminifera benthos adalah salah satu golongan fosil foraminifera yang
dikelompokkan berdasarkan cara hidup nya yaitu hidup secara benthonik didasar
laut. Kebanyakan dari foram – foram penghuni dasar laut termasuk golongan vagil
benthos, yang dapat bergerak di dasar laut dengan menggunakan pseopodia.
Disamping bentuk – bentuknya yang vagil juga jenis – jenisnya yang
menunjukkan adanya pergerakan pada tingkat permulaan hidupnya dan kemudian
menjadi sesile pada tingkat terakhir hidupnya.
Golongan ini hidup di dasar laut mulai dari tepi sampai kedalaman lebih
dari 4000 m, cangkang nya terditi dari polythalamus Test dan monothalamus Test.
Sedangkan komposisi penyusun cangkangnya terdiri dari aglutin dan arenaceous,
umumnya foraminifera jenis ini peka terhadap perubahan lingkungan, karena itu
golongna ini sering dipakai sebagai indikator untuk menentukan lingkungan
pengendapan.
Dasar laut dapat dibagi menjadi zona – zona bathyametric, yaitu:
Zona lithoral : Antara garis pasang dan garis lurus
Zona neritik : Antara kedalaman 0 – 200 m
Zona bathyal : Antara kedalaman 200 – 4000 m
Zona abysal : Antara kedalaman 4000 – 6000 m
Zona hadal : Lebih dari 6000 m
Dari setiap zona – zona tersebut biasanya dihuni oleh species – species yang
tertentu, karena itulah golongan ini baik untuk penentuan lingkungan
pengendapan. Beberapa petunjuk yang dapat dipergunakan:
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 44
Golongan milliolif yang siliceous, smiliamina fusca, dan jenisaraneceous
yang sederhana seperti ammotium jadamina, rhopax dan trochaminam,
merupakan populasi didaerah rawa- rawa (Pheleger, 1960. bandy, 1963).
Jumlah species menurun dari zona bathyal kearah zona hadal.
Jumlah species dan genus naik dari facies paralis menuju kelaut terbuka
hingga zona bathyal(Shandy dan Arnal, 1960).
Golongan pocellaneous, terutama milliolidae banyak ditemukan di laut –
laut tertutup (inshore seas) pada daerah tropis.
Pada zona abysal populasi foraminifera gampingan menjadi kurang
(minor) bahkan hampir sama sekali tidak ada, sehingga terdiri dari
golongan
Secara umum cukup mudah untuk membedakan antara foraminifera benthonic
dengan foraminifera plangtonik. Foraminifer benthonic mempunyai cirri umum
sebagai berikut :
- Test atau cangkang : bulat, beberapa agak prismatic
- Susunan kamar : sangat bervariasi
- Komposisi test : gamping hyaline, arenaceous, silikaan Hidup di laut pada
dasar substratum
-
II.4.1 Morfologi Foram Plangtonik
Dalam mendiskripsi foraminifera benthonic baik dalam penentuan
genus maupun spesies harus memperhatikan antara lain :
A. Susunan Kamar
Berdasarkan jumlah kamar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
Monothalamus, hanya terdiri dari satu kamar
Polythalamus, tersusun oleh jumlah kamar yang banyak.
Monothalamus
Tersusun oleh satu kamar, dapat dibedakan atas berikut :
- Bulat : Saccamina
- Botol : Lagena
- Tabung : Bathysiphon
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 45
- Terputar Planispiral : Ammodiscus
Gambar 2.19 : Susunan kamar monothalamus : bulat ( Saccamina ), botol (
Lagena ), tabung ( Bathysiphon ), dan planispiral ( Ammodiscus ).
Polythalamus
Cangkang foraminifera disusun oleh lebih dari 1 kamar. Terdapat 3
jenis kamar susunan kamar, yaitu :
4. Uniserial, berupa satu baris susunan kamar yang seragam, contoh:
Nodosaria, dan Siphonogenerina.
5. Biserial, berupa dua baris susunan kamar yang berselang-seling, contoh:
Bolivina dan Textularia.
6. Triserial, berupa tiga baris susunan kamar yang berselang-seling, contoh:
Uvigerina dan Bulimina.
Berdasarkan keseragaman susunan kamar dikelompokkan menjadi:
4. Uniformed test: jika disusun oleh satu jenis susunan kamar, misal
uniserial saja atau biserial saja.
5. Biformed test: jika disusun oleh dua macam susunan kamar yang berbeda,
misal diawalnya triserial kemudian menjadi biserial. Contoh:
Heterostomella.
6. Triformed test: terdiri dari tiga susunan kamar yang berbeda. Contoh:
Valvulina.
Susunan kamar uniserial dapat berkembang kedalam bentuk test :
Planispiral : terputarpada satu bidang, semua kamar terlihat, pandangan
dan jumlah kamar ventral dan dorsal sama. Contoh : Elphidium,
Amphistegina, dsb
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 46
Lurus : tidak terputar, dapat mempunyai leher atau tidak. Contoh
Nodosaria, Nodogerina, dsb
Melengkung : Berbrntuk kurva. Contoh : Dentalina
B. Bentuk
Dibedakan menjadi dua yaitu bentuk kamar dan bentuk test. Bentuk
kamar dapat globular, rhomboid menyudut atau kerucut menyudut. Bentuk test
dpat membulat atau elips.
C. Komposisi Test
Kebanyakan foraminifera benthonic mempunyai dinding test gamping
hyaline, porselen dan arenacous.
D. Aperture
Aperture foraminifera benthos dengan foraminifera plankton berbeda. Aperture
foraminifera benthos dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi, yaitu :
Aperture yang bulat sederhana.
Berbentuk bulat, sederhana, biasanya terletak pada ujung kamar akhir.
Contoh : Lagena dan Bathysipon.
Aperture yang memancar (radiate).
Merupakan sebuah lubang yang bulat dengan golongan-golongan yang memancar
dari pusat lubang.
Contoh : Nodosaria dan Dentalina.
Aperture Phialine.
Merupakan lubang bulat, mempunyai bibir (lip) dan leher (neck).
Contoh : Uvigerina dan Amphikoryna.
Aperture Crescentik.
Berbentuk tapal kaki kuda atau busur panah..
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 47
Contoh : Nodosarella dan Pleurostomella.
Aperture Virguline dan Bulimine.
Berbentuk seperti koma (,) yang melengkung.
Contoh : Virgulina dan Bulimina.
Aperture yang slit-like.
Merupakan Aperture yang membentuk lubang sempit yang memanjang.
Contoh : Sphaeroidinella dan Pullenia.
Aperture Ectosolenia.
Aperture yang memiliki leher yang pendek.
Contoh : Ectosolenia dan Oolina.
Aperture Entosolenia.
Aperture yang mempunyai leher dalam (internal neck).
Contoh : Fissurina dan Entosolenia.
Aperture Multiple, Cribrate, Accesory.
Aperture yang terdiri dari beberapa lubang bulat dan kadang-kadang
membentuk saringan (cribrate) atau terdiri dari satu lubang utama dan beberapa
lubang bulat yang lebih kecil (accesory).
Contoh : Elphidium dan Cribrostomu.
Aperture
Berbentuk seperti ranting pohon (dendrit) terletak pada “septal-face”.
Contoh : Dendritin.
Aperture yang bergerigi.
Berbentuk lubang yang melengkung dimana didalamnya terdapat tonjolan
menyerupai gigi (single tooth, bifid tooth).
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 48
Contoh : Pyrgo dan Quinquelokulina.
Aperture yang berhubungan dengan Umbilicus.
Biasanya merupakan lubang yang berbentuk busur, ceruk ataupun persegi kadang-
kadang dilengkapi dengan bibir (lip), gigi-gigi atau ditutupi dengan selaput tipism
(bulla).
E. Hiasan
Hiasan sangat penting karena sangat khas pada genus tertentu. Misal
bridged suture khas pada Ephildium, Retral Procrsses pada Amphistegina.
II.5 Foraminifera Besar
Foraminifera besar merupakan bagian yang dapat dengan mudah
dipisahkan secara fisik dari golongan foraminifera kecil (planktonik dan
bentonik). Di samping ukurannya yang berbeda, juga struktur kamar bagian
dalamnya lebih rumit dan kompleks sehingga memerlukan suatu preparasi khusus
(dengan sayatan tipis) dan observasi yanmg khusus pula (mempergunakan sinar
transmisi). Golongan ini merupakan penyusun batuan yang penting dan sebagian
besar merupakan unsur pembentuk batugambing atau gamping terumbu. Dengan
demikian untuk study tentang batuan karbonat klastik kasar maka foraminifera
besar memegang peranan penting dalam penentuan ekologi pengendapannya.
Yang perlu diperhatikan dalam pengamatan foraminifera besar adalah jenis
sayatan tipis yang dilakukan pada saat preparasi. Karena jenis sayatan sangat
mempengaruhi kenampakan fisik kamar-kamar bagian dalam fosil tersebut.
Beberapa jenis sayatan tipis yang mungkin terdapat dalam observasi foraminifera
besar dapat dilihat pada gambar berikut.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 49
Gambar 2.20. Kenampakan umum pada beberapa jenis sayatan tipis pada
foraminifera besar
Keterangan :
Sayatan median (ekuatorial, horizontal) adalah sayatan yang melalui
bagian tengah secara horizontal. Biasanya merupakan bentuk lingkaran.
Sayatan vertikal atau transversal adalah sayatan yang melalui bagian
tengah yang dipotong secara vertikal. Biasanya membentuk ellips yang
cembung di bagian tengah
Sayatan oblique adalah sayatan sembarang yang tidak melalui bagian
tengah fosil tersebut. Biasanya membentuk ellips yang
Sayatan tangensial adalah sayatan yang sejajar dengan sayatan median,
tetapi tidak melalui bagian tengahnya. Biasanya berbentuk lingkaran yang
lebih kecil dari sayatan median.
Dari jenis-jenis sayatan ini pengamatan mengenai struktur bagian dalam dari
kamar-kamar foraminifera besar dapat dilakukan di bawah mikroskop binokuler
dengan sinar transmisi.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 50
II.5.1 Morfologi Foram Besar
Morfologi foraminifera besar sangat rumit, sehingga diperlukan sayatan tipis
untuk dapat mengenali atau mengidentifikasi taksanya. Beberapa hal yang perlu
diperhatikan dalam pengamatan foraminifera besar : kamar, bentuk test, jenis
putaran dan ornamentasi struktur dalam.
A. Kamar
Jumlah kamar dari foraminifera besar sangat banyak dan terputar, serta
tumbuh secara bergradasi. Jenis kamar dapat dibedakan atas kamar embrional,
ekuatorial dan lateral. Pengenalan yang baik terhdap jenis kamar sangat
membantu dalam taksonomi
Gambar 2.21 : Jenis – jenis dan posisi kamar dalam foraminifera besar.
1. Kamar Embrional
Merupakan kamar yang tumbuh pertama kali atau dikenal sebagai
proloculus. Pada umumnya proloculus dijjumpai di bagian tengah,
namun beberapa genus terdapat di bagian tepi seperti Miogypsina. Kamar
embrional dpat dibedakan menjadi dua, yaitu : protoconch dan deutroconh.
Terkadang diantara kamar embrionik dengan kamar ekuatorial terdapat
nepionik, namun dalam pengamatan suli dikenali.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 51
Gambar 2.22 : Susunan kamar embrionik, a1) protoconh, a2) deutroconh, b1-4)
kamar – kamar nepionik
2. Kamar Ekuatorial
Kamar ini terdapat pada bidang ekuatorial. Jumlah kamar ekuatorial sangat
membantu untuk mengetahui jumlah putaran dari test foraminifera bear.
Jumlah putaran pada beberapa golongan menjadi pembeda diantar genus.
3. Kamar Lateral
Kamar lateral terdapat di atas dan di bawah dari kamar – kamar ekuatorial.
Identifikasi pada kamar ini ad pada tebal – tipisnya dinding kamar ( seta
filament ), selain itu pada beberapa genus sering dijumpai adanya stolon
yang menghubungkan rongga antar kamar. Jumlah kamar terkadang
memberikan pengaruh namn tidak terlalu signifikan.
B. Bentuk Test
Bentuk test adalah identifikasi awal yang dapat dikenali. Bentuk dasar
test dibedakan menjadi beberapa : diskoid, fusiform ( cerutu ), bintang dan
trigonal.
- Discoid
Dicirikan dengan sumbu putaran pendek dan sumbu ekuatorial
panjang. Mudah dikenali dengan bentuk reatof cembung atau
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 52
bikonvek. Contoh : genus : Nummulites, Discocyclina,
Lepidocyclina dan Camerina.
- Fusiform
Memiliki sumbu putaran yang lebih panjang dari sumbu ekuatorial.
Contoh genus adalah Fussulina, Alveolina dan Schwagerina.
- Bintang
Dicirikan bertumbuhnya kamar ke berbagai arah dengan tidak
teratur. Sangat sedikit genus yang mempunyai bentuk test seperti
ini, contohnya Asterocyclina.
- Trigonal
Dicirikan dengan pertumbuhan kamar anular membentuk segitiga.
Kamar embrional biasanya terdapat di bagian tepi. Contoh :
Miogypsina.
Gambar 2.23 : Bentuk – bentuk dasar test foraminfera besar
1. Taksonomi Foram Besar
A. Golongan Orbioidae
Merupakan kelompok Lepidorbitoides, Orbitoicyclina dan
Lepydocyclina, cirri fisik :
- Test besar, lenticular atau discoidal, biconcave.
- Berkamar banyak, dihubungkan dengan stolon ( berpori – pori
berbentuk tabung ).
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 53
- Dinding lateral mempunyai pori – pori dan tebal, dimana terdapat
kamar – kamar lateral dan pilar – pilar.
Gambar 2.24 : macam – macam bentuk kamar Lepidocyclina sebagai penentu
spesies.
B. Golongan Camerinidae
a. Sub Famili Camerininae
Merupakan kelompok Nummulites, Pellatispira, Operculina,
Operculinoides, dan Assilina. Bentuk test umumnya besar, lenticular, discoidal,
planispiral dan bilateral simetris. Test tersusun oleh zat – zat gampingan.
Gambar 2.25 : Genus Operculina
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 54
b. Sub Famili Heterostegininae
Merupakan kelompok Heterostegina, Spiroclypeus, dan Cycloclypeus.
Bentuk test umumnya lenticular, discoidal, planispiral. Dinding licin, kadang –
kadang granulated. Genus tertentu tidak mempunyai kamar – kamar lateral.
Gambar 2.26 : Genus Heterostegina
C. Golongan Miogypsinidae
Kelompok dari Miogypsina dan Miogypsinoides. Bentuk test pipih,
segitiga atau asimetris. Kmar embrionik terletak dipinggir atau dipuncak, dengan
protoconch dan deutroconch yang hamper sama besar. Memiliki pilar – pilar yang
jelas.
Gambar 2.37 : Genus Miogypsina
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 55
D. Golongan Discocyclinidae
Merupakan kelompok Discocyclina. Golongan ini dicirikan dengan
bentuk bentuk test discoid atau lenticular. Pada jenis yang megalosfeer kamar
embrionik biasanya biloculer terdiri atas protoconch dan deutroconch. Sedangkan
pada jenis mikrosfeer kamar embrionik terputar secara planispiral.kamar – kamar
lateral dibatasi oleh septa –septa.
Gambar 2.28 : Genus Discocyclina
E. Golongan Fusulinidae
Golongan ini umumnya punah, muncul pada Paleozoik Atas dan
Mesozoik. Golongan ini dicirkan dengan bentuk putaran yang fusiform.
Gambar 2.29 : Genus Fusulinidae
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 56
II.6 Aplikasi Mikropalentologi
Mikrofosil khususnya foraminifera memiliki nilai kegunaan dibidang
geologi yang sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh sifat keterdapatnya yang
dijumpai diahmpir semua batuan sedimen yang mengandung karbonat.
Penggunaan data yang sering digunakan adalah untuk penentuan umur termasuk
penyusunan biostratigrafi dan penentuan lingkungan pengendapan.
II.6.1 Penentuan Umur
Penentuan umur batuan dengan foraminifera dan mikrofosil yang lain
memiliki bebrapa keuntungan, yaitu :
- Mudah, murah dan cepat
- Didukung oleh publikasi yang banyak
- Banyak digunakan di berbagai eksplorasi minyak bumi
- Keterdapatannya pada hamper semua batuan sedimen yang mengandung
unsure karbonat.
a. Biozonasi
Terdapat beberapa satuan biostratigarfi seperti :
- Zona Kumpulan ( Assemblage )
Yaitu penentuan biozonasi yang berdasarkan atas sekumpulan beberapa
takson yang muncul bersamaan. Pada penarikan ini tidak memperhatikan
umur dari masiing – masing takson. Kegunaan zona kumpulan ini untuk
penentuan lingkungan pengendapan. Penamaan zona diambil dari satu atau
lebih takson yang menjadi penciri utamanya. Misal : Zona Amphistegina
Lesonii.
- Zona Interval
Yaitu penentuan biozonasi berdasarkan kisaran stratigrafi dari takson – takson
tertentu. Penarikan batas dilakukan dengan meliahat kemunculan awal dan
kemunculan akhir dari suaru atau lebih takson yang ada. Pada batas bawah
ditarik berdasarkankemunculan awal dari suatu takson yang muncul paling
akhir, sedangkan batas atas ditarik berdasarkan kemunculan akhir dari suatu
takson yang paling dahulu punah.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 57
- Zona Kelimpahan ( Abudance atau Acme )
Yaitu penentuan biozonasi yang didasarkan atas perkembangan jumlah
maksimum dari suatu takson yang terdpat pada lapisan batuan. Zona
kelimpahan dapat digunakan untuk petunjuk kronostratigrafi dari tubuh
lapisan batuan
- Zona Selang ( barren Interval )
Yaitu penentuan biozonasi yang didasarkan pada selang antara dua
biohorison. Batas bawah atau atas suatu Zona Selang ditentukan oleh horizon
pemunculan awal atau akhr takson- takson penciri.
Gambar 2.30 : Berbagai macam bizonasi ( Amstrong dan Brasier, 2005 )
a. Biozonasi Foraminifera Besar
Biozonasi ini mempunyai kelemahan berupa keberlakuannya yang
beesifat local. Hal ini disebabkan distribusi foraminifera besar yang tidak
cosmopolitan. Biozonasi ini membagi Zaman Tersier dalam beberapa zona yang
dinotasikan dalam huruf Ta ( Tersier awal ) sampai Th ( tersier Akhir ).
b. Biozonasi Foraminifera Kecil Plangtonik
Banyak digunakan, karena sifat foraminifera kecil plangtonik yang
cosmopolitan. Dapat untuk korelasi regional jarak jauh. Seluruh biozonasi
foraminifera plangtonik menggunakan datum pemunculan awal atau akhir.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 58
II.6.2 Penentuan Lingkungan Pengendapan
Salah satu kegunaan dari mikrofosil khususnya foraminifera adalah
untuk penentuan lingkungan pengendapan purba. Yang dimaksud dengan
lingkungan pengendapan adalah tempat dimana batuan sedimen tersebut
terendapkan, dapat diketahui dari aspek fisik, kimiawi dan biologis. Aspek
biologis inilah yang disebut denagn fosil.
Untuk dapat megetahui lingkungan pengedapannya dapat dapat
menggunakan fosil foraminifera kecil benthic. Beberapa fosil penciri lngkunagn
pengendapan adalah :
1. Habitat air Payau : mengandung foraminifera arenaceous seperti :
Ammotium, Trochammina dan Miliammia.
2. Habitat Laguna : fauna air payau masih dijumpai ditambah dengan
Ammonia dan Elphildium.
3. Habitat Pantai Terbuka : Lingkunagn dengan energy yang kuat.
Didominasi oleh fauna berukuran besar seperti : Elphidium spp, Ammonia
becarii dan Amphistegina.
4. Zona Neritik Dalam (0 – 30 m) : Elphildium, Eggerella avena dan
Textularia.
5. Zona Neritik Tengah (30 – 100 m) : Eponides, Cibicides, Robulus dan
Cassidulina.
6. Zona Neritik Luar (100 – 200 m) : Bolivina, Marginulina, Siphonina dan
Uvigerina.
7. Zona Bathyal Atas (200 – 500 m) : Uvigerina spp, Bulimina, Valvulineria,
Bolivia, dan Gyroidina soldanii.
8. Zona Bathyal Tengah (500 – 1000 m) : Cyclammia, Chilostomelia,
Cibicides wuellerstrofi dan Cibicides regosus.
9. Zona Bathyal Bawah (1000 – 2000 m) : Melonis barleeanus, Uvigerina
hispida, Uvigerina prergrina dan Oridorsalis umbonatus.
10. Zona Abyssal (2000 – 5000 m) : Melonis pompiloides, Uvigerina
ampulacea, Bullimina rostrata, Cibicides mexicanus, dan Eponides
tumidulus.
11. Zona Hadal ( > 5000 m) : Bathysiphon, Recurvoides turbinatus.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 59
BAB III
PEMBAHASAN
III.1 Diskripsi Morfologi Foraminifera
DISKRIFSI MORFOLOGI FORAMINIFERA
Nama : I made Widya Putra
Nim : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
Pendang Ventral Pandangan Dorsal Pandangan samping
No. Peraga Keterangan Gambar
Filum : Protozoa 1. Arperture
Klas : Foraminifera 2. Proloculus
Ordo : 3. Kamar
Sup. Famili : 4.Dinding
Famili : Rotaliidae
Genus : Eyronida
Spesies : Ryronida orbiculent
Diskrifsi
a. Dinding : Gamping Hyalin
b. Bentuk test : Plano-convex
c. Bentuk kamar : Rombohid Menyudut
d. Susunan kamar : Polythalamus
e. Jumlah kamar :7
f. Pertumbuhan Kamar : Gradasi
g. Arah Putran Kamar : dextral
h. Arperture : bulat Sederhana
i. Hiasan : smooth
j. Lngkungan Pengendapan : Transisi
k. Jenis : Bentonik
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 60
DISKRIFSI MORFOLOGI FORAMINIFERA
Nama : I made Widya Putra
Nim : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
Pendang Ventral Pandangan Dorsal Pandangan samping
No. Peraga Keterangan Gambar
Filum : Protozoa 1. Arperture
Klas : Foraminifera 2. Proloculus
Ordo : 3.
Sup. Famili : 4.
Famili : Textulariidae
Genus : Begerina
Spesies :
Diskrifsi
a. Dinding : Gamping Hyalin
b. Bentuk test : Elips
c. Bentuk kamar : Bulat
d. Susunan kamar : Polythalamus
e. Jumlah kamar : 16
f. Pertumbuhan Kamar : cepat (uniserial - uniserial)
g. Arah Putran Kamar :-
h. Arperture : bulat Sederhana
i. Hiasan : smooth
j. Lngkungan Pengendapan : Transisi
k. Jenis : Bentonik
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 61
DISKRIFSI MORFOLOGI FORAMINIFERA
Nama : I made Widya Putra
Nim : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
Pendang Ventral Pandangan Dorsal Pandangan samping
No. Peraga Keterangan Gambar
Filum : Protozoa 1. Arperture
Klas : Foraminifera 2. Proloculus
Ordo : Astrothizina 3. Kamar
Sup. Famili : Phaldamminidae 4.Dinding
Famili : Batthysiphanime
Genus :
Spesies : Bathyshipon
Diskrifsi
a. Dinding : Gamping Hyalin
b. Bentuk test : Tabung
c. Bentuk kamar : Memanjang
d. Susunan kamar : Monothalamus
e. Jumlah kamar :1
f. Pertumbuhan Kamar : Cepat
g. Arah Putran Kamar :-
h. Arperture : bulat Sederhana
i. Hiasan : smooth
j. Lngkungan Pengendapan : Transisi
k. Jenis : Bentonik
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 62
III.2 Diskripsi Foraminifera Plangtonik
DISKRIFSI FORAMINIFERA PLANTONIK
PANDANGAN VENTRAL PANDANGAN PANDANGAN
DORSAL SAMPING
TAKSONOMI:
Filum : protozoa
Kelas :sarcodina
Ordo : foraminifera
Family : globogerinidae
Genus :globogerina
Spesies : globogerina bullodes
Deskripsi:
Fosil ini memiliki susunan kamar planispiral,dekstral dengan
bentuk kamar polytalamus bulat,jumlah kamar delapan di lihat dari
pandangn dorsal,memiliki aperture bulat sederhana,phialine,dan hiasan
punctuate,perkembangan kamar fosil ini yaitu gradasi dengan umur
jurasic-resent dan termaksud jenis dari foraminifera plangthonik.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 63
DISKRIFSI FORAMINIFERA PLANTONIK
Nama : I made Widya Putra
Nim : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
Pendang Ventral Pandangan Dorsal Pandangan samping
No. Peraga Keterangan Gambar
Filum : Protozoa 1. Arperture
Klas : Foraminifera 2. Proloculus
Ordo : 3. Kamar
Sup. Famili : 4.Dinding
Famili : Rotaliidae
Genus : Eyronida
Spesies : Ryronida orbiculent
Diskrifsi
a. Dinding : Gamping Hyalin
b. Bentuk test : Plano-convex
c. Bentuk kamar : Rombohid Menyudut
d. Susunan kamar : Polythalamus
e. Jumlah kamar :7
f. Pertumbuhan Kamar : Gradasi
g. Arah Putran Kamar : dextral
h. Arperture : bulat Sederhana
i. Hiasan : smooth
j. Lngkungan Pengendapan : Transisi
k. Jenis : Bentonik
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 64
DISKRIFSI FORAMINIFERA PLANTONIK
PANDANGAN VENTRAL PANDANGAN PANDANGAN
DORSAL SAMPING
TAKSONOMI :
Filum : protozoa
Kelas : sarcodina
Ordo :foraminifera
Family : globogerinidae
Genus : globogerina
Spesies : globigerina venezuelena
DESKRIPSI:
Fosil ini memiliki bentuk kamar politalamus,bulat dengan susunan
kamar planispiral,dekstral dan jumlah kamar empat di lihat dari pandangan
ventral, fosil ini juga memiliki aperture interior marginal amburacal serta hiasan
punctuate,perkembangan kamarnya cepat,kisaran hidup N.9-N.23.termaksud
dalam foraminifera plangthonik.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 65
III.3 Diskripsi Foraminifera Benthik
DISKRIFSI FORAMINIFERA BENTONIK
PANDANGAN VENTRAL PANDANGAN PANDANGAN
DORSAL SAMPING
TAKSONOMI:
Fillum : Foraminifera
Kelas : Nodosariata
Ordo : Nodosariida
Family : plectofrondiculuriidae
Genus : Plectofrondicularia
Spesies : Plectofrondicularia floridiana
DESKRIPSI:
Fosil ini memiliki bentuk kamar dan bentuktest tabung dengan susunan
kamar monotalamus dan jumlah kamar satu di lihat dari pandangan
samping,memiliki aperture terminal,bentuk sederhana,mempunyai hiasan keel
dengan lingkungan pengedapan laut neuritik atau laut dangkal,serta umurnya
masuk pada meosen-neogen.fosil ini termaksud dalam kelompok foraminifera
benthonic.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 66
DISKRIFSI FORAMINIFERA BENTONIK
Nama : I made Widya Putra
Nim : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
Pendang Ventral Pandangan Dorsal Pandangan samping
No. Peraga Keterangan Gambar
Filum : Protozoa 1. Arperture
Klas : Foraminifera 2. Proloculus
Ordo : Astrothizina 3. Kamar
Sup. Famili : Phaldamminidae 4.Dinding
Famili : Batthysiphanime
Genus :
Spesies : Bathyshipon
Diskrifsi
a. Dinding : Gamping Hyalin
b. Bentuk test : Tabung
c. Bentuk kamar : Memanjang
d. Susunan kamar : Monothalamus
e. Jumlah kamar :1
f. Pertumbuhan Kamar : Cepat
g. Arah Putran Kamar :-
h. Arperture : bulat Sederhana
i. Hiasan : smooth
j. Lngkungan Pengendapan : Transisi
k. Jenis : Bentonik
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 67
DISKRIFSI FORAMINIFERA BENTONIK
PANDANGAN PANDANGAN PANDANGAN
VENTRAL DORSAL SAMPING
TAKSONOMI :
Fillum : Protozoa
Kelas : Sarcodina
Ordo : Foraminifera
Family : Heterohelicidae
Genus : Nodogerinae
Spesies : Nodogerina advena
DESKRIPSI :
Fosil ini memiliki bentuk kamar yang bulat,dengan susunan kamar
polytalamus,uniserial,dengan test uniformed memiliki delapan kamar di
lihat dari pandangan samping,dan apeturenya terminal bentuk sederhana
serta hiasa smooth,lingkungan pengendapanya laut dangkal,umurnya
karbon-resent.fosil ini termaksud dalam kelompok foraminifera benthonic.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 68
III.4 Diskrifsi Foraminifera Besar
DISKRIFSI FORAMINIFERA BESAR
Nama : I Made Widya Putra
No. mhs : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
SAYATAN VERTIKAL SAYATAN HORISONTAL
No. Peraga : FB-15 keterangan gambar
Filum : Protozoa 1. protocon
Klas : sarcodino 2. Kamar nepionik
Ordo : foraminifera
Sup. Family :-
Family : comerilidae
Genus : Nummulites
Spesies : Disco
Diskrifsi vertikal
1. Jenis sayatan : Axial
2. Kamar : Embrionik
3. Bentuk Test : Discoid
4. Jumlah Putaran :-
5. Arah Putaran :-
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 69
DISKRIFSI FORAMINIFERA BESAR
Nama : I Made Widya Putra
No. mhs : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
SAYATAN VERTIKAL SAYATAN HORISONTAL
No. Peraga : FB-06 keterangan gambar
Filum : Protozoa 1. protocon
Klas : Scocaraina 2. Kamar Ekuatorial
Ordo : foraminifera
Sup. Family :
Family : Discocylinidae
Genus : Discocylina
Spesies : Discocylina sp
Diskrifsi Horisontal
1. Jenis sayatan : Ekuatorial
2. Kamar : Ekuatorial
3. Bentuk Test : Discoid
4. Jumlah Putaran : Banyak
5. Arah Putaran : Dextral
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 70
DISKRIFSI FORAMINIFERA BESAR
Nama : I Made Widya Putra
No. mhs : 410014142
Kelompok : jumat 09.15
SAYATAN VERTIKAL SAYATAN HORISONTAL
No. Peraga : GBT/14/763 keterangan gambar
Filum : Protozoa 1. protocon
Klas : Scocaraina 2. Kamar Ekuatorial
Ordo : foraminifera
Sup. Family :
Family : Discocylinidae
Genus : Discocylina
Spesies : Discocylina sp
Diskrifsi Horisontal
1. Jenis sayatan : Ekuatorial
2. Kamar : Ekuatorial
3. Bentuk Test : Discoid
4. Jumlah Putaran : Banyak
5. Arah Putaran :-
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 71
BAB IV
PENUTUP
Kesimpulan
Setelah melakukan pengamatan secara mikroskopis dari berbagai macam
mikrofosil serta kenampakannya dalam mikroskop maka praktikan dapat
menyimpulkan bahwa Foraminifera dari kelompok planktonik memiliki bentuk
yang tidak terlalu bervariasi cenderung tersusun oleh beberapa kamar saja
sehingga dalam membedakan foraminifera planktonik masih lebih muda
dibanding bentonik. Susunan kamar dari plankton juga tidak terlalu rumit
dibanding dengan susunan kamar benthos.
Dalam kehidupannya organisme ini ada yang hidup di dasar laut dengan
cara menambat di berbagai material yang ada dalam laut serta ada juga yang
bergerak secara pasif. Dari kehidupan organisme ini kita bisa mengetahui bahwa
planktonik yang hidup serta bergerak secara pasif ukuran serta bentuk tubuhnya
tidak terlalu beragam, berbeda dengan bentos yang hidup secara menambat di
dasar secara harfiah memperoleh makanan yang cukup dan dapat bergerak dengan
mudah sehingga ukuran tubuhnya lebih bervariasi dan tersusun oleh berbagai
bentuk kamar dan kedudukan aperture yang berbeda antara satu genus dangan
genus yang lain.
Susunan kamar foraminifera plankton dominan membulat hanya di
bedakan dari pandangan ventral serta dorsal dan samping, sedangkan dalam
bentos susunan kamar ada yang membulat ada pula yang keliatan memanjang.
Bentuk test dari foraminifera juga sangat beragam ada yang berukuran
tabular, irregular, zig – zag, conical, spherical dan masih banyak lagi. Septa dan
suture dalam foraminifera juga sangat beragam bentuknya terutama yang ditemui
pada foraminifera bentonik, aperture hampir sangat umum di jumpai pada semua
foraminifera serta menjadi hal yang tidak lepas dari susunan organisme
mikrofosil.
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 72
DAFTAR PUSTAKA
http://www.marinespecies.org/foraminifera/aphia.php?p=search. Diakses
pada tanggal 21 Juni 2015
Pandita. H., 2015, Buku Panduan Praktikum Mikropaleontologi,
Yogyakarta, hal 1-40
Adama, C. G, 1970. A Reconsideration of The East Indian Letter
Clasification of The Tertiary. Br. Mus. Nat. Hist. Bull. (Geo), ln 87 – 137
Blow, W.H., 1969. Late Middle Eocene to Recent Planktonic Foraminifera
Biostratigraph Cont. Planktonic Microfossil, Geneva, 1967, Pro Leiden,
E.J Bull v.1
Cushman, J.A., 1969 Foraminifera Their Clasification and Economic Use,
Cambridge, Massachusets, USA Harvard University Press
Kennett, J.P Srinivasan, M.S 1983, Neogene Planktonic Foraminifera.
Hucthison Ross Publishing Company, h.265
Maha, M., 1995. Biozonasi, Paleobatimetri dan Pemerian Siaternatis
Foraminifera Kecil Sumur TO-04, Sumur TO-08 dan Sumur -95, Daerah
Cepu dan sekitarnya, Cekungan Jawa Timur Utara, Thesis, ITB, Bandung
Phleger, F.B., 1951. Ecology of Foraminifera, Northwest Guff of Mexico,
The Geological Society of America, Memorial 46
Postuma, J.A., 1971. Manual of Planktonic Foraminifera, Amsterdam,
London, New York, Elsevier Publishing Company
Pringgopawiro. H., 1984. DiklatMikropaleontologi Lanjut, Laboratorium
Mikropaleontologi Jur. T. Geologi, ITB, Bandung
Subandrio. A., 1994, Study Paleobathymetry Cekungan Sumatera Utara
Subbcekungan Jambi dan Cekungan Barito, Thesis, ITB, Bandung
http://dokumen.tips/documents/preparasi-mikrofosil.html
http://rizalgunawan06.blogspot.com/2014/02/mikro-dan-makro-fosil.html
https://mwamir.wordpress.com/geologi/laporan-
praktikum/mikropaleontologi/
http://laporanp.blogspot.co.id/2010/02/bab-i-pendahuluan-1_07.html
http://geohaniez.blogspot.co.id/2010/12/mikropaleontologi-dan-
aplikasinya-dalam.html
http://geologistl.blogspot.co.id/2014/01/kegunaan-fosil.html
http://www.kamusq.com/2012/10/foraminifera-adalah-pengertian-
dan.html
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 73
KRITIK DAN SARAN
Menurut saya, dalam pelaksanaan praktikum Mikropaleontologi itu harus
di lakukan secara teliti dalam mendeskripsi segala sesuatu yang berhubungan
dengan fosil di mikroskop. Untuk itu kita perlu menerapkan sikap disiplin dalam
melakukan praktikum tersebut demi mencapai hasil yang kita inginkan.Untuk
mengidentifikasinya perlu panduan dan petunjuk yang jelas, namun yang lebih
penting adalah kemampuan dari diri kita untuk mengembangkannya.
Dalam laporan ini penulis mempunyai saran untuk rekan-rekan sesama
calon geologist yaitu “ Tetap semangat untuk belajar geologi “, terima kasih
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 74
LAMPIRAN
LAPORAN PRAKTIKUM MIKROPALEONTOLOGI 75
Anda mungkin juga menyukai
- Mikropal Acara1Dokumen17 halamanMikropal Acara1Muhammad Resky0% (1)
- Bab I Pendahuluan: Praktikum MikropaleontologiDokumen41 halamanBab I Pendahuluan: Praktikum MikropaleontologiAntonio zidaneBelum ada peringkat
- Rifqi Andi Naufal - Deskripsi Fosil Foraminifera PlanktonikDokumen5 halamanRifqi Andi Naufal - Deskripsi Fosil Foraminifera PlanktonikRifqi AndiBelum ada peringkat
- Laporan Analisis PlanktonikDokumen10 halamanLaporan Analisis PlanktonikBobo LajuBelum ada peringkat
- Laporan Acara 2Dokumen22 halamanLaporan Acara 2Reynaldi Dwi CahyoBelum ada peringkat
- Mikropal Acara1Dokumen19 halamanMikropal Acara1Sunrise HomeBelum ada peringkat
- Laporan Resmi Praktikum MikropalentologiDokumen79 halamanLaporan Resmi Praktikum Mikropalentologiwidya putra100% (1)
- Deksripsi Morfologi ForaminiferaDokumen39 halamanDeksripsi Morfologi ForaminiferaRyanNasrulBelum ada peringkat
- Laporan Acara 2 BentonikDokumen19 halamanLaporan Acara 2 BentonikMuh Fahmi AlkafBelum ada peringkat
- Akhmad Dwi Tular - Deskripsi Foraminifera BentonikDokumen7 halamanAkhmad Dwi Tular - Deskripsi Foraminifera BentonikAkhmad Dwi TularBelum ada peringkat
- IsnainiPermata PoriferaDokumen10 halamanIsnainiPermata PoriferaIsnaini PermataBelum ada peringkat
- Laporan Foraminifera BesarDokumen4 halamanLaporan Foraminifera BesarauzanBelum ada peringkat
- Artikel Prosedur Preparasi Foram KecilDokumen4 halamanArtikel Prosedur Preparasi Foram KecilarsarcanumBelum ada peringkat
- Materi FiksDokumen47 halamanMateri FiksLidya AprilitaBelum ada peringkat
- Brachiopoda Gerad HasdesDokumen4 halamanBrachiopoda Gerad HasdesRafiyan BondanBelum ada peringkat
- Bab Vi. Foraminifera Besar: Tinjauan UmumDokumen14 halamanBab Vi. Foraminifera Besar: Tinjauan UmumlindamahaditaBelum ada peringkat
- Lembar Deskripsi Acara ForbesDokumen4 halamanLembar Deskripsi Acara ForbesDimas Anas HakimBelum ada peringkat
- Fosil JejakDokumen14 halamanFosil JejakYovie AdhityaBelum ada peringkat
- Foram BesarDokumen9 halamanForam BesarAnonymous RhxuWp8MBelum ada peringkat
- Laporan Foram BesarDokumen24 halamanLaporan Foram BesarAndini Nur FajrinaBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Mikropal Acara 2Dokumen17 halamanLaporan Praktikum Mikropal Acara 2agung nur ihsanBelum ada peringkat
- Zonasi Foraminifera PlanktonikDokumen5 halamanZonasi Foraminifera PlanktonikMuhammad Ary IsmoehartoBelum ada peringkat
- Echinodermata GauDokumen5 halamanEchinodermata GauJoshua AdityaBelum ada peringkat
- Deskripsi Morfologi Foraminifera BenthonikDokumen7 halamanDeskripsi Morfologi Foraminifera BenthonikFahmi LubertoBelum ada peringkat
- Rekonstruksi Porifera: Teknik Geologi, Jurusan Teknologi Produksi Dan Industri, Institut Teknologi Sumatera EmailDokumen8 halamanRekonstruksi Porifera: Teknik Geologi, Jurusan Teknologi Produksi Dan Industri, Institut Teknologi Sumatera EmailDilan TelaumbanuaBelum ada peringkat
- Artikel Foraminfera Bentonik BesarDokumen8 halamanArtikel Foraminfera Bentonik BesarJordan FernaldyBelum ada peringkat
- Lembar Deskripsi MakropaleontologiDokumen4 halamanLembar Deskripsi MakropaleontologiheirbintangBelum ada peringkat
- Deskripsi Foraminifera Bentonik BesarDokumen13 halamanDeskripsi Foraminifera Bentonik BesarHadrian FahrezaBelum ada peringkat
- GloboquadrinaDokumen3 halamanGloboquadrinaAbd Wasi'Belum ada peringkat
- Foraminifera PlanktonikDokumen25 halamanForaminifera PlanktonikAbdi DharmawanBelum ada peringkat
- Foraminifera BesarDokumen25 halamanForaminifera BesarSabar Itu AgusBelum ada peringkat
- Foraminifera PlanktonDokumen24 halamanForaminifera PlanktonGABelum ada peringkat
- SpiroclypeusDokumen2 halamanSpiroclypeusJalu BiasBelum ada peringkat
- Lampiran Foraminifera PlanktonikDokumen5 halamanLampiran Foraminifera PlanktonikSondangMarisStellaSimamoraBelum ada peringkat
- Agim Yustian Bakhtiar - Rekonstruksi Fosil PoriferaDokumen5 halamanAgim Yustian Bakhtiar - Rekonstruksi Fosil Poriferaagim yustianBelum ada peringkat
- Album Foramini Bentonik 2 IntanDokumen31 halamanAlbum Foramini Bentonik 2 IntanEko Galeh Wahyu PrayetnoBelum ada peringkat
- Bab Ii Tugas Batuan Sedimen PDFDokumen39 halamanBab Ii Tugas Batuan Sedimen PDFdamasM1Belum ada peringkat
- BIOSTRATIGRAFI KlompokDokumen14 halamanBIOSTRATIGRAFI KlompokWahyu Satria KencanaBelum ada peringkat
- Hasil Deskripsi Foraminifera BentonikDokumen8 halamanHasil Deskripsi Foraminifera BentonikRino Dwi HutamaBelum ada peringkat
- Kuliah - Foram Besar BDokumen22 halamanKuliah - Foram Besar BSinta Dewi Yanti0% (1)
- Batuan Piroklastik PDFDokumen29 halamanBatuan Piroklastik PDFRidho MuhariBelum ada peringkat
- Album Foraminifera BenerDokumen48 halamanAlbum Foraminifera BenerDiana Desi Pertiwi0% (1)
- Acara BrachiopodaDokumen16 halamanAcara BrachiopodaMuh FaisalBelum ada peringkat
- Album Mikrofosil ForaminiferaDokumen28 halamanAlbum Mikrofosil ForaminiferaFajar Anggara50% (2)
- Model FasiesDokumen13 halamanModel FasiesLidya AprilitaBelum ada peringkat
- Laporan MikropaleontologiDokumen39 halamanLaporan MikropaleontologiMAbdulYazifaM0% (1)
- 3549 - Laporan PaleontologiDokumen17 halaman3549 - Laporan PaleontologiNinagstinaBelum ada peringkat
- Hasil Deskripsi MakropalDokumen5 halamanHasil Deskripsi MakropalLaras CahyaniBelum ada peringkat
- Freeze, Amber, Dan EkskavasiDokumen7 halamanFreeze, Amber, Dan EkskavasiAditya Bayu RivaldiBelum ada peringkat
- Aplikasi Paleontology Invertebrata Di Pulau JawaDokumen4 halamanAplikasi Paleontology Invertebrata Di Pulau Jawaaditya azam fashaBelum ada peringkat
- Foraminifera PlanktonicDokumen30 halamanForaminifera PlanktonicGifari CandraBelum ada peringkat
- Iyf 8 IyDokumen18 halamanIyf 8 IyniaBelum ada peringkat
- Album MikrofosilDokumen32 halamanAlbum MikrofosilM Rudy Ardiyansah67% (3)
- Aperture Mikro KelasDokumen4 halamanAperture Mikro KelasKira LightBelum ada peringkat
- Arthropoda LaporanDokumen18 halamanArthropoda LaporanVan Wihel Okrian MoncaiBelum ada peringkat
- Zonasi Bolli PDFDokumen7 halamanZonasi Bolli PDFFarizPrayogiBelum ada peringkat
- Makalah MikropaleontologiDokumen57 halamanMakalah MikropaleontologiEny KhairunnisaBelum ada peringkat
- Laporan Mikropaleontologi 4Dokumen8 halamanLaporan Mikropaleontologi 4Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Laporan Mikropaleontologi 3Dokumen9 halamanLaporan Mikropaleontologi 3Johan Albert SembiringBelum ada peringkat
- Mikropal 1 FixDokumen8 halamanMikropal 1 FixridhoBelum ada peringkat