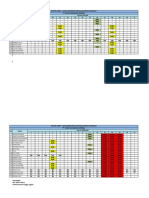Kang Sejo Melihat Tuhan
Diunggah oleh
wambes rikal0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
58 tayangan6 halamanHak Cipta
© © All Rights Reserved
Format Tersedia
DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
0 penilaian0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara)
58 tayangan6 halamanKang Sejo Melihat Tuhan
Diunggah oleh
wambes rikalHak Cipta:
© All Rights Reserved
Format Tersedia
Unduh sebagai DOC, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
Anda di halaman 1dari 6
Kang Sejo Melihat Tuhan
oleh Mohammad Sobary
Bukan salah saya kalau suatu hari saya ceramah agama di depan sejumlah mahasiswa
Monash yang, satu di antaranya, Islamnya menggebu. Artinya, Islam serba berbau Arab.
Jenggot mesti panjang. Ceramah mesti merujuk ayat, atau Hadis. Lauk mesti halal meat.
Dan, semangat mesti ditujukan buat meng-Islam-kan orang Australia. Tanpa itu semua
jelas tidak Islami.
Saya pun dicap tidak Islami. Iman saya campur aduk dengan wayang. Dus, kalau pakai
kaca mata Geertz, seislam-islamnya saya, saya ini masih Hindu. Memang salah saya, sebab
ketika itu saya main ibarat: Gatutkaca itu sufi. Ia satria-pandita. Tiap saat seperti tidur,
padahal berzikir qolbi. Jasad di bumi, roh menemui Tuhan. Ini turu lali, mripat turu, ati
tangi: mata tidur hati melek, seperti olah batin dalam dunia aum sufi.
Biar masih muda, hidup Gatutkaca seimbang, satu kaki di
dunia satu lagi di akhirat. Mirip Nabi Daud: hari ini puasa,
sehari esoknya berbuka. Dan saya pun dibabat ...
Juli tahun lalu saya dijuluki Gus Dur sebagai orang yang
doanya pendek. Bukan harfiah cuma berdoa sebentar.
Maksudnya, tak banyak doa yang saya hafal. Namun, yang tak
banyak itu saya amalkan.
"Dan itu betul. Artinya, banyak ilmu ndak diamalkan buat
apa?" kata Pak Kiai sambil bergolek-golek di Hotel
Sriwedari, Yogya. Apa yang lebih indah dalam hidup ini,
selain amal yang memperoleh pengakuan Romo Kiai? Saya merasa
hidup jadi kepenak, nikmat.
Dalam deretan Sufi, Al Adawiah disebut "raja." Wanita ini
hamba yang total. Hidupnya buat cinta. Gemerlap dunia tak
menarik berkat pesona lain: getaran cinta ilahi. Pernah ia
berkata, "Bila Kau ingin menganugerahi aku nikmat duniawi,
berikan itu pada musuh-musuh-Mu. Dan bila ingin Kau
limpahkan padaku nikmat surgawi, berikanlah pada
sahabat-sahabat-Mu. Bagiku, Kau cukup."
Ini tentu berkat ke-"raja"-annya. Lumrah. Lain bila itu
terjadi pada Kang Sejo. Ia tukang pijit -maaf, Kang, saya
sebut itu- tunanetra.
Kang Sejo pendek pula doanya. Bahasa Arab ia tak tahu.
Doanya bahasa Jawa: Gusti Allah ora sare (Allah tak pernah
tidur): potongan ayat Kursi itu. Zikir ia kuat. Soal ruwet
apa pun yang dihadapi, wiridannya satu: "Duh, Gusti, Engkau
yang tak pernah tidur ..." Cuma itu.
"Memang sederhana, wong hidup ini pun dasarnya juga
sederhana," katanya, sambil memijit saya.
Saya tertarik cara hidupnya. Saya belajar. Guru saya ya
orang macam ini, antara lain. Rumahnya di Klender.
Kantornya, panti pijat itu, di sekitar Blok M. Ketika saya
tanya, apa yang dilakukannya di sela memijit, dia bilang,
"Zikir Duh, Gusti ..." Di rumah, di jalan, di tempat kerja,
di mana pun, doanya ya Duh, Gusti ... itu. Satu tapi jelas
di tangan.
"Berapa kali Duh Gusti dalam sehari?" tanya saya.
"Tidak saya hitung."
"Lho, apa tak ada aturannya? Para santri kan dituntun kiai,
baca ini sekian ribu, itu sekian ribu," kata saya
"Monggo mawon (ya, terserah saja)," jawabnya. "Tuhan memberi
kita rezeki tanpa hitungan, kok. Jadi, ibadah pun tanpa
hitungan."
"Sampeyan itu seperti wali, lo, Kang," saya memuji.
"Monggo mawon. Ning (tapi) wali murid." Dia lalu ketawa.
Diam-diam ia sudah naik haji. Langganan lama, seorang
pejabat, mentraktirnya ke Tanah Suci tiga tahun yang lalu.
'Senang sampeyan, Kang, sudah naik haji?"
"Itu kan rezeki. Dan rezeki datang dari sumber yang tak
terduga," katanya.
"Ayat menyebutkan itu, Kang."
"Monggo mawon. Saya tidak tahu."
Ketularan bau Arab, saya tanya kenapa doanya bahasa Jawa.
"Apa Tuhan tahunya cuma bahasa Arab?"
"Kalau sampeyan Dah Duh Gusti di bis apa penumpang lain ..."
"Dalam hati, Mas. Tak perlu diucapkan."
Ia, konon, pernah menolak zakat dari seorang tetangganya.
Karena disodor-sodori, ia menyebut, "Duh, Gusti, yang tak
pernah tidur ..." Pemberi zakat itu, entah bagaimana,
ketakutan. Ia mengaku uang itu memang kurang halal. Ia minta
maaf.
"Mengapa sampeyan tahu uang zakat itu haram"? tanya saya.
"Rumah saya tiba-tiba panas. Panaaaas sekali."
"Kok sampeyan tahu panas itu akibat si uang haram?"
"Gusti Allah ora sare, Mas," jawabnya.
Ya, saya mengerti, Kang Sejo. Ibarat berjalan, kau telah
sampai. Dalam kegelapan matamu kau telah melihatNya. Dan
aku? Aku masih dalam taraf terpesona. Terus-menerus
---------------
Mohammad Sobary, Tempo 12 Januari 1991
TUHAN TERSENYUM
Don't take your organs to heaven
Heaven knows we need them here.
Pernahkah Tuhan tersenyum, atau melucu? Dalam kitab suci tak
saya temukan dua hal itu. Begitu juga dalam hadis nabi.
Pemahaman tekstual saya atas agama terbatas. Pengajian saya
masih randah, kata orang Minang. Tapi kalau soalnya cuma
"adakah khatib yang melucu, atau marah," saya punya data.
Di tahun 1978, seorang khatib melucu di masjid UI
Rawamangun. Akibatnya, jemaah yang tadinya sudah liyep-liyep
jadi melek penuh. Mereka menyimak pesan Jumat, sambil
senyum. Tapi khatib ini tak cuma menghasilkan senyum itu. Ia
diganyang oleh khatib yang naik mimbar Jumat berikutnya.
"Agama bukan barang lucu," semburnya. "Dan tak perlu dibikin
lelucon. Mimbar Jumat bukan arena humor. Karena itu, sengaja
melucu dalam khotbah dilarang ..."
Vonis jatuh. Marah khatib kita ini. Dan saya mencatat
"tambahan" larangan satu lagi. Sebelum itu demonstrasi
mahasiswa sudah dilarang "yang berwajib". Senat dan Dewan
dibekukan. Milik mahasiswa yang tinggal satu itu, "melucu
buat mengejek diri sendiri", akhirnya dilarang juga.
Kita memang perlu norma. Tapi juga perlu kelonggaran. Maka,
saya khawatir kalau menguap di masjid bakal dilarang. Siapa
tahu, di rumah Allah hal itu tak sopan. Buat jemaah yang
suka menguap macam saya, karena jarang setuju dengan isi
khotbah, belum adanya larangan itu melegakan.
Saya dengar Komar dikritik banyak pihak. Soalnya, dalam
ceramah agamanya ia melucu. Tapi Komar punya alasan sahih.
Ia, konon, sering mengamati sekitar. Di kampungnya, banyak
anak muda tak tertarik pada ceramah agama.
"Mengapa?" tanya Pak Haji Komar.
"Karena isinya cuma sejumlah ancaman neraka."
Wah ... Itu sebabnya ia, yang memang pelawak, memberi warna
humor dalam ceramahnya. Dan remaja pun pada hadir.
Saya suka sufisme. Di sana Tuhan dilukiskan serba ramah. Dan
bukannya marah melulu macam gambaran kita. A'u dibaca angu,
tidak bisa. Dzubi jadi dubi, tidak boleh. Khotbah lucu,
jangan. Lho? Bukankah alam ini pun "khotbah" Tuhan? Langit
selebar itu tanpa tiang, bulan bergayut tanpa cantelan dan
aman, apa bukan "khotbah" maha jenaka? Apa salahnya humor
dalam agama?
Di tahun 1960-an, Marhaen ingin hidup mati di belakang Bung
Karno. Dalam humor, saya cukup di belakang Bung Komar.
Artinya, bagi saya, humor agama bikin sehat iman. Dus, tidak
haram jadah.
Di Universitas Monash saya temukan striker: "Jangan bawa
organmu ke surga. Orang surga sudah tahu kita lebih
memerlukannya di sini". Imbauan ini bukan dari Gereja,
melainkan dari koperasi kredit. Intinya: kita diajak
berkoperasi. Dengan itu kita santuni kaum duafa, kaum lemah.
Ini pun "khotbah" lucu. Dalam kisah sufi ada disebut cerita
seorang gaek penyembah patung. Ia menyembah tanpa pamrih.
Tapi di usia ke-70 ia punya kebutuhan penting. Doa pun
diajukan. Sayang, patung itu cuma diam. Kakek kecewa. Ia
minta pada Allah. Dan ajaib: dikabulkan.
Bukan urusan dia bila masalah kemudian timbul, sebab
Allah-lah, bukan dia, yang diprotes oleh para malaikat.
"Mengapa ya, Allah, Kaukabulkan doa si kakek? Lupakah Kau ia
penyembah patung? Bukankah ia kafir yang nyata?"
Allah senyum. "Betul," jawabnya, "Tapi kalau bukan Aku,
siapa akan mengabulkan doanya? Kalau Aku pun diam, lalu apa
bedanya Aku dengan patung?"
Siang malam aku pun berdoa, semoga humor kaum sufi ini tak
dilarang.
---------------
Mohammad Sobary, Tempo 27 Oktober 1990
SANDAL JEPIT KESEDERHANAAN
Mungkin ada pesona tertentu yang menghubungkan rohani para
penyair. Setahu saya, ada dua penyair yang terpesona pada
kesederhanaan. Yang satu Taufiq Ismail. Yang satu lagi Emha
Ainun Nadjib.
Bulan Juni, 1979, ketika Ki Mohamad Said Reksohadiprodjo
meninggal dunia, Taufiq terharu. Ia merasa kehilangan. Ia
lalu menulis sajak, buat mengenang orang tua sederhana tapi
memancarkan kewibawaan itu.
Yang paling pertama ia ingat tentang orang tua itu ialah
sandal jepitnya, yang selalu berbunyi soh, soh, soh,
menggosok debu Jakarta, menggosok debu Indonesia.
Di rumahnya, Taufiq mencari sepatu lari, yang ia beli di
negara dunia kesatu. Harganya, tentu saja, mahal. Dan itu
membuat Taufiq malu mengenang kesederhanaan Ki Mohamad Said.
Penyair ini silau melihat kehidupan orang tua itu.
Ketika Mohamad Kasim Arifin, mahasiswa IPB yang selama 15
tahun "menghilang" di Waimital, P. Seram, kembali ke IPB
dengan kisah suksesnya membantu petani transmigran yang
miskin, Taufiq juga terharu. Kasim, sahabatnya itu, meraih
keberhasilan dengan swadaya, tanpa sepeser pun bantuan dana
dari pemerintah.
Begitu melihat dirinya sendiri, seorang dokter hewan yang
hanya bersyair-syair saja kerjanya (begitulah diakuinya
dalam sajaknya untuk mengenang Mohamad Kasim Arifin), ia
merasa perlu menyembunyikan wajahnya menyembul di kali
Ciliwung itu. Kasim yang hidupnya tak gemerlapan itu pun,
seperti halnya Ki Mohamad Said, membuatnya merasa malu,
risi, dan bersalah.
Getaran apakah yang membuat kita bisa merasa risau dan
terpojok tak berdaya seperti itu? Mungkin cuma Taufiq
sendiri yang tahu jawaban persisnya.
Tapi, saya kira Taufiq mengharapkan agar kita punya lebih
banyak lagi tokoh seperti Ki Mohamad Said dan Kasim Arifin.
Ia, dengan kata lain, tak ingin melihat Ki Mohamad Said
berangkat meninggalkan kita.
Kematian memang sering bisa memberikan kenangan seperti itu.
Dan, celakanya, kita seperti baru sadar, bahwa orang seperti
itu penting dan kita perlukan.
Dalam "Sajak-sajak Sederhana"-nya, nampak bagaimana penyair
Emha Ainun Nadjib gandrung pada kesederhanaan itu.
"Tuhanku" katanya.
"Ambillah aku sewaktu-waktu.
Kematianku kehendak sederhana saja.
Orang-orang menguburku hendaknya juga dengan sederhana
saja."
Barangkali, ini pesan Emha. Tapi barangkali juga salah satu
cermin dari pergulatan batinnya sebagai seorang seniman.
Seperti Taufiq Ismail, Emha Ainun Nadjib juga kuat
memperlihatkan pada kita pemihakannya pada nilai
kesederhanaan.
Ketika Soedjatmoko meninggal dunia, Emha juga menulis
kenangan. Ada sesuatu yang ia kagumi pada diri intelektual
beken itu. Oleh karena itu, tak segan ia menyebut
Soedjatmoko sebagai ulama. Benar, kata Arab itu artinya
memang persis mencerminkan kehidupan Soedjatmoko: orang yang
banyak ilmu. Tapi pemberian gelar ulama itu jelas memiliki
konotasi lebih: bahwa almarhum bukan cuma berilmu tapi juga,
dan ini yang lebih penting, mampu memberikan teladan laku
bagi siapa saja.
Goenawan Mohamad bahkan menyebut Soedjatmoko bukan cuma
teladan ilmu, melainkan juga teladan "laku". Bagi
Soedjatmoko, apa yang dikatakan dan yang ditulis tidak cuma
cermin ketangkasan berolah pikir, melainkan juga cermin
pergulatan batinnya.
Orang bilang, keteladanan adalah sesuatu yang hilang dari
kita. Kita tak lagi punya sesuatu yang kita banggakan. Tak
ada lagi sosok pribadi yang layak kita jadikan teladan.
Tampil secara sederhana saja misalnya, juga sesuatu yang tak
mudah. Imbauan untuk menyederhanakan hidup sebetulnya pas
buat kita. Ia bukan cuma problem bagi orang kaya yang
cenderung hidup gemerlapan. Orang miskin pun, entah berkat
rangsangan virus apa, banyak yang tak mau tampil apa adanya.
Mereka tidak gemerlap, mungkin juga memperlihatkan sikap
anti pada gaya hidup itu, barangkali hanya karena belum ada
kesempatan.
Benar kekaguman Taufiq pada Ki Mohamad Said, karena orang
itu telah membuktikan dalam hidupnya. Ia bukan cuma orang
sederhana, melainkan mungkin kesederhanaan itu sendiri.
---------------
Mohammad Sobary, Jawa Pos 12 Januari 1992
Anda mungkin juga menyukai
- Kang Sejo Melihat TuhanDokumen9 halamanKang Sejo Melihat Tuhanayu pramBelum ada peringkat
- Cerita Teladan Tentang SolatDokumen47 halamanCerita Teladan Tentang SolatAlyson BrownBelum ada peringkat
- Antara Gereja Dan MasjidDokumen4 halamanAntara Gereja Dan Masjidfauziah hanum abdullahBelum ada peringkat
- Aa Navis - Robohnya Surau KamiDokumen7 halamanAa Navis - Robohnya Surau KamiEdi SubkhanBelum ada peringkat
- Analisis CerpenDokumen19 halamanAnalisis CerpenAndika SanjayaBelum ada peringkat
- Robohnya Surai KamiDokumen5 halamanRobohnya Surai KamiAisBelum ada peringkat
- Robohnya Surau KamiDokumen12 halamanRobohnya Surau KamiM Luthfi Rabby RadhiyaBelum ada peringkat
- LK 3.2 Analisis ProsaDokumen8 halamanLK 3.2 Analisis ProsaKhadafi DafiBelum ada peringkat
- Doa Kang SutoDokumen7 halamanDoa Kang SutoBhakti PertiwiBelum ada peringkat
- Tugas Jihan CerpenDokumen9 halamanTugas Jihan CerpenHendra Siagian,s.pdBelum ada peringkat
- Cerpen Robohnya SurauDokumen22 halamanCerpen Robohnya Suraufira100% (1)
- Robohnya Surau Kami 2-1Dokumen5 halamanRobohnya Surau Kami 2-1mora nihhkakkBelum ada peringkat
- Cerpen - Robohnya Surau KamiDokumen4 halamanCerpen - Robohnya Surau KamiMTs YASFI BekasiBelum ada peringkat
- Tikam SamuraiDokumen24 halamanTikam Samuraiisnaini arsaBelum ada peringkat
- Analisis Cerpen Dan Contoh NyaDokumen8 halamanAnalisis Cerpen Dan Contoh NyaJumali EndroBelum ada peringkat
- Naskah Drama KlmpokDokumen12 halamanNaskah Drama KlmpokRirinBelum ada peringkat
- Naskah Teater Xii Ips - Robohnya Surau KamiDokumen11 halamanNaskah Teater Xii Ips - Robohnya Surau KamiGusfi Maulidinda KirmilaBelum ada peringkat
- Unsurintrinsikcerp Dra.i.mufidah, M.PD 15069Dokumen10 halamanUnsurintrinsikcerp Dra.i.mufidah, M.PD 15069Gomos Parulian ManaluBelum ada peringkat
- MONOLOG Robohnya Surau EmasDokumen4 halamanMONOLOG Robohnya Surau EmasRein safariBelum ada peringkat
- Kritik Sastra Semester 5Dokumen29 halamanKritik Sastra Semester 5adi mauliaBelum ada peringkat
- Robohnya Surau KamiDokumen8 halamanRobohnya Surau KamiNADIABelum ada peringkat
- Tugas CerpenDokumen9 halamanTugas CerpenZein AksesorisBelum ada peringkat
- CERPENDokumen8 halamanCERPENHalby SyahputraBelum ada peringkat
- Cerpen Robohnya Surau KamiDokumen8 halamanCerpen Robohnya Surau Kamizikri arnandaBelum ada peringkat
- Horror MisteriDokumen4 halamanHorror MisteriFityah BibenBelum ada peringkat
- Analisis Unsur Intrinsik Dan Unsur EkstrinsikDokumen15 halamanAnalisis Unsur Intrinsik Dan Unsur EkstrinsikFarhan ramadhan SaputraBelum ada peringkat
- LKPD CerpenDokumen11 halamanLKPD CerpenVia MarsandaBelum ada peringkat
- Robohnya Surau KamiDokumen6 halamanRobohnya Surau KamiStevBelum ada peringkat
- Humor IDokumen35 halamanHumor Ifrid liunokasBelum ada peringkat
- Robohnya Surau KamiDokumen10 halamanRobohnya Surau KamievaoctvnyBelum ada peringkat
- TugasDokumen22 halamanTugasJannatya PlBelum ada peringkat
- Lembar Kerja SiswaDokumen9 halamanLembar Kerja SiswaDede RizalBelum ada peringkat
- Bangsawan PandirDokumen103 halamanBangsawan PandirfebriansasiBelum ada peringkat
- Apresiasi Cerpen (Sofyan Hadi Nim.1888202002)Dokumen11 halamanApresiasi Cerpen (Sofyan Hadi Nim.1888202002)Sofyan hadiBelum ada peringkat
- Cerpen Robohnya Surau KamiDokumen5 halamanCerpen Robohnya Surau KamiSyifa Nisaburi100% (1)
- Cerpen Robohnya Surau Kami Karya AA NavisDokumen12 halamanCerpen Robohnya Surau Kami Karya AA Navisqueenrara desakBelum ada peringkat
- Cerpen Robohnya Surau Kami Karya AA NaviDokumen18 halamanCerpen Robohnya Surau Kami Karya AA NaviNova Cristy SaragihBelum ada peringkat
- Rohohnya Surau KamiDokumen14 halamanRohohnya Surau KamiStill HypeBelum ada peringkat
- Cerpen Gus Ja'far Gus MusDokumen5 halamanCerpen Gus Ja'far Gus MusAl HadiBelum ada peringkat
- Robohnya Surau KamiDokumen9 halamanRobohnya Surau KamiIngeu Widyatari Heriana100% (1)
- Resensi Novel B, IndoooooDokumen12 halamanResensi Novel B, IndoooooFadhilahMiftahulIlmiBelum ada peringkat
- ARIEFDokumen4 halamanARIEFSeptian Putra RaflyansyahBelum ada peringkat
- Analisi Cerpen Rian& TegarDokumen6 halamanAnalisi Cerpen Rian& TegarCAPOSLITA GAMINGBelum ada peringkat
- KISI Pengajian Alarkom Ramadahn 1427Dokumen3 halamanKISI Pengajian Alarkom Ramadahn 1427Wasis Abu IfaBelum ada peringkat
- Kisah Hikayat Pemuda Saleh Pecinta Masjid & Iblis yang Baik HatiDari EverandKisah Hikayat Pemuda Saleh Pecinta Masjid & Iblis yang Baik HatiPenilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (1)
- Robohnya Surau KamiDokumen15 halamanRobohnya Surau KamiAida Fitriana50% (2)
- Anih DimekahDokumen43 halamanAnih DimekahSalim SalvadorBelum ada peringkat
- Robohnya Surau KamiDokumen8 halamanRobohnya Surau KamiWinda MarisaBelum ada peringkat
- Malim PesongDokumen5 halamanMalim Pesonguya_so7100% (1)
- Tugas Resensi Cerpen BINDDokumen3 halamanTugas Resensi Cerpen BINDIvan FrpBelum ada peringkat
- Analisis Robuhnya Surau KamiDokumen3 halamanAnalisis Robuhnya Surau KamiImmet PakpahanBelum ada peringkat
- Robohnya Surau Kami 2Dokumen15 halamanRobohnya Surau Kami 2Diva FarisaBelum ada peringkat
- Mujibuddakwah (Spiritual Journey in Ramadan)Dokumen31 halamanMujibuddakwah (Spiritual Journey in Ramadan)Mujibuddakwah Al-NgawiyiBelum ada peringkat
- Siri Bercakap Dengan Jin - Jilid 10Dokumen43 halamanSiri Bercakap Dengan Jin - Jilid 10Frankly F. ChiaBelum ada peringkat
- CERPEN Gus Ja'farDokumen7 halamanCERPEN Gus Ja'farSyafikKifaysBelum ada peringkat
- Che Guevara Wajah Sang LegendaDokumen5 halamanChe Guevara Wajah Sang LegendaHusnul WahyuniBelum ada peringkat
- Investigasi KecelakaanDokumen31 halamanInvestigasi Kecelakaanwambes rikalBelum ada peringkat
- Aktivitas Sex Saat HamilDokumen2 halamanAktivitas Sex Saat Hamilwambes rikalBelum ada peringkat
- Bahan Galian Merupakan Salah Satu Sumber Daya Alam Yang Keterjadiannya Disebabkan Oleh ProsesDokumen3 halamanBahan Galian Merupakan Salah Satu Sumber Daya Alam Yang Keterjadiannya Disebabkan Oleh Proseswambes rikalBelum ada peringkat
- Esensi Perang Gerilya by GuevaraDokumen4 halamanEsensi Perang Gerilya by GuevaraHusnul WahyuniBelum ada peringkat
- Hazard RiskDokumen66 halamanHazard Riskwambes rikalBelum ada peringkat
- Basis Radikalisasi PerempuanDokumen6 halamanBasis Radikalisasi Perempuanwambes rikalBelum ada peringkat
- Sejarah GerwaniDokumen20 halamanSejarah Gerwaniwambes rikalBelum ada peringkat
- Cerita KamiDokumen18 halamanCerita Kamiwambes rikalBelum ada peringkat
- Mira Mahardika Soal Krisis EkonomiDokumen8 halamanMira Mahardika Soal Krisis Ekonomiwambes rikalBelum ada peringkat
- Perempuan Timor LesteDokumen19 halamanPerempuan Timor Lestewambes rikalBelum ada peringkat
- Kisah Sufi Isa Dan Orang-Orang BimbangDokumen2 halamanKisah Sufi Isa Dan Orang-Orang Bimbangwambes rikalBelum ada peringkat
- Sejarah Gerakan Mahasiswa KerakyatanDokumen35 halamanSejarah Gerakan Mahasiswa Kerakyatanwambes rikalBelum ada peringkat
- Gerakan Mahasiswa RevolusionerDokumen12 halamanGerakan Mahasiswa Revolusionerwambes rikalBelum ada peringkat
- Company Profile Pt. Abdi Jaya PersadaDokumen110 halamanCompany Profile Pt. Abdi Jaya Persadawambes rikalBelum ada peringkat
- Bagian 1 - Kenalan Dulu Dengan HTMLDokumen8 halamanBagian 1 - Kenalan Dulu Dengan HTMLwambes rikalBelum ada peringkat
- Pemutusan Hubungan KerjaDokumen6 halamanPemutusan Hubungan Kerjawambes rikalBelum ada peringkat
- BukuPrak MP2-6Dokumen4 halamanBukuPrak MP2-6wambes rikalBelum ada peringkat
- Dasar Dasar PHP Bagian IDokumen4 halamanDasar Dasar PHP Bagian Iwambes rikalBelum ada peringkat
- StringDokumen2 halamanStringwambes rikalBelum ada peringkat
- Daftar Nama AbsensiDokumen2 halamanDaftar Nama Absensiwambes rikalBelum ada peringkat
- 03Bandung-Pengelolaan Lingkungan PertambanganDokumen27 halaman03Bandung-Pengelolaan Lingkungan Pertambanganwambes rikalBelum ada peringkat
- Rincian Anggaran Pembuatan DokDokumen2 halamanRincian Anggaran Pembuatan Dokwambes rikalBelum ada peringkat
- Pembuatan Website Sederhana Menggunakan HTML (Hyper Text Markup Languaage)Dokumen11 halamanPembuatan Website Sederhana Menggunakan HTML (Hyper Text Markup Languaage)wambes rikalBelum ada peringkat
- Karnaval Raja CebolDokumen5 halamanKarnaval Raja CebolEnal Sipil TeknikBelum ada peringkat
- Chairil Anwar Berguru Nyolong Pada Muh YaminDokumen3 halamanChairil Anwar Berguru Nyolong Pada Muh Yaminwambes rikalBelum ada peringkat
- Cermin ZazuliDokumen4 halamanCermin ZazuliAndy EenBelum ada peringkat
- Cerita BermaknaDokumen7 halamanCerita Bermaknawambes rikalBelum ada peringkat
- Cerita IslamiDokumen4 halamanCerita IslamiEnal Sipil TeknikBelum ada peringkat