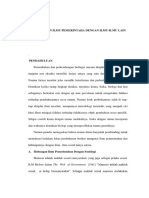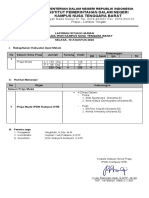JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Diunggah oleh
mustami fataDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Diunggah oleh
mustami fataHak Cipta:
Format Tersedia
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 1
Ilmu Pemerintahan:
Anti pada Politik, Lupa pada Hukum,
dan Enggan pada Administrasi
Sutoro Eko Yunanto
Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Korespondensi Penulis: toroeko@yahoo.com
Demokrasi patut dipuji, tetapi pemerintahan hukum bagaikan roti kita sehari-hari,
seperti air untuk minum dan udara untuk bernafas, dan hal terbaik tentang demokrasi
adalah bahwa hanya dia yang sanggup mengamankan
pemerintahan hukum untuk kita. (Gustav Radbruch, 1946)
ABSTRAK
Ilmu Pemerintahan (IP) adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia lain.
Tetapi IP selalu memperoleh stimulus eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan
neoliberalisme. Para pendiri membuat IP untuk alasan aksiologis-praktis, tanpa disertai
dengan ontologi dan epistemologi yang memadai. Secara ontologis, konsep pemerintah
merupakan tradisi Anglo Saxon, tetapi pemerintahan diambil dari tradisi hukum Eropa
Kontinental dan bestuurskunde warisan kolonial, yang di negeri asal disebut administrasi.
IP sukses mencetak banyak birokrat, tetapi ia tidak membawa roh “pemerintahan rakyat”
dan tidak sanggup mencerahkan praktik pemerintahan Indonesia, melainkan hanya ikut
menjaga law and order yang diwarisi dari beamtenstaat kolonial. Developmentalisme
dan administrasi negara datang mewarnai Orde Baru, sekaligus juga membentuk sosok
IP. Dekade 1990-an Ilmu Politik datang melakukan ‘subversi’ terhadap IP, yang sanggup
melucuti warna hukum, tetapi tidak merekonstruksi IP. Di era reformasi, studi politik
semakin jauh dari pemerintahan, dan IP mengikuti tradisi neoliberalisme, dengan
memahami pemerintahan sebagai manajemen publik dan governance. Hari ini, IP anti
pada politik, lupa pada hukum, dan enggan pada administrasi. Ia mengalami krisis
identitas, yang tidak sanggup membedakan antara Administrasi Publik dan IP. Krisis
epistemologi juga terjadi, yakni klaim IP sebagai disiplin ilmu tidak disertai dengan
penggunaan pemerintahan sebagai subjek dan perspektif untuk memahami dan
menjelaskan fenomena sosial.
Kata kunci: Ilmu Pemerintahan, pemerintah, politik, hukum, administrasi.
ABSTRACT
Governmental Science (GS) is unique to Indonesia, which is unknown in the rest of the
world. But GS always gets an external stimulus: colonialism, developmentalism, and
neoliberalism. The founders created GS for axiological-practical reasons, without being
accompanied by adequateontology and epistemology. Ontologically, the concept of
government is an Anglo-Saxon tradition, but government is taken from Continental
European legal traditions and bestuurskunde colonial heritage, which in the origin country
is called administration. GS succeeded in producing many bureaucrats, but it did not carry
the spirit of "people's government" and was unable to enlighten the practice of the
Indonesian government, but only participated in maintaining the law and orders inherited
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
2 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
from colonial beamtenstaat. Developmentalism and state administration came to color the
New Order, as well as to form an GS figure. The decade of the 1990s Political Science
came to subvert GS, which was able to ignite the color of law, but did not reconstruct GS.
In the reform era, political studies are farther away from government, and GS follows the
tradition of neoliberalism, understanding government as public management and
governance. Today, GS is anti-politics, forget the law, and are reluctant about
administration. GS experienced a crisis of identity, which was unable to distinguish
between Public Administration and GS. The epistemological crisis also occurred, namely
the claim of GS as a scientific discipline not accompanied by the use of government as a
subject and perspective to understand and explain social phenomena.
Keywords: Governmental Science, government, politics, law, administration.
Informasi Artikel
Diterima: April 2020, Disetujui: Mei 2020, Dipublikasikan: Juni 2020
DOI: https://doi.org/10.47431/governabilitas.v1i1.77
PENDAHULUAN
Apa itu pemerintah (an)? Apa itu Ilmu Pemerintahan (IP)? Apakah IP layak
menyandang predikat sebagai disiplin ilmu? Apa kekhasan IP yang berbeda dengan ilmu
politik dan administrasi publik? Apakah pemerintahan itu sebagai objek semata atau bisa
hadir sebagai subjek dan perspektif? Apa yang dimaksud pemerintah dan pemerintahan
menurut IP? Bagaimana IP memahami dan menjelaskan hakikat dan fenomena
pemerintahan? Selain telah mencetak banyak pamong praja, serta bicara efisiensi,
efektivitas dan kinerja pemerintahan, apa sumbangan IP terhadap pengetahuan
pemerintahan yang berguna untuk perubahan pemerintahan berkedaulatan rakyat sesuai
mandat konstitusi?
Saya mengajukan sederet pertanyaan itu sebagai bentuk otokritik terhadap IP,
yang sudah berumur tujuh dekade, dan saya menjadi bagian di dalamnya selama tiga
dekade terakhir. Munculnya beragam sekte, mazhab, dan perspektif tentu merupakan
kelaziman dalam ilmu pengetahuan. Almond (1990) pernah berbicara sekte dan mazhab
dalam ilmu politik, yang masing-masing duduk pada meja terpisah, yakni: meja kanan
bermetodologi lunak, meja kiri yang bermetodologi lunak, meja kanan bermetodologi
keras, dan meja kiri bermetodologi keras. Semakin kaya perspektif, maka ilmu semakin
kaya dengan novelty, yang bisa mengatasi anomali dan krisis. Beragam perspektif saling
bekontestasi tentang pemahaman dan penjelasan, sehingga komunitas epistemik, praktisi,
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 3
dan orang banyak akan bisa menemukan perspektif apa yang paling relevan dengan
pengetahuan, praktik, dan realitas sosial.
MASALAH ONTOLOGI DAN IDENTITAS
Sebagian kecil sarjana pemerintahan pasti tahu tentang kontestasi beragam
perspektif dalam ilmu sosial. Tetapi komunitas IP belum memiliki epistemologi tersendiri
untuk memahami dan menjawab fenomena luas pemerintahan semacam kemiskinan-
ketimpangan. Berbicara tentang kekayaan perspektif tentu terlalu jauh dan mewah, sebab
sejauh ini, IP tidak sanggup menjawab sederet pertanyaan dasar di atas. Merujuk pada
Soewargono (2015), IP tidak memiliki common ground, landasan dan dasar pengetahuan
yang sama, untuk membentuk disiplin sendiri dan metadisiplin. Raadschelders (2005)
juga mengingatkan bahwa apa yang kita ketahui tentang pemerintahan terfragmentasi
dalam lintas disiplin ilmu dan dengan demikian kita berisiko tidak mengetahui apa yang
sebenarnya kita ketahui. Para sesepuh dan para guru besar, yang mengajarkan
pemerintahan pun, memahami pemerintahan sama dengan birokrasi, administrasi, dan
manajemen publik, meskipun mereka tahu bahwa pemerintah dibentuk oleh politik dan
bekerja dengan politik.
Di mata saya, IP masih menghadapi masalah definisi, imajinasi dan posisi, yang
dapat disebut ontologi dan identitas. Ketika IP masih belum beres dengan ontologi dan
identitas, maka jangan harap ia akan memiliki epistemologi yang kaya dan aksiologi yang
relevan. Perkara ontologi dan identitas, sejak dekade 1980-an, muncul tiga cara pandang
terhadap IP.
Pertama, para generasi sesepuh pendiri-perintis (seperti Soewargono, S. Pamudji,
Soejamto, E. Koeswara, Bayu Surianingrat, Taliziduhu Ndraha, dan lain-lain) berhaluan
Eropa Kontinental, berpendapat bahwa IP adalah ilmu yang mandiri, lepas dari ilmu
politik, sekaligus setara dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Mereka menyamakan
kemandirian IP setara dengan ilmu administrasi negara yang sudah lama lepas dari ilmu
politik. IP, kata mereka, mempunyai objek kajian yang jelas, yakni fenomena
pemerintahan, yang dikaji secara sistematis sesuai kaidah ilmu. Bahkan kata mereka, IP
sudah berkembang pesat di Negeri Belanda dalam bentuk bestuurskunde, sekaligus sudah
diakui luas oleh masyarakat dan pemerintah Indonesia.
Kedua, generasi ilmuwan politik maupun sarjana administrasi publik pengikut
tradisi Anglo Saxon (seperti Afan Gaffar, Riswandha Imawan, Maswadi Rauf), yang
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
4 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
mendukung eksistensi IP, bukan IP yang otonom, melainkan IP sebagai bagian/turunan
Ilmu Politik. Pandangan ini bisa ditafsirkan bahwa disiplin IP merupakan sebuah cabang
dalam studi Ilmu Politik, sebagaimana dilembagakan dalam bentuk department of
government. “Di AS sendiri tidak ada perbedaan antara Department of Government
dengan Department of Political Science, baik dalam hal kurikulum maupun fokus
studinya”, tutur Maswadi Rauf (2015).
Y. Adiwisastra (2015), seorang guru besar administrasi publik, secara lugas
menelanjangi identitas disiplin IP yang tidak jelas. Ia mengatakan bahwa focus interest
IP adalah focus interest ilmu politik. Pemerintahan hanya merupakan salah satu
subdisiplin ilmu politik, dan bestuurkunde merupakan salah satu silabus ilmu administrasi
negara. Ia mengatakan administrasi publik merupakan pemerintahan dalam tindakan.
Dengan demikian, pemerintahan adalah obyek kajian, yang bisa dilihat dari sisi Ilmu
Politik maupun sisi Ilmu Administrasi Publik. Ia secara lugas menambahkan: “Nama ‘IP’
sekadar menyesuaikan diri dengan selera tertentu, sehingga dicari-cari justifikasi agar
‘ilmu’ ini tetap ada”.
Ketiga, kelompok ilmuwan yang berpandangan pemerintahan bukan disiplin
ilmu, melainkan hanya bidang (objek) kajian. Raadschelders (2015) istilah pemerintahan
merujuk pada objek pengetahuan substantif, sedangkan administrasi publik mengacu
pada studi akademik. Dengan kalimat lain, pemerintahan merupakan sebuah bidang-
objek studi yang antara lain bisa didekati dengan disiplin administrasi publik. Dengan
menolak “pemerintahan sebagai ilmu”, Pratikno (2003) berpendapat: “Pada level global,
istilah ‘science of government’ atau ‘governmental science’ sangat sulit (kalau tidak bisa
dibilang tidak bisa) ditemui sebagai terminologi maupun sebagai nama lembaga”
Pendapat “pemerintahan sebagai studi” itu mungkin lebih relevan ketimbang posisi
“IP sebagai turunan ilmu politik” maupun posisi “IP sebagai disiplin otonom”. Di belahan
dunia, science of government atau governmental science, hanya dikenal sebagai sebutan
dan pelajaran. Pendiri Amerika, George Washington dan John Adams, beberapa kali
bicara science of government (S. Cook dan W. Earleklay, 2014). Sebutan itu yang
mendorong kehadiran sejumlah buku yang disajikan oleh para penulis Amerika pada
dekade 1800-an sebelum lahir ilmu politik dan studi administrasi pada tahun 1880-an.
Sejumlah universitas di Amerika dan Inggris memiliki institusi “department of
government” atau “department of government and politics” tetapi tidak mengembangkan
“science of government” sebagai disiplin ilmu, melainkan berisi ilmu politik. Government
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 5
Department Harvard University mengembangkan studi politik atas pemerintahan, namun
institusi ini sampai sekarang memiliki sebutan “Eaton Professor of the Science of
Government” yang antara lain disematkan pada sejumlah ilmuwan politik seperti Carl
Friedrich, Charles McIlwain, Samuel Huntington, Robert Bates, Samuel Beer, dan Daniel
Ziblatt.
Di tengah “science of government” yang mati suri, hanya sebagai sebutan dan
pelajaran, studi pemerintahan berkembang pesat. Pemerintahan sebagai bidang studi
menjadi perhatian berbagai disiplin ilmu dan perspektif, bukan hanya ilmu politik dan
administrasi publik, tetapi juga filsafat, hukum, sosiologi, antropologi, psikologi,
ekonomi, ekonomi-politik, manajemen, geografi, dan ekologi. Karena posisi
“pemerintahan sebagai studi” inilah, UGM yang dulu menjadi perintis IP, malah
meninggalkan IP dan menggantikannya dengan “politik dan pemerintahan” sejak 2009.
Mengikuti jejak UGM itu, pada tahun 2014/2015, rezim kodifikasi sempat
merekomendasikan kepada program studi IP di seluruh Indonesia agar mengganti “IP”
menjadi “studi pemerintahan” (governance studies atau governmental studies). Tetapi
asosiasi IP melakukan advokasi yang menolak rekomendasi itu, sehingga sampai
sekarang, tetap berhasil mempertahankan IP, bahkan juga hadir pengakuan tentang gelar
kesarjanaan baik sarjana IP maupun magister IP.
Melalui artikel ini, saya tetap mengakui dan menghargai jerih payah klaim IP yang
sudah berjalan selama tujuh dekade, sebagai ilmu khas Indonesia, tanpa harus
memperoleh pengakuan dan kesepakatan dunia. IP tetap bisa dipakai di Indonesia, seperti
halnya Afrika Selatan memakai regeerkunde, meskipun dunia tidak mengenal disiplin
science of government atau governmental science. Tetapi kalau melakukan pergaulan
global, IP harus sanggup beradaptasi dengan tradisi “study of government” yang sudah
menglobal. Pilihan ini serupa dengan Belanda yang tetap mempertahankan bestuurkunde
sebagai administrasi publik ala Belanda, dan sanggup beradaptasi dan berkonestasi
dengan hegemoni public administration ala Anglo Saxon. Demikian juga
staatswissenschaft, yang dulu berbau hukum, tetapi sekarang dirayakan sebagai ilmu
politik ala Jerman, yang sanggup bersanding dengan hemenoni political science dalam
tradisi Anglo Saxon.
Tetapi menghargai bukan berarti membiarkan cacat yang dibawa dan diajarkan oleh
IP. Sebagai otokritik, tulisan ini justru hendak melucuti IP, sebuah klaim dan academic
enterpresise yang gegap gempita, tetapi prematur, salah kaprah, rapuh, dan krisis. IP tidak
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
6 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
sanggup menjawab pertanyaan pada paragraf pertama. Banyak sarjana bisa membuat dan
mengumpulkan definisi IP, yang cukup untuk dihafal mahasiswa, tetapi tidak
memperkaya pengetahuan dan tidak mencerahkan praktik pemerintahan. Itu semua terjadi
karena IP mewarisi kolonialisme, meniru praktik salah kaprah pemerintahan, dan
mengikuti neoliberalisme. Dengan begitu, tulisan ini bertujuan agar masyarakat IP
berubah dari “tidak mengetahui apa yang diketahui, diajarkan, dan dihafal” menjadi
“mengetahui apa yang diketahui”, sehingga IP duduk tegak lurus sebagai disiplin ilmu.
Jika mau duduk tegak lurus, maka IP tidak bisa sibuk dengan barang basi (seperti objek
formal dan objek material dengan pendekatan monodisplin, multidisiplin, dan
interdisplin, yang sebenarnya tidak jelas), tetapi secara epistemologis tidak sanggup
menghadirkan pemerintahan sebagai subjek dan perspektif.
PEMAHAMAN DAN PEMETAAN
Orang “tidak mengetahui apa yang diketahui” tentang pemerintahan memang bisa
dimaklumi, sebab konsep ini terlalu licin dan sulit ditangkap. Bahasa Inggris mengenal
government untuk menyebut pemerintah sekaligus pemerintahan, sehingga menyulitkan
pemahaman. Namun kata dasar govern menjadi dasar untuk memahami fungsi dan
aktivitas pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintah. Bahasa Belanda mengenal
beberapa konsep yang membingungkan: gouvernement(en), reeger, overheid, dan
bestuur. Dengan menggunakan Bahasa Indonesia, kita akan memperoleh kata dasar
“perintah” dalam konsep pemerintahan, yang mudah tergelincir menjadi “titah
penguasa”, sebuah makna yang tidak disukai oleh masyarakat modern. Namun dalam
sejarah panjang, masyarakat mengenal pemerintah(an) otokratis, yang identik dengan
perintah dan titah itu untuk merawat ketundukan dan kesetiaan rakyat pada penguasa.
Bahasa tentu bersifat partikular, dan karena itu, pemerintah(an) perlu dipelajari
dengan pengetahuan dialektis antara pengetahuan universal dan ikatan budaya. Dwight
Waldo (1955) menyarankan untuk memahami pemerintahan dengan kerangka konstitusi
dan demokrasi, meski demokrasi hanya menjadi salah satu jenis pemerintahan.
Bagaimanapun pemerintahan demokratis (kedaulatan rakyat) adalah pilihan konstitusi
Indonesia, yang tentu memahami pemerintahan bukan sekadar perintah dan titah.
Demokrasi adalah jenis politik paling utama dan mulia. Karena itu, meminjam S. Finer
(1970), pemahaman pemerintahan harus dimulai dari politik, yakni sebagai politik yang
dilembagakan, yakni kekuasaan yang dilembagakan menjadi kewenangan untuk
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 7
memutuskan dan melaksanakan. Bukan sekadar politik, H. Finer (1946), yang kerap
dikutip, memahami pemerintahan sebagai politik dan administrasi, atau pemerintahan
terdiri dari proses politik dan proses administrasi yang koheren. Politik adalah soal
kehendak sosial, persetujuan rakyat, dan kekuasaan untuk menetapkan hukum.
Administrasi adalah penggunaan cadangan kehendak dan kekuasaan sosial ini dengan
metode personal, mekanik, teritorial, dan prosedural yang sesuai untuk memberikan
layanan pemerintah secara spesifik kepada mereka yang berhak. Mesin administrasi
berada di bawah fase politik dalam pemerintahan, dan memang seharusnya demikian,
sebab politik menentukan kehendak dan fungsi, dan ini bekerja sebelum, berdaulat atas
dan pencipta mesin dan prosedur administrasi. Administrasi adalah pelengkap diskresi
dan diskresi adalah politik yang hampir sepenuhnya tidak terhalang dan karakter serta
kehendak bebasnya, tetapi administrasi hanyalah cerminan dari kekuasaan politik. Ini
adalah penerima jumlah kebijaksanaan yang lebih kecil.
Lebih kompleks dari makna dan proses memerintah, pemerintahan secara lengkap
berbicara tentang “siapa memerintah siapa, apa, dan bagaimana”. Konsep siapa pertama
menunjuk subjek, yakni pemerintah. Dalam politas fasis, negara bertindak sebagai
pemerintah, kepala negara secara absolut menjalankan pemerintahan. Dalam politas
demokratis, pemerintah sebagai representasi kedaulatan rakyat menjalankan
pemerintahan. Di luar dua politas itu, ada pula penguasa yang bertindak sebagai
pemerintah, ada pula aristokrat, segelintir elite yang disebut pemerintahan oligarkhis,
serta ada pula pemerintahan dipegang oleh birokrat yang kerap disebut negara pegawai
(birokratik).
Masalah who govern itu bisa menjadi analisis empirik yang selalu menarik. Tetapi
saya hendak mengatakan bahwa frasa “siapa memerintah siapa, apa, dan bagaimana”
merupakan susunan kelembagaan yang dipengaruhi oleh tradisi pengetahuan. Dalam
konteks ini, pengetahuan dan praktik pemerintahan di Indonesia dibentuk oleh divergensi
dan konvergensi antara tradisi Eropa Kontinental versus Anglo Saxon sekaligus
perbedaan antara politik versus administrasi. Tradisi Eropa yang mengutamakan
stateness, berbicara tentang negara, hukum dan administrasi; sebaliknya tradisi Anglo
Saxon yang bercorak stateless berbicara pemerintah, politik dan administrasi (Dyson,
1980; B.G Peters, 1999; Overeem, 2013; Bohne, 2014; Grimm, 2016; Maier, 2019).
Konsepsi negara hukum (rechtsstaat) sebenarnya bukan negara legal-formal belaka,
tetapi esensinya adalah negara adil yang melindungi kebebasan, tetapi legalisme negara
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
8 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
hukum telah membentuk pemahaman tentang hukum pemerintahan. Konvergensi
administrasi pada dua tradisi itu membuat mazhab administrasi pemerintahan, dan di
zaman neoliberal, konvergensi ini melahirkan manajemen dan tatakelola pemerintahan.
Tradisi ilmu politik yang kuat di Amerika membentuk mazhab politik pemerintahan.
Beragam mazhab itu menunjukkan bahwa pengetahuan pemerintahan terpotong-
potong (mutilasi) sehingga tidak terbangun koherensi secara utuh. Raadschelders (2000),
misalnya, menyampaikan analogi “bisa melihat pohon-pohon, tetapi tidak bisa melihat
hutan. Analogi itu berarti, orang melihat pohon hukum, pohon politik, dan pohon
administrasi, tetapi tidak melihat hutan pemerintahan. Dengan analogi itu, Raadschelders
menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pemerintahan mengalami fragmentasi dan
kompartemenisasi. “... para peneliti semakin menyadari bahwa pengetahuan kita tentang
pemerintah dan pemerintahan terkotak sedemikian rupa sehingga pemahaman yang lebih
holistik atas fenomena sosial ini dalam konteks sosialnya sangat hilang baik dalam
penelitian maupun pengajaran”, demikian ungkap Raadschelders.
HUKUM PEMERINTAHAN
UUD 1945 memperoleh pengaruh campuran antara tradisi Anglo Saxon dan Eropa
Kontinental yang dikontekstualisasikan sesuai aspirasi dan kondisi Indonesia. Konstitusi
menyebut “rakyat” 100 kali, “negara” juga 100 kali, “pemerintah(an)” 32 kali, “hukum”
20 kali, “warga” 17 kali, “manusia” 10 kali, dan “masyarakat” 10 kali. Konstitusi
menegaskan rakyat yang menyatakan kemerdekaan untuk membentuk Negara Republik
Indonesia.
Namun campuran ini pasti licin, diperebutkan oleh beragam sekte dan mazhab
pengetahuan. Saya sebagai sarjana politik-pemerintahan sangat menyukai paragraf
keempat Pembukaan UUD 1945 yang ideologis, baik frasa “Pemerintah Negara
Indonesia” yang diikuti dengan rangkaian tujuan kemerdekaan; serta frasa “Negara
Repubik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Sebaliknya, para sarjana hukum lebih
sering mendiskusikan frasa “Indonesia negara hukum demokratis” yang ada dalam batang
tubuh. Bagi saya, frasa “Negara Repubik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” adalah
kebaruan, buah dari dekolonisasi, yang membedakan dengan negara kolonial.
Bagaimanapun praktik negara hukum sudah ada dalam negara kolonial, yakni penguasa
kolonial memerintah dengan hukum (rule by law), meski hukum itu bukan untuk
kebebasan, hak asasi manusia dan demokrasi.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 9
Konsep negara hukum (rechtsstaat) pernah disebut dalam konstitusi awal, namun
kata asing itu hilang dan diganti menjadi “negara hukum yang demokratis” dalam
konstitusi amandemen, yang mungkin dimaksudkan bisa mengakomodasi secara luwes
terhadap gagasan rule of law yang muncul dari tradisi Anglo Saxon. Frasa “negara hukum
demokratis” (democratic rechtsstaat) juga sudah dipakai oleh Jerman setelah Perang
Dunia II, yang sekarang disebut negara konstitusional. Bahkan di era neoliberal selama
hampir tiga dekade terakhir, rule of law dipakai secara global, menandai konvergensi cara
pandang hukum, baik Amerika maupun Eropa.
Karena pengaruh tradisi Eropa, dan karena warisan kolonial, ide “negara centris”
memang sangat kuat, bahkan lebih kuat ketimbang pemerintah demokratis, meski kata
kunci rakyat – sebagai sebuah konsep politik -- sangat fundamental dalam konstitusi. Para
sarjana hukum sukses melakukan glorifikasi konsep negara hukum, supremasi hukum,
penegakan hukum, dan hukum sebagai panglima untuk melawan politik atau ekonomi
sebagai panglima. Pandangan hukum positivis dan dogmatis mengatakan bahwa
supremasi hukum harus di atas segalanya, bahwa kekuasaan negara dan penyelenggaraan
pemerintahan harus berdasar pada hukum secara konstitusional, bukan pada kekuasaan
semata. Argumen ini adalah sebuah “moralitas politik” yang anti-politik untuk melawan
penguasa yang mereka sebut lalim dan tidak bermoral seperti setan.
Pemikiran negara centris melahirkan ilmu negara di Fakultas Hukum. Ilmu negara,
yang legal formal, dipotong-potong menjadi hukum tata negara, hukum administrasi
negara, hukum tata pemerintahan. Ketika kuliah S1, saya memperoleh empat mata kuliah
berjudul hukum: Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Hukum Tata Negara,
dan Hukum Tata Pemerintahan. Tetapi setelah pembaruan kurikulum 1991 yang
disubversi oleh Ilmu Politik, mata kuliah bernama hukum hilang dari kurikulum IP,
diganti dengan sejumlah mata kuliah bernama politik.
Para sarjana hukum positivis-kontinental memahami pemerintahan bukan dengan
politik dan demokrasi, melainkan dengan kerangka negara hukum, dan menempatkan
peran sentral hukum dalam pemerintahan (BG Peters, 1999), sehingga dapat dikatakan
bahwa pemerintahan adalah hukum. Secara hukum, aktivitas pemerintahan dimaknai
sebagai perbuatan “mengatur dan mengurus”, yang sampai sekarang dikenal secara paten
dalam undang-undang. Menurut sudut hukum, pemerintahan mengandung pembentukan
hukum, pelaksanaan hukum, dan penegakan hukum. Pembentukan hukum, menurut
aliran hukum positif, harus menurunkan perintah dan harus sesuai dengan konstitusi.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
10 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
Karena itu institusi hukum maupun sarjana hukum harus mengambil peran besar dalam
membuat undang-undang. Menurut Anglo Saxon, pembentukan hukum adalah perbuatan
politik, dan pelaksanaan hukum adalah tindakan administrasi. Politik berbicara tentang
siapa yang membuat hukum dan apa isi hukum, dan administrasi adalah soal bagaimana
menjalankan hukum. Subjek yang disebut siapa tidak lain adalah institusi pemegang
kedaulatan rakyat, yakni parlemen dan pemerintah.
Hukum positivistik memandang pemerintahan harus bekerja seperti baris-berbaris:
“setiap orang tidak bisa melakukan apapun kecuali yang diperintah”. Pejabat pemerintah
bisa berbuat kalau memperoleh perintah hukum. Jika tidak ada perintah hukum, maka
pejabat tidak boleh berbuat meskipun didesak oleh rakyat. Hukum bukan ekspresi
kebebasan seperti bermain sepak bola (setiap pemain bebas melakukan apapun kecuali
yang dilarang, seperti petuah rule of law oleh AV Dicey), bukan pula untuk pencapaian
kehendak rakyat dan hak warga secara adil, bukan pula untuk memperkuat otoritas dan
diskresi pemerintah yang sesuai dengan konteks sosial dan kehendak rakyat. Hukum yang
kaku lebih banyak untuk mengendalikan dan membatasi kekuasaan pemerintah, daripada
memberi energi kepada pemerintah. “Ketika orang Amerika berpikir tentang masalah
pembangunan pemerintah, ia mengarahkan dirinya bukan pada penciptaan otoritas dan
akumulasi kekuasaan tetapi lebih pada pembatasan otoritas dan pembagian kekuasaan”,
ungkap Huntington (1968). Dengan begitu, hukum tidak menjadi apa yang disebut J.
Wilson (1896) sebagai “otot besar pemerintah” (great sinew of government) untuk
mewujudkan kehendak rakyat, melainkan malah menjadi birokrasi “sangkar besi” yang
diingatkan Max Weber. Pejuang hukum progresif, Prof. Satjipto Rahardjo, juga
mengingatkan bahwa Indonesia bukan “negara hukum” melainkan “negara peraturan”;
yakni bukan hukum untuk manusia tetapi manusia untuk hukum.
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
IP secara eksplisit menjadi sebuah nama jurusan, bersama Publisistik dan
Hubungan Internasional, dalam Akademi Ilmu Politik (AIP) yang berdiri tahun 1947 di
Yogyakarta. Kata “politik” dan tiga jurusan itu sebenarnya bercita rasa Anglo Saxon
ketimbang Eropa Kontinental, sebab selama masa penjajahan, tidak pernah mengajarkan
kata politik, dan kata ini tentu hadir karena spirit dekolonisasi. AIP dibubarkan pada tahun
1949, bergabung ke dalam Fakultas Hukum Sosial Politik di UGM. Fakultas ini
bertambah menjadi Fakultas Hukum Ekonomi Sosial Politik pada tahun 1951. Tahun
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 11
1958, Jurusan IP hilang, diganti dengan nama ilmu usaha negara. Dua tahun sebelumnya
lahir sekolah kedinasan Departemen Dalam Negeri, yakni Akademi Pemerintahan Dalam
Negeri, yang memiliki tubuh pengetahuan IP. Tahun 1960, ilmu usaha negara berganti
lagi menjadi IP, dan lahir pula ilmu administrasi negara di Fakultas Sosial Politik.
Pembentukan dan pengajaran IP dilakukan karena alasan aksiologis-praktis, yaitu
mengisi tenaga pamong praja yang terdidik dan terlatih, seperti halnya pengajaran yang
pernah dilakukan oleh negara kolonial. Pilihan kebijakan ini tidak salah tetapi juga tidak
duduk. Jika duduk secara koheren, maka IP seharusnya mendidik kader-kader pemerintah
maupun mencerahkan pemerintah(an), meski siapapun bisa menjadi pemerintah,
termasuk rakyat jelata yang tidak sekolah. Untuk mendidik kader-kader negara (baca:
pamong praja, atau birokrat), lebih duduk dengan administrasi publik atau ilmu usaha
negara. Dengan begitu, IP tumpul tidak berkembang sesuai dengan ontologi-epistemologi
pemerintahan, melainkan sebagai sekolah pamong praja atau bisa disebut birokratologi
(ilmu yang mempelajaridan membentuk birokrasi). Konstruksi pemahaman ini tidak lain
karena roh pemerintahan “negara pegawai” (HJ Benda, 1966; R. McVey, 1982) yang
diwarisi dari negara kolonial, meskipun konstitusi sudah menegaskan “pemerintahan
berkedaulatan rakyat”.
Pendiri dan pengasuh IP generasi awal adalah para sarjana hukum didikan Indologi,
meskipun tradisi ini sebenarnya tidak mengenal konsep pemerintah, melainkan negara.
Agar tidak terlalu hukum, para mahasiswa IP memperoleh pelajaran tentang bestuur
(yang diterjemahkan menjadi pemerintahan), sebuah konsep yang sudah lama dikenal
dalam pengajaran dan praktik administrasi negara kolonial. Buku Gerrit van Poelje
Algemene Inleiding tot de Bestuurskunde telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia,
Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan (1953), yang diajarkan sekaligus menjadi buku
hafalan bagi mahasiswa IP. Bestuurskunde, yang disebut IP (terapan) itu, menurut Poelje,
adalah ilmu yang mengajarkan bagaimana mengatur dan memimpin sebaik-baiknya dinas
umum. Ini serupa dengan ilmu kedinasan dan perkantoran. Bahkan tidak sedikit sarjana
IP yang menobatkan Gerrit van Poelje sebagai Bapak IP. Penobatan ini merupakan
perbuatan salah dan serampangan yang tidak pantas untuk diakui.
Pemahaman pemerintahan dengan lensa bestuur itu mengandung sejumlah
masalah dan kesalahan. Pertama, kesalahan etimologi dan terjemahan. Menterjemahkan
bestuur menjadi pemerintahan adalah salah kaprah, kesalahan serius yang selalu
dibenarkan menjadi kebenaran. Tradisi pengetahuan Eropa Kontinental, termasuk
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
12 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
Belanda, tidak pernah menjadikan “pemerintah” sebagai tema pemikiran dan subjek
kajian. LP van de Spiegel pernah menulis risalah Schets Der Regeerkunde (1786), dengan
makna regeer lebih dekat ke konsep pemerintahan ketimbang bestuur, dan buku ini
dianggap Rutgers (2005) sebagai Het Gulden Boekje Uit De Nederlandse Bestuurskunde,
buku emas administrasi Belanda. Tetapi regeerkunde mati suri di Belanda, dan kelak
nama ini malah dijadikan semacam “IP” oleh Afrika Selatan. Baru tahun 1928, hadir
Gerrit van Poelje, seorang pejabat yang menjadi profesor pertama dalam bidang
bestuurskunde dan mendirikan bestuurskunde di Nederlandsche Handels-Hoogeschool.
Para sarjana Belanda memaknai bestuur bukan sebagai pemerintahan tetapi sebagai
administrasi. Setelah Perang Dunia II, apa yang disebut bestuurskunde disepakati dan
dirayakan oleh para sarjana sebagai administrasi publik ala Belanda, yang setara dengan
public administration ala Amerika Serikat (Kickert dan Toonen, 2006; Philip Marcel
Karré dkk, 2020).
Bahkan generasi baru sudah meninggalkan ajaran bestuurskunde warisan van
Poelje yang praktikal, menuju ilmu yang reflektif dan kritis. Bestuurkunde warisan lama
dipandang mengabaikan rasionalitas hukum, ekonomi dan pratik politik (Kickert
danToonen, 2006; Braun dkk, 2015; Schillemans, 2017). Jurnal Bestuurkunde edisi
terbaru 2020, sengaja mengusung tema Kritische Bestuurskunde, yang meninjau ulang
pengetahuan instrumental, sembari membawa studi kebijakan dan administrasi
menggunakan teori kritis. “Kami percaya bahwa pendekatan kritis tidak hanya memiliki
prinsip-prinsip lapangan sebagai objek analisis, tetapi juga realitas politik dan praktik
kebijakan”, ungkap Robert van Putten dkk (2020). Dengan pendekatan kritis, Asosiasi
Administrasi Publik Belanda (Vereniging voor Bestuurskunde) hendak membawa
kebijakan dan administrasi yang mereka tekuni menjadi masalah publik, bersentuhan
dengan konflik nilai dalam masyarakat, masuk ke ruang percakapan demokratis,
sekaligus relevan dengan praktik debat sosial yang lebih luas.
Kedua, praktik dan IP dipandang dan disusun sebagai bestuur, atau pemerintahan
sebagai administrasi, membuatnya menjadi sempit, parsial, tanggung, praktis, dan naif.
Pemahaman ini serupa dengan perbuatan administratif yang dilakukan oleh para
administrator di kantor organisasi perangkat daerah (OPD, yang bukan organisasi
pemerintahan daerah), mulai dari dinas hingga kecamatan. Ranah openbaar bestuur itu
termasuk pemerintahan, tetapi pemerintahan tanpa pemerintah, atau pemerintahan yang
dikerjakan oleh administrator. IP dalam pengertian bestuurkunde cenderung mekanik,
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 13
normatif, menuntun, menggurui, menawarakan sollen, dan hanya membekali
keterampilan profesional-birokratis (S. Djojowadono, 2015; M. Tjokrowinoto, 2015).
Pemahaman praktis-instrumental para sesepuh itu menurun kepada anak didik dari
generasi ke generasi yang sebagian besar menjadi aparat sipil negara. Salah satu yang
“salah kaprah” adalah munculnya pemahaman bahwa kecamatan adalah pemerintah,
dengan sebutan “pemerintah kecamatan”, disertai artikulasi diskursus bahwa camat harus
dipegang oleh sarjana pemerintahan. Ada pula profesor yang “mengukur” pemerintahan
dengan lensa administrasi formal tanpa politik, menyebut pemerintahan desa adalah
pemerintahan palsu karena desa tidak mempunyai council, dinas, inspektorat, pegawai
negeri, dan tidak menyelenggarakan pelayanan publik seperti local government. Di mata
saya, yang palsu bukan pemerintahan desa, melainkan yang palsu adalah pengetahuan
profesor itu tentang pemerintahan; ibarat bersikukuh hanya mengakui pada satu jenis
ayam untuk mengatakan bahwa jenis-jenis ayam yang lain bukan ayam
Secara keilmuan, IP anti pada politik, padahal “pemerintahan berkedaulatan rakyat”
sangat bermakna politik, sebagai bentuk dekolonisasi dan pembebasan dari
“pemerintahan birokratik” atau “negara pegawai”, menyerupai gagasan pemerintahan
republiken dalam tradisi Anglo Saxon. IP selama tiga dekade sudah bercerai dan
melupakan hukum, yang sebenarnya mendirikan dan membentuk IP. Meninggalkan
hukum positif itu sangat baik, tetapi kalau IP tidak mengetahui hukum progresif, hukum
politik, dan hukum deliberatif, juga berbahaya. Sebaliknya di kandang Fakultas Hukum
juga masih melakukan kajian dan mengajarkan pemerintahan dengan lensa hukum positif.
Mereka secara eksklusif mendidik dan mengajarkan orang banyak untuk melihat
pemerintahan dengan cara hakim, meletakkan jargon supremasi hukum di atas
pemerintahan, sehingga sanggup membuat pemerintah patuh pada hukum (baca: aturan)
tetapi abai secara politik pada daulat rakyat.
Meskipun dibentuk dengan bestuur (administrasi ala kolonial Belanda), dan
kemudian ditambah administrasi publik ilmiah ala Amerika sejak Orde Baru, namun IP
enggan disebut dan menyebut sebagai Ilmu Administrasi. IP mempelajari, mengajarkan,
dan mengkaji berbagai konsep kunci dalam administrasi publik (kinerja, efektivitas,
formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, pelayanan publik, standar operasional dan
prosedur, dan lain-lain), tetapi ia mengaku bukan administrasi publik, meskipun tidak
sanggup membedakan antara pemerintahan dan administrasi.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
14 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
Mungkin semua itu bisa disebut “ketidaktahuan atas apa yang diketahui”. Tetapi
pengetahuan dan praktik pemerintahan yang mungkin mengandung “ketidaktahuan atas
apa yang diketahui” itu sudah menjadi norma, habitus, dan wabah yang disengaja, baik
di kampus maupun di kantor kecamatan, sehingga saya sebut bukan lagi sebagai “ilmu
pengetahuan” melainkan “politik pengetahuan”. Maksudnya adalah, di balik pengetahuan
terdapat kepentingan dan kekuasaan, yakni kekuasaan pemerintahan birokratik yang anti-
politik dan anti pemerintahan berkedaulatan rakyat yang dimandatkan konstitusi.
Ketiga, konsep pemerintah merupakan tradisi Anglo Saxon, dan dengan semangat
dekolinisasi, konstitusi Indonesia menegaskan konsep “pemerintah yang berkedaulatan
rakyat”, tetapi sayang, tetapi sayang, IP mengajarkan pemerintahan sebagai bestuur ala
kontinental dan kolonial. Pemerintahan sebagai bestuur itu sudah diajarkan dan
dipraktikkan oleh negara kolonial Belanda di Hindia Belanda dengan sebutan
binnenlands bestuur (BB), yang dimaknai sebagai Pemerintahan Dalam Negeri. BB
secara keilmuan mengandung hukum-administrasi yang bercorak formalistik, hirarkhis,
sentralistik, dan birokratik. Negara kolonial yang memilah birokrasi menjadi dua lapis:
BB sebagai birokrasi level tinggi dari gubernur jenderal sampai asisten residen yang
dipegang oleh orang Eropa, dan pangreh praja (Indslands Bestuur) sebagai level rendah
yang mewadahi priyayi pribumi ke dalam birokrasi mulai dari bupati ke bawah.
HJ Benda (1966) menyebut negara kolonial itu sebagai negara pegawai
(Beamtenstaaten), yang apolitis, dengan corak pemerintahan administratif par
excellence. BB, dimata Benda, adalah sosok "setengah dewa" yang sangat kuat di dunia
kolonial. Para aparat negara kolonial bertugas mempertahankan perdamaian dan
ketertiban sebagai sumum bonum, sekaligus juga mengutamakan kebijakan kolonial di
atas semua instrumen untuk implementasi, bukan dari tuntutan sosial yang bersaing tetapi
dari dan untuk "administrasi yang baik" semata. Untuk mendukung birokrasi dan
“administrasi yang baik” itu, pada awal 1900, negara kolonial mendirikan Opleiding
Schoolen voor Indlansche Ambtenaren atau Sekolah Pendidikan Pegawai Bumiputera),
setingkat perguruan tinggi, di Bandung, Magelang, dan Probolinggo, yang kemudian
berkembang menjadi MOSVIA (Middelbaar Opleiden Schoolen voor Indische
Ambtenaren) pada 1927. Keduanya mengajarkan hukum administrasi untuk menyiapkan
pangreh praja yang kompeten, cekatan, tertib, loyal, berwibawa, dan menjadi pusat
teladan bagi rakyat jelata.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 15
Pengetahuan tentang bestuur terus diwariskan melalui IP di UGM, universitas lain,
maupun lebih massif di APDN. IP identik dengan Orde Baru, yang mewarisi kolonialisme
dan menyepuhnya dengan developmentalisme. Bestuur merupakan warisan kolonial,
administrasi merupakan sepuhan developmentalisme untuk keperluan modernisasi
birokrasi. Keduanya anti-politik, apalagi hidup di zaman Orde Baru. Waktu itu, tidak
sedikit mahasiswa yang menulis skripsi dengan pola template dan bercita rasa
administrasi, dengan judul seputar: “Pengaruh Kepemimpinan, Koordinasi, Motivasi,
dan Pengawasan terhadap Efektivitas Penarikan Retribusi Daerah”. Ini tampak lebih
cocok sebagai ilmu kedinasan atau ilmu perkantoran ketimbang IP.
Cita rasa bestuurkunde tidak pernah hilang dalam jiwa IP, sebagaimana cita rasa
“negara pegawai” dalam pemerintahan Indonesia. Nama Gerrit van Poelje masih tetap
harum, menghiasi pengetahuan dan tulisan para sarjana kontemporer (F. Van Ylst, 2015;
N. Karniawati, 2015; P. Polyando, 2016). Namun IP tetap enggan untuk menjadi Ilmu
Administrasi. Sementara disiplin Administrasi Publik, yang mengkaji government in
action, berkembang pesat secara epistimelogis di belahan dunia, tetapi terlalu banyak
mahasiswa dan sarjana IP masih rajin meneliti “administrasi lama” dengan tema “kinerja
dan efektivitas” dengan pola template dan positivistik.
MANAJEMEN DAN TATAKELOLA PEMERINTAHAN
Konvergensi pertama administrasi antara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon,
yang disebut big government (negara administratif, pemerintahan birokratik, dan otonomi
birokrasi) bertahan selama empat dekade sampai 1980-an. Seiring dengan krisis
kapitalisme, antara lain akibat Perang Teluk yang panjang, sejak dekade 1980-an
melahirkan ideologi dan proyek neoliberalisme. Kehadiran neoliberalisme melahirkan
bentuk konvergensi kedua di sisi administrasi antara Eropa Kontinental dan Anglo Saxon,
yang antara lain menyajikan diskursus managerialisme baru, manajemen publik baru,
tatakelola (governance, dan lebih khusus good governance), dan reinventing government.
Di bawah payung neoliberalisme, konvergensi baru antara Eropa dan Amerika terjalin
kuat, yang menggempur konvergensi pertama, seraya menggeser big government menjadi
big governance, dari more government ke less government dan more market, mengganti
konsep negara ke konsep sektor publik, dari administrasi ke manajemen, dari negara
hukum (rechtsstaat) ke rule of law, dari birokrasi ke jaringan, dari birokratisasi ke
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
16 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
deregulasi, debirokratisasi, dan privatisasi, dari sentralisasi ke desentralisasi, serta dari
nasionalisasi ke globalisasi.
Para pendukung neoliberalisme berujar bahwa pemerintah adalah masalah,
pemerintah menyebalkan, yang di mata mereka gagal mengelola kapitalisme. Presiden
Ronald Reagan pada tahun 1982 berujar bahwa pemerintah adalah bagian dari masalah.
Pada tahun 1996, Presiden Bill Clinton, yang memperoleh nasihat dari penulis buku
Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1992), berujar bahwa era pemerintah
besar telah berakhir, yang berubah menjadi pemerintah ramping.
Dengan diskursus “pemerintah adalah masalah”, seolah kaum neoliberal
menganggap bahwa pemerintah adalah musuh mereka, dan seolah mereka tidak
membutuhkan pemerintah. Masksudnya bukan itu. Buruh adalah musuh utama
neoliberalisme. Negara berdaulat, pemerintah besar dan kuat, serta demokrasi yang kokoh
adalah hambatan bagi neoliberalisme dan kapitalisme global. Kalau negara, pemerintah,
dan demokrasi kuat, maka dengan sendirinya juga bersatu dengan buruh yang kuat.
Formasi politik yang kuat membahayakan bagi bisnis kaum neoliberal, sehingga yang
dipukul pertama adalah pemerintah. Mereka tidak menghendaki pemimpin, negarawan,
politisi, maupun parlemen yang kuat, sebaliknya lebih suka pada para ahli, profesional,
dan teknokrat yang mudah mereka kendalikan (Harvey, 2007). Kaum neoliberal
sebenarnya tidak menghendaki negara kecil dan langsing, tetapi negara yang
membengkak melalui banyak campur tangan pemerintah (Plant, 2010). Campur tangan
pemerintah itu antara lain memotong monopoli otoritas Bank Central yang sebagian
otoritasnya dipindahkan ke Otoritas Jasa Keuangan, memotong otoritas institusi yudikatif
konvensional untuk dipindahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, hingga menuntut
pemerintah membuat regulasi yang ramah terhadap pasar dan swasta maupun regulasi
yang bisa menciptakan stabilitas dengan cara mengendalikan amarah buruh.
Pada level meso dan mikro, kaum neoliberal mempunyai pengetahuan dan
teknologi kekuasaan seperti manajemen publik, reformasi sektor publik, maupun
tatakelola (governance) yang lebih khusus lagi pada good governance. Pertama,
pemerintahan dimaknai sebagai manajemen publik untuk menyepuh pemerintahan
sebagai administrasi publik. Para pengajar Fakultas Manajemen Pemerintahan di IPDN
cenderung berdiri di sini (Ndraha, 2003; Wasistiono, 2017). Seperti halnya disiplin
Administrasi Publik, titik perhatian “pemerintahan sebagai manajemen” adalah
pelayanan publik. Apa yang membedakan manajemen dengan administrasi? Administrasi
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 17
dikenal dalam dunia pemerintahan negara. Manajemen dikenal dalam dunia bisnis
perusahaan. Dalam pemerintahan demokratis, administrasi merupakan kelanjutan dari
politik dan hukum. Politik adalah soal menentukan arah dan nilai yang melandasi
kebijakan, sekaligus juga berurusan dengan apa, siapa dan bagaimana pembentukan
hukum (undang-undang), yakni melalui institusi pemegang kedaulatan rakyat
(pemerintah-eksekutif dan parlemen-legislatif). Administrasi adalah soal pelaksanaan
hukum yang dijalankan oleh birokrasi dengan dikendalikan oleh pemerintah-eksekutif.
Rangkaian ini semua bermaksud untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagai “input”
pembentuk pemerintahan, sekaligus menghadirkan negara untuk melayani-melindungi
warga sebagai “output”. Manajemen, yang dipelajari oleh ekonomi, berbicara tentang
perbuatan merencanakan, mengelola, mengendalikan, dan menggerakkan sumberdaya
dalam organisasi bisnis secara efisien untuk mencapai efektivitas dan produktivitas
berupa keuntungan sebesar-besarnya.
Kedua konsep itu barangkali mempunyai kesamaan pada tindakan, tetapi sangat
berbeda pada sisi nilai, kepentingan, dan tujuan. Administrasi birokrasi juga berbicara
tentang kompetensi profesional, efisiensi dan efektivitas, tetapi administrasi yang
digerakkan oleh pemerintah ini tidak mengejar laba-keuntungan seperti halnya dalam
manajemen perusahaan.
Tetapi neoliberalisme membuat manajemen menjadi digdaya dan hegemonik.
Kaum neoliberal membuat manajemen bukan sebagai perangkat ilmiah tetapi menjadi
ideologi, yang para kritikus, menyebutnya sebagai manajerialisme. Mereka memasukkan
manajemen dan manajerialisme ke dalam dunia politik, pemerintahan dan negara. Mereka
menggunakan manajerialisme untuk melucuti pemerintah-negara, yang melalui
manajemen publik, mengarahkan sektor publik dan pelayanan dikelola dengan
manajemen bisnis dengan mata uang efisiensi dan laba. Demikian catatan kritis Thomas
Klikauer (2013):
“Manajerialisme menggabungkan alat generik dan pengetahuan manajemen dengan
ideologi untuk memantapkan dirinya secara sistemik dalam organisasi, lembaga publik,
dan masyarakat sambil merampas pemilik bisnis (properti), pekerja (organisasi-ekonomi)
dan masyarakat sipil (sosial-politik) dari semua kekuatan pengambilan keputusan.
Manajerialisme membenarkan penerapan teknik manajerial satu-dimensi untuk semua
bidang pekerjaan, masyarakat, dan kapitalisme atas dasar ideologi unggul, pelatihan
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
18 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
pakar, dan eksklusivitas pengetahuan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan
lembaga publik dan masyarakat sebagai korporasi.”
Pengetahuan itu sudah jauh dari konsep “pemerintahan berkedaulatan rakyat” yang
dimandatkan konstitusi. Bagaimanapun pelayanan publik untuk warga harus baik dan
efektif. Tetapi apakah ini bisa diselesaikan dengan manajemen publik dan pendekatan
pelanggan? Bagaimana konstruksi pengetahuan “pemerintahan sebagai manajemen”
memahami perbuatan pemerintahan secara politik, hukum, dan administrasi untuk
melakukan transformasi dari manusia menjadi rakyat dan menjadi warga? Cara pandang
manajerialisme tidak peduli pada masalah itu. Mereka tidak peduli pada pemerintah yang
kuat dan berkedaulatan rakyat. Kepedulian mereka adalah membuat pemerintah sebagai
korporasi.
Kedua, pemerintahan sebagai tatakelola (governance). Konsep, yang dibangun
dengan anti-government ini, sungguh licin. Seperti halnya konsep government
sebelumnya, konsep governance juga dimaknai dengan sudut yang berbeda. Politik pada
umumnya memahami governance sebagai relasi kuasa antara pemerintah dan rakyat, atau
relasi antara negara dan nonnegara. Selebihnya memahami governance dari sudut
administrasi, manajemen dan teknis, yakni governance dalam pengertian pasar, jaringan,
kerjasama, kemitraan, dan lain-lain.
Peringatan dan kritik terhadap governance sudah sangat banyak. Rhodes (1996),
seorang professor of government, yang selalu mengutamakan pemerintah (government),
mengingatkan bahwa tatakelola sebagai jaringan yang mengatur diri sendiri merupakan
tantangan bagi kemampuan memerintah karena jaringan menjadi otonom dan menolak
panduan pusat. Mereka adalah contoh utama “kepemerintahan tanpa pemerintah”. Bagi
saya, governance sangat penting, tetapi bisa juga berbahaya. Pemerintah(an) tanpa
governance akan membuat birokratik dan lalim, tetapi governance tanpa pemerintah,
akan membuat teknokrasi yang kian melemahkan pemerintah demokratis untuk
mewujudkan kehendak rakyat.
Meskipun diskusi governance berbuih-buih, namun akhirnya, ia diambil alih oleh
governance (GG), yang oleh M. Grindle (2017), sebagai pendamping normatif. GG
sangat marak di Indonesia selama era reformasi. Ketika bicara GG, orang langsung
menunjuk sejumlah indikator, misalnya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, rule of
law, responsivitas dan seterusnya. Dulu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat
gemar dengan GG, yang beliau pidatokan di ruang wakil rakyat hingga dalam sidang
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 19
PBB. Sejumlah indikator GG lantas menjadi asas-asas penyelenggaraan pemerintahan
yang baik dalam UU No. 30/2014 tentang administrasi pemerintahan. Rezim pendidikan
tinggi juga suka “good university governance” sebagai instrumen standarisasi dan
kendali. GG diajarkan menjadi materi diklat bagi PNS, yang harus dihafal dengan baik
seperti menghafal Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Para mahasiswa dan sarjana IP
sangat suka pada dua konsep ini, dengan nalar yang lazim: melubangi dan melemahkan
pemerintah. Mereka memanfaatkan indikator GG sebagai barang template yang mudah,
positif, dan objektif untuk penelitian deskriptif terhadap pekerjaan pemerintah.
Di tengah wabah GG, di tempat lain kritik terhadap GG sudah berhamburan,
bahkan mengajak untuk meninggalkan mantra buatan kaum neoliberal itu. Dengan
analisis poskolonial yang anti-orientalisme, R. Abrahamsen (2000), berujar bahwa
agenda GG, yang lahir ketika Perang Dingin usai, merupakan bagian tak terpisahkan dari
teknologi kekuasaan yang bekerja dalam politik internasional dan merupakan salah satu
cara yang digunakan negara-negara Utara dalam mengelola dan melegitimasi
keberlangsungan dan kekuasaan dan hegemoninya atas negara-negara Selatan. Dalam
pidato guru besar, Cornelis Lay (2019) berujar: “Good governance merupakan solusi
seragam untuk semua masalah, dari ujung Afrika sampai pelosok Indonesia, tetapi tidak
membawa akibat apapun”. Setelah berulang tahun 30, demikian ungkap M. Grindle
(2017), GG sebenarnya sudah mati (rest in peace). Di mata Grindle GG membuat
kecanduan ketimbang membangkitkan pemikiran analitik; ia lebih banyak mengaburkan
ketimbang mencerahkan.
POLITIK PEMERINTAHAN
Para penganut “IP otonom” pernah menuding bahwa IP di UGM, yang lahir
kembali pada tahun 1960, lebih bersifat politik daripada pemerintahan. Kondisi ini,
menurut Sujamto (2015), karena “penguasa secara sadar menempatkan politik sebagai
panglima”. Ini pendapat khas administrasi bestuurkunde yang anti-politik, untuk
melemahkan Soekarno -- yang memaknai politik sebagai debat tentang arah dan
kebijakan guna mencapai tujuan kemerdekaan – sebagai pembenar kehadiran “ekonomi
sebagai panglima” model developmentalis-kolonial pada era Orde Baru.
Ketika politik masih menjadi barang tabu di zaman Orde Baru, mulai penghujung
hadir Afan Gaffar, Riswandha Imawan, dan M. Ryaas Rasyid yang membawa ilmu politik
untuk mewarnai IP. Meski analisis sistem politik dan struktural fungsional sudah
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
20 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
diajarkan bertahun-tahun yang sangat cocok dengan developmentalisme Orde Baru,
namun kehadiran mereka menyuntikkan banyak pengetahuan politik yang berguna untuk
subversi terhadap dominasi hukum dan administrasi dalam IP.
Era reformasi, sebagai era politik, disambut dengan banjir studi politik. Para
sarjana meninggalkan konsep pemerintah (government), karena secara metodologis, studi
tentang pemerintah(an) identik dengan studi institusionalisme lama. Para sarjana ilmu
politik, maupun sebagian mahasiswa dan sarjana pemerintahan yang menyukai politik,
lebih banyak berbicara tentang kekuasaan (power) dan penguasaan (ruling) ketimbang
governing. Kajian tentang kekuasaan dialamatkan pada studi tentang negara, proses
elektoral, dan penguasa untuk menggantikan konsep pemerintah. Dengan spirit
moralisme-malaikatisme (entah pluralisme liberal atau elitisme sebagai pluralisme
terbalik), mereka sangat suka dengan sederet konsep (oligarki, elite predator, elite
capture, dinasti, negara gagal, bossisme, patronase, klientelisme, transaksionalisme,
pragmatisme, politik uang, korupsi, vote buying, dan lain-lain) untuk menuding aktor-
aktor politik (politisi, bupati, kapala desa, kandidat, dan sebagainya) bekerja secara
negatif dan amoral seperti setan. Karya-karya orientalis Vedi Hadiz (2010), Jeffrey
Winters (2013), Edward Aspinall (2019) selalu bicara defisit politik itu, sekaligus juga
menjadi rujukan template oleh para mahasiswa dan sarjana yang menggeluti studi politik.
Terkait soal konsep-konsep itu, saya mengingat kembali petuah guru saya, Prof.
Mohtar Mas’oed, empat belas tahun silam: “Anda jangan membawa moral untuk
menganalisis politik. Anda akan kecewa jika mengunakan moral. Politik itu ya begitu itu,
sebaiknya dilihat secara realis dan kontekstual”. Guru saya yang satu lagi, Prof. Purwo
Santoso, menambahkan pentingnya humanizing politics, dan bahaya rabun metodologi
dalam analisis politik yang mengedepankan “pendekatan patologis”. Kedua guru itu
meningatkan saya untuk meninggalkan analisis potisivistik dan menerapkan analisis
politik kontekstual.
Analisis patologis di atas seolah-olah membela rakyat dengan cara melucuti elite
yang lalim. Cara pandang ini terlalu melebihkan kuasa elite, dan mengabaikan kekuatan
rakyat. Dengan konsep sak pada-pada, antropolog Pujo Semedi (2019) menunjukkan
bahwa hubungan elite desa dengan rakyat sudah berubah, menjadi posisi yang sama,
yakni elite desa bisa ditekan, diolok-olok, dan dinegosiasi oleh rakyat. Meskipun seolah-
olah membela rakyat, tetapi analisis patologis malah menuding rakyat amoral dan
pragmatis karena sangat doyan politik uang. Bagi saya, praktik politik uang tidak perlu
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 21
dibaca secara moral, tetapi sebaiknya dilihat sebagai arena dan kesempatan bagi rakyat
untuk melakukan negosiasi, bahkan, merebut sumberdaya dari elite. Ruang negosiasi
elite-rakyat itulah yang perlu dikaji secara kontekstual, sehingga bisa menjadi modalitas
untuk meninggalkan politik patologis menuju politik perubahan.
Perspektif poskolonialis, yang anti-orientalis Barat, lebih tajam melucuti analisis
politik patologis yang positivistik. Di mata kaum anti-orientalis, analisis yang berpusat
pada elite itu, sungguh tidak mempunyai kontribusi secara aksiologis terhadap perubahan,
malah sebaliknya, membenarkan (melegitimasi) intervensi teknologi kekuasaan
teknokratis dari Jakarta maupun dari Barat. Kritik ini mengingatkan saya pada warning
sejarawan Nordholt (1996) terhadap penggunaan “despotisme oriental” oleh para sarjana
Barat untuk memberi gambaran tentang kerajaan Asia yang berwatak lalim dan menindas
republik desa. “Model ini membantu melegitimasi penundukan kolonial atas sebagian
besar Asia: begitu penguasa lalim digantikan oleh kuasa kolonial yang rasional dan
budiman, penduduk lokal dijamin dan hidup tenang bersama dengan desa tradisional
mereka yang tertutup”, demikian ungkap Nordholt.
KESIMPULAN
IP adalah khas Indonesia, yang tidak dikenal di belahan dunia. Tetapi IP selalu
memperoleh stimulus eksternal: kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme.
Ia hadir karena keperluan aksiologi pragmatis, yang bukan untuk menyiapkan kader-
kader pemerintah, bukan pula untuk mencerahkan praktik pemerintahan secara utuh,
tetapi sekadar untuk mencetak birokrasi yang lebih banyak untuk menjaga law and order,
seperti halnya para pangreh praja kolonial untuk menjaga rust en orde. Tujuan aksiologi
yang tidak duduk itu tidak dilengkapi dengan ontologi yang memadai. Para sarjana
berputar-putar menentukan objek IP adalah gejala pemerintahan. Tetapi makna
pemerintahan yang disajikan sungguh salah kaprah dan dangkal. Pertama, konsep
pemerintah lahir dari tradisi Anglo Saxon, tetapi para sesepuh memahami pemerintahan
dari sudut Eropa Kontinental, yakni konsep bestuurkunde yang diimpor dari Negeri
Belanda. Adaptasi ini adalah kesalahan parah. Orang Belanda menyebut bestuurskunde
sebagai administrasi, orang Indonesia menerjemahkan bestuurskunde sebagai
pemerintahan. Kedua, konstitusi telah menyediakan roh, semangat, dan pengetahuan
tentang “pemerintahan berkedaulatan rakyat”, yang mirip dengan “pemerintahan
republikenisme” ala Anglo Saxon, tetapi para sesepuh malah membuat “pemerintahan
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
22 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
administratif-birokratis” yang diwarisi dari praktik-pengetahuan kolonial. Konstitusi
malah dimonopoli oleh para sarjana hukum positivis-dogmatis, yang sibuk bicara negara
hukum dan supremasi hukum, yang melihat pemerintahan dengan lensa hakim, bukan
lensa pemerintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat.
IP secara epistemologis tidak mempengaruhi, apalagi mencerahkan praktik, malah
sebaliknya, pengetahuan pemerintahan lebih banyak dipengaruhi oleh praktik.
Kolonialisme, yang membentuk negara pegawai, membentuk DNA IP.
Developmentalisme Orde Baru, yang meneruskan kolonialisme, sangat kuat membentuk
IP. Wajah Orde Baru adalah wajah IP. Era reformasi, yang menganut neoliberalisme, juga
diikuti oleh IP, yakni, tidak mencerahkan dan memperkuat pemerintah(an) rakyat,
melainkan menggunakan manajemen publik dan tatakelola untuk membentuk
pemerintahan pasar dan pemerintahan teknokratik.
Meskipun IP mengklaim sebagai disiplin mandiri, tetapi secara de facto
pemerintahan hanya sebuah studi. Ia dikaji dari hukum yang berorientasi regulating, dari
administrasi yang berorientasi administering, dari sisi manajemen yang bermakna
managing, dan dari sisi governance yang berbau networking. Kita tidak pernah
memperoleh pemahaman utuh tentang governing yang dijalankan pemerintah, sebuah
institusi pemegang kedaulatan rakyat. Mutilasi ini ibarat orang melihat sejumlah pohon
yang berbeda-beda, tetapi tidak pernah melihat hutan. Akibatnya komunitas IP “tidak
mengetahui apa yang diketahui dan apa yang dihafal” tentang pemerintahan.
Masalah ontologi tentu berdampak ke epistemologi. Orang hanya bicara sejumlah
pendekatan untuk melihat pemerintahan serta berbagai metode untuk memperoleh
pengetahuan sistematis. Namun komunitas IP tidak secara epistemologis menggunakan
“pemerintahan” sebagai subjek dan perspektif untuk melihat, memahami dan
menjelaskan politik, administrasi, hukum, kehidupan sosial, ekonomi, hajat hidup orang
banyak, dan lain-lain. Dengan kalimat lain, pemerintahan adalah objek studi yang dilihat
dari banyak disiplin ilmu, tetapi IP tidak pernah berhasil melihat secara terbalik, yakni
melihat halaman ilmu lain dengan perspektif pemerintahan.
DAFTAR PUSTAKA
Adiwisastra, Y. 2015. “Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Administrasi Negara”, dalam M.
Labolo, dkk. eds. Dialektika Ilmu Pemerintahan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
Almond, G. 1990. A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science. London
and Newbury Park: Sage Publications.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2020 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169 | 23
Aspinall, E. dan W. Berenschot. 2019. Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and
the State in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.
Benda, H.J. 1966. “The Pattern of Administrative Reforms in the Closing Years of Dutch
Rule in Indonesia”. The Journal of Asian Studies. 25: 4.
Bohne, E. et. al. eds. 2014. Public Administration and the Modern State Assessing Trends
and Impact. Basingstoke: Palgrave.
Braun, C. dkk. 2015. Quo Vadis, Nederlandse Bestuurskunde?. Bestuurskunde. 24:
Djojowadono, S. 2015. “Perkembangan Ilmu Pemerintahan”. dalam M. Labolo, dkk.
Dyson, K. 1980. The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and an
Institution. Oxford: Oxford University Press.
Finer, H. 1946. Theory and Practice of Modern Government. New York: Deal Press.
Finer, S. 1970. Comparative Government. London: Allen Lane.
Grimm, D. 2016. Constitutionalism: Past, Present, and Future. Oxford: Oxford
University Press.
Grindle, M. 2017. “Good Governance, R.I.P.: A Critique and an Alternative”.
Governance. 30: 1.
Hadiz, V. 2010. Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia
Perspective. Stanford: Stanford University Press.
Harvey, D. (2007). A Brief History of Neoliberalism. Oxford: Oxford University Press.
Huntington, S. 1968. Political Order in Changing Societies. Yale: Yale University Press.
Karniawati, N. 2015. “Hakekat Ilmu Pemerintahan”. CosmoGov: Jurnal Ilmu
Pemerintahan, 1:2.
Karré, P.M. et. al. 2020. “Public Administration in the Netherlands: State of the Field”,
dalam Geert Bouckaert and Werner Jann eds. European Perspectives for Public
Administration. Leuven: Leuven University Press
Kickert, W dan T. Toonen. 2006. “Public Administration in The Netherlands: Expansion,
Diversification and Consolidation”. Public Administration. 84:4
Klikauer, T. 2013. “What Is Managerialism?”. Critical Sociology, 41:7.
Lay, C. (2019).“Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan
Kemanusiaan”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Politik dan Pemerintahan,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 6 Februari.
Labolo, M. dkk. eds. 2015. Dialektika Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Maier. C. 2019. Der Rechtsstaat in Spanien und Deutschland – Überlegungen zum
Modell einer Europäischen Demokratie,
https://www.academia.edu/37131719/Der_Rechtsstaat_in_Spanien_und_Deutschl
and_%C3%9Cberlegungen_zum_Modell_einer_europ%C3%A4ischen_Demokrat
ie, 27 Mei 2020.
McVey, R. (1982), “The Beamtenstaat in Indonesia”. dalam B. Anderson dan A. Kahin
(eds.), Interpreting Indonesian Politics: Thirteen Contributions to the Debate,
Ithaca: Cornell University Modern Indonesia Project.
Nordholt, H.S. 1996, Spell of Power: A History of Balinese Politics 1650-1940, Leiden:
KITLV Press.
Ndraha, T. 2003. Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru. Jakarta: Rineka Cipta.
Osborne, D dan T. Gaebler. 1992, Reinventing Government. New York: Penguin.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
24 | Governabilitas: Volume 1 Nomor 1 Juni 2022 ISSN: 2722-1792 E-ISSN: 2723-4169
Overeem, P. 2013. The Politics-Administration Dichotomy: Toward a Constitutional
Perspective, London: Routledge.
Peters, B.G. 1999. Institutional Theory in Political Science, London & New York: Pinter.
Plant, R. 2010. The Neo-Liberal State, Oxford: Oxford University Press.
Polyando, P. 2016. “Menelusuri Duduknya Ilmu Pemerintahan”, Jurnal Politikologi. 3:1.
Pratikno. 2003. “Melacak Ruang Kajian Pemerintahan Dalam Ilmu Politik: Sebuah Riset
Awal”, Transformasi: Jurnal Kajian Kritis Transformatif. 1:1
Raadschelders, Jos C. N. 2000. “Understanding Government in Society: We See The
Trees, But Could We See The Forest? Administrative Theory & Praxis. 22:2.
Raadschelders, Jos C. N. 2005. “Government and Public Administration: Challenges to
and Need for Connecting Knowledge”, Administrative Theory & Praxis. 27:4.
Raadschelders, Jos C. N. 2015. Government: A Public Administration Perspective,
London: Routledge.
Radbruch, G. 1946. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht”, Süddeutsche
Juristen-Zeitung , 1:5.
Rauf, M. 2015. “Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik: Suatu Pengantar”, dalam M.
Labolo. dkk
Rhodes, R.AW. 1996. “The New Governance: Governing without Government”, Political
Studies. 44:4.
Rutgers, M.R. 2005. Het Gulden Boekje uit de Nederlandse Bestuurskunde. Delft:
Eburon.
Schillemans, T. 2017. “Staat van de Bestuurskunde”, Bestuurskunde, 26:1.
Scott, A.C dan W. Earleklay. 2014. “George Washington and Enlightenment Ideas on
Educating Future Citizens and Public Servants”, Journal of Public Affairs
Education, 20:1.
Semedi, P. 2019. Sakpada-pada: Menjaga kesetaraan di pedesaan Jawa 1850 – 2010,
Pidato Ilmiah disampaikan pada Dies Natalis ke-54 STPMD “APMD” Yogyakarta,
28 November.
Soewargono. 2015. “State of the Art Ilmu Pemerintahan”, dalam M. Labolo. dkk.
Sujamto. 2015. “Perkembangan Konsep Ilmu Pemerintahan”, dalam M. Labolo dkk.
Tjokrowinoto, M. 2015. “Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik: Suatu Pengantar Diskusi”,
dalam M. Labolo. dkk.
Van Putten, R. dkk (2020). “Kritische Bestuurskunde: Naar een Reflexief Perspectief op
Bestuur en Beleid”, Bestuurskunde, 29:1.
Van Poelje, GA. 1953. Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan, Djakarta: Soeroengan
Van Ylst, F. 2015. “Eksistensi Ilmu Pemerintahan”. CosmoGov: Jurnal Ilmu
Pemerintahan, 1:1.
Waldo, D. 1955. The Study of Public Administration. New York: Random House.
Wasistiono, S. 2017. Perkembangan Ilmu Pemerintahan dari Klasik sampai
Kontemporer. Sumedang: IPDN Press.
Winters, J. 2013. Oligarchy and Democracy in Indonesia, Indonesia, 96.
JURNAL ILMU PEMERINTAHAN SEMESTA
Anda mungkin juga menyukai
- 4.+180-199+Menghidupkan+Kembali+Spirit+Politik+dalam+Ilmu+Pemerintahan FixDokumen20 halaman4.+180-199+Menghidupkan+Kembali+Spirit+Politik+dalam+Ilmu+Pemerintahan FixAnindya Putri MaharaniBelum ada peringkat
- The Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionDari EverandThe Three Shades from the Past to the Present Indonesian VersionBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Ilmu PEMERINTAHANDokumen14 halamanSejarah Perkembangan Ilmu PEMERINTAHANChan ChanBelum ada peringkat
- PEMBONGKARAN IDEOLOGIDokumen22 halamanPEMBONGKARAN IDEOLOGIhinata karasunoBelum ada peringkat
- Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia IslamDari EverandIslam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia IslamBelum ada peringkat
- An Dan Dinamika Administrasi Negara Di Indonesia 1Dokumen23 halamanAn Dan Dinamika Administrasi Negara Di Indonesia 1Semara Putra100% (1)
- Perkembangan Dan Paradigma Ilmu Administrasi PublikDokumen9 halamanPerkembangan Dan Paradigma Ilmu Administrasi Publikdior dilanBelum ada peringkat
- Tugas - 2 - 041571971 - Dara Ferlena - Adpu4531Dokumen7 halamanTugas - 2 - 041571971 - Dara Ferlena - Adpu4531pemdessidoharjo89Belum ada peringkat
- Perkembangan Ilmu Administrasi NegaraDokumen12 halamanPerkembangan Ilmu Administrasi NegaraDEVI NOVITA SARIBelum ada peringkat
- New Public Service - 2009120021Dokumen15 halamanNew Public Service - 2009120021Edi Surya0% (1)
- Administrasi Publik KontemporerDokumen17 halamanAdministrasi Publik KontemporerFandy ManuainBelum ada peringkat
- Ilmu Politik di IndonesiaDokumen5 halamanIlmu Politik di IndonesiaDiana FebriantiBelum ada peringkat
- ILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUANDokumen18 halamanILMU POLITIK SEBAGAI ILMU PENGETAHUANMuhammad Razik Qusayri100% (1)
- Presentasi DDIPDokumen24 halamanPresentasi DDIPGiffary Adi NugrahaBelum ada peringkat
- Sejarah Dan Perkembangan Ilmu Administrasi NegaraDokumen12 halamanSejarah Dan Perkembangan Ilmu Administrasi NegaraNizar Muhammad100% (4)
- Definisi Ilmu Politik Atas Dasar Hakikat PolitikDokumen5 halamanDefinisi Ilmu Politik Atas Dasar Hakikat PolitikPuti Ranti RahmianiBelum ada peringkat
- Ruang LIngkup Administrasi PublikDokumen4 halamanRuang LIngkup Administrasi Publikmc2hin9100% (5)
- Proses Pemerintahan Sebagian Ilmu PengetahuanDokumen14 halamanProses Pemerintahan Sebagian Ilmu PengetahuanChan ChanBelum ada peringkat
- Makalah Perkembangan Administrasi NegaraDokumen7 halamanMakalah Perkembangan Administrasi NegaraYudistia TioBelum ada peringkat
- Perkembangan Ilmu Politik di IndonesiaDokumen7 halamanPerkembangan Ilmu Politik di IndonesiaBISMOKO RAHADRIAN SBelum ada peringkat
- Pengkajian Ilmu Administrasi NegaraDokumen7 halamanPengkajian Ilmu Administrasi NegaraTusy Novita D PrasetyoBelum ada peringkat
- Tugas 1 - PipDokumen3 halamanTugas 1 - Pipwawanaja2097Belum ada peringkat
- SEJARAHDokumen16 halamanSEJARAHAcim M KarimBelum ada peringkat
- Diskusi Sesi 2Dokumen19 halamanDiskusi Sesi 2fira lailasariBelum ada peringkat
- Ujian Perbaikan Nilai Uts Pengantar Ilmu PolitikDokumen17 halamanUjian Perbaikan Nilai Uts Pengantar Ilmu PolitikYohan MaengasiBelum ada peringkat
- Ilmu PolitikDokumen15 halamanIlmu PolitikGiffary Adi NugrahaBelum ada peringkat
- Teori Administrasi P. Ke 1Dokumen11 halamanTeori Administrasi P. Ke 1prayogiadityaBelum ada peringkat
- Tugas Ilmu Politik 2Dokumen25 halamanTugas Ilmu Politik 2muhammad alwalidBelum ada peringkat
- Ilmu Politik PengantarDokumen35 halamanIlmu Politik PengantarAldy humokorBelum ada peringkat
- Teori AdministrasiDokumen5 halamanTeori AdministrasiAnggun SarnitaBelum ada peringkat
- MAKALAH Sejarah Perkembangan Ilmu Politik Dan PembidangannyaDokumen10 halamanMAKALAH Sejarah Perkembangan Ilmu Politik Dan PembidangannyaReskia 43182073Belum ada peringkat
- Resume Dasar Ilmu Politik Miriam BudiharjoDokumen16 halamanResume Dasar Ilmu Politik Miriam Budiharjoandriys67% (6)
- 2.136 159 Dekolonisasi Dan Indegenisasi Ilmu PemerintahanDokumen24 halaman2.136 159 Dekolonisasi Dan Indegenisasi Ilmu PemerintahanNandaaBelum ada peringkat
- Tugas Uts Dasar Ilmu PemerintahanDokumen23 halamanTugas Uts Dasar Ilmu Pemerintahankamfret287Belum ada peringkat
- NPS-Paradigma Mutakhir Administrasi NegaraDokumen14 halamanNPS-Paradigma Mutakhir Administrasi NegaraFahreza PutraBelum ada peringkat
- Rangkuman Tertulis Disiplin Ilmu PolitikDokumen6 halamanRangkuman Tertulis Disiplin Ilmu PolitikRizqi Kajayaan Tri PutraBelum ada peringkat
- Hubungan Ilmu Pemerintaha Dengan Ilmu-Ilmu Lain (Recovered 1)Dokumen16 halamanHubungan Ilmu Pemerintaha Dengan Ilmu-Ilmu Lain (Recovered 1)Rafly AmarBelum ada peringkat
- BirokrasiDokumen4 halamanBirokrasiAndika PermanaBelum ada peringkat
- ILMUPOLDokumen97 halamanILMUPOLSuci RamadantiBelum ada peringkat
- BAB I Rudhi RevisiDokumen20 halamanBAB I Rudhi RevisiVinaBelum ada peringkat
- DASIDokumen37 halamanDASIChelsa Dwi ArifchanBelum ada peringkat
- SOSPOLDokumen11 halamanSOSPOLangelia hereBelum ada peringkat
- Inisiasi 1.2Dokumen12 halamanInisiasi 1.2Yanafi R EBelum ada peringkat
- Aggsimnt AnDokumen13 halamanAggsimnt Anbadhackers89Belum ada peringkat
- Pelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia Dan Prospek Ke DepannyaDokumen28 halamanPelaksanaan Administrasi Publik Di Indonesia Dan Prospek Ke DepannyaAntonius Galih Prasetyo88% (24)
- Makalah Politik BangsaDokumen17 halamanMakalah Politik Bangsayusrijal100% (3)
- Inisiasi 1Dokumen6 halamanInisiasi 1Aminah ElviBelum ada peringkat
- Review Jurnal Hakekat Ilmu PemerintahanDokumen6 halamanReview Jurnal Hakekat Ilmu Pemerintahanwahyuni100% (3)
- Sifat, Arti, Dan Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan LainnyaDokumen19 halamanSifat, Arti, Dan Hubungan Ilmu Politik Dengan Ilmu Pengetahuan LainnyaDita Aprilia50% (4)
- ILMU POLITIKDokumen30 halamanILMU POLITIKWaffyBelum ada peringkat
- ILMU POLITIKDokumen30 halamanILMU POLITIKWaffy0% (1)
- Makalah Netralitas BirokrasiDokumen19 halamanMakalah Netralitas BirokrasiAngga100% (1)
- Dasar-Dasar Ilmu PemDokumen88 halamanDasar-Dasar Ilmu PemBudiansyah Ibnus-Syahli50% (2)
- Pertemuan 3Dokumen7 halamanPertemuan 3Frayudha ADRBelum ada peringkat
- Critical ResumeDokumen12 halamanCritical Resumeiftikhar firdausBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan Administrasi Publik: Modul 1: DR - Tuswoyo, M.SiDokumen16 halamanSejarah Perkembangan Administrasi Publik: Modul 1: DR - Tuswoyo, M.SiNatalia SaswitaBelum ada peringkat
- Resume Buku DasarDokumen16 halamanResume Buku DasarnabillahBelum ada peringkat
- Kelompok 4 (Paradigma Administrasi Negara)Dokumen10 halamanKelompok 4 (Paradigma Administrasi Negara)Ramadani RachmanBelum ada peringkat
- Kegiatan Harian Praja IPDN NTB 10 Agustus 2022Dokumen5 halamanKegiatan Harian Praja IPDN NTB 10 Agustus 2022mustami fataBelum ada peringkat
- Tugas 1Dokumen1 halamanTugas 1mustami fataBelum ada peringkat
- Daftar Jaga Wisma Wisma Nusantara 2 Lantai 1 Dan 2Dokumen2 halamanDaftar Jaga Wisma Wisma Nusantara 2 Lantai 1 Dan 2mustami fataBelum ada peringkat
- Pertemuan PertamaDokumen2 halamanPertemuan Pertamamustami fataBelum ada peringkat
- STRATEGI BNN DALAM PERANG MELAWAN NARKOBADokumen48 halamanSTRATEGI BNN DALAM PERANG MELAWAN NARKOBAmustami fataBelum ada peringkat
- Pembagian Wisma Praja IPDNDokumen62 halamanPembagian Wisma Praja IPDNmustami fataBelum ada peringkat
- Alasan Dibalik Perubahan Dan Pencabutan Peraturan Lingkup Provinsi Atau Kabupaten/KotaDokumen1 halamanAlasan Dibalik Perubahan Dan Pencabutan Peraturan Lingkup Provinsi Atau Kabupaten/Kotamustami fataBelum ada peringkat