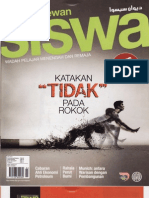Cerpen Sunlie Thomas Alexander
Diunggah oleh
Maltuf A. GungsumaDeskripsi Asli:
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Cerpen Sunlie Thomas Alexander
Diunggah oleh
Maltuf A. GungsumaHak Cipta:
Format Tersedia
Pamungkas Asmara Cerpen Sunlie Thomas Alexander Dimuat di Suara Merdeka 06/20/2010 Telah Disimak 242 kali
Nujum Iblis Buta "Aku tak akan mati selama dosa dan kejahatan masih ada di dunia ini. Aku telah bersumpah demi arwah nenek moyangku, untuk membunuhmu lalu menghisap darahmu! Begitulah nujummu jatuh atas diri sendiri, Iblis Buta! Lalu serupa manusia pertama dijadikan dari debu tanah, jasadmu yang telah mengabu pun perlahan bergerak menyatu kembali bersamaan dengan berembusnya angin kencang di dasar Lembah Jagat Pangeran. Udara begitu dingin menusuk pori-pori, serasa menanggalkan tulang-belulang. Ah, segalanya memang seperti berhasrat membeku pada malam yang jahanam itu. Kau tahu, betapa menakjubkan sekaligus menakutkan di bawah terang purnama yang mencemaskan menyaksikan butir-butir debu itu memadat lagi jadi tetulang dan dagingmu yang fana. Lantas kau pun beranjak berdiri dari kematianmu yang kedua. Telanjang bulat seperti manusia pertama yang terpana melihat fajar perdana. Tetapi malam susut kelabu, Iblis Buta. Meski bintang-bintang tak gentar berkerdip. Dengan angin yang membawakan aroma liang lahat. Busuk menyengat, bagai hendak membongkar seisi perut. Ah, seorang peladang malang yang sejak mula bersembunyi ketakutan di balik kerapatan pohon pisang, lari lintang-pukang ketika tiba-tiba kau meraung keras. Air kencingnya bercucuran membasahi celana! Tentu, tentu ini bukanlah kejadian yang bisa dinalar. Bagaimana mungkin manusia yang telah mati, dengan tubuh tinggal abu bisa bangkit lagi? Nyali siapakah yang tak lumer melihat semua kegilaan ini dengan mata kepala sendiri? Namun begitulah, Iblis Buta. Kepada iblis neraka yang telah memberimu keabadian, kau telah bersumpah hanya akan hidup dengan meminum darah. Berkarib dendam dan kebencian! Bukankah telah lama bagimu nyawa manusia tak ada lagi harganya? Sejak bertahun-tahun lalu, ketika kedua orang tuamu membuangmu selayaknya seekor anjing kudisan karena tak sudi punya anak buta. Ketika semua orang meremehkan dan menghinamu, mengusir dan meludahimu. Dan tak seorang anak pun di kolong kampung yang sudi berada di dekatmu, apalagi berteman denganmu. Karena itulah, riwayat mengerikan ini pun tergores di lembar-lembar cerita bergambar: ke mana pun tongkat dengan gantungan tengkorak itu menuntunmu, maka darah bisa dipastikan bakal tercecer dari setiap jejak langkahmu. Teror demi teror bagi setiap yang bernyawa. Dari kota-kota karesiden hingga kampung-kampung terpencil, demikianlah bertahun-tahun kau menjelajahi seantero rimba persilatan seraya menebar bencana. Ah, konon bayang-bayangmu lebih menakutkan dari wabah penyakit menular yang paling mematikan sekalipun. Kendati tak punya biji mata, siapa nyana mata tongkatmu lebih
tajam dari mata sekalian setan. Mengincar setiap urat leher, yang lena maupun terjaga! Ai, maut layaknya orang buta yang lewat sambil meraba-raba dengan tongkatnya. Mencari Barda Mandrawata Aku tidak tahu kuasa apa yang telah membangkitkan engkau dari liang kubur. Tetapi yang pasti kuasa yang melawan kodrat Ilahi pasti akan hancur. Begitulah tukas putra Paksi Sakti Indrawata, pemimpin perguruan Elang Putih itu dingin. Suaranya terdengar dalam, namun tenang. Hari itu, lagi-lagi di dasar Lembah Jagat Pangeran, kalian kembali mesti berhadapan. Namun hingga matahari tergelincir ke barat, selain kesiur angin yang membuat daun-daun pepohonan bergemirisik riuh, belum juga ada di antara kalian yang bergerak. Tegak berptopang tongkat, terpisah dalam jarak dua tombak, kalian sepertinya saling mengukur kekuatan. Seratus dua puluh purnama berlalu, terang bukanlah waktu yang singkat. Tentu sudah banyak ilmu kesaktian bertambah. Jika saja masih punya mata, barangkali ia akan menatapmu lekat-lekat dengan pandangan menusuk. Dan bila punya biji mata, kau mungkin akan menantang kedua matanya dengan tatapan membesi. Tapi toh, kalian sama butanya. Ya, itulah pertemuan kalian yang kedua setelah ratusan purnama. Ah, betapa sudah begitu lamanya kau menantikan waktu ini tiba untuk menyelesaikan segala hutang nyawa. Kau tahu, sebagaimana telah kau nujumkan, pertarungan itu memang tak bakal terelakkan. Entahlah siapa duluan yang membuka jurus, tahu-tahu tubuh kalian telah menjelma kelebat bayang-bayang. Saling menggulung dan membelit, tongkat kalian begitu sebatnya menusuk dan menangkis dan menyabet. Konon, hanya mata para pendekar kawakan nomor satulah yang mampu melihat jalannya pertarungan. Jurus berganti jurus, tak juga salah satu dari kalian tampak terdesak. Debudebu dan bebatuan beterbangan, rumput-rumput tercerabut, daun-daun melayang berguguran, dan pohon-pohon besar kecil pun tumbang satu persatu. Ai, begitulah aku mengingat gambar-gambar itu dulu berkisah, Iblis Buta. Hingga memasuki jurus ke sekian ratus tentu tak kuingat lagi pada halaman berapa dalam satu kesempatan kau berhasil menyelinap ke belakang pendekar buta berpakaian kulit ular itu dan bersiap menghujamkan tongkatmu! Tetapi, sebelum ajal berpantang mati, begitulah ujar-ujar yang lazim berlaku di rimba persilatan, Iblis Buta. Maka, sebagaimana dulu kau dibangkitkan oleh petir, demikianlah pula kematianmu yang kedua ini ditakdirkan. Lidah-lidah api mengerikan itu menyambar dan menghanguskan tubuhmu hingga luluh-lantak, sekaligus menyelamatkan nyawa si pendekar kelana. Karenanya, pada kebangkitan kedua dari abu, tentu kini bakal kau cari lagi jejaknya untuk menuntaskan pertarungan yang tak usai. Sebab, bukankah hanya satu jawara buta yang boleh tegak di kolong jagat ini? Malaikat Maut Tanpa Asal
Ya, maut memang orang buta yang berjalan lewat dengan tongkatnya. Karena itu, tak seorang pun tahu dari mana asalmu, sebagaimana tak seorang pun yang bisa memberitahumu di mana beradanya Si Buta dari Goa Hantu. Begitu saja kau muncul menggegerkan rimba persilatan, seolah-olah tanpa latar belakang. Tentu saja masih kuingat bagaimana kau pertama kali hadir dan mengobrak-abrik desa tempat tinggal Barda Mandrawata yang tentram. Ratusan penduduk tak berdosa mesti merenggang nyawa di ujung tongkatmu yang (tak) bermata. Padahal tujuanmu hanyalah satu: Mencari dan menantang pemimpin Perguruan Silat Elang Putih, Paksi Sakti Indrawatara yang kesohor itu demi membuktikan siapa yang lebih digdaya. Ah, seandai saja kau tahu, kalau hari ituhari terbunuhnya Ki Paksisebuah babak baru sejarah pun dimulai: Ya, Iblis buta. Ya, kaulah pembawa kunci takdir bagi kehidupan Barda Mandrawata menjadi Si Buta dari Goa Hantu. Pulang menemukan kedua orang tua, semua saudara dan seluruh murid perguruan tewas menggenaskan, hati siapa yang tak koyak, dendam siapa tak menetas? Namun, jika seluruh riwayat kebengisanmu berpangkal dan berujung pada kemarahan tak kunjung reda kepadaNya yang telah menakdirkanmu lahir tanpa biji matabarangkali Bardalah satusatunya orang di muka bumi ini yang memilih buta! Buta mungkin lebih baik, agar tak perlu lagi melihat segala kekejian di dunia, begitulah ujarnya lirih usai menghujamkan kedua matanya pada paku yang tertancap di sebatang pohon. Tetapi kau paham, semua itu dilakukannya demi mempelajari Ilmu Membedakan Gerak dan Suara, lantaran hanya orang butalah yang sanggup mempelajari ilmu tak tertandingi yang kau kuasai itu. Ah, kalian mungkin layaknya sekeping mata uang dengan dua sisi, Iblis Buta. Demikianlah takdir jatuhkan pilihan kepadamu dan kepadanya. Seperti dua kutub saling bertolak dalam kehidupan. Saling ada dan mengadakan. Tanpa dirimu dalam kehidupannya, kisah panjang ini memang tak bakal ada, Iblis Buta. Ya, seperti halnya lahir dan mati, sesungguhnya memang telah ditentukan bagi kalian menjadi dua musuh bebuyutan selamanya! Tapi apa yang sebetulnya kau cari, Iblis Buta? Apa yang kau inginkan dari dunia yang keparat ini? Kekuasaan? Raja diraja rimba persilatan? Atau hanya sekadar rasa takut dari makhluk-makhluk malang? Sampai kapan kau hendak membalaskan dendam kesumatmu pada hidup yang tak ramah? Sampai kapan pula kau hendak menggugat-Nya? Hingga lonceng pengadilan terakhir berdentang? Bersama angin buruk yang menyelinap masuk ke setiap rumah yang lena merapatkan pintu dan jendela, kau pun kembali menggembara sembari mencabut setiap nyawa. Ya, sebagaimana bertahun-tahun silam, kau kembali berjalan dari kutuk ke kutuk, dari kebencian ke kebencian. Tapi ke mana gerangan kau harus mencari pendekar buta yang malang-melintang mengikuti hembusan angin itu, Iblis? Ingatan pada dua kematian, membuat dadamu kian membara oleh dendam. Terang masih lekat, bagaimana kepalamu terpenggal oleh sabetan tongkatnya dalam pertarungan kalian
yang pertama. Bagaimana pula manusia sial Si Maung Lugai membawa lari kepalamu untuk memenuhi persyaratan cinta Marni Dewiyanti. Sehingga, setelah dibangkitkan oleh petir yang menyambar makammu, kau pun menghantui rimba persilatan tanpa kepala! Interlude: Dua Kisah Kepala Oh, syahdan kepalamu itu memiliki kisahnya sendiri, Iblis Buta. Entahlah. Barangkali memang begitu istimewanya, sehingga ia mesti mengalami dua versi penceritaan yang berbeda dalam rentang waktu sepuluh tahun lamanya. Baiklah, ini cuma sekadar mengingatkan pahitnya kekalahanmu saja! Dalam kisah pertama, tatkala kau terbunuh dalam petarungan dengan Si Buta dari Goa Hantu, sabetan tongkatnya yang membentuk tanda tambah, telah membelah tubuhmu dari atas ke bawah lalu memutuskan pinggangmu. Sesungguhnya tidaklah pernah dikisahkan bahwa ia telah memenggal kepalamu, Iblis Buta. Hal ini pun diperkuat Marni yang mengaku bahwa saat Si Maung Lugai membawakan kutungan kepalamu kepadanya, ia masihlah melihat kepalamu itu dalam kondisi terbelah dua. Ah, adakah Si Maung Lugai keparatlah yang telah memenggal kepalamu tatkala ia menemukan mayatmu? Bukankah ia sempat bertarung dengan Barda sebelum pendekar itu meninggalkan Lembah Jagat Pangeran? Tetapi dalam episode keenam belas Bangkitnya Si Mata Malaikat yang terbit sepuluh tahun kemudian, nyatanya terpenggalnya kepalamu telah menyimpang dari jalan kisah yang lama, Iblis Buta. Pada episode ini diceritakan bahwasannya sabetan tongkat Bardalah yang telah pisahkan kepalamu dari badan dalam pertarungan dashyat di Lembah Jagat Pangeran itu. Dan kemunculan Si Maung Lugai Penyapu Jagat dalam cerita ini pun tatkala Barda sudah tak ada, sehingga dengan demikian tak ada pertarungan di antara mereka. Begitulah! Dua Perempuan Penyejuk Hati Ah, maut adalah orang buta yang menuding dengan tongkatnya. Namun toh, hidup nyatanya tak melulu kebencian, Iblis Buta! Dalam pengembaraan panjang mencari Barda, kau tahu, cinta sesekali masih berkenan menyapa hatimu yang telah mengeras oleh lapisan dendam dan kebencian itu. Bukankah terkadang kau masih terkenang pada suara lembut Mandrawati? Ai, harum rambutnya yang beraroma melati! Hmm, perempuan adakah sedikit saja kau pahami kelembutannya yang mampu meredam panasnya bara dendam di dadamu, Iblis? Seperti setetes demi setetes air yang membuat lubang di atas kerasnya batu goa. Entahlah. Tapi di desa Cibarusa, tempat langkahmu terhenti sejenak untuk mengumbar bencana kepada para penduduk yang tak berdosa, Iblis Buta, sekali lagi kau mesti kembali menemui sentuhan lembut itu di hatimu yang gersang berdebu. Rosiana, Rosiana! Kecantikan seperti apa yang kau miliki hingga mampu menghentikan keganasan seorang pendekar buta yang paling durjana? Adakah kau benar-benar jatuh hati pada pembunuh biadab itu, atau semata-mata hanya niat tulus untuk menyelamatkan
kedua orang tuamu dan warga desa dari pembantaian kejinya? Ataukah berkat petunjuk sesederhana kata-kata halus Uwak Kiwul-lah, kau nekat mengorbankan diri? Barangkali dalam kisah ini, takdir memang terlalu berkuasa dan lancang bicara. Ia mempermainkan setiap tokoh seperti wayang di tangan seorang ki dalang yang dingin namun fasih membawakan kisah sedih memukau. Bahkan kerapkali begitu licinnya ia mengelakkan nujummu, Iblis Buta. Tentu awalnya kau tak menduga, bila pada akhirnya kau bertekuk lutut juga di hadapan anak gadis juragan Kowara yang cantik jelita itu. Gadis yang sudah berpenampilan kelondo-londoan lantaran terlalu lama tinggal di Batavia. Tapi begitulah kau rasakan getar itu sesayup sampai, serupa getar yang dulu dikirimkan Mandrawati ke mata hatimu. Getar yang melumpuhkan, pun setiapkali kau mendesiskan namanya, mengingat suara dan aroma melati di rambutnya. Ya, mungkin ini memang takdir bagi si jelita, yang begitu dicintai oleh para pemuda di desanya, namun toh memilih menjadi bagian dari riwayat hidupmu yang durjana. Sejak itu, kau mulai berubah, Iblis Buta! Perlahan, selapis demi selapis karatan kebencian dan dendam di hatimu pun mulai menggelupas. Perlahan, kau mulai menurut pada Rosiana. Kau tak lagi membunuh, tak lagi menghisap darah para korbanmu. Selama beberapa waktu, kau hanya menggantungkan hidup dari tetes demi tetes darah yang dikucurkannya dengan rela untukmu dari goresan tipis di pergelangan tangannya. Bahkan bukan cuma darah, tapi juga tubuh dan jiwanya ia korbankan agar kau tak lagi menebar malapetaka. Hingga akhirnya benihmu pun tumbuh subur di rahimnya. Ah, toh kau tak juga berhenti membandingkannya dengan si manis Mandrawati. Belum juga berhenti dari menyebutnyebut nama gadis kecil itu dan mengenang masa-masa kalian bersua. Oh, Mata Malaikat, iblis buta tanpa nama tanpa asal! Oh, hati membutakan diri dari kasih, kini mampuslah kau dikoyak moyak cinta! * Karena itu, hanya satu ilmu kesaktian di bawah kolong langit ini yang bisa melenyapkanmu, Iblis Buta. Ilmu itu, kau tahu, bernama Pamungkas Asmara. Pukulan api cinta! Kobaran api yang meletup dashyat dari hati sepasang insan yang dimabuk asmara. *** AI, tentu aku tak berhasrat menjadi juru cerita baru bagi kisah jahanammu, Iblis Buta! Kulihat Uwak Kiwul berdiri termenung. Wajahnya tampak keruh meski jari-jari tangannya yang kurus tak henti-hentinya menghitung butir-butir tasbih melafadzkan kebesaran namaNya. Jurus silat Karno dan Surti memang kian teruji, tenaga dalam kedua muridnya itu pun meningkat dengan tajam. Tetapi Pamungkas Asmara, ia tahu, ilmu aneh bin langka itu hanyalah dapat dikuasai oleh sepasang insan yang tulus saling mencinta! Ah, inilah perkara peliknya. Siapa nyana hati Karno, pemuda tampan itu telah terpikat demikian dalam pada Rosiana, putri majikannya, teman semasa kanak-kanaknya. Dan Surti, perawan ranum dengan mata sebening embun di atas daun talas itu hanyalah bertepuk sebelah.
Kulihat sepasang mata Uwak Kiwul memandang jauh ke kerimbunan bukit di utara desa, di mana Rosiana dilarikan olehmu. Kedua mata itu tampak begitu lelah, wajahnya terlihat dua kali lipat lebih tua. *** Gaten, Yogyakarta, 2007-2010 Cerita ini merupakan interpretasi ulang atas cergam serial Si Buta dari Goa Hantu karya Ganes Th, episode Bangkitnya Si Mata Malaikat dan Pamungkas Asmara berdasarkan ingatan dan sejumlah catatan Damuh Bening. * Terilhami sepenggal sajak Chairil Langit Ketiga Puluh Tiga Cerpen Sunlie Thomas Alexander Dimuat di Suara Merdeka 03/20/2010 Telah Disimak 491 kali
Ketika bunga padma mekar, itulah saat baginya untuk pergi mencari jalan menuju langit ketiga puluh tiga, sam sip sam thian 1). Hanya di kala bunga padma mekarlah, ia dapat menemukan jalan itu. Sebagaimana yang selalu dikatakan pamannya yang tua. Mengapa, pamannya juga tidak mengerti. Karena memang begitulah petunjuk yang terdapat dalam Kitab Thung Su 2) yang tak dapat ditawar-tawar, tukas pamannya. Tetapi kini, di sebuah tebing tinggi, ia terpaksa berhenti sejenak. Dia tengadahkan wajah ke langit. Mencoba mencari posisi matahari. Sia-sia. Langit begitu muram dengan awan hitam tebal yang bergumpalgumpal. Karena itu untuk mengetahui waktu yang tepat pun sulit baginya. Padahal ia harus segera menuju ke timur, ke arah matahari terbit. Arah mana orang-orang selalu menghadap dengan tiga batang hio di depan dada saat memanjatkan doa. Karena arah itulah yang telah diberitahu oleh seekor burung kundul tanpa bulu ekor yang dilihat di tepi hutan karet tiga hari lalu. Burung itu sambil memekik keras terbang ke arah timur dari pinggiran hutan terbakar. Ia memang selalu yakin Song Ti 3) akan senantiasa membimbingnya lewat pertandapertanda di langit dan bumi. Namun saat ini, ketika letak matahari pun tak dapat diketahui, pertanda apakah yang diberikan mendung? Maka diletakkannya buntalan kainnya di tanah tebing. Membuka ikatan buntalan itu, lalu mengeluarkan sebuah kompas dari sana. Dia cari-cari tempat yang datar hingga ditemukan sebuah batu cadas yang pipih untuk meletakkan kompas. Dia perhatikan dengan saksama kompas pemberian seorang pendeta bermata kudus itu berputar, menunggu sampai huruf E terdiam. Untuk beberapa waktu, ia masih terpaku di atas tebing tinggi itu, memandang ke kejauhan dengan mata terpicing. Berharap menemukan sebuah pondok atau pohon lebat tempat ia dapat berteduh bila hujan tiba-tiba runtuh. Tetapi sejauh matanya sanggup memandang, yang tampak hanyalah hamparan rumput kering meranggas dengan sebuah sungai kecil
yang mengalir di kejauhan. Namun firasatnya mengatakan kalau di balik sungai kecil itu ada perkampungan. Dia masukkan kompas kembali ke dalam buntalan lalu bergegas berlari menuruni tebing. Hujan rintik-rintik langsung menyergap begitu kaki menginjak padang rumput kering. Sejenak hatinya agak ragu, namun ia cepat-cepat membaca doa untuk memusnahkan segala ganjaran: Lam bu kiu khou khiu lan Kwan See Iem Pou Sat, Pek chian ban ek hut, heng ho sua sou hut 4) Doa itu, yang diajarkan oleh pamannya, memancar bagaikan sebuah mata air di pegunungan yang melenyapkan dahaga, menyiram kebimbangannya. Ia pun berlari kencang menerobos hujan yang menderas. *** Ia berangkat pada hari suci Kwan Iem Pou Sat 5) mencapai moksa, 19 Lak Gwee. Ketika itu hujan juga turun dengan derasnya 6). Pamannya mengiringi kepergiannya dengan menabuh sebuah gendang kecil berwarna merah yang biasa digunakan dalam ritual di kelenteng sambil melantunkan syairsyair dari Kitab Suci Koo Ong Kwan See Iem Keng. Sebuah kitab yang syahdan bila dibaca sebanyak 1000 jurus, akan membuat kesulitan pupus seperti embun disapa matahari pagi. Bahaya api tak akan mendekati, senjata tajam tidak mempan, kemarahan berbalik jadi kesukaan, dan kematian menjadi kehidupan. Itu juga kata pamannya, meski pada awalnya ia hanya percaya dengan setengah hati. Tetapi sejak kecil ia memang telah diwajibkan membaca kitab tersebut dengan tekun, hingga menghafal semua doa-doa yang terdapat di dalamnya. Pagi itu, sesudah bersujud kepada delapan Pou Sat dan membakar tiga batang hio menghadap ke langit timur dengan bergegas karena hujan rintik-rintik mulai turun, ia pun meninggalkan rumah yang membesarkannya. Sebenarnya hatinya masih diliputi perasaan was-was mesti meninggalkan pamannya yang tua, yang akan tinggal sendirian setelah kepergiannya. Tetapi perjalanan itu telah begitu lama memanggil, sejak pamannya membuka Kitab Thung Su pada suatu malam dan menemukan takdirnya tertera di sana. Ia tahu, ia tidak akan dapat menolak takdir itu lantaran tanggal, bulan, dan tahun kelahirannya tercantum jelas di sana. Sebagaimana Hou Xiang Tjhe 7) tidak dapat menolak takdir menjadi dewa, meskipun harus menjalani tiga kali reinkarnasi. Sejak semula ia tahu, kalau perjalanan ini tidaklah mudah. Akan penuh dengan rintangan. Tak urung pada malam itu ia sempat tergetar. Dan tak dapat memejamkan mata hingga pagi menjelang. Teringat ia pada kisah Rahib Tang yang mendapat takdir melakukan perjalanan ke Barat untuk mencari kitab Mahayana dengan dikawal tiga siluman yang bertaubat. *** Masa kecilnya dihabiskan di kampung kecil yang hibuk dengan doa, dengan bunyi gong yang nyaring bergema dari kelenteng tua, dan santer aroma hio itu. Setiap pagi dan sore,
berduyun-duyun orangtua-muda, besar-kecil, laki-perempuanbakal datang ke kelenteng besar yang dijaga dua buah arca Khilin 8) di muka pintunya tersebut. Memohon rezeki, penyembuhan penyakit, atau meminta jodoh. Pamannya selalu sibuk melayani orang-orang yang datang, membuka-buka Kitab Sam Se Su 9), membacakan pantun dan syair-syair, juga mantera bagi para Thung Se 10) yang akan menjadi perantara dewa-dewi dalam ritual. Ia selalu membantu. Memotong kertas-kertas kuning untuk phu 11), atau menyiapkan hio dan gelas-gelas berisi air putih. Tak jarang pula ialah yang menabuh gong besar dari kuningan, tiga puluh tiga kali. Dari perlahan hingga semakin cepat hingga suara gong yang lantang bergaung jauh ke ujung tanjung. Bila siang hari dan kelenteng sepi dari pengunjung, biasanya ia akan duduk di bawah sebatang pohon ceri besar di seberang kelenteng sambil memperhatikan laju perahu-perahu sampan para nelayan yang menyisir sungai berkelok-kelok. Sampai sampansampan itu lenyap di belakang kelenteng. Kadang ia akan mengeluarkan seruling bambu dari dalam tas rumput resam yang selalu dibawa, memainkan lagu-lagu tua yang sering dinyanyikan pamannya. Suara tiupan seruling itu akan terbawa angin, saling tindih-menindih dengan suara gesekan daundaun bambu yang tumbuh rimbun di seberang sungai. Lalu pada malam-malam yang panjang, sambil duduk berdiang di depan tungku di dapur, pamannya akan berkisah tentang riwayat Buddha, juga bagaimana para Pou Sat dan dewadewi menempuh jalan berliku-liku hingga mencapai langit ketiga puluh tiga. Tempat segala yang baik dan bijak berdiam. Pintu gerbangnya dijaga oleh Dewa Erl Lang bermata tiga dan Anjing Langit. Tak ada seorang pun yang dapat memasuki gerbang suci tersebut selain orang-orang yang memang telah ditakdirkan Song Ti untuk memasukinya, tukas sang paman. Pamannya juga mengajarinya membaca pelbagai macam mantera pengundang dewa. Yang dihafalnya dengan tersendat-sendat Thi mun sam sip sam thian thai kau cu Thai song ng ngian cin lo kiun Bong mu chit chien liung tu cun 12) Sampai pagi itu, ia terbangun pagi-pagi sekali. Udara yang masih diliputi kabut tipis begitu dingin menggigit. Setelah memberi makan ayam dan bebek peliharaan, ia melihat bunga padma di kolam ikannya telah mekar. Ia tahu, itulah tanda baginya untuk pergi. Hari itu adalah hari kesempurnaan Kwan Iem Pou Sat. *** Aku mendengar cerita ini dari seorang tua di sebuah kota kecil yang pikuk. Kota yang terletak di tepian timur sungai kecil keruh itu dulunya --kata orang tua yang bicara denganku-adalah sebuah kampung yang kumuh, miskin, dan terbelakang. Para penduduknya selalu berwajah murung dan lebih suka menghabiskan waktu dengan
melamun, bermain gaple atau menyabung ayam. Bila Tuan datang ke kampung itu, yang akan Tuan temui hanyalah pemandangan yang sangat tidak menyenangkan. Jalanjalan berdebu dipenuhi sampah, rumahrumah tua tak terawat yang lebih mirip kandang berdempetan. Dengan lelaki-lelaki yang termenung sepanjang hari di muka rumah bersama segelas kopi, perempuan-perempuan dekil yang selalu bermuka masam, serta anak-anak yang kurus kering berperut buncit. Kampung itu betul-betul terpencil. Satu-satunya penghubung kampung tersebut dengan dunia luar hanyalah jembatan bambu kecil di sungai yang tinggal menunggu waktunya ambruk. Untuk menemukan kendaraan bermotor, Tuan harus berjalan kaki puluhan kilo hingga tiba di kampung lain yang terdekat. Sampai pada suatu hari, ketika hujan turun dengan begitu deras, padahal telah berbulanbulan hujan tak turun, Llewatlah orang suci itu dengan sebuah buntalan kumal, dengan sekujur tubuh yang basah kuyup. Wajahnya begitu elok, bercahaya laksana malaikat. Membuat perempuan-perempuan terpukau takjub. Dan ketika ia berbicara, suaranya penuh wibawa dengan tutur kata yang begitu halus. Karena itu percayakah, Tuan, kalau begundal yang paling laknat pun seolah menjadi tak berdaya? Serempak pintu-pintu rumah segera terbuka untuknya singgah berteduh (Syahdan, orang suci itu sendiri juga nyaris tak percaya. Ia jadi terkenang pada pendeta bermata kudus tinggal di atas bukit yang memberinya sebuah kompas. Pendeta tua yang telah mengajarinya membaca pertanda di langit). Maka ia pun memilih salah satu rumah, yaitu rumah orang tua yang bercerita padaku. Karena hujan tidak juga reda sementara hari semakin gelap, akhirnya orang suci itu memutuskan untuk bermalam di rumah tersebut. Orangorang kampung pun seketika berdatangan mengerumuninya. Mendapatkan kejadian yang tak disangka-sangkanya itu, sambil menyantap ubi rebus dan menghirup kopi yang disuguhkan, orang suci itu akhirnya bercerita. Ia bicara tentang penderitaan Buddha dan perjalanan para Pou Sat, seperti yang selalu dikisahkan pamannya kepadanya. Juga mengenai dirinya sendiri. Orang-orang yang mendengarkan jadi ternganga dengan muka terbengong-bengong, lalu berebutan menciumi tangannya. Ah, aku jadi ikut-ikutan terpukau mendengar cerita yang dituturkan orang tua yang kutemui di kota kecil itu... Konon, ketika keesokan pagi-pagi sekali, orang suci itu akan berangkat lagi meneruskan perjalanannya ke timur, orang-orang kampung melepaskannya dengan air mata bercucuran. Anak-anak dan para perempuan bergantian memeluknya. Begitulah Tuan, setelah keberangkatannya, di kampung itu pun mulai terjadi perubahan yang tak terduga. Wajah para penduduk berangsur-angsur mulai tampak cerah. Perempuan-perempuan mulai suka bernyanyi ketika mandi-mencuci di sungai dan anakanak tampak begitu riang bermain.
Kemudian seperti digerakkan oleh sesuatu yang gaib, tak dinyana satu per satu para lelaki diikuti para perempuan mulai kembali turun ke ladang. Ada pula yang berternak dan membuka warung makan di pinggir jalan. Entah kenapa, kehadiran orang suci itu bukan hanya membangkitkan semangat para penduduk tetapi juga seperti membawa berkah. Hujan menjadi kerap turun, menyuburkan kembali tanah-tanah yang retak, membuat tanaman-tanaman meruap hijau segar. Orang-orang tak henti-hentinya bersyukur. Setiap kali malam Minggu tiba, mereka berkumpul di tanah lapang, tua-muda hingga kanak-kanak. Mereka bernyanyi, menabuh gendang dan rebana, lalu berjoget dengan riuh, kata orang tua yang bicara denganku itu menerawang. Tak lama kemudian satu demi satu para perantau pun mulai berpulangan. Termasuk yang telah meninggalkan kampung puluhan tahun dan belum pernah sekali pun pulang lagi. Hal itu kemudian disusul dengan berdatangannya orang-orang asing. Mereka membuka perkebunan sawit, toko-toko, bahkan kemudian mendirikan pabrik es. Dalam kurun waktu lima tahun, siapa yang menduga kampung kumuh yang senyap itu telah berubah menjadi sebuah kota kecil yang hiruk-pikuk. Aku semakin tercengang. Tapi orang tua yang bicara padaku itu tiba-tiba berhenti berkisah. Sekilas aku menangkap sebersit sinar matanya yang begitu pilu. Aku menunggu dengan jantung berdebar-debar. Cukup lama. Sampai akhirnya ia kembali membuka mulut bicara. Suaranya terdengar serak dan parau, seperti menyimpan suatu beban yang amat berat. Dengan mata berkaca-kaca, ia kemudian bercerita bagaimana pada suatu sore sepulang dari ladang, ia menemukan ibunya sedang bergelut dengan seorang lelaki asing dalam kamar. Amarahnya tanpa dapat dibendung, langsung mendidih serupa minyak sayur yang dituangkan ke atas wajan panas. Tanpa berpikir panjang, dikuncinya pintu rumah dari luar. Lalu dengan tubuh bergetar dituangkannya bensin ke sekeliling rumah dan langsung menyalakan korek api hingga dalam waktu sekejap saja, papan-papan lapuk rumah tua peninggalan mendiang ayahnya itu telah berderak-derak dilahap lidah api yang meliuk-liuk ganas. Sambil tertawa terbahakbahak seperti orang kurang ingatan, ia pun berkacak pinggang menyaksikan bagaimana rumah yang membesarkannya itu semakin tenggelam dalam kobaran api bersama jeritan-jeritan histeris di dalamnya. Aku merasa kedua lutut goyah, dan mulutku begitu kering. Kejadian itu telah puluhan tahun yang lalu, waktu itu orang tua yang menceritakan padaku masihlah seorang pemuda tanggung. Aku tidak tahu --agaknya juga tidak seorang pun yang tahu, termasuk lelaki tua yang berkisah padaku--di mana orang suci itu sekarang. Ke mana ia pergi dan apakah ia berhasil menemukan jalan menuju langit ketiga puluh tiga. Aku hanya mengenang cerita tentang orang suci itu sebagai sebuah cerita yang aneh dan menuliskannya untuk Tuan.*** Bangka, 2004-2007/ Yogyakarta, 2010
Catatan: 1. Sam sip sam thian: langit lapis ketiga puluh tiga. Dalam khazanah mitologi, konon merupakan khayangan tingkat tertinggi. Tempat Kaisar Giok (Nyuk Fong Thai Ti) dan para dewata berdiam. Keberadaannya sering digambarkan secara profan dalam sejumlah karya sastra Cina klasik seperti Si Yu Ki, Nan Yu Ki, Tung Yu Ki dan lain-lainnya yang sangat kental dengan ajaran Buddha. Penyebutannya juga ditemukan dalam banyak mantera ritual Lok Thung (trance) yang dilakoni para penganut Senisme (berasal dari kata Sen=dewa). 2. Thung Su: semacam buku pintar yang berisi berbagai perihal tentang dunia-akhirat. 3. Song Ti: salah satu sebutan untuk Tuhan. 4. Dikutip dari Kitab Suci Koo Ong Kwan See Iem Keng. 5. Pou Sat: Bodhisatva. 6. Pada hari-hari suci para Bodhisatva (dan dewata), konon diyakini akan selalu turun hujan deras. 7. Hou Xiang Tjhe: salah satu dari Delapan Dewa (Pat Sien). Konon ia menolak keras takdirnya menjadi dewa lantaran cintanya kepada isteri dan ibunya yang sudah tua. Sehingga Kerajaan Langit menghukumnya bereinkarnasi sampai tiga kali. 8. Khilin: binatang Barongsay, binatang ganjil perpaduan singa dan naga. 9. Sam Se Su: sejenis buku primbon. 10. Thung Se: medium/ pengantara para dewata dalam ritual Lok Thung (trance). 11. Phu: kertas kuning persegi panjang yang berisi mantera penolak bala. 12. Mantera mengundang Dewa Thai Song Lo Kiun.
Mobil Pengantin Cerpen Sunlie Thomas Alexander Dimuat di Jawa Pos 07/05/2009 Telah Disimak 723 kali Dulu, setiap pasangan pengantin Tionghoa di kota kecil kami selalu diarak berkeliling dengan mobil. Seingatku mobil itu sedan Mitsubishi buatan tahun 70-an, milik seorang pemilik salon yang memang khusus direntalkan untuk keperluan mobil pengantin. Sedan itu biasanya dirias meriah dengan sulur-sulur pita panjang berwarna-warni yang melintang
dari depan moncong ke belakang dengan ikatan simpul yang indah di atas atapnya serupa ikatan pita pada kotak kado. Di bagian moncong mobil itu juga dipasangi rangkaian kembang aneka rupa dan sebuah boneka kecil berwujud pengantin perempuan. Kedatangan mereka akan ditandai oleh hentakan musik tanjidor yang gegap gempita memainkan lagu-lagu yang lagi hits kala itu, baik pop Mandarin dan Barat, maupun lagulagu pop Melayu atau dangdut. Sebagai kanak-kanak, aku dan teman-teman sebaya pun berhamburan keluar rumah meninggalkan sarapan dan film si Unyil di televisi, atau permainan yang sedang seru-serunya di pekarangan, lalu melonjak-lonjak kegirangan di pinggir jalan demi menyaksikan perarakan (Ai, kebanyakan mereka lewat pada Minggu pagi, entahlah kenapa orang-orang Tionghoa di kota kecil kami lebih suka menikah di hari Minggu). ''Pengantin lewat! Pengantin lewat!'' teriak kami sambil melambai-lambaikan tangan ke arah sedan pembawa kedua mempelai yang berada di bagian terdepan rombongan dan disusul mobil bak terbuka dengan bangku panjang berhadap-hadapan yang membawa para pemain tanjidor, baru kemudian barisan mobil pengantar yang berisi keluarga, sanakkerabat, dan sahabat kedua mempelai.
''Pengantin perempuannya cantik, tapi mempelai laki-lakinya tampak bodoh!'' terkadang terlontar pula dari mulut jahil kami kata-kata sadis itu. Tapi jika pasangan pengantin itu ramah, mereka akan tersenyum dan melambaikan tangan keluar jendela sedan membalas sambutan kami.
''Peeeleee, peelleeeeee chuuumm...! Sin ngiong kauw loo kuuunng!"1 sorak-sorai kami terdengar riuh sepanjang jalan sambil terus berjingkrak-jingkrak menirukan sesuara alat musik tanjidor. Aku dan teman-teman sebayaku selalu berangan-angan suatu hari nanti kami pun akan dibawa dengan mobil pengantin itu menyusuri jalanan kota. Mereka diarak berkeliling di jalan-jalan utama kota kecil kami, dari rumah pengantin perempuan menuju rumah pengantin lelaki di mana prosesi pernikahan dilanjutkan kembali
setelah sang mempelai perempuan dijemput. Kami akan terus bersorak-sorai dan melambai-lambai hingga mobil terakhir rombongan pengantin itu lenyap di tikungan jalan meninggalkan gema musik tanjidor. Bahkan sampai jauh mereka pergi, kami masih terus melambai-lambai di tepi jalan. Gema musik tanjidor dan bayangan mobil pengantin yang dirias meriah itu masih saja tertinggal dalam pikiran dan hati kami. Dan kemudian mengilhami kami bermain pengantin-pengantinan.
Kami berkeliling di pekarangan rumah dengan sepeda mini yang kami rias dengan kertaskertas klip dan kertas mas beragam warna, juga bunga-bunga yang kami petik dan rangkai sendiri dan kami letakkan pada bagian depan keranjang sepeda. Yang paling sering menjadi pengantin adalah aku dan Mei Cin. Ia meminjamkan boneka pengantin oleh-oleh pamannya dari Jakarta untuk diikat pada stang sepedaku. Lalu kami pun didaulat berboncengan sepeda yang telah kami amsal sebagai mobil pengantin itu dengan diiringi teman-teman lain di belakang sambil bernyanyi, menabuh kaleng dan meniup terompet kertas menirukan para pemusik tanjidor. Mei Cin selalu tampak cantik dan manis dengan gaun pestanya serta rambut tergulung rapi yang dirias oleh anak-anak perempuan lain dengan rupa-rupa kembang dan pernik-pernik manik...
Ah! Begitulah masa kanak-kanak yang semanis gulali, Kawan. Kau tahu, betapa menggemaskannya! *** KINI, tentu saja tidak ada lagi pengantin yang diarak dengan mobil di kota kecil kami. Orang-orang lebih suka melangsungkan pesta pernikahan di gedung sewaan (gedung olahraga atau serbaguna milik perusahaan timah) atau bolehlah hotel berbintang tiga di kota kabupaten, tanpa perlu berkeliling kota dengan mobil pengantin. Yang tak punya banyak biaya, cukuplah mengadakan resepsi sederhana di rumah mempelai perempuan atau laki-laki dengan menggelar pelaminan merah menyala.
Kelompok tanjidor dengan pemusiknya yang sudah tua-tua dan satu-dua pemain lebih
muda yang menggantikan personal-personel yang telah meninggal memang masih ada, tetapi mereka sudah jarang tampil. Paling hanya pada acara-acara pemakaman atau sembahyang kubur dengan membawakan lagu-lagu duka. Tentunya, orang-orang lebih senang mengundang musik band atau organ tunggal dengan biduannya yang cantik dan seksi. O, rasa kehilangan kami pun kian sempurna pada setiap kepulangan! Didera kenangan. Tapi jangan menuding zaman, Kawan. Karena kami tahu betul bagaimana mulanya tradisi perarakan pengantin itu lenyap dari kota kelahiran kami. Seperti halnya haru-biru masa kecil kami yang terus diawetkan, kisah ini pun tetaplah mengendap sebagai trauma dalam kehidupan sebuah kota kecil.
Hmm, kau ingin tahu ceritanya bukan? Bagaimana dan apa yang menyebabkan mobil pengantin *** AI, kalau saja peristiwa naas itu tak pernah terjadi, barangkali tradisi mobil pengantin masih akan tetap hidup di kampung halaman yang kami cintai ini. Tak cuma sekadar bagian masa lalu yang penuh nostalgia di hati orang-orang yang bersetia pada kenangan. Tetapi bakal terus berkeliling kota membawa pasangan-pasangan pengantin baru yang memupuk mimpi hidup bahagia untuk selama-lamanya seperti dongeng Pangeran dan Cinderella. Akan tetap menjadi hiburan tersendiri bagi kehidupan kota kecil kami yang monoton. Namun Kawan, demikianlah peristiwa tragis itu terjadi. Perempuan separo baya itu menghambur ke tengah jalan ketika arakan pengantin sedang melintas, tertabrak mobil pengantin dan mati! Hari istimewa yang berbahagia pun segera berubah jadi mimpi buruk bagi kedua mempelai malang hari itu. Ah, bagaimana tidak buruk dan takkan menghantui kehidupan perkawinan kelak, bila mobil pengantin yang sedianya menjadi perlambang dari menghilang dari kota kecil kami?
bahtera rumah tangga telah meminta korban di hari pernikahan; awal dari hidup baru yang penuh pengharapan! Duh...
Pengantin perempuan menjerit-jerit histeris. Sementara pengantin laki-laki tegak pucat pasi di depan korban yang tergeletak bersimbah darah (Darah itu memerciki moncong mobil pengantin, bunga-bunga, dan boneka!). Di matanya membersit ketakutan akan nasib ke depan yang seolah telah dipayungi awan mendung. Terlebih karena orang-orang ramai tanpa tenggang rasa bergunjing keras, mengulurkan prasangka, saling menerka isyarat dan pertanda apakah yang dilemparkan langit kepada keduanya! Duh, dosa apakah yang telah mereka perbuat hingga ditimpa bala sedemikian rupa?
Mungkin memang takdir buruk semata yang tak dapat ditolak. Tapi tentu takkan pengantin lelaki itu dihimpit rasa sesal yang sebegitu besar, seandainya ia tak berkeras melangsungkan pernikahannya pada Sabtu pagi tersebut, tanggal tatkala mereka pertama kali berjumpa. Padahal sinsang2 yang bertugas menentukan hari baik sudah menyampaikan was-was. Konon, kitab Thung Su3 yang dibuka telah memberi ingat agar tidaklah melangsungkan hajat pada hari Sabtu, sebab hari itu merupakan Ciong4 bagi shio keduanya. Sabtu adalah hari panas yang berunsur api di bawah naungan Mars. Namun, ia hanya tertawa mencemooh, bersikeras!
Orang-orang pun menuduh-menyalahkan, mencemooh penuh kemarahan. Dan semenjak itu mitos dan adat pun kian kental terpelihara di kota kecil kami. Sebagai ketakutan! *** TETAPI gerangan apa yang membuat perempuan separo baya tersebut nekat berlari ke tengah jalan pagi itu hingga mati tertabrak mobil pengantin yang malang? Hal apa yang membuatnya --konon begitulah kesaksian orang-orang-- seperti sengaja menyongsong laju kendaraan? Kau ingin tahu juga kan?
Hampir setiap orang Tionghoa di kota kecil kami mengenal Bibi Hwa, demikianlah
perempuan yang mati itu dipanggil, sebagai seorang perawan tua yang tinggal bersama keluarga keponakannya. Orang tuanya sudah lama meninggal, dan keponakannya itulah satu-satunya keluarganya yang masih tinggal di kota kecil kami. Sehari-hari Bibi Hwa berjualan kemplang5 dari rumah ke rumah. Kemplang itu buatannya sendiri, yang digoreng dengan pasir dan biasanya dibungkus dengan kantung plastik besar yang diboncengkan di belakang sepeda kumbangnya. Semua orang menyukai Bibi Hwa dan kemplang-nya yang gurih, terutama anak-anak kecil seperti kami. Terlebih Bibi Hwa sering memberi lebih jika kami membeli kemplang-nya, bahkan kadangkala ia memberi gratis kalau kami lagi tak punya cukup uang. Meski, kata orang-orang, pikiran Bibi Hwa sedikit terganggu. Ia suka tertawa dan menangis sendiri, dan kami pun pernah memergokinya tiba-tiba cekikikan tanpa sebab di atas laju sepeda! Tapi kami tak peduli, bagi kami ia tetap saja baik hati dan menyenangkan ketika diajak bersenda gurau.
Ah, ''penyakit''-nya itu konon berasal dari masa lampau yang getir, sepahit empedu dan hendak dikuburnya sedalam mungkin, demikian orang-orang menebar kisah tua. Masa lalu, yang sesekali suka kembali mendera: dengan tak tertanggungkan! Membuat hati setiap orang yang tahu ceritanya pun menjadi iba, dan membuat Bibi Hwa tak pernah berhasrat menikah... Dulu, di waktu mudanya --cerita orang-orang-- kecantikan Bibi Hwa pernah membuat banyak lelaki tergila ingin mempersuntingnya (Ai, bukankah kecantikan itu seolah tak habis dimakan usia dan derita?). Tetapi hanya seorang lelaki sajalah yang berkenan di hatinya. Keduanya telah lama saling mengenal. Lelaki itu, A Kwet, adalah bekas teman sekolahnya di Chung Hwa Hwee Kon6 yang tak pernah berijazah lantaran sang bapak keburu meninggal. A Kwet kemudian bekerja sebagai buruh bangunan sebelum akhirnya berjualan sayur-ikan di pasar.
Toh, Bibi Hwa tegas memilih teman sekolahnya itu, meskipun yang menyukai dirinya tak kurang anak-anak orang berada dan orang tuanya sendiri sebenarnya kurang restu (Hm, tentunya berharap ia dapat dipersunting seorang kaya. Ya, maklumlah orang tuanya sendiri cuma pedagang toko kelontong kecil-kecilan. Tentu menantu yang berduit akan ikut
memperbaiki nasib mertua pula, hahaha!) Namun apa mau dikata, keduanya saling suka. Ketika A Kwet datang melamar, orang tua Bibi Hwa pun tak kuasa lagi menolak. Dan hari pernikahan kemudian segera ditetapkan.
Tetapi, inilah kisah getirnya: Setelah semua telah rapi diatur pada pagi yang cerah itu, dan sang mempelai lelaki bersiap menjemput mempelai perempuan, segalanya mendadak berkhianat! Padahal betapa Bibi Hwa yang telah didandani dengan pakaian pengantin merah beludru lengkap dengan kembang-kembang emas di kepala, tampak begitu sumringah. Sungguh cantik merona, puji orang-orang berdecak. Semua sanak keluarga pun telah menunggu tak sabaran mulainya prosesi adat nikah.
Namun sampai waktu yang telah ditentukan, sang pengantin lelaki tak kunjung bertandang. Semua orang mulai bergunjing dengan gelisah. Pihak pengantin perempuan baru saja hendak mengutus seorang kerabat pergi menanyakan segala hal ihwal; siapa tahu ada kendala yang tak disangka. Belum sempat utusan itu berangkat, tiba-tiba seorang kemenakan telah datang mendahului dengan tersaruk-saruk membawa kabar duka. Tak mungkin! Semua orang terperangah, tercengang tak percaya. Bibi Hwa sendiri terbeliak, menjerit lalu jatuh pingsan sebelum kalimat terbata-bata itu habis meluncur dari mulut sang pembawa berita. Kabar duka itu kemudian berhembus lebih cepat dari angin: Pengantin lelaki hari itu meninggal dalam mobil pengantin dalam perjalanan menjemput mempelainya! Suara-suara kaget seperti dengung kawanan lebah, mengundang kegemparan di seantero kota kecil kami. Tak seorang pun yang tahu pasti bagaimana sebetulnya kejadian! Kecuali bahwa A Kwet keracunan minuman yang belum lama berselang diteguknya saat hendak berangkat. Itu pun diketahui kemudian setelah jenazah dan bekas gelas minuman diperiksa oleh satu-satunya dokter yang berpraktik di kota kecil kami kala itu. Semua orang terpana. Siapa yang telah melakukannya? Apa motifnya? Polisi tidak berhasil mendapatkan
petunjuk. Yang ada, hanya hembusan isu kalau salah seorang lelaki yang ditolak Bibi Hwalah yang punya kerja, barangkali lewat tangan orang suruhan yang menyamar jadi seorang kemenakan jauh. Namun jauh hari kemudian, ada pula yang mengaitkannya dengan peristiwa besar di tahun 65. Tentu dengan berbisik-bisik, jika A Kwet yang diketahui menjadi bendahara perkumpulan Lo Kung Fei7, telah disingkirkan lebih awal oleh kawankawannya sendiri setelah ketahuan diam-diam menggelapkan dana, juga beras-gula-gabah. Di samping menjual arsip-arsip bernilai yang rahasia kepada tentara!
Mana yang benar, sampai kini tetap pekat. Yang jelas, sejak kejadian itu, Bibi Hwa makin menjauhkan diri dari kaum lelaki (Meski tetap banyak yang berkenan meminang). Sampai menjadi perawan tua yang suka tertawa-menangis sendiri, sampai peristiwa ia menghamburkan diri ke tengah jalan menyongsong mobil pengantin yang melintas lewat dan tertabrak mati.
Ah, pengantin lelaki yang malang tersebut, syahdan, menurut orang-orang, wajahnya begitu *** YA, sejak itulah, sejak kejadian tragis tak terduga itu, tak ada lagi mobil pengantin dengan gegap gempita iringan musik tanjidor di kota kecil kami. Entah kenapa orang-orang seolah begitu takut untuk memeriahkan pesta pernikahan dengan perarakan mobil pengantin keliling kota; tapi cukuplah menggelar resepsi di rumah dengan hiburan band atau organ tunggal seadanya. Mungkin ada semacam rasa kuatir jika malapetaka serupa bakal berulang --bala yang akan mengundang ilusi buruk sepanjang usia perkawinan sepasang pengantin malang! Atau karena menganggap kejadian naas tersebut merupakan sebuah isyarat bila tata prosesi perarakan pengantin dengan mobil tidaklah disukai para dewa (Ai, sudah kukatakan jika mitos kian kental menggeliat di kota kecil kami!). mirip-serupa dengan A Kwet!
Ya, tentu banyak yang merasa kehilangan, terutama kami anak-anak. Terasa hingga kami dewasa dan satu per satu menikah. Kebanyakan dari kami menikah di tanah rantau dengan
orang
jauh,
termasuk
Mei
Cin.
Aku menyempat diri datang saat ia melangsungkan resepsi pernikahannya di sebuah villa mewah di Puncak. Lama kami bersitatap, tertegun dengan kenangan yang mengalir deras, ketika aku menyalaminya untuk mengucapkan selamat. Seperti ada sesuatu --yang lebih dari sekadar nostalgia-- membuncah hebat di mata kami berdua. Dan, diam-diam aku merasa dijalari oleh semacam perasaan gerah. Mungkinkah itu perasaan cemburu atau rasa kehilangan *** Belinyu-Jogjakarta, Catatan: 1. 2. 3. Semacam "Pele, pele chum... Dukun buku Pengantin menikah!" China. primbon. 2005-2009 yang nyata? Entahlah.
4. Secara harfiah dapat diartikan sebagai sebuah posisi saling berhadapan, "via a vis". Dalam khazanah kosmologi China, posisi ini merupakan posisi yang sangat rawan karena bakal menuntut korban. Ciong juga berarti semacam "sekak" dalam permainan Catur Gajah. 5. Kerupuk khas Bangka, kebanyakan dipanggang namun ada juga yang digoreng dengan pasir 6. Sekolah Tionghoa yang ditutup oleh pemerintah sekitar tahun panas. 60-an.
7. Perkumpulan Tionghoa yang bernaung di bawah PKI.
Bangku Beton Cerpen Sunlie Thomas Alexander Dimuat di Jawa Pos 01/06/2008 Telah Disimak 1143 kali
BANGKU beton itu masih di sana, di bawah rindang batang jambu air. Kusam dan berlumut tebal. Alangalang tumbuh lebat di sekelilingnya, tanaman pakis menjalar liar. Di atasnya, berserakan guguran daundaun tua. Sebagian telah membusuk oleh hujan. Ia tertegak di pintu dapur, tak berkesip memandang bangku di sudut pekarangan rumah itu. Entahlah, lamat-lamat ia seolah mendengar tiupan harmonika, mendengar lagu Les Premiers Sourires de Venessa-nya Richard Clayderman. Beberapa saat lamanya ia merasa terbuai. Tapi, sesuatu seperti menyesaki dadanya. Tanpa sadar ia menggigit bibir. Pandangannya menjadi buram. Tentu ia tak pernah bisa melupakan lagu itu, juga lagu-lagu Richard Clayderman lainnya. Meskipun sudah demikian lama, bertahun-tahun, tak pernah mendengarnya lagi. Ia ingat, lelaki itu nyaris dapat memainkan semua lagu Richard Clayderman dengan segala instrumen, dengan cukup sempurna. Di tengah pandangannya yang berkabut, lelaki itu seolah masih duduk di sana sambil meniup harmonika. Hampir setiap sore, setelah toko tutup, lelaki itu akan duduk-duduk di bangku beton di bawah pohon jambu air lebat itu sambil meniup harmonika, membaca buku atau koran. Kadangkala secangkir kopi menemaninya. Lelaki itulah yang membuat ia jatuh cinta pada musik, juga mengenalkannya pada wushu. "Pinggangmu kurang lentur, geser kaki kananmu lebih ke belakang," ia seperti mendapat instruksi dari lelaki itu lagi. "Ya, turunkan kuda-kudamu lebih rendah. Kalau lawan datang dari samping, kau akan punya kesempatan mengelak dan menyerang bagian rusuknya." Tapi, lututnya sudah goyah, bahunya terasa linu. "Sudah Pa, sudah capek. Aku mau main bola..." "Ah, manja kau!" lelaki itu menyeringai." Kau les piano kan nanti malam?" Aroma dupa mengental, menyengat hidungnya. Gerimis sudah berhenti. Tiupan harmonika itu timbultenggelam, terus mengiang-ngiang di telinganya. Lagu-lagu silih berganti, menyeret kembali kenangannya dengan kejam. Ballade Pour Adeline, A Comme Amour, Un Blanc Jour Dun Chaton, Nostalgy, Lettre A Ma Mere... Agaknya ia masih menghafal semua judul lagu. Meskipun ia tidak pernah bisa memainkan lagu-lagu itu dengan baik di atas tuts-tuts piano, dan lebih tertarik pada musik klasik murni. Pada Chopin, Mozart, Beethoven, dan Bach. Atau yang lebih kontemporer, Stravinsky. Dan, ketika memutuskan untuk belajar di akademi musik, ia pun lebih senang mengambil mayor gitar. Ada jalan setapak kecil dari susunan batu-batu putih, membentuk lengkungan setengah lingkaran dari pintu dapur ke bangku beton itu, memotong hamparan rumput jarum yang meranggas. Agak ragu ia melangkahkan kakinya ke sana. Angin sore terasa basah, sedikit kencang, membuat dedaunan jambu air bergemerisik ribut. Ia melihat daun-daun tua keemasan yang melayang jatuh seakan dalam gerak slow motion. Dan, hal itu, entah kenapa, membuat perasaan sedihnya semakin tajam. Seperti mengiris di dada. Ah, waktu! Waktu! Namun, saat langkah kakinya sampai di sana, bangku beton itu tiba-tiba terasa begitu senyap. Bungkam, seakanakan tak berkenan menyambut kedatangannya. Tak ada lagi tiupan harmonika, tak ada lagu-lagu Richard Clayderman yang mengiang di telinganya. Semua lenyap. Ia berdiri tertegun di bawah kerindangan pohon jambu.
Memandang sekeliling, ia melihat pekarangan rumahnya kini agak kurang terurus. Ia tahu, sejak muda ibunya bukanlah perempuan yang cukup telaten mengurus rumah. Lagi pula sekarang di rumah mereka tak ada pembantu. Bibi Fatonah dipulangkan ibu ke kampung setelah lelaki itu meninggal. "Dia sudah tua, biarlah istirahat di kampung. Ibu beri pesangon secukupnya," kata ibunya dalam sepucuk surat. Ah, dulu lelaki itu selalu wantiwanti kalau pekarangan belakang rumah itu harus selalu bersih dan rapi. Tiba-tiba ia baru menyadari kalau di teras belakang itu tak ada lagi pot-pot bunga berukuran besarkecil yang tertata indah. Beragam bunga, terutama euphorbia, anggrek, dan adenium. ia termangu-mangu di depan bangku beton yang kusam berlumut itu. Mencoba mengingat semua kejadian indah yang pernah dilewati. "Kau mau makan dulu?"Suara ibu sedikit mengagetkan lamunannya. Ia berpaling dan mendapatkan perempuan itu sedang berdiri di ambang pintu dapur. Ia menggeleng ragu. *** IA pulang juga setelah sembilan tahun. Rumahnya -sebuah ruko tepatnya-tidak banyak berubah seperti juga kota kecilnya. Bagian muka ruko tampak sepi, ketika ia turun dari angkot yang membawanya dari pelabuhan. Rolling door biru muda kusam berkarat tertutup rapat dengan gembok besar terkait di bagian bawahnya. Hujan rintik-rintik menyergapnya di depan ruko. Kernet angkot membantu menurunkan dua ransel besar yang dibawanya. Setelah membayar sesuai harga yang telah disepakati di pelabuhan, ia mengangkat kedua ransel besarnya, agak sempoyongan karena berat. Ada beberapa orang menatapnya. Ia berpaling ketika merasa mengenali seseorang. Seorang perempuan separo baya. Ia masih mengenali perempuan itu, tetangga bertahun-tahun. Ia tersenyum lebar. Tapi perempuan itu diam saja, terus menatapnya tak berkedip, meskipun kemudian mengangguk kecil. Tanpa senyum. Ah, apakah ia tidak kenal padaku lagi? Pikirnya kurang enak. Diteruskan langkahnya ke pintu depan rumah yang terbuka dengan rolling door tergulung ke atas. Sebetulnya itu pintu samping dari ruko yang berfungsi sebagai pintu masuk rumah tinggal. Los toko dipisahkan dari rumah dengan pembatas dinding triplek yang membentuk semacam lorong kecil dari pintu masuk itu. Lampu di lorong kecil itu belum dinyalakan. Ia akhirnya sampai ke bagian dalam rumah. Ruang tengah juga tidak banyak berubah. Sebuah lukisan pemandangan alam pegunungan masih tergantung sayu di dinding. Agak miring. Berpaling ke kiri, ia melihat pintu kamar baca itu tertutup rapat. Kenangan yang berdebu menyergapnya. Gelenggeleng kepala, ia meneruskan langkahnya melewati ruang tengah. Ada seekor kucing belang tidur di dekat sofa. Bangun mendadak ketika ia lewat. Kucing itu tampak waspada. Ia menyeringai lebar. Ketika ia sampai di dapur, ibunya sedang mengatur sesajen di atas meja sembahyang. Perempuan itu menoleh ketika mendengar langkah kaki anaknya masuk. Tampak begitu tua dan ringkih, tapi senyumnya masih menyisakan kecantikan di masa muda. "Ah, kau sudah sampai rupanya. Pas! Mama baru saja mau sembahyang." Perempuan itu menarik sebuah kursi plastik di dekatnya, "Duduklah." Perempuan itu kemudian menuangkan secangkir teh dari teko keramik untuk anaknya. Diperhatikan betul kerut-merut wajah ibunya, juga uban di kepala perempuan itu. Ia tersenyum getir. "Mama pikir kau tak jadi pulang," suara ibunya seperti menggantung. Ah, tidak Ma, aku pasti pulang seperti yang aku katakan di telepon, elaknya buruburu. Ibunya tersenyum tipis. Tiba-tiba ia merasa malu karena teringat dua kali ia pernah berjanji untuk pulang tapi tak pernah jadi. Pertama, saat kakak perempuannya menikah. Kedua, ketika neneknya sakit lalu meninggal. Setelah itu, ia seolah ditelan tanah rantau, nyaris tak pernah berkabar ke rumah. Diperhatikannya ibunya menuang arak dari botol bekas sirup ke tiga cawan kecil di atas meja sembahyang. Perempuan itu kemudian merobek sebungkus dupa merah, dan membakarnya pada lilin besar di sisi kiri
meja. Tiga buah kaleng bekas susu bubuk yang dililit kertas merah berisi pasir diletakkan bersusun di tepi meja. Tiga lembar kertas merah bertulisan China yang masing-masing ditempel pada dua batang dupa tertancap pada setiap kaleng. Ia tak bisa membaca hanji -meskipun pernah diajari- tapi ia tahu mana nama bapaknya, kakek, dan neneknya. "Sembahyanglah! Kabari papamu kalau kau pulang!" kata perempuan itu sambil mengulurkan sejumlah dupa berasap kepadanya. Ia menerima dengan begitu bimbang. Dengan canggung ia memegang dupa itu dengan kedua tangannya di depan meja. Dan, semakin ragu ketika menatap beragam buah, kue, dan daging yang tertata dalam piring-piring di atas meja. Akhirnya, dengan setengah hati, ia menuruti juga keinginan ibunya. Ia bersin berulang kali oleh asap dupa yang tajam menyengat. Padahal, dulu, aroma dupa itu begitu harum bagi hidungnya. Ia hanya menggerakgerakkan kedua tangannya yang memegang dupa di depan dada sekadarnya dengan mulut terkatup, tanpa mengucapkan sepatah doa pun. Dulu, ibunya, juga nenek, selalu saja mengajarinya berdoa panjang-lebar setiap kali sembahyang. Ia merasa tak ada yang harus dipanjatkan, tak ada kata-kata yang mesti diucapkan untuk masa lalu. Orangorang yang telah pergi itu cukuplah menjadi hantu di dalam kenangan. Sekadar hantu, yang kadangkadang membuat kita terharu -atau sakit-oleh beragam peristiwa yang telah lewat. Demikian ia berpikir ketika menancapkan dupa di kaleng. Sampai tiba- tiba ia menangkap bayangan bangku beton itu lewat ambang pintu dapur yang terbuka lebar. *** Lelaki itu seharusnya bisa memilihuntuk melupakan masa silamnya. Seharusnya. Tetapi lelaki itu memilih mengawetkannya, bahkan kemudian menjemput masa silam itu. Ia tahu alangkah sulit bagi lelaki itu untuk menjatuhkan pilihan. Ia selalu yakin lelaki itu seorang yang cukup bijak. Tapi ketika lelaki itu akhirnya memilih tidak seperti yang ia harapkan, kekecewaan tak mampu ia pendam. Ia memang menghargai pilihan lelaki itu, meskipun sejak itu dendam perlahan mulai tumbuh di dadanya, menggerogoti hatinya. Barangkali seperti lumut yang kini melapisi bangku beton di hadapannya, pikirnya sedikit sinis. Ia ingat, bermalam-malam ibunya menangis. Cuma menangis. Tak ada keributan di rumah. Semua berjalan seperti biasa. Hanya saja, kemudian lelaki itu semakin sering keluar rumah, mulai jarang duduk-duduk di bangku beton itu sambil memainkan harmonika atau membaca. Meskipun setiap kali pergi, lelaki itu selalu saja pulang, kadang menjelang dini hari. Dan ibunya tetap setia membukakan pintu. Ia tidak tahu apa yang salah. Apakah ia memang pantas membenci lelaki itu. Yang pasti, ia mulai jarang bicara dengan lelaki itu. Lebih sering menghindar bila berpapasan. Tak ada makan malam bersama, tak ada latihan wushu, atau acara pergi memancing berdua ke pelabuhan. Hubungan mereka jadi aneh. Serba canggung. Richard Clayderman menghilang. "Papamu tidak salah, Nak. Mamalah yang merebutnya dari perempuan itu...."Ada senyum tipis di wajah ibunya. Mama tidak sakit kok! Papamu akan tetap bersama kita. Mama bisa mengerti dia. Sederetan kalimat meluncur lancar, senyum di wajah ibunya merebak lebih lebar. Tapi ia melihat luka menganga yang sia-sia disembunyikan itu, di dalam bola mata ibunya. Mata yang indah, meski sedikit sayu. Mirip dengan mata Natalia. Ah! Ibunya kemudian menuturkan sebuah cerita, nyaris seperti dongeng-dongeng yang suka dikisahkan perempuan itu waktu ia masih kecil. Tentang seorang lelaki yang jatuh cinta pada seorang gadis penyanyi di sebuah bar. Seorang biduan yang manis. Ah, tidak, Nak, itu bukan pertemuan mereka yang pertama. Perempuan itu sesungguhnya bersama dari masa lalu si lelaki. Masa kecil yang hilang. Saat itu, si lelaki masih seorang mahasiswa tingkat akhir yang mencari tambahan uang saku dengan menjadi pianis di sejumlah bar. Ia begitu bahagia menemukan biduan itu, yang selalu dikenangnya sebagai seorang gadis cilik berkepang dua. Diajaknya perempuan itu pulang ke kampung halaman. "Tapi aku tidak punya rumah dan siapa-siapa lagi di sana?" kata perempuan itu bimbang. Lelaki itu tergetar
oleh sepasang matanya yang begitu sunyi, "Tapi ada aku. Aku akan membawamu kepada orang tuaku." Biduan manis itu hanya tersenyum sipu, senyum yang tak kentara maknanya. Toh, itu sudah cukup membuat lelaki itu berbunga-bunga. Namun, kampung halaman ternyata bukan lagi tempat yang ramah untuk menerima si perempuan, juga rumah lelaki itu. Wajah kedua orang tuanya, suami-istri pemilik toko kelontong, begitu masam ketika menerima jabatan tangan si biduan. "Kau tahu, perempuan apa yang kau bawa kemari?!" Suara bapaknya cukup keras di tengah malam, "Kau bahkan tak tahu siapa orang tuanya kan?!" Lelaki itu balas menatap bapaknya lekat-lekat, tak gentar. Ia tak peduli siapa perempuannya, siapa orang tua perempuan itu sebagaimana yang diceritakan bapaknya. Ia juga tak peduli pada peristiwa besar yang pernah terjadi di kota kecilnya, juga seluruh negeri. Sebuah peristiwa politik yang kelabu. Tahun gelap yang kemudian tercatat penuh dusta di buku sejarah anak-anak sekolah. "Aku mencintainya!" Si lelaki menjadi garang. Kedua matanya berapi-api. Tapi perempuan itu sudah lenyap keesokan pagi. Lenyap. Tanpa meninggalkan pesan apa pun. Lelaki itu menangis, ia kehilangan untuk yang kedua kali. *** IA tidak tahu kenapa perempuan itu kembali. Apa keinginannya. Ia mengenal Natalia ketika gadis berkulit kuning langsat dengan rambut potongan poni itu pindah ke sekolahnya. Berwajah polos tapi sensual. Ia diam-diam suka mencuri pandang pada gadis itu ketika pelajaran sedang berlangsung dengan dada yang sedikit berdebar. Tapi gadis itu jinak-jinak merpati. Menjauh kalau didekati, mendekat ketika ia menjauh. Toh, justru membuat ia makin penasaran dan bersemangat mendekati gadis itu. Sampai kemudian ia melihat sebuah luka. Luka yang begitu muram di kedua mata Natalia yang sayu... Dan, ia bertemu perempuan itu, perempuan yang fotonya dulu pernah ia temukan di laci meja baca bapaknya. Waktu itu ia kelas enam SD. Ibunya buru-buru merebut foto itu dari tangannya dan memasukkan kembali ke laci, sekaligus mengunci laci itu. "Jangan lancang, Nak! Jangan ganggu barang-barang di laci itu!" Ibunya bergegas menariknya keluar dari ruang baca yang merangkap perpustakaan kecil. "Siapa perempuan di foto itu, Ma?" tanyanya. Namun ia tidak pernah mendapat jawaban. "Jangan masuk lagi ke ruang baca Papa!" Lelaki itu menatapnya tajam dengan wajah agak merah. Ia buruburu menunduk. Belum pernah lelaki itu bersuara keras padanya. Sejak itu ruang baca selalu terkunci rapat, namun wajah perempuan cantik di dalam foto itu tak pernah pudar dari ingatannya. "Aku bertemu dengan perempuan dalam foto Papa...," katanya sore itu sepulang dari rumah Natalia. Gadis itu memang tidak pernah mau mengatakan padanya tinggal di mana, tetapi siang itu sepulang sekolah ia diamdiam menguntit Natalia. Dan perempuan itu ada di sana, mempersilahkannya masuk dan menghidangkan untuknya secangkir teh. Ia sama sekali lupa apa tujuannya datang ke sana, pun ketika Natalia mempersilahkan minum. Mereka duduk berhadapan dengan begitu kaku. "Aku bertemu dengannya, Ma," ia mengulangi sekali lagi. Dilihatnya wajah ibunya berangsur-angsur berubah pucat. Tertegun menatapnya. *** ENTAH telah berapa tahun, bangku beton itu tinggal sepi. Sudah belasan tahun agaknya. Setelah semuanya berlangsung, sesekali lelaki itu memang masih duduk-duduk di sana, tapi tidak bermain harmonika atau membaca. Dia hanya duduk termangu di sana, dengan raut wajah yang kadangkala tampak kosong. Mereka tidak pernah lagi bicara. Badan kekar lelaki itu kian hari semakin susut, tampak rapuh. Asam urat, iritasi lambung, ada masalah dengan ginjal dan lever. Malarianya juga sering kambuh, kata ibunya terisak. Entah
dari mana segala penyakit itu datang, barangkali akibat waktu muda papamu terlalu banyak mengonsumsi alkohol. Dia dulu peminum? Tanyanya, tapi cuma di dalam hati. Lelaki itu meninggal ketika ia hampir tamat SMA. Ibu dan kakaknya menangis berhari-hari tapi ia tidak. Ia hanya menatap jenazah lelaki itu dimasukkan ke peti mati dengan perasaan yang ia sendiri tak bisa jelaskan sepenuhnya. Pandangan matanya seperti berkabut. Perempuan itu datang ke pemakaman bersama Natalia, keduanya mengenakan pakaian serbaputih seperti halnya ia, ibu, dan kakak perempuannya. Tetapi mereka tidak saling bertegur sapa. Tak lama setelah itu, ia pergi meninggalkan rumah, meninggalkan pulau kecil itu, dan tak pernah pulang sekali pun... "Mama harap kau mau pulang. Kakakmu sedang dalam masalah. Toko bangkrut. Kakak iparmu entah di mana sekarang. Hampir tiap hari selalu saja ada orang datang menagih hutang, tambang-tambang itu benarbenar menguras seluruh uang kakak iparmu!" Itu kata-kata ibunya dalam telepon beberapa hari lalu. Ia tak menyangka kalau akan tiba di rumah tepat pada hari sembahyang arwah Chit Ngiat Pan... yang kusam dan berlumut itu, ketika namanya dipanggil. Menoleh, ia melihat kakak perempuannya sedang berjalan mendatanginya. Wajah Ai Ling tampak tirus dan kusut, lebih tua dari usia yang sebenarnya. Begitu berbeda dengan sosok gadis manis dan periang yang dikenalnya bertahun-tahun lalu. Ibunya masih berdiri di pintu dapur. Ah, tiba-tiba ia merasa ingin sekali bermain harmonika, memainkan Les Premiers Sourires de Venessa dan lagu-lagu lainnya... *** Gaten, Yogyakarta, Mei 2007 /kenang-kenangan buat bapak
Gadis Bunga Cerpen Sunlie Thomas Alexander Dimuat di Jawa Pos 06/03/2007 Telah Disimak 1330 kali AKU bayangkan kau sekuntum bunga. Hanya bunga yang selalu dihinggapi oleh kupukupu, sebagai takdirnya. Jangan protes lagi. Aku yakin kau memang secantik bunga. Mungkin Mawar, Melati, Anggrek, atau Calla. Ah, aku lebih suka bunga yang terakhir. Bukan hanya karena di mataku bunga itu tampak lebih cantik dari bunga lain, tetapi Calla selalu saja mengingatkanku pada sebuah film Korea. Dan film itu mengingatkanku pula pada seseorang, lantaran perjumpaan kami yang begitu mirip dengan sebuah adegan dalam film tersebut.
Namun kau lebih suka bunga Sedap Malam. Bunga itu menghiasi kamarmu dalam sebentuk lukisan cat minyak, katamu. Eh, kau bisa melukis kan? Aku pingin punya lukisan Sedap Malam satu lagi? Bikinkan untukku ya? Pintamu sambil tertawa.
Kau pernah marah dan menegurku lewat SMS-SMS yang meradang agar aku berhenti berimajinasi tentang dirimu. Sebab, menurutmu, imajinasi suka menyesatkan dan kau takut aku akan kecewa setelah menemukan kenyataan tidak seperti yang aku bayangkan. "Aku tidak secantik imajinasimu!" Gerutumu kesal. Tetapi, aku tak bisa berhenti berimajinasi tentangmu. Aku telah terobsesi pada tatto kupu-kupu, yang katamu, ada di lehermu itu. Maka kubayangkan kau bagai sekuntum Calla, tentu dengan leher yang jenjang seperti tangkai Calla yang panjang. Dan, kupu-kupu itu tampak mengepakkepakkan sayapnya yang indah di lehermu, sebelum akhirnya hinggap di ujung hidungmu yang bangir. Sungguh menggemaskan.
Film Korea itu kutonton malam hari, sendirian di kamar kontrakan, dan aku berjumpa dengan seseorang itu keesokan paginya dalam perjalanan bis ke kantor. Persis cerita dalam film Korea tersebut. Tentu, aku takjub. Bagaimana mungkin ada kejadian yang begitu mirip? Adakah memang kebetulan semacam ini di dunia? Atau aku yang terlampau melebih-lebihkannya? Yang pasti, seperti adegan dalam film, kami bertabrakan di dalam bis yang sarat penumpang, dan aku bergegas minta maaf. Ia tersipu dan aku terperangah. Untuk beberapa saat kami saling bertatapan lalu sama membuang muka. Aku pura-pura melemparkan pandang ke luar jendela bis yang kusam dengan jengah tapi diam-diam melirik. Aku tahu, ia sama gelisahnya dari sepasang matanya yang bening?
Bis kota yang kami tumpangi terus merayap, bagai merangkak di tengah lalu lintas pagi hari yang padat. Berkali-kali mata kami kembali bertemu untuk kembali terburunya menghindar. Kutangkap rona memerah di wajahnya, dan rasa gelisah --oh, gelisah yang nikmat itu-- di dadaku semakin kentara. Aku ingin sekali menyapanya, mungkin sekadar menanyakan nama, kerja di mana, atau bisa minta nomor teleponmu? Atau lebih jauh lagi. Tapi tiada sepatah kata pun yang sanggup terucap dari mulutku. Semua kata, semua kalimat seolah bersepakat membuat kubangan di dalam kepalaku.
Dan untuk saat-saat seperti ini, kau tahu, waktu selalu saja terlalu bergegas! Ia turun dua blok *** SEBAGAIMANA sudah bisa kauduga, sejak itu, tokoh utama dalam film Korea yang kutonton tersebut terus terbayang pada perjumpaannya yang terlampau ringkas dengan gadis dalam bis kota. Wajah gadis itu dengan lirikan ekor mata yang sedikit nakal namun gugup serta rona memerah di pipi yang begitu manis, mulai menempati sebuah bilik yang cukup luas dalam batok kepalanya, menciptakan siang dan malam yang mulai berbeda untuknya. Tak di kantor, di rumah kontrakan, di jalan, atau di mana saja ia berada. Terkadang sedikit mengganggu kesibukannya. sebelum kantorku. Begitu tergesa dan tanpa berpaling.
Tentu, setiap pagi ia selalu naik bis yang sama ke kantor --meski mobilnya telah keluar dari bengkel-- tapi tak pernah lagi ia bersua dengan gadis itu. Ai, gadis itu seperti lenyap tak berjejak. Walau setiap jam istirahat siang, setiapkali pulang lebih cepat dari jam kantor, ia senantiasa menyempatkan diri menelusuri setiap blok perkantoran dan pertokoan di sekitar kantornya, menyusuri setiap ruas jalan hingga ke beberapa gang kecil. Berharap akan menemukan gadis itu di suatu tempat.
Hingga suatu pagi, ia menemukan setangkai bunga Calla tergeletak di atas meja kantornya. Hanya setangkai Calla, tanpa disertai kartu ucapan atau pesan apa pun.
"Dari gadis itu?" Usikmu di ponsel. Ah, bersabarlah, dengarkan dulu ceritaku sampai selesai. Tokoh utama film Korea itu pun menduga hal yang sama denganmu, mungkin tepatnya berharap seperti itu. Ia sempat bertanya sana-sini, ke hampir semua pegawai kantor. Tetapi tak seorang pun yang tahu perihal bunga tersebut. Sampai kemudian ia mendengar dari seorang satpam, kalau pagi-pagi sekali seorang bocah laki-laki mengantarkan bunga tersebut saat satpam itu sedang membuka pintu kantor. Selanjutnya setiap pagi, ia selalu menerima setangkai Calla yang serupa. Selalu bocah lelaki itu yang mengantar, kata satpam. Tetap tanpa pesan, selain bunga itu untuknya.
Karena penasaran, satu pagi ia memutuskan datang lebih awal. Dan, benar kata satpam, ia bertemu dengan bocah lelaki pengantar bunga itu?
Kau menahan nafas di seberang. Membuatnya iseng menahan cerita untuk beberapa jenak, ingin menikmati rasa penasaran dan keteganganmu.
"Saya diupah oleh pegawai toko bunga tak jauh dari sini mengantarkannya untuk Tuan," jawab bocah lelaki itu. Selebihnya bocah itu hanya menggeleng. Ia mendesah kecewa, namun diputuskannya untuk mencari toko bunga itu.
Tiba-tiba kau tertawa keras di ponsel. Begitu keras hingga aku buru-buru menjauhkan ponsel dari telinga.
"Ada apa?" tanyaku polos meski agaknya sudah dapat menebak apa yang membuatmu tertawa. Dan benar saja dugaanku, kau tertawa membayangkan diriku berkhayal jadi tokoh utama film Korea itu. Ah, kalau saja kau tahu, bagaimana aku selalu mengangankan seluruh adegan dalam film itu berulang padaku, tentu dalam versi happy ending. Terkadang aku ingin menertawakan diriku habis-habisan, menertawakan segala kekonyolan yang kuperbuat meskipun kerapkali aku begitu menikmati peranku sebagai tokoh utama film Korea itu. Sayangnya, tidak seperti tokoh utama film tersebut, aku tidak berhasil menemukan seseorang itu di sebuah toko bunga kecil yang agak tersembunyi di sudut jalan. Terang saja, karena tak sekuntum pun bunga yang pernah tergeletak di atas meja *** AKU memanggilmu gadis bunga, sebagaimana tokoh utama film Korea tersebut menjuluki gadis idamannya yang akhirnya ditemukannya di toko bunga kecil itu. Seharusnya panggilan itu memang untuk gadis yang bertabrakan denganku di dalam bis. Tapi ia sungguh raib ditelan waktu. Tidak seperti gadis Korea penjual bunga. Teman-teman sekantorku mengejekku habis-habisan. kantorku!
Maka, kepadamulah akhirnya panggilan itu kutujukan. Jangan protes, sebab hanya sekuntum bunga yang senantiasa dihinggapi oleh kupu-kupu. Ya, kupu-kupu yang katamu telah lama menghiasi lehermu. Sejak itu, aku terus menghujanimu dengan SMS-SMS yang kadang kelewat melankoli, sesekali meneleponmu.
"Kau akan kecewa," tukasmu jengkel, "Aku sama sekali tidak seperti gadis idamanmu itu. Kau bersikap tak adil padaku." Suaramu ketus. Aku hanya tertawa getir. Lalu memintamu mengirimkan selembar fotomu padaku lewat pos atau e-mail, itu kalau kau berkenan. Agar aku berhenti berimajinasi, kataku. Sungguh, aku merasa tak mampu mengekang laju imajinasiku, terlebih setiapkali membayangkan kupu-kupu itu mengepak-kepakkan sayap di lehermu. Dan, kau benar, mungkin aku memang telah berbuat tak adil padamu. Setiapkali mencoba membayangkan dirimu, kepalaku selalu saja dipenuhi oleh bayangan gadis itu. Barangkali lebih tepat kalau dikatakan aku membayangkan dirimu sebagai dia, daripada sepenuhnya berimajinasi tentang sosokmu. Maaf.
Kapan kita bisa bertemu? Mungkin di suatu tempat yang kau suka? Di sebuah kafe kecil barangkali? Atau di pantai? Di mana aku bisa sepuasnya menyaksikan kupu-kupu itu mengepak-kepakkan sayapnya di lehermu sambil menikmati secangkir teh hangat. Aku ingin sekali mengunjungimu di Kota Kembang. Kalau saja pekerjaan kantorku tidak selalu menumpuk dan keluargaku tidak semena-mena merampas sisa waktuku. Bukankah kau telah berjanji menjadi guide bagiku? Kita bisa jalan-jalan di Braga, atau kau lebih suka nongkrong *** KAU akan tiba sebentar lagi dengan kereta senja, dan kumasuki stasiun dengan degup di dada yang tak berirama. Hujan melebar, tempiasnya membasahi kaki celanaku. Orangorang berlarian dan berteduh, barangkali di dalam hati mengutuk hujan yang celaka. Padahal betapa hujan selalu menyegarkan di mataku. Di mana-mana payung bermekaran, serupa kelopak bunga beraneka warna. Semarak dan indah. di Dago?
Hujan awal November. Entahlah, di awal musim, selalu saja aku merasa memperoleh
semangat baru, seperti rumput-rumput kering meranggas yang dihijaukan oleh hujan. Meski kini aku sedikit menggigit cemas.
Aku sudah tak sabar lagi menunggu kereta yang membawamu tiba, seperti juga aku tak lagi sabar untuk melihat sosokmu, tak lagi sabar menyaksikan kupu-kupu yang mengepakkepakkan sayap di lehermu dan tak lagi sabar mengakhiri cerita film Korea itu untukmu. Sengaja memang aku menyimpan akhir cerita hingga kau datang. Aku hanya ingin mengakhiri cerita itu di depanmu, agar aku dapat merasakan keteganganmu lebih dekat. Adakah kau marah, kesal, atau justru senang?
Mungkin nanti kau bakal kecewa, seperti halnya diriku ketika film Korea itu ternyata berakhir menyedihkan.
Keretamu belum tiba juga. Rasanya demikian lama. Tetapi aku berusaha menikmati penantianku, layaknya tokoh utama film Korea itu menikmati segenap upayanya mencari gadis idamannya, sebelum kemudian menemukan gadis itu di sebuah toko bunga kecil yang agak tersembunyi di sudut jalan.
Toko bunga itu ditemukannya tak sengaja setelah sekian lama mencari. Saat itu ia baru keluar dari hotel tempat ia bertemu dengan seorang klien, ketika gerimis mendadak jatuh. Ia baru saja berpikir hendak kembali ke hotel, kalau matanya tidak keburu menangkap bayangan bunga-bunga beragam warna. Sebuah toko bunga kecil yang meriah, dengan potpot bunga tertata rapi di teras, sebagian bergantungan. Toko bunga kecil itu berada tepat di seberang hotel, agak tersembunyi di pojok jalan, diapit butik batik dan sebuah swalayan cukup besar. Ia tertegun dengan jantung berdebar kencang. Kemudian, tanpa menghiraukan lagi gerimis yang melebar, ia segera berlari menyeberang jalan, sambil merutuk habishabisan kenapa tidak pernah menyadari keberadaan toko bunga itu padahal cukup sering ia keluar-masuk hotel yang baru ditinggalkannya.
Gadis itu ternyata ada di sana! Agak terkejut ketika melihat kedatangannya, tetapi segera menyambutnya dengan riang dan ramah.
"Ada yang bisa saya bantu, Tuan?" tanya gadis itu sambil tersenyum. Ia hanya terpaku dan merasa tubuhnya mendadak menjelma jadi manekin sebagaimana yang ada di butik sebelah toko Aku tak ingin seperti itu di depanmu bunga. nantinya?
Hujan tercurah semakin deras. Aku mengetuk-ketukkan ujung payungku dengan sedikit jengkel ke lantai peron. Sebuah kereta baru saja memasuki stasiun beberapa menit yang lalu, namun bukan dari jurusan kotamu. Kau naik kereta apa sih? Aku mencoba menghubungi ponselmu, tetapi lagi-lagi masuk ke mailbox. Kenapa mematikan ponsel? Takut kecopetan atau ditodong dalam kereta? Atau jangan-jangan kau tak jadi datang? Kau hanya mempermainkanku? Padahal sebelum aku sampai ke stasiun ini, kita masih sempat bercakap-cakap lumayan lama.
Peron kian gerah dengan orang-orang yang berdesakan. Maklum akhir pekan. Kembali terdengar suara pluit melengking. Keras dan panjang. Lalu disusul pengumuman dari pengeras suara: sebuah kereta dari jurusan kotamu sedang memasuki stasiun. Aku berpaling dengan tegang, dan hujan kian menjadi. Kurasa keringat dingin membasahi sekujur Belinyu-Yogyakarta, : buat Dian Hartati? tubuhku.*** 2006-2007
Hikayat Kuda Api Cerpen Sunlie Thomas Alexander Dimuat di Pikiran Rakyat 01/06/2007 Telah Disimak 11251 kali
MASIH banyak orang yang diam-diam mencari kuda api. Aku tahu itu. Mereka bergerak seperti bayangan, bersilangan di tembok-tembok. Saling bercuriga dan tentu, rapat menyimpan rahasia. Siapa saja mereka? Di antara mereka sendiri pun, barangkali, tak saling mengenal selain hanya menduga-duga. Ah, kuda api, kuda sihiran! Kuda pejantan
itu, konon, seluruh bulunya berwarna merah laksana api menyala, dengan sulai bagai terbakar.... "Setiapkali kuda api lewat," kata engkong, "Seolah tercipta puting beliung." Aku terpukau dan mencoba membayangkannya. Meski kata engkong, kuda itu terlampau cepat. Nyaris tak seorang pun dapat melihatnya dengan jelas. Ia selalu lewat bagaikan angin, sehingga hanya kelebat bayangan merahnya saja yang tertangkap mata. Ah, sebenarnya hikayat ini telah lama berkembang di kampung kami, dan tampaknya tak seorang pun yang masih memedulikan. Ia ibarat cerita yang sudah basi, setelah turuntemurun dikisahkan. Meski tetap saja mengendap. Mungkin hanya engkong yang masih setia menumbuhkannya di kepalaku hampir setiap malam sebelum tidur. Seolah beliau punya kewajiban memelihara hikayat itu, dan berkewajiban pula menumbuhkannya dalam kepalaku. Entah berapa ribu kali sudah, beliau berkisah tentang kuda merah itu. Dengan suaranya yang serak namun teratur, engkong seakan hendak menghadirkan kuda mestika itu dari negeri antahberantah. Dan antara kantuk dan terjaga, aku seolah dapat mendengar derap ladam kuda itu memalu tanah, juga sambaran angin keras dari tubuhnya yang berkelebat laksana anak panah terlepas dari busur. Melesat entah ke mana. Hanya bayangan merah, ya, bayangan merah. Kian mengabur dari pelupuk mataku yang berat bersama suara derap kakinya yang menjauh. Sebelum tertidur lelap, aku masih sempat membayangkan debudebu yang mengepul. Dan aku bermimpi melihat kuda itu. Begitu gagah di atas tebing cadas yang menghadap ke laut, sementara langit bulan lengkung. Si kuda api, dengan tubuh laksana api menyala, meringkik keras sambil mengangkat kedua kaki depannya tinggi-tinggi. Ringkikan yang penuh luka, penuh resah. Terasa mendirikan bulu roma. ** SEPASANG mata lelaki tua bersorban putih itu tampak begitu gelisah di bawah remang nyala obor. Entah sudah berapa lama ia mondar-mandir di halaman surau kecil di tepi hutan itu. Sesekali ia mendongakkan kepalanya ke langit malam yang buram, lalu mengelus-elus janggutnya yang separuh warna. Sementara tangan kanannya yang mengenggam tasbih bergerak tiada henti. "Sudah lewat sepertiga malam, Guru," salah seorang dari dua lelaki muda yang sedari awal hanya diam di bawah rindang sebatang rambutan, tiba-tiba bersuara. Lelaki tua bersorban tidak menjawab, hanya terus mondar-mandir sambil menghitung biji tasbihnya. Lelaki muda bertubuh ceking yang bicara jadi salah tingkah. Angin berembus sedikit kencang, membuat daun-daun pepohonan mendesau. Lelaki muda ceking itu menggigil kedinginan, "Guru...." "Diamlah, Pengkin!" hardik lelaki tua bersorban melirik tajam. Wajahnya tampak semakin gelisah di antara liukan api obor bambu yang tertancap di halaman surau. Malam semakin hening, terasa mencekik. Tak terdengar suara jangkrik atau kodok. Lelaki tua bersorban kembali mendongak ke langit, mendesah kecewa karena apa yang ditunggunya belum juga muncul. Langit nyaris tertutup mendung, hanya beberapa bintang berkerdip lemah.
"Guru...," akhirnya lelaki muda yang satu lagi memberanikan diri bersuara, tentu dengan hati-hati, "Apa kita akan tetap menunggu, bagaimana kalau...," ucapannya berhenti, matanya tak kalah gelisah. "Kita tunggu sebentar lagi, Indra," tukas lelaki tua bersorban tegas. Indra cuma mengangguk. Ketiganya kembali terdiam. Angin kali ini seolah membeku, pohon-pohon tegak kaku bagaikan makhluk-makhluk asing yang sedang berjaga. "Guru! Lihat!" tiba-tiba Pengkin berteriak sambil menunjuk ke arah langit. Lelaki tua bersorban dan Indra seketika mendongak. Ada senyum kecut yang memanjang di wajah keriput lelaki tua bersorban, buru-buru ia memasukkan tasbih ke kantong jubah hijaunya. Mulutnya berkomat-kamit entah mengucapkan kalimat apa. "Mana patung kudanya?" tanyanya agak tersengal sambil mengulurkan tangan pada Pengkin. Bergegas lelaki ceking itu membuka buntalan kain yang selalu disandangnya. Tangan Pengkin sedikit gemetar ketika mengeluarkan benda dari dalam buntalan itu. Sebentuk patung kuda dari kayu berukuran sejengkal, berwarna merah tersembul dari balik kain. Segera diulurkannya patung kuda tersebut kepada lelaki tua bersorban yang menerimanya dengan cepat. Masih berkomat-kamit, lelaki tua bersorban meletakkan patung itu dengan hati-hati di depan kakinya. "Ingat, apa yang terjadi malam ini adalah rahasia kita bertiga. Jangan pernah sesekali kalian ceritakan kepada siapa pun, atau kita semua akan celaka. Terlebih rahasia mantranya." Lelaki tua bersorban menatap kedua muridnya dengan wajah tegang, suaranya dalam seperti mengancam. Wajah Pengkin dan Indra ikut tegang. Keduanya mengangguk kaku. Lelaki tua bersorban kembali mendongak ke langit. Bulan sabit tampak berkilau keperakan. Indah namun terasa mencekam. Lelaki tua itu mengangkat kedua tangannya, tengadah seperti berdoa. Cukup lama, sebelum akhirnya perlahan kedua telapak tangannya dibalikkan menghadap patung kuda yang terletak di atas tanah di depan kakinya. Aku mendengar lelaki tua itu mengucapkan "bismillah" lalu serentetan kalimat cepat yang tak kupahami meluncur dari bibirnya. "Kemarikan obor!" teriaknya. Dan aku terbangun dengan sekujur tubuh banjir keringat. Kulihat dipan di sampingku kosong, engkong tak ada. Ah, ke mana engkong? Kedua mataku masih terasa berat, tapi aku kepingin kencing. ** KAU memanggil kuda itu "Sapar Maulana". Entahlah, dalam mimpimu yang ke berapa kau pernah mendengar nama itu disebutkan. Oleh siapa dan di mana tempatnya, kau barangkali lupa. Tapi kau seakan begitu yakin, kuda itu memang diciptakan pada bulan Sapar, ketika bulan sabit yang muram tampak begitu anggun sekaligus menakutkan di atas langit. Didahului lafadz "bismillah", kau membacakan mantra penjinak yang entah sejak kapan kau ingat di luar sadar. Kuda merah itu meringkik keras. Semak-semak tersibak oleh angin kencang tatkala kuda itu menderu ke arahmu. Sejenak air mukamu mengeras, matamu terbelalak, mungkin antara takjub dan takut. Tapi ketika kuda merah itu sampai di hadapanmu, dengan sigap kau melompat. Hup! Hup! Hiiyaaaa...! Dengan tangkas dan
ringan, kau melompat ke atas punggungnya yang menyala dan menyambar sulainya yang terbakar. Hiiiyaaaaa...! Kau segera menggebrak si kuda api, kedua kakinya terangkat dan ringkikan keras melengking dari moncongnya sebelum akhirnya melesat ke depan laksana anak panah. Menerobos semak belukar dan pepohonan. Aku tertegun. Tak percaya kau begitu gagah, bagaikan Indra yang menderu ke medan laga dengan golok batu di tangan kanan, mata yang bernyala-nyala dan wajah bercahaya terbasuh air wudhu. Ada gema azan isya yang sumbang mengasah ringkik si kuda api, dan aku seakan kembali melihat orang-orang kafir putih dan para pengkhianat yang kocarkacir, bertumbangan tersambar tajam golok batu atau terdepak kaki si kuda api. Tubuhtubuh terlempar. Warna merah berhamburan di atas semak belukar, warna darah dan api yang saling berbelit. "Kuda api kuda sihiran! Bawalah aku kepada musuhku-musuhku, kita tumpas semua iblis penenung tanah moyang! Merajah siang, mendepak malam!" Indra berteriak lantang. Ah, seperti yang telah lama tersurat, setiap kali golok batu ditebaskan, sesosok tubuh akan roboh bersimbah darah. Dan kuda api menjelma kuda sedeng, melesat kian-kemari bagai mata panah mencari mangsa. Berkelebat bagaikan bayangan, bagaikan deru angin. Panjipanji perang terbakar di tengah padang semak samun. Pedang, golok, tombak, cambuk terus bersilangan, seperti berkejaran dengan rakaat Salat Isya. Kulihat Indra terus mendesak ke depan kepungan orang-orang kafir putih dan para pengkhianat. Pelor-pelor yang beterbangan dikibasnya dengan sekali putaran golok batu, cukup setengah lingkaran. Wajahnya terang bagaikan purnama. Ya, sebagaimana nujuman sang guru, setiap kali kuda api mendengus, satu nyawa dipastikan melayang. Tapi aku melihat satu sosok yang tak asing menyelinap di tengah barisan musuh. Wajahnya pucat bagai tak berdarah. Ya, kukenali sosok itu sebagai Pengkin. Tubuhnya tampak jelas gemetar di atas punggung kuda hitam ketika merapat ke kuda pimpinan orang kafir putih yang berwajah tak kalah pucat. Entahlah apa yang dibisikkan, malam terlalu gaduh oleh denting logam beradu dan letupan pelor. Ketika kuda hitamnya melesat ke depan barisan, Pengkin kian gemetaran. Salah seorang pengkhianat mengulurkan obor padanya yang disambut dengan gugup. Kutahu, Indra bakal menarik tali kuda api. Kutahu betul! Kuda api meringkik keras dan mengangkat kedua kaki depannya ke atas. "Kau!" Indra mendesis kaget. Pengkin masih gemetar di atas punggung kuda. Keduanya bertatapan. Wajah terkejut Indra perlahan-lahan berubah merah, semakin merah di bawah terang purnama lima belas dan nyala puluhan obor. Tangan kirinya terlihat kejang pada kekang. Keheningan menjadi sempurna. Puluhan obor meliuk gelisah. Kulihat tangan kanan Indra yang mengenggam golok batu bergetar. Tiba-tiba Pengkin kembali menggebrak kudanya maju sambil berteriak garang. Tangan kanan Indra bergetar keras, tapi kulihat kebimbangan bersarang di sepasang matanya yang kelam. "Kuda api, kuda sihiran! Dari kayu kembali ke kayu, dari api kembali ke api! Bila ini mantra tak cukup mengantar kau pada moksa, pergilah kau ke dunia hikayat yang tak kasat mata!" sembari mengangkat obor di tangan kanannya tinggi-tinggi, Pengkin berseru lantang. Lalu.... Bla, bla, bla, bla, bla, blaaa...! Sederetan kalimat meluncur deras dari mulutnya, tak terpahami.
Kuda api meringkik keras, meraung. Sekujur tubuhnya laksana dikobari api dahsyat. Di atas pelana, Indra berteriak. Tubuh lelaki muda itu terjungkal dari punggung kuda. Semua orang ikut berteriak demi menyaksikan bagaimana si kuda api berputar laksana gasing. Angin berpusing bagaikan beliung. Tubuh-tubuh terlempar ke udara, semak-semak tercabut, batu-batu berhamburan, pohon-pohon tumbang. Lalu purnama lima belas Ramadan sehening kuburan.... Tapi kau bukan Indra, Cucuku! Aku tahu hatimu tak pernah bimbang. Aku yakin, kau akan tetap menggebrak si kuda api mendepak maju menjemput kematian musuh! Kau telah menyaksikan dalam mimpi-mimpimu, bagaimana kuda api menghilang ke dunia hikayat, golok batu patah berdentang di atas batu hitam, dan Indra, pendekar yang bimbang, mati dengan dua belas lubang pelor di tubuhnya. Kunujum kau jadi satria kelana pembawa nubuat lama yang tak kenal bimbang, Cucuku! ** SEPERTI yang telah aku katakan, hikayat itu telah lama berkembang di kampung kami. Telah lama sekali, sehingga tampaknya tak seorang pun yang masih mau menggubrisnya, berkenan meluangkan waktu untuk menuturkan dan menyimaknya. Lagipula, hikayat dan dongeng-dongeng baru terus saja berlahiran. Lebih canggih dan lebih menarik. Tentu, siapa lagi yang mau mengisahkan dan mendengar sebuah cerita lama yang tokoh utamanya jadi pecundang! Barangkali hanya kami berdua, engkong yang terus menuturkannya berulangulang, dan aku yang selalu bersedia mendengarkan. Namun tidak! Aku tahu, tidaklah benar jika hanya kami berdua yang masih menjaga dan menghidupkan kisah. Ya, aku tahu, diam-diam, banyak orang yang masih terus berusaha mencari si kuda api yang lenyap ke dalam hikayat --tatkala mantra sakti diucapkan Pengkin di malam purnama lima belas Ramadhan-- itu. Masih banyak orang. Mereka berseliweran seperti bayangan yang tak kentara di tembok-tembok, di antara rapat pepohonan. Waspada dan penuh rahasia. Karena syahdan, sebagaimana cerita engkong, suatu hari si kuda api akan kembali dan siapa pun yang memilikinya akan mendapatkan kedigdayaan. "Tetapi hanya seorang yang telah ditakdirkan berjodoh dengannya, mampu memanggil si kuda api kembali dari alam hikayat," tukas engkong, "Seorang yang bersedia merawat hikayatnya dan tak bimbang seperti Indra. Seorang yang mampu mengucapkan mantra saktinya, dan konon ruh si kuda api sendirilah yang akan membawakan mantranya kepada orang itu." Engkong melirikku tajam, dan aku membayangkannya seperti orang tua bersorban putih yang menciptakan si kuda api dari patung kayu dan api obor di malam bulan Sapar ketika bulan sabit muram di atas langit. Ah, jawara tua berjenggot putih tanpa lawan yang menemui kematiaan naas di malam Lailatul Qadar! "Karena pengkhianatan Pengkin, muridnya," cerita engkong, entah untuk yang ke berapa ribu kali. Aku hanya mengangguk, tak lagi dengan penuh penasaran bertanya seperti saat pertama kali engkong menuturkannya. "Kenapa, Kong? Kenapa Pengkin mengkhianati
gurunya?" Waktu itu engkong tertawa terkekeh. Beliau tidak segera menjawab, tapi sibuk melinting tembakaunya sehingga aku harus bertanya dua kali. Mata engkong berbinar-binar, seolah begitu menikmati ketidaksabaranku menunggu lanjutan kisah. "Karena si kuda api ternyata memilih Indra sebagai penunggangnya. Padahal sang guru telah mengangkat Pengkin sebagai pemimpin lasykar para santri," bisik engkong sembari menghisap tembakau lintingannya dalam-dalam. Asap tembakau yang harum meliuk-liuk lalu perlahan melayang keluar lewat jendela kecil pondok yang terbuka. Aku mencoba membayangkan kekecewaan Pengkin dan diam-diam menjadi gelisah. Angin malam sedikit kencang, mengantarkan udara yang basah dari halaman. ** AKU bisa menyaksikan sosok Pengkin menyelinap ke pekarangan belakang surau kecil itu. Sesekali bayangan tubuhnya timbul-tenggelam di antara rapat tanaman singkong. Bulan separuh muncul-menghilang di balik awan tebal. Cahaya yang samar sekilas menyinari wajahnya, memperlihatkan air mukanya yang begitu tegang. Aku terus mengikuti langkah lelaki ceking itu hingga tiba di depan pintu belakang surau. Kulihat ia menoleh ke kiri-kanan-belakang dengan cepat. Setelah memastikan tak ada orang, lelaki ceking itu bergegas mengetuk pintu, "Guru.... Guru, ini aku, Pengkin." "Guru...," sekali lagi ia memanggil. Angin serasa membeku. Cukup lama, pintu itu baru terbuka perlahan. "Cepat masuk!" terdengar suara berat berbisik. Pengkin cepat-cepat menyelinap ke dalam, dan pintu segera tertutup. Ruangan itu gelap, hanya ada nyala kecil sebuah lampu yang tampaknya kekurangan minyak di pojok. Tapi aku bisa mengenali sosok lelaki tua bersorban yang duduk bersila di tengah ruangan itu. Pengkin langsung menjatuhkan diri duduk di hadapannya. "Kau yakin tidak ada yang melihatmu?" suara lelaki tua bersorban terdengar tajam. Pengkin hanya mengangguk. Aku merasakan aura di dalam ruangan itu sangat tidak nyaman. "Kau siap melakukannya 'kan?" tanya lelaki tua bersorban. Pengkin tidak menjawab, hanya menunduk. "Pengkin! Jawab pertanyaanku!" lelaki tua bersorban menghardik. "Aku tidak tega, Guru...," suara Pengkin terdengar kecut. "Dia sudah jadi pendekar kesohor yang dipuja orang di mana-mana. Dan jadi tinggi hati, seolah hanya dialah jawara! Sedang kau cuma jadi cecunguk!" lelaki bersorban mendengus, "Dipikirnya tanpa kuda api ciptaanku, dia bisa jadi seperti sekarang." Aku merasakan sekujur tubuhku bersimbah peluh karena gerahnya ruangan.
"Tapi bagaimanapun dia sahabat baikku," jawab Pengkin lemah, masih menunduk. "Aku tidak suka sikapmu yang pasrah, Pengkin! Kau pikir dia sungguh-sungguh menganggapmu sebagai sahabatnya?" suara lelaki tua bersorban bergetar menahan kemarahan. Api lampu minyak mendadak padam, dan ruangan menjadi pengap. "Lakukanlah besok malam! Kita akan diserang tepat waktu isya. Ini perintah!" tegas lelaki tua bersorban, "Kau paham, Anakku?" "Iya, Guru...," Pengkin menjawab lirih. "Sudah berulang kukatakan, jangan panggil aku guru kalau kita sedang berdua. Panggil ayah," suara lelaki tua bersorban tiba-tiba berubah lembut. Dan aku tahu, dalam gelap Pengkin menunduk semakin dalam. ** NAMUN engkong masih terus bercerita bagaimana kecewanya lelaki tua bersorban pada pengkhianatan muridnya, Pengkin. "Dia harus menemui kematian begitu mengenaskan karena pengkhianatan Pengkin," tukas engkong dengan nada sedih, "Lenyapnya kuda api dan tewasnya Indra telah melumpuhkan kekuatan para santri dan begitu memukul hati Syekh Maulana. Lalu engkong kembali mengisahkan peristiwa pada malam dua puluh delapan Ramadan itu. Aku merasakan malam yang begitu sunyi. Tak ada sesayup pun suara. Segala satwa malam seolah lelap, bahkan angin seolah mati. Dari dalam surau kecil di pinggir hutan itu, hanya lamat-lamat terdengar suara orang mengaji yang begitu merdu dan sempurna. Mengalun seperti perahu jung di tengah lautan. "Tapi menjelang dini hari," kata engkong seperti menahan sesuatu, "Kesunyian itu dipecahkan oleh hiruk-pikuk derap kaki kuda dan teriakan." Aku menahan tegang. Kubayangkan barisan ratusan batang obor di atas punggung kuda yang bergerak cepat menuju surau kecil di pinggir hutan itu. Derap kaki-kaki kuda itu semakin lama semakin keras. "Keluarlah Syekh Maulana! Kau sudah terkepung!" begitu rombongan itu sampai di depan surau, sang pemimpin orang kafir putih segera maju dan berseru lantang di atas punggung kuda. Tapi tiada jawaban dari dalam surau, selain suara mengaji yang mengalun merdu. Ratusan kuda meringkik gelisah. Pemimpin orang kafir putih itu tampak kehilangan kesabaran, "Syekh Maulana, keluarlah dan menyerah baik-baik, kau akan kuampuni! Atau kami terpaksa mendobrak tempat ibadahmu!" "Tak perlu repot-repot," tiba-tiba sebuah suara menyahut tenang. Dengan kaget semua orang berpaling ke arah batang rambutan di sudut kanan halaman surau. Seorang lelaki tua bersorban entah sejak kapan telah berdiri di bawah pohon. "Syekh Maulana, kau kami tangkap!" teriak pemimpin orang kafir putih dingin, "Bawa dia!" Lelaki tua bersorban bergerak maju memasang kuda-kuda. Aku melihat lagi ratusan mata pedang, golok, dan kapak terangkat, memantulkan merah cahaya obor yang meliuk-liuk ganas. Aku melihat ratusan busur dan bedil terpasang. Tapi
tak perlu kuceritakan bagaimana tajamnya ratusan mata pedang, golok atau kapak berkelebat, dan bagaimana ratusan mata panah dan pelor melesat setelah Syekh Maulana menolak dibawa. Mungkin engkong benar, Syekh Maulana terlalu yakin dengan ketangguhan jurus bombang dan wapak kebalnya, sehingga ketika ratusan mata pedang, golok, kapak, mata busur, dan pelor bersarang di tubuhnya, ia masih terbelalak tak percaya. Seharusnya ia memekik menyebut nama Allah atau mengulang dua kalimah syahadat, tapi tubuhnya keburu ambruk tanpa suara. Aku yakin, ia tahu seseorang telah membocorkan rahasia kesaktiannya.... Ai, entah untuk yang keberapa ribu kali, engkong menatapku demikian rupa sehabis bercerita. Dan aku mengerti makna tatapan itu. Aku memang bukan Indra, tapi aku juga tak ingin menjadi penunggung kuda api yang kedua setelah Indra. Aku tak ingin menjadi pendekar kelana pembawa nubuat lama dalam nujumannya. Bila saja mungkin, aku hanya ingin seperti Pengkin, lenyap ke dalam suram hikayat dan tak pernah diramalkan akan kembali. "Bila saja mungkin...," Aku mendesah sambil melirik kedua kakiku yang kekecilan dan lunak tak bertulang.*** Yogyakarta, Juli 2006 : buat Zen Hae (thanks atas ilham puisimu "Rajah Waktu")
Anda mungkin juga menyukai
- A.A. Navis: Saraswati Si Gadis SunyiDokumen6 halamanA.A. Navis: Saraswati Si Gadis SunyiSenyum Sank Kamboja0% (1)
- Cerpen Asma NadiaDokumen8 halamanCerpen Asma NadiaDevi Liedany100% (2)
- Kau, Aku, Dan Sepucuk Angpau MerahDokumen1 halamanKau, Aku, Dan Sepucuk Angpau Merahtimah24100% (1)
- Puisi GMDokumen52 halamanPuisi GMDinda Leo Listy100% (1)
- Akulah Si TelagaDokumen25 halamanAkulah Si TelagafireworkrwBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi Beberapa PenyairDokumen50 halamanKumpulan Puisi Beberapa PenyairM.S. ArifinBelum ada peringkat
- Balada SumarahDokumen9 halamanBalada SumarahAdytia PangestuBelum ada peringkat
- DarahDokumen2 halamanDarahWulan Widiasih7Belum ada peringkat
- Utardji Calzoum Bachri Lahir Di RengatDokumen8 halamanUtardji Calzoum Bachri Lahir Di Rengatso tanyBelum ada peringkat
- ZIKIR - Acep Zamzam NoorDokumen3 halamanZIKIR - Acep Zamzam Noorjihanruhiat100% (1)
- Hikayat Abdullah Jilid Pertama Third EditionDokumen190 halamanHikayat Abdullah Jilid Pertama Third EditionBellicose LeoBelum ada peringkat
- Analisis The Signal ManDokumen3 halamanAnalisis The Signal Manatika zumnaBelum ada peringkat
- PUISIDokumen36 halamanPUISIDian Afiandi100% (1)
- (PDF) Seno Gumira Ajidarma-Sepotong Senja Untuk PacarkuDokumen17 halaman(PDF) Seno Gumira Ajidarma-Sepotong Senja Untuk PacarkudiaanyantibatamBelum ada peringkat
- 07.boneka Hidup BeraksiDokumen144 halaman07.boneka Hidup Beraksiker4sakt1Belum ada peringkat
- Cerpen Saga (Un Soir Du Paris 9)Dokumen5 halamanCerpen Saga (Un Soir Du Paris 9)lizphobee100% (1)
- AKUARIUM (Sapardi Djoko Damono)Dokumen1 halamanAKUARIUM (Sapardi Djoko Damono)kahfieBelum ada peringkat
- Njanji SoenjiDokumen4 halamanNjanji SoenjiMuhammadRomlyMutakinBelum ada peringkat
- Sengsara Membawa NikmatDokumen178 halamanSengsara Membawa NikmatgabemzamanBelum ada peringkat
- Frankenstein GHSDDokumen157 halamanFrankenstein GHSDChaa ChannisaBelum ada peringkat
- Sajak Saut SitumorangDokumen19 halamanSajak Saut SitumorangSoni Tri Harsono100% (1)
- Naskah Film Setengah Sendok Teh - Ifa IsfansyahDokumen9 halamanNaskah Film Setengah Sendok Teh - Ifa Isfansyahmah_rizalBelum ada peringkat
- Nyanyi Sunyi Seorang BisuDokumen21 halamanNyanyi Sunyi Seorang Bisu5. SABHAN ABDILLAH RASYIDBelum ada peringkat
- Jurnalistik - HumorDokumen3 halamanJurnalistik - HumorWulansari NFBelum ada peringkat
- Gabriel Garcia MarquezDokumen25 halamanGabriel Garcia MarquezKlaudia Anastasia DedaBelum ada peringkat
- Cerpen Budi Darma (Jawa Pos, 26 April 2020) Sebuah Kisah Di CandipuroDokumen6 halamanCerpen Budi Darma (Jawa Pos, 26 April 2020) Sebuah Kisah Di CandipuroWidjaya HarahapBelum ada peringkat
- PuisiDokumen21 halamanPuisiGazebo English CourseBelum ada peringkat
- 10keajaibangambaranakyangterlupakan 131223204355 Phpapp01Dokumen33 halaman10keajaibangambaranakyangterlupakan 131223204355 Phpapp01JokJulBelum ada peringkat
- Novel AyahkuDokumen21 halamanNovel AyahkudewaayukhBelum ada peringkat
- Alih Media Hilayat Tuanku Nan Muda Pagarruyuang PDFDokumen753 halamanAlih Media Hilayat Tuanku Nan Muda Pagarruyuang PDFBenny RozaldyBelum ada peringkat
- Kumpulan Puisi Kahlil GibranDokumen6 halamanKumpulan Puisi Kahlil Gibranamiaries100% (1)
- Esai Puisi Sajak Rajawali WS RendraDokumen2 halamanEsai Puisi Sajak Rajawali WS RendraunderlinedgirlBelum ada peringkat
- PrincessDokumen322 halamanPrincessElizabeth BonitaBelum ada peringkat
- PUISIDokumen16 halamanPUISIDonitha Fausiahh JamilBelum ada peringkat
- Ikhlas Paling SeriusDokumen7 halamanIkhlas Paling Seriusalwmhmmd45Belum ada peringkat
- Dewan Siswa Mac 2010Dokumen2 halamanDewan Siswa Mac 2010pss smk selandarBelum ada peringkat
- Naskah Drama Dalam Atap Sebuah Cinta KarDokumen15 halamanNaskah Drama Dalam Atap Sebuah Cinta KarRika WijayantiBelum ada peringkat
- Majalah SagangDokumen68 halamanMajalah SagangRyan Ariyanto Sendal JepretBelum ada peringkat
- Senopati Pamungkas 01Dokumen257 halamanSenopati Pamungkas 01hastjarjo100% (4)
- PULANGDokumen668 halamanPULANGDIDIT DitaMurpradanaBelum ada peringkat
- Keberkesanan Pengajaran Menulis EseiDokumen94 halamanKeberkesanan Pengajaran Menulis EseiMaharamukm100% (1)
- Autobiografi KartiniDokumen6 halamanAutobiografi KartiniS F1nerBelum ada peringkat
- Antologi Puisi - Perjumpaan PDFDokumen80 halamanAntologi Puisi - Perjumpaan PDFFajarMartaBelum ada peringkat
- P01-Petualangan Di Pulau Suram PDFDokumen266 halamanP01-Petualangan Di Pulau Suram PDFAlif AlkausarBelum ada peringkat
- Mirah Dari Banda PDFDokumen393 halamanMirah Dari Banda PDFMuhammad Ilham NurBelum ada peringkat
- Cerpen Kematian Paman GoberDokumen5 halamanCerpen Kematian Paman GoberapriyantiBelum ada peringkat
- Puisi Roestam Effendi Dalam Percikan PermenunganDokumen3 halamanPuisi Roestam Effendi Dalam Percikan PermenunganAlfaqir Muhyi ArruhamaaniaBelum ada peringkat
- 64 Cerpen KompasDokumen251 halaman64 Cerpen KompastopwanBelum ada peringkat
- Adimas ImanuelDokumen17 halamanAdimas ImanuelMuhammad Hendrawan100% (1)
- Cerpen Putu WijayaDokumen9 halamanCerpen Putu WijayaSetyo AjiBelum ada peringkat
- Anak KabutDokumen2 halamanAnak KabutFakhriBelum ada peringkat
- Puisi KHALIL MUTHRANDokumen9 halamanPuisi KHALIL MUTHRANLillah N. Lailatul MunirohBelum ada peringkat
- Mati Itu Spektakuler - Khawaja MuhammadDokumen445 halamanMati Itu Spektakuler - Khawaja MuhammadRintan NabilaBelum ada peringkat
- Sepasang Mata IblisDokumen127 halamanSepasang Mata IblisdewaarifBelum ada peringkat
- Tanah AirkuDokumen7 halamanTanah AirkuAfrinaChBelum ada peringkat
- Puisi 25 Januari 2006 PDFDokumen7 halamanPuisi 25 Januari 2006 PDFDwi TaryantoBelum ada peringkat
- Wahai Negeriku TercintaDokumen2 halamanWahai Negeriku TercintaNgurah BimantaraBelum ada peringkat
- Puisi WS RendraDokumen60 halamanPuisi WS RendraMukhlis AminullahBelum ada peringkat
- Cinta BerkabutDokumen1 halamanCinta BerkabutMaltuf A. GungsumaBelum ada peringkat
- Analisis Regresi Linear SederhanaDokumen4 halamanAnalisis Regresi Linear SederhanaNurulWahyuniBelum ada peringkat
- Amplop Bem IpiDokumen1 halamanAmplop Bem IpiMaltuf A. GungsumaBelum ada peringkat
- Tabloid Menara BantenDokumen20 halamanTabloid Menara BantenMaltuf A. GungsumaBelum ada peringkat
- Opini Polemik Gedung Baru Dan Aspirasi RakyatDokumen2 halamanOpini Polemik Gedung Baru Dan Aspirasi RakyatMaltuf A. GungsumaBelum ada peringkat
- Opini Buku2Dokumen2 halamanOpini Buku2Maltuf A. GungsumaBelum ada peringkat
- Pembakaran Gereja Di Temanggung - Pembakaran Gereja Di Temanggung Terjadi Pada SelasaDokumen4 halamanPembakaran Gereja Di Temanggung - Pembakaran Gereja Di Temanggung Terjadi Pada SelasaMaltuf A. GungsumaBelum ada peringkat
- Romansa Kali OpakDokumen3 halamanRomansa Kali OpakMaltuf A. GungsumaBelum ada peringkat
- Romansa Kali OpakDokumen3 halamanRomansa Kali OpakMaltuf A. GungsumaBelum ada peringkat