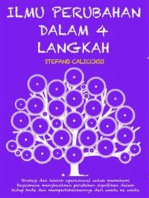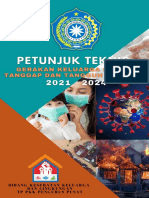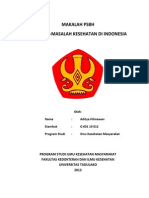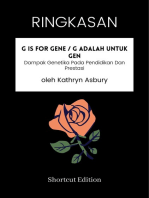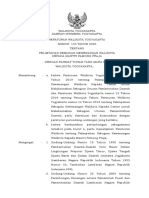Hearth TT
Hearth TT
Diunggah oleh
Opa YatJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Hearth TT
Hearth TT
Diunggah oleh
Opa YatHak Cipta:
Format Tersedia
Model Tungku (Hearth) Terbukti Mampu Mengeliminasi Kasus Kurang Gizi Secara Berkelanjutan (Sirajuddin) Meluasnya busung lapar
saat ini disebabkan oleh multi faktor. Hingga saat ini ada dua faktor langsung yang diyakini menyebabkan timbulnya gizi kurang yaitu rendahnya konsumsi makanan dan adanya penyakit infeksi. Rendahnya konsumsi makanan memang umumnya merupakan sindroma kemiskinan dan meluasnya penyakit infeksi merupakan refleksi sanitasi lingkungan yang buruk. Saat ini kita tidak harus disibuk mencari siapa yang salah, akan tetapi lebh baik kita fokus pada solusi. Jika kita telusuri sejarah perbaikan gizi di Indonesia ada dua dimenasi yang harus dilihat yaitu. Perbaikan gizi dalam kondisi emergency dan perbaikan gizi bukan dalam kondisi emergensi. Pendekatan yang digunakan untuk kedua kondisi itu sangatlah berbeda. Dalam keadaan darurat penanggulangan lebih difokuskan pada intervensi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan selama 90 hari makan anak yang dikucurkan pemerintah kepada mereka yang menderita gizi kurang dan gizi buruk. Tetapi dalam jangka panjang PMT ini tidak dapat menjadi pilihan utama, karena akan menimbulkan ketergantungan yang hebat diantara penerima bantuan. Jika bukan dalam keadaan darurat pencegahan kurang gizi harus dilakukan dengan konsep pemberdayaan keluarga. Hingga saat ini konsep pemberdayaan keluarga dalam mengatasi kasus gizi kurang masih jarang dilakukan, karena sulitnya untuk merumuskan bentuk intervensi yang melibatkan aspek income generating keluarga. Terlebih jika kemudian disimpulkan bahwa penyebab gizi kurang adalah sindroma kemiskinan. Theory Of Constraint (TOC) yang dikembangkan Eliyahu Goldratt menuntun kita untuk megatasi masalah mulai dari rantai yang paling lemah, dan setiap saat hanya ada satu rantai yang paling lemah lalu kemudian kita akan keluar dengan hasil yang cukup signifikan mengatasi masalah (Poli, WIM , 2000) Jika kemudian variabel ekonomi menjadi mata rantai paling lemah menurut analisis Unicef (1998), lalu apakah kita dapat keluar dari masalah gizi dengan segera?. Ada satu hypotesis yang menarik untuk kita sandingkan dengan modelnya Unicef yaitu bahwa perbaikan status gizi dapat saja dilakukan tanpa harus menunggu variabel ekonomi yang mapan dan meskipun masalah gizi terkait dengan masalah biomedik tetapi pengentasannya tidak hanya memerlukan ilmu-ilmu biomedik saja. Sangat diperlukan analisis yang sistematis dan terukur dari aspek manajemen pengentasan kasus kurang gizi (Soekirman, 2001) Pada abad ke 20 ada satu gerakan modernisasi yang dikakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan disegala bidang yaitu pendekatan Button Up (arus bawah). Pendekatan ini memiliki daya ungkit yang besar untuk mengatasi masalah termasuk dalam mengatasi masalah
gizi. Keunggulannya adalah berbasis pada potensi masyarakat yang akan menuntun mereka mengatasi sendiri masalahnya tanpa menimbulkan ketergantungan pada pihak lain termasuk pemerintah. Dengan pendekatan Top Down Approach yang selama ini berjalan perbaikan gizi masyarakat tidak membawa hasil yang nyata. Bukti paling dekat dengan kita saat ini adalah jatuhnya nilai tukar rupiah tahun 1997 menyebabkan munculnya gizi buruk dengan prevalensi yang cukup tinggi. Meluasnya masalah gizi buruk awal tahun 1998 kemudian mengilhami pemerintah untuk melakukan langkah pengamanan yang disebut Social Safety Mate atau yang dikenal dengan jaring pengaman sosial. Dalam bidang kesehatan dikenal Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai bagian dari Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK). PMT-JPS BK kemudian menjadi idola tetapi masih menyisahkan masalah besar akibat mewariskan karakter ketergantungan yang hebat, bukan saja pada level petugas kesehatan tetapi juga pada level masyarakat penerima bantuan. Di Sulawesi Selatan sejalan dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JPS-BK) ada sebuah hasil riset yang dipublikasi tahun 2002 mengemukakan bahwa peran keluarga luas sangat diperlukan untuk suksesnya Pemberian Makanan Tambahan. (Yahya, Djunaedi MD, Sudirman, HN, 2002) Fakta ini membuat clue bagi kita bahwa masih ada factor yang harus kita cari selain variabel ekenomi sebagaimana yang disebutkan dalam Model Unicef (1997) untuk mengatasi masalah gizi. Dalam sebuah Rakor Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan dan Strategi Perbaikan Gizi, Kementerian Kesra RI di Makassar, 21 Mei 2004 seorang guru besar Ilmu Gizi Universitas Hasanuddin (A Razak Thaha ) menyebutkan bahwa untuk melakukan hal yang tepat diperlukan cara yang benar. Selanjutnya beliau menjelaskan ada empat azas yang harus diikuti untuk menangani masalah dengan cerdas yaitu (1) Tepat masalah (2) Tepat akar penyebab (3) Tepat intervensi (4) Tepat implementasi. Pada bagian akhir paparan beliau dijelaskan bahwa hambatan kunci tidak signifikannya hasil yang diperoleh dalam perbaikan gizi adalah mental model Project Oriented Dua kajian diatas yaitu (1) Model Unicef dan (2) Mental Model Project Orientyed. Kedua kajian ini menuntun kita untuk mulai memikirkan fakta pada level grass root (akar rumput) yaitu masyarakat sebagai subject bukan sebagai object. Teori hambatan dengan jelas menyebutkan bahwa mengatasi masalah dimulai harus dari mata rantai paling lemah. Jika kita analisis secara sederhana dimana letak mata rantai paling lemah ini, maka kemungkinan ada pada tiga domain (1) masyarakat (2) pemerintah (3) metodenya. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah (1) Dimana letak mata rantai paling lemah (2) Apa masalah intinya (3) bagaimana mengatasinya.
Menjawab ketiga pertanyaan diatas tidaklah sederhana karena memerlukan kajian yang menyeluruh, bukan atas pragmentasi dari sebuah masalah ke masalah yang lain. Hukum pertama dalam Sistem Thingking and Learning Organization menyebutkan masalah hari ini adalah akibat sukses masa lalu dan sukses masa kini merupakan masalah pada masa yang akan datang. Melihat masalah secara terpisah ibarat membelah gajah menjadi dua tidak akan akan melahirkan dua gajah kecil (Peter Senge) Editorial Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Nomor 1, volume 01 2004 mengangkat tema Belajar berubah atau mati sebuah wacana adaptasi lingkungan yang berubah cepat (Dahlan, DM, 2004). Pada bagian akhir editorial ini dijelaskan bahwa pada akhirnya kulturlah yang digunakan masyarakat untuk memecahkan masalahnya dan kuncinya adalah kemampuan untuk berfikir dalam pola pikir masa depan. Wacana ini sebenarnya telah lama dipikirkan oleh Charles Darwin dalam bukunya Survival of the Fittes Bahwa kekuatan bukan jaminan untuk dapat bertahan hidup tetapi kemampuan beradaptasilah yang membuat kita survive. Hilangnya dinosaurus pada berjuta tahun lalu bukan karena mahluk ini lemah tetapi karena mahluk ini tidak dapat beradaptasi. Berdasarkan kajian diatas ada 4 grand issue yang saling terkait untuk kita jadikan buku saku menelusuri upaya perbaikan gizi yang cerdas yaitu (1) Theory of Constraint (Goldratt) (2) Survival of The Pittes (Charles Darwin) (3) Sistem Thinking (Peter Senge) dan (4) Mental Model (Razak Thaha) Menelusuri kultur masyarakat sebagai potensi dalam memecahkan masalah akhirnya merupakan satu titik yang tidak salah kalau kita tekuni, khususnya dalam upaya perbaikan gizi balita. Mengapa? Jawabnya sederhana yang bermasalah itu adalah masyarakat dengan demikian gunakan potensi kultur masyarakat untuk mengatasi sendiri masalahnya. Asumsinya adalah rantai paling lemah ada dimasyarakat (ingat teori hambatan). Untuk membenahi aspek manajerial dari sisi pelayanan kesehatan harus diperbaiki sisi provider (petugas) (ingat mental model project oriented). Salah satu kajian yang cukup menarik untuk dijadikan pijakan dalam merumuskan bentuk intervensi perbaikan gizi balita dengan basis potensi sumberdaya keluarga (masyarakat) adalah belajar dari kasus deviasi positif (Positif Deviance). Kasus penyimpangan positif secara rinci dijelaskan oleh Zeitlin at.al (1990) dalam sebuah buku yang berjudul Positive Deviance in Child Nutrition. Dari sini lahirlah Metode Hearth yang telah berhasil di beberapa negara seperti Vietnam, Haiti, Bangladesh, Thailand. Metode Hearth ini membuat konfilasi antara konseling gizi keluarga dan pemberian makan anak dengan menggunakan dapur bersama. Keunggulan metode Hearth adalah ibu yang memiliki anak gizi buruk belajar mengasuh anak dari rekan sejawat yang anaknya tidak kurang gizi. Potensi sumber daya keluarga adalah andalan utama dan sheering
pengalamanan adalah proses interaksi yang dipersyaratkan dalam metode ini. Pada Bulan Desember 2004 Plan Interational dan Media Gizi Makassar tengah menguciconba model Tungku (Hearth) di Kota Makassar, Jeneponto dan Takalar telah melatih sebanyak 22 orang kader Pendamping Model hearth di Tiga Kota. Hasil uji coba ini cukup menggembirakan, karena tanpa bentuan makanan tambahan dari pihak lain, kenaikan berat badan anak dapat dicapai hanya dalam waktu 12 hari. Sesi Tungku (Hearth) sendiri menggunakan 12 hari x 3 sesi = 36 hari. Model hearth memiliki dua kegiatan pokok yang langsung memengaruhi perubahan status gizi, meskipun kegiatan sesi hearth terdiri dari sembilan langkah. Kedua kegiatan tersebut adalah (1) Kegiatan masak dan makan bersama anak dengan bahan baku patungan para anggota binaan (2) Kegiatan konseling gizi anak oleh official Haerth (TPG, Kader, Advisor Hearth). Kedua issue yang dikemukakan dalam dua kegiatan ini bersumber dari kasus penyimpang positif status gizi anak di daerah tersebut. Kasus deviasi positive adalah anak dari keluarga miskin yang memiliki gizi baik. Dalam sebuah daerah yang tertinggal sekalipun pasti akan didapatkan kasus seperti ini. Dari cara memberi makan anak, perawatan, pengasuhan dan menjaga kebersihan anak mereka kita belajar. Karena dialah orang yang sukses mengatasi masalah gizi secara sederhana. Mengapa. Seharusnya orang miskin akan mengalami kasus gizi kurang. Tetapi pada kasus deviasi positif hal ini tidak berlaku. Karenanyalah kita wajib belajar cara apa yang ia lakukan sehingga anaknya mampu keluar dari ancaman kurang gizi. Pada Model Hearth, intinya adalah bagaimana mentrasfer praktik pengasuhan, pemberian makan, perawatan dan kebersihan diri dapat diterapkan dengan baik oleh sasaran. Daru hasil uji coba di tiga kota dengan menggunakan analisis faktor risiko, maka ada beberapa point penting yang menyebabkan terjadinya kasus deviasi positif yaitu yaitu: 1. Pemberian air susu yang pertama keluar (kolostrum) kepada anak (P=0,002) 2. Selisih antara waktu lahir anak dengan keluarnya ASI lebih singkat (P=0,036) 3. Posisi menyusui bayi dalam keadaan duduk rileks (P=0,001) 4. Interaksi Ibu dengan Anak saat menyusui dalam keadaan santai dan bershabat (P=0,088) 5. Produksi ASI tidak bermasalah (0,001) 6. Jika harus mengganti ASI maka h nasi sebagai alternatif utama dibanding yang lainnya (P=0,016) 7. Frekuensi pemberian makan sehari lebih banyak (P=0,061) 8. Kesukaan terhadap Nasi lebih menonjol (P=0,077) 9. Mendapat tablet Fe saat menyusui (P=0,059) 10. Tidaj memiliki kebiasaan malas makan (P=0,041) 11. Punya kiat untuk mengatasi malas makan (0,061) 12. Pergaulan dengan tetangga dekat yang lebih harmonis (P=0,088)
13. Diasuh Mertua saat keluar rumah (P=0,010) 14. Diasuh Paman saat keluar rumah (P=0,065) 15. Diasuh tante saat keluar rumah (P=0,011) 16. Diasuh nenek saat keluar rumah(P=0,052) Keenambelas item inilah yang mencadi kunci pokok mengapa mereka yang miskin mampu menjadikan anaknya gizi baik. Sungguh suatu keadaan yang sangat sederhana tetapi jarang dapat dilakukan oleh ibu yang tidak memiliki kepedulian kepada anaknya. Bahwa kepedulian tidak dapat diukur hanya dengan pengakuan lisan, tetapi tindakan nyata yang lebih utama. Berdasarkan temuan diatas, maka Tim Positive Deviance merumuskan pesan yang akan disampaikan selama sesi Tungku (Hearth) berlangsung yaitu sebagai berikut Tabel 1 Rumusan Pesan Aplikatif dalam Sesi Hearth No Pesan Aplikatif 1 Sebaiknya posisi ibu saat menyusui dalam keadaan duduk rileks 2 Saat menyusui tataplah anak dengan penuh kasih sayang, jangan mengabaikan anak saat ia sedang menyusui 3 Jika ada masalah dengan prosuksi ASI atasi segera menurut cara yang lazim digunakan (perbanyak makan sayur) 4 Kalaupun harus mengganti ASI, maka sebaiknya gunakan bahan dasar nasi sebagai pilihan utama 5 Berikan makan anak anda sesering mungkin, jika ia malas makan perkecil porsinya 6 Jika anak anda tidak suka dengan nasi, biasakan ia makan nasi, walau hanya sedikit dalam sehari 7 Mintalah tablet Fe saat menysui atau hamil 8 Biasakan agar anak anda tidak terbiasa melalaikan waktu makan 9 Tanyakan kepada teman anda bagaimana caranya agar anak mau makan 10 Permudahlah begaul dengan orang diluar rumah, karena itu dapat meringankan beban anda 11 Jika harus meninggalkan rumah, titiplah anak anda pada orang terdekat anda Dari pesan tersebut selanjutnya dilakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan ibu dalam mengikuti seluruh pesan yang dipantau selama sesi hearth berlangsung dengan skala 1-11. Seorang peserta harus dinilai tingkat keberhasilnnya untuk dapat ditetapkan sebagai peserta yang lulus atau harus mengulang sesi hearth berikutnya. Acuannya adalah tingkat kepatuhan (lihat grafik 1) dan pencapaian berat badan selama sesi hearth (lihat grafik 2) . Demikianlah pendekatan ini akan bergulir ke peserta baru dan ke daerah lain.
Hasil metode tungku sangat terukur. Untuk menurunkan jumlah penderita gizi kurang diperlukan waktu 3 x 12 hari sesi hearth dengan jumlah sasaran 60 orang anak. Dari jumlah ini diperlukan 12 orang kader pendamping satu orang supervisor. Perlu ditambahkan bahwa setiap ibu / anak yang dinyatakan lulus sesi hearth tidak akan mengalami kasus gizi kurang yang berulang. Karena paket tungku (hearth) dirancang sedemikian rupa sehingga ia tidak akan tergantung kepada pihak diluar keluarga dengan penghematan terhadap penggunaan sumberdaya keluarga. Inilah bedanya metode tungku (hearth) dengan metode lain. Misalnya kita mengandalkan bentuk intervensi yang bahan bakunya tidak ada dalam keluarga, sekalipun itu barang murah meriah tetap saja keberlanjutannya sangat tergantung pafa siapa yang memproduksi bahan bakunya. Contohnya MP-ASI, sekalipun itu harganya murah bahkan gratis, tetapi efek dominonya luar biasa. Ibu semakin tidak betdaya dalam keridaktahuannya tentang apa dan bagaimana ia dapat menyediakan sendiri makanan untuk anaknya. Kita harus belajar dari kasus terpinggirnya air susu ibu secara perlahan-lahan hingga akhirnya mencapai kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini. Faktanya setiap 100 anak yang lahir hanya 19 orang dapat diberi ASI semata tanpa makan lain hingga usia 4 bulan. Padahal ASI cukup untuk kebutuhan bayi hingga usia 6 bulan. Jika dikalkulasi dengan harga susu yang dikonsumsi anak selama 24 bulan, dengan harga Rp20000 setiap 7 hari. Maka total biaya yang harus disediakan sebesar Rp. 2.057.142,-. Apa artinya nilai nominal ini?. Jika ibu tidak sanggup untuk menyediakan uang sebanyak itu dalam 24 bulan, dipastikan gizi kurang akan selalu menyertai anaknya. Bagi mereka yang berkecukupan sekalipun, masih kurang bijaksana jika semata-mata menghitung nilai ASI dalam bentuk rupiah. Karena dalam ASI ada nilai kasih sayang yang tidak dapat dinilai dengan rupiah. Ada perkenalan terhadap cita rasa makanan sejak dini yang menyebabkan anak mampu menganekaragamkan makanannya kelak dikemudian hari. Ini adalah garansi yang mengantar seseorang untuk tidak bersahabat dengan penyakit degeneratif kelak jika ia menjadi keluaga yang mapan.
Kesimpulan Model Tungku (hearth) dapat digunanakan sebagai salah satu cara pencegahan kurang gizi yang berkelanjutan, yang mencoba memberdayakan masyarakat karena secara ketat mengajarkan ibu untuk mampu mengelola sumberdaya yang serba terbatas, menanamkan disiplin pengasuhan, membiasakan hidup bersih, merangsang asuhan dini dan tumbuh kembang anak, dan mengajarkan cara memberi makan anak. Semua proses ini dalam bingkai potensi Sumber Daya Keluarga. Kita harus yakin bahwa kepedulian akhirnya dapat mengatasi masalah kurang gizi meski sumberdaya ekonomi terbatas. Karena jumlah, bentuk dan jenis makanan anak hanya 1/3 dari kebutuhan orang dewasa. dewasa bisa survival mengapa anak tidak? Kalau orang
Referensi Agustian Ipa, Asmaruddin Pakhri, Siti Nur Rochimiwati, Hikmawati, Sirajuddin, 2002. Pengentasan Gizi Buruk melalui Peningkatan Pemberdaayaan Keluarga di Kecamatan Tallo dan Ujungtanah Kota Makasaar, Laporan Kerjasama Kemitraan Jurusan Gizi (Media Gizi Makassar) dengan Plan International Makassar, Agustian Ipa, Asmaruddin Pakhri, Siti Nur Rochimiwati, Hikmawati, Sirajuddin, 20003. Deteksi Dini Gizi Buruk dan Uji Coba Pendekatan Deviasi Positif Dalam Penanganan Gizi Buruk, Laporan Kerjasama Kemitraan Jurusan Gizi (Media Gizi Makassar) dengan Plan International Makassar, Dewi Parmaesih, 2000. Dampak Krisis ekonomi terhadap Perubahan Status Gizi, Biokimia Gizi dan Pola Makan di Masyarakat Pedesaan (Data tahun 1992 dibandingkan data tahun 1999). Badan Libangkes Depkes RI Felicity Savege Kinng & Ann Burgess. Nutrition For Developing Countries. Oxford University Press. Tokyo Kirk A Dearden, Le Nga Quan, Mai Do, David R, Marsh, Helena Pachon, Dirk G, Schroeder, and Tran Tahi Lang (2002). Work Outside the Home is the Primery Barrier to Exclusive Breastfeeding in rural Vietnam. Food and Nutrition Bulletin Vol 23 No 4 (supplemented @2002) The National University. Kathrin Bolles, Cathrine Speraw, Gretchen Berggren, and Jack Guy Lafontant, 2002, Ti Foyer (Hearth) Community Based Nutrition Activities Informed by the Positive Deviance Approach in Leogane, Heiti : A programmatic Description. Food and Nutrition Bulletin Vol 23 No 4 (supplemented @2002) The National University. Moniqie Sterning, Jerry Sterning & David Mars, 1998, Designing a Community Based Nutrition Program Using the Heart Model and the Positive Deviance Approach- A Field Guide. Save The Children. Mery Zaitlin. 1990. Positive Deviance in Child Nutrition. United Nation University. Tokyo Michael J Gibney, Barrie M Margaret, John M Kaearney dan Lanore Arab, 2004. Public Health Nutrition (the nutrition society textbook series). Blakwell Publishing, Iowa USA. M Aruna, Shahnaz Vazir, P Vidyasagar, 2000. Maternal Child rearing Behaviors, Parental Attributes and Socio Economic Status of the family an to analyze their association with positive deviance in the developmental status of preschool children, National Institut of Nutrition, Jamai Osmania, India Sihadi, 2000. Aktivitas Ibu dalam Organisasi dan Paparan terhadap Media Massa dalam Penyimpangan Positif Status Gizi Anak Balita, Badan Libangkes Depkes RI. Soekirman, dkk. Prosiding Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (Jakarta 17 Januari sd 19 Mei 2004) Setyoedi. (2005) Modul Pelatihan Deviasi Positif. Plan Internatonal. Indonesia Thomas P. Davis Jr, MPH, Adiguna Kebede, MD, MPH, Kim Cutler (2005). Expanded Posditive Deviance Study Report. USAID & Food for Hungry
Anda mungkin juga menyukai
- ILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuDari EverandILMU PERUBAHAN DALAM 4 LANGKAH: Strategi dan teknik operasional untuk memahami bagaimana menghasilkan perubahan signifikan dalam hidup Anda dan mempertahankannya dari waktu ke waktuPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (6)
- PSIKOLOGI, DEPRESI DAN DISTURBILITAS HUMOR: Memahami mekanisme dasarDari EverandPSIKOLOGI, DEPRESI DAN DISTURBILITAS HUMOR: Memahami mekanisme dasarPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (3)
- Bahaya Gadget Bagi Kesehatan AnakDokumen11 halamanBahaya Gadget Bagi Kesehatan AnakSurya Mira90% (10)
- PSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaDari EverandPSIKOLOGI PERKEMBANGAN ANAK DAN DISTURBILITAS PADA USIA EVOLUTIF: Apa itu dan bagaimana cara kerjanyaBelum ada peringkat
- Pendidikan Kesehatan MasyarakatDokumen22 halamanPendidikan Kesehatan MasyarakatChintya_putry39100% (1)
- Juknis Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh BencanaDokumen68 halamanJuknis Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh BencanaSurya Mira91% (32)
- Manajemen Pendekatan KeluargaDokumen80 halamanManajemen Pendekatan KeluargaSurya MiraBelum ada peringkat
- Strategi Perubahan PerilakuDokumen16 halamanStrategi Perubahan PerilakuFiera RiandiniBelum ada peringkat
- Laporan Pengmas Gizi SeimbangDokumen42 halamanLaporan Pengmas Gizi Seimbangcintia100% (1)
- Laporan Perkembangan Pilot Project-NewDokumen6 halamanLaporan Perkembangan Pilot Project-NewSurya Mira100% (11)
- Positif DevianceDokumen29 halamanPositif DevianceAsepMaryamanBelum ada peringkat
- SPM, Pis PK, GermasDokumen89 halamanSPM, Pis PK, GermasSurya Mira0% (1)
- Rumah Tangga Rosulullah PDFDokumen16 halamanRumah Tangga Rosulullah PDFSurya Mira100% (1)
- Materi Sistem Penguatan Kelurahan Siaga Di Kota YogyakartaDokumen33 halamanMateri Sistem Penguatan Kelurahan Siaga Di Kota YogyakartaSurya MiraBelum ada peringkat
- INSTRUMEN PENDATAAN PHBS DI RUMAH TANGGA EdDokumen4 halamanINSTRUMEN PENDATAAN PHBS DI RUMAH TANGGA EdSurya MiraBelum ada peringkat
- Contoh Proposal Tesis UnsyiahDokumen10 halamanContoh Proposal Tesis UnsyiahFP Ersida100% (1)
- C4 - Makalah Etika Profesi Mendayagunakan Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Intervensi GiziDokumen24 halamanC4 - Makalah Etika Profesi Mendayagunakan Potensi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Intervensi GizikarinBelum ada peringkat
- Pengembangan Kisi-Kisi Instrumen Pengkajian Komunitas - SUSTYARKO ONNY A - 202311101105Dokumen19 halamanPengembangan Kisi-Kisi Instrumen Pengkajian Komunitas - SUSTYARKO ONNY A - 202311101105RositaBelum ada peringkat
- Makalah Positive Deviance - Elvia Riska - Kelas BDokumen11 halamanMakalah Positive Deviance - Elvia Riska - Kelas Belvia riskaBelum ada peringkat
- Kelompok 6 ADokumen8 halamanKelompok 6 Aangenia zegaBelum ada peringkat
- Kel 12 PGMDokumen6 halamanKel 12 PGMHasana HusnaBelum ada peringkat
- Jurnal Anak Sulit MakanDokumen9 halamanJurnal Anak Sulit MakanMasniahBelum ada peringkat
- Gizi Kesehatan Masyarakat PesisirDokumen5 halamanGizi Kesehatan Masyarakat PesisirkiaBelum ada peringkat
- Penerapan Teknologi Augmented Reality Sebagai Bentuk Edukasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Gizi Buruk (Autorecovered)Dokumen20 halamanPenerapan Teknologi Augmented Reality Sebagai Bentuk Edukasi Masyarakat Terhadap Permasalahan Gizi Buruk (Autorecovered)Asrianti Putri LestariBelum ada peringkat
- Makalah PSBHDokumen13 halamanMakalah PSBHAditya HilmawanBelum ada peringkat
- Jurnal Komunitas Tugas KlompokDokumen11 halamanJurnal Komunitas Tugas Klompok6A peni kartikaBelum ada peringkat
- Hampir LGKP Makalah Peppgm Kelompok 12Dokumen14 halamanHampir LGKP Makalah Peppgm Kelompok 12Selya MahulaeBelum ada peringkat
- SB - Kekurangan Gizi Balita DKI JakartaDokumen8 halamanSB - Kekurangan Gizi Balita DKI JakartaReza Arrafi RasyidBelum ada peringkat
- LO Modul 3Dokumen13 halamanLO Modul 3intan zuryaniBelum ada peringkat
- LP PromkesDokumen4 halamanLP Promkessandyclaudio labuluBelum ada peringkat
- LP Kep Komunitas Pada BalitaDokumen20 halamanLP Kep Komunitas Pada BalitaAyhu KimBelum ada peringkat
- LKM 3 - Kel 6 - Kastrat DDokumen5 halamanLKM 3 - Kel 6 - Kastrat DRahayu TitisBelum ada peringkat
- StuntingDokumen3 halamanStuntingNayyBelum ada peringkat
- 264+dr +niningDokumen7 halaman264+dr +niningFaiz SujudiBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen21 halamanBab 2ameliaipBelum ada peringkat
- Poa Kel 6Dokumen23 halamanPoa Kel 6Rosaldi MilleniantoBelum ada peringkat
- ILM DinkesDokumen22 halamanILM DinkesDeq JongBelum ada peringkat
- Positive DevianceDokumen14 halamanPositive DevianceAnonymous ycciSniPv7Belum ada peringkat
- 2.ISI Revisi FixxDokumen12 halaman2.ISI Revisi FixxICUHCU BHINABelum ada peringkat
- Tutorial Klinik Program Gizi PKM Tarakan FixeddDokumen41 halamanTutorial Klinik Program Gizi PKM Tarakan FixeddAichsaniarBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Aplikasi KomunitasDokumen78 halamanLaporan Akhir Aplikasi KomunitasYoga GinanjarBelum ada peringkat
- Laporan SCL Gizi Kel. 12Dokumen30 halamanLaporan SCL Gizi Kel. 12Nurul KhotimahBelum ada peringkat
- 25-Article Text-52-1-10-20220810 PDFDokumen5 halaman25-Article Text-52-1-10-20220810 PDFelnattaBelum ada peringkat
- Analisis Isu Kontemporer Pelatihan Dasar CPNSDokumen7 halamanAnalisis Isu Kontemporer Pelatihan Dasar CPNSdilaBelum ada peringkat
- Laporan Akhir Praktik Kep - Komunitas Kel.2Dokumen41 halamanLaporan Akhir Praktik Kep - Komunitas Kel.2Riyan FirmanBelum ada peringkat
- Gizi BalitaDokumen5 halamanGizi BalitaMina MinoBelum ada peringkat
- Satuan Acara PenyuluhanDokumen3 halamanSatuan Acara PenyuluhanFaiyaz AtharrazkaBelum ada peringkat
- Makalah Komunitas Kelompok 5Dokumen20 halamanMakalah Komunitas Kelompok 5Ismi MimiBelum ada peringkat
- Resume Wika HumanioraDokumen17 halamanResume Wika HumanioraYuwika CahyaBelum ada peringkat
- Bab 1-4 Riris BaruuDokumen48 halamanBab 1-4 Riris BaruuMarsam MsBelum ada peringkat
- Quiz Health PromotionDokumen3 halamanQuiz Health PromotionPratiwi SuryaBelum ada peringkat
- Analisis Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Anak Kelas 1Dokumen15 halamanAnalisis Tentang Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat Pada Anak Kelas 1vens100% (1)
- Pencegahan StuntingDokumen10 halamanPencegahan StuntingNaila IlmiBelum ada peringkat
- 2 1Dokumen24 halaman2 1Erna LisaBelum ada peringkat
- Kak TFC Beber Yg BenerDokumen15 halamanKak TFC Beber Yg BenerDede Kurnia Mega100% (1)
- Template Penugasan Individu PesertaDokumen6 halamanTemplate Penugasan Individu PesertaSidarajaBelum ada peringkat
- Makalah Analisis Kependudukan Fakultas Kesehatan MasyarakatDokumen8 halamanMakalah Analisis Kependudukan Fakultas Kesehatan MasyarakatYayaat33100% (2)
- Makalah GKR - Kelompok 5Dokumen13 halamanMakalah GKR - Kelompok 5VthreeBelum ada peringkat
- Faktor Sosial Budaya Yang Berhubungan Dengan Program KBDokumen4 halamanFaktor Sosial Budaya Yang Berhubungan Dengan Program KBNadya Ryani PutriBelum ada peringkat
- Term of ReferenceDokumen3 halamanTerm of ReferenceSofia ZaharaBelum ada peringkat
- Kie - Makalah Sulit Makan Pada AnakDokumen9 halamanKie - Makalah Sulit Makan Pada AnaknadislaBelum ada peringkat
- MTBSDokumen16 halamanMTBSRatna Prabawati NopiutamiBelum ada peringkat
- Mengejar Target Penurunan Stunting - UasDokumen6 halamanMengejar Target Penurunan Stunting - UasHilallia MBelum ada peringkat
- STUNTINGDokumen12 halamanSTUNTINGEkaRima MelatiSuciBelum ada peringkat
- Isi Laporan KKN IPE KLP 28Dokumen126 halamanIsi Laporan KKN IPE KLP 28Fendy Anugrah100% (1)
- Gizi BurukDokumen15 halamanGizi BurukBuket Wisuda BangkalanBelum ada peringkat
- Proposal Deteksi Dini Kelompok 3Dokumen16 halamanProposal Deteksi Dini Kelompok 3srijonoyanti16Belum ada peringkat
- RINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyDari EverandRINGKASAN: G Is For Gene / G Adalah Untuk Gen: Dampak Genetika Pada Pendidikan Dan Prestasi Oleh Kathryn AsburyBelum ada peringkat
- Obes Anemia 3 Juli 21Dokumen29 halamanObes Anemia 3 Juli 21Surya MiraBelum ada peringkat
- Pelaporan AKIDokumen6 halamanPelaporan AKISurya MiraBelum ada peringkat
- Identifikasi Dan Capaian Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh BencanaDokumen17 halamanIdentifikasi Dan Capaian Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Dan Tangguh BencanaSurya MiraBelum ada peringkat
- Materi 3 Posyandu Dalam AKBDokumen45 halamanMateri 3 Posyandu Dalam AKBSurya MiraBelum ada peringkat
- Perwal 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong PrajaDokumen67 halamanPerwal 135 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong PrajaSurya MiraBelum ada peringkat
- Posyandu SatelitDokumen33 halamanPosyandu SatelitSurya MiraBelum ada peringkat
- Survey PHBS Tatanan Rumah TanggaDokumen4 halamanSurvey PHBS Tatanan Rumah TanggaSurya MiraBelum ada peringkat
- Si Kesi Gemes 2020Dokumen81 halamanSi Kesi Gemes 2020Surya Mira100% (1)
- Gagasan Pembudayaan Germas - TrihonoDokumen78 halamanGagasan Pembudayaan Germas - TrihonoSurya MiraBelum ada peringkat
- Pelajaran 45 - Pembagian Jumlah Mufidah Halaman 11Dokumen1 halamanPelajaran 45 - Pembagian Jumlah Mufidah Halaman 11Surya MiraBelum ada peringkat
- Seminar Kesehatan Tentang Bahaya Gadget Tanpa Video PDFDokumen71 halamanSeminar Kesehatan Tentang Bahaya Gadget Tanpa Video PDFSurya MiraBelum ada peringkat
- Gerakan Masyarakat Sehat (Germas)Dokumen5 halamanGerakan Masyarakat Sehat (Germas)Surya MiraBelum ada peringkat
- Germas - IksDokumen11 halamanGermas - IksSurya MiraBelum ada peringkat