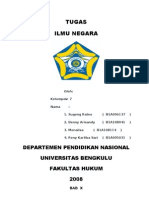Implikasi Dari Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Terhadap Hubungan Bilateral Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima
Implikasi Dari Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Terhadap Hubungan Bilateral Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima
Diunggah oleh
Nabillah SariekideHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Implikasi Dari Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Terhadap Hubungan Bilateral Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima
Implikasi Dari Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Terhadap Hubungan Bilateral Antara Negara Pengirim Dan Negara Penerima
Diunggah oleh
Nabillah SariekideHak Cipta:
Format Tersedia
1
BAB. I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Negara merupakan salah satu subyek hukum internasional, di antara subyek hukum yang lainnya yaitu: Organisasi internasional, palang merah internasional, tahta suci atau vatikan, organisasi pembebasan atau bangsa bangsa yang sedang memperjuangkan hak-haknya, wilayah-wilayah
perwalian, kaum beliigerensi dan individu.1 Negara merupakan subjek hukum yang paling utama2. Menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara mensyaratkan suatu negara dengan karakteristik memiliki penduduk yang tetap, pada wilayah tertentu, memiliki pemerintahan yang berdaulat dan yang ke-4 berupa kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain di luar negaranya.3 Sebagai subjek hukum internasional negara memiliki kemampuan untuk melakukan hubungan internasional,
hukum internasional dalam berbagai kehidupan masyarakat
baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai konsekuensinya maka negaralah yang paling
1 2
Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1999, h. 59. J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal 127-128. 3 Ibid.
banyak memiliki, memikul dan memegang kewajiban-kewajiban berdasarkan hukum internasional dibanding dengan subjek hukum intenasional lainnya.4 Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyebutkan tujuan dari Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-bangsa itu adalah : 2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa
berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak rakyat untuk menetukan nasib sendiri, dan mengambil tindakantindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal; 3. Mencapai kerjasama iternasional dalam memecahkan persoalanpersoalan internasional di lapangan ekonomi, social, kebudayaan, atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama, dan.. Perwujudan dari Pasal 1 ayat (2) dan (3) Piagam PBB tersebut direalisasikan dalam suatu hubungan antar-negara yang disebut dengan hubungan diplomatik dengan aturan hukum internasional yaitu Konvensi
Febi Hidayat, Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI di Myanmar Tahun 2004), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2011, hal.3
Wina 1961 yang mengatur tentang Hubungan Diplomatik. Pada pembukaan Konvensi Wina 1961 disebutkan bahwa :
Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations
Disebutkan di atas bahwa pembentukan Konvensi Wina 1961 itu sendiri ditujukan untuk menjalankan misi yang dimuat dalam Piagam PBB yang mengakui persamaan kedaulatan negara, untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia dan untuk mempromosikan hubungan pertemanan yang baik antara negara-negara. Hal inilah yang menjadi landasan hukum dibukanya suatu hubungan diplomatik. Dengan kata lain, hukum diplomatik merujuk pada norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang kedudukan dan fungsi misi diplomatik yang dipertukarkan oleh Negara-negara yang telah membina hubugan diplomatik.5 Pada masa dinasti-dinasti besar dunia praktik pengutusan perwakilan dari kerajaan untuk berkunjung ataupun melakukan misi-misi tertentu di wilayah kerajaan lain sudah banyak terjadi. Utusan yang merupakan kurir atau penyampai pesan dari raja. Baik itu di kerajaan-kerjaan
Ibid.
Romawi kuno, Siria, Byzantium, Mesir, Babilonia, India dan China memberikan perlakuan khusus terhadap utusan raja walaupun utusan tersebut hanyalah seorang kurir atau penyampai pesan dari raja. Utusan tersebut tidak boleh dibunuh, disakiti, dilukai ataupun disandera.6 Perlakuan khusus terhadap utusan perwakilan diplomatik itu menjadi suatu kebiasaan dalam hukum internasional. Seorang petugas perwakilan diplomatik memiliki imunitas dan hak-hak keistimewaan lainnya dan diberlakukan sampai saat ini. Pada masa pemrintahan Ratu Anne kerajaan Britania Raya (Inggris) 1706 Masehi yang memenjarakan Duta Besar Rusia dengan tuduhan penipuan, kemudian Kaisar Russia mengirimkan ultimatum perang kepada kerajaan Inggris karena penangkapan atas Duta Besarnya tersebut. Semenjak itu kerajaan Inggris menyatakan bahwa setiap perwakilan asing harus
dianggap suci, dan tidak dapat diganggu gugat (inviolability). 7
Pemberian kekebalan dan keistimewaan pada utusan perwakilan diplomatik ini didasarkan pada teori Functional Necessity. Menurut teori ini kekebalan dan hak-hak istimewa seorang wakil diplomatik diberikan agar wakil-wakil diplomatik dapat menjalankan tugas dan misinya dengan leluasa dan maksimal. Teori ini pula yang dianut oleh Konvensi Wina 1961. Disebutkan dalam pembukaannya atau preamble-nya dalam alinea ketiga :
Simon Szykman, Diplomacy An Historical Perspective. www.mellonuniversity.org diaakses tanggal 21 Desember 2013 7 Setyo Widagdo dan hanif Nur.S, Op. Cit, hal 79
Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States ( diartikan oleh penulis sebagai menyadari bahwa tujuan dari keistimewaan dan kekebalan tersebut tidak untuk kepentingan pribadi melainkan untuk memastikan efisiensi dari pelaksanaan fungsi dari perwakilan misi diplomatik)
Pemberian kekebalan dan keistimewaan wakil-wakil diplomatik itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi misi diplomatik. Tugas dan fungsi diplomatik ini diatur oleh Konvensi Wina 1961. Berdasarkan Pasal 3 Konvensi Wina 1961 tugas dan fungsi perwakilan diplomatik dan konsuler adalah; 1. Representasi 2. Proteksi 3. Negosiasi 4. Pelaporan 5. Peningkatan Hubungan Persahabatan Antarnegara Pemberian imunitas dan hak-hak keistimewaan tersebut tentunya berdasar atas prinsip reciprocity antarnegara.8 Jadi dengan kata lain, jika negara penerima memberikan perlakuan yang baik terhadap utusan dari negara pengirim, maka kemungkinan besar negara pengirim juga akan memberi perlakuan yang sama terhadap utusan dari negara penerima di negara
8
Ibid, hal. 80
pengirim ataupun sebaliknya. Akan tetapi, perlakuan yang baik serta imunitas dan hak-hak keistimewaan lainnya tersebut bukan berarti seorang petugas diplomatik dapat berlaku di luar batas kewajaran dan kenormalan ataupun melanggar aturan hukum dari negara penerima dengan sengaja. Para petugas diplomatik juga harus menghormati kedaulatan negara penerima dengan cara tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan kerugian ataupun mengancam serta ikut campur dalam urusan dalam negeri negara penerima. Dalam praktik hubungan diplomatik ini banyak sekali kepentingankepentingan lain di luar dari misi diplomatik yang ditugaskan dari negara pengirim. Misi diplomatik menjadi kamuflase dari misi spionase yakni melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengetahui segala aktivitas, tujuan, rencana, kapabilitas dan kelemahan-kelemahan musuh atau negara yang dituju baik melalui cara penyadapan ataupun pengiriman agenagen intelejen yang berkedok diplomat serta kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan hukum internasional. Tugas dan misi dari hubungan diplomatik yang memberikan kekebalan dan hak-hak istimewa kepada wakil diplomatik ini disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar misi yang seharusnya. Banyak kasus-kasus yang terjadi dari penyimpangan-
penyimpangan tugas dan fungsi diplomatik itu sendiri, seperti kasus penyadapan di kedutaan-kedutaan besar, kasus spionase yang banyak terjadi
pada masa perang dunia,dan lain-lain. Contoh kasus adalah Ryan Fogle yaitu seorang agen CIA (Central Intellegence Agency atau badan
intelijen pemerintah federal Amerika Serikat) yang didelegasikan oleh pemerintah Amerika untuk berperan ganda sebagai petugas atau staf diplomatik di kedutaan Amerika di Negara Rusia yang akhirnya dapat diketahui dan ditangkap oleh FSB (Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Federal Security Service atau dinas kontra-intelijen Rusia).9 Pada tahun 2006, terdapat kasus seorang atase Angkatan Laut Kedutaan Besar Amerika Serikat di Venezuela dituduh melakukan praktik mata-mata berkedok misi diplomatik.10 Begitu juga kasus penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap Indonesia yang baru diketahui publik melalui pengakuan dari Edward Snowden yaitu mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) yang membocorkan data rahasia NSA. Tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Australia ini bertentangan dengan Konvensi Wina 1961 tentang cara-cara yang dibenarkan untuk mendapatkan informasi mengenai negara penerima dalam hubungan diplomatik. Dengan kemajuan teknologi dan kurangnya aturan hukum yang mengatur tentang tindakan penyadapan sangat memudahkan praktek-praktek
9
Kompasioner, Spionase Fogle di Rusia: Keberhasilan FSB vs Kegagalan CIA, http://luarnegeri.kompasiana.com, di upload tanggal 21 Mei 2013 Rita Uli Hutapea, AS-Venezuela Saling Usir Diplomat, http://news.detik.com, Sabtu, 04/02/2006 11:10 WIB
10
seperti ini. Terutama untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia yang memiliki teknologi yang lebih tinggi dari teknologi Indonesia. Tindakan penyadapan seperti yang dilakukan oleh perwakilan Diplomatik Australia tersebut tentunya mencedrai hubungan baik antar kedua negara. Perbuatan tersebut juga tidak sesuai dengan prinsip umum dibentuknya suatu perjanjian termasuk perjanjian untuk membuka hubungan diplomatik harus berdasarkan tujuan atau niat yang baik dan tidak bertentangan dengan hukum serta tidak sesuai dengan prinsip bertetangga yang baik antar-negara yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia. Oleh Karena banyaknya kasuskasus penyelewengan fungsi dan misi diplomatik seperti yang telah dijelaskan di atas. Termasuk penyelewengan yang berhubungan dengan praktik penyadapan yang banyak dikecam oleh negara-negara, namun tetap saja terjadi dan dilakukan oleh hampir setiap negara. Melihat dari hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi IMPLIKASI DARI PRAKTIK PENYADAPAN DALAM HUBUNGAN
DIPLOMATIK TERHADAP HUBUNGAN BILATERAL ANTARA NEGARA PENGIRIM DAN NEGARA PENERIMA (Studi Kasus Penyadapan Australia atas Pejabat Negara Indonesia 2013) B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana peranan hukum internasional khususnya konvensi wina 1961 dalam mengatur masalah penyadapan antar negara?
2. Tindakan apakah yang dapat dilakukan oleh negara penerima sebagai akibat dari praktik penyadapan kepada negara pengirim berdasarkan hukum internasional? 3. Bagaimakah pengaturan hukum di Indonesia mengenai tindakan spionase dari seorang perwakilan diplomatik? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui aturan Hukum Internasional mengenai spionase dalam hubungan diplomatik berdasarkan konvensi Wina 1961? 2. Untuk mengetahui tindakan lain yang diatur oleh hukum intrnasional yang dapat dilakukan oleh negara penerima terhadap wakil diplomatik negara pengirim selain Persona non-Grata? 3. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang praktik spionase di Indonesia? D. Manfaat Penelitian Peniliti berharap penelitian ini memiliki manfaat praktis maupun manfaat akademis bagi segenap civitas academica maupun masyarakat umum yang berminat terhadap masalah-masalah spionase serta hukum diplomatik dan konsuler :
1. Manfaat Teoritis
10
a. Agar menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang penguasaaan tentang hukum internasional serta hukum diplomatik dan konsuler. b. Agar mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dari negara yang yang melakukan tindakan spionase terhadap negara lain melalui misi diplomatiknya. c. Agar mengetahui bagaimana hukum internasional mengatur tentang praktik spionase yang banyak terjadi hamper di setiap negara. d. Agar dapat menerapkan pengetahuan tentang hukum internasional dan hukum diplomatik dan konsuler yang didapat selama masa perkuliahan.
2. Manfaat Praktis
a. Diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum linternasional dan hukum diplomatik dan konsuler di Indonesia. b. Dapat menjadi pertimbangan bagi negara-negara yang mengalami kerugian berupa informasi penting yang disadap oleh negara lain di wilayah negaranya sebagai akibat tindakan spionase yang dilakukan oleh perwakilan diplomatik negara lain. c. Menjadi bahan referensi bagi pembaca, baik mahasiswa, maupun dosen ataupun masyarakat umum sehubungan dengan hukum diplomatik dan konsuler.
11
E. Kerangka Pemikiran a. Teori Dasar Pemberian Kekebalan dan Keistimewaan Diplomatik 1) Teori Fungsional (Functional Necessity Theory) Functional Necessity Theory dalam bahasa Indonesia disebut teori kebutuhan fungsional. Menurut teori ini, hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik perlu diberikan kepada diplomat agar dapat melaksanakan fungsinya secara optimal sehingga hasil pekerjaannya memuaskan negara penerima dan negara pengirim.11
Hak-hak keistimewaan lainnya yang dimiliki oleh seorang pejabat diplomatik sesuai dengan yang dimuat oleh Pasal 27 Konvensi Wina 1961 antara lain adalah freedom of communication kebebasan berkomunikasi. Kebebasan berkomunikasi yang dimaksud adalah para pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya mempunyai kebebasan penuh dan dalam kerahasian untuk berkomunikasi dengan pemerintahnya. Kebebasan berkomunikasi ini juga berlaku bagi semua korespondensi resmi antara suatu perwakilan dengan pemerintahnya dan kebebasan ini harus dilindungi oleh negara penerima. Surat menyurat para pejabat diplomatik tidak boleh digeledah, ditahan atau disensor oleh negara penerima. Suatu perwakilan asing dapat menggunakan kode dan sandi rahasia dalam
11
Ibid, hal. 120
12
komunikasinya dengan pusat sedangkan instalasi radio dan pemancar radio hanya dapat dilakukan atas izin negara setempat.12 b. Pasal 41 Ayat (3) Konvensi Wina 1961 yang berbunyi Gedung (kantor) perwakilan diplomatik tidak boleh digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsi misi sebagaimana dituangkan di dalam konvensi ini atau aturan umum hukum internasional atau oleh perjanjian khusus yang berlaku diantara negara pengirim dan negara penerima. Dengan ketentuan yang terdapat pada pasal ini terlihat bahwa bisa bertindaknya aparat keamanan terhadap perwakilan negara asing hanya terbatas pada tindakan-tindakan yang dianggap membahayakan. c. Teori Par Im Paren Non Habet Imperium Maksudnya adalah negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya, yang dalam hal ini kepala perwakilan diplomatik.13 Artinya negara pengirim tudak dapat menerapkan yursdiksi hukum negaranya di wilayah negara penerima. Pemberian keistimewaankeistimewaan seorang pejabat diplomatik itu didasarkan pada hukum kebiasaan internasional guna memberikan keleluasaan seorang pejabat diplomatik dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, baik negara pengirim ataupun pejabat diplomatik tidak dapat berlaku sewenang12
Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik: Kekebalan dan keistimewaanya , Angkasa, Bandung, 1991, hal. 39 13 A. Mansyur Effendi, Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara, IKIP Malang, 1994, hal. 44
13
wenang dengan mengenyampingkan hukum negara penerima seperti melakukan penyadapan. d. Azas Resiprositas Teori ini didasarkan pada tindakan yang dilakukan atas dasar hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak negara, yakni dalam hal ini negara penerima maupun negara pengirim. Jadi dengan adanya perwakilan diplomatik antar kedua negara, menyebabkan terdapat adanya hubungan yang saling timbal balik dan tentunya saling menguntungkan antara masing-masing pihak. Jadi, jika suatu negara menginginkan suatu perlakuan yang baik dari negara lain, maka negara tersebut juga harus memberi perlakuan yang baik terhadap negara yang bersangkutan.14 e. Pertanggungjawaban Negara Hukum internasional merupakan hukum yang pada dasarnya mengatur hubungan antar negara-negara. Kaitannya dengan hukum
pertanggungjawaban yaitu dengan cirri utamanya, menempatkan negara sebagai subyek utama. Hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam pasal pertama mengenai tanggung jawab dalam hukum internasional oleh the International Law Commission atau Komisi Hukum Internasional (yang selanjutnya disingkat dengan ILC), yang menyatakan: setiap tindakan negara yang salah secara internasional membebani kewajiban negara
14
Eddy O.S. Hiariej,Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 41
14
bersangkutan (every internationally wrongfull act of a state entails the international responsibility of that state).15 Tanggung jawab muncul diakibatkan oleh pelanggaran atas hukum internasional. Suatu negara tersebut melakukan pelanggaran atas perjanjian internasional, yang mana dalam kasus tersebut diatas yang terjadi adalah pelanggaran terhadap kekebalan berkomunikasi oleh negara penerima. Pertanggungjawaban negara berbeda-beda kadarnya tergantung pada kewajiban yang diembannya atau besar kerugian yang telah ditimbulkan. Semua hak yang berkarakter internasional memiliki pertanggungjawaban internasional. f. Azas Pacta Sunt Servanda Berdasarkan teori ini bahwa suatu perjanjian internasional adalah dianggap sebagai undang-undang oleh para pihak-pihak yang telah membuat perjanjian tersebut dan segera meratifikasinya menjadi hukum nasional di negara mereka masing-masing. Prinsip ini juga mensyaratkan bahwa kesepakatan atau perjanjian yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.16 g. Teori-teori Mengenai Hubungan Antara Hukum Internasional dan Hukum Nasional Teori Monisme
15
J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional kontemporer, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal.196 16 J.B. Daliyo, et. al., Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prehallindo, Jakarta, 1987, hlm. 205.
15
Teori mengatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem, yaitu hukum pada umumnya. Semua hukum dianggap sebagai suatu ketentuan tunggal yang tersusun dari kaidah-kaidah hukum yang mengikat negara-negara, individu-individu, atau kesatuan-kesatuan lain yang bukan negara.17 Anggapan demikian didasarkan pada karakteristik isi dari hukum itu sendiri. Hukum nasional dan hukum internasional merupakan bagian dari himpunan peraturan yang universal, yang mengikat semua oknum, baik secara kolektif maupun secara individual. Teori Dualisme Hukum nasional dan hukum internasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda sama sekali, hukum internasional dan hukum nasional berbeda sama sekali secara instrinsik. Menurut Triepel, terdapat perbedaan fundamental di antara kedua sistem hukum tersebut, yaitu : a) Subyek-subyek hukum nasional adalah individu-individu, sedangkan subyek-subyek hukum internasional adalah
semata-mata dan secara ekslusif hanya negara-negara. b) Sumber-sumber hukum keduanya berbeda : sumber hukum nasional adalah kehendak negara itu sendiri, sumber hukum
17
J. G. Starke, Op. Cit, hal 98
16
internasional adalah kehendak bersama (gemenwille) dari negara-negara.18
Menurut Anziloti hukum internasional dan hukum nasional berbeda menurut prinsip-prinsip fundamental dengan mana masing-masing sistem itu ditentukan. Pentaatan terhadap perundang-undangan negara didasarkan pada prinsip atau norma fundamental, sedangkan pentaatan terhadap hukum internasional didasarkan pada azas pacta sunt servanda.19
h. Teori Tarnsformasi dan teori delegasi Teori transformasi Teori ini membedakan antara traktat yang bersifat janji (promises) dengan undang-undang yang bersifat perintah (command). Akibat dari perbedaan mendasar ini adalah diperlukannya suatu transformasi dari satu tipe kepada tipe yang lain baik secara formal maupun secara subtantif.20 Teori delegasi Menurut teori ini ada pendelegasian dari hukum internasional kepada konstitusi hukum nasional mengenai hak-hak pemberlakuan traktat atau konvensi. Mengenai prosedur atau cara-cara pengadopsian
18 19
Triepel, dalam J.G. Starke. Op. Cit, hal 97 Ibid. 20 Ibid, hal 102
17
hukum internasional ke hukum nasional merupakan diskresi negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Prosedur ratifikasi dan asas publisitas yang bervariasi. Teori ini pula yang dianut oleh Indonesia.
F. METODE PENELITIAN 1. Metode Pendekatan Dalam penulisan karya tulis ini akan digunakan pendekatan Yuridis Normatif, atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.21 Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:22 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum 2. Penelitian terhadap sistematik hukum 3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal 4. Perbandingan hukum 5. Sejarah hukum 2. Jenis Data Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):
21
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13-14 22 Ibid, hal. 14
18
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat pokok yang menjadi acuan dasar penulisan skripsi ini.14 Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi dan petusan-putusan hakim.
b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.16 Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan lain sebagainya. 3. Metode Pengumpulan Data Agar didapat hasil yang baik, maka perlu didukung dengan tersedianya data yang cukup dan akurat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari data sekunder seperti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, literatur hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, buku-buku, majalah, tesis, makalah dan sebagainya, yang peneliti temukan pada:
19
a. Perpustakaan Universitas Negeri Padjajaran Bandung b. Perpustakaan Universitas Islam Bandung c. Buku-buku dan jurnal koleksi dosen d. Buku-buku, majalah, dan literatur hukum koleksi pribadi penulis 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data Adapun pengolahan dan Analisis data yang digunkan adalah Analisis Kualitatif, yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka, tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar hukum, literature hukum, hasil-hasil penelitian, perjanjian internasional/konvensi, dan sebagainya.
G. SISTEMATIKA PENULISAN Sistematika penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yang masingmasing bab terdiri atas ;
BAB I. Pendahuluan
Bab ini berisi uraian latar belakang dari pokok permasalahan. Sub bab nya terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
20
BAB II. Tinjauan Pustaka
Pada bab ini dikaji teori-teori ilmiah yang berhubungan dengan konsep-konsep yang dipermasalahkan dan dipakai dalam analisis terhadap masalah yang diteliti. Kajiannya mencakup negara sebagai subyek hukum internasional, syarat-syarat berdirinya sebuah negara, hubungan dan hukum diplomatik, tugas dan fungsi misi diplomatik, penyelesaian permasalahan diplomatik.
BAB III. Metode Penelitian
Pada bab ini diuraikan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, yang dihubungkan dengan fakta-fakta dari berbagai sumber mengenai tindakan penyadapan dan spionase yang dilakukan oleh kedutaan Amerika Serikat dan Australia di Indonesia.
BAB IV. Hasil Pembahasan dan Kegunaan Pada bab ini ditulis laporan rinci pelaksanaan kegiatan penelitian berikut hasil-hasil penelitian yang dikumpulkan dan dianalisis dari bahan-bahan hukum yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan melihat ketentuanketentuan hukum lingkungan internasional dan hukum humaniter,
21
buku-buku, jurnal, artikel berita, yurisprudensi serta teori-teori para sarjana yang dijadikan sumber kebiasaan dalam hukum
internasional yang berkaitan dengan masalah yang akana dibahas.
BAB V. Penutup Mengemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis babbab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran atas analisis yang dilakukan berdasarkan pokok-pokok permasalahan.
22
DAFTAR PUSTAKA Daliyo, J.B. et. al., Pengantar Hukum Indonesia, PT. Prehallindo, Jakarta, 1987. Eddy O.S. Hiariej,Pengantar Hukum Pidana Internasional, Erlangga, Jakarta, 2009. Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, Hukum Diplomatik: Kekebalan dan keistimewaanya, Angkasa, Bandung, 1991. J. Thontowi dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, 2006. Quincy Wright The Study of International Relations dalam Setyo Widagdo dan Hanif Nur Hukum diplomatik dan Konsuler, Bayumedia, Malang, 2008. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009. Starke, J. G. Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988. Syahmin, Ak, Hukum Diplomatik dalam Kerangka Studi Analisis, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Parthiana, Wayan, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung, 1999. A. Mansyur Effendi, Hukum Konsuler, Hukum Diplomatik serta Hak dan Kewajiban Wakil-Wakil Organisasi Internasional/Negara, IKIP Malang, 1994.
23
Febi Hidayat, Pertanggungjawaban Negara Atas Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik Ditinjau dari Aspek Hukum Internasional (Studi Kasus Penyadapan KBRI di Myanmar Tahun 2004), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Sumatera Barat, 2011. Hutapea, Rita Uli, AS-Venezuela Saling Usir Diplomat, http://news.detik.com, 2006. Kompasioner, Spionase Fogle di Rusia: Keberhasilan FSB vs Kegagalan CIA, http://luar-negeri.kompasiana.com, di upload tanggal 21 Mei 2013. Konvensi Montevideo 1933 tentang Hak-hak dan Kewajiban Negara Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 1973
24
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Hukum Diplomatik Hukum diplomatik sebelum menjadi hukum tekstual yang dituangkan dalam Konvensi Wina 1961 merupakan hukum kebiasaan internasional yang sudah dikenal dan dilakukan oleh kerajaaan-kerajaan kuno di dunia. Pertukaran misi diplomatik ataupun utusan dari kerajaan menjadi agenda dari kerajaan. Sejarah membuktikan bahwa jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal dan menjalankan praktik hubungan diplomatik secara tetap seperti yang ada sekarang, pada zaman India Kuno telah dikenal ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang mengatur hubungan antar raja-raja ataupun kerajaan, dimana hukum bangsa-bangsa pada waktu itu telah mengenal istilah duta.23 Penerimaan duta-duta ke negara asing sudah dikenal di kerajaankerajaan Indonesia dan negara-ngera Asia serta Arab sebelum negara-negara barat mengetahuinya. Di benua Eropa, baru pada abad ke-16 soal pengiriman dan penempatan duta itu diatur menurut hukum kebiasaan.24 Karena banyaknya kepentingan negara yang diatur dalam hukum kebiasaan internasional mengenai hubungan diplomatik, barulah pada abad ke-19 pembicaraan tentang pengkodifikasian hukum diplomatik ini dilakukan,
23
Setyo widagdo dan Hanif Nur,Hukum Diplomatik dan Konsuler, Bayumedia, Bandung, 2008, hal Ibid.
9.
24
25
dimulai dengan Konvensi Wina 1815, kemudian Protokol Aixla-Chapelle 1818. Pada saat telah dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa usaha untuk mengkodifikasi aturan hukum tekstual mengenai hukum diplomatik ini masih dilanjutkan yakni pada tahun 1927, konfrensi Den Haag 1930. Kemudian setelah terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Komisi Hukum Internasional merancang aturan-aturan hukum diplomatik 1949-1979. Keluarlah hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik yaitu tanggal 2 Maret sampai 14 April 1961 atau dieknal dengan Konvensi Wina 1961 dan Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Negara merupakan subyek hukum utama hukum internasional, oleh karena itu negara dapat melakukan tindakan hukum layaknya subyek hukum lainnya. Salah satunya adalah membuka hubungan diplomatik dengan negara lain. Namun, berdasarkan Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 mengenai Hakhak dan Kewajiban-kewajiban Negara mensyaratkan suatu negara yang dapat dikatakan sebagai subyek hukum internasional harus memenuhi karateristikkarakterstik sebagai berikut : a. Memiliki penduduk tetap Artinya dalam hal ini dalam suatu negara haruslah memiliki penduduk yang tinggal, dan terdaftar tetap sebagai warga negara dari negara tersebut dan bukan merupakan penduduk yang bersifat sementara kemudian berpindah kepada negara lain. b. Wilayah tertentu
26
Sebuah negara haruslah memiliki wilayah territorial yang jelas dan permanen. Dimana negara itu nanti akan menjalankan yurisdiksi hukumnya pada wilayah tersebut. Seperti halnya Negara Indonesia yang memiliki ribuan pulau yang menyebar dari Sabang sampai Merauke serta kepemilikan atas wilayah laut yang memisahkan pulaupulau di Indonesia. c. Pemerintahan yang berdaulat Suatu negara harus dipimpin dan dijalankan oleh suatu rezim pemerintahan. Baik itu bentuk negara monarki ataupun republik atau dengan sistem pemerintahan presidensiil ataupun parlementer. d. Kemampuan untuk melakukan hubungan dengan negara lain Dalam hukum internasional, syarat (d) merupakan syarat yang paling penting. Suatu negara harus memiliki kemampuan untuk
menyelenggarakan hubungan-hubungan ekstern dengan negara-negara lain. Hal ini yang membedakan negara dalam arti sesungguhnya dari unit-unit yang lebih kecil seperti anggota-anggota suatu federasi, atau protektorat-protektorat, yang tidak mengurus hubungan-hubungan luar negerinya sendiri, dan tidak diakui oleh negara-negara lain sebagai anggota masyarakat internasional yang sepenuhnya mandiri.25
J. G. Starke, Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hal 127-128.
25
27
Syarat (d) di atas dapat menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu negara yaitu berinteraksi dengan negara lain, salah satunya adalah dengan melakukan hubungan kerjasama dan diplomatik. Hubungan
internasional atau lintas negara semacam ini harus dilandasi dengan maksud dan tujuan-tujuan yang baik (good offices). Menurut Hugo de Groot, bahwa dalam hubungan internasional asas persamaan derajat merupakan dasar yang menjadi kemauan bebas dan persetujuan dari beberapa atau semua negara. Tujuannya adalah untuk kepentingan bersama dari mereka yang menyatukan diri di dalamnya. Dalam hubungan internasional, dikenal beberapa asas yang didasarkan pada daerah dan ruang lingkup berlakunya ketentuan hukum bagi daerah dan warga negara masing-masing. a. Asas Teritorial Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional) sepenuhnya. b. Asas Kebangsaan Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara untuk warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara di manapun ia berada, tetap menapat perlakuan hukum dari negaranya. Asas ini mempunyai
28
kekuatan exteritorial. Artinya hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya, walaupun berada di negara asing. c. Asas Kepentingan Umum Asas ini didasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Apabila ketiga asas ini tidak diperhatikan, akan timbul kekacauan hukum dalam hubungan antar bangsa (internasional). Oleh sebab itu, antara satu negara dengan negara lain perlua ada hubungan yang teratur dan tertib dalam bentuk hukum internasional. Walaupun demikian, kerapkali masih terdapat masalah dan pertikaian-pertikaian yang perlu dipecahkan. Misalnya persoalan dwi-kewarganegaraan, batas-batas negara, wajib militer dan wajib pajak.26 Hubungan internasional ini memiliki banyak cabang, salah satunya adalah hubungan diplomatik. Berasal dari kata diplomacy yang memiliki arti yang berbeda-beda dari para ahli. Sir ernest Satow memberikan batasan diplomasi sebagai berikut.
Tumija Adi Prawira, Hubungan Internasional, www.ayobelajar.com, di upload tanggal 15 Maret 2011
26
29
Application of intelligence and tact to conduct of official relations between the Goverments of independent states, extending sometimes also to their relations with vassal states or more briefly still, the conduct of business between states by peaceful means.27 (diterjemahkan oleh penulis yaitu caracara atau kemampuan dan keahlian untuk mengadakan hubungan resmi antarpemerintahan dari suatu negara yang berdaulat, bahkan dengan negara-negara yang dijajah atau sedang memperjuangkan kemerdekaannya, dengan cara dan tujuan untuk perdamaian). Kemudian Quency Wright dalam bukunya The study of International Relaions memberikan batasan dalam dua hal. 1) The employment of tact, shrewdness and skill in any negotiation or transaction (kemampuan dari kebijaksanaan, kelihaian dan
keterampilan dalam setiap negosiasi atau transaksi) 2) The art of negotiation in order to achieve the maximum of cost within a system of politics in which war is a possibility.28( seni dari negosiasi dalam usaha pencapaian nilai tertinggi dalam suatu sistem politik di mana perang menjadi kemungkinan terbesar yang akan terjadi).29
Husni Syam, SH., LL.M, Hukum Diplomatik dan Konsuler, hand out bahan kuliah tanggal 6 Oktober 2013, hal 2 28 Quincy Wright The Study of International Relations dalam Setyo Widagdo dan Hanif Nur Hukum diplomatik dan Konsuler, Bayumedia, Malang, 2008, hal. 5 29 Setyo Widagdo dan Hanif Nur, Op. Cit, hal 5.
27
30
Hubungan diplomatik ini diatur oleh hukum diplomatik, hukum diplomatik itu sendiri merupakan cabang hukum internasional yang terdiri dari seperangkat aturan-aturan dan norma-norma hukum yang menetapkan kedudukan dan fungsi para diplomat termasuk bentuk-bentuk organisasional dari dinas diplomatik.30 Pengertian hukum diplomatik pada hakekatnya merupakan ketentuan-ketentuan atau prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur hubungan diplomatik antar negara yang dilakukan atas dasar permufakatan bersama dan ketentuan atau prinsip tersebut dituangkan dalam instrumen-instrumen hukum sebagai hasil kodifikasi hukum kebiasaan internasional dan pengembangan hukum internasional.31 Sumber hukum dari hukum diplomatik selalin yang dimuat dalam Pasal 38 Statuta mahkamah Internasional antara lain ; 1. The Final Act of The Congress of Vienna (1815) on Diplomatic Ranks; 2. Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol (1961), termasuk di dalamnya: a. Vienna Convention on Diplomatic Relations; b. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality c. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 3. Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol 1963, yang memuat :
30 31
Jan Osmancyk, dalam Husni Syam, Op. Cit hal 3 Sumaryo Suryokusumo. Hukum Dilomatik, Teori dan Kasus, Alumni, Bandung, 2005, hal.5.
31
a. Vienna Convention on Consular Relations; b. Optional Protocol Concerning Acquisition of Nationality; c. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 4. Convention on Special Mission and Optional Protocol (1969), yang di dalamnya memuat : a. Convention on Special Mission; b. Optional Protocol Concerning the Compulsory Settlement of Disputes 5. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes against Internatioally Protected Persons, including Diplomtic Agents (1973) 6. Vienna Convention on the Reperesentation of State in their Relations with International Organization of a Universal Character (1975).32 B. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Diplomatik 1. Mutual Consent/ Kesepakatan Menurut Pasal 2 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa : The establishment of diplomatic relations between States, and of permanent diplomatic missions, takes place by mutual consent. (diterjemahkan oleh penulis sebagai syarat untuk membuka hubungan diplomatik antar-negara dan melaksanakan misi-misi diplomatik yang bersifat permanen (bukan misi khusus yang bersifat ad hoc) harus berdasarkan kesepakatan bersama).
32
Setyo Widagdo dan Hanif Nur, Op. Cit, hal 16
32
Untuk membuka suatu hubungan diplomatik harus berdasarkan kesepakatan dari negara pengirim dan negara penerima misi dan pejabat diplomatik. Harus ada prosedur pendelegasian pejabat diplmatik danada penerimaan resmi dari negara atau pemerintahan negara dimana suatu misi diplomatik akan diakreditasikan. Untuk itu pembukaan suatu hubungan diplomatik merupakan hak dari negara (Right to Legation) 2. Inviolabilitas Pasal 29 Konvensi Wina 1961 menyatakan bahwa : The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not liable to any form of arrest or detention. The receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to pre-vent any attack on his person, freedom or dignity. (Diterjemahkan oleh penulis sebagai seorang utusan diplomatik harus tidak dapat diganggu gugat. Dia tidak dapat dikenakan penahanan atau penghukuman dalam bentuk lainnya. Negara penerima harus memperlakukan utusan perwakilan diplomatik dengan hormat dan melakukan segala bentuk tindakan yang diperlukan untuk mencegah tindakan kekerasan atau tindakan lain yang dapat mengancam kebebasan dan kehormatannya) Pengaturan mengenai inviolabilitas ini diatur dalam pasal 22-29 Konvensi Wina 1961. Inviolability diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan kekebalan terhadap segala
33
gangguan yang merugikan sehingga di sini terkandung pengertian memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari alat-alat kekuasaan negara penerima. Sementara Immunity diartikan sebagai kekebalan terhadap yurisdiksi dari negara penerima, baik hukum pidana maupun perdata.33 3. Reasonable and Normal
33
Setyo Widagdo dan Hanif Nur.s, Op. Cit, hal 100
Anda mungkin juga menyukai
- ProjectDokumen75 halamanProjectNabillah SariekideBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen8 halaman1 SMKasih KaruniaBelum ada peringkat
- Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut KonvensiDokumen16 halamanTanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Pejabat Diplomatik Menurut Konvensibayu teBelum ada peringkat
- XXXXXDokumen13 halamanXXXXXMellisa Rolys PurbaBelum ada peringkat
- 1 SMDokumen9 halaman1 SMNur Amaliyah PutriBelum ada peringkat
- Tugas Hukum Internasional Sesi 5Dokumen13 halamanTugas Hukum Internasional Sesi 5jaka ramdhaniBelum ada peringkat
- Latar Belakang Hak Kekebalan Dan Keistim-DikonversiDokumen17 halamanLatar Belakang Hak Kekebalan Dan Keistim-DikonversiJosua RobertoBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan A. Latar BelakangDokumen15 halamanBab I Pendahuluan A. Latar Belakangekanovya pBelum ada peringkat
- Skripsi Yulifia RefraDokumen56 halamanSkripsi Yulifia RefraOnaViiBelum ada peringkat
- Artikel DiplomatikDokumen9 halamanArtikel DiplomatikSefrin Nur SabilaBelum ada peringkat
- Tugas Proposal-2Dokumen17 halamanTugas Proposal-2OnaViiBelum ada peringkat
- Inisiasi 8-HUKUM DIPLOMATIK Dan KONSULER - RhsDokumen11 halamanInisiasi 8-HUKUM DIPLOMATIK Dan KONSULER - RhsRuth SimatupangBelum ada peringkat
- Kasus PersonanongrataDokumen5 halamanKasus Personanongratapeel bananaBelum ada peringkat
- Revisian Proposal AccDokumen31 halamanRevisian Proposal AccTeguh Prasetyo AjiBelum ada peringkat
- BLOCKBOOK H.DiplomtkDokumen39 halamanBLOCKBOOK H.Diplomtkhantu pocongBelum ada peringkat
- Bab I: Setyo Widgago Dan Hanifa Nur W, Hukum Diplomatik Dan Konsuler, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hal 38Dokumen18 halamanBab I: Setyo Widgago Dan Hanifa Nur W, Hukum Diplomatik Dan Konsuler, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, Hal 38Andi Nurfadilla SulmiantiBelum ada peringkat
- Tugas DiplomatikDokumen6 halamanTugas DiplomatikDesi nataliaBelum ada peringkat
- Tugas 2Dokumen5 halamanTugas 2Nurani mila utamiBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang MasalahDokumen23 halamanBab I Pendahuluan A. Latar Belakang Masalahcatwater006Belum ada peringkat
- Hukum DilomatikDokumen23 halamanHukum DilomatikZahrah Zafirah AnwarBelum ada peringkat
- Pelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik AtaDokumen23 halamanPelanggaran Hak Kekebalan Diplomatik AtaKireinaBelum ada peringkat
- ANALISIS (Parafrase 3)Dokumen19 halamanANALISIS (Parafrase 3)dinamarlina001122Belum ada peringkat
- ANALISA PENAHANAN DUTA BESAR ITALIA OLEH INDIA DENGAN PERSPEKIF HUKUM DIPLOMATIK (Hukuminternasional)Dokumen12 halamanANALISA PENAHANAN DUTA BESAR ITALIA OLEH INDIA DENGAN PERSPEKIF HUKUM DIPLOMATIK (Hukuminternasional)Adha AmirBelum ada peringkat
- Prlngan PJBTDokumen9 halamanPrlngan PJBTpeel bananaBelum ada peringkat
- 1614101004-Bab 1 PendahuluanDokumen9 halaman1614101004-Bab 1 Pendahuluan001.Abinaya NafaiqBelum ada peringkat
- Apsarihadii, 66-77 JuwitaDokumen12 halamanApsarihadii, 66-77 JuwitaAmanda OctaveraBelum ada peringkat
- Tugas 2Dokumen5 halamanTugas 2Nurani mila utamiBelum ada peringkat
- Hukum DiplomatikDokumen41 halamanHukum DiplomatikTyaBelum ada peringkat
- TERBARUDokumen25 halamanTERBARUTeguh Prasetyo AjiBelum ada peringkat
- Kelompok DiplomatikDokumen24 halamanKelompok DiplomatikDea SyuciBelum ada peringkat
- Apsarihadii, 4 - KOMANG SUKANIASA 157 - 169 PDFDokumen13 halamanApsarihadii, 4 - KOMANG SUKANIASA 157 - 169 PDFBettyBelum ada peringkat
- Hukin IsiDokumen54 halamanHukin IsiDina Pratiwi SianturiBelum ada peringkat
- B011201030 - Khulaifi HamdaniDokumen5 halamanB011201030 - Khulaifi HamdaniKhulaifi AlfariziBelum ada peringkat
- 1 PBDokumen17 halaman1 PBAnggaBelum ada peringkat
- Tiara Anggita Noverina - A1012191194 - Uas Hukum Diplomatik&konsuler - B PpapkDokumen3 halamanTiara Anggita Noverina - A1012191194 - Uas Hukum Diplomatik&konsuler - B PpapkadebudipamungkasBelum ada peringkat
- DiplomatikDokumen11 halamanDiplomatiklabscinereBelum ada peringkat
- Dasar Hukum DiplomasiDokumen2 halamanDasar Hukum DiplomasiIsma Zul AbdilahBelum ada peringkat
- ID Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan ImmunDokumen18 halamanID Akibat Hukum Penanggalan Kekebalan ImmunRakha Aditya putraBelum ada peringkat
- Tugas 2 Hukum InternasionalDokumen3 halamanTugas 2 Hukum InternasionalOdeh OpdianaBelum ada peringkat
- Bagaimana Individu Mendapat Tempat Dalam Hubungan InternasionalDokumen5 halamanBagaimana Individu Mendapat Tempat Dalam Hubungan InternasionalAd Agung SulistyoBelum ada peringkat
- Pengantar Hukum Internasional MakalahDokumen8 halamanPengantar Hukum Internasional MakalahAminah TuzahariaBelum ada peringkat
- Fungsi Konsuler Jika Seorang Wni Terkena Kasus Tindak Pidana Hukuman Mati Di Negara Lain.Dokumen8 halamanFungsi Konsuler Jika Seorang Wni Terkena Kasus Tindak Pidana Hukuman Mati Di Negara Lain.AsharramdhanBelum ada peringkat
- Perlindungan Terhadap Warga Negara Asing Dikaitkan Dengan Prinsip Yurisdiksi EkstraterritorialDokumen22 halamanPerlindungan Terhadap Warga Negara Asing Dikaitkan Dengan Prinsip Yurisdiksi EkstraterritorialMuhammad YahusafatBelum ada peringkat
- Hukum Diplomatik Dan KonsulerDokumen48 halamanHukum Diplomatik Dan KonsulerWira PratamaBelum ada peringkat
- Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Credential Letter Duta Besar Indonesia Untuk Brasil Menurut Konvensi Wina 1961 Tentang DiplomatikDokumen13 halamanAnalisis Yuridis Terhadap Penolakan Credential Letter Duta Besar Indonesia Untuk Brasil Menurut Konvensi Wina 1961 Tentang DiplomatikRaihan RamadhillahBelum ada peringkat
- Hak Istimewa Dan Kekebalan Perwakilan DiplomatikDokumen5 halamanHak Istimewa Dan Kekebalan Perwakilan DiplomatikAgung SyaputraBelum ada peringkat
- Suaka Diplomatik (KLP 11)Dokumen16 halamanSuaka Diplomatik (KLP 11)Wahudi YudiBelum ada peringkat
- Penyelesaian Kasus Hubungan DiplomatikDokumen19 halamanPenyelesaian Kasus Hubungan DiplomatikSagung DindaBelum ada peringkat
- 001 - Penyalahgunaan Hak Diplomatik Arab Di Jerman 2009 - Kelompok WahyuDokumen13 halaman001 - Penyalahgunaan Hak Diplomatik Arab Di Jerman 2009 - Kelompok Wahyuwahyu pramujiBelum ada peringkat
- Hukum DiplomatikDokumen4 halamanHukum DiplomatikNur khamariyahBelum ada peringkat
- Mulai Dan Berakhirnya Misi Perwakilan DiplomatikDokumen11 halamanMulai Dan Berakhirnya Misi Perwakilan DiplomatikNinis SweetBelum ada peringkat
- Contoh Makalah AcuanDokumen15 halamanContoh Makalah Acuansbz6p8xmbpBelum ada peringkat
- Bab IDokumen22 halamanBab IAl MarianaBelum ada peringkat
- Hukum Diplomatik Dan KonsulerDokumen14 halamanHukum Diplomatik Dan KonsulerekasariatiBelum ada peringkat
- Punya RendiDokumen6 halamanPunya RendiZinedin Zidan AkbarBelum ada peringkat
- Hukum InternasionalDokumen20 halamanHukum InternasionalDina Pratiwi SianturiBelum ada peringkat
- 1351 3849 1 PBDokumen8 halaman1351 3849 1 PBMuhammad IlmanBelum ada peringkat
- Hukum DiplomatikDokumen5 halamanHukum DiplomatikSuci HaerunnisaBelum ada peringkat
- Tugas Ekonomi PembangunanDokumen16 halamanTugas Ekonomi PembangunanNabillah SariekideBelum ada peringkat
- Contoh MPHDokumen33 halamanContoh MPHNabillah SariekideBelum ada peringkat
- Contoh Proposal Kegiatan 17 Agustus Tahun 2022Dokumen6 halamanContoh Proposal Kegiatan 17 Agustus Tahun 2022Nabillah SariekideBelum ada peringkat
- Surat Pernyataan PerdamaianDokumen1 halamanSurat Pernyataan PerdamaianNabillah SariekideBelum ada peringkat
- Tugas HIDokumen12 halamanTugas HINabillah SariekideBelum ada peringkat
- ProjectDokumen75 halamanProjectNabillah SariekideBelum ada peringkat
- Makalah Hukum PersDokumen11 halamanMakalah Hukum PersNabillah SariekideBelum ada peringkat
- TUGAS KuliahDokumen7 halamanTUGAS KuliahNabillah SariekideBelum ada peringkat
- Implikasi Dari Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Terhadap Hubungan Bilateral Antara Negara Pengirim Dan Negara PenerimaDokumen33 halamanImplikasi Dari Praktik Spionase Dalam Hubungan Diplomatik Terhadap Hubungan Bilateral Antara Negara Pengirim Dan Negara PenerimaNabillah Sariekide100% (1)
- Studi Kasus Ukraina Vs Rusia (Crimea Case)Dokumen4 halamanStudi Kasus Ukraina Vs Rusia (Crimea Case)Nabillah Sariekide100% (1)
- BAB X Negara Autokrasi ModernDokumen16 halamanBAB X Negara Autokrasi ModernNabillah Sariekide75% (4)