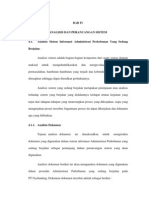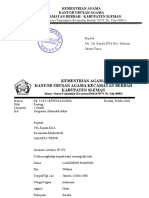Cpooo
Cpooo
Diunggah oleh
selonika_Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Cpooo
Cpooo
Diunggah oleh
selonika_Hak Cipta:
Format Tersedia
STUDI PABRIK PENGOLAH CPO
MENJADI PRODUK ANTARA
Oleh
Dina Mardhatillah
No. Mahasiswa 09.1056. MMP
MAGISTER MANAGEMENT PERKEBUNAN
INSTITUT PERTANIAN STIPER
YOGYAKARTA
2010
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis) berasal dari Afrika, didatangkan
ke Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848. Perkebunan
kelapa sawit pertama kali dibangun di Indonesia pada tahun 1911 di daerah
Sumatera Utara dengan luas 5.123 Ha. Pada tahun 1957 pemerintah Indonesia
menasionalisasikan seluruh perkebunan swasta asing termasuk perkebunan kelapa
sawit menjadi perkebunan milik pemerintah. Perkembangan kelapa sawit secara
nyata dimulai pada tahun 1967 dengan luas 144.308 ha, hingga tahun 2009 luas
perkebunan sawit mencapai 7.125.331 juta ha, dengan total produksi CPO
16.091.500 juta ton per tahun.
Diperdagangan Internasional ekspor produk perkebunan sawit Indonesia
dalam bentuk; CPO dan produk turunan, yang dimaksud produk turunan dapat
berupa produk antara dan produk hilir. Pada periode tahun 2001 - 2005 ekspor
produk antara sebesar 21.552.000 juta ton sedangkan ekspor CPO sebesar
15.931.636 juta ton. Tetapi pada periode tahun 2006 - 2009 volume ekspor
produk antara lebih rendah sebesar 24.392.000 dibandingkan volume ekspor CPO
sebesar 29.285.841. Nuryanti (2008) mengatakan kenaikan pajak ekspor CPO dan
produk antara dari tahun 2006 sebesar (1,5%) menjadi (6,5%), hal ini mendorong
produsen CPO memproduksi dan mengekspor CPO bukan produk antara, hal ini
di karenakan kenaikan pajak ekspor akan meningkatkan biaya produksi yang
berdampak kepada pay back periode.
2
Pada kenyataannya ekspor produk antara mempunyai nilai tambah yang
lebih besar dibandingkan ekspor CPO. Sugema (2007) mengatakan nilai tambah
produk CPO AS$ 458 per ton sedangkan nilai tambah produk antara AS$ 488 per
ton. Goenadi (2005) mengatakan jumlah pabrik fraksinasi CPO di Indonesia
hanya berjumlah 10 pabrik, dengan kapasitas terpasang 11 juta ton per tahun, dan
pabrik refinery di Indonesia berjumlah 46 pabrik, dengan kapasitas terpasang
masing-masing pabrik sebesar 10 juta ton per tahun (Soeharto, 2010).
Dari kenyataan diatas apakah rendahnya volume ekspor produk antara
dikarenakan pendirian pabrik pengolahan CPO menjadi produk antara
membutuhkan modal yang sangat besar untuk pembiayaan investasi dan
operasional, atau dibutuhkan sumberdaya manusia yang mampu menjalankan
manajemen serta menguasai teknologi pengolahan CPO menjadi produk antara,
atau apakah betul pajak ekspor membebani ekspor produk antara. Berdasarkan
permasalahan ini perlu dilakukan penelitian untuk memberikan informasi
investasi kebutuhan modal maupun kualifikasi sumberdaya manusia dalam
menjalankan manajemen.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:
1. Mengetahui besarnya biaya investasi dan biaya operasional pabrik
pengolahan CPO menjadi produk antara
2. Mengetahui spesifikasi maupun kualifikasi sumberdaya manusia yang
diperlukan dalam menjalankan manajemen pabrik pengolahan CPO
menjadi produk antara pada tingkat top manajer sampai ke tingkat
pelaksana.
3
II. TINJAUAN PUSTAKA
A. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit
Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis) berasal dari Afrika,
didatangkan ke Indonesia oleh pemerintahan Hindia - Belanda pada tahun
1848 (Pahan, 2005). Saat ini kelapa sawit sebagai tanaman perkebunan
menjadi sumber penghasil devisa non-migas terbesar bagi Indonesia.
Tanaman kelapa sawit mulai dikembangkan oleh pemerintah pada tahun 1967.
Berdasarkan (Tabel 1), pada periode 1967 - 1978 sebagian besar perkebunan
kelapa sawit di miliki oleh perusahaan perkebunan, baik pemerintah sekitar
98,892 ha (68,5%), dan swasta sekitar 46,235 ha (32%). Pada periode tahun
1979 - 1989 total luas area perkebunan besar baik milik pemerintah maupun
swasta 144.308 ribu ha, selain itu terdapat perkebunan milik rakyat seluas
220.707 ha (32%). Pada periode 1990 - 2000 areal Perkebunan kelapa sawit
meningkat hingga 3.031.400 juta ha yang didominasi oleh perkebunan milik
swasta seluas 1.940.101 juta ha (64%) , kemudian disusul perkebunan milik
rakyat sebesar 874.920 ribu ha (28%) dan perkebunan milik pemerintah
215.879 ribu ha (8%). Cerahnya prospek komoditi minyak kelapa sawit telah
tercermin dari peningkatan areal perkebunan sawit, pada tahun 2009 total luas
pengembangan perkebunan sawit mencapai 2.411.896 juta ha dimana
1.729.430 juta ha (72%) di kuasai oleh perkebunan rakyat, kemudian disusul
oleh perkebunan swasta seluas 522.383 ribu ha (21%), dan yang terkecil
adalah perkebunan milik pemerintah seluas 151.063 ribu ha (7%).
4
Peningkatan luas areal tersebut diikuti dengan peningkatan produksi
CPO sebagai berikut: Pada periode 1967 - 1978 produksi CPO terbesar di
hasilkan oleh perkebunan milik pemerintah sebanyak 228.71 ribu ton (97 %),
sedangkan perkebunan swasta hanya 5.905 ribu ton (3%). Pada periode tahun
1979 - 1989 produksi CPO sudah dihasilkan oleh perkebunan rakyat sebesar
182,929 ribu ton (15%), produksi CPO tertinggi masih dihasilkan oleh
perkebunan milik pemerintah sebesar 745.470 ribu ton (56%), dan swasta
sebanyak 395,315 ribu ton (29%). Pada periode 1990 - 2000 produksi CPO
tertinggi dihasilkan oleh perkebunan milik swasta sebesar 2.845.395 juta ton
(80%) sedangkan produksi CPO terendah dihasilkan dari perkebunan milik
pemerintah sebesar 186.789 ribu ton (5,2%). Pada periode tahun 2001 - 2009
produksi CPO dari perkebunan milik rakyat 3.512.123 juta ton (45%) hampir
menyamai volume produksi perkebunan swasta yaitu sebesar 3.542.765 juta
ton (46%).
Perkebunan sawit Indonesia pada periode 2001-2009 didominasi oleh
perkebunan rakyat sebesar (72%), tetapi produksi CPO perkebunan rakyat
hampir sama jumlahnya dengan perkebunan swasta yang luas perkebunannya
hanya sepertiga dari luas perkebunan rakyat. Kemungkinan perbedaan ini
disebabkan banyaknya tanaman sawit pada perkebunan rakyat yang belum
menghasilkan (TBM). Anonim ( 2006) mengatakan produksi CPO per hektar
rata-rata 2,15 ton. Pada perkebunan milik negara produksi CPO 2,77 ton/ha,
perkebunan milik swasta produksi CPO 1,87 ton/ha, dan perkebunan milik
rakyat produksi CPO hanya 1,8 ton/ha.
5
Tabel 1: Penambahan luas lahan perkebunan sawit dan produksi CPO
Periode
tahun
Luas areal (ha) Produksi CPO (ton)
Rakyat (ha) Pemerintah (ha) Swasta (ha) Total (ha) Rakyat (ton)
Pemerintah
(ton) Swasta (ton)
Total
(ton)
1967-1978 0 98,892 (68,5%) 46,416 (32%) 144,308 0 228,710 (97%) 5,905 (3%) 234,615
1979-1989 220,707 (32%) 189,620 (26%) 302,262 (42%) 712,589 182,929 (15%) 745,470 (56%) 395,315 (29%) 1,323,814
1990-2000 847,920 (28%) 215,879 (8%) 1,940,101 (64%) 3,031,111 520,703 (14%) 186,798 (5,2%)
2,845,395
(80%) 3,552,896
2001-2009 1,729,430 (72%) 151,063 (7%) 522,383 (21%) 2,411,896
3,512,123
(45%) 640,140 (8,3%) 3,542,765(46%) 7,695,028
Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan, 2009.
B. Proses pengolahan CPO menjadi produk antara
Proses pengolahan CPO menjadi produk antara merupakan tahapan
untuk menghasilkan produk-produk hilir seperti; minyak goreng, margarin,
shortening, cocoa butter, dan sabun. Proses yang dimaksud adalah refining
dan fraksinasi; yang akan menghasilkan produk seperti RBD olein, RBD
stearin, crude stearin, crude olein, dan DALMS sebagai produk samping
(Bailey, 1996). Produk ini disebut sebagai produk antara karena untuk dapat
di konsumsi masih membutuhkan pengolahan. Berdasarkan tahapan proses
dan produk yang dihasilkan ada tiga proses pengolahan;
a. Proses yang hanya melakukan refining, produk yang dihasilkan adalah
RBD palm oil dan produk samping berupa DALMS
b. Proses yang melakukan refining dan fraksinasi, produk yang dhasilkan
adalah RBD olein dan RBD stearin
c. Proses yang melakukan fraksinasi, produk yang dihasilkan adalah crude
olein, dan crude stearin.
6
Secara diagramatis masing-masing proses tersebut dapat dilihat pada
Gambar 1 sebagai berikut:
a.
b.
c.
Gambar 1: Hasil proses pengolahan CPO berdasarkan tahapan proses
(Lubis, 1992).
Keterangan (a; proses refining, b; gabungan proses refining dan fraksinasi, c; proses fraksinasi
CPO (100%) Refining RBD Palm Oil (94%)
DALMS (5%)
Fraksinasi RBD Palm Oil (94%) Refining CPO
RBD stearin
(21%)
RBD olein
(73%)
DALMS (5%)
CPO Fraksinasi Crude Strearin 20 %
Crude Olein 80%
7
Berikut ini adalah penjelasan prinsip masing-masing proses
pengolahan CPO berdasarkan tahapan proses menjadi produk antara.
1. Refining
Pada prinsipnya proses refining adalah menghilangkan kandungan
selain minyak dalam CPO seperti zat warna (pigmen), gum, senyawa odor,
dan asam lemak bebas. Pada proses refining ada tiga tahapan proses yaitu
Degumming, Bleaching, dan Steam Refining (Yussof, 2003). Masing-
masing tahapan proses tersebut adalah sebagai berikut:
a. Degumming
Tujuan degumming adalah menghilangkan gum (getah),
protein, residu karbohidrat, phospatida, dan air dalam CPO. Proses
degumming dilakukan dengan cara memanaskan minyak pada suhu
85
0
C selama 15 menit dilanjutkan penambahan asam phospat 0,1-
0,4% (ortho posporit acid). Protein dan getah akan mengalami
koogulasi; sehingga perlu dilakukan proses pengendapan dan
pemisahan antara minyak dan koogulan (Yussof, 2003).
b. Bleaching
Tujuan bleaching adalah menghilangkan kotoran penyebab
pewarnaan minyak; seperti karotenoid, maupun pigmen lain (Frasser
and Frank, 1981 cit. Yussrof, 2003). Proses bleaching dilakukan
dengan cara penambahan lempung aktif sebanyak 1,0 - 2,0% dari
jumlah minyak dalam kondisi vakum 20mm Hg - 25mm Hg pada
8
suhu 95
0
C selama 1,5 jam dan diakhiri dengan proses filtrasi (Howes,
1993 cit. Yussof, 2003),
c. Steam Refining
Tujuan steam refining adalah menghilangkan asam lemak
bebas dan senyawa penyebab bau pada minyak. Proses steam refining
dilakukan dengan cara memanaskan minyak pada suhu 240
0
C -270
0
C
dalam kondisi vakum 2 5 mmHg (Corley, 2003). Penambahan alat
stripping yang akan mempermudah lepasnya senyawa volatile dalam
minyak (Yussof , 2003).
1. Fraksinasi
Tujuan fraksinasi adalah memisahkan fraksi cair (olein) dari
fraksi padat (stearin) (Yussof, 2003). Dalam prosesnya fraksinasi di
bagi menjadi tiga macam; fraksinasi kering, fraksinasi detergen, dan
fraksinasi menggunakan sovlen (Yussof, 2003). Fraksinasi kering lebih
banyak diterapkan di pabrik-pabrik pengolahan minyak karena lebih
efisien baik dari segi biaya maupun dari segi proses ( Wong et al., 1991
cit. Yussof, 2003).
Proses fraksinasi kering dilakukan dengan cara mendinginkan
minyak yang telah difraksinasi sehingga didapatkan fraksinasi olein
dengan nilai cloud point yang rendah dan mempunyai stabilitas yang
baik pada suhu dingin, kemudian dilanjutkan proses filtrasi untuk
memisahkan fraksi cair (olein) dari fraksi padat (stearin).
9
Berdasarkan diagram alir pada Gambar 1(a,b,c), maka hasil
pengolahan CPO berdasarkan tahapan proses didapatkan enam macam
produk yang diperdagangkan yaitu: DALMS, RBD palm oil, RBD
olein, RBD stearin, crude olein dan crude stearin. Persentase secara
keseluruhan proses pengolahan CPO berdasarkan tahapan proses
menghasilkan 73% olein, 21% RBD stearin, 5% DALMS, dan 94%
RBD palm oil.
C. Perdagangan CPO dan turunanya
Pengolahan jenis produk antara sangat tergantung dari permintaan
(pasar) konsumen. Berdasarkan permintaan dari konsumen maka produk
antara yang terdapat di pasaran adalah RBD stearin, RBD olein, RBD palm
oil, crude olein, crude stearin, DALMS (Anonim, 2010).
Tabel 3: Perkembangan volume ekspor CPO dan produk antara CPO
Indonesia dalam (ribu matrik ton)
Tahun CPO
Produk antara CPO (ton)
RBD olein
RBD palm
oil
RBD
stearin DALMS
Total produk
antara
2001 1.849.142 950.000 350.000 930.000 300.000 2.530.000
2002 2.804.792 2.025.000 280.000 970.000 280.000 3.555.000
2003 2.892.150 2.500.000 325.000 1.200.000 300.000 4.325.000
2004 3.819.927 3.100.000 550.000 1.430.000 380.000 5.460.000
2005 4.565.625 3.330.000 650.000 1.600.000 102.000 5.682.000
total
(ton) 15.931.636 11.905.000 2.155.000 6.130.000 1.362.000 21.552.000
Sumber: Gapki, 2007
10
Tabel 4: Perkembangan volume ekspor CPO dan produk antara CPO
Indonesia dalam (ribu matrik ton)
Tahun CPO
Produk antara CPO (ton)
RBD olein
RBD palm
oil
RBD
stearin DALMS
Total produk
antara
2006 6.113.631 2.614.000 901.000 2.140.000 175.000 5.830.000
2007 5.701.286 3.692.000 838.000 936.000 280.000 5.746.000
2008 7.904.178 3.831.000 772.000 1.121.000 366.000 6.090.000
2009 9.566.746 4.107.000 752.000 1.554.000 313.000 6.726.000
total
(ton) 29.285.841 14.244.000 3.263.000 5.751.000 1.134.000 24.392.000
Sumber: kementrian Perdagangan, 2010
Produk antara CPO yang paling banyak diekspor adalah RBD olein.
Hal ini dikarenakan RBD olein merupakan produk antara yang akan diolah
lebih lanjut menjadi minyak goreng (Tomek and Robinson, 1972 cit. Ibrahim,
2009). Pada tahun 2002-2003 terjadi kenaikan ekspor RBD stearin sebesar
230 ribu ton dari 970 pada tahun 2002 menjadi 1.200.000 juta ton pada tahun
2003. kemudian diurutan kedua adalah produk antara RBD stearin 1.650.000
juta ton.
Ekspor CPO (Tabel 3) terihat pada periode tahun 2001 2005 sebesar
15.931.636 juta ton lebih rendah dibandingkan ekspor produk antara sebesar
21.552.000 juta ton. Penurunan ekspor produk antara mulai terjadi pada tahun
2006. Terlihat pada (Tabel 4) periode 2005 2006 ekspor RBD olein
mengalami penurunan sebesar 716 ribu ton dari 3.330.000 juta ton pada tahun
2005 menjadi 2.624.000 juta ton pada tahun 2006. Penurunan ekspor RBD
stearin terlihat pada periode tahun 2006 2007 sebesar 1.204.000 juta ton,
dari 2.140.000 juta ton pada tahun 2006 menjadi 936 juta ton pada tahun
11
2007. Pada tahun 2009 ekspor CPO sebesar 29.566.746 juta ton dan volume
ekspor produk antara lebih rendah sebesar 24.392.000 juta ton.
D. Pembiayaan proses pengolahan CPO menjadi produk antara
Biaya adalah nilai yang diukur dalam satuan uang yang digunakan
untuk memperoleh barang atau jasa yang dapat memberikan manfaat di massa
sekarang atau yang akan datang bagi perusahaan (Suproyono, 2006;
Simamora, 2002; Supriyono., 1999; Mulyadi, 2001). Hamm (2000)
mengatakan jenis pembiayaan pada proses pengolahan CPO menjadi produk
antara terbagi menjadi dua yaitu investasi dan biaya operasional. Secara detail
akan dijabarkan sebagai berikut:
1. Investasi
Investasi adalah biaya yang ditanamkan pada suatu asset berbentuk
bangunan dan perkembangan fisik selama beberapa periode kedepan untuk
mendapatkan keuntungan (Suryana, 2009; Joness, 2004; Sutrisno, 2009).
Dryden (1959) mengatakan komponen investasi pabrik pengolahan CPO
menjadi produk antara menurut meliputi: pembelian alat dan mesin,
pemasangan alat dan mesin, bangunan dan utilities.
2. Biaya operasional
Biaya operasional (operational cashflow) adalah biaya yang
digunakan untuk menutup investasi pada suatu periode tertentu (Suryana,
2006; Helmi, 2008; dan Jaladri, 2009). Dryden (1959) mengatakan
komponen biaya operasional pabrik pengolahan CPO menjadi produk
antara meliputi: pengadaan listrik, pengadaan air, pengadaan uap,
12
treatment gas buang, maintenance, man power, environmental, dan over
head (5% of over all).
E. Evaluasi Kelayakan Usaha
Jumingan (2009) mengatakan terdapat enam metode penilaian
investasi suatu proyek yaitu:
1. Accounting rate of return
Accounting rate of return (AAR) adalah rasio antara laba setelah
pajak terhadap investasi. AAR digunakan untuk mengetahui besarnya
tingkat keuntungan dari investasi. AAR dipengaruhi oleh besar kecilnya
pajak, jika pajak penjualan tinggi akan mempengaruhi laba setelah pajak
yang diperoleh.
Untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu investasi maka dapat
dilihat dari:
Nilai AAR (%) lebih besar dari keuntungan yang diisyaratkan, maka
investasi tidak layak.
Nilai AAR (%) lebih kecil dari keuntungan yang diisyaratkan, maka
investasi layak.
13
2. Average accounting rate of return
Average accounting rate of return adalah rasio antara laba
setelah pajak terhadap rata-rata investasi, maka untuk menilai investasi
tersebut diterima atau ditolak diketahui dari:
Accounting rate of return (Rp) lebih besar dari rate of return yang
diisyaratkan, maka investasi tersebut diterima
Accounting rate of return (Rp) lebih kecil dari rate of return yang
diisyaratkan, maka investasi ditolak.
3. Pay back periode
Pay back periode adalah suatu investasi yang menunjukkan
berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengembalian investasi.
Besar kecilnya pajak akan mempengaruhi cashflow yang dierima per
tahunnya, sehingga dapat mempengaruhi pay back periode. Untuk
menilai investasi tersebut diterima atau ditolak diketahui dari:
Pay back periode lebih kecil dari waktu yang ditargetkan (5 tahun),
maka investasi layak
Pay back periode lebih besar dari waktu yang ditargetkan (5 tahun),
maka investasi tidak layak
14
4. Internal rate of return (IRR) adalah mencari discount rate yang
dapat menyamakan antara present value dari cashflow dengan present
value dari investasi. Besar kecilnya pajak akan mempengaruhi
besarnya cashflow, sehingga akan mempengaruhi IRR yang diperoleh.
Untuk menilai investasi tersebut diterima atau ditolak diketahui dari:
Dimana:
Rr = Tingkat discount rate 5% (r) lebih rendah
Rt = Tingkat dicount rate 5% (r) lebih tinggi
TPV = Total present value
NPV = Net present value
IRR (%) lebih besar dari keuntungan yang diisyaratkan (%), maka
investasi layak
IRR (%) lebih kecil dari keuntungan yang diisyaratkan (%), maka
investasi tidak layak
5. Net present value
Net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari
cashflow dengan nilai sekarang dari investasi. Untuk menghitung NPV
pertama dilakukan dengan menghitung present value dari penerimaan
(cash flow) dengan discount rate tertentu, kemudian dibandingkan
dengan present value dari investasi. untuk menilai investasi tersebut
diterima atau ditolak diketahui dari:
15
Dimana:
K = Required rate of return atau weight average cost of capital.
At = Cash flow untuk periode t
Total present value of cash flow (Rp) lebih besar dari investasi
maka, investasi layak
Total present value of cash flow (Rp) lebih kecil dari investasi maka,
investasi tidak layak.
6. Profitability index (benefit cost rasio)
Profitability index (benefit cost rasio) adalah ratio antara present
value dari penerimaan dengan present value dari investasi. Besar
kecilnya pajak akan mempengaruhi present value of cashflow, sehingga
akan mempengaruhi nilai Profitability Index. Untuk menilai investasi
tersebut diterima atau ditolak diketahui dari:
Profitability index lebih kecil dari 1 maka investasi tidak layak
16
F. Manajemen pabrik refining dan fraksinasi
Manajemen adalah alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan cara
yang efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,
dan pengendalian sumber daya organisasi. Secara detail akan di jabarkan
sebagai berikut (Daft, 2006; Taylor, 1911)
a. Perencanaan
Perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang akan dicapai
oleh organisasi dengan cara mengerahkan semua sumberdaya yang ada.
Perencanaan yang kurang baik akan menggagalkan organisasi dalam
mencapai tujuan.
b. Pengorganisasian
Pengorganisasian adalah pengalokasian seluruh sumberdaya yang
ada sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
c. Pengarahan
Pengarahan adalah pembekalan yang diberikan bagi karyawan
baik berupa skill, motivasi, dan pembentukan karakter seseorang.
d. Pengendalian (controlling)
Pengendalian adalah kegiatan mengawasi keadaan maupun
aktifitas seluruh sumberdaya yang ada untuk mengetahui pencapaian
target yang diinginkan, pengendalian perlu dilakukan untuk mendapatkan
umpan balik (feed back) bagi organisasi.
17
Tujuan manajemen pada pabrik refinery dan fraksinasi adalah
mengolah CPO menjadi produk antara yaitu RBD olein dan RBD stearin yang
memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Dalam pelaksanaanya untuk mencapai
tujuan tersebut perlu memperhatikan sumber daya manusianya, sumber daya
keuangan, bahan baku (Supply chain), dan teknologi. Keseluruhannya
merupakan sub sistem sub sistem manajemen yang saling berhubungan dan
terkait satu dengan lainnya untuk mencapai suatu tujuan ( Simatupang, 1995).
Terdapat tiga tingkatan manajemen pada suatu organisasi: pada
tingkatan pertama adalah manajer puncak (top manager), tingkat kedua adalah
manajer menengah (middle manager), dan tingkatan terakhir adalah manajer
lini pertama (Project manager). Tugas masing-masing tingkatan manajemen
akan dijelaskan secara detail sebagai berikut (Banoma, 1989 cit. Daft, 2006) :
a. Top manager
Top manager merupakan posisi tertinggi pada suatu organisasi;
seperti Presiden, Ketua, Direkur eksekutif dan Wakil Presiden Eksekutif
pada suatu organisasi. Top Manager bertanggung jawab untuk menentukan
tujuan organisasi, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan organisasi,
mengawasi, dan mengambil keputusan.
b. Middle manager
Middle manager merupakan posisi tingkat menengah organisasi
yang memiliki dua atau lebih tingkatan manajemen dibawahnya; kepala
unit bisnis, manajer umum, administrator, manajer lini produk, manajer
18
kendali mutu, direktur laboratorium riset. Middle manajer bertanggung
jawab atas unit usaha, mengevaluasi kinerja tim, menyelesaikan konflik.
c. Project manajer
Project manajer merupakan tingkatan manajer yang secara
langsung bertanggung jawab atas produksi barang dan jasa.
Sistem organisasi yang dilakukan di pabrik refining dan fraksinasi
adalah sistem vertical organization, dimana perintah berasal dari top manager
dan di sampaikan kepada bawahan secara bertahap, yang akhirnya sampai
kepada karyawan pelaksana. Tujuan menggunakan sistem ini adalah untuk
kelancaran jalannya perusahaan, khususnya untuk hal-hal yang bersifat intern.
19
Gambar 2: Lay out alokasi tenaga kerja refinery dan fraksinasi
(Jiungpe, 2008)
1. Pembagian tenaga kerja pada pabrik refining dan fraksinasi
a. Operator maintenance refining terdiri dari; supervisor, operator
bleaching, operator deodorizing.
b. Operator maintenance fraksinasi; supervisor, operator fillter press,
operator cristallizer, operator chiller
20
2. Job description pada pabrik refinering dan fraksinasi
a. Shift leader refinering (supervisor)
Tujuan umum jabatan: mengkoordinasi pelaksanaan proses
produksi phisical refinering sesuai rencana harian shift
Tugas dan tanggung jawab: mengawasi proses produksi dan
kualitas hasil produksi
Mengawasi ketepatan pemakaian raw material dan bahan pembantu
dalam proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan
Membuat laporan pelaksanaan produksi physical refinering
Mengawasi pelaksanaan preventive maintenance dan memastikan
peralatan instrumen dapat digunakan dengan baik
Melakukan serah terima sift, serta mencatat kondisi operasi dalam
log book
Menjalankan saftey regulation berdasarkan kebijakan yang berlaku
Wewenang: Menghentikan produksi apabila dipandang akan
membahayakan keselamatan jiwa dan menimbulkan kerusakan
pada mesin
b. Operator degumming
Tujuan umum jabatan: melaksanakan proses produksi
degumming sesuai dengan work instruction.
Tugas dan tanggung jawab:
Memeriksa kelayakan mesin sebelum beroperasi
21
Menjalankan proses degumming dan menjaga konsistensi kondisi
operasinya
Membuat laporan kondisi operasi dan penyimpangan proses yang
terjadi
Melakukan serah terima shift
Menjalankan sistem manajemen mutu (HCCP, ISO, Halal)
Menjaga dan memelihara seluruh peralatan
Mempunyai wewenang untuk menghentikan mesin degumming
apabila proses menyebabkan kerusakan pada mesin
c. Operator bleaching
Tujuan umum jabatan: melaksanakan proses produksi bleaching
sesuai dengan work instruction.
Tugas dan tanggung jawab:
Memeriksa kelayakan mesin sebelum mengoperasikannya
Menjalankan operasi bleaching dan menjaga kondisi operasinya
Membuat laporan tentang kondisi operasi dan penyimpangan
proses yang terjadi
Melakukan serah terima shift
Menjalankan sistem manajemen mutu (HCCP, ISO, Halal)
Menjaga dan memelihara seluruh peralatan
Mempunyai wewenang untuk menghentikan mesin bleaching
apabila proses menyebabkan kerusakan pada mesin
22
d. Operating deodorizing
Tujuan umum jabatan: melaksanakan proses produksi
deodorizing sesuai dengan work instruction
Tugas dan tanggung jawab:
Menyiapkan bahan pembantu untuk proses deodorizing
Memeriksa kelayakan mesin sebelum mengoperasikannya
Menjalankan operasi deodorizing dan menjaga kondisi operasinya
Membuat laporan tentang kondisi operasi dan penyimpangan
proses yang terjadi
Melakukan serah terima shift
Menjalankan sistem manajemen mutu (HCCP, ISO, Halal)
Menjaga dan memelihara seluruh peralatan
Mempunyai wewenang untuk menghentikan mesin deodorizing
apabila proses menyebabkan kerusakan pada mesin
e. Shift leader fraksinasi
Tujuan umum jabatan: mengkoordinasi pelaksanaan proses
produksi fraksinasi
Tugas dan tanggung jawab
mengawasi proses produksi dan kualitas hasil produksi
Mengawasi ketepatan pemakaian raw material dan bahan
pembantu dalam proses produksi sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan
Membuat laporan pelaksanaan proses fraksinasi
23
Mengawasi pelaksanaan preventive maintenace dan memastikan
peralatan instrumen dapat digunakan dengan baik
Melakukan serah terima sift, serta mencatat kondisi operasi dalam
log book
Wewenang dan kewajiban: menghentikan mesin bila akan
membahanyakan keselamatan jiwa dan menimbulkan kerusakan
pada mesin.
f. Operating fraksination
Tujuan umum jabatan: melakukan proses fraksinasi sesuai
dengan work instruction
Tugas dan tanggung jawab pelaksanaan:
Menyiapkan raw material untuk proses fraksinasi
Memeriksa kelayakan mesin sebelum mengoperasikannya
Menjalankan operasi fraksinasi dan menjaga kondisi operasinya
Membuat laporan tentang kondisi operasi dan penyimpangan
proses yang terjadi
Mengambil dan mengirim sampel bahan baku minyak dan hasil
produksi kepada quality control, serta mendokumentasikan
hasilnya
Menjalankan sistem manajemen mutu (HCCP, ISO, Halal)
Menjaga dan memelihara seluruh peralatan produksi
Mempunyai wewenang untuk menghentikan mesin fraksinasi
apabila proses menyebabkan kerusakan pada mesin
24
g. Operating Maintenance
Tujuan umum jabatan: melaksanakan perawatan dan perbaikan
ringan pada mesin produksi (refining dan fraksinasi)
Tugas dan tanggung jawab:
Melakukan pemeriksaan kelayakan fungsi mesin refining dan
fraksinasi secara rutin
Mempersiapkan bahan-bahan pembantu yang dibutuhkan
Melakukan perawatan mesin produksi secara berkala
Melakukan perbaikan ringan mesin produksi
Menjalankan safty regulation sesuai kebijakan yang berlaku
Menjalankan sistem manajemen mutu (HCCP, ISO, Halal)
Menjaga dan memelihara seluruh peralatan Wewenang: tidak ada
25
26
Anda mungkin juga menyukai
- Surat Pernyataan Pembagian WarisanDokumen1 halamanSurat Pernyataan Pembagian Warisanciptomx92% (13)
- Proposal Investasi Sawit 3in1Dokumen25 halamanProposal Investasi Sawit 3in1Hafdillah HandyBelum ada peringkat
- Roadmap CpoDokumen33 halamanRoadmap CpoHeri Luky Anggrainy Supagi100% (1)
- Roadmap KelapaDokumen17 halamanRoadmap KelapasafrizalibrahimBelum ada peringkat
- Biaya Revit Tahun 2008Dokumen10 halamanBiaya Revit Tahun 2008Unke Lahana IbrahimBelum ada peringkat
- Pengolahan Minyak Kelapa SawitDokumen16 halamanPengolahan Minyak Kelapa Sawitarnoplanter507100% (2)
- TUGAS 1 TATA LETAK PT SMART GegeDokumen22 halamanTUGAS 1 TATA LETAK PT SMART GegeGigih TawangBelum ada peringkat
- Sistem Pengupahan Pekerja Tetap & KontrakDokumen96 halamanSistem Pengupahan Pekerja Tetap & KontrakSendi SomantriBelum ada peringkat
- Sop Panen PlasmaDokumen12 halamanSop Panen PlasmaMRudiNurrudinHasanBelum ada peringkat
- PENDAHULUAN Dolomit Dan PusriDokumen18 halamanPENDAHULUAN Dolomit Dan PusriRemulti bintangBelum ada peringkat
- Konsep Pemasaran CPO PTPN IVDokumen159 halamanKonsep Pemasaran CPO PTPN IVAzhari RizalBelum ada peringkat
- Proposal Kelapa SawitDokumen12 halamanProposal Kelapa SawitAnonymous nS0io2soR100% (1)
- Kasus Minyak Kelapa SawitDokumen6 halamanKasus Minyak Kelapa SawitAnastasia Meirina HandojoBelum ada peringkat
- Sejarah Singkat PT MoeisDokumen1 halamanSejarah Singkat PT MoeisRobyhanggan BerutuBelum ada peringkat
- Format Kertas Kerja BudgetDokumen90 halamanFormat Kertas Kerja BudgetYosdi HarmenBelum ada peringkat
- Proposal Kelapa SawitDokumen10 halamanProposal Kelapa SawitChilvya Natasya D'friversBelum ada peringkat
- Makalah Beatrix AklsDokumen37 halamanMakalah Beatrix AklsMonicaBelum ada peringkat
- Manajemen Panen Kelapa Sawit PDFDokumen89 halamanManajemen Panen Kelapa Sawit PDFAzhari Rizal50% (2)
- DJEnterprise - Biaya Pembuatan PKSDokumen23 halamanDJEnterprise - Biaya Pembuatan PKSEndra SYBelum ada peringkat
- Proses Pengolahan Minyak SawitDokumen2 halamanProses Pengolahan Minyak SawitSarwan Dhafin RamadhanBelum ada peringkat
- Bisnis Pemasaran Minyak Kelapa SawitDokumen4 halamanBisnis Pemasaran Minyak Kelapa Sawitrambutan0408Belum ada peringkat
- The Oil Palm Planters - Menyusun Master Budget Kelapa SawitDokumen33 halamanThe Oil Palm Planters - Menyusun Master Budget Kelapa SawitMasmanyul4741Belum ada peringkat
- Analisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Pasca Umur Ekonomis PDFDokumen12 halamanAnalisis Pendapatan Usahatani Kelapa Sawit Pasca Umur Ekonomis PDFYudhi HuseinBelum ada peringkat
- Pengolahan Spenth Bleaching EarthDokumen23 halamanPengolahan Spenth Bleaching EarthAhmad Husni LubisBelum ada peringkat
- Katalog Improvement Vol Iv 2014 - Rev00Dokumen32 halamanKatalog Improvement Vol Iv 2014 - Rev00luthfan bagus Saputra100% (1)
- Respon Pembentukan Bunga Sawit Pada An Pupuk N Dengan Dosis BerbedaDokumen26 halamanRespon Pembentukan Bunga Sawit Pada An Pupuk N Dengan Dosis BerbedaDeni Ramadoni100% (1)
- Pembuatan Pembakaran Batok KelapaDokumen14 halamanPembuatan Pembakaran Batok KelapaSbastian100% (1)
- Analisa TrukDokumen6 halamanAnalisa TrukArya Hayang LintuhBelum ada peringkat
- 3 Produk Yang Dihasilkan Dari CpoDokumen9 halaman3 Produk Yang Dihasilkan Dari Cpoarbotomo_marbun100% (1)
- Analisis Sistem Perkebunan KaretDokumen68 halamanAnalisis Sistem Perkebunan KaretIbank YahyaBelum ada peringkat
- A13mrf PDFDokumen43 halamanA13mrf PDFIqbal Putera MahariBelum ada peringkat
- REFERAT Tatalaksana Nyeri Akut Dan Nyeri KronisDokumen39 halamanREFERAT Tatalaksana Nyeri Akut Dan Nyeri KronisAyu Febriyanti AbbasBelum ada peringkat
- The Oil Palm Planters - Struktur Biaya Perkebunan Kelapa Sawit PDFDokumen9 halamanThe Oil Palm Planters - Struktur Biaya Perkebunan Kelapa Sawit PDFMuh Nasir LewaBelum ada peringkat
- Makalah Iha Sabun SawitDokumen34 halamanMakalah Iha Sabun SawitM Ridho TriadiBelum ada peringkat
- Proses Pengolahan CPO Menjadi Minyak GorengDokumen5 halamanProses Pengolahan CPO Menjadi Minyak Gorenganggunfcr100% (1)
- Daftar Pabrik Kelapa SawitDokumen3 halamanDaftar Pabrik Kelapa SawitLukman Hakim100% (1)
- Tafsir Surat Al Ashr PDFDokumen8 halamanTafsir Surat Al Ashr PDFZakeBelum ada peringkat
- Sawit Sumbermas Sarana Annual Report 2014 SSMS Company Profile Indonesia InvestmentsDokumen223 halamanSawit Sumbermas Sarana Annual Report 2014 SSMS Company Profile Indonesia InvestmentssfatimahimahBelum ada peringkat
- Analisis Pembiayaan Perkebunan Kelapa SawitDokumen30 halamanAnalisis Pembiayaan Perkebunan Kelapa SawitKurniawan Yusril100% (1)
- Draft Mediator Fee22Dokumen1 halamanDraft Mediator Fee22mulawarmanBelum ada peringkat
- Materi - Aspek Perijinan Kelapa Sawit-Februari 2021Dokumen31 halamanMateri - Aspek Perijinan Kelapa Sawit-Februari 2021Fauzan100% (1)
- Cangkang SawitDokumen12 halamanCangkang SawitAndry MandhaLikoBelum ada peringkat
- Cara Install Vray + PatchDokumen5 halamanCara Install Vray + PatchMuhammad Teguh PrayudhiBelum ada peringkat
- Perencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa SawitDokumen43 halamanPerencanaan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitaistop100% (3)
- 223kajian Biaya Replanting Tanaman Kelapa Sawit - Elaeis Guineensis Jacq - Di Kebun Merbaujaya I)Dokumen43 halaman223kajian Biaya Replanting Tanaman Kelapa Sawit - Elaeis Guineensis Jacq - Di Kebun Merbaujaya I)Julian Winata100% (2)
- Surat Perjanjian Kerja Karyawan LusmodigitalDokumen7 halamanSurat Perjanjian Kerja Karyawan LusmodigitalSyamsul AlamBelum ada peringkat
- Analisis Kapasitas Produksi Menggunakan Metode Rough Cut Capacity Planning Di Workcenter 1 Departemen Produksi 2 Divisi Alat Berat PTDokumen2 halamanAnalisis Kapasitas Produksi Menggunakan Metode Rough Cut Capacity Planning Di Workcenter 1 Departemen Produksi 2 Divisi Alat Berat PTSarwendahBelum ada peringkat
- Pemeliharaan DOC Ayam KampungDokumen5 halamanPemeliharaan DOC Ayam KampungSimar Dan Rudy SamaBelum ada peringkat
- Kuliah Hulu Rempah Dan Kelapa SawitDokumen117 halamanKuliah Hulu Rempah Dan Kelapa SawitThenMust Andy PrasetioBelum ada peringkat
- Panduan Perencanaan Kelapa SawitDokumen32 halamanPanduan Perencanaan Kelapa SawitDecki Iswandi100% (1)
- Adoc - Pub Manajemen Pemupukan Kelapa Sawit Elaeis GuineensisDokumen63 halamanAdoc - Pub Manajemen Pemupukan Kelapa Sawit Elaeis GuineensisDeaBelum ada peringkat
- Adoc - Tips - Manajemen Panen Kelapa SawitDokumen67 halamanAdoc - Tips - Manajemen Panen Kelapa Sawitkadek aripBelum ada peringkat
- Penyusunan Pedoman Penilaian Fisik KebunDokumen1 halamanPenyusunan Pedoman Penilaian Fisik KebunSawit TanhungarBelum ada peringkat
- PAbrik Minyak Goreng Kapasitas 500 Ton Per HariDokumen18 halamanPAbrik Minyak Goreng Kapasitas 500 Ton Per Hariagus rasidBelum ada peringkat
- Crude Palm OilDokumen68 halamanCrude Palm OilSilvia Anggrainy NasutionBelum ada peringkat
- Roadmap CpoDokumen31 halamanRoadmap CpoSari Ningtyas100% (1)
- Investasi Refinery 1000 TonDokumen8 halamanInvestasi Refinery 1000 Tondyradyko100% (3)
- Sitem Manajemen Rantai Pasokan Pada Industri Agrobisnis Kelapa Sawit IndonesiaDokumen8 halamanSitem Manajemen Rantai Pasokan Pada Industri Agrobisnis Kelapa Sawit IndonesiaFath Diwirja50% (2)
- Kilang Minyak DiindonesiaDokumen21 halamanKilang Minyak DiindonesiaM. irfan kurniawanBelum ada peringkat
- Seminar Proposal Disertasi (Sidkom1)Dokumen98 halamanSeminar Proposal Disertasi (Sidkom1)NovindraBelum ada peringkat
- Buku Mengenal Minyak Sawit Dengan Beberapa Karakter Unggulnya-GAPKIDokumen16 halamanBuku Mengenal Minyak Sawit Dengan Beberapa Karakter Unggulnya-GAPKIgreg_jkBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Grafika (Sucipto) 2016Dokumen6 halamanLaporan Praktikum Grafika (Sucipto) 2016ciptomxBelum ada peringkat
- RPS Grafika Komputer Dan KomunikasiDokumen9 halamanRPS Grafika Komputer Dan KomunikasiciptomxBelum ada peringkat
- Siti Mutrofin - Manajemen Pengelolaan OJS Sesuai Pedoman AkreditasiDokumen201 halamanSiti Mutrofin - Manajemen Pengelolaan OJS Sesuai Pedoman AkreditasiciptomxBelum ada peringkat
- Template Proposal PKM-MDokumen12 halamanTemplate Proposal PKM-MciptomxBelum ada peringkat
- Surat Keterangan Kepemilikan Usaha KecilDokumen1 halamanSurat Keterangan Kepemilikan Usaha KecilciptomxBelum ada peringkat
- Surat Audiensi DikNas SMGDokumen1 halamanSurat Audiensi DikNas SMGciptomxBelum ada peringkat
- Surat Permohonan Sertifikat OkabunDokumen1 halamanSurat Permohonan Sertifikat OkabunciptomxBelum ada peringkat
- Surat Lamaran ApotekDokumen2 halamanSurat Lamaran ApotekciptomxBelum ada peringkat
- Surat Perjanjian GadaiDokumen2 halamanSurat Perjanjian GadaiciptomxBelum ada peringkat
- Surat Perjanjian Kontrak TanahDokumen1 halamanSurat Perjanjian Kontrak Tanahciptomx100% (1)
- Surat Perjanjian Jual Beli TanahDokumen1 halamanSurat Perjanjian Jual Beli TanahciptomxBelum ada peringkat
- Surat KuasaDokumen1 halamanSurat KuasaciptomxBelum ada peringkat
- Kementrian AgamaDokumen2 halamanKementrian Agamaciptomx100% (1)
- Daftar SMU & SMK Di YogyakartaDokumen7 halamanDaftar SMU & SMK Di Yogyakartaciptomx100% (2)