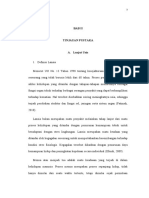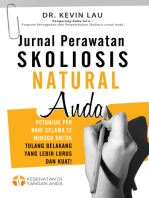Jtptunimus GDL Gunturpras 6599 3 Babii
Jtptunimus GDL Gunturpras 6599 3 Babii
Diunggah oleh
pongidaeJudul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Jtptunimus GDL Gunturpras 6599 3 Babii
Jtptunimus GDL Gunturpras 6599 3 Babii
Diunggah oleh
pongidaeHak Cipta:
Format Tersedia
9
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A.
Teori Menua (Aging)
Gerontologi, studi ilmiah tentang efek tentang penuaan dan
penyakit yang berhubungan dengan penuaan pada manusia, meliputi
efek biologis, fisiologis, psikososial, dan espek rohani dari penuaan
(Stanley 2006). Menua (aging) adalah suatu proses menghilangnya
secara
perlahan-lahan
kemampuan
jaringan
untuk
memperbaiki
diri/mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya,
sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan
memperbaiki kerusakan yang diderita (Santoso 2009).
Menurut Constantindes (1994) dalam Nugroho (2000) mengatakan
bahwa proses menua adalah suatu proses menghilangnya secara
perlahanlahan kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau
mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya, sehingga tidak dapat
bertahan terhadap infeksi dan memperbaikinya kerusakan yang diderita.
Proses menua merupakan proses yang terus-menerus secara alamiah
dimulai sejak lahir dan setiap individu tidak sama cepatnya. Menua
bukan status penyakit tetapi merupakan proses berkurangnya daya tahan
tubuh dalam menghadapi rangsangan dari dalam maupun dari luar tubuh.
Menjadi tua (aging) adalah suatu proses menghilangnya secara
perlahan-perlahan
kemampuan
jaringan
untuk
memperbaiki
diri/mengganti diri dan mempertahankan struktur dan fungsi normalnya
sehingga tidak dapat bertahan terhadap jejas (termasuk infeksi) dan
memperbaiki kerusakan yang diderita.
10
Menurut Darmojo (2006) tujuan hidup manusia itu ialah menjadi
tua tetapi tetap sehat (Healthy aging). Healthy aging artinya menjadi tua
dalam keadaan sehat. Takemi (1977) yang pertama kali menyatakan
Gerontology is concerned primarily with problem of healthy aging
rather than the prevention of aging.
Healthy aging akan dipengaruhi oleh faktor:
1. Endogenoc aging, yang dimulai dengan cellular aging, lewat tissue
dan anatomical aging kearah proses menuanya organ tubuh. Proses
ini seperti jam yang terus berputar.
2. Exogenix faktor, yang dapat dibagi dalam sebab lingkungan
(environment) dimana seseorang hidup dan faktor sosio budaya
yang paling tapat disebut gaya hidup (Life style). Faktor exogenix
aging tadi, sekarang lebih dikenal denga ssebutan faktor resiko.
Wacana diatas jelas kiranya tugas dan tujuan gerontology/geriatri
dalam mengabdi ilmu kesehatan yaitu menuju healthy aging (menuju
menua sehat). Pengalaman menunjukkan bahwa rupa-rupanya yang
lebih berpengaruh adalah faktor-faktor eksogen yaitu gaya hidup dan
lingkungan yang juga saling mempengaruhi satu satu sama lain.
Endogenic dan exogenix faktors ini seringkali sulit untuk dipisahpisahkan karena saling memepngaruhi dengan erat. Bila faktor-faktor
trsebut tidak dapat dicegah terjadinya maka orang tersebut akan lebih
cepat meninggal dunia (Darmojo 2006).
Menurut Mc. Kenzie (2006), banyak yang beranggapan bahwa
status kesehatan lansia telah membaik selama beberapa tahun ini karena
banyak diantara mereka yang hidup lebih lama. Lainnya memegang
pandangan berbeda, yaitu lansia merupakan orang yang rapuh dan
bergantung. Kedua pandangan tersebut tidak seluruhnya benar. Namun
kita tahu bahwa faktor resiko yang paling konsisten dari sakit dan
kematian untuk seluruh penduduk adalah usia, dan secara umum, status
kesehatan lansia tidak sebaik saat mereka muda. Ada beberapa masalah
11
kesehtan yang berkaitan dengan penuaan yaitu mencakup mortalitas,
morbilitas, dan prilaku kesehatan, serta pilihan hidup.
Prilaku kesehatan dan faktor sosial pasti memainkan peranan
signifikan dalam membantu lansia memelihara kesehatan dalam
menjalani tahun-tahun lanjutannya. Beberapa lansia percaya bahwa
mereka terlalu tua untuk mendapatkan manfaat apapun dari perubahan
prilaku kesehatan mereka. Hal itu, tentu saja tidak benar; tidak pernah
ada kata terlambat untuk melakukan perubahan untuk kebaikan.
1. Definisi Usia Lanjut
Menurut pengertian gerontologi, lansia adalah suatu tahap dalam
hidup manusia mulai dari bayi, anak-anak, remaja, tua dan usia lanjut
dan bukan penyakit melainkan suatu proses alami yang tidak bisa
dihindarkan. Jadi lansia merupakan proses ilmiah terus menerus dan
berkesinambungan yang dalam keadaan lanjut menyebabkan perubahan
anatomi, fisiologi dan biokimia pada jaringan atau organ yang pada
akhirnya mempengaruhi keadaan, fungsi dan kemampuan badan secara
keseluruhan (Depkes. RI, 2005).
Menurut Wahyudi (2008), lansia (lanjut usia) adalah kelompok
umur pada manusia yang telah memasuki tahapan akhir fase
kehidupannya. Sedangkan Depkes RI (2003), mendefinisikan lansia
adalah seseorang yang berumur 60 tahun atau lebih.
Usia lanjut adalah suatu kejadian yang pasti akan dialami oleh
semua orang yang dikaruniai usia panjang, terjadinya tidak bisa dihindari
oleh siapapun. Pada usia lanjut akan terjadi berbagai kemunduran pada
organ tubuh. Jadi walapun usia sudah lanjut, harus tetap menjaga
kesehatan dengan memperhatikan gaya hidup, seperti pola makan,
aktifitas fisik, kebiaaan istirahat dan lain-lain (Stanley 2006).
Dengan begitu manusia secara progresif akan kehilangan daya tahan
terhadap infeksi dan akan menumpuk makin banyak distorsi metabolic
dan struktural yang disebut sebagai penyakit degeneratif (seperti
hipertensi, aterosklorosis, diabetes meletus dan kanker) yang akan
12
menyebabkan kita menghadapi akhir hidup dengan episode terminal yang
dramatic seperti stroke, infark miokard, koma asidotik, metasis kanker
dan sebagainya.
2. Klasifikasi Usia Lanjut
Menurut Word Healty Organisation (WHO) dalam (Anggreini
2008), usia lanjut meliputi:
1. Usia pertengahan (middle age), ialah kelompok usia 45-59 tahun.
2. Lanjut usia (elderly) antara 60-74 tahun.
3. Lanjut usia tua (old) antara 75-90 tahun.
4. Lanjut usia sangat tua (very old) diatas 90 tahun.
3. Perubahan Fisiologis Usia Lanjut
Dengan meningkatnya usia, jantung dan pembuluh darah
mengalami perubahan baik struktural maupun fungsional. Secara umum,
perubahan yang disebabkan oleh penuaan berlangsung lambat dan dengan
awitan yang tidak disadari. Penurunan yang terjadi berangsur-angsur ini
sering terjadi ditandai dengan penurunan kebutuhan darah yang
teroksigenasi. Namun, perubahan yang menyertai penuaan ini menjadi
lebih jelas ketika sistem ditekan untuk meningkatkan keluarannya dalam
memenuhi peningkatan kebutuhan tubuh.
a. Perubahan Struktural Pada Sistem Kardiovaskuler
Tekanan
darah
meninggi
akibat
meningkatnya
resistensi
pembuluh darah perifer, kehilangan elastisitas pembuluh darah,
kurangnya efektifitas pembuluh darah perifer untuk oksigenasi,
elastisitas dinding aorta menurun, katup jatung menebal dan menjadi
kaku kemampuan jantung memompa darah menurun 1% setiap tahun
seudah berumur 20 tahun, hal ini menyebkan merunnya kontraksi dan
volumenya (Nugroho 2000).
13
Pada orang lanjut usia, umumnya besar jantung akan sedikit
mengecil. Yang paling banyak mengalami penurunan adalah rongga
bilik kiri, akibat semakin berkurangnya aktivitas. Yang juga
mengalami penurunan adalah besarnya sel-sel otot jantung hingga
menyebabkan menurunnya kekuatan otot jantung.
b. Perubahan Fungsional Pada Sistem Kardiovaskuler
Prinsip perubahan fungsional terkait usia yang dihubungkan
dengan pembuluh darah secara progresif meningkatkan tekanan
sistolik. Tidak ada perubahan dalam tekanan diastolic adalah normal.
Kemungkinan diakibatkan oleh kekakuan pembuluh darah atau karena
selama bertahun-tahun menerima aliran darahh bertekanan tinggi,
baroreseptor yang terletak di arkus aorta dan sinus karotis menjadi
tumpuul atau kurang sensitive.
Perubahan yang jauh lebih bermakna dalam kehidupan lanjut
usia adalah yang terjadi pada pembuluh darah. Proses yang disebut
sebagai arteriosklerosis atau pengapuran dinding pembuluh darah
dapat terjadi dimana-mana. Proses pengapuran akan belanjut menjadi
proses yang menghambat aliran darah yang pada suatu saat akan
menutupi pembuluh darah tadi (Stanley 2006).
Artreoklorosi yang sejauh ini merupakan proses patologis paling
sering memengaruhi sistem kardiovaskuler, adalah proses penyakit
yang secara umum memiliki dampak pada semua arteri. Namun,
secara individual bervariasi dalam derajat sampai berbagai area tubuh
yang terpengaruh. Pada banyak individu, obstruksi terjadi pada arteri
koroner, sedangkan pada individu lain mungkin terjadi pada sirkulasi
serebral atau peripheral.
Artreoklorosis tidak memiliki perbedaan pada orang yang masih
muda ataupun pada yang telah tua. Proses penyakit mungkin lebih
jelas pada orang yang lebih tua karena terdapat akumulasi yang lebih
besar
bertahun-tahun.
Penyakit
aterosklorosis
terutama
mempengaruhi tunika intima (bagian paling dalam) dari arteri, yang
14
memiliki permukaan endothelial yang halus untuk memfasilitasi
aliran darah. Pada kondisi normal, hanya plasma darah yang
melakukan kontak dengan endothelial, sedangkan komponen seluler
(misalnya factor koagulasi) tetap ditengah-tengah aliran darah. Ketika
permukaan endothelial menjadi kasar, walaupun hanya plasma darah
yang melakukan kontak dengan endotel, maka tibul potensi untuk
terbentuknya thrombus ketika factor koagulasi melakukan kontak
dengan endothelium (Stanley 2006).
Pengatur irama inharen jantung oleh simpul SA ternyata
menurun dengan naiknya umur. Denyut jantung maksimum pada
latihan (exercise) ternyata juga menurun dengan naiknya usia ini.
Cardiac output juga menurun dengan bertambahnya usia. Aritmia
berupa ekstra systole dikatakan ditemukan pada dari lebih 10%
penderita-penderita usia lanjut yang diperiksa EKG-nya secara ruutin.
Fungsi sistolik tidak berkurang dengan peninggian usia. Kelainan
fungsi daistolik berupa gangguan relaksasi disebabkan pengurangan
compliance jantung pada permukaan diastole (Darmojo 2006).
B.
Hipertensi
Perubahan-perubahan yang dapat dijumpai pada penderita jantung iskemi
adalah pembuluh darah adalah pada pembuluh darah jantung akibat
arterioklerosis itu belum diketahui dengan pasti, tetapi faktor-faktor yang
mempercepat timbulnya antara lain: banyak merokok kadar kolestrol tinggi,
penderita diabetes meletus, berat badan berlebihan serta kurang olahraga.
Faktor-faktor tersebut sebenarnya dapat dicegah atau dihindari, seperti gaya
hidup kecuali faktor umum seperti: jenis kelamin, keturunan.
15
Menurut Stieglitz dalam Darmojo (2006) dikemukakan adanya empat
penyakit yang sangat erat hubungannya dengan proses menua, yakni:
1. Gangguan sirkulasi darah, seperti :hipertensi, kelainan pembuluh
darah, gangguan pembuluh darah diotak (koroner), dan ginjal.
2. Gangguan metabolism hormonal.
3. Gangguan Persendian.
4. Berbagai macam neoplasma.
Dari
banyak
peneliian
epidemiologi
didapatkan
bahwa
dengan
meningkatnya umur dan tekanan darah meninggi. Hipertensi menjadi masalah
pada lanjut usia karena sering ditemukan dan menjadi faktor utama stroke,
payah jantung dan penyakit jantung koroner. Lebih dari separuh kematian
diatas usia 60 tahun disebabkan oleh penyakit jantung dan serebrovaskuler.
1. Definisi Hipertensi
Dapat dikatakan hipertensi pada lanjut usia adalah pada tekanan
sistolik sama atau lebih besar dari 140 mmHg dan/atau tekanan diastolic
sama atau lebih besar dari 90 mmHg (Darmojo, 2006).
Pada tahap awal, ganngguan dari dinding pembuluh darah yang
menyebabkan elastisitasnya bekurang akan memacu jantung bekerja
lebih keras, karena terjadi hipertensi. Selanjutnya, bila terjadi sumbatan
maka jaringan akan dialiri zat asam oleh pembuluh darah ini kan rusak
dan mati, hal inilah yang disebut infark. Bila terjadi dijantung, dapat
saja menyebebkan infark jantung, atau infark miokard, atau bila
masih lebih ringan dapat tejadi angina pictoris dan gangguan koroner
lainnya (Stanley 2006).
Pada lanjut usia, tekanan darah akan naik secara bertahap. Elastisitas
Jantung pada orang berusia 70 tahun menurun sekitar 50% disbanding
orang berusia 20 tahun, maka dari itu tekanan darah wanita dan pria tua
itu relative tinggi.
16
2. Klasifikasi Hipertensi
Menurut Gunawan (2001), tekanan darah manusia dapat diklasifikasikan
menjadi tiga kelompok, sebagai berikut :
a. Tekanan darah rendah (hipotensi)
b. Tekanan darah normal (normotensi)
c. Tekanan darah tinggi (hipertensi)
Menurut WHO ISH (Word Health Organitation Intenational Of
Hypertension) hipertensi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa
kategori, dapat disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1:2. Klasifikasi Tekanan Darah Menurut WHO-ISH
Tapan (2004)
Kategori
Systole (MmHg)
Diastole (MmHg)
Optimal
<120
< 80
Normal
120-129
80-84
Normal Tinggi
130-139
85-89
Hipertensi Ringan
140-159
90-99
Hipertensi Sedang
160-179
100-109
Hipertensi Berat
>180
>110
3. Pengendalian Hipertensi
Muhammadun (2010), beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam upaya
pengendalian hipertensi :
a. Pengendalian hipertensi dengan olah raga teratur
b. Pengendalian hipertensi dengan istirahat yang cukup
c. Pengendalian hipertensi dengan cara medis
d. Pengendalian hipertensi dengan cara tradisional
e. Pengendalian hipertensi dengan cara mengatur pola makan
f. Pengendalian hipertensi dengan cara mengurangi konsumsi garam
satu sendok teh perhari
17
Menurut Gunawan (2001), untuk menghindari terjadinya komplikasi
hipertensi yang fatal, maka penderita perlu mengambil tindakan
pencegahan yang baik (stop high blood pressure) sebagai berikut:
a. Mengurangi konsumsi garam
Puasa garam untuk kasus hipertensi dapat meurunkan tekanan
darah secara nyata. Umumnya kita mengkomsumsi lebih banyak
garam daripada yang dibutuhkan tubuh. Idealnya, kita cukup
menggunakan sekitar satu sendok the saja atau sekitar 5 garam per
hari (vitahealth 2004).
b. Menghindari kegemukan (obesitas)
Untuk menghindari kegemukan obesitas dapat ditentukan oleh pola
makan untuk setiap harinya (vitahealth 2004).
c. Membatasi konsumsi lemak
Lemak dapat meningkatkan aliran darah akibat dari penyembutan
dari artereoklorosis (vitahealth 2004).
d. Olahraga teratur
Olahraga dapat digolongkan kedalam bentuk statis dan dinamis.
Olahraga dinamis mampu meningkatkan aliran darah sehingga sangat
menunjang pemeliharaan jantung dan sistem pernafasan (Kusmana,
1997 dalam Angreini (2008)).
e. Makan banyak buah dan sayuran segar.
f. Tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol
g. Melakukan relaksasi atau meditasi, dan
h. Berusaha membina hidup yang positif (gaya hidup sehat)
C.
Gaya Hidup
1. Definisi Gaya Hidup
Dalam health promotion glossary WHO pengertian sebagai
berikut: Lyfstyle is a way of living based on identifiable patterns of
behavior which are determined by the interplay between an individuals
personal characteristics, social interaction, and socioeconomic and
environmental living condition.
18
Pola-pola prilaku (behavioral patterns) akan selalu berbeda dalam
situasi atau lingkungan sosial yang berbeda, dan senantiasa berubah,
tidak ada yang menetap (fixed). Gaya hidup individu, yang dicirikan
dengan pola prilaku individu, akan memberi dampak pada kesehatan
individu dan selanjutnya pada kesehatan orang lain. Dalam kesehatan
gaya hidup seseorang dapat diubah dengan cara memperdayakan individu
agar merubah gaya hidupnya, tetapi merubahnya bukan pada si individu
saja, tetapi juga merubah lingkungan sosial dan kondisi kehidupan yang
mempengaruhi pola prilakunya.
Dan tidak ada aturan ketentuan baku tentang gaya hidup yang
berlaku untuk semua orang. Budaya, pendapatan, struuktur keluarga,
umur, kemampuan fisik, lingkungan rumah dan lingkungan tempat kerjaa
yang berbeda, menciptakan berbagai gaya yang berbeda pula (Ari. W
dalam promosikesehatan.com,2007).
Deklarasi Vientiane tentang Gaya Hidup Sehat Asean, 2002 (dalam
dalam promosikesehatan.com,2007). Mengartikan gaya hidup sebagai
praktek prilaku dan praktek sosial yang mendukung kesehatan dan
merupakan cerminan dari nilai-nilai dan jati diri dari kelompok dan
masyarakat dimana penduduk hidup dan menghabiskan sebagaian besar
hidupnya untuk memenuhi kehidupan ekonomi, sosial dan lingkungan
fisik.
Sedangkan menurut Belloc dan Breslow pada Human Population
Laboratory of California State Dept. of Public Helth, tahun 2005 bahwa
yang termasuk kedalam tujuh kebiaaan sehat adalah sebagai berikut:
a.
Tidak merokok
b.
Tidak minum-minuman keras / obat-obatan
c.
Olahraga
d.
Berat badan seimbang
e.
Makan 3 kali sehari tanpa jajan
f.
Sarapan setiap pagi
g.
Tidur 7-8 jam perhari
19
2. Pola Makan
Pola makan adalah cara seseorang atau sekelompok orang yang
memilih dan mengkonsumsi makanan sebagai tanggapan terhadap
pengaruh fisiologi, psikologi, budaya dan sosial sebagai bagian yang
mempengaruhi pola makan dapat meliputi kegiatan memilih pangan, cara
memperoleh, menyimpan, beberapa faktor utama yang mempengaruhi
kebutuhan makan manusia yaitu faktor ekstrinsik dan faktor instrintik
(Khumaidi, 1994 dalam Angreini (2008)). Pola makan individu meliputi
bahan makanan pokok, lauk-pauk (hewani dan nabati), sayur dan buah.
Pola makan yang tidak baik akan menimbulkan beberapa gangguan
seperti kolestrol tnggi, tekanan darah meningkat dan kadar gula yang
meningkat (Triwibowo, 1998 dalam Angreini (2008)).
Dengan bertambahnya usia seseorang, kecepatan metabolisme tubuh
cenderung turun. Kebutuhan kalori pada lanjut usia berkurang, hal ini
disebabkan karena berkurangnya kalori dasar dari kegiatan fisik. Kalori
dasar adalah kalori yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan tubuh
dalam keadaan istirahat, misalnya : untuk jantung, usus, pernafasan,
ginjal, dan sebagainya. Jadi kebutuhan kalori bagi lansia harus
disesuaikan dengan kebutuhannya. Petunjuk bagi lansia adalah sebagai
berikut:
a.
Menu bagi lansia hendaknya mengandung zat gizi dari berbagai
macam bahan makanan yang terdiri dari zat tenaga, pembangun dan
pengatur.
b.
Jumlah kalori yang baik untuk dikonsumsi lansia 50% adalah hidrat
arang ynag bersumber dari hidrat arang komplex (sayur-sayuran,
kacang-kacangan, biji-bijian)
c.
Sebaiknya jumlah lemak dalam makanan dibatasi, terutama lemak
hewani.
d.
Makanan sebaiknya mengandung serat dalam jumlah yang besar
yang bersumber pada buah, syur dan beraneka pati, yang dikonsumsi
dengan jumlah bertahap.
20
e.
Menggunakn bahan makanan yang tinggi kalsium, seperti susu non
fat, yoghurt, ikan.
f.
Makan yang mengandung zat beesi dalam jumlah besar, seperti
kacang-kacangan, hati, bayam, atau syuran hijau.
g.
Membatasi penggunaan garam atau makanan yang mengandung
natrium, hindari makanan yang mengandung alkohol.
h.
makanan sebaiknya banyak dikunyah.
i.
bahan makanan sebagai sumber zat gizi sebaiknya darii bahan-bahan
yang segar dan mudah dicerna.
j.
Hindari makanan yyang terlalu manis, gurih, dan goreng-gorengan.
k.
Makan disesuaikan dengan kebutuhan
Contoh pola makanan yang tidak seimbang antara asupan dengan
kebutuhan baik jumlah maupun jenis makanannya, seperti makan
makanan yang tinggi lemak, kurang mengkonsumsi sayuran dan buah
dan sebagainya. Juga makanan yang melebihi kebutuhan tubuh yang bisa
menyebabkan obeistas atau kegemukan (Hariani, 2007)
Kejadian penyakit infeksi dan kekurangan gizi menurun sebaiknya
penyakit degenaratif dan penyakit kanker meningkat. Di beberapa daerah
masalah penyakit infeksi masih menonjol sehingga dalam transisi
epidemologi
kita
menghadapi
beban
ganda
(Double
Burden),
peningkatan kemakmuran diikuti oleh perubahan gaya hidup karena pola
makan diikota-kota besar bergeser dari pola makan tradisional yang
mengandung banyak karbohidrat, serat dan sayuran, ke pola makan
masyarakat barat yang komposisinya terlalu banyak mengandung protein,
lemak, gula dan garam tetapi reendah serat (Suryono dan Samsuridjal,
1994 dalam Angreini (2008))
Sedangkan menurut WHO (2005) meningkatnya industrialisasi,
urbanisasi, mekanisme yang terjadi di sebagian besar negara didunia,
berhubungan dengan perubahan makanan dan prilaku, termasuk ke
dalamnya makan yang tinggi lemak dan tinggi energi serta gaya hidup
yang lebih santai.
21
Tingginya kandungan surkosa dalam makanan meningkatkan
tekanan arteri pada beberapa orang dengan tensi normal yang kemudian
memberikan efek meningkatkan penyerapan NaCl pada orang yang
memiliki tekanan darah normal dan hipertensi (Kotchen dan Jane, 1995
dalam Angreini (2008)). Surkosa mungkin dapat menurunkan kadar HDL
darah dan memiliki efek merugikan pada toleransi glukosa, selain itu
karbohidrat juga dapa meningkatkan tekanan darah dan ekresi
katekolamin pada hewan percobaan dan mungkin juga pada manusia
(Willet, 1990 (Angreini 2008))
Sedangkan menurut Willet (1990) efek dari protein dan jenis
protein pada manusia belum jelas dan hubungan jenis dengan risiko PJK
diterima dengan sedikit perhatian pada studi-studi epidemiologi darah,
studi pada hewan dengan meningkatkan konsumsi jenis dari protein
mungkin berefek pada penyakit kardiovaskuler (Kotchen dan Jane 1995
dalam Angreini (2008)).
Serat memberi perlindungan terhadap PJK dan juga menurunkan
tekanan darah dan konsumsi setiap hari dan sayuran direkomendasikan
untuknmengurangi risiko PJK, Stroke dan tekanan darah tinggi (WHO,
2003). Kemudian (Kusni dan Kolega 1985 dalam Angreini 2008) pada
1001 laki-laki di Irlandia dan Boston yang diikuti selama 20 tahun
memperoleh hasil terbanyak 101 orang meninggal akibat PJK (Penyakit
Jantung Koroner), dari hasil ini terdapat hubungan yang terbalik antara
asupan serat dengan risiko PJK.
Berikut adalah beberapa yang harus diperhatikan pada pola makan
penderita hipertensi :
a. Pengaturan Natrium (rendah garam)
Pada penderita hipertensi bahan-bahan tersebut, termasuk
makanan yang dimasak dengan bahan tersebut harus dibatasi
penggunaanya.
Pembatasan
ini
tergantung
tingkat
hipertensi yang diderita. Rinciannya sebagai berikut:
keparahan
22
1) Untuk hipertensi berat yaitu apabila tekanan darah systole >180
mmHg dan/ atau diastole >110 mmHg maka dalam pemasakan
tidak boleh ditambahkan garam sedikitpun. Makanan yang tinggi
garam juga harus dihindari. Pengaturan seperti ini biasa disebut
diet rendah garam I (RG I).
2) Untuk hipertensi sedang yaitu apabila tekanan darah sistol : 160
179 mmHg dan atau tekanan darah diatole : 100 109 mmHg
maka penggunaan garam dibatasi hanya sendok teh atau 1 gram
sehari/orang. Makanan yang tinggi garam harus dihindari.
Pengaturan ini biasa disebut diet rendah garam II (RG II).
3) Untuk hipertensi ringan yaitu apabila tekanan darah sistol : 140
149 mmHg dan/atau tekanan darah diastole : 90 99 mmHg,
maka penggunaan garam dibatasi hanya sendok teh atau 2 gram
sehari/orang. Makanan tinggi garam harus dihindari. Pengaturan
ini biasa disebut Diet rendah garam III (RG III).
b. Memperbanyak Kalium
Penelitian menunjukkan bahwa dengan mengkonsumsi 3500
miligram kalium dapat membantu mengatasi kelebihan kalium dapat
membantu mengatasi kelebihan natrium, sehingga dengan volume
darah yang ideal dpaat dicapai kembali tekanan yang normal. Kalium
bekerja mengusir natrium dari senyawanya, sehingga lebih muudah
dikeluarkan.
Sumber kalium mudah didapatkan dari asupan makanan seharihari. Misalnya, sebutir kentang rebus mengandung 838 miligram
kalium sehingga empat butir kentang (3352 miligram) akan mendekati
kebutuhan
tersebut.
Atau
dengan
semangkuk
bayam
yang
mengandung 800 miligram kalium cukup ditambah 3 butir kentang.
Makanan lain yang kaya kalium adalah pisang, sari jeruk, jagung,
kubis dan brokoli (vitahealth, 2004).
23
c. Penuhi Kebutuhan Magnesium
Juga ditemukan hubungan antara rendahnya asupan magnesium
dengan hipertensi. Tetapi belum dapat dipastikan berapa banyak
magnesium yang dibutuhkan untuk mengatasi hipertensi. Kebutuhan
magnesium menurut kecukupan gizi yang dianjurkan atau RDA
(Recommended
Dietary
Allawance)
adalah
350
miligram.
Kekurangan asupan magnesium terjadi dengan semakin banyaknya
makanan olahan yang dikonsumsi.
Sumber makanan yang kaya magnesium antara lain kacangkacangan dan bayam (vitahealth, 2004).
d. Memperbanyak Serat
Mengkonsumsi lebih banyak sayur atau makanan rumahan yang
mengandung banyak serat akan memperlancar buang air besar dan
menahan sebagian asupan natrium. Sebaiknya penderita hipertensi
menghindari makanan kalengan dan makanan siap saji dari restoran
(sejenisnya) yang dikhawatirkan mengandung banyak pengawet dan
kurang serat. Dari penelitian lain ditemukan bahwa dengan
mengkonsumsi 7 gram per hari dapat membantu menurunkan tekanan
darah sistolik sebanyak 5 poin. Konsumsi serat juga dapat
memperlancar buang air, menyebabkan makan lebih sedikit dan
mengurangi asupan natrium. Serat pun mudah didapatkan dalam
makanan (vitahealth, 2004)
e. Mengatur Menu Makanan
Mengatur menu makanan sangat dianjurkan bagi penderita
hipertensi untuk menghindari dan membatasi makanan yang dpat
meningkatkan kadar kolesterol darah serta meningkatkan tekanan
darah, sehingga penderita tidak mengalami stroke atau infark jantung.
Makanan yang harus dihindari atau dibatasi adalah (diet bagi
penderita hipertensi, pdf 2002):
24
1) Makanan yang berkadar lemak jenuh tinggi (otak, ginjal, paru,
minyak kelapa, gajih).
2) Makanan yang diolah dengan menggunakan garam natrium
(biscuit, craker, keripik dan makanan kering yang asin).
3) Makanan dan minuman dalam kaleng (sarden, sosis, korned,
sayuran serta buah-buahan dalam kaleng, soft drink).
4) Makanan yang diawetkan (dendeng, asinan sayur/buah, abon,
ikan asin, pindang, udang kering, telur asin, selai.
f. Vitamin
Fungsi dari vitamin yaitu untuk mempercepat metbolisme,
mempertahankan
fungsi
jaringan
tubuh
dan
mempengaruhi
pertumbuhan dan pembentukan jaringan.
Pada lansia vitamin sangat penting, terutama vitamin B1 agar
tubuh selalu bugar. Contoh makanan: beras merah Makanan yang
boleh: semua buah yang tidak diawtkan garam/ soda, air putih.
Makanan yang tidak boleh: durian, buah-buahan yang diawetkan oleh
garam dan soda, kopi dan coklat (gizi pada lansia hipertensi, pdf
2005).
g. Protein
Fungsi dari protein sebagai zat pembangun dari sel tubuh.
Pada lansia sebaiknya memilih daging unggas-unggasan daripada
daging sapi atau kambing dan hendaknya tidak makan lebih dari 2
potong daging pada sehari. Makanan yang boleh: daging, ikan telur
dan susu, semua kacang-kacangan dan sayuran. Makanan yang tidak
boleh: ikan asin, keju, kornet, ebi, telur asam, pindang, dendeng,
udang, kacang tanah dan sayuran yang dimasak/ diawetkan dengan
garam dapur (gizi pada lansia hipertensi, pdf 2005).
25
h. Karbohidrat
Fungsi karbohidrat adalah penyedia energi. Pada lansia konsumsi
gula dibatasi karena: Gula tidak mengandung gizi kecuali zat tenaga.
Sedangkan pada lansia konsumsi zat zat gizi lain seperti vitamin,
protein dan mineral diutamakan untuk mencegah proses penurunan
fungsi tubuh. Gula cepat diserap (absorpsi) sehingga mengakibatkan
perubahan kadar gula darah dan memungkinkan terjadinya obesitas
(kegemukan) dan diabetes. Makanan yang tidak boleh: Roti, biscuit
dan kue yang dimasak dengan garam dapur (gizi pada lansia
hipertensi, pdf 2005).
i. Lemak Dan Kolestrol
Batasi penggunaan minyak goreng, margarine, mentega, dan keju.
Dianjurkan menggunakan minyak yang mengandung lemak tak jenuh
seperti minyak zaitun, minyak kacang, minyak wijen, minyak jagung,
minyak kedele dan minyak biji bunga matahari. Tapi hindarkan
pemasakan yang menggunakan panas tinggi seperti menggoreng
maupun oven. Karena pemasakan seperti ini akan merusak lemak
sehingga justru lebih berbahaya (gizi pada hipertensi lansia, pdf
2005).
Di dalam penerapannya, diet rendah kolesterol dan lemak terbatas
perlu memerhatikan hal-hal berikut.
1) Hindari mengonsumsi bahan makanan sumber lemak jenuh,
seperti kelapa dan produk olahannya (minyak kelapa), lemak
hewan, margarin, dan mentega.
2) Batasi konsumsi daging dan jeroan, seperti hati, limpa, dan ginjal.
3) Ganti susu penuh (full cream) dengan susu rendah lemak,
misalnya susu skim.
4) Batasi konsumsi kuning telur. Di dalam seminggu, konsumsi
kuning telur tidak boleh lebih dari tiga kali.
5) Tingkatkan konsumsi tahu, tempe, dan jenis kacang-kacangan
lainnya.
26
6) Kurangi penggunaan gula dan makanan manis.
7) Perbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan.
8) Perhatikan kombinasi makanan yang dikonsumsi agar sesuai
dengan kadar kolesterol darah.
3. Aktivitas Fisik
Menurut Supariasa 2001, aktivitas fisik adalah gerakan yang
dilakukan oleh otot tubuh dan sistem penunjangnya. Selama melakukan
aktivitas fisik, otot membutuhkan
energi diluar metabolisme untuk
bergerak, sedangkan jantung dan paru-paru memerlukan tambahan energi
untuk mengantarkan zat-zat gizi dan oksigen ke seluruh tubuh dan untuk
mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh (Aisyiah 2009).
Melakukan aktifitas fisik yang cukup merupakan salah satu dari
banyak hal yang dikategorikan ke dalam pengobatan non farmakologis.
Aktifitas fisik yang cukup dan teratur terbukti dapat membantu
menurunkan tekanan darah. (dr Marliani dan Tantan 2007).
Pada zaman sekarang, dengan berbagai kemudahan membuat orang
enggan melakukan kegiatan fisik dalam kegiatan sehari-hari mereka.
Aktifitas fisik sangatlah penting untuk mengendalikan tekanan darah.
Aktifitas fisik yang cukup dapat membantu menguatkan jantung. Jantung
yang lebih kuat tentu dapat memompa lebih banyak darah dengan hanya
sedikit usaha. Semakin ringan kerja jantung, semakin sedikit tekanan
pada pembuluh darah arteri sehingga tekanan darah akan menurun.
(Marliani dan Tantan 2007).
Aktifitas fisik yang cukup dan teratur dapat mengurangi risiko
terhadap penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah selain dapat
membantu mengurangi berat badan pada penderita obesitas. ( Marliani
dan Tantan 2007).
Tekanan darah dipengaruhi oleh aktivitas fisik. Tekanan darah
akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas fisik dan lebih rendah
ketika beristirahat (Armilawati 2007). Seseorang dengan aktivitas fisik
yang kurang, memiliki kecenderungan 30%-50% terkena hipertensi
27
daripada mereka yang aktif. Penelitian dari Farmingharm Study
menyatakan bahwa aktivitas fisik sedang dan berat dapat
mencegah
kejadian stroke. Selain itu, dua meta-analisis yang telah dilakukan juga
menyebutkan hal yang sama. Hasil analisis pertama menyebutkan bahwa
berjalan kaki dapat menurunkan tekanan darah pada orang dewasa sekitar
2% (Kelley 2001). Analisis kedua pada 54 randomized controlled trial
(RCT), aktivitas aerobik menurunkan tekanan darah rata-rata 4 mmHg
TDS (tekanan darah sitole) dan 2 mmHg TDD (tekanan darah diastole).
(Aisyiah 2009).
Perubahan gaya hidup Sedentary merupakan gaya hidup dimana
gerak fisik yang dilakukan minimal sedang beban kerja mental maksimal.
Keadaan ini besar pengaruhnya terhadap tingkat kesehatan termasuk
keadaan gizi seseorang dan selanjutnya berakibat sebab penyebab dari
berbagai penyakit (Amir, 1997). Latihan fisik secara teratur kedalam
kegiatan sehari-hari adalah penting untuk mencegah hipertensi dan
penyakit jantung (Hull, 1996 dalam Angreini (2008)).
Sedangkan olahraga apa pun baik untuk kesehatan kita seperti
senam, berenang, jalan kaki, yoga, waitangkung, taichi, dan lain-lain.
Berolahraga bersama orang lain lebih menguntungkan, karena dapat
bersosialisasi, berjumpa dengan teman-teman, dan mendapat kenalan
baru, mengadakan kegiatan lainnya, seperti bisa berwisata dan makan
bersama. Kebanyakan olahraga dilakukan padapagi hari setelah subuh.
Dimana udara masih bersih, Berolahraga dapat menuurnkan kecemasan
dan mengurangi perasaan depresi dan lowself esistem. Selain fisik sehat
jiwa juga terisi, membuat kita merasa muda dan sehat diusia tua (Hariani,
2007).
Sejumlah studi menunjukkan bahwa olahrga teratur, mengurangi
beberapa faktor risiko terhadap PJK, termasuk hipertensi (Soeharto,
2000). Kemampuan aktifitas fisik yang berhubungan dengan kesehatan
akan mempengaruhi kemampuan tubuh untuk berfungsi secara baik,
komponen aktifitas fisik yang berhubungan dengan kesehatan akan
28
mempengaruhi kemampuan tubuh untuk berfungsi secara baik,
komponen tersebut antara lain efisiensi kardiovaskuler, kelenturan,
pengendalian berat badan, dan pengurangan stress (Stoel, 1986 dalam
amir, 1997).
Hasil penelitian Merdin (2003) terdapat hubungan, antara kurang
aktifitas fisik dengan kejadian hipertensi dengan OR 1,4 sehingga,
kurang beraktifitas akan meningkatkan risiko hipertensi sebesar 1,4 kali
(95% CI 1,025-1,8952). Pada tahun 1987, Paffen Berger meneliti para
alumni Harvard dan hasil penelitiannya menunjukan bahwa mereka yang
teratur berolahraga atau bekerja fisik secara teratur lebih sedikit terkena
serangan jantung. Survei Monica tahun 1983 dilakukan terhadap 2040
orang diwilayah Jakarta Selatan menunjukkan mereka yang teratur
memiliki resiko terendah untuk terkena hipertensi maupun penyakit
jantung koroner. (Kusmana, 1997 dalam Angreini (2008)).
Beberapa contoh olahraga yang sesuai dengan batasan diatas yaitu,
jalan kaki, dengan segala bentuk permainan yang ada unsur jalan kaki
misalnya golf, lintas alam, mendaki bukit, senam dengan faktor kesulitan
kecil dan olahraga yang bersifat rekreatif dapat diberikan. Dengan latihan
otot manusia lanjut dapat menghambat laju perubahan degenaratif.
Table 2:2. Kategori AKtifitas fisik (Sumber: Baecke (1982) dalam
Kamso 2000))
No
Aktifitas Fisik
Index Kerja (IK)
Skala
Tidak Pernah
Jarang
Kadang
Sering
Sangat Sering
Index Sport (IS)
Index
Luang
Tidak Pernah
Jarang
Kadang
Sering
Sangat Sering
Tidak Pernah
Jarang
Kadang
Sering
Sangat Sering
Waktu
Tingkat
1. Ringan : Supir, Guru, Pensiunan,
Pedagang tetap, Ibu rumah tangga dan
sejenisnya.
2. Sedang : Buruh Pabrik dan sejenisnya.
3. Berat : Buruh bangunan, Pedagang
keliling, dan Petani dan sejenisnya.
1. Ringan : Memancing.
2. Sedang : Bulu tangkis, Sepeda,
Senam, Renang, lari-lari keci.
3. Berat :Sepak Bola.
1.
2.
3.
4.
5.
<5 menit = 1
5-15 menit = 2
16-30 menit = 3
31-45 menit = 4
> 45 menit = 5
29
4. Pola Istirahat Dan Tidur
Tidur adalah suatu proses perubahan kesadaran yang terjadi
berulang-ulang selama periode tertentu (Potter & Perry, 2005). Menurut
Chopra (2003), tidur merupakan dua keadaan yang bertolak belakang
dimana tubuh beristirahat secara tenang dan aktivitas metabolisme juga
menurun namun pada saat itu juga otak sedang bekerja lebih keras
selama periode bermimpi dibandingkan dengan ketika beraktivitas di
siang hari (MP Dewi 2011)
Tidur merupakan salah satu kebutuhan pokok tubuh manusia untuk
memperbaiki fungsi organ dan masa pertumbuhan. Banyak para ahli
yang berpendapat jika kurang tidur dapat membahayakan kesehatan,
seperti mengakibatkan penyakit diabetes ataupun darah tinggi tetapi tidur
terlalu banyak juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi tubuh.
Dimulai dengan atherosclerosis, gangguan struktur anatomi pembuluh
darah perifer yang berlanjut dengan kekakuan pembuluh darah.
Kekakuan
pembuluh
kemungkinan
darah
pembesaran
disertai
plaque
dengan
yang
penyempitan
mennghambat
dan
gangguan
peredaran darah perifer. Kekakuan dan kelambanan aliran darah
menyebabkan
beban
jantung
bertambah
berat
yang
akhirnya
dikompensasi dengan peningkatan upaya pemompaan jantung yang
memberikan gambaran peningkatan tekanan darah dalam sistem sirkulasi
(Bustan, 2007).
Satu teori fungsi tidur adalah berhubungan dengan penyembuhan.
Teori lain tentang kegunaan tidur adalah tubuh menyimpan energi selama
tidur , otot skeletal berelaksasi secara progresif, dan tidak adanya
kontraksi otot menyimpan energi kimia untuk proses selular. Penurunan
laju metabolik basal lebih jauh menyimpan persediaan energi tubuh
(Anch dkk, 1988 dikutip dari Potter & Perry, 2005).
30
Istirahat yang cukup diperlukan agar tubuh dapat kembali ke
kondisi normal setelah digunakan untuk beraktifitas. Istirahat terbaik
adalah tidur. Tidur 6-8 jam sehari sudah lebih cukup. Tidur terlalu lama,
akan cenderung menggangu kesehatan. Sebagaimana dijelaskan diatas,
saat tidur pun tubuh butuh nutrisi. Bila tidur terlalu lama, tubuh akan
mengalami ketabolik. Akibatnya, akan semakin merasa malas, tidak
bertenaga, dan memboroskan waktu (Hudzifah.org,2007).
Kurang tidur dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk
mengingat informasi yang kompleks. Penelitian di Universitas de Lille,
Perancis, mengindikasikan bahwa otak memerlukan tidur untuk
mempertahankan kemampuan mengingat informasi yang kompleks.
Umumnya manusia bisa tidur dalam 6 s/d 8 jam sehari. Tapi terkadang
ada orang yang bisa tidur dibawah 6 jam. Kurang tidur berdampak
negatif bagi tubuh kita seperti konsentrasi, cepat marah, lesu.lelah.
(dechacare.com,2007).
Menurut (Angraeni 2008) Klasifikasinya adalah
a. Kurang < 6 jam satu hari.
b. Sedang 6-8 jam satu hari.
c. Lebih > 8 jam satu hari.
Istirahat yang cukup sangat dibutuhkan badan kita. Orang lansia
harus tidur enam sampai delapan jam sehari. Hasil riset terbaru para ahli
dari University of Chicago membuktikan, tiga hari mengalami kurang
tidur, kemampuan tubuh dalam memproses glukosa akan menurun secara
drastis, sehingga dapat meningkatkan risiko mengidap diabetes.
5. Pola Merokok
Merokok dapat menganggu kerja paru-paru yang normal, karena
Hemoglobin lebih mudah membawa Karbondioksida daripada membawa
Oksigen. Jika terdapat Karbondioksida dalam paru-paru, maka akan
dibawa oleh Hemoglobin sehingga tubuh memperoleh Oksigen yang
kurang dari biasanya. Kandungan Nikotin dalam rokok yang terbawa
dalam aliran darah dapat mempengaruhi berbagai bagian tubuh yaitu
31
mempercepat denyut jantung sampai 20 kali lebih cepat dalam satu menit
daripda dalam keadaan normal, menurunkan suhu kulit sebesar setengah
derajat karena penyempitan pembuluh darah kulit dan menyebabkan hati
melepaskan gula kedalam aliran darah (Amstrong, 1991 dalam Angreini
(2008)).
Merokok merupakan faktor resiko terpenting untuk terjadinya
penyakit tidak menular, karena dapat menyebabkan Arterio Sklerosis
dini, PJK, penyakit paru obstruktif menahun, kanker paru, Larynx,
rongga mulut, pancreas dan esofagus, selain itu juga dapat meningkatkan
tekanan darah dan kadar lemak dalam darah sebagai faktor resiko
terjadinya Stroke, penyakit jantung dan pembuluh darah (Kosen, 2001
dalam Siregar, 2006).
Merokok
sigaret
dengan
kandungan
nikotin
menyebabkan
peningkatan frekuensi denyut jantung serta meningkatkan tekanan
sistolik dan distolik, meskipun nikotin dan merokok menaikkan tekanan
darah secara akut, namun tidak selalu muncul pada perokok (Kaplan dan
Stample, 1994).
Zat-zat kimia beracun yang terdapat dalam rokok seperti nikotin
dan karbon monoksida dan diisap melalui rokok dibawa masuk kedalam
aliran darah. Selanjutnya zat ini merusak lapisan Endotel pembuluh darah
arteri, sehingga mengakibatkan tekanan darah meningkat , merokok juga
meningkatkan denyut jantung dan kebutuhan oksigen untuk disuplai ke
otot-otot jantung (Karyadi, 2002).
Farmingham
Heart
Study
menemukan
bahwa
merokok
menurunkan kadar kolesterol baik (HDL). Penurunan HDL pad,5 mg/dl
pada perempuan dan laki-laki rata-rata 6,5 mg/dl.
Perokok dikategorikan sebagai berikut:
a.
Perokok ringan
:<10 batang/hari
b.
Perokok sedang
: 10-20 batang/hari
c.
Perokok berat
: >20 batang/hari
32
Penelitian yang dilakukan oleh Lipid Research Program prevalence
study menunjukkan bahwa mereka yang merokok dua puluh batang atau
lebih perhari, mengalami penurunan kadar HDL sekitar 11% pada lakilaki dan 14% pada perempuan. Merokok juga mengurangi usia harapan
hidup, rata-rata 10 tahun. Atau apabila tidak merokok berarti menambah
usia harapan hidup rata-rata 10 tahun. (BKKBN.go.id,2007).
6. Perokok Pasif
Merokok tembakau sangat merugikan kesehatan perokok maupun
orang yang berada didekatnya. Merokok dapat atau mencetuskan
penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu penyakit jantung koroner,
berupa
infark
otot
jantung
sampai
serangan
angina
pektoris,
arteriosklorosis, dan penyakit pembuluh darah tepi. Perokok pasif, yaitu
mereka yang tinggal disekitar perokok, mempunyai resiko menderita
penyakit akibat merokok sama besarnya dengan perokok itu sendiri
(Joewana, Satya, M.D.2004).
Lebih dari 95% pasien penyakit jantung koroner adalah perokok
aktif, namun dari hasil penelitian ternyata perokok pasif, yaitu orang
yang hidup disekitar perokok aktif sehari-hari mempunyai resiko yang
sama dengan perokok aktif. Perokok aktif biasanya memulai kebiasaan
sejak masa sangat muda/kanak-kanak dan setelah berpuluh tahun
kemudian, yaitu usia produktif mereka menuai hasilnya berupa
penyakit jantung kororner. (Joewana, Satya, M.D.2004).
Pada jantung, hipertensi mengakibatkan pembengkakan jantung
yang gilirannya akan memudahkan seseorang terkena serangan jantung
maupun gagal jantung. Gagal jantung menyebabkan seseorang tidak
mampu lagi bekerja sehari-hari karena selalu sesak nafas setiap
melakukan kegiatan sehingga menjadi seseorang tidak produktif lagi
karena jantung telah gagal memenuhi fungsinya untuk memompakan
kehidupan keseluruh tubuh. (dr. J.B. Cahyono, Suharjo B. SpPD, 2008).
33
Studi pertama mengenai pengaruh perokok pasif berhasil
menemukan fakta bahwa menghirup asap rokok orang lain telah
menyebabkan 600.000 kematian setiap tahun, sekitar satu dari 100 di
seluruh dunia.
Sekitar 5,1 juta kematian yang merupakan akibat merokok (aktif),
untuk mendapatkan efek penuh dari merokok secara aktif maupun pasif.
Kebiasaan merokok ini menyebabkan lebih dari 5,7 juta kematian setiap
tahun.
Paparan asap rokok diperkirakan telah mengakibatkan 379.000
kematian perokok pasif dari penyakit jantung, 165.000 dari infeksi
saluran pernafasan, 36.900 dari asma, dan 21.400 dari kanker paru-paru
(Marie Claire 2012 dalam Irfan Arief 2012)
D.
Variabel Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mempunyai variabel
tunggal / mandiri yaitu gaya hidup lansia hipetensi. Penelitian deskiptif
adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa
membuat perbandingan atau menghubungkan
dengan variabel lain.
(Sugoyono, 2002).
E.
Kerangka Teori
Dalam Undang-undnag No. 23 Tahun 1992, kesehatan mencakup 4 aspek,
yakni fisik (badan), mental (jiwa), sosial dan ekonomi, namun penelitian
hanya menggunakan 2 aspek di dalam penelitian ini, yaitu aspek fisik (badan)
dan aspek mental dalam status kesehatan pada lansia, dimana kesehatan fisik
terwujud apabila seseorang tidak merasa sakit atau tidak adanya keluhan dan
memang secara klinis tidak adanya penyakit. Semua organ tubuh berfungsi
normal atau tidak ada gangguan fungsi tubuh. Sedangkan kesehatan mental
dapat terlihat dari 3 komponen, yakni: fikiran, emosional dan spiritual
(Notoatmodjo, 2005).
Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut diatas status kesehatan pada lansia
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu antara lain adalah Endogenic
aging dan Exogenic faktors.
34
Dimana Endogenic aging yaitu dimulai dengan cellular aging, lewat tissue
dan anatomical aging kearah proses menuanya organ tubuh dan exogenic
faktors yaitu adalah faktor-faktor dari luar, seperti gaya hidup dan lingkungan
(darmojo 2006). Dari dua faktor tersebut, diambil hanya variabel gaya hidup
yang terdapat pada exogenic faktors, dimana variabel-variabel dalam gaya
hidup yang diambil adalah hanya Pola makan, aktifitas fisik, kebiasaan
merokok dan kebiasaan istirahat, maka terbentuklah kerangka konsep sebagai
berikut:
Gambar Skema 2:1
Kerangka Teori (Boedi-Darmojo 2006)
Endogenic faktor
(tidak dapt
diubah)
1. Kelamin
2. Genetic
3. Ras/suku
4. Umur/degene
ratif
Exogenix faktor (dapat
diubah)
hipertensi
Life style (gaya
hidup)
1. Aktifitas fisik
2. Pola makan
3. Kebiasaan
merokok
4. Pola istirahat
Ket:
Tidak diteliti
Diteliti
Anda mungkin juga menyukai
- DokumenDokumen13 halamanDokumenRohadhatul AtikaBelum ada peringkat
- Tugas Gerotik Gangguan Kardiovaskuler Pada LansiaDokumen11 halamanTugas Gerotik Gangguan Kardiovaskuler Pada Lansiaolineajjah100% (2)
- Laporan Pendahuluan Praktik Keperawatan Gerontik Pada Penerima Manfaat Dengan HipertensiDokumen23 halamanLaporan Pendahuluan Praktik Keperawatan Gerontik Pada Penerima Manfaat Dengan HipertensiAnisa NadhirohBelum ada peringkat
- LP Gerontik HadiDokumen47 halamanLP Gerontik HadihadiBelum ada peringkat
- Imobilitas Pada LansiaDokumen11 halamanImobilitas Pada LansiaNunki Eka Artura Sari IIBelum ada peringkat
- GerontikDokumen68 halamanGerontikRismala PramudithaBelum ada peringkat
- Teori Proses MenuaDokumen14 halamanTeori Proses MenuaDewaWisnuBudiSuryawanBelum ada peringkat
- BAB II EditDokumen29 halamanBAB II EditVirna SoaresBelum ada peringkat
- Bab 2Dokumen27 halamanBab 2Rizqika MahardikaBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen29 halamanBab IiVirna SoaresBelum ada peringkat
- Makalah Hipertensi LansiaDokumen17 halamanMakalah Hipertensi LansiaNikmah El-husna HusainBelum ada peringkat
- LP GerontikDokumen24 halamanLP GerontikNur lailah sakinahBelum ada peringkat
- Asuhan Keperawatan Pada LansiaDokumen12 halamanAsuhan Keperawatan Pada LansiaLianBelum ada peringkat
- LP GGN Kardiovaskuler LansiaDokumen12 halamanLP GGN Kardiovaskuler Lansiarosmini100% (1)
- LP DM GerontikDokumen19 halamanLP DM GerontikNovianti Lailiah67% (3)
- Pembahasan Tugas Patooo DegeneratifDokumen18 halamanPembahasan Tugas Patooo Degeneratifniwayan budiariBelum ada peringkat
- Askep Gadar Trauma LansiaDokumen18 halamanAskep Gadar Trauma LansiaNur Anisya100% (1)
- AskepDokumen15 halamanAskepKharismatul MaghvirohBelum ada peringkat
- Bab I Pendahuluan 1Dokumen42 halamanBab I Pendahuluan 1Ryan FirnandaBelum ada peringkat
- LansiaDokumen4 halamanLansiaVanBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen29 halamanBab IiNiar HasbullahBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen5 halamanBab IianandaBelum ada peringkat
- Hipertensi Lansia PDFDokumen35 halamanHipertensi Lansia PDFDöèlkhä Room Ibs100% (2)
- Masalah Kesehatan Yang Sering Dijumpai Pada DewasaDokumen10 halamanMasalah Kesehatan Yang Sering Dijumpai Pada DewasaNoviade JusmanBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen30 halamanBab IiLely JuniariBelum ada peringkat
- BAB II RevisiDokumen18 halamanBAB II RevisiNindy ElfaniaBelum ada peringkat
- LAPORAN PENDAHULUAN KolestrolDokumen13 halamanLAPORAN PENDAHULUAN KolestrolCV Jazirah GrafikaBelum ada peringkat
- Lapsus Geriatri RSP FixfixDokumen30 halamanLapsus Geriatri RSP FixfixIkha Shafiyyah100% (2)
- Imobility LPDokumen16 halamanImobility LPfarih jaya ahmadiBelum ada peringkat
- Lansia Dan KemandirianDokumen18 halamanLansia Dan KemandirianAmanda Kardinasari100% (1)
- Makalah Senam LansiaDokumen15 halamanMakalah Senam LansiaAnonymous eS8cbvYz1100% (3)
- Makalah AgingDokumen12 halamanMakalah Agingnurfarida kausaBelum ada peringkat
- BAB II FleksibilitasDokumen35 halamanBAB II FleksibilitasYosi FadhilahBelum ada peringkat
- Bab Ii Fungsi KognitifDokumen40 halamanBab Ii Fungsi KognitifHeni Ayu Purnama100% (3)
- Tutorial MuskulosDokumen16 halamanTutorial MuskulosTiara TiaBelum ada peringkat
- LP LansiaDokumen14 halamanLP Lansiadini rismaladewiBelum ada peringkat
- 11210005-Yohanes Enggal Pastike-D3 KEPERAWATAN-PROSES DEGENERATIFDokumen10 halaman11210005-Yohanes Enggal Pastike-D3 KEPERAWATAN-PROSES DEGENERATIFSay MitaBelum ada peringkat
- Laporan Asuhan Keperawatan FriskiDokumen40 halamanLaporan Asuhan Keperawatan FriskifriskiayulpBelum ada peringkat
- Tuga Rhematoid Artritis SantiDokumen13 halamanTuga Rhematoid Artritis Santiafrida pratiwiBelum ada peringkat
- Kelompok 1 Makalah Keperawatan GerontikDokumen20 halamanKelompok 1 Makalah Keperawatan GerontikFirnawati MaspekeBelum ada peringkat
- Tugas Sindrom GeriatriDokumen20 halamanTugas Sindrom Geriatrinovriadi suhendraBelum ada peringkat
- Tinjauan Pustaka Jatuh Pada LansiaDokumen13 halamanTinjauan Pustaka Jatuh Pada LansiaPradnyadewi NataswariBelum ada peringkat
- Digital 126399 S 5765 Hubungan Asupan LiteraturDokumen26 halamanDigital 126399 S 5765 Hubungan Asupan LiteraturdawamjamilBelum ada peringkat
- Askep RinaDokumen22 halamanAskep RinaJusmanBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen33 halamanBab IiVirna SoaresBelum ada peringkat
- PBL SK 4 SoqiDokumen11 halamanPBL SK 4 SoqimiftaBelum ada peringkat
- LP Panti Werda Pekan 1Dokumen58 halamanLP Panti Werda Pekan 1ink ianBelum ada peringkat
- LP 2 DemensiaDokumen57 halamanLP 2 DemensiaKikiBelum ada peringkat
- Makalah Patofisiologi Senam LansiaDokumen14 halamanMakalah Patofisiologi Senam LansiaYoga RyzkyBelum ada peringkat
- KLP 1 Askep Rhematoid ArthritisDokumen59 halamanKLP 1 Askep Rhematoid ArthritisWulandariBelum ada peringkat
- KLP 1 Askep Rhematoid Arthritis-2Dokumen54 halamanKLP 1 Askep Rhematoid Arthritis-2YociYn NewBelum ada peringkat
- REFERAT Giant Geriatri Fix LionDokumen37 halamanREFERAT Giant Geriatri Fix Lionlionerz4899100% (1)
- Bab IiDokumen23 halamanBab IiJeje BEM BinusBelum ada peringkat
- Laporan Pendahuluan Lansia - Maria Rosari TjemeDokumen12 halamanLaporan Pendahuluan Lansia - Maria Rosari TjemesaryBelum ada peringkat
- LP MenuaDokumen9 halamanLP MenuaFitria EloquentBelum ada peringkat
- Askep Gerontik Ny IDokumen28 halamanAskep Gerontik Ny IWahyudiBelum ada peringkat
- 33 - Syahrul Rahman - 203110195 - Proses MenuaDokumen4 halaman33 - Syahrul Rahman - 203110195 - Proses MenuaSyahrul RahmanBelum ada peringkat
- LP Lansia Resiko JatuhDokumen12 halamanLP Lansia Resiko JatuhChandra WidyastutiBelum ada peringkat
- Pembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisDari EverandPembedahan Skoliosis Lengkap Buku Panduan bagi Para Pasien: Melihat Secara Mendalam dan Tak Memihak ke dalam Apa yang Diharapkan Sebelum dan Selama Pembedahan SkoliosisPenilaian: 4 dari 5 bintang4/5 (13)
- Jurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Dari EverandJurnal Perawatan Skoliosis Natural Anda: Petunjuk per hari selama 12 minggu untuk tulang belakang yang lebih lurus dan kuat!Penilaian: 4.5 dari 5 bintang4.5/5 (7)