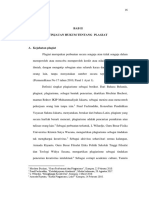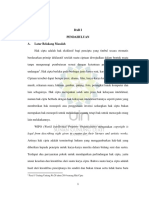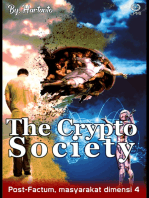Epigonisme Dan Plagiarisme
Diunggah oleh
Meidiawan Cesarian SyahHak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
Epigonisme Dan Plagiarisme
Diunggah oleh
Meidiawan Cesarian SyahHak Cipta:
Format Tersedia
Epigonisme
dan Plagiarisme: Fenomena Miskin Identitas
Oleh: Meidiawan Cesarian Syah
Orang Indonesia harus memahami tentang mahalnya sebuah ide, keluh saya pada suatu ketika. Di layar kaca, media utama yang mempengaruhi alam bawah sadar sebagian besar penduduk negeri ini, banyak sekali ide yang dipermainkan, ditiru sebagian, bahkan dijiplak mentah-mentah. Sudah tidak ada lagi batas toleransi penghargaan atas orisinalitas sebuah ide. Kemudian ingatan saya berlabuh pada beberapa tahun lalu. Saat itu saya membaca artikel sebuah surat kabar yang membanding-bandingkan antara epigonisme dan plagiarisme, dua jenis pengambilan ide orang lain. Berbagi perspektif, itu yang hendak saya coba lakukan. Tidak selamanya pengambilan ide orang lain itu buruk, meskipun saya tidak menganjurkan hal demikian. Sedihnya, di Indonesia seni comot-mencomot ide ini sangat serampangan sehingga kemonotonan saja yang kita dapat. Sedikit dari mereka benar-benar menyuguhkan pesona baru. Lack of creativity. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiarisme atau sering disebut plagiat adalah penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat, sebagus apapun, hanya merupakan kejahatan intelektual. Pelakunya, plagiator, mencederai pilar-pilar ilmu pengetahuan yang paling dasar. Bebepara orang lebih suka menyebut mereka pencuri hak cipta. Pencuri, sebagaimana maling ayam, sangat pantas mendapatkan hukuman. Di Indonesia, plagiarisme dapat dianggap sebagai tindakan pidana karena pencurian hak cipta. Sayangnya, dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang tindakan plagiarisme ini. Tetapi bukan berarti para plagiat bisa melenggang begitu saja. Dalam kacamata hukum, kegiatan plagiarisme termasuk pencurian hak cipta seperti disebutkan sebelumnya, diatur melalui UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Sanksi hokum yang membayangi kegiatan plagiarism sesuai pasal 72 ayat (1) UU Hak Cipta adalah pidana penjara masing-masing paling singkat 1 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00. Hal yang harus digarisbawahi dari sanksi tersebut adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran Hak Cipta menurut UU Hak Cipta sendiri itu terjadi apabila memenuhi beberapa unsur, yakni adanya ciptaan yang dilindungi hak cipta dan perlindungannya masih berlaku, adanya bagian dari ciptaan tersebut yang diperbanyak, dan kegiatan memperbanyak tersebut tidak sesuai dengan kegiatan yang dibenarkan melalui UU ini dan tanpa sepengetahuan pemilik hak cipta. KEtiga unsur ini sifatnya akumulatif, jadi suatu kegiatan dianggap plagiarisme apabila memenuhi kriteria tersebut. Plagiat mencederai ilmu, mencederai ide, mencederai kejujuran. Saya sendiri sedikit menyayangkan banyak diantara kita yang terlambat atau bahkan tidak
pernah memiliki hak cipta atas gagasan kita sendiri, yang dilindungi negara tentunya. Makanya banyak juga yang asal comot tulisan orang tanpa menyertakan sumbernya, seperti fenomena yang beberapa waktu lalu ramai di twitter. Well, agaknya menyidangkan plagiator masih susah. Fenomena kedua yang tidak kalah heboh adalah epigonisme. Epigonisme berasa; dari kata epigon. Epigon adalah orang yang tidak memiliki gagasan baru dan hanya mengikuti jejak pemikir atau seniman yg mendahuluinya. Sebutan singkatnya: peniru. Sadar atau tidak di tiap diri kita pastilah terdapat sifat seorang epigon. Saya tidak mempermasalahkannya, yang jadi masalah adalah siapa pun yang mencari nafkah dengan menjadi epigon. Come on, dudeyoure a lot more than that. Epigon paling sering saya temukan di toko buku. Saat novel The Da Vinci Code dan Ayat- Ayat Cinta booming, entah darimana asalnya keluar pelbagai macam novelis yang mengekor dengan menerbitkan novel serupa yang tak sama. Saat The Da Vinci Code menjadi terkenal, maka toko buku tiba-tiba disesaki oleh novel konspirasi, bermacam-macam. Alam bawah sadar kita dipenuhi keseragaman yang sama ketika kita melihan televise. Band, sinetron, reality show, dan acara lain pun konsepnya sama. Saya sampai bingung sebenarnya siapa yang memulai trend music melayu, sinetron yang mengurai air mata (ya, temanya juga ga jauh-jauh dari masalah warisan dan kekayaan) atau acara musik. Tidak ada pelanggaran hukum dalam epigonisme. Sang epigon bisa leluasa melakukan kegiatannya, dan bagi orang yang karyanya ditiru juga tidak bisa apa- apa. Fair enough, maybe. Seperti telah saya katakan tadi, epigon bisa jadi ada di diri kita semua, bukan? Memang tidak semua epigon buruk, ada epigon yang berhasil mengembangkan gagasan orang lain yang ditirunya. Namun, apabila tanpa izin, saya kira itu tetap saja hal yang negatif. Ide itu mahal. Hal paling buruk bagi seorang epigon adalah dia (atau karyanya) tidak akan dikenal siapapun karena selamanya tidak punya identitas. Ia hidup sebagai peniru, menyajikan menu yang sudah disediakan hari sebelumnya. Penikmatnya pun mengecap manis sesaat, lalu lupa, karena sesuatu yang mereka rasakan itu tanpa identitas. Pada akhirnya, epigon dan plagiator akan hidup tanpa identitas. Celakanya, tiap hari kita disuguhkan benda tersebut melalui tayangan di televisi kita. Perbedaan nama yang seragam, saya menyebutnya. Apakah ide itu begitu mahal untuk dihasilkan? Atau terlalu murah sehingga lebih baik untuk meniru? Entahlah, saya cuma mengajak agar kita punya identitas dalam hidup yang bukan hanya nama. (penulis adalah mahasiswa yang tanpa perguruan tinggi, nirgelar, dan hanya bisa menerka-nerka)
Anda mungkin juga menyukai
- Makalah Hak Cipta Dan PatenDokumen14 halamanMakalah Hak Cipta Dan PatenPrimsBelum ada peringkat
- Hak Cipta IndonesiaDokumen6 halamanHak Cipta Indonesiabapa bipiBelum ada peringkat
- MEMAHAMI HAK MILIK INTELEKTUALDokumen7 halamanMEMAHAMI HAK MILIK INTELEKTUALRosidyLeoBelum ada peringkat
- Inf Presentasi 1Dokumen16 halamanInf Presentasi 1Weeb NosBelum ada peringkat
- MPPH ProposalDokumen17 halamanMPPH ProposalDevi HartadyBelum ada peringkat
- PlagiarismeDokumen37 halamanPlagiarismebektisuhartimahBelum ada peringkat
- Plagiat Dalam BerkaryaDokumen1 halamanPlagiat Dalam BerkaryaNovia ApriliantiBelum ada peringkat
- Makalah PlagiasiDokumen9 halamanMakalah PlagiasiMisbah Yeoja DarlingElfishyBelum ada peringkat
- PengaruhPlagiarismeDesainGrafisDokumen8 halamanPengaruhPlagiarismeDesainGrafis019Fajar FerdiansyahBelum ada peringkat
- MakalahDokumen194 halamanMakalahayodya septiBelum ada peringkat
- PencegahanPlagiatKaryaSeniDokumen2 halamanPencegahanPlagiatKaryaSeniSAKTIBelum ada peringkat
- Tindakan Plagiat PBAKDokumen9 halamanTindakan Plagiat PBAKReza OktaviaBelum ada peringkat
- Tanya Jawab Plagiarisme PDFDokumen18 halamanTanya Jawab Plagiarisme PDFFairuzul MumtazBelum ada peringkat
- Cara Mencegah PlagiarismeDokumen4 halamanCara Mencegah PlagiarismeYufa SekarBelum ada peringkat
- KERUSAKANNEGARAAKIBATKORUPSIDokumen6 halamanKERUSAKANNEGARAAKIBATKORUPSIAndorra BimbiBelum ada peringkat
- Plagiat di Sektor PendidikanDokumen5 halamanPlagiat di Sektor PendidikanAbrory FitriyantoBelum ada peringkat
- Makalah PlagiarismeDokumen8 halamanMakalah PlagiarismeSandra Saffira0% (1)
- PlagiarismeDokumen5 halamanPlagiarismeDwn KrmBelum ada peringkat
- Semua Hasil Karya Senin Adalah CurianDokumen13 halamanSemua Hasil Karya Senin Adalah CurianGitaBelum ada peringkat
- Skripsi KriminologiDokumen23 halamanSkripsi KriminologiMahupala UnibBelum ada peringkat
- Makalah-Plagiarisme CompressDokumen16 halamanMakalah-Plagiarisme CompressSukma JelekBelum ada peringkat
- KEPODokumen1 halamanKEPOLiana Shinta DewiBelum ada peringkat
- Analisis Kasus HakiDokumen6 halamanAnalisis Kasus HakiAnnisa Amelia FirdhaniBelum ada peringkat
- Tgs Perbandingan Agama Pak Dewo (Jadi)Dokumen7 halamanTgs Perbandingan Agama Pak Dewo (Jadi)Felicia AureliaBelum ada peringkat
- MAKALA HKI SalinanDokumen7 halamanMAKALA HKI SalinanJefri ReinnatiBelum ada peringkat
- Bab Ii Kajian Toeri Plagiat PDFDokumen34 halamanBab Ii Kajian Toeri Plagiat PDFAhmad RoufBelum ada peringkat
- TINJAUAN HUKUM PLAGIATDokumen14 halamanTINJAUAN HUKUM PLAGIATCyclone JokerBelum ada peringkat
- KATA BIJAK YG KOPLAKDokumen7 halamanKATA BIJAK YG KOPLAKReza PrasetyoBelum ada peringkat
- Tiga Tesis Tentang PosmodernismeDokumen6 halamanTiga Tesis Tentang PosmodernismeGaloeh NatraBelum ada peringkat
- Skripsi KriminologiDokumen23 halamanSkripsi Kriminologiinbom 123Belum ada peringkat
- Study Kasus HaKIDokumen5 halamanStudy Kasus HaKIGagga RagazzaBelum ada peringkat
- Total PlagiarismeDokumen2 halamanTotal Plagiarismearaka nusantaraBelum ada peringkat
- HUKUM HAK CIPTADokumen112 halamanHUKUM HAK CIPTATinabeautyBelum ada peringkat
- Persembahan X-RatedDokumen5 halamanPersembahan X-RatedjamaljaafarBelum ada peringkat
- Plagiarisme Dalam Perspektif PancasilaDokumen7 halamanPlagiarisme Dalam Perspektif PancasilaDavidBelum ada peringkat
- TolongDokumen41 halamanTolongAyaaBelum ada peringkat
- Open MindedDokumen3 halamanOpen Mindedzean arifinBelum ada peringkat
- Bab IiDokumen16 halamanBab IijalakBelum ada peringkat
- Buku Sejarah Hak Cipta LukisanDokumen3 halamanBuku Sejarah Hak Cipta LukisanVevinBelum ada peringkat
- MAKALAHDokumen13 halamanMAKALAHLuluul JannahBelum ada peringkat
- Kasus Pelanggaran Hak Cipta Fotokopi Buku Dan FilmDokumen3 halamanKasus Pelanggaran Hak Cipta Fotokopi Buku Dan FilmTria Wulan Suci RamadhaniBelum ada peringkat
- Makalah Plagiat-1Dokumen14 halamanMakalah Plagiat-1resaBelum ada peringkat
- Bab IiiDokumen15 halamanBab IiiAndhini AfrilianiBelum ada peringkat
- B.indo Topik 9-15Dokumen99 halamanB.indo Topik 9-15Polan LauBelum ada peringkat
- Korupsi dan Aksi RakyatDokumen2 halamanKorupsi dan Aksi Rakyatputri vinaBelum ada peringkat
- Jenayah Cetak RompakDokumen8 halamanJenayah Cetak RompakShonnia SiminBelum ada peringkat
- KASUS PLAGIARISME REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHADokumen13 halamanKASUS PLAGIARISME REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHAKetut Argo M WBelum ada peringkat
- Tugas Akhlak Tasawuf Kelompok 7 (Isi)Dokumen7 halamanTugas Akhlak Tasawuf Kelompok 7 (Isi)AnsyariBelum ada peringkat
- AkhbarDokumen13 halamanAkhbarDayang Rudiah AimiBelum ada peringkat
- Uts DdipbDokumen6 halamanUts DdipbDanty Alya Bestari0% (1)
- Begal Dalam Perspektif Kriminologi DanDokumen16 halamanBegal Dalam Perspektif Kriminologi DansalvatorealfinBelum ada peringkat
- (FHUI) Hak Atas Kekayaan IntelektualDokumen17 halaman(FHUI) Hak Atas Kekayaan IntelektualAbednego ManullangBelum ada peringkat
- Uas Kriminolog - Haiqal Hafidz Suryadi - B1a018252Dokumen7 halamanUas Kriminolog - Haiqal Hafidz Suryadi - B1a018252haiqal hafidzBelum ada peringkat
- Sekilas Tentang Budaya LatahDokumen2 halamanSekilas Tentang Budaya LatahAhmad FaidyBelum ada peringkat
- Saya WidyaDokumen11 halamanSaya WidyawidyanadarlisBelum ada peringkat
- Artikel Argumentasi - FarahDokumen10 halamanArtikel Argumentasi - FarahFarah SalviaBelum ada peringkat
- Kesesatan LogikaDokumen7 halamanKesesatan LogikaGhias AsrfBelum ada peringkat
- Haki 3Dokumen6 halamanHaki 3Naomi PanggabeanBelum ada peringkat
- Semua kebetulan aneh dalam hidup Anda. Peristiwa aneh kecil. Firasat. Telepati. Apakah itu terjadi pada Anda juga? Fisika kuantum dan teori sinkronisitas menjelaskan fenomena ekstrasensor.Dari EverandSemua kebetulan aneh dalam hidup Anda. Peristiwa aneh kecil. Firasat. Telepati. Apakah itu terjadi pada Anda juga? Fisika kuantum dan teori sinkronisitas menjelaskan fenomena ekstrasensor.Penilaian: 5 dari 5 bintang5/5 (4)
- Are You Your Parents Favourite ChildDokumen2 halamanAre You Your Parents Favourite ChildMeidiawan Cesarian SyahBelum ada peringkat
- Non Deliverable ForwardDokumen2 halamanNon Deliverable ForwardMeidiawan Cesarian SyahBelum ada peringkat
- Am I Wrong If I Born GayDokumen2 halamanAm I Wrong If I Born GayMeidiawan Cesarian SyahBelum ada peringkat
- Penjelasan Sederhana Mengenai Pertumbuhan EkonomiDokumen4 halamanPenjelasan Sederhana Mengenai Pertumbuhan EkonomiMeidiawan Cesarian SyahBelum ada peringkat