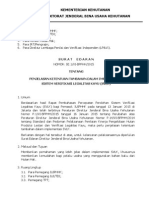As Jati Milik Di Blora
Diunggah oleh
Agus SumindarDeskripsi Asli:
Judul Asli
Hak Cipta
Format Tersedia
Bagikan dokumen Ini
Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?
Apakah konten ini tidak pantas?
Laporkan Dokumen IniHak Cipta:
Format Tersedia
As Jati Milik Di Blora
Diunggah oleh
Agus SumindarHak Cipta:
Format Tersedia
Historisitas Jati Milik di Blora
ditulis oleh: agus budi purwanto (ARuPA)
1. Pendahuluan Catatan para sarjana kehutanan dan sarjana ilmu sosial humaniora menyebutkan bahwa hutan jati di Jawa mengalami signifikansi eksploitasi pada abad ke-17. Sementara itu, modernisasi pengelolaan hutan jati dilakukan oleh Belanda pada abad ke-19 dengan mengadopsi ilmu kehutanan modern dari Jerman (Peluso 1990, 2006; Poffenberger 1990, 1994; Warto 2001; Arupa et all 2005). Empat abad hutan jati di Jawa berada di 2,4 juta hektar tanah negara dan dikelola oleh perusahaan negara bernama boschwezen atau Perhutani pada era Indonesia merdeka. Perusahaan negara menguasai dan mengelola hutan jati dalam kerangka tiga hal yaitu tanah hutan, spesies jati, dan tenaga kerja (Peluso 1990, 2006). Dalam kurun waktu tersebut, interaksi antara penduduk lebih dari setengah juta desa hutan dengan hutan jati selalu ada baik berwujud tenaga kerja maupun kelompok kepentingan lain yang bersinggungan dengan pengelola hutan negara. Pada sisi lain, paruh kedua abad ke-20, pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan menjalankan serangkaian program penanaman tanaman keras di lahan milik penduduk. Pada tahun 1980an masyarakat mulai menanam jati, sengon, mahoni, dan lain-lain di lahan milik secara swadaya. Tanaman kayu di lahan milik sering disebut hutan rakyat. Spesies jati di hutan rakyat menarik untuk dikaji lebih lanjut mengingat Perhutani telah lama dikenal sebagai penguasa dari tanah, spesies, dan tenaga kerja di hutan negara. Selain itu, pilihan menanam jati di lahan milik merupakan fenomena perubahan agraria yaitu perihal pemanfaatan dan fungsi lahan milik. Secara ringkas, tulisan ini menjelaskan sejarah hutan rakyat jati di Jawa dan perubahan agraria yang terjadi pada lahan milik petani Jawa.
2. Historisitas Hutan Rakyat di Blora Hutan rakyat di Jawa telah berkembang pada abad ke-20, terutama pada paruh keduanya. Periodenya kami bagi menjadi tiga fase yaitu periode kolonial, periode konservasi, periode ekonomi. Fase pertama, pada tahun 1930 pemerintah kolonial Belanda melaksanakan program penanaman pohon di lahan milik. Pada saat itu, penduduk jawa sebesar 40,89 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 309 jiwa/km2 (Simon, 1999). Coster seorang pakar kehutanan Belanda melakukan eksperimen tentang hutan dan erosi. Berdasarkan hasil eksperimen lapangan yang dilakukan di Ciwidey Bandung, di dapat kesimpulan bahwa peranan utama fungsi hidro-logi yaitu resapan air adalah tumbuhan di bawah tegakan kayu hutan dan seresah. Oleh karena itu, untuk mempertahankan mencegak erosi dan meningkatkan fungsi hidrologi, hutan harus tetap ada tanaman di bawah tegakan baik berupa rumput maupun semak belukar dan tidak boleh membuang seresah.
Coaster adalah pemimpin dari Badan Reboisasi tahun 1930 yang akhirnya memberikan bibit tanaman keras untuk ditanam di lahan milik warga untuk mengurangi peluang masyarakat mencuri kayu serta sebagai proses perbaikan lahan kritis di pekarangan. Namun pada dasarnya, pekarangan di Jawa Tengah Jawa Timur, serta talun di Jawa barat telah berkembang pada awal abad ke-20. Menurut Awang, terdapat korelasi antara model-model pekarangan dengan model-model tegalan yang komposisi tanamannya mirip dengan komposisi tanaman yang ada di pekarangan. Seandainya pedesaan di Jawa di lihat dari udara, maka yang terlihat adalah hamparan tanaman berbentuk kotak-kotak, hanya tajuk tanaman keras saja yang terlihat. Sementara satuan pemukiman dan fasilitas sosial lainnya nyaris tidak terlihat dari udara (Awang dkk, 2001). Artinya, pada awal abad ke-20 masyarakat pedesaan di Jawa telah menanam tanaman keras di pekarangan, terutama tanaman buah yang seperti kelapa, nangka, dan lain-lain. jadi, bukan kayu yang menjadi obyek eksploitasinya. Fase kedua, pada tahun 1952, 196an 1990an merupakan era program-program penghijauan di lahan milik mulai digalakkan kembali. Tahun 1952 Kementrian Kemakmuran membuat program menanam pohon-pohonan di tegal atau pekarangan yang disebut Karangkritri. Program ini belum sempat diwujudkan karena alasan keuangan dan organsisasi (Awang dkk 2001: 28). Kemudian tahun 1960an hingga tahun 1990an dimulailah program penghijauan baik berupa konservasi lahan kritis dan kering maupun program penghijauan pekarangan. Teknisnya, masyarakat diberikan bibit oleh dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (Dinas PKT lalu sejak tahun 1999 berubah menjadi Dinas kehutanan ataupun Dinas Kehutanan dan Perkebunan). Lalu masyakarakat yang dikoordinir oleh kepala desa dan petugas penyuluh menanam bibit tanaman keras di lahan milik baik pekarangan maupun tegalan. Dalam perjalanan program ini, di berbagai daerah di Jawa pada awalnya tidak berjalan dengan baik terutama di lahan tegalan. Sepertinya, kondisi pedesaan pada awal abad ke-20 yang digambarkan Awang di atas (Awang dkk 2001) berbeda dengan kondisi pedesaan pada tahun 1960-1970an terutama pada konteks tegalan. Berdasarkan hasil penelilitian kecil yang kami lakukan di wilayah kabupaten Blora bagian utara, penduduk desa banyak yang menolak proyek rehabilitasi lahan kritis dengan strategi menolak menanam ataupun mencabuti bibit tanaman keras yang telah ditanam oleh dinas Perhutanan dan Konservasi Lahan pada tahun 1960an-1970an. Jadi sepertinya, terdapat perbedaan antara pola pemanfaatan pekarangan dan tegalan pada periode ini. Masih pada periode 1960-1970an, kontribusi terhadap pengembangan tanaman keras di lahan milik tidak hanya dilakukan oleh dinas Perhutanan dan Konservasi Lahan, Perhutani melalui program prosperity approach pada tahun 1970an awal menggandeng kepala desa untuk mengintegrasikan program penanaman tanaman keras di hutan negara dengan penanaman tanaman keras di lahan milik. Pada waktu itu, diharapkan program ini dapat menghentikan masyarakat desa hutan dalam mencuri kayu di kawasan hutan negara. Kepala desa dianggap representasi kekuasaan politik dan kultural di desa. Sehingga konstruksi pengetahuan tentang pentingnya keutuhan aset kayu Perhutani dapat disebarluaskan oleh Kepala desa. Program ini juga dilakukan di kabupaten Blora. Sebagai contoh di desa Jurangjero tahun 1976, Kepala Desa Sukiban mendapatkan bantuan bibit jati dari perhutani. Bibit tersebut kemudian ditanam di bengkok dan lahan miliknya dengan luasan 4,25 hektar. Sementara itu, di desa Plantungan-Blora tahun 1978, terdapat tiga orang yang mendapat bantuan bibit jati
dari perhutani yaitu Soewadji (kepala desa saat itu), Joyo Mijan, dan Mul. Ketiganya merupakan perangkat desa saat itu. Mereka bertiga menanam bibit jati di bengkok dan tegalan milik masing-masing. Kendati harapan pengamanan hutan tersebut tidak berjalan secara maksimal dengan model strategi tanam kayu di lahan milik tersebut, episode ini beberapa menjadi titik awal perkembangan hutan rakyat. Fase ketiga, pada tahun 1980-1990an, ketika beberapa generasi pertama penanam jati di lahan milik telah panen, penduduk desa mulai melihat ada kemanfaatan secara ekonomi ketika menanam jati di tegalan maupun di pematang sawah. Maka ketika ada bantuan bibit terutama dari dinas kehutanan, masyarakat menyambutnya dengan baik, bahkan cenderung berebut untuk mendapatkan bibit tesebut untuk ditanam dilahan mereka. Bahkan tahun 1992 di desa Jurangjero, masyarakat atas dampingan dinas kehutanan membuat pembibitan sendiri di desa. Bibit tersebut dijual kepada penduduk desa Jurangjero dan desa yang lain di sekitar. Ada dua cara mendapatkan bibit, pertama yaitu menerima bantuan dari instansi terkait atau membeli bibit jati dari pembibitan. Kedua yaitu mencari tukulan di hutan negara. Tukulan adalah bibit jati yang tumbuh liar di bawah tegakan hutan negara yang berasal dari biji jati yang jatuh ke tanah lalu tumbuh dengan sendirinya. Pada periode ini, penduduk desa sudah mulai mengadakan bibit secara mandiri. Artinya, penanaman tanaman jati di lahan milik dilakukan atas inisiatif penduduk sendiri. Tahun 1998 terjadi peristiwa politik yang merubah sendi kehidupan Indonesia. Kekuasaan politik orde baru yang dipimpin oleh Suharto runtuh, dan diganti dengan periode yang disebut reformasi. Ketika krisis ekonomi melanda saat itu, terjadi banyak PHK dan situasi tidak aman di kota. Kaum urban baik tua maupun muda banyak yang pulang ke desa. Pada saat yagn bersamaan, ketika terjadi penjarahan di toko-toko besar di kota, masyarakat desa hutan menjarah hutan negara. Kayu ditebang untuk buat rumah dan untuk dijual guna mendapatkan uang. Pada saat yang bersamaan pula, hutan rakyat tetap aman tidak dijarah oleh siapapun. Ketika stok kayu hutan negara menipis karena penjarahan hutan negara tahun 1998-2001, hutan rakyat mulai dilirik oleh industri berbasis kayu baik di jepara, solo, klaten, dan kota lain. Seketika kayu dari hutan rakyat mulai laris. Banyak kasus yang dulunya biasa menebang seperlunya, pada saat itu hingga kini banyak yang melakukan tebang habis, terutama untuk kebutuhan-kebutuhan besar macam pesta perkawinan, beli tanah, maupun naik haji. Tahun 2002, pemerintah mencanangkan proyek GNRHL atau Gerhan baik di lahan milik penduduk maupun di hutan negara. Proyek ini terutama sukses di lahan milik penduduk, namun tidak sukses di jalankan di lahan hutan negara. Kegagalan tersebut mudah ditebak, karena proyek penanaman tidak diintergrasikan dengan perawatan. Sementara pada lahan milik, yang merawat cukup jelas yaitu yang punya lahan itu sendiri. Sementara itu, di hutan negara, terjadi perubahan model hubungan antara penduduk desa hutan dengan Perhutani. Penduduk yang dulu taat terhadap petugas perhutani, saat itu mulai tidak taat. Era reformasi merebakkan uforia mempertanyakan peran negara atas kesejahteraan warga. Perhutani sebagai representasi negara kemudian dipertanyakan perannya bagi kesejahteraan penduduk desa hutan. Hingga kini (2011) hutan rakyat jati di Jawa diintensifkan oleh pengelolannya yaitu rumah tangga petani dengan terus menerus dengan sistem pengelolaan yang mereka tahu dan yang mereka lakoni sehari-hari. Sementara itu, luas hutan rakyat di Jawa dan Madura + 2,6 juta hektar dengan potensi sekitar 5,9 juta m3 (BPKH Jawa Madura, 2009).
3. Hutan Rakyat Jati di Blora, Persinggungan Hutan Negara Studi yang berbasis grouded research dilakukan oleh beberapa NGO di Jawa menyebutkan bahwa hutan rakyat merupakan sebuah pengetahuan asli Indonesia yang dapat disejajarkan dengan pengetahuan pengelolaan sumberdaya hutan dalam skala luas yang mengadopsi ilmu kehutanan ilmiah dari Eropa. Sementar itu, prakarsa eksistensi hutan rakyat didorong oleh kebutuhan penyeimbangan ekologi lokal serta penyesuaian terhadap kondisi sosial ekonomi pedesaan terkini (Awang dkk, 2007). Terdapat dua tradisi penyelenggaraan kehutanan antara pengelolaan hutan negara dengan pengelolaan hutan rakyat. Kedua tradisi tersebut saling berjalan beriring terutama pada era tahun 1950 hingga sekarang. Ini sebuah penyandingan pengelolaan. Dengan begitu akan jelas kenampakan perkembanganperkembangan masing-masing tradisi. Hutan negara di Jawa pada eks karesidenan Rembang (termasuk kabupaten Blora) dan sekitarnya didominasi oleh tanaman Jati. Hal ini terutama berlaku untuk periode pra penjarahan tahun 1998 2000. Pada tahun-tahun setelahnya, ada beberapa kawasan hutan negara di Blora utara yang ditanami pohon mindi. Pada saat yang sama, pasca penjarahan 1998-2000 masyarakat desa hutan terus menanami lahan pekarangan dan tegalan mereka dengan tanaman jati. Sehingga di desa Plantungan (Blora) dan sekitarnya kita dapat menemukan dua hutan yang hanya dipisahkan oleh sebilah jalan kampung. Di samping barat jalan kita mendapati barisan kurus pohon mindi di hutan negara dan di sebelah timur jalan terdapat barisan rapi pohon jati di hutan rakyat. Perihal tersebut dapat dibaca sebagai sebuah fenomena gugurnya dominasi klaim bahwa Perhutani adalah satu-satunya unit usaha yang memproduksi spesies jati berkualitas tinggi. Fakta sejak pasca reformasi hingga sekarang, terdapat dua perkembangan yang signifikan di kabupaten Blora bagian utara yaitu semakin berkembangnya budidaya hutan rakyat di pegunungan kapur utara sertanya semakin terbukanya pasar kayu rakyat dalam perdagangan kayu di Blora dan Jawa Tengah pada umumnya. Fenomena tersebut muncul di atas tiga akar kausalitas yaitu kebutuhan optimalisasi pemanfaatan lahan, proyek penghijauan dan rehabilitasi lahan, dan pudarnya simbol jati negara. Gambar 1. Sketsa perkembangan hutan rakyat pegunungan kapur utara
Gambar 2. Membaca fenomena hutan rakyat
Bagan di atas menerangkan bahwa hutan rakyat merupakan fenomena lintas sendi dalam kehidupan pedesaan di Blora. Pada sendi budaya-ekologi hutan rakyat merupakan tradisi menanam tanaman keras di pekarangan dan tegalan. Selain tradisi, hal tersebut juga mencerminkan perlindungan terhadap lingkungan baik itu mata air maupun pencegahan ancaman longsor tanah. Pada sendir budaya-ekonomi, hutan rakyat sebagai usaha pemenuhan kebutuhan hidup baik itu pemenuhan kebutuhan kayu untuk membuat rumah serta penjualan kayu jati untuk kebutuhan ekonomi skala menengah dan besar. Pada sendi ekologi-politik, masyarakat desa memiliki pertimbangan politis sejak dulu kala, bahwa menanam pohon merupakan wujud penjagaan keseimbangan antara manusia dan alam. Agak ubsurd tetapi begitulah adanya terutama pada tanaman-tanaman kayu di lingkungan mata air serta pada pematang-pematang sawah. Pada sendi ekonomi-politik, beberapa pemilik hutan rakyat yang tergolong kaya memaknai tanaman kayu di lahannya sebagai bagian dari strategi investasi ekonomi untuk kebutuhan-kebutuhan masa datang. Sementara itu, produktivitas hutan rakyat saat ini telah menjadi pemasok utama industri perkayuan di Jawa Tengah. Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2010, jumlah indstri pengolahan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Jawa Tengah yang telah berizin sebanyak 553 unit dengan kebutuhan bahan baku kayu bulat 4,7 juta meter kubik pertahun. Sumbernya berasal dari hutan alam 1,6 juta meter kubik dan hutan tanaman 3,1 juta meter kubik. Dari angka tersebut, produk kayu di Jawa Tengah berasal dari hutan negara yang dikelola Perhutani 300.000 meter kubik per tahun dan hutan rakyat 2,2 juta meter kubik pertahun. Satu banding sembilan (1:9), kemenangan untuk hutan rakyat dengan angka yang sangat telak (Suryanto, 2011).
4. Penutup Saya masih berandai-andai, masyarakat yang telah terbukti sangat mampu mengelola spesies jati di lahan milik, akan dipasrahi mengelola hutan jati milik negara. Semoga.
Daftar Pustaka Arupa, at all (2005) Hutan Wonosobo: Keberpihakan yang Tersendat. Yogyakarta: BP Arupa. Awang, S.A., dkk (2007) Unit Managejem Hutan Rakyat: Proses Konstruksi Pengetahuan Lokal. Yogyakarta: Banyumili. Cordes. J.W.H. (1992) Hutan Jati di Jawa, Malang: Yayasan Manggala Sylvia Lestari, Biro Jasa Konsultan Perencanaan Hutan. Hasanu Simon (1993) Hutan Jati dan Kemakmuran. Yogyakarta: Aditya Media. BPKH Wilayah XI Jawa-Madura (2009) Strategi Pengembangan Pengelolaan dan Arah Kebijakan Hutan Rakyat di Pulau Jawa. Yogyakarta: BPKH Wilayah XI Jawa-Madura dan Forest Governance and Multistakeholder Forestry Programme (MFP II). R. Soepardi (1975) Hutan dan Kehutanan dalam Tiga Jaman. Jakarta: Perum Perhutani. Peluso, N.L. (1990) A History of State Forest Management in Java, dalam Mark Poffenberger (ed), Keepers of the Forest: Land Management Alternatives in Southeast Asia, Hartford: Kumarian Press. Peluso, N.L. (2006) Hutan Kaya Rakyat Melarat. Jakarta: Konphalindo. Mark Poffenberger (ed), Keepers of the Forest: Land Management Alternatives in Southeast Asia, Hartford: Kumarian Press. Suyanto (2011) Hutan Rakyat: Penyelamat Ekologi Jawa, dalam Jurnal Wacana edisi 25 Tahun XIII 2011 Rekonfigurasi Pengelolaan Hutan Jawa.
Anda mungkin juga menyukai
- Bab IDokumen21 halamanBab IJanu NestaBelum ada peringkat
- 199-Article Text-387-1-10-20151004Dokumen16 halaman199-Article Text-387-1-10-20151004Nindya SafiraBelum ada peringkat
- Pertemuan 3Dokumen16 halamanPertemuan 3The P-ManBelum ada peringkat
- Pengelolaan Hutan oleh Perhutani Tengah Digugat MasyarakatDokumen80 halamanPengelolaan Hutan oleh Perhutani Tengah Digugat MasyarakatLumbungPadiBelum ada peringkat
- Sosiologi Kehutanan Dan LingkunganDokumen7 halamanSosiologi Kehutanan Dan LingkunganAlfi SofyanBelum ada peringkat
- Legal Review Perhutanan SosialDokumen26 halamanLegal Review Perhutanan SosialGuntur RadicBelum ada peringkat
- Dai Tugas 1 Pengatar Ilmu PertanianDokumen10 halamanDai Tugas 1 Pengatar Ilmu PertanianDa'i ParakkasiBelum ada peringkat
- Paper Sejarah UsahataniDokumen16 halamanPaper Sejarah UsahataniIrma NovianaBelum ada peringkat
- 01 Pengantar Ilmu Pertanian (Pendahuluan) Kuliah 1Dokumen23 halaman01 Pengantar Ilmu Pertanian (Pendahuluan) Kuliah 1muty mutiaraBelum ada peringkat
- 1LJK Uts Konservasi Sda - Irodatul Jannah - 182010'010Dokumen5 halaman1LJK Uts Konservasi Sda - Irodatul Jannah - 182010'010Alifah MuyasarohBelum ada peringkat
- Review Eksploitasi Hutan JatiDokumen4 halamanReview Eksploitasi Hutan JatilatifBelum ada peringkat
- Resume BukuDokumen30 halamanResume BukuSalsabila ZebalitaBelum ada peringkat
- Modul SosperDokumen19 halamanModul SosperFahmi LazuardiBelum ada peringkat
- SEJARAH PERTANIANDokumen180 halamanSEJARAH PERTANIANEka SaputraBelum ada peringkat
- Kondisi Hutan IndonesiaDokumen9 halamanKondisi Hutan IndonesiaannaBelum ada peringkat
- Analisis Peran WWF Dalam Sertifikasi Kayu Hutan Kalimantan Periode 2003-2009Dokumen67 halamanAnalisis Peran WWF Dalam Sertifikasi Kayu Hutan Kalimantan Periode 2003-2009Erika AngelikaBelum ada peringkat
- Kerusakan HutanDokumen14 halamanKerusakan HutanDwi Budi SumartonoBelum ada peringkat
- Kehutanan Masyarakat dan Konsep SosialDokumen18 halamanKehutanan Masyarakat dan Konsep SosialHari KaskoyoBelum ada peringkat
- Interaksi Hutan Dan MasyarakatDokumen6 halamanInteraksi Hutan Dan MasyarakatKeong KerucutBelum ada peringkat
- UNIKOM - R.Ibrahim Adam - BAB IIDokumen23 halamanUNIKOM - R.Ibrahim Adam - BAB IIAbelkameBelum ada peringkat
- Etno Sejarah Konservasi Di IndonesiaDokumen7 halamanEtno Sejarah Konservasi Di IndonesiaIlyas NursyamsiBelum ada peringkat
- Tugas Resume Biokonserfasi Ahmad Migi Fatoni 193030903032Dokumen8 halamanTugas Resume Biokonserfasi Ahmad Migi Fatoni 193030903032Ahmad MigifatoniBelum ada peringkat
- Imbang Tugas Proposal HadaeDokumen28 halamanImbang Tugas Proposal HadaeAhmad-RidwanBelum ada peringkat
- Sosper Modul 2-Masyarakat Pedesaan Indonesia (Kelompok 1)Dokumen23 halamanSosper Modul 2-Masyarakat Pedesaan Indonesia (Kelompok 1)Luthfi TaqiBelum ada peringkat
- Review Jurnal Kelompok 2 - ConflictDokumen3 halamanReview Jurnal Kelompok 2 - ConflictDewa HendraBelum ada peringkat
- Tugas Essai Kehutanan MasyarakatDokumen7 halamanTugas Essai Kehutanan MasyarakatThe P-ManBelum ada peringkat
- Essai EKOLOGI Suksesi WanagamaDokumen5 halamanEssai EKOLOGI Suksesi WanagamaRoona OhBelum ada peringkat
- Moratorium AntoDokumen4 halamanMoratorium AntoUjang HermansyahBelum ada peringkat
- Bio 2Dokumen7 halamanBio 2Kartika Wahyu IllahiBelum ada peringkat
- Persentasi Hutan Dan Pengentasan KemiskinanDokumen4 halamanPersentasi Hutan Dan Pengentasan KemiskinanJharz Nagh SmataygcalucheerfuleverydayBelum ada peringkat
- Sejarah Perkembangan PenyuluhanDokumen16 halamanSejarah Perkembangan PenyuluhanMutyara Dewi Hafifah100% (2)
- Kelompok 4 Sejarah Hutan RakyatDokumen9 halamanKelompok 4 Sejarah Hutan Rakyateka nala puspitaBelum ada peringkat
- Tugas 1 Botani Pertamanan I Widya SafitriDokumen3 halamanTugas 1 Botani Pertamanan I Widya Safitriwidyasafitri162325Belum ada peringkat
- SEJARAH PENYULUHAN PERTANIANDokumen17 halamanSEJARAH PENYULUHAN PERTANIANRiston Hansel67% (3)
- KEAGRARIAAN IND-WPS OfficeDokumen5 halamanKEAGRARIAAN IND-WPS OfficeLelin MusliadiBelum ada peringkat
- 18-11-2022 Etika LingkunganDokumen1 halaman18-11-2022 Etika LingkunganvegaBelum ada peringkat
- ID Analisis Ketergantungan Masyarakat TerhaDokumen13 halamanID Analisis Ketergantungan Masyarakat TerhaMuhammad SarifBelum ada peringkat
- Pengelolaan Hutan RakyatDokumen9 halamanPengelolaan Hutan RakyatImamoto KinuBelum ada peringkat
- Teks EksposisiDokumen10 halamanTeks Eksposisiplayerunknow65Belum ada peringkat
- Sejarah Usahatani Di IndonesiaDokumen5 halamanSejarah Usahatani Di IndonesiaHabi SusiloBelum ada peringkat
- Konteks Sejarah SilvikulturDokumen13 halamanKonteks Sejarah SilvikulturardiatmaBelum ada peringkat
- Implementasi Reforma Agraria Di Sektor KehutananDokumen10 halamanImplementasi Reforma Agraria Di Sektor KehutananPUSTAKA Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP)100% (1)
- SEJARAH LINGKUNGANDokumen6 halamanSEJARAH LINGKUNGANvira rihanaBelum ada peringkat
- Sejarah Pengelolaan Hutan Di IndonesiaDokumen7 halamanSejarah Pengelolaan Hutan Di IndonesiaDhimas HidayatullahBelum ada peringkat
- Laporan Praktikum Invent Acara Xi (Nope)Dokumen5 halamanLaporan Praktikum Invent Acara Xi (Nope)Fahrul RahmanBelum ada peringkat
- Sejarah Pertanian Dunia Dan IndonesiaDokumen17 halamanSejarah Pertanian Dunia Dan IndonesiamuthiaBelum ada peringkat
- Hutan Desa1Dokumen14 halamanHutan Desa1Elok Ponco MulyoutamiBelum ada peringkat
- Tugas Sosiologi Kehutanan Chelsea Clariesta Pasalli (M1A118036) Kelas ADokumen13 halamanTugas Sosiologi Kehutanan Chelsea Clariesta Pasalli (M1A118036) Kelas AWa UcilianaBelum ada peringkat
- OPTIMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTANDokumen12 halamanOPTIMASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DALAM DAN SEKITAR HUTANNur IlhamBelum ada peringkat
- Dampak Sosek Ekolg Peng HTN PinusDokumen27 halamanDampak Sosek Ekolg Peng HTN PinusDe AlvinBelum ada peringkat
- Resistensi Dan Gaya Hidup para Petani DiengDokumen14 halamanResistensi Dan Gaya Hidup para Petani DiengHery Santoso100% (1)
- Soshut - Essay - KHT A - Gifli Oktori - 2106126425Dokumen5 halamanSoshut - Essay - KHT A - Gifli Oktori - 2106126425Gifli Oktori 2106126425Belum ada peringkat
- Bab IvDokumen33 halamanBab IvKurnia RivaiBelum ada peringkat
- Perkembangan Pertanian - Muh. Anugrah RustamDokumen10 halamanPerkembangan Pertanian - Muh. Anugrah RustamAnoa ProBelum ada peringkat
- Struktur KayuDokumen20 halamanStruktur KayuAyu Andriani WiWiBelum ada peringkat
- KEARIFAN LOKALDokumen15 halamanKEARIFAN LOKALfidelis_harefaBelum ada peringkat
- 53 - Anandio Rendy Pamungkas - 13040220130123 - Antrop Pembangunan ADokumen3 halaman53 - Anandio Rendy Pamungkas - 13040220130123 - Antrop Pembangunan ADio BobothBelum ada peringkat
- Komunitas Petungkriyono - Potret Komunitas Desa Yang RasionalDokumen5 halamanKomunitas Petungkriyono - Potret Komunitas Desa Yang RasionalAli Murtadha AlaydrusBelum ada peringkat
- Factsheet TenggarejoDokumen2 halamanFactsheet TenggarejoAgus SumindarBelum ada peringkat
- PetaTAP JawaDokumen1 halamanPetaTAP JawaAgus SumindarBelum ada peringkat
- 13 April 2017 - Konsorsium Satunama Kembangkan 25.000 Pohon Kepayang - ANTARA News JambiDokumen2 halaman13 April 2017 - Konsorsium Satunama Kembangkan 25.000 Pohon Kepayang - ANTARA News JambiAgus SumindarBelum ada peringkat
- Nyoman 2005 Sejarah Hukum HutanDokumen21 halamanNyoman 2005 Sejarah Hukum HutanAgus SumindarBelum ada peringkat
- Surat Edaran SE.1 Tahun 2015 Penjelasan Ketentuan Tambahan Dalam Implementasi SVLKDokumen8 halamanSurat Edaran SE.1 Tahun 2015 Penjelasan Ketentuan Tambahan Dalam Implementasi SVLKAgus SumindarBelum ada peringkat
- 4 Samin Dan Kehutanan Abad XIXDokumen17 halaman4 Samin Dan Kehutanan Abad XIXAgus SumindarBelum ada peringkat
- Presentasi Semarang 27012014Dokumen11 halamanPresentasi Semarang 27012014Agus SumindarBelum ada peringkat
- Memahami Konflik Tenurial Melalui Perspektif SejarahDokumen9 halamanMemahami Konflik Tenurial Melalui Perspektif SejarahAgus SumindarBelum ada peringkat
- Kausalitas Gerakan SaminDokumen6 halamanKausalitas Gerakan SaminAgus SumindarBelum ada peringkat
- 1 HR Blora - Preminilary ReportDokumen3 halaman1 HR Blora - Preminilary ReportAgus SumindarBelum ada peringkat